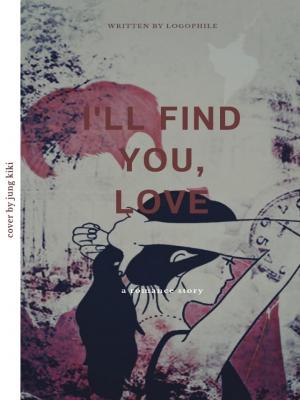Adik kecil lelakiku, Tian. Tangannya berlumur cat. Dinding putih rumah kami menjadi korbannya. Ibu dan aku sengaja membiarkan, dengan begitu dapat mengurangi tantrum yang kerap terjadi.
Ia berkreasi pada dinding tidak menggunakan kuas, melainkan tangan kecilnya yang asyik menari-nari bersama lelehan cat acrylic.
“Kau marah, Salli?” tanyanya dengan mata membelalak.
“Sama sekali tidak,” jawabku menenangkannya.
“Lantai ruang tamu juga kuwarnai merah,” ujarnya lagi.
“Tak apa.” Aku masih berusaha santai. Aku tahu Tian sengaja memancing amarahku.
“Karpet dan sofa juga … kuhias dengan warna hitam.”
Ucapan Tian disertai wajah jenaka yang menyebalkan.
Hmm, rupanya Tian masih bermaksud membuat keributan. Aku menahan diri. Tidak akan kuberi apa yang diinginkannya.
“Baiklah.” Aku menghela napas sejenak.
Aku berdiri berhadapan dengannya. Tubuhnya menegang, jari-jari mengepal. Aku menunduk mencoba menyamakan tinggi badanku dengannya, lantas memeluknya dan mengusap punggungnya lembut.
Ya, aku tidak memarahinya. Setidaknya tidak saat ini. Jiwanya terlalu rapuh sehingga menuntut banyak perhatian. Kenakalan yang di buat-buat adalah bentuk protes dari diri Tian.
Tian sering melakukan hal berlawanan dari yang dianjurkan ibu. Itu semua karena ia mencari perhatian. Termasuk berlarian, berteriak histeris ketika menonton acara kartun di televisi, padahal tidak ada yang menakutkan pada tayangannya. Sekali waktu Tian tertawa terbahak-bahak dan sulit berhenti, ternyata tak ada hal lucu pada tontonan itu.
Aku dan ibu sering saling berpandangan kemudian memeluk tubuh Tian erat guna membuatnya lebih tenang.
Segala hal hanya perlu berjalan sesuai alurnya. Bagaimanapun kami menolak, yang sudah ditentukan Tuhan akan tetap menjadi bagian dari cerita hidup.
***
Dear seseorang di tahun 2001
Saat ini kami duduk di ruang tunggu sebuah rumah sakit. Adik kecilku telah memeriksakan gangguan listrik di otaknya. Itulah sebabnya kami menunggu di depan pintu poli elektromedik, menunggu hasil EEG untuk segera dibacakan hasilnya oleh dokter neurologi.
Adik kecilku yang baru berusia enam tahun tiba-tiba saja memiliki tics. Entahlah, aku tidak tahu apakah ini berhubungan dengan trauma di kepala atau terkejut dengan perubahan hidup tanpa ayah kami. Diagnosa mengatakan adikku mengidap sindrom tourette( tourette syindrome) nama yang sebelumnya begitu asing di telinga kami.
Adikku yang selalu memakai kaus kaki terbalik dengan berbeda warna. Adikku yang tidak suka bersekolah formal. Adikku yang sebelumnya hiperaktif dengan segala tingkah polahnya, tiba-tiba berubah pendiam. Lehernya terus digelengkan dengan bibir menekuk tanpa terkendali, terlebih jika rasa gugup mendera, kejang itu sangat kuat, dan saat itu kami sadar itu bukanlah tics biasa.
Hilang tawa cerianya berganti pandangan kosong. Dia yang kecil tak tahu mengapa terjadi pada dirinya. Ia mulai menggambar monster-monster jahat di dinding rumah. Gambar-gambar itu berwarna muram penuh kemarahan.
Psikolog berkata, hal yang selalu diulang dikatakan adik adalah tentang rasa ketakutan. Hari saat ia ingin menangis namun tak setetespun air mata mengalir di pipinya. Di mana itu menjadi hari terakhir ayah bersama kami. Saat ayah dengan alibi cintanya meneriaki ibu dan memilih pergi dari rumah.
Hal yang paling menyakitkan adalah betapapun mengecewakan perbuatan ayah, seorang anak tetap mencintai ayahnya penuh. Ketika malam semakin larut dan ia tidak juga beranjak tidur, matanya menatap sayu keluar jendela. Menantikan seseorang menyesal dan kembali memeluknya.
Kepergian ayah bukan saja meninggalkan luka pada wanita yang melahirkan kami, namun juga mengubah kehidupan adik seperti kaus kaki terbalik yang selalu dikenakannya.
Salli, 2023
***
Aku mengingatnya, telah menuliskan kisah adik ke dalam surat menembus waktu yang kukirim untuk tahun 2001.
Aku sungguh-sungguh mengharapkan mesin waktu benar-benar menelannya. Rasanya ingin sekali menghapus kehidupan adik bersama tourette syindrome yang melekat seumur hidup pada dirinya.
Mengisahkan adik, menciptakan getaran khusus pada diriku. Dendam pada ayah, tidak terima kondisi adikku jadi begini akibat keegoisan ayah. Namun, ibu selalu menenangkanku, ia mengatakan kondisi adik terpengaruh oleh beberapa faktor. Terlebih riwayat kelahirannya yang prematur dapat menyebabkan berbagai komplikasi sejak bayi. Selain tourette, Tian juga mengidap ADHD. Sehingga ada banyak faktor sebagai pemicu sindrom tourette-nya. Tidak semata-mata muncul karena kekecewaan dan kesedihan terdalam. Kata ibu lagi, kami harus menerima, merawat dan menjalani pengobatan adik dengan ikhlas dan sabar. Ada beberapa obat yang harus rutin ia minum setiap hari. Terkhusus malam hari, Tian wajib minum obat untuk penderita anxiety supaya tidurnya tidak gelisah.
Kehidupan terus berjalan dan juga butuh biaya. Tidak mungkin kubiarkan ibu dengan keterbatasannya mencari nafkah sambil mengasuh Tian yang istimewa. Sebab itu kuputuskan bekerja. Nasib mujur membawaku pada Kafe Gerimis. Desember tahun lalu, tanpa sengaja mendengar rumor nyanyian gerimis. Rumor yang menyebar dengan cepat di antara murid-murid SMA yang tengah mempersiapkan diri memasuki perguruan tinggi negeri. Mereka berseloroh untuk meminta bantuan kotak pos merah di Kafe Gerimis dengan tujuan memberi tahu diri mereka di masa lalu, agar tak menyia-nyiakan waktu belajar di SMA, karena memang cukup sulit untuk lulus ujian masuk PTN (Perguruan Tinggi Negeri).
Begitu penasarannya diriku, mencoba datang dan mendengarkan langsung nyanyian gerimis dengan petikan gitar akustik setiap sabtu malam. Menyimak dengan serius nyanyian gerimis itu dan bisik-bisik pengunjung kafe tentang rumor tersebut terus berdengung di sekitarku.
Pemuda yang menyanyikan nyanyian gerimis dengan petikan gitarnya terlihat murung dan sedih. Itu pertama kali aku melihatnya. Pemilik kafe sekaligus bos dari Kafe Gerimis. Saat itu juga vibrasi aneh menyelimutiku, aku merasa terhubung dengannya. Tak kupingkiri bos telah menyita perhatianku kala pertemuan pertama.
Aku ingat betul, harus mengubur ketegangan dan memberanikan diri bertanya padanya. Pertanyaan yang saat itu kupikir adalah pertanyaan terbodoh pada orang yang baru pertama kali bertemu.
“Apakah nyanyian itu benar adanya?” tanyaku waktu itu.
Dia terdiam dan tidak terkejut. Sepertinya sudah terbiasa dan siap jika salah satu pengunjung kafe akan melontarkan pertanyaan tersebut.
Aku tidak menghiraukan diamnya. Dia masih berjongkok memasukkan gitar pada tas gitar terbuat dari bahan kulit berwarna coklat.
“Benarkah kotak pos merah itu dapat mengantarkan suratku pada seseorang di masa lalu?”
Aku bertanya lagi, kali ini cukup berhasil membuat respon di wajahnya. Ia tersenyum sinis. Sejenak ia menoleh mengamatiku. Lantas ia berdiri tepat di hadapanku. Wajahku langsung mendongak karena tinggiku tidak melebihi bahunya.
“Itu hanya rumor!” serunya bernada tegas, jelas tak ingin lagi ada pembahasan lebih lanjut.
Tiba-tiba seseorang menyela, pemuda yang lebih muda dari pemilik kafe, berwajah ceria seperti matahari.
“Moon, kita kekurangan karyawan, pengunjung semakin ramai saja setiap malam minggu!” keluhnya, “eh, siapa ini? Apa kau butuh bantuan, Nona?” pemuda yang sebelumnya tidak melihatku, terlihat kaget dan menyapaku ramah.
“A-aku dapat bekerja di sini!” tukasku, mereka berdua saling berpandang dan … ya, sejak itulah akhirnya aku menjadi bagian dari Kafe Gerimis. Tak terasa hampir setahun yang berlalu. Hal menguntungkan bagi keluargaku karena itu artinya aku mendapatkan gaji rutin setiap bulan.
***
Pernah di suatu sore, pada minggu pertamaku bekerja. Sengaja, aku kembali melontarkan tanya kepada bos pemilik kafe. Tentang rahasia kotak pos merah yang menjadi tujuan pokok aku bekerja di Kafe Gerimis.
“Kenapa kau terlalu penasaran?” tanya bos curiga, “bukankah telah kujawab bahwa itu hanya rumor!”
“Aku memiliki misi!” seruku lantang.
“Batalkan misimu! Tidak ada yang bisa kau lakukan!” jawab bos setengah memerintah.
Aku menatapnya dengan pandangan memelas, rasa sedih yang lama tenggelam muncul ke permukaan. Entah apa yang bos lihat, tapi hal ini cukup membuat ia mengurangi intonasi bicaranya.
“Mau apa kau bila rumor itu benar?” tanya bos lirih, kali ini hampir tanpa emosi.
Aku menunduk sesaat lantas menjawab tak kalah lirih, “Aku tak ingin hidup, Bos.”
“Hah? Apa kau pikir kafe ini tempat mengakhiri hidup?” tanya bos kembali naik darah.
“A-aku bukannya ingin membunuh diriku, Bos! Aku hanya tak mau lahir ke dunia ini!”
“Omong kosong! Itu sama saja, Salli!”
Bos lalu melemparkan pandangannya ke luar jendela, tempat kotak pos merah berdiri kokoh. Entah berapa tahun lamanya berada di sana. Kehujanan, kepanasan. Kisah tentangnya telah melegenda ke seluruh penjuru kota kecil ini, sehingga menjadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung kafe. Apalagi, nyanyian gerimis yang rutin dinyanyikan setiap malam minggu oleh bos pemilik kafe dengan suara syahdu seolah menghipnotis para pengunjung untuk meresapi kalimatnya. Terngiang-ngiang, kemudian didengungkan ceritanya dari mulut ke mulut.
“Bukan salah kami, bila terpengaruh cerita dalam nyanyian tersebut, Bos! Jika kau menyangkal berita yang tersebar … mengapa kau tak hentikan saja nyanyianmu?” tanyaku lugas.
Bos tidak menjawab, seperti berpikir ia pun berdeham tiga kali. Akh, apakah aku kelewatan, ya? Baru bekerja sepekan dan kini mulai berani berdebat dengannya. Bagaimanapun ia adalah bos tempat aku bekerja. Sesal datang merambat, sungguh aku tak ingin dipecat secepat ini.
“Nyanyian gerimis itu hanyalah pemikat, sekadar drama, tidak mengandung unsur keajaiban apa pun. Sebagai pewaris dan cucu satu-satunya pemilik kafe terdahulu … aku hanya meneruskan tradisi yang bertahun-tahun terjaga yaitu nyanyian gerimis tiap sabtu malam.” Bos menjelaskan panjang lebar, mencoba menjaga intonasi suaraya agar stabil dan tidak terbaca emosi dalam hatinya olehku.
Aku termangu. Mulai memperhatikan dengan benar ekspresi wajah bos yang hampir mirip adikku, Tian. Sorot mata misterius, ekspresi datar dan perkataan yang tak mudah ditebak. Yeah, tentu saja Tian lebih parah, dan tentu saja bos tidak memakai kaus kaki terbalik seperti Tian.
Sejak percakapan sore itulah, bos menjaga jarak denganku. Begitu juga aku, yang lebih senang mengobrol dengan senior, ia lebih tergambar jelas emosi bahagia, sedih, marah atau apa pun yang tengah dirasakan dalam nada bicaranya.
Meskipun akhirnya aku lebih dekat dengan senior, tapi tetap saja … setiap kali aku melihat kaus kaki terbalik yang dikenakan Tian, justru langsung teringat pada bos dan bukannya senior. Sungguh gila!


 missera
missera