Aku terbaring lemah, tubuhku hampir mati rasa dari rasa sakit yang menjalar. Aku tahu apa yang akan terjadi, dan meskipun aku sadar akan itu, aku tak mampu berbuat apa-apa. Kekuatan sudah mengkhianati tubuhku, dan aku hanya bisa menunggu akhir yang sudah jelas di depan mata.
“Berhenti di situ,” sebuah suara yang akrab tiba-tiba menggema di udara, menggetarkan setiap syaraf di tubuhku. Saat itu juga, aku memaksa mataku untuk terbuka, dan di sana dia berdiri—Cedric, tegap dan tak tergoyahkan. Hatiku berdegup kencang, sebuah harapan kecil menyelinap masuk di antara kepasrahan yang sebelumnya menguasai diriku.
Pria bernama Agung itu menghentikan langkahnya dengan kesal, memutar tubuhnya untuk menghadapi Cedric. “Cih, kalian ini tidak ada habisnya,” desisnya. Aku tak bisa mempercayai pandanganku; Cedric, yang beberapa saat lalu terkapar, sekarang berdiri seolah-olah tak ada yang terjadi. Tapi yang lebih mengejutkan adalah kekuatannya yang sekarang memancar dengan begitu luar biasa.
“Aura kekuatannya melimpah,” bisikku dengan sisa nafas yang masih tersisa. Aku begitu takjub melihatnya, auranya bercampur biru dan kuning keemasan, terlihat begitu indah, seperti sebuah pertunjukan cahaya di tengah malam yang gelap. Cedric berjalan maju, dengan keyakinan seorang pahlawan yang selalu datang di saat terakhir. Aku bisa mendengar suaranya di dalam kepalaku, seolah ia berkata, “Aku akan menyelamatkanmu, Rika.”
Perasaanku campur aduk. Mataku melebar, pupilku mengecil, dan wajahku memerah. Aku tak bisa menyembunyikan rasa malu yang tiba-tiba menyeruak. Meski kata-katanya klise, aku tak peduli. Di tengah kekacauan ini, mendengar sesuatu yang begitu indah dari orang yang kupercaya memberiku kekuatan baru, meski hanya sesaat.
Tanpa buang waktu, Agung melesat maju, tangan kanannya bersinar biru, bersiap untuk memberikan pukulan yang menghancurkan. Bum! Pukulan itu berhasil ditepis oleh Cedric, hanya dengan satu tangan. Napasnya terasa lebih stabil, kekuatannya jelas telah meningkat berkali-kali lipat. Dalam benakku, aku bertanya-tanya, apakah dia telah berhasil melewati evolusi kedua? Tapi sekarang bukan saatnya untuk memikirkan itu.
Cedric dengan mudah membalas serangan, tinjunya meluncur cepat, diikuti oleh tendangan memutar yang mengesankan. Agung, yang sebelumnya begitu dominan, sekarang tampak lelah dan ketakutan. Aku bisa melihat ketakutan di matanya, sebuah ekspresi yang sebelumnya tak pernah kulihat dari dirinya. Kekuatan baru Cedric benar-benar mengintimidasi.
“Aaaaaargh!” teriakan putus asa Agung menggetarkan udara di sekitar kami, suaranya seolah-olah sebuah sonar yang mematikan, mencoba merusak partikel-partikel kekuatan Cedric. Tapi kali ini, hal itu tidak mempan. Bum! Agung terhempas sejauh 10 meter, pukulan Cedric begitu keras, bahkan gelombang suara itu tak mampu menghentikannya.
Cedric tidak berhenti di situ. Dia melompat maju dengan kecepatan yang membuatnya tampak seperti karakter fiksi, melesat secepat kilat. Flash! Dalam sedetik, pukulan keras Cedric menghantam Agung, mematahkan satu per satu tulang di tubuhnya. Aku tak bisa berpaling saat Agung akhirnya terbaring tak berdaya di tanah, kekuatannya memudar dengan cepat.
Cedric berdiri di atasnya, gagah dan tak terkalahkan, mengangkat satu tangan ke wajah Agung, siap untuk memberikan pukulan terakhir jika dia masih mencoba melawan. “Apa yang kau lakukan? Mengasihani lawanmu?” ejek Agung, meskipun wajahnya penuh amarah, matanya bersinar dengan kegilaan. Dia tidak takut mati—tidak, dia bahkan tampak menikmati pertarungan ini.
“Akan kubunuh kau,” Cedric mengangkat tangannya, dan aku tahu dia bersungguh-sungguh. Hatiku mencelos, dan tanpa sadar aku berteriak, “Tahan, Cedric!”
Sesaat sebelum pukulan itu menghancurkan hidung Agung, Cedric menahan tangannya. Dia menatapku dengan ekspresi bertanya, seolah-olah ingin tahu apa yang membuatku menghentikannya. “Tanyakan kepadanya rencana fraksi Teror Malam,” seruku dengan sisa tenaga yang masih kumiliki, mencoba bangkit dari tempatku tergeletak.
Cedric mengangguk, setuju, lalu kembali menatap Agung dengan tatapan tajam. Aura Cedric semakin pekat, semakin besar, menyebarkan ketakutan yang membuatku merinding. “Katakan apa rencana kalian,” suaranya berat, lebih dalam dari biasanya, tubuhnya tampak membesar, hampir tak kukenali. Beberapa bagian tubuhnya bercahaya biru, menunjukkan kekuatan yang mengalir melalui pembuluh darahnya.
“Apa yang kau pikirkan, anak muda?” Agung tersenyum sinis, meski suaranya mulai goyah. “Aku tidak ada waktu,” Cedric mendesak, tangan kanannya siap memukul. “Baiklah, setidaknya izinkan aku meminta pengampunan atas dosa-dosaku,” jawab Agung, nadanya berubah, lebih lemah, seolah dia tahu akhirnya sudah dekat.
“Aku akan mengatakan dua hal penting kepadamu,” ucap Agung, suaranya kecil, terbata-bata, tapi aku mendengarnya dengan cermat. Ada sesuatu yang mengerikan dalam ucapannya, dan aku bisa merasakan ketegangan yang semakin menebal di antara kami. Cedric menatapnya dengan serius, bersiap untuk mendengar apa yang mungkin menjadi rahasia paling gelap dari musuh kami.
“Aku akan mengatakan yang paling buruk,” Agung memulai, Cedric menjawab acuh
“Terserah, sebelum kau mati dengan sendirinya,” pria itu tertawa kecil, tawa yang dingin dan penuh kepuasan. Di tengah rasa sakit yang menjalari seluruh tubuhku, tawanya itu justru mengiris lebih dalam, menambah kepedihan yang sudah terlalu sulit kutanggung.
Kemudian, dengan nada yang seolah meremehkan, dia melanjutkan, “Pemimpin dan pasukan utama bukan di tempat ini. Mereka sudah bersiap di tempat lain dan sebentar lagi akan menggempur sisi lain garis perbatasan.”
“Apa!” Seruan keluar dari mulutku tanpa kendali, keterkejutan memukul kesadaranku yang lemah. Pikiran langsung berkelana ke arah Yeriko dan pasukan lainnya. Ini buruk—sangat buruk. Jika mereka menyerang sisi yang lemah, pasukan kita mungkin tak akan mampu bertahan. Aku mencoba mencari alat komunikasi, tapi sayang, semua hancur. Tidak ada cara untuk memberi tahu mereka.
“Tenanglah sobat, itu bukan yang terburuk,” suara pria itu kembali terdengar, kali ini dengan nada yang lebih meremehkan. Ucapan itu seperti angin dingin yang menerpa, membawa firasat buruk yang tak bisa kuabaikan.
“Katakanlah,” Cedric menjawab, meskipun aku bisa merasakan rasa prihatinnya yang dalam terhadap pria di hadapannya. Dia tahu ada sesuatu yang lebih dari sekadar perang di sini, dan aku juga bisa merasakannya.
Pria itu menarik napas dalam, seolah menikmati setiap detik penderitaan yang dia ciptakan, lalu berkata, “Ini mungkin buruk untuk kalian berdua.”
“Apa maksudmu?” Cedric bertanya, ketegangan merayap ke dalam suaranya.
“Tenanglah, aku belum menyelesaikan kata-kataku,” lanjutnya, mempermainkan rasa ingin tahu kami seolah-olah ini semua hanya permainan baginya. “Intinya, cepat atau lambat kalian akan tiada. Kekuatan kristal komet itu sama seperti narkoba. Saat tubuh kalian sudah teracuni, maka akan kecanduan, dan jika tidak mendapatkan pasokan, maka perlahan kalian akan mati.”
Kata-katanya menghantamku seperti palu godam. Aku bisa merasakan darahku mendidih, tapi bukan karena marah—itu karena ketakutan. Suaranya samar di telingaku, seperti gema yang menjauh, tapi aku bisa mengerti sepenuhnya apa yang dia sampaikan. Kami telah terpapar kristal komet itu. Aku tidak tahu apakah itu bagus atau tidak, tapi sekarang, aku tahu bahwa itu bukan berkah—itu kutukan yang perlahan membunuh kami.
Cedric, dengan ekspresi dingin dan penuh tekad, membalas, “Berikan cincinmu.” Pria itu, yang sudah tak berdaya di bawah kaki Cedric, hanya bisa tersenyum tipis.
“Bunuh aku,” pintanya, suaranya penuh keputusasaan yang mendalam, “itu lebih baik daripada harus tersiksa sebelum kematian tiba.” Dia menatap Cedric dengan mata penuh harapan akan akhir yang cepat. Cedric mengangguk, wajahnya tidak menunjukkan emosi, namun aku tahu di dalam hatinya, ada pertarungan batin yang keras.
Cedric melangkah mengambil sebuah tombak, menggenggamnya erat. Aku bisa merasakan beratnya keputusan itu dalam setiap gerakan yang dia lakukan. “Terima kasih untuk informasi yang kau sampaikan,” Cedric berkata dengan nada yang dingin, meski di balik kata-kata itu ada perasaan yang campur aduk.
Pria itu mengangguk, menutup matanya, menyerah pada nasib yang menantinya. Tanpa sepatah kata lagi, Cedric menebas lehernya hingga putus. Pria itu tewas dalam sekejap. Tidak ada rasa sakit, setidaknya begitulah yang kami yakini. Meskipun demikian, dalam hatiku, aku tahu membunuh seseorang, dengan alasan apapun, bukanlah hal yang mudah diterima.
***
Tidak ada waktu—itulah yang dikatakan Cedric kepadaku, dengan nada tegas yang tidak bisa dibantah. Dia menjelaskan sisanya padaku saat perjalanan, dan sekarang kami masih terus berlari. Tepatnya, hanya Cedric yang berlari, karena tubuhku tak mampu menopang diriku sendiri. Dia menggendongku dengan hati-hati, berusaha secepat mungkin menuju tempat pelarian Luna dan Freya. Sebelumnya, kami sudah menempatkan titik koordinat penjemputan. Kami harus mengeceknya dan memastikan semuanya aman sebelum tim konstelasi pergi dari tempat ini menuju markas pusat.
“Cedric, kau sudah memakai cincinnya, kan?” tanyaku, suaraku lemah, napasku berat. Tangan-tanganku melingkar di bahunya, mencoba menahan rasa sakit yang terus mendera.
“Sudah,” jawabnya singkat, matanya tetap fokus ke depan, tatapannya serius tanpa celah. “Tubuhmu sudah pulih total?” tanyanya, meskipun aku tahu dia sudah tahu jawabannya.
Aku menggeleng lemah. “Tidak, ini masih belum semuanya,” kataku, mencoba jujur meski tahu itu akan membuatnya khawatir. Beberapa tulang belakangku masih patah, dan meskipun kekuatan regenerasiku meningkat berkat cincin ini, tetap saja membutuhkan waktu untuk pulih sepenuhnya. Aku bukan seorang penyembuh alami, dan cedera sebesar ini tak bisa sembuh dalam sekejap.
Puing-puing bangunan runtuh perlahan di sekitarku, hujan mulai turun, seolah membawa kabar buruk yang tak diundang. Rintik hujan terdengar di jalan, dan angin mulai menerpa pakaian kami. Tapi Cedric terus maju, melawan cuaca dan kelelahan, dengan satu tujuan—menyelamatkan mereka yang kami kasihi.
Namun, semakin jauh kami berlari, semakin besar kekhawatiran yang menggerogoti hatiku. Matahari mulai menampakkan dirinya, sinarnya menyinari rintik hujan yang mulai mereda. Angin dingin perlahan berhenti, berganti dengan kehangatan yang seolah berkata bahwa kemenangan telah tiba. Tetapi, aku tahu lebih baik dari mempercayai perasaan yang menipu itu.
Ketika kami tiba di titik pertemuan, pemandangan di depan kami membuat hatiku tenggelam. Tidak ada jejak kehidupan yang tersisa, hanya bekas goresan pertempuran, beberapa senjata, dan mayat-mayat yang tergeletak dingin di tanah. Pemandangan itu membuatku mual, tapi aku harus terus mencari. Mata air mataku mencari sesuatu—apa saja yang bisa memberiku harapan bahwa mereka masih hidup.
“Freya, Luna!” Aku berteriak memanggil nama mereka, meskipun hatiku tahu kemungkinan mereka mendengar suaraku hampir nol. Kaki-kakiku gemetar, dan akhirnya kehilangan kekuatan, membuatku jatuh berlutut di tanah yang becek. Matahari, yang kini berada tepat di hadapanku, seolah mengejek keputusasaan yang perlahan menelanku.
Cedric terus menatap sekitar, memastikan tidak ada musuh lain di dekat kami. Wajahnya serius, tapi aku bisa merasakan bahwa dia juga merasakan kehampaan yang sama sepertiku. Aku mencoba bertahan, tapi tak bisa menahan air mata yang mengalir deras di pipiku. Setiap detik terasa seperti siksaan.
“Cedric,” sebuah suara terdengar dari arah kanan kami. Aku langsung menoleh, waspada. Cedric bergerak cepat, mendekat ke arahku dan memasang barrier, siap untuk apa pun yang mungkin datang. Hati kami berdegup kencang, terjepit di antara harapan dan ketakutan, menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya.


 silvius
silvius 




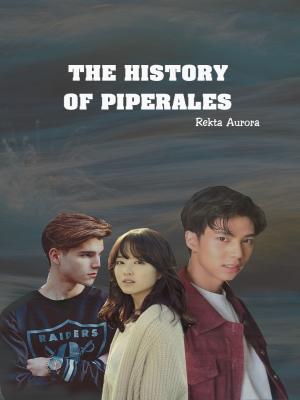




Halo readersvol. ada perubahan jadwal upload mulai bab berikutnya. Evolvera Life akan upload bab baru setiap 3 hari sekali. Terimakasih sudah menikmati cerita.
Comment on chapter Episode 22