30 Juli 2061. Dalam hitungan singkat, dunia merosot ke jurang kehancuran. Kematian menyapu bersih tiap sudut mayat-mayat tergeletak membusuk di jalan, diserang sengat alam yang tak kenal ampun. Kini hanya tersisa 15% harapan untuk hidup. Bagi kebanyakan orang, itu nyaris nihil, banyak yang memilih mengakhiri penderitaan daripada menunggu maut menjemput perlahan.
Saat ini, 1,8 miliar nyawa telah melayang. Kekacauan merajalela di mana-mana. perang meletus, pembunuhan dan pencurian jadi santapan sehari-hari, orang-orang berkelahi demi secarik kekuasaan. Insting keburukan manusia yaitu ego, keserakahan, haus validasi meledak di tengah runtuhnya hukum dan peraturan.
Pemerintah dunia bersama WHO memerintahkan penguncian total hingga solusi ditemukan. Namun di lapangan, masyarakat tak mau pasrah. Seperti yang kubilang, keserakahan manusia tertanam terlalu dalam. Mereka saling berkelahi demi tabung oksigen murni di rumah sakit, sementara tabung penuh pun kian menipis.
Hari menjelang senja, teriakan adikku tiba-tiba menyobek keheningan kamarku. Jantungku melonjak, napas tercekat oleh ketakutan. Aku terbang keluar pintu, berlari tanpa memikirkan apa pun selain suara panik yang memanggil namaku.
Tiba di ruang keluarga, pandanganku membeku kakek, nenek, mama, ayah semua terbaring tak bernyawa. Tubuh mereka membiru kehitaman, mulut mengeluarkan busa putih, mata yang dulu hangat kini kosong pucat. Dadaku sesak, tangan gemetar mengepal, seolah otot-ototku menolak kenyataan ini.
Suara sirine ambulans memecah kaku, aku tiba di rumah sakit beberapa menit setelah abang ku menelpon nomor darurat. Aku terbatuk, suaraku serak saat bertanya, “Apa yang terjadi?” Tak ada jawaban hanya langkah cepat orang-orang yang mengevakuasi jenazah. Di sekitarku, keluarga lain menangis histeris. Dokter yang menangani kedua orang tua, kakek dan nenek ku akhirnya membuka suara, ia mengatakan dengan jelas membuat ku tak pernah lupa bahwa “partikel komet mencemari oksigen dan kini merusak imunitas semua orang.“
Teriakan dan tangisan jadi sorak duka di koridor rumah sakit, berganti tanpa henti. Setiap detik muncul nyawa baru yang pasrah menjemput ajal. Para dokter sang prajurit berjubah putih berteriak memanggil “pasien membutuhkan oksigen murni,” mereka juga menyalakan alat meski mereka tahu perjuangan ini nyaris sia-sia.
Di tengah riuh itu, aku berjalan tanpa arah. Kaki lunglai menapak lantai dingin, pikiran kosong menatap deretan ranjang berisi mayat membiru kehitaman. “Mengapa ini harus tragis? Mengapa kakek, nenek, Mama, Ayah? Mengapa bukan aku saja?” gumamku, suaraku tercekat. Bahuku terhuyung menahan beban duka.
Angkuh aku menentang Tuhan. “Aku benci Engkau! Mengapa merenggut mereka? MENGAPA?!” Teriakku ke langit senja. Tanganku memukul dinding keras berulang kali, tetapi hantaman itu tak mampu mengusir pedih di hatiku.
“Aku MINTA lebih sakit lagi!” bentakku, lalu terdiam. Energi di tanganku padam seiring tubuhku kehabisan tenaga. Isak tangis menggantikan amarah, air mata menetes tanpa henti, membasahi lengan dan pipi.
Angin malam merangkulku, hujan rintik menari di jendela. Senja tak kunjung menutup dengan indah, awan tebal menutupi sisa cahaya, seolah alam sendiri meratap. Waktu berlalu tanpa arah, aku tak tahu jam berapa, tak tahu harus ke mana. Hanya kehampaan yang menemaniku.
Tiba-tiba sebuah pelukan hangat mencengkeram tubuhku dari belakang. Suara lembut terbisik di telingaku, “Sudah, Rika. Abang di sini.”
Aku terdiam. Tubuhku rapuh, tapi pelukan itu seolah menjadi satu-satunya titik tumpu. “Kenapa bisa seperti ini?” suaraku nyaris hilang di antara deru angin.
“Inilah takdir, adikku. Abang akan selalu menjagamu,” jawabnya mantap, suaranya bagai karang di tengah badai. Aku tak mampu membalas, hati ini terlalu lelah berharap.
Adikku yang satu-satunya ku sayangi, ia pergi pukul sembilan malam itu, dalam ruang yang sama di mana keluarga kami meninggal. Keheningan menggantikan teriakan. Seharusnya aku yang meraung, tapi suaraku terkunci dalam dada.
Abang memecah senyap. “Rika, mau ke mana?”
Aku menoleh sekilas, lalu melangkah pergi tanpa kata. Langkahku sempoyongan, kepala pening bagai habis diputar putar komedi putar.
Di lorong rumah sakit, derap kakiku bergema monoton. Abang mengekor di belakang, menawarkan kata penghibur yang kupandang hampa. Aku duduk di kursi tunggu, menatap langit-langit retak, hati menolak segala kata penenang itu.
“Percuma,” gumamku. Tangan mengepal kain celana, air mata jatuh menetes ke paha. “Abang juga akan pergi, kan?” suaraku hampir tak terdengar.
Wajahnya terkejut, air mata menggenang di sudut mata tegarnya. “Rika, apa maksudmu?” tanyanya lirih.
“Jangan bohong. Tubuhmu mulai memberiku dengan cepat, aku tahu kau takkan lama.”
“RIKA, CUKUP!” bentaknya, suaranya bergetar. Ia menunduk, tersedu. “Abang yakin akan sembuh. Ini hanya mutasi. Percayalah padaku. Jika pun abang pergi, abang takkan mendahuluimu.”
Aku terdiam, menunduk, meremas kain di pangkuan. “Kenapa abang begitu keras kepala?” bisikku.
“Hanya satu alasan: karena kau adikku, keluarga terakhir yang harus kubela.” Ia merangkulku erat—seolah takut melepaskan. Aku tahu, ia mungkin yang pertama pergi.
***
31 Juli 2061. Laporan terbaru: 1,5 miliar nyawa sirna dalam sehari. Bisikan perawat di sudut ruangan memberi bocoran pahit “tak ada obat, hanya ketahanan antibodi masing-masing”. Debu partikel komet Halley merubah struktur oksigen, mengkontaminasi setiap tarikan napas dengan energi beracun. Tabung oksigen steril? Habis direbut Hyper yaitu sebutan untuk para penyintas yang berhasil berevolusi dan bermutasi yang kini mendapat kekuatan super.
Semestinya kabar ini menyalakan harapanku, tapi hatiku beku. Impian kekuatan berubah jadi mimpi buruk. Dunia porak-poranda demi mewujudkan permintaanku. Abang pun terbaring kian lemah, janji-janji kosongnya tinggal gema.
“Bang, ayo cepat ke rumah sakit,” kataku panik, menopang tubuhnya yang lunglai.
“Sudah… uhuck,” batuk berdarah, warna kulitnya berubah kebiruan semakin gelap.
Tubuhnya terhuyung, suara hampir padam mengabarkan, “Jangan ke rumah sakit… nanti terpapar lebih parah. Abang ingin kau hidup.”
“Apa?! Tapi kau janji…”
Ia tersenyum lemah, tawa kecilnya getir. “Maaf, Rika. Ini terbaik.” Kata-kata terakhir sebelum matanya memutih, raganya tak lagi bernyawa.
Aku terjengkang, lutut menyentuh lantai dingin ruang tamu. “Terbaik? Padahal aku tak bisa mati lebih cepat.”
Jam menunjukkan hampir pukul lima sore. Matahari pun hendak pergi, meninggalkan aku sendiri di lorong sunyi ini.
Aku menarik napas panjang, suara angin dan debu jadi saksi. “Sudahlah. Air mataku kering. Mentalku siap.”
Sore berakhir tanpa isak, hanya desir angin menuntun debu melewati tubuhku. Aku terjatuh, pingsan di lantai, lelah memapah jenazah abang ku sendiri dari rumah ke rumah sakit. Setidaknya dirinya yang ku sayangi bisa mendapatkan pemakaman yang lebih layak dari pada di biarkan terkapar di ruang tamu yang berdebu.
***
Entah berapa lama aku tertidur. Saat sadar, mataku ditusuk cahaya lampu ruang rumah sakit. Dokter dan perawat berseliweran dengan troli, wajah mereka serius.
“Di mana abang saya?” suaraku parau.
Dokter menunduk, nada pilu “Kami menemukan kalian di halaman, nak. Abangmu… sudah tiada.”
Pipi basah. Kutelan ludah, terkejut air mata masih bisa keluar, aku terisak hingga teriakan ku terdengar ke lorong rumah sakit.
3 menit berlalu, ketika diriku mulai tenang. Aku bertanya dengan nada serius menatap sang dokter yang menunggu ku tenang.
“Dokter, di mana TV? Saya… perlu melihat berita.”
“Di ruang tunggu,” jawabnya singkat.
Aku bangkit, melepaskan infus, lalu berlari menembus lorong pengap. Di depan TV, muncul angka mengerikan.
1 Agustus 2061, 1,3 miliar jiwa lenyap. Tersisa 7,37 miliar manusia.
Aku tak tahan. Meninggalkan rumah sakit tanpa sepatah kata. Di lorong, keluarga pasien menunduk pilu. Aku tahu, mereka sepertiku, Hyper yang tak bisa mati, tapi terus kehilangan orang tercinta.
Berlari empat menit sampai gerbang, kemudian terus ke rumah yang hancur. Pintu reyot kuketuk, kupanggil pelan, “Aku pulang.”
Ruang keluarga sunyi dulu tempat tawa, kini hanya kenangan pahit. Kupaksa diri membuka kulkas: hanya ada mie instan. Genetika mutasi mungkin melindungiku dari sakit, tapi perut lapar tak peduli.
Beberapa hari kulalui dengan harapan palsu. Energi negatif mengalir mendorong ku mundur ke jurang kesepian. namun dunia akan tetap memburuk , perlahan jumlah manusia terus merosot.
2 Agustus 2061: 1,1 miliar kematian.
3 Agustus: 940,5 juta.
4 Agustus: 799,5 juta.
5 Agustus: 679,5 juta.
6 Agustus: 417 juta.
7 Agustus: 417 juta—hari terakhir kematian masal.
Dunia menua, menyisakan 2,36 miliar dari 12 miliar jiwa. Peristiwa ini dikenang sebagai Ledakan Evolvera. Para Hyper di anggap sebagai manusia terpilih telah mewarisi kekuatan sesuai jiwa mereka, apakah mungkin ini adalah puncak Evolusi mahluk perusak seperti kita? Mahluk yang telah merusak dunia bahkan sebelum menerima kekuatan besar.
“Seiring dengan kekuatan yang besar, datang juga tanggung jawab yang besar.” (Stan Lee)
Tapi apalah guna kekuatan yang hebat, jika bayarannya seluruh keluarga dan teman yang engkau cintai. Pada akhir di antara puing duka dan kehampaan, aku hanya memandang langit yang kelam, pasrah pada takdir yang belum usai.


 silvius
silvius 



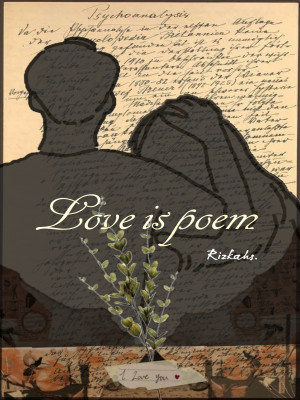





Halo readersvol. ada perubahan jadwal upload mulai bab berikutnya. Evolvera Life akan upload bab baru setiap 3 hari sekali. Terimakasih sudah menikmati cerita.