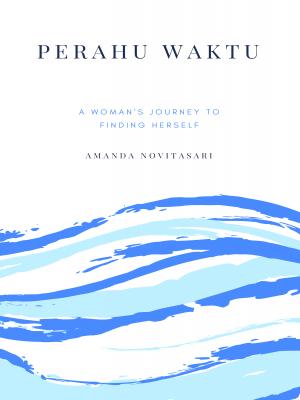Aku menghirup dan mengembuskan napas beberapa kali untuk menghilangkan kegugupanku. Itu dia di sana. Hanya beberapa meter dariku. Dia duduk di sebuah booth penandatanganan buku, sambil sesekali mengobrol dengan beberapa orang yang menghampirinya. Kalau tidak ada orang, dia akan melanjutkan menandatangani bukunya. Orang-orang silih berganti meminta tanda tangannya di buku yang sudah mereka beli, tapi aku belum juga berani melangkahkan kaki ke sana.
Dua hari sebelumnya, aku melihat temanku memposting di story Instagramnya bahwa akan ada penandatanganan buku Life Map Muslim Gen Z di Gramedia Matraman lantai 3 oleh penulisnya. Gio Andreas. Saat itu aku merasa jantungku mau copot. Apa ini benar? Apakah aku akhirnya bisa bertemu langsung dengan sang penulis?
Sebulan sebelumnya, aku melihat teman yang sama mempromosikan buku tersebut. Kebetulan temanku bekerja sebagai layouter di sebuah penerbit dan buku itu salah satu naskah yang ditanganinya. Entah mengapa aku langsung tertarik membeli buku itu, padahal selama ini aku kurang suka membaca buku pengembangan diri. Aku lebih suka membaca novel thriller. Namun, aku tidak terlalu memusingkannya. Aku langsung membelinya dan membaca buku itu. Ternyata sangat mencerahkan.
Alasan aku sangat ingin bertemu Gio Andreas secara langsung bukan karena isi buku tersebut.
Saat aku tuntas membaca buku tersebut, aku melihat bionarasi penulis di bagian belakang buku. Dia mencantumkan laman media sosialnya. Jadi, aku membuka Instagram dan mencari nama si penulis. Saat aku melihat foto profilnya dan beberapa foto di postingannya, aku syok.
Apa benar ini dia?
Jemariku gemetar selagi aku menggulir layar, melihat satu demi satu fotonya untuk meyakinkan diriku sendiri bahwa itu memang dia. Aku tidak tahu harus melakukan apa. Saat itu aku hanya berdoa: Ya Allah, jika memang dia, mudahkanlah jalannya.
Maka, di sinilah aku. Akhirnya aku berkesempatan melihatnya secara langsung, bertemu langsung dengannya. Namun, apakah aku akan mengambil kesempatan itu, melangkah ke sana dan memperkenalkan diri? Atau aku akan melepaskan kesempatan itu dan tidak tahu kapan akan berjumpa lagi dengannya?
“Bismillah,” ucapku lirih sembari melangkah ke booth Gio.
Aku menyapanya dengan sopan tanpa berlebihan dan menyodorkan bukuku. Gio menandatanganinya dan bertanya hal-hal remeh sebagai sopan santun.
“Oh iya, kayaknya aku pernah lihat Kak Gio di Tanah Haram 6 bulan lalu waktu umrah,” ujarku.
Gio terkejut. Kedua alisnya tertaut. “Wah, saya belum umrah, Mbak.”
Kali ini aku yang terkejut. Aku sangat yakin itu Gio! Sangat jelas, aku tidak salah lihat.
“Oh, begitu. By the way, terima kasih,” aku melambaikan buku yang baru saja ditandatanganinya. “Mari, Kak.”
Gio tersenyum sopan dan mengangguk.
Saat aku berbalik, tak sengaja aku menabrak seseorang. “Niken?”
“Elysa? Hai, apa kabar?”
***
Ketegangan dan gegap gempita menyambut pernikahan sudah berlalu. Tak kusangka, melaksanakan pernikahan ternyata memberi banyak tekanan. Padahal bukan aku yang menikah. Ya, saudari kembarku yang hampir selalu bersamaku sejak dalam kandungan, Erica, menemukan jodohnya. Dia akan mengarungi sisa hidupnya bersama lelaki pilihannya. Aku turut senang untuknya, tapi di saat yang sama merasa sendu.
Erica dan calon suaminya memutuskan akan langsung tinggal terpisah dari keluarga. Calon suaminya sudah menyiapkan tempat tinggal untuk mereka. Jadi, selain mempersiapkan dokumen-dokumen pernikahan dan acara pesta, kami juga mempersiapkan rumah itu agar bisa langsung dihuni setelah akad nikah. Hal itu meliputi memindahkan barang dari kamar Erica ke rumahnya yang baru secara bertahap, membeli beberapa furnitur baru dan menatanya rumah baru. Aku, Erica, dan Mama, sering sekali ke rumah baru Erica sebelum pernikahan untuk melakukan itu semua, terkadang dibantu calon suami Erica dan juga Erwan, adik lelakiku.
Kurasa itu juga cara Mama untuk melepas Erica. Mama jelas sekali terlihat sedih harus melihat putrinya menikah. Anak yang dikandungnya selama sembilan bulan, yang dirawat dan dibesarkan dengan cinta, yang dia kenali suara tawa, aroma tubuh, dan kebiasaannya, tiba-tiba meninggalkan rumah untuk membangun keluarga sendiri. Mungkin Mama mengira anak-anaknya akan di sisinya selamanya.
Bagaimana kalau aku menikah nanti, ya?
Akad nikah Erica telah dilangsungkan. Berlokasi di masjid besar dekat rumah kami, Papa melimpahkan tanggung jawab dan penjagaan atas Erica kepada lelaki ‘asing’ yang segera menjadi menantunya itu. Tangis haru mewarnai acara, diiringi senyum bahagia kedua mempelai.
Kini, euforia pernikahan telah mereda. Aku kembali pada aktivitasku sehari-hari. Namun, setelah kemeriahan pesta, rasanya sekarang ada lubang hitam di dalam hari-hariku. Tanpa kesibukan mempersiapkan pernikahan Erica, kini aku jadi punya banyak waktu untuk merenung. Kian lama pikiranku kian menarikku ke jurang perasaan kesepian.
Aku ingin menikah juga.
Aku ingin berbagi hidup dengan seorang pria yang akan menyayangiku.
Aku ingin bercerita kepadanya tentang hari-hariku.
Hati tidak bisa berbohong. Aku sudah lama ingin menikah, melihat saudariku menikah lebih dulu membuatku merasa terluka.
Kenapa dia yang menikah duluan?
Kapan aku akan bertemu jodohku?
Yang kurasakan bukan hanya sejenis rasa iri, tapi lebih tepatnya mendamba. Sebuah perasaan yang kurasa tak ada obatnya, selain dengan menikah itu sendiri.
Hatiku terasa sangat sempit, tidak muat menampung segala rasa sakitku. Aku harus menumpahkan perasaanku di tempat yang tepat: di ‘pangkuan’ Allah Al-Wasi’, Yang Maha Luas. Maka, keputusan itu pun kubuat.
“Ma, Pa, kita umrah, yuk.”
***
Keluargaku bukan keluarga yang religius. Bahkan, aku perempuan pertama di rumah ini yang mengenakan hijab. Di rumahku, jangan dikira terdengar lantunan tilawah atau nasihat takwa. Juga tidak pernah ada motivasi untuk bermimpi umrah atau menunaikan haji. Bukan karena orang tuaku tidak mampu, tapi memang tidak terpikirkan saja. Sesederhana itu. Jadi, tak heran ajakanku saat makan malam itu membuat kedua orang tuaku mengangkat alis.
“Umrah?” Tanya Papa.
“Gimana, ya? Kamu, ‘kan, tahu sendiri Mama sehari-hari belum pakai kerudung. Mama juga gak pintar-pintar amat perihal agama. Rasanya belum pantas. Mama masih banyak dosa, takut di sana kenapa-kenapa. Kata orang, di sana itu cepat dapat balasan akibat keburukan kita.”
Aku tersenyum lembut kepada Mama. “Umrah itu syariat Islam, Ma. Gak harus pinter agama untuk bisa umrah. Lagi pula, umrah dan haji itu jihadnya kaum wanita. Pahalanya besar sekali untuk kita, kalau kita ikhlas. Justru, dengan umrah, Mama bisa puas-puasin berdoa dan minta ampunan Allah di tanah suci.”
“Pa,” kali ini aku menoleh kepada Papa. “Mau, ya, Pa? Elysa ingin banget kita umrah sama-sama.”
Papa tidak punya dalih untuk menolak. Setelah beberapa waktu Papa terlihat berpikir, Papa pun menyetujui. “Baik, kalau begitu. Kita umrah. Papa, Mama, Elysa, dan Erwan. Elysa, kamu urus ticketing dan segala keperluannya, ya.”
Hatiku melambung mendengar jawaban Papa.
“Erica dan suaminya gimana?” Tanya Erwan.
“Kalau mereka mau umrah juga, nanti Papa biayai, tapi sekarang biarkan mereka beradaptasi dulu menjadi suami-istri.”
Meski baru saja mengadakan pesta pernikahan untuk Erica, yang menghabiskan biaya yang tak sedikit, aku tahu tabungan Papa pasti masih banyak. Bahkan, mungkin cukup untuk berangkat haji tahun ini. Namun, seperti yang kubilang, orang tuaku tidak ada ketertarikan melaksanakan ibadah ke tanah suci itu. Siapa tahu, setelah umrah, hati mereka terbuka untuk melaksanakan rukun Islam kelima itu.
Alhamdulillah.
Persetujuan dari Papa adalah lampu hijau. Semangatku menggebu-gebu. Aku merasa seperti akan bertemu seseorang di Tanah Haram dan aku tidak sabar.
***
Setelah mengurus segala keperluan, mulai dari mendaftar di agen travel umrah, bikin paspor, menyiapkan perlengkapan yang perlu dibawa, menuntaskan pekerjaan-pekerjaan freelance-ku dan mengatur pesan otomatis bahwa aku tidak akan bisa dihubungi selama 2 minggu, lalu training manasik umrah, akhirnya kami berempat berada di bandara internasional Soetta untuk berangkat.
Selama penerbangan, aku tak henti-henti berzikir dan membaca doa-doa dari buku saku yang disediakan agen perjalanan. Aku menenggelamkan diriku di dalam untaian kalimat thayyibah, membisukan semua urusan duniawi dari kepalaku. Tidak memikirkan pekerjaan. Tidak memikirkan jodoh dan masa depan, atau masa lalu. Tidak memikirkan orang lain. Hanya fokus pada diriku dan Allah.
Begini, ya, nikmatnya beribadah. Hanya beribadah.
Aku membayangkan Maryam ‘Alaihassalam yang menghabiskan usia mudanya beribadah di mihrabnya. Tidak ada kekhawatiran apa pun. Hanya menyibukkan dirinya mendekatkan diri kepada Allah. Rasa-rasanya, aku ingin hidup yang seperti itu saja.
Tapi itu tidak mungkin.
Tidak mungkin aku hanya mengurung diri untuk salat dan berzikir, sementara mengabaikan peran sosial. Jangan menjadi seperti pertapa! Kalau semua orang berpikir menjadi seperti itu, umat ini akan hancur. Roda ekonomi akan terhenti, pendidikan terabaikan, dan tidak ada yang berinovasi untuk keperluan umat. Begitu lah yang sering kudengar di pengajian.
Aku menyadari keinginanku untuk mengurung diri dan beribadah itu hanyalah dalih. Padahal aku ingin melarikan diri dan bersembunyi. Lemah banget, ya? Bukankah Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wassalam menyuruh kita untuk melakukan hal yang bermanfaat, jangan bersikap lemah, dan tetap meminta pertolongan Allah?
Jadi, ya, begitulah. Sepulang dari umrah ini, aku akan kembali melakukan aktivitas sehari-hari. Sakit hati, bersedih, kecewa, itu hanyalah bagian dari kehidupan. Justru, di situlah ladang pahala bagiku, jika aku mampu bersabar. Bahkan bisa menjadi penghapus dosa-dosaku.
Sementara itu, biarkan aku terhanyut di dalam kekhusyukan di tanah suci. Biarkan aku mengisi ulang ‘tangki cintaku’ dengan berkhalwat kepada Sang Malik. Agar aku kembali kuat menghadapi badai yang menerpa. Agar aku kembali semangat mengejar pahala.
***
Seluruh muslimin dari berbagai negeri, ras, usia, warna kulit, warna rambut, warna mata yang berbeda, berkumpul di sini. Membuatku merasa aku bukan siapa-siapa, hanya salah satu dari hamba-hamba-Nya.
Ya, Allah menunjukkan kuasa-Nya, bahwa Dia lah yang menciptakan kita semua, memberi rezeki kepada kita, menetapkan takdir bagi masing-masing kita dengan takdir yang unik dan diukur sedemikian detail. Karenanya, hanya Dia satu-satunya yang layak untuk kita mengabdikan hidup kita dan kepada-Nya tempat kita bersandar.
Ya Allah…
Sekali lagi aku mengerjakan salat sunnah mutlak 2 rakaat. Tidak perlu buru-buru di sini. Aku menikmati setiap rukuk dan sujudku. Kalau aku lelah, aku akan duduk saja di atas sejadahku atau mengobrol dengan Mama yang juga salat di sampingku. Namun, kebanyakannya kami khusyuk dengan ibadah masing-masing. Membaca Al-Quran atau berzikir dengan tasbih digital, sembari menatap bangunan kubus dengan kiswah hitam di tengah sana. Lalu aku akan salat lagi dan memanjangkan sujudku. Menumpahkan semua keluh-kesahku.
Satu waktu, ada seorang muslimah bersama kedua putrinya duduk di dekatku. Dia menghamparkan sejadah di sampingku. Anak-anaknya mungkin berusia 5 dan 6 tahun. Kedua gadis kecil itu kadang mengobrol dengan Bahasa Arab, sambil makan roti yang sudah disiapkan ibunya. Kadang, gadis yang lebih besar membacakan bukunya kepada si adik. Pemandangan itu membuatku tersenyum. Melihat anak-anak membuat hatiku menghangat.
“Assalamu ‘alaikum,” sang ibu menyapaku. Usianya mungkin hanya 5 tahun lebih tua dariku. Aku menjawab salamnya sambil tersenyum. Dia lalu bertanya, “You’re from Malaysia?”
“No, no. I’m Indonesian.”
“Oh, I thought you’re Malaysian. I have a friend in Malaysia.”
“Oh, really? And where’re you come from?”
“I’m from Gaza.”
“Gaza… Like, in Palestine?”
Muslimah tersebut tersenyum dan mengangguk.
“Allah…” air mataku langsung menggenang. Aku teringat berita-berita tentang Palestina. Bagaimana mereka selama puluhan tahun ini dijajah dan mereka tak pantang menyerah melakukan perlawanan untuk meraih kemerdekaan mereka. “Palestine will be free.”
“It will. It will,” ujar muslimah itu. Dia tersenyum lembut dan mengusap-usap pundakku, menenangkanku.
Pertemuan yang singkat dengan wanita Palestina itu membuatku merenung. Memang betul kata orang-orang, keimanan kita kalah jauh kalau dibandingkan dengan keimanan muslimin di Palestina sana. Meski kita tidak bisa menilai isi hati orang, tapi keimanan itu tercermin di dalam perbuatan. Contohnya saja tadi, malah wanita Palestina itu yang menenangkanku dengan suaranya yang penuh keyakinan.
Di sisi lain, betapa lemahnya mentalku, ya? Hanya karena belum menikah, aku galau begitu hebatnya sampai-sampai ingin mengasingkan diri. Aku menggeleng pelan dan menertawakan diriku sendiri dalam hati.
Elysa, bukankah mencari rida Allah adalah tujuan hidupmu? Bukan menikah atau mencari pasangan hidup lah yang menjadi tujuan.
Meski kalau dibandingkan, ujian hidupku tidak ada apa-apanya dengan perjuangan muslimin di Palestina, atau Suriah, atau di tempat lainnya, tapi ujian hidupku harus kujalani. Setiap orang diuji dengan ujian yang berbeda-beda, bukan? Mungkin saat ini ujian hidupku adalah kecemasan karena belum menikah. Namun, mungkin nanti setelah menikah aku akan mendapat ujian lain. Selalu begitu, kan? Hidup memang tempat ujian, agar kita bisa memantaskan diri masuk surga lewat ujian-ujian itu.
Pada hari terakhir kami di Mekkah, aku berdoa sungguh-sungguh kepada Allah: “Ya Allah, tunjukkanlah kepadaku siapa yang akan menjadi jodohku nanti… supaya hilang kecemasanku. Supaya aku bertambah yakin dan bertambah keimananku kepada-Mu.”
Ada sisi diriku yang menganggap doaku itu konyol. Namun, ternyata Allah tidak pernah ingkar janji, bahwa Dia menjawab setiap doa. Seusai aku salat dan bersiap untuk pergi, aku mengalami sesuatu yang ajaib. Lautan manusia di hadapanku terbuka, seperti Laut Merah yang terbelah untuk memberi jalan bagi Nabi Musa ‘Alaihissalam, dan menampakkan sesosok lelaki berwajah orang Indonesia, dengan kulit agak sawo matang, tubuhnya tegap mengenakan kain ihram putih, dan rambut hitam cepak. Tubuhnya memang menghadapku, tetapi dia tidak memandang ke arahku.
Waktu seakan terhenti.
Meski terbentang jarak yang cukup jauh di antara kami, aku bisa melihat wajahnya dengan sangat jelas.
Astgahfirullah. Ketika sadar aku tengah memandangi wajah seorang lelaki, aku langsung menundukkan pandangan. Momen ajaib itu sirna secepat datangnya. Meski aku hanya melihatnya sekitar 5 detik, tapi aku tetap bisa mengingat wajah itu dengan jelas. Saat aku mendongak lagi, lelaki itu hilang ditelan lautan jamaah.
Aku tidak pernah lagi memikirkan kejadian itu, sampai aku melihat profil penulis buku tersebut. Itu adalah dia. Aku yakin itu.
***
Setelah berbincang sebentar dengan Niken, temanku yang merekomendasikan buku itu, aku pun meninggalkan toko buku. Aku kembali teringat kejadian waktu umrah kemarin. Aneh sekali. Aku yakin pria yang kulihat waktu itu adalah Gio. Namun, seperti yang Gio bilang, dia belum pernah umrah.
Aku menggeleng kecil dan terkekeh dengan pikiran konyolku. Jangan-jangan dia punya kembaran, dan kembarannya itu yang kulihat waktu di Makkah?
Entah apa yang dikatakan Niken kepada Gio setelah aku pergi. Dua hari kemudian, aku menerima Direct Message dari Niken.
Sebenarnya, sudah sering aku mendengar cerita-cerita aneh atau ajaib yang terjadi di Makkah dari orang-orang yang sudah melaksanakan haji atau umrah. Aku menjadi yakin, yang kualami waktu itu adalah salah satunya. Maksudku, Allah memang Mahakuasa berbuat sesuatu. Terlebih, di rumah-Nya, di Baitullah, tentu tempat itu adalah tempat paling mungkin Allah menunjukkan kemahakuasaan-Nya.
Gio tidak sedang umrah waktu itu, tapi Allah menghadirkan sosoknya di depan mataku sebagai jawaban atas doaku.
Aku berdoa dan Allah mengabulkannya. Allah menjawab doaku.
Pesan dari Niken berbunyi:
“Lys, lo mau gak ta’aruf sama Gio? Gw kirimin CV nya ke email lo, ya.”
Ya, Allah menjawab doaku.


 yuniyustikasari
yuniyustikasari