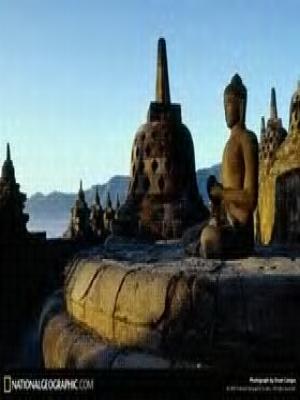Cori menemukan kenyamanan duduk diapit oleh kedua orang tuanya. Perasaan hangat menyergap secepat maaf yang datang meski terlambat. Hatinya yang kosong akan kasih sayang mulai terisi sedikit-sedikit. Tidak mengapa. Semua butuh proses, butuh waktu.
Dan yang lebih menyenangkan adalah, Mutia tak melepas genggaman tangannya dari tangan Cori yang tak lagi membengkak. Meski tangannya kaku digenggam sejak tadi, Cori memprediksi kegiatan baru ini bakal mengasyikkan.
Abang pasti seneng kalau tahu Mama menemuiku.
Sedetik kemudian, dia menggigit bibir bawahnya kuat-kuat, menyesal karena membiarkan dirinya ceroboh meliarkan pikirannya akan angan indah tadi.
"Kami berdua menemui Popy seminggu yang lalu," cetus Sudjana tiba-tiba.
"Untuk apa, Pa?"
"Bisa dibilang, memperbaiki sebuah hubungan yang seharusnya bersatu sejak lama," sambungnya misterius. Cori mengernyitkan keningnya.
"Percaya atau tidak, Mbak Popy duluan yang menghubungi papamu. Dia curhat, Ben menolak semua bakal calon istri yang Mbak sodorkan setahun belakang. Mbak Popy ndak tega lihat anaknya selalu bermuram durja setiap setelah memandang foto kamu di ponselnya. Sekarang, Ben jadi jarang pulang semenjak kalian putus. Mbak merasa Ben menjauhi rumah-nya"
Abang...
"Untuk apa Mama dan Papa memberi tahu Cori informasi tadi?" pungkasnya. ia ingin mencari ujung dari pembicaraan ini.
Terlalu banyak informasi enggak penting tentang dia Ma, Pa. Sedetik kemudian Cori meralat pikirannya sendiri. Oke, oke. Penting banget!
"Kabarnya Ben ada di Jakarta," tukas Mutia.
“Lalu?”
"Papa tahu kamu belum bisa melupakan Ben sebagaimana Ben juga ndak bisa melupakan anak Papa. Jadi, mulailah petualanganmu lagi dengannya, Nak. Kamu telah mendapat restu dari kami, para orang tua."
***
Seseorang meletakkan piring nasi pecel di depan piring nasi iga bakarnya. Belum jadi mendongak melihat siapa pelakunya, Ben dibuat kaget setengah mati dengan suara yang menyapanya.
"Abang kenapa makan sendiri?"
Berkali-kali ia kedipkan matanya demi membersihkan debu atau apapun yang mungkin mengganggu penglihatannya. Ben pikir ada yang salah dengan bola matanya. Nyatanya tidak. Tidak ada yang salah, hanya sosok itu saja yang tampak berbeda.
Ia duduk dengan anggun di meja yang sama dengannya. Berhadap-hadapan. Padahal masih banyak meja kosong lain tak berpenghuni di kantin PT. Sejahtera Bersama. Tapi Ben tidak akan protes.
"Ada nasi di dagu Abang. Udah gede makannya masih belepotan."
Sebutir nasi itu kini masuk ke piring nasi pecelnya. Ben menganga seperti orang bodoh.
Darahnya berdesir hebat gegara sentuhan tadi. Dia yakin semua penghuni kantin tengah melihat aksi kecil barusan. Tapi Ben tidak peduli. Ia lebih peduli dengan sosok yang sedang memakan sayur-sayur hijau tanpa wajah penolakan.
Ben yakin rasa itu tidak pernah berubah meski seseorang yang sedang memakan nasi pecel dengan lahap ini telah berubah banyak. Tidak ada pipi chubby lagi, rambut legamnya yang lurusnya menjuntai bebas di atas bahunya. Namun, cantiknya tetap di sana. Mau pipinya tirus atau chubby, Ben tidak peduli. Sebab, kecantikannya masih sama seperti yang Ben rekam terakhir kali di dalam memori di Bandara Hang Nadim saat ia mengantarnya keluar dari Pulau Batam 547 hari yang lalu.
Ya. Pria malang ini menghitung hari perpisahannya dengan si Gadis Ketumbar. Maka dari itu, ia tak mau menyia-nyiakan kesempatan emas ini untuk berlama-lama memandangnya. Mana tahu ini adalah makan siang terakhir mereka.
"Sekarang Abang tugas di mana?"
“Makassar.”
"Sudah berapa hari Abang di kantor pusat?"
"Tiga hari."
"Berapa hari lagi Abang di Jakarta?"
"Empat hari," jawabnya bak robot. Cori mengangguk sekali.
"Jadi waktu kita hanya tersisa empat hari." Lalu Cori menyendok nasi dengan toping daun bayam rebus dan saus kacang ke mulutnya.
"Waktu ... kita?"
"M-hm." Anggukannya membuat Ben makin bingung. "To catch everything up for the last one and a half year."
"Tunggu. Sejak kapan kamu makan sayur?"
"Dari semua pertanyaan tentang aku setelah sekian lama, Abang nanyain sejak kapan aku makan sayur?" Cori terkekeh, membuat Ben terlena. Sudah lama ia tidak mendengar tawa perempuan ini. Perempuan yang selalu mampir dalam benaknya tanpa permisi.
"Iya," jawabnya mantap.
"Kayaknya sejak kita makan bibimpab di restoran Myong-Ga, deh. Ternyata rasa sayur enggak seburuk itu."
Ben mengangguk-anggukkan kepalanya seperti boneka goyang di dashboard mobil.
"Makan, Abang. Waktu istirahat tinggal 20 menit lagi."
Ben mengangguk patuh dan menghabiskan sisa iga bakar yang sempat ia abaikan dalam kecepatan super. Ia tidak mau berlama-lama makan sedangkan ada banyak hal yang ingin ia sampaikan pada Gadis Ketumbar ini.
Piring kosong Ben disingkirkan dengan cepat. Cori pun demikian.
"Cori."
"Apa, Abang?"
"Ini ... ini beneran, kan?"
Lagi-lagi Cori terkekeh. Setelah menuntaskan kegelian di perutnya, Cori mencondongkan tubuhnya pada Ben.
"Mau cubit pipiku? Tapi enggak empuk kayak dulu, ya?" peringatnya sambil tersenyum malu-malu.
Alih-alih mencubit, dia hanya ingin mengatakan ini pada Cori.
"Aku ... boleh peluk?"
Lepas sudah tawa Cori di kantin Sejahtera Bersama, membuat beberapa pasang mata menoleh penasaran. Ben tidak mau tawa barusan menjadi tontonan gratis pria-pria antah barantah. Dia hanya ingin tawa tadi ekslusif untuknya.
Tapi ... siapa dia untuk Cori?
Kali ini Cori tidak akan memukul lengan mantan kekasihnya gara-gara mulutnya yang 'nakal'.
"Nanti ya, Abang. Nanti waktunya akan datang," bisiknya playful. "Kalau kita udah nikah. Eh, memangnya Abang masih mau nikah sama aku?"
"Tentu saja Abang masih mau menikahi kamu, tapi ... enggak semudah itu, Coriander. Bunda..." Ben tak sanggup melanjutkan kalimatnya, karena hanya akan membuat dadanya terhimpit batu granit Natuna sekali lagi.
"Cuma itu jawaban yang ingin aku dengar. Makasih katena enggak pernah mengubah niat Abang."
"Maksud kamu?"
Cori memberi seringaian misterius.
"By the way, cincin safir Abang muat nggak yah di jari aku? Kayaknya enggak perlu di-adjust deh ke toko perhiasan." Cori menunjukkan jari manis kanannya yang tidak bengkak lagi. "Untung dulu kita enggak pernah sempat ke toko emas. Soalnya jariku kurusan. Kayaknya sekarang bakal muat."
"Kita bisa memastikannya sekarang."
"Apa?" tanyanya bingung.
Ben mengeluarkan sesuatu dari dompet kulit hitamnya yang terselip di saku belakang.
"Abang bawa cincin itu setiap hari?" Senyum bahagia tak dapat Cori sembunyikan.
Tanpa perlu menjawab, tangan Ben dengan lihai menyelipkan cincin emas putih bermata biru itu ke jari manis Cori.
"Pas banget," gumam Ben tak percaya.
"Cantiknya," puji Cori, bersamaan dengan Ben.
"Cori ..." Suara memelas Ben membuat Cori mengalihkan matanya dari cincin di jarinya.
"Bagaimana aku bisa mengakhiri pertemuan kita dengan baik kalau kamu memberiku harapan? Kamu memberiku pilihan sulit, Coriander."
Ben yang malang. Ternyata ia tak sanggup menghadapi patah hati jilid dua.
"Abang ...."
"Kamu sudah tahu kita tidak akan berakhir seperti yang kita inginkan, Cori," bisiknya nelangsa. “Aku sayang kamu, hingga detik ini. Aku juga sayang Bunda, tapi—”
"Tapi Bunda udah nyuruh aku untuk segera bilang ke Abang kalau Bunda udah merestui kita. Maaf aku bikin Abang bingung," timpalnya menyesal.
"Hah? Gimana?"
"Papa dan Mamaku juga udah kasih restu. Dan Abang tahu? Ternyata mereka udah sering ketemuan di belakang kita untuk bahas gedung, katering, acaranya mau pakai adat atau mau pakai tema modern? Bunda dan Boni malah mau kasih kita hadiah honeymoon."
"Sebentar. Mama? Mama Mutia dan kamu ... udah baikan?"
"Udah. Ya, walaupun aku dan Mama lebih banyak canggung saat ngobrol, but it doesn't matter. Kami berdua hanya butuh waktu untuk adaptasi menerima kehadiran kami masing-masing."
"Abang turut bahagia mendengarnya. Sungguh."
"Terima kasih, Abang," ucapnya tulus.
Secercah senyum terbit di wajah tampan Ben yang sejak tadi kebingungan. Cori menghembuskan napas lega. Namun, sedetik kemudian wajah itu langsung suram.
"Abang mikirin apa?" tanyanya khawatir.
"Kalau kita menikah, masa harus berjauhan? Abang enggak bisa, Coriander. Kamu kerja di sini, sedangkan Abang di Makassar. Kita akan terpisah. Abang—"
"Aku akan menempeli Abang seperti permen karet ke manapun Abang ditugaskan, seperti rencana kita dulu," sela Cori lembut.
“Kamu ... yakin?”
"Aku nggak pernah seyakin ini seumur hidupku, Calon Suami."
Senyum mengembang kini hadir di wajah lelaki yang tak lagi bimbang, tak lagi durja. Jelaga hitamnya yang jernih perlahan berkaca-kaca, turut menularkan sensasi yang sama pada perempuan di hadapannya. Akhirnya air mata bahagia lolos di sudut mata mereka. Ben dan Cori sama-sama mengusap air mata bahagia.
"Boleh peluk kamu?" tanyanya sekali lagi.
"Boleh."
Membola mata Ben dibuatnya. "Bener?"
"Kalau udah ijab kabul."
Cori kembali membuat harapannya terhempas.
"Coriander ...." rengeknya bak anak TK.
"Tapi setelah ijab kabul ...." Kerlingan Cori membuat jantung Ben berdentam keras.
"Setelah ijab kabul?" ulang Ben. Kilatan mata si Auditor Senior membuat Cori bergidik. Tapi Cori tidak pernah berencana untuk mundur.
"Terserah Sayangnya Cori ini."
-Tamat-


 kepodangkuning
kepodangkuning