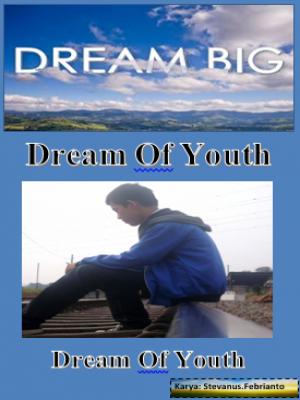"Win, alamat Cori di Kompleks Nuri 1, kan?" Moza menghadang Winnie ketika ia hendak naik ke lantai 2.
"Iya, Mbak."
"Cori di kluster Kepodang, kan?"
"Iya."
"NAH!"
Winnie terkejut sampai memegang dadanya.
"Lo apa-apaan sih, Mbak? Deket sama lo bikin umur gue berkurang 5 tahun," kesal Winnie.
"Iya, iya gue minta maaf."
"Dimaafin," katanya cepat. "Kenapa Mbak Moza tanya alamat Kak Cori?" tanya Winnie curiga.
"Lo mau tahu apa yang aneh dari alamat Cori?"
Winnie jadi mengurungkan niatnya menaiki undakan tangga, lalu mendekati Moza dengan rasa penasaran yang memuncak.
"Emang apa, Kak? Nggak ada yang aneh seinget gue."
"Ck! Ini anak pasti enggak tahu. Pak Malik sama Cori sama-sama tinggal di Kluster Kepodang, Win!"
"Heee? Imposibel. Enggak mungkin."
"Apa sih yang nggak mungkin di dunia ini?" Moza memutar bola matanya.
"Kenapa Kak Cori enggak pernah cerita ke gue?"
"Sengaja, kali?" Mata Moza menyipit curiga.
"Emang Mbak tahu dari mana alamat Pak Malik?"
"Gue kebetulan nemu paket Pak Malik di meja sekuriti." Winnie mengangguk-angguk.
"Eh tapi, apanya yang aneh? Menurut gue biasa aja. Berarti mereka tetanggaan. Selesai perkara."
"Jangan-jangan mereka tinggal berdu--"
"Mbak! Kalo ngomong ati-ati dong," sela Winnie buru-buru.
"Tapi menurut gue ada yang aneh dari mereka, deh," imbuh suara di belakang mereka.
Dua pasang mata itu menoleh pada Marzuki yang baru datang, lengkap dengan jaket kulit dan tentengan helm racing yang tidak bisa ditinggal sembarangan di parkiran.
"Kenapa lo bilang begitu, Ki?" Lagi-lagi mata Moza menyipit curiga.
"Soalnya..." Pria itu sengaja berhenti dan kepalanya menoleh ke kiri dan ke kanan seperti pencuri yang hendak menyambar target diam-diam.
"Soalnya?" ulang Winnie.
"Soalnya apa, Juki?" tanya suara berat dari arah ruangan kepala cabang Mega Legenda.
"Astaga naga! Bapak ngagetin!" teriak Marzuki.
"Yah Bapak. Bapak gangguin aja nih," protes Moza. "Juki lagi serius, Pak."
Yusuf bukan sedang kehilangan wibawa sebagai pemimpin cabang, tapi kepribadiannya yang friendly membuatnya sedekat itu dengan stafnya.
"Kalian! Ngobrolin apa, sih? Serius amat." Yusuf nimbrung tanpa diundang. Radar gosip Yusuf berdiri tinggi bagai tower provider seluler.
Tidak karyawannya, tidak bosnya, penyakit ingin tahu sudah menjangkiti semua lapisan hirearki di PT. Sejahtera Bersama.
"Itu lho, Pak. Kita baru tahu kalau Cori dan Pak Malik tetanggaan."
"Oooh, Malik tinggal di Perumahan Nuri 1 juga, Za?"
"Bener Pak. Yang bikin spektakuler, ternyata mereka sama-sama tinggal di Kluster Kepodang!" tambah Moza.
"Oh, ya?" Dahi Yusuf mengernyit samar.
"Terus Pak," sambung Marzuki. "Saya lihat mereka berdua jalan di mal."
"Okay. Lalu?" Yusuf, walaupun terlihat biasa, tapi lama-kelamaan gerak tubuhnya semakin condong pada Marzuki.
"Pak Malik ngerangkul Cori terang-terangan di depan umum!"
Semua mulut terkesiap. Mereka tak siap dengan berita panas barusan. Apa lagi Moza.
"Pak Malik ngerangkul Cori banget, Ki?" tanya Moza tak mau percaya.
"Setahu gue pacarnya Kak Cori kan Mas Arga, Bang."
"Iya. Bapak juga pernah dikenalin Cori sama pacarnya." Yusuf membenarkan. "Yang kerja di perusahaan gas negara."
"Lha, apa gue salah lihat? Ah, enggak. Kemarin mereka lagi di Es Teler 77, kok!" Marzuki tanya sendiri, jawab sendiri.
Moza? Kedua alisnya yang sudah dibentuk senatural mungkin dengan pensil alis hampir menyatu sempurna.
Pak Malik dan si Gembrot. Aneh!
***
Tepat ketika pintu rolling door dirapatkan oleh Tonggo pertanda jam pelayanan telah selesai, Winnie menghentikan pekerjaannya sejenak.
Bilang nggak, ya? batin si Kasir.
"Pak Malik nggak ke kantor, Kak?"
"Dia lagi nugas di Belakang Padang."
"Ooh."
Belakang Padang itu salah satu kecamatan di Batam, yang kalau ke sana mesti menyeberang lautan menggunakan boat pancung, alias perahu kayu yang dipasang mesin.
Cori jadi ingat rewelan si tetangga nomor empat tadi pagi sebelum berangkat kerja.
"Aku nggak suka naik kapal!" Ben bergidik merinding.
"Kenapa?"
"Sensasi terombang-ambing itu , Cori. Bikin aku mual. Apalagi, jarak kita dengan permukaan laut itu bener-bener dekat. Kalau kapalnya sampai kebalik gimana?"
Cori terkekeh. "Bang, kapal pancung itu transportasi warga setempat setiap hari. Insyaallah aman."
"Tetap enggak suka!" Ben terlihat seperti bocah yang terperangkap dalam tubuh lelaki dewasa.
"Padahal mau ajak Abang ke Singapura. Kan pake kapal juga."
"Walaupun dekat tetap nggak mau. Paspor juga belum diperpanjang. Kalau kamu ngotot masih mau juga, kita pakai pesawat aja ke sana!"
Cori justru tertawa menikmati pemandangan wajah nelangsa Ben yang masih bersungut-sungut meninggalkan Kluster Kepodang.
"Kak, lo senyam-senyum sendiri setelah bicarain Pak Malik."
"Kapan gue senyum-senyum?" Cori sibuk menata raut wajahnya cepat-cepat menjadi normal kembali.
Baru saja Winnie mau bersuara, Tonggo masuk dengan memegang selembar kertas di tangan kanannya. Diam-diam Winnie mendesah lega. Ia sepertinya belum sanggup mengklarifikasi informasi panas dari Marzuki ke rekannya.
"Buk Cori, ada satu nasabah yang mau memroses pelunasannya." Tonggo melambaikan kertas tadi. "Ibuk sama Buk Winnie masih mau terima?"
"Gimana, Win? Lo mau terima? Terserah di elo sih."
"Cuma satu ini. Oke Pak Tonggo. Satu aja ya. Jangan nambah."
Seorang wanita paruh baya mengucapkan terima kasih pada pada Tonggo di depan pintu. Darah Cori berdesir ketika tahu siapa yang masuk.
"Selamat siang," sapa Winnie profesional.
"Selamat siang. Maaf, saya harus menyita waktu Mbak-Mbak sekalian. Padahal sudah tutup," ucap Mutia meringis pada kedua perempuan di depannya, dan sedikit berlama-lama menatap ... Cori.
"Nggak apa-apa, Bu. Ibu Mutia mau melakukan pelunasan pinjaman ya?"
"Iya."
Cori? Keringat dingin mulai membasahi dahinya. Saat Mutia berdiri di depan Winnie, ia memperhatikan dengan lekat perempuan yang telah meninggalkannya 27 tahun yang lalu.
Mutia masih cantik di usianya yang sudah memasuki angka 55 tahun ini. Apa ia tidak membaca namanya yang tercetak di surat perjanjian pinjaman itu? Apa Mutia tidak menemukan kemiripannya dengan Sudjana? Atau, karena ia gemuk, pipinya bulat, Mutia tidak mengenalinya?
Atau jangan-jangan ... Mutia lupa namanya? Ah, itu lebih masuk akal. Makanya Mutia tidak mengenalinya sebagai anaknya yang ... pernah ia tinggalkan.
Sedetik kemudian, Cori memutar bola matanya.
Aku mengharapkan apa sih? Kamu mau Mama mengenalimu? Lalu, setelah itu apa? Mau nuntut Mama? Mau meminta hak sebagai anak? tanyanya bertubi-tubi pada dirinya sendiri.
"Mbak Cori."
"Y-Ya, Bu?" Ada apa, Ma?
"Saya sedang bereksperimen dengan resep baru." Mutia meletakkan sebuah tas kertas di atas meja granit. "Tolong dicicipi, ya? Kalau ada kritik dan saran untuk kukisnya, saya tunggu. Saya terbuka dengan ide dan kritik yang membangun."
"Ini, buat saya, Bu?"
Cori sampai bangkit dari duduknya dan melihat isi tas itu: berbagai macam kue dalam kemasan mika segitiga menggiurkan dan beberapa toples kukis.
Diam-diam, dada Cori membuncah akan sebuah perasaan yang sudah lama ia tinggalkan di belakang. Perasaan itu adalah sebuah rasa bangga ketika Mutia pernah menjadi ibu khayalannya yang sempurna dan hebat.
"Iya. Nah ini," Sebuah tas lain yang sama juga diberikan pada Winnie. "untuk Mbak Winnie."
"Waaah, Terima kasih, Bu Mutia." Betapa senangnya Winnie.
"Win..." bisik Cori.
"Kenapa, Kak?"
"Maaf Bu Mutia, tapi kami tidak diperbolehkan menerima bingkisan apa pun oleh perusahaan," ucap Cori penuh penyesalan. Bukannya tidak mau menerima, tapi peraturan menolak bingkisan dalam bentuk apa pun dari nasabah atau mitra kerja merupakan salah satu SOP PT. Sejahtera Bersama sebagai bentuk pencegahan gratifikasi kepada karyawannya.
"Tapi... saya nggak ada maksud apa-apa dengan kue-kue ini. Ini tulus dari saya pribadi untuk Mbak-Mbak sekalian." Mutia kecewa.
"Kak, nggak apa-apa aja, lah. Lagian Buk Mutia udah selesai transaksi," bujuk Winnie.
"Tapi Win--"
"Nak..."
Darahnya lagi-lagi berdesir ketika Mutia memanggilnya 'Nak'. "Y-Ya, Bu?" Kenapa, Ma?
"Sekali ini saja. Ya?" mohon Mutia.
Wajah memelas mamanya membuat otak Cori membeku dan tanpa pikir panjang, Cori mengatakan, "Baiklah, Bu."
***
"Nggak masuk akal!" teriak Moza di tengah jalan melawan polusi dan debu jalanan Batam.
"Apanya yang nggak masuk akal?" teriak Marzuki. Dia sedang menjadi tameng anginnya Moza di atas motor.
"Cori dan Pak Malik, Juki."
"Emang kenapa?" tanya Marzuki normal setelah membuka penutup helmnya. Sebab, motornya sedang berhenti di persimpangan lampu merah Simpang Kepri Mall.
"Gue masih nggak percaya mereka berdua punya hubungan spesial. Nggak cocok aja." Moza tak segan mengeluarkan nada mencemooh.
"Ah elah. Biasa aja, kali."
"Tapi dilihat dari sisi mana pun tetap nggak cocok." Moza bersikeras.
"Bukan tempat kita ngehakimi hidup orang lain."
"Tapi jomplang banget, Ki. Apa yang dilihat Pak Malik ya dari Cori? Cori kan, gendut. Pipinya bulet, perutnya, lengannya, pahanya, sampai lehernya--,"
"Ngucap woy! Lo yang kayak sempurna aja, Za," geram Marzuki. Meski terkadang mulut Marzuki suka tidak sopan pada Cori, tapi ia masih tahu batas.
"Badan gue emang lebih proporsional dibanding Cori. Tapi bukan itu maksud gue." Marzuki memutar bola matanya. "Kalau semisal Pak Malik balikan sama Mbak Agni, gue sih oke-oke aja. Mereka tuh kayak pasangan serasi yang emang diciptakan oleh Tuhan. Tapi kalau Cori--,"
"Hush! Apa lo nggak mikir, lo udah kelewatan menilai Cori? Apa jangan-jangan lo punya dendam kesumat sama Cori?" tuduh Marzuki.
"Helow. Buat apa gue dendam sama dia? Nggak guna, juga," ujar Moza tak peduli.
"Tapi pendapat lo terhadap Cori selama ini terlalu tendensius, Za." Marzuki mulai menjalankan motornya perlahan, menyalip di antara mobil dan truk yang masih bergerak pelan. Lampu lalu lintas sudah berubah hijau.
"Perasaan lo aja kali, Ki. Selama gue kenal Cori setahun belakangan, gue cuma ngerasa tuh anak mentang-mentang pindahan dari Jakarta kayak, songong gitu. Dia nggak nyadar apa, body-nya itu nggak cocok duduk di front liner. Usaha dikit kek buat ngurusin badan. Kan, ngerusak citra perusahaan kita aja, Ki."
Motor melaju lebih kencang karena mereka telah terbebas dari antrian di lampu merah.
Marzuki mulai berteriak. "Bukan Cori yang mesti ngurusin badan. Tapi elo yang mesti cuci otak lo ke Pantai Nongsa pake air laut. Biar bersih dari pikiran yang enggak-enggak."
"Sialan, lo Marzuki!" teriak Moza kesal.
Dua tim marketing itu sampai juga di kantor cabang Legenda 15 menit kemudian dalam keadaan kepanasan dan kecapekan.
Tepat sebelum Moza membuka rolling door, Marzuki memanggil rekannya, membuat Moza menoleh ke belakang.
"Apa?"
"Berhenti bicara omong kosong tentang Cori, Za!" tegas Marzuki.
Moza kembali berjalan ke rekannya yang masih duduk di motor dengan kening berkerut.
"Juki, bukannya elo yang bilang kalau ada yang aneh dengan Pak Malik dan Cori yang tetanggaan? Dan mereka rangkulan walaupun udah punya pacar."
"Itu ... gue cuma penasaran mereka ada hubungan apa. Sumpah, gue ... gue nggak mikir yang macam-macam."
Sial, kayaknya gue salah ngomong deh, tadi pagi, sesal Marzuki kemudian.
"Berarti lo juga mikir hubungan mereka berdua patut dicurigai, kan? Berarti memang ada yang aneh!" Suka-sukanya Moza menarik kesimpulan sendiri. "Jangan-jangan mereka udah tinggal serumah."
Marzuki spontan menarik tangan rekannya dan berbisik tajam, "Fitnah lebih kejam daripada enggak memfitnah! Hati-hati lo kalau ngomong. Mending tanya langsung ke orangnya daripada lo ngembangin cerita seenak udel lo!"
"Mendang, mending. Suka-suka gue."
"Kalau mereka saling suka, terserah mereka. Itu hidup mereka. Gue minta jangan bikin orang berasumsi aneh-aneh. Dan soal tetanggaan, setelah gue bawa bertapa di kamar mandi, nggak seaneh yang lo pikirin. Mungkin kebetulan aja mereka tetangga. So what, gitu lho?"
"Terus soal pacarnya?"
"Gue nggak tahu dan nggak mau tahu. Lagian itu urusan pribadi Cori. Udah, ah. Capek ngurusin hidup orang lain."
Moza mencibir kesal dan merentak kaki meninggalkan rekan setimnya.
"Oke. Gue bakal tanya sendiri ke orangnya!" Moza sudah membulatkan tekadnya.
Bersambung


 kepodangkuning
kepodangkuning