Nama-nama yang dipanggil sepanjang sore di loket farmasi ini terus memenuhi telinga. Aku mulai bosan mendengar nada panggilan yang statis dan robotik. Entah sudah berapa puluh nama, berapa puluh orang yang telah dipanggil, namun nama Gamma Aditya belum juga terdengar.
Sudah hampir tiga bulan sejak kecelakaan itu terjadi. Setiap tiga hari sekali, aku rutin mendatangi rumah sakit untuk fisioterapi, dan setiap dua minggu sekali akan bertemu dengan Dokter Gusman. Siang tadi, Dokter Gusman mengatakan hal yang melegakan. Pergelangan tangan Anda sudah menunjukkan kemajuan dalam proses penyembuhan. Gerakan dan fungsinya juga sudah mulai membaik. Tapi, penting untuk tetap melanjutkan fisioterapi dan latihan ringan untuk memperkuat otot dan memastikan pemulihan yang optimal – begitu katanya.
Tyas, yang duduk di sampingku, sedang menelepon Trisna. Dia menanyakan bagaimana kondisi tubuh Trisna setelah menerima vaksin Corona. Bulan lalu, minggu kedua Januari, Presiden Jokowi menjadi orang pertama yang menerima vaksin dalam program vaksinasi massal secara gratis di Indonesia. Jelas sekali, tanpa perlu dipertanyakan lagi bahwa tujuan tindakan itu dilakukan untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap keamanan dan keefektifan vaksin tersebut. Namun sayang, banyaknya informasi yang tidak akurat atau menyesatkan di media sosial dan platform lainnya telah menyebabkan kebingungan dan ketakutan terhadap vaksin ini.
“Trisna cuma demam, itupun sorenya udah baikan,” kata Tyas padaku sambil kembali menyimpan handphone-nya di tas.
“Ya, terserah, sih. Kalau lu mau vaksin, ya, gas aja. Gua belum boleh sama dokter Gusman. Tunggu surat pengantar,” aku menjawab sambil menggenggam-genggam bola kecil dengan duri-duri rapat –alat bantu fisioterapi. Bola ini terlihat seperti durian mini dengan warna silver mengilap. Tyas mengangguk sambil mengatakan akan mendapatkan vaksin bersama mama dan papanya.
Kursi ruang tunggu ini tidak pernah kosong; setiap orang yang pulang segera digantikan oleh orang yang baru datang. Wajah-wajah di sekitar kami asing, atau mungkin ada yang kami tahu, tapi sulit dikenali karena setengah wajahnya tertutup masker. Kami bertiga—aku, Tyas, dan Aruna—terkadang saling memandang. Aruna tersenyum dengan tangan tertangkup di depan dada, sementara lampu LED di belakangnya tampak redup. Tidak seperti saat pertama, melihatnya sekitar dua tahun lalu saat menunggu obat asam lambung, kini menatap wajahnya hanya memunculkan getaran-getaran halus di dada. Rindu itu tetap masih ada, tapi seperti menonton ulang film yang dulu membuatmu menangis dan tertawa –hanya membangkitkan nostalgia. Aku baru sadar bahwa sudah lama tidak menulis surat lagi untuk Aruna, sejak kecelakaan dan sejak tangan kananku tidak bisa berfungsi dengan baik. Ada masa-masa ketika Pak Gusman menyarankan agar aku perlahan-lahan mulai menulis lagi sebagai bentuk latihan. Namun, yang kutuliskan justru daftar-daftar klinik bedah plastik yang direkomendasikan di Thailand atau bahkan Korea Selatan, hasil dari browsing berjam-jam. Diam-diam, aku ingin membawa Tyas untuk menghilangkan bekas jahitan di pipinya, berharap bisa meredakan rasa bersalahku meskipun penyesalan itu masih menggunung.
Namaku akhirnya dipanggil. Aku berdiri, sudah bisa jalan dengan normal, tanpa tongkat, tanpa tertatih-tatih. Kakiku sembuh lebih cepat. Tongkat yang hanya berguna untuk waktu seminggu saja itu sudah kujual, dengan bantuan Ares tentunya.
Begitulah, tiga bulan belakangan aku banyak menghabiskan waktu di kost. Ares datang setiap malam selama sebulan awal, tak jarang juga menginap. Tyas bukan hampir lagi, dia benar-benar datang setiap hari. Kami membahas pekerjaan. Dia banyak membantuku untuk Midas atau bisa dikatakan dia memang bekerja untuk Midas sebab bagaimana juga, ayahnya pemilik pertama dan juga pemodal terbesar. Aturan PSBB, PPKM atau apalah itu namanya, masih membuat kami bekerja dari rumah. Tidak ada aktifitas di kantor Midas kecuali Tyas yang memang bolak-balik ke sana untuk memeriksa beberapa hal. Bukan tidak sering aku sampaikan pada Tyas, beberapa di antaranya justru dengan memohon, bahwa dia tidak perlu repot-repot datang hanya untuk membantuku. Di luar gak aman, Yas. Kamu bisa kena Covid kalau tiap hari harus bolak-balik, begitu kataku. Dia berkilah mengatakan dia tidak betah di rumah saat harus mengurusi Midas. Sejujurnya, di dalam hatiku, aku merasa seperti pecundang setiap kali Tyas datang. Rasa bersalah semakin menumpuk juga semakin memberatkan pundakku tiap kali melihat luka di wajahnya. Namun, seiring berjalannya waktu, aku mulai terbiasa. Bahkan, suatu hari, Tyas datang terlambat. Memang tidak ada jam khusus, hanya saja biasanya dia datang sebelum makan siang. Aku merasa tidak mungkin menanyakan kenapa dia terlambat (karena itu terasa seperti sebuah keharusan), dan malah khawatir sendirian. Apa terjadi sesuatu di perjalanan? Apa dia sakit? Ketika akhirnya dia datang sore sekitar pukul empat, aku merasa lega. Dia tidak menjelaskan alasan keterlambatannya, dan aku pun bertahan untuk tidak menanyakan. Melihatnya datang dalam keadaan sehat saja sudah membuatku merasa senang.
“Udah gak sebanyak dulu obatnya,” kata Tyas saat kami berjalan meninggalkan ruang tunggu farmasi, melewati lorong-lorong yang tampak sibuk. Sebagian perawat masih mengenakan APD lengkap, sebagian lagi tidak.
“Iya, nih …,” kataku sambil memasukkan obat ke ransel, Tyas membantu.
Sepanjang perjalanan pulang, hingga sampai di kost, kami hanya membicarakan pekerjaan. Juga beberapa seminar online yang masih aku terima meskipun tangan dan kaki sedang tidak baik. Saat itu, Tyas banyak membantu menyiapkan materi.
Banyak hal berubah menjadi dramatis sejak awal tahun karena situasi pandemi. Orang-orang mulai berpacu-pacuan hidup sehat. Misal, bersepeda. Seolah semakin banyak kamu mengayuh sepeda, semakin jauh virus darimu. Pada berbagai platform media sosial, tak jarang disiarkan juga di televisi, orang-orang bersepeda dengan gaya, bukan hanya untuk olahraga. Orang-orang yang tidak membeli sepeda pada saat itu mungkin merasa kehilangan kesempatan dan takut tidak bisa merasakan manfaat atau kesenangan yang sama dengan mereka yang sudah memiliki sepeda. Begitu juga yang terjadi dengan tanaman. Banyak orang mencari cara untuk mengatasi stres. Tanaman hias mampu menciptakan suasana yang tenang dan menyenangkan di rumah juga merasa dekat dengan alam. Orang semakin tertarik untuk mengoleksi tanaman hias, termasuk ibu. Bagiku ini sedikit berlebihan seolah semakin menyerupai hutan halaman rumahmu, semakin susah virus mengendap-endap masuk ke rumahmu. Ares mengeluhkan banyak nyamuk di sekitar kontrakannya karena tetangganya memelihara banyak tanaman hingga menutupi nyaris seluruh teras. Tidak mengapa, yang jelas dan yang pasti, ini menjadi harapan perputaran perekonomian. Penjual sepeda senang, penjual tanaman hias riang, Midas gembira karena banyak klien yang datang dari dua jalur itu.
Memasuki bulan Ramadhan, klien Midas, terutama yang bergerak pada bisnis makanan, menyediakan paketan menu berbuka. Sehingga Midas lebih sibuk dari biasanya, mempersiapkan konten visual yang menarik perhatian dan menggugah selera. Mereka mengirimkan sampel makanan kepada manajer proyek Midas, Bang Nugi. Lalu Bang Nugi akan mengunggah foto dan video produk sampel itu ke penyimpanan bersama milik Midas, yang bisa diakses secara online oleh seluruh tim. Kemudian, mereka akan mengerjakannya sesuai bidang masing-masing. Aku dan Tyas selalu memantau prosesnya. Sering kali produk sampel itu menjadi makanan berbuka puasa untuk tim Midas. Bang Nugi yang membaginya agar semua orang bisa mencicipi. Begitu juga menjelang Lebaran, klien Midas yang memiliki usaha patiseri dan kue rumahan berlomba-lomba membuat paket kue lebaran dan hampers.
Dua hari sebelum Idul Fitri, Midas sudah mulai libur. Tahun ini, ada tambahan syarat bagi masyarakat yang ingin melintas antar kota: surat keterangan vaksinasi. Aku hanya menunjukkan surat dari dokter Gusman yang menyatakan bahwa pasiennya belum bisa mendapatkan vaksinasi karena masalah kesehatan lain. Cukup lama aku berada di pos pemeriksaan, ditanyai segala macam tentang tanganku. Aku dicurigai berbohong, membawa surat dari spesialis ortopedi dan traumatologi, tapi tanganku terlihat luwes saja mengendarai motor.
“Ini nahan sakit sebenarnya, Pak,” kataku lagi. Untuk meyakinkan mereka, aku sampai mengeluarkan obat – yang sebenarnya sudah tidak aku minum lagi, tapi untungnya masih ada dalam ransel.
Akhirnya mereka percaya, aku kembali melanjutkan perjalanan. Menjelang Ashar, aku sudah sampai di rumah. Mendengar suara motor di halaman Marwa berlari mengejar dan memeluk, membuat kami nyaris saja jatuh bersama motor.
Ibu berjalan mendekati kami. Aku merentangkan sebelah tangan pada Ibu dan kami bertiga berpelukan di halaman rumah diiringi suara azan Ashar.
“Kangen…,” kataku pelan.
“Aku juga, Kak …,” bisik Marwa pelan, masih sambil memeluk.
Ibu, sambil menyandarkan kepalanya pada bahuku, tangannya mengusap-usap punggungku. Terasa nyaman sekali. Aku benar-benar rindu keluargaku. Terakhir kali bertemu satu setengah tahun lalu pada acara syukuran Ares.
Kami masuk. Aku istirahat sebentar, sholat dan kembali ke meja makan dimana ibu dan Marwa sedang sibuk di sana.
Wangi kue yang sedang dipanggang menguar, sekilas perutku berbunyi. Marwa dengan bangga mengatakan bahwa dia sudah bisa membuat kue dan berencana membuat sendiri kue kering untuk lebaran.
“Dia belajar masak sekarang,” kata Ibu sambil memijat-mijat pelan pergelangan tangan kananku. Selama tidak bertemu, terlebih sejak kecelakaan, ibu setiap hari melakukan panggilan video untuk memeriksa keadaan. Sehingga setelah bertemu lagi, kami tidak banyak bercerita mengenai kecelakaan. Ibu hanya menanyakan keadaan Tyas. Aku sampaikan pada ibu rencanaku membawa Tyas menjalani bedah plastik.
“Gak apa-apa. Memang harus begitu. Semoga lancar semuanya,” ucap ibu. Aku tahu, ibu menatapku dengan bangga. “Tyas udah tahu?” tanya ibu lagi.
Aku menggeleng. “Belum. Aku masih mikirin gimana cara ngomongnya biar dia gak tersinggung.”
“Aku rasa gak akan tersinggung,” sahut Marwa, “dia bakalan nerima tawaran kakak. Perempuan mana yang diajak oplas biar cantik lagi malah tersinggung?” ujar Marwa sambil memasukkan adonan kue lain ke oven.
“Dia beda. Dia perempuan yang gak kayak perempuan,” kataku.
“Beda?” tanya Marwa seolah tidak yakin. Dia menarik kursi dan duduk.
“Ya.”
“Beda gimana?”
“Yaaa … beda aja. Susah aku jelasinnya.”
“Tapi tetap perempuan, kan?”
“Ya iya, lah!”
“Nah itu poinnya. Karena dia perempuan, dia bakalan nerima niat baik kakak.”
Aku diam, mengembuskan napas.
Apa benar begitu? Apa benar dia tidak akan tersinggung?
“Mau gimana respons Tyas nanti,” kata ibu, “kamu tetap harus sampaikan rencana kamu ke dia mengenai bedah plastik.”
Aku mengangguk.Setelah itu, tidak ada lagi pembicaraan yang menyertakan nama perempuan lain di rumah ini. Tidak Tyas. Tidak Aruna. Bahkan, sepertinya Marwa menahan keinginannya untuk bertanya, karena dia tahu betul bahwa aku, sama seperti dia; tidak tahu apa-apa lagi mengenai Aruna.
Kami berbuka dengan bolu bikinan Marwa. Harus kuakui bolu pandan ini baik rasa dan aromanya mengingatkanku pada bolu bikinan ibu semasa kami kecil hingga remaja yang kami santap nyaris setiap sore akhir pekan, teman dari jagung bakar atau barbeque kecil-kecilan yang menyibukkan bapak di depan panggangan. Dulu, menjelang malam, kami akan tertawa bersama di halaman belakang. Benar-benar waktu yang menyenangkan. Aku melirik kursi pada meja makan ini yang selalu diduduki bapak. Meja makan bundar ini hanya memiliki empat kursi, sesuai dengan jumlah anggota keluarga kami. Kursi itu nyaris tidak pernah diduduki siapapun, kecuali saat-saat genting. Misalnya, saat Aruna di sini, maka aku akan duduk di kursi bapak, atau jumlah kursi hanya akan bertambah jika tamu datang.
Selesai berbuka, kami menggeser beberapa sofa untuk sholat maghrib dan berlanjut tarawih di ruang keluarga. Ibu dan Marwa masih mengenakan mukena dan aku masih mengenakan sarung saat kami membahas rencana pernikahan Marwa yang akan dilangsungkan bulan Desember tahun ini. Sejak bulan Maret, saat bertelepon dengan ibu atau Marwa, atau keduanya, pembahasan pernikahan Marwa mulai mencuat karena Ikhsan mengatakan ingin melamar saat lebaran. Bukan acara pertunangan besar-besaran, selain karena pandemi, juga keluarga Ikhsan begitu mirip dengan keluargaku: sederhana dan tidak suka menarik perhatian. Hanya orang tuanya, neneknya, serta Ikhsan dan tiga adiknya yang akan datang melamar Marwa pada Idul Fitri kedua.
Aku banyak mengangguk saja, karena berpikir akhirnya sampai juga pada waktu-waktu seperti ini. Marwa akan menikah dan aku akan menjadi walinya. Lalu aku terharu dan terenyuh secara bersamaan mengingat bagaimana bapak akan bereaksi di saat-saat seperti ini. Bapak akan tersenyum seharian, mungkin saja, karena akan mengantarkan anak perempuannya pada laki-laki pilihannya. Laki-laki yang dia percaya mampu menjaga sekaligus mendidik permata hatinya.
Dan hari itu datang, hari dimana keluarga Ikhsan duduk di ruang keluarga rumah kami dengan keakraban yang nyaris tidak masuk akal untuk dua keluarga yang tidak memiliki hubungan darah. Pembicaraan serius mengenai pernikahan sesekali terselip candaan, karena aku dan juga Ikhsan tampak sedikit kaku. Tentu saja Ikhsan gugup dan tiba-tiba menjadi grogi saat mulai berbicara, karena ini menyangkut hari besar dalam fase hidupnya. Sedangkan aku gugup karena sebagai kakak laki-laki, aku selalu merasa memiliki tanggung jawab besar untuk melindungi Marwa, menjaganya dari segala sesuatu yang bisa menyakitinya. Sejak kecil, bapak sudah melatihku untuk begitu pada adikku. Kamu itu adalah tempat dia mencari perlindungan, itu yang sering bapak ucapkan. Dan kini, aku harus bisa memercayakan semua itu pada satu laki-laki baru yang bukan dari darah bapakku. Seolah tahu apa yang ada dalam kepalaku, ibu yang duduk di samping, menggenggam erat tanganku.
Aku menatapnya, ibu tersenyum dan mengangguk pelan. Meyakinkan bahwa semuanya akan baik-baik saja.
Aku mengangguk karena sadar bahwa kegelisahanku bisa saja mengganggu kebahagiaan Marwa, lantas aku berusaha bersikap wajar.
Ayahnya Ikhsan, Pak Nawal, menyampaikan –mungkin juga karena telah melewati perundingan antara Ikhsan dan Marwa lalu berlanjut pada Ikhsan dan keluarganya– bahwa setelah menikah mereka akan tinggal di rumah ini, di rumah kami. Aku lega, bukannya kami tidak tahu bahwa Ikhsan sudah memiliki rumah sendiri, tapi dia berbesar hati ikut menjaga ibu dengan tinggal bersama.
Ibunya Ikhsan, Bu Remi, memasangkan cincin emas putih di jari manis Marwa dan cincin itu tampak serasi sekali dengan adikku yang mengenakan baju gamis biru dan jilbab abu-abu. Aku memotret momen itu. Lalu momen-momen kebersamaan setelahnya. Setelah makan siang, rombongan keluarga Ikhsan pulang. Saat kami masuk kembali ke rumah setelah mengantarkan dan melambai-lambaikan tangan pada mobil keluarga Ikhsan yang beringsut keluar halaman, Marwa memeluk ibu sambil tersedu mengatakan rindu bapak. Dadaku sedikit nyeri melihat dua perempuan itu berpeluk dalam rindu dan haru.
Hari kelima Lebaran, tepat Minggu malam, aku kembali ke Jakarta karena mendapat telepon dari Ares. Dengan kemanja-manjaan yang menjijikkan dan berhasil membuat bulu kudukku berdiri bergidik geli, dia mengatakan terjangkit Covid.
“Lemes banget. Kayaknya napas gua gak nyampe besok pagi,” katanya dari seberang telepon sore itu saat aku sedang mencuci mobil.
Sampai di Jakarta, aku langsung ke daerah Mampang, ke kontrakan Ares. Pintunya tidak terkunci, aku masuk dan mendapati dia terbaring lemah di kasur sambil memandangi potret lukisan kakeknya. Yang membuatku ingin segera melemparnya dengan helm di tanganku adalah dia menangis tersedu-sedu sambil mengatakan akan bertemu kakek dan neneknya di surga. Dia menoleh, masih sambil berurai air mata. Selayaknya orang yang akan mati, atau setidaknya merasa akan mati, dia mengakui kesalahan yang dia lakukan dan berharap si korban memaafkan dengan kerelaan dan kebesaran hati.
“Gaaamm,” katanya setengah memelas, “gua pernah masukin kondom ke tas lu.”
Aku menggaruk-garuk alis, malas melihatnya yang cengeng, tidak pantas sama sekali, “Iya.”
“Lu pake?” Ares tampak khawatir.
“Gua buang.”
Dia diam, rengekannya berhenti sejenak. Tampak pada kedua ujung bibirnya bergerak ragu naik seakan tersenyum nyengir. “Alhamdulillah, gua masuk surga juga. Gua khawatir dosanya nempel ke gua,” katanya sambil mengusap wajah dan kembali menangis memanggil neneknya dan memintanya menunggu di depan pintu surga.
“Heh, monyet! Lu kira dosa lu itu doang? Neraka tuh, nungguin!”
Akhirnya aku tidak tahan untuk tidak melemparnya dengan helm. Dia segera menangkap helm yang nyaris saja menghantam perutnya.
Aku memutuskan menginap di kontrakan Ares. Dia mengatakan telah kehilangan indra penciuman dan pengecap sambil menunjukkan hasil swab yang positif.
“Nih …,” aku memberinya plastik berisi obat-obatan dan vitamin yang aku beli.
“Lu gak takut ketularan?” tanya Ares sambil meneguk obat itu.
Aku menghela napas, lelah dan muak sudah mengakar di mana setiap hari hanyalah rangkaian ketidakpastian dan ketakutan sehingga aku sendiri sudah tidak terlalu peduli jika ketularan. “Yah, gak Covid pun sebenarnya kita semua tiap hari berjuang buat hidup kan?”
Ares diam, lalu menyeringai buruk, “Udah kayak ceramah Pak RT aja lu!”
Ares yang memang demam, akhirnya tertidur dengan sedikit drama: berdoa. Lengkap, dan juga terdengar serakah. Dia meminta kepada Tuhan agar masih memberikannya kesempatan bangun besok pagi, kalaupun tidak, dia hanya ingin masuk surga, lalu ditutup dengan ayat kursi (mencengangkan, ternyata dia hapal) dan doa mau tidur. Lebih menggelikan lagi, dia menyetel alarm pukul lima pagi. Dia mau sholat subuh, katanya.
“Lu gak yakin hidup sampai besok pagi, tapi yakin banget nyalain alarm,” kataku.
“Brader,” ujar Ares yang saat itu sedang mengembangkan selimut, “itu yang orang-orang sebut harapan.”
“Najis! Sok spiritual lu!” sambarku segera. Aku jadi khawatir dengan perubahan sikapnya ini.
Jangan-jangan temanku ini betul akan mati, pikirku lagi.
“Terserah, deh!” jawab Ares seadanya.
Lalu dia memejamkan mata, menghadapkan seluruh badannya ke kanan dan memeluk selimutnya dengan kedua tangan mengepal tepat di bawah dagu. Menggeliat dengan manis dan imut yang sangat bertolak belakang dengan wajahnya. Melihatnya begitu, aku ingin sekali menendangnya. Mungkin akan aku tendang jika saja dia sedang tidak sakit. Malam itu, aku tidur di depan, di ruang kerja Ares dan beberapa kali masuk ke kamarnya memeriksa apakah dia masih bernapas atau tidak.
Besok pagi, setelah menyaksikan sendiri ternyata temanku tidak jadi mati, dan bagaimana khusyuknya dia mengerjakan sholat subuh, aku pulang ke kost. Ares sembuh setelah seminggu, dia dengan riang menunjukkan hasil swab yang negatif pada panggilan video di Minggu siang. Lalu dua bulan ke depan, Juni-Juli, Jakarta seolah runtuh sistem kesehatannya. Lonjakan kasus meningkat setelah lebaran. Varian baru muncul, mereka menyebutnya Delta. Televisi tanggal 27 Juli heboh menyiarkan jumlah kematian karena Covid mencapai 2,069 jiwa. Hingga penyair Joko Pinurbo menggambarkan betapa mencekam suasana di waktu-waktu sulit dalam sebait puisi: “Juli 2021: Hari-hariku terbuat dari innalillahi”. Dua bulan ini semua kabar terdengar mencengangkan dengan cara yang tidak baik. Hampir seluruh kenalanku terjangkit, termasuk Kak Ami dan Bu Dewi. Sedikit demi sedikit, pikiranku melayang pada Aruna, apakah dia sedang bekerja atau tidak, apakah dia sudah terjangkit Covid atau belum. Apa pun yang terjadi pada dirinya, semoga dia dalam keadaan baik— dia dan anaknya.
Sedangkan Midas masih sama, semua anggota tim bekerja dari rumah saja. Terus saling memantau dari tempat masing-masing, dari layar masing-masing. Tyas, meskipun sudah tidak setiap hari, setidaknya dia akan mampir ke kost tiga kali dalam seminggu. Setiap dia datang, aku selalu berniat mengutarakan penawaranku untuk membawanya bedah plastik setelah pandemi berakhir, yang juga aku tidak tahu kapan. Setidaknya aku masih punya cukup waktu untuk mengumpulkan uang. Tapi selalu urung karena masih memikirkan bagaimana perasaannya. Aku benar-benar khawatir dia akan salah paham mengenai ini.
Hingga pada satu hari di bulan September dimana kasus Covid sudah mulai landai, aku dan Tyas berencana ke rumah Cak Son karena ada beberapa hal mengenai pekerjaan yang harus dibicarakan. Tyas duduk termangu di sofa sambil menatap handphone-nya. Wajahnya yang memang selalu serius itu kini tampak jauh lebih serius, lebih seperti raut kalut, atau marah. Aku yang sedang mengemas beberapa lembar kertas yang bergambarkan desain dummy food, memanggilnya, “Yas? Ada apa?”
Tyas dengan wajah mendung mengatakan, “Dia gak terlalu peduli siapa tunangannya. Yang dia pedulikan cuma waktunya, tanggalnya,” kata Tyas pelan, baik tempo maupun nada, “kemarin, seharusnya jadi hari pertunangan kami. Tunangannya memang gak batal, Kak, tetap di tanggal itu. Pasangannya aja yang ganti.” Tyas menunjukkan padaku layar handphone-nya. Pada akun sosial media yang aku tahu kemudian milik Gilang, terpampang foto mesra, dia dengan seorang wanita, berpakaian jas biru tua dan pasangannya berkebaya dengan warna serupa. Mereka berdiri di depan dekorasi serba putih bertuliskan Happy Engagement. Pasangan itu tersenyum bahagia memamerkan jari masing-masing yang dipasangi cincin.
Aku menatap Tyas. Inilah saat tepat mengutarakan rencana bedah plastik, pikirku kemudian. Belum sempat aku membuka mulut, Tyas berdiri dengan emosi yang dia tahan mati-matian, mengambil tas laptop di kasurku dan mengajakku segera berangkat, “Yok, Kak! Ntar Cak Son ngomel kalau kita kelamaan.”
Tidak pernah lagi sejak kecelakaan itu terjadi, aku memboncengi Tyas dengan motor. Tanpa dikatakan pun aku tahu dia mengalami sedikit trauma. Beberapa kali aku dapati dia bahkan tidak sanggup menatap motorku, dia selalu akan menunduk atau membuang muka. Sehingga, jika harus pergi berdua, kami mengendarai mobil Tyas. Kali ini aku menyetir. Tidak ada perbincangan selama perjalanan. Sesekali aku meliriknya dari ekor mata, dia hanya banyak menatap ke jendela.
Aku juga sibuk menyusun kalimat di kepala, tentang bagaimana kata-kata terbaik untuk menyampaikan rencana bedah plastik itu padanya.
Keluar dari rumah Cak Son, langit sudah berwarna keunguan.
“Kita beli makan dulu, Kak,” kata Tyas sambil menunjuk sebuah rumah makan Padang. Kami turun dan masuk untuk memilih lauk, lalu kembali dengan dua bungkus makanan. Aku tidak tahu kenapa, tapi apa porsi makan orang di Sumatera Barat memang sebanyak ini? Kantong plastik merah muda pucat yang kubawa ini tampak sempit meskipun hanya terisi dua bungkus makanan –yang gemuk.
Aku dan Tyas, sampai di kost disambut dengan suara cempreng tetanggaku yang karaokean. Aku terkikik-kikik saat memutar anak kunci, Tyas hanya tersenyum simpul. Kami masuk, meletakkan tas dan duduk untuk makan bersama, dan dengan sangat hati-hati, aku mulai mengutarakan rencanaku. Tyas terkejut mendengarnya.
“Hmmm …, gua udah cari-cari sejak beberapa minggu lalu. Ada yang di Korsel, ada juga di Thailand,” ujarku sambil menatap matanya, mencari-cari dan berusaha menerka apa yang ada dalam pikirannya mengenai usulan ini. Apakah dia suka lalu menerima atau –dan yang paling aku takutkan– dia akan terusik dan merasa berkecil hati.
Dia mengunyah pelan makanannya, tampaknya sedang berpikir. Pada wajah yang tidak bisa aku tafsirkan rautnya itu, semuanya terlihat serba setengah-setengah. Setengah setuju, setengah lagi tidak. Setengah menyukai, setengah lagi enggan. Bibirnya bergerak ragu, ingin bicara tapi tampaknya juga dia tahan, entah dia merasa apa yang akan dia katakan terdengar tidak lagi penting atau dia sedang menahan diri untuk tidak mengumpatiku karena telah menyinggung perasaannya.
Aku berhenti makan. Kukemas bungkusan nasi dan memasukkannya kembali ke kantong plastik. Sudahlah kehilangan selera makan, aku juga ingin membicarakan ini serius dengan Tyas. “Yas, gua gak maksud apa-apa. Gak maksud nyakitin perasaan lu. Tapi selagi masih bisa dipulihin, gua rasa lebih baik kita co–”
“Gak!” Tyas menyambar cepat, “gua gak mau bedah plastik.”
Aku sudah membuka mulut untuk bicara, tapi urung karena benar sepertinya Tyas salah paham. Dahinya berkerut, tatapannya menusuk.
“Pada akhirnya luka ini ganggu mata lu, ya, Kak?” tanyanya kemudian, dengan nada menyindir.
Aku menggeleng cemas, “Gak, Yas. Sama sekali enggak. Gua cuma mau lu pulih. Semuanya pulih, fisik dan mental.”
Tyas menelan ludah. Tidak lama dia juga mengemas makanannya, menyatukan sisa makanan itu bersama dengan bungkusan sisa makananku di kantong plastik. Lalu dia minum tergesa-gesa, “Ini gua buang sekalian turun, sekalian pulang,” katanya lagi dan sambil berdiri membawa plastik merah muda pucat itu.
“Kita belum selesai bicara, Yas. Jangan pulang dulu,” kataku ikut berdiri, mencegatnya.
Tyas menarik napas dalam-dalam, menyabarkan hatinya. Lalu mendesis sebelum akhirnya bicara, “Gua gak ngelak kalau ini –dia menunjuk pipinya– pernah ngancurin mental gua, terlebih pas Gilang milih pergi. Gua gak bohong kalau gua pernah nangis berhari-hari karena luka ini,” dia menatapku, “tapi, Kak, gak sedetik pun pernah terlintas di pikiran gua kalau luka ini adalah kesalahan lu. Gak pernah. Begitu juga papa, mama dan kakak gua.” Tyas memegang pergelangan tanganku yang dulu cedera itu, “Lu juga korban, lu luka, lu sakit. Jadi bukan lu yang harus tanggung jawab atas apa yang terjadi sekarang atau … apapun yang terjadi nanti.”
Hatiku sakit.
Bukan karena dia menolak apa yang aku tawarkan. Tapi mengetahui sudah berapa banyak air mata atau sudah berapa lama dia merasa resah karena luka itu dan tidak pernah dia ceritakan padaku selama ini, selama nyaris satu tahun ini. Dia justru hadir sebagai penolong di saat sebenarnya dia sendiri yang membutuhkan bantuan.
“Kalau lu khawatir gak ada yang naksir gua karena luka ini. Lu salah,” katanya lagi.
“Oh, ya?” kataku lega. “Syukurlah. Sekarang ada cowok lain, nih?” godaku lagi.
Tyas tersenyum sambil menggeleng. “Bukan. Maksud gua, lu salah karena khawatirin itu. Masalah cowok atau pendamping hidup nanti, gua cuma bisa lakuin dua hal. Nunggu laki-laki yang tulus or being single forever. Apapun yang terjadi dari salah satu itu, gua udah persiapkan diri. Lagi pula apa buruknya jadi single selamanya? Gua gak benar-benar sendirian, kan? Gua masih punya keluarga dan teman.”
Nyeri. Jantungku seakan diremas.
Dadaku membuncah.
Alih-alih berderai air mata, dia justru mengucapkan kalimat itu dengan bersih –tanpa protes, tanpa sesal, dan tidak menuntut. Aku tahu dia kuat, tapi tolong, jangan sampai begitu tangguh; aku jadi tak bisa berkata apa-apa lagi. Apa lagi yang bisa kulakukan jika dia sudah begitu berdaya? Tidak ada. Dia bahkan dapat beradaptasi dengan cepat dalam situasi yang tidak hanya melukai wajahnya juga melukai perasaannya, mengoyak hatinya dengan bengis. Dia perempuan, dan setiap perempuan menyayangi wajah mereka seperti mereka menyayangi ibunya. Dia perempuan, dan setiap perempuan mendambakan kekasih yang setia. Dia perempuan, dan tidak semua perempuan bisa perkasa seperti dia. Dan di hadapannya, aku merasa benar-benar tidak menjadi laki-laki.
Aku ingin bicara, tapi tidak bisa. Leherku terasa dicekik. Akhirnya, aku memeluknya. Kuat. Entah tubuh siapa yang bergetar di antara kami, aku tidak tahu, tapi pelukan itu penuh gelombang, membisukan semua kata-kata yang menggantung di tenggorokan.
“Maafin diri lu sendiri. Maafkanlah diri kakak yang gak bersalah sama sekali itu. Menyedihkan memang, lu gak bersalah sama gua. Lu bersalah ke diri lu sendiri karena terlalu keras meyakini kalau ini semua kesalahan lu,” katanya lagi. Dan aku nyaris saja meneteskan air mata. Tapi aku tahan kuat-kuat, karena jika saja sempat air mata itu jatuh, aku cap diriku benar-benar gagal sebagai laki-laki di hadapan perempuan yang sedang aku peluk ini.
Percakapan itu, pada setiap kalimat yang keluar dari mulut Tyas, juga tatapan matanya yang penuh makna, beriringan dengan raut wajahnya yang memberikan tafsiran paling dalam, berhasil membuatku nyaris tidak tidur bermalam-malam. Bolak-balik berpikir, mengira-ngira, menimbang-nimbang, memperdebatkan lalu mendamaikan. Beberapa hari aku berdoa agar bertemu bapak dalam mimpi untuk berdiskusi tapi nihil, aku tidak bertemu Bapak, bahkan bermimpi pun tidak. Semuanya itu, semua kegelisahan yang tidak terjangkau oleh malam itu, hanya untuk merumuskan satu keputusan besar. Ini adalah pilihan paling gamang karena butuh keyakinan besar, dan keyakinan berarti menekan diriku untuk memercayai sesuatu yang sebelumnya sulit kuakui. Lalu aku sadar, dalam situasi ini, hanya keberanian yang bisa aku tebalkan.
-oOo-
Ares menyanyi-nyanyi kecil mengikuti Once membawakan Separuh Nafas Dewa 19 yang melantun cukup kuat dari perangkat audio mobil mami. Setelah mengantar mami ke bandara, dia menjemputku dan menemaniku mengantarkan satu karya foto yang aku daftarkan pada pertengahan September lalu untuk mengikuti pameran fotografi. Setelah menunggu sekitar satu bulan, melalui e-mail juga pesan whatsapp, karyaku dikabarkan lulus seleksi kurator dan diminta segera mempersiapkan karya tersebut untuk dipamerkan: mencetak dalam ukuran dan media yang sudah ditentukan penyelenggara. Dan untuk itulah, kami mengantar karyaku ke Kota Tua, tempat pameran itu akan diselenggarakan selama satu Minggu di pertengahan November.
“Label udah lu tulisin?” tanya Ares memastikan.
“Udah,” jawabku sambil mengecek handphone, Pak Adimas mengirimkan pesan, menanyakan beberapa proyek kepunyaan temannya. “Untuk harga gua kosongin. Gua gak jual,” kataku lagi sambil membalas pesan Pak Adimas.
Ares manggut-manggut lalu menoleh sebentar ke bangku belakang, dimana foto dengan bingkai kayu itu duduk rapi. Kemudian Ares nyengir, “Ya kali lu jual dua cewek berarti di hidup lu.”
Aku terkekeh, melongok ke foto ibu dan Aruna di dapur dulu. Foto yang menyuguhkan kehangatan dan memberikan kenyamanan bagi siapa saja yang melihatnya nanti.
Selesai mengantarkan foto itu, aku dan Ares kembali ke rumah mami untuk mengembalikan mobil. Sebelum pulang kami sempatkan main PES di kamar Ares. Mbok Rah menyiapkan beberapa cemilan dan es kopi. Wanita yang sudah pada usia senja itu, dan sudah memiliki dua cucu berusia SD, tidak kalah geram melihat rivalitas kami pada permainan sepak bola.
Ayok, Mas Ares! Golin! seturut dengan gaya menendangnya. Karena kecewa Mas Ares-nya kalah, dia keluar dengan mengomel. “Mending si Mbok yang main lawan Mas Gamma,” gerutunya, “pasti kalah.”
Aku dan Ares tertawa setelah saling berpandangan.
Permainan sudah selesai dan kami makan cemilan. Aku –yang sedari game dimulai tadi sudah menimbang-nimbang untuk bercerita– mulai menceritakan pada temanku ini apa yang sudah bermalam-malam dan berminggu-minggu aku pikirkan mengenai keputusan besar.
Ares ternganga hingga memperlihatkan kue kering di mulutnya setelah mendengar satu kalimat yang aku katakan dengan suara sedikit bergetar.
“Lu yakin, nih?” tanyanya kemudian.
“Kalau dibilang yakin, yaaa … yakin. Gua kan udah mikirin lama juga.”
Ares membawa semua rambutnya ke belakang, mengusap-usap dengan kasar, “Lu gak bisa mundur lagi kalau udah ngomong begitu ke dia.”
“Ke bokapnya,” sambarku cepat.
“Hah?”
“Gua gak ngomong ke dia, langsung ke bokapnya aja.”
Ares mengembuskan napas kasar lalu dia berdiri menuju jendela, menyalakan api untuk rokok yang sudah terselip di bibirnya, “Gua yang deg-degan, Nyet!” katanya dengan resah.
Aku bangkit, menghempaskan punggung pada kasur, “Yah, lu support gua aja.”
“Lu gimana ke dia?”
“Selama ini kalau ngomong nyambung.”
“Perasaan lu? Suka?”
“Ya kalau suka, sih, suka. Gak ada alasan gua gak suka juga.”
“Naksir, gitu?”
“Enggak,” aku berdeham, “belum …,” untuk kata kedua itu, aku sedikit ragu mengucapkannya.
Ares diam hingga menghabiskan rokoknya, lalu berkata, “Yah, pada dasarnya lu emang begitu, kan? Lu orang yang tanggung jawab. Bokap lu meninggal, lu tanggung jawab sama nyokap dan adik lu, lu tanggung jawab sama kuliah, sama kerjaan, bahkan gua dulu ngilang pun lu bisa-bisanya sendirian ngadepin semua hal yang udah gua hancurin di Gammares,” Ares berdeham, menelan ludah, “bahkan Aruna, secinta mati gimana pun lu ama dia, lu relain demi masa depannya karena waktu itu lu masih amburadul. Itu tanggung jawab, Man. Gak mudah.”
Aku mengesah, menatap plafon kamar Ares yang mewah dengan segala ukiran klasik pada tepiannya.
Memang tidak mudah, justru sangat berat. Lebih gilanya lagi, aku merasa telah mengkhianati Aruna dengan keputusan ini. Dulu, aku merelakan satu kekasih demi masa depannya yang lebih baik. Kini, dengan alasan yang sama, aku justru menggenggam satu perempuan lain erat-erat. Perasaan bersalah dan keraguan bercampur, seolah berjalan di atas tali tipis antara dua bukit dengan angin kuat, lalu aku merentangkan tangan untuk menyeimbangkan antara pengorbanan dan egoisme. Namun, dibalik semua itu, ada dorongan kuat yang tak bisa diabaikan, sebuah harapan bahwa kali ini aku bisa melakukannya dengan benar.
“Ya. Gak mudah. Tapi gua percaya gua bisa.”
Kulihat Ares menatapku, dan lagi-lagi dengan tatapan iba.
-oOo-
Runa, kamu ingat? Dulu saat kita datang ke pameran fotografi, sambil menggenggam tanganku, kamu berkata bahwa suatu saat aku akan hadir sebagai seniman, bukan hanya sebagai pengunjung. Sekarang, aku di sini, Runa. Tiga setengah tahun setelahnya, berdiri di depan foto kamu dan ibu sebagai seorang seniman. Di Kota Tua. Di tempat kita pernah duduk sore bersama, kamu makan es krim dan aku minum cola.
Kamu yang mengantarkan aku ke titik ini. Kamu yang dulu dan kamu yang ada dalam bingkai. Semuanya tentang kamu. Tapi sayangnya, kamu tidak hadir untuk menyaksikannya, juga tidak ada di sini untuk hari bahagia ini. Hilangnya kehadiranmu terasa begitu nyata di tengah pencapaian ini. Aku senang dengan cara yang paling hambar. Bayanganmu panjang. Namamu tertorehkan. Dan itu semua membuat rindu tidak pernah menjadi abu-abu.
Napas terembus. Aku mengusap label dengan tulisan Bunga Seruni Kemerah-Merahan, judul untuk foto ini. Seruni, nama ibuku dan juga nama bunga. Aruna berarti cahaya merah.
Ares menepuk pundakku, sedangkan Trisna datang menyodorkan satu botol air mineral.
“Siap?” tanya Ares dengan semringah.
Aku mengangguk.
Hari ini adalah hari pembukaan pameran. Aku akan memberikan sambutan kepada para tamu dan menjelaskan dengan singkat konsep dan inspirasi di balik karya ini.
Pengunjung datang dengan kapasitas ruangan terbatas, juga dengan protokol kesehatan yang harus dipatuhi.
-oOo-
“Ibu sama Marwa berencana besok ke Jakarta. Mau lihat pameran foto kamu. Sekalian ada beberapa teman dan saudara yang mau Ibu kunjungi.” Begitu kata Ibu pada telepon Jumat sore. Besoknya, tepat pukul sebelas ibu dan Marwa datang. Marwa mengeluhkan parkiran yang kecil di kost baru ini dan memintaku memperbaiki posisi mobil yang dia parkirkan sembarangan. Benar saja, Marwa menutupi jalan keluar-masuk motor di parkiran. Setelah solat Zuhur, kami keluar, mengunjungi teman dan saudara ibu untuk mengabarkan pernikahan Marwa pada hari Minggu pertama di bulan Desember nanti. Tidak banyak, hanya tiga rumah yang kami kunjungi, mengingat Marwa dan Ikhsan tidak mengadakan resepsi besar-besaran. Setelah itu, kami berangsur ke Kota Tua, melihat pameran fotografi. Ibu banyak berfoto pada karyaku yang dipajang itu. Lalu Marwa, dengan air muka yang tampak cemburu, dia protes kenapa bukan foto dia yang diikutsertakan. Untuk menyenangkan hatinya dan, lagi-lagi, agar tidak muncul rasa iri hati yang membentuk persaingan (meskipun Aruna sudah tidak di sini bersama kami) aku katakan, “Foto kamu itu semuanya kelihatan wajah. Kakak gak mau kamu dilihat-lihat banyak orang. Ini kebetulan ibu sama Aruna back shot. Nyamping doang, liat-liatan.”
Marwa yang sudah sejak kecil hidup bersamaku tentu tahu aku hanya berusaha berada di tengah saja.
“Cari aman banget!” katanya kemudian.
Meskipun begitu, aku tahu, dia bangga padaku. Hanya saja tidak dia ucapkan. Aku lirik, dia mengirimkan foto karyaku itu ke grup Whatsapp pertemanannya. Lalu sebelum pulang, kami berfoto bertiga di depan karya itu dibantu oleh security.
Ibu ingin langsung pulang ke Bogor, lalu aku mengantarkan mereka malam itu juga. Sebelum itu Marwa yang mengeluhkan lapar, menyebutkan satu restoran yang sering aku dan Aruna datangi, dulu. Kini, sudah beberapa tahun sejak aku dan Aruna tidak bersama lagi, aku tidak pernah menginjakkan kaki di sana. Bukan karena sengaja menghindari kenangan atau tiba-tiba membenci tempat-tempat yang pernah kami kunjungi, hanya saja aku memang tidak punya preferensi khusus terhadap makanan. Jarang sekali kepingin ini atau kepingin itu. Aku makan apa saja, asal kenyang, itu sudah cukup bagiku.
Tempat itu tampaknya tidak banyak berubah. Jika bukan karena penambahan ayunan di halaman, semuanya hampir sama seperti dua tahun lalu. Spanduk besar di pintu masuk bertuliskan ‘Hanya Melayani Take Away’. Marwa dan ibu masuk ke dalam, sementara aku menunggu di mobil. Mereka cukup lama di restoran itu, hingga aku menelepon Marwa untuk menanyakan apakah ada masalah. Ternyata, handphone-nya, serta milik ibu juga, tertinggal di mobil. Saat aku berencana menyusul, mereka akhirnya keluar.
“Kak!” kata Marwa segera setelah menutup pintu mobil, “ada Kak Aruna di dalam, mau ketemu dulu, gak?”
Aku sudah memegang persneling, bersiap melajukan mobil, menoleh ke belakang, menatap Marwa, dan segera menoleh ke samping, menatap Ibu. Ibu mengangkat kedua alisnya, menunggu reaksiku.
Aruna? Selama ini dia di sini? Di Jakarta?
“Dia sama suaminya dan juga anaknya,” kata ibu.
“O-oh …,” kataku lagi sambil memindahkan tuas persneling dengan canggung. Aku urung turun. Mobil jalan, meninggalkan parkiran restoran itu tepat saat Aruna keluar bersama Andre yang sedang menggendong balita berambut tebal. Aruna di sampingnya, mencubit-cubit gemas pipi balita itu. Pemandangan itu cukup membuatku yakin bahwa Aruna telah hidup layak dan bahagia.
Mobil sudah cukup jauh meninggalkan restoran.
“Alpha,” kata ibu lagi.
Aku menoleh, “Alpha?” tanyaku ragu-ragu.
“Nama anak Aruna. Alpha,” ibu menjelaskan.
“O-oh, ya.”
Alpha?
Alpha …
Jalan berbelok ke kiri dan aku, setelah kecelakaan itu terjadi –nyaris setahun lalu, sedikit khawatir berada di perempatan. Takut entah tiba-tiba ada pengguna jalan yang datang dari arah berlawanan, atau justru aku yang ditabrak lagi oleh pengendara lain.
Pikiranku sedikit kacau. Sesuatu pada nama Alpha telah mengingatkanku pada kenangan lama.
“Kayaknya mirip kamu, deh, Gam …,” kata ibu setengah menuntut setengah bercanda.
“Bu, banyak yang bilang kalau perempuan lagi hamil, terus benci banget sama seseorang, anak kita bakal mirip orang itu,” Marwa yang sedari tadi hanya mendengarkan obrolan sambil menyantap nasi gorengnya, kini menjawab, “bisa aja, kan, Kak Aruna tuh kesel sama mantannya, makin menjadi karena sedang hamil. Mood swing!” pada kata mantannya Marwa menekan kuat. “Contohnya banyak. Kayak temen aku, lagi hamil kesel sama satu artis. Eh, sampai anaknya umur dua tahun wajahnya banyak yang bilang mirip artis itu!” jelas Marwa lagi.
Aku diam.
Ibu menaikkan bahunya, “Mungkin …. Yah, lagipula hampir semua bayi wajahnya mirip-mirip. Gitu-gitu aja.”
Marwa mengangguk sambil memilah-milah makanannya, “Ah! Aku lupa minta nomor Kak Aruna!” kemudian menepuk dahinya sendiri, sepertinya dia sangat kesal. Bunyi pukulannya terdengar kuat.
Aku tertawa melihatnya. Separuh bersyukur juga karena dia lupa. Kalau saja Marwa memiliki nomor Aruna, bisa saja aku kembali berkelahi dengan diri sendiri perkara meminta nomor Aruna dari Marwa atau tidak.
Setengah perjalanan, ibu tertidur, sedangkan aku dan Marwa hanya membicarakan pernikahannya yang akan dilangsungkan dua minggu lagi.
Sampai di Bogor, lewat sedikit pukul sembilan. Marwa langsung masuk kamar, sedangkan ibu, yang sudah tidur hampir satu jam di mobil, tampak segar. Ibu ke dapur, membuat minuman hangat. Teh untukku dan seduhan jahe untuknya. Aroma dari jahe itu tiba-tiba kembali mengingatkanku pada Aruna, seduhan jahe dan madu yang dia buatkan untukku dulu, saat badanku tidak karuan tidak sehatnya, begadang hampir setiap malam, bekerja tanpa peduli waktu. Ah, waktu-waktu itu. Waktu-waktu dimana meskipun di luar mengalami desakan, bingung dan segalanya serba tergesa-gesa, aku selalu pulang dengan hati lapang karena tahu ada yang menantikan. Waktu-waktu dimana kesedihanku dipeluk dengan sempurna oleh tubuh kekasih yang mengantarkan ketenangan. Aruna, aku masih saja mengingatnya. Maaf.
“Nak …,” panggil ibu. Ibu menarik napas dalam lalu mengeluarkannya perlahan, “Ibu bangga hasil foto kamu dipamerkan. Selamat.”
“Do’a Ibu nembus langit,” aku mengacungkan kedua jempol dengan senyum yang membuat ibu tertawa. Untuk sementara, ruang makan penuh riuh tawa kami berdua. Tidak lama. Sebelum akhirnya ibu menggenggam tanganku di atas meja, ibu berkata dengan hati-hati, “Ibu sama sekali gak masalah foto ibu dan foto Aruna dipajang di sana. Kamu juga udah izin sebelumnya sama ibu, kan?” Ibu diam, menatapku, “tapi … meskipun wajahnya gak kelihatan jelas, apa kamu udah bilang sama Aruna?”
Bibir mengatup rapat dan aku menggeleng sambil menunduk.
“Ibu tahu, mungkin salah satu alasan kamu milih foto itu karena sesuatu yang ada di dada kamu. Ibu juga tahu, masa-masa kamu dan dia dulu itu memunculkan harapan baru buat kamu.”
Aku kembali menatap ibu. Pada wajah ibu muncul satu raut kekhawatiran.
“Tapi itu udah lama berlalu, kan?” Aku paham. Ibu tidak benar-benar bertanya, ibu berusaha mengingatkan. Dan aku, yang tahu ibu tidak membutuhkan jawaban hanya bisa diam.
“Udahlah, Nak. Buang jauh-jauh perasaan yang pernah ada buat Aruna, atau … simpan dalam-dalam sampai gak ada satu orang pun tahu bahkan kamu sendiri gak mengingat dimana kamu simpan, lambat laun kamu benar-benar lupa.”
Aku masih diam.
“Untuk bisa maju, kamu harus meninggalkan apa-apa yang memang udah di belakang. Kalau enggak, kamu hanya akan merangkak atau justru jalan di tempat. Ibu gak ngomong soal apa aja yang bisa kamu ukur dengan angka, ibu bicara tentang apa yang kamu rasa.”
Aku ingin memberikan senyuman meyakinkan pada ibu, tapi sepertinya gagal. Aku tersenyum dengan bimbang, “Ya, Bu.”
Suara detakan jarum jam menemaniku hingga dini hari, aku tidak bisa tidur lagi. Nasihat ibu menggema-gema di kepala. Membuang jauh-jauh atau menyimpan rapat-rapat. Apapun caranya, tujuannya hanya satu: melupakan. Benar memang aku merasa sakit karena masih menyimpan rindu, tapi kini merasa lebih sakit lagi karena harus melupakannya segera. Lalu aku tidak bisa menepis perkataan ibu mengenai merangkak atau jalan di tempat. Sangat benar. Harapanku pada Aruna sudah lama menguap. Kini aku harus benar-benar fokus pada apa yang aku hadapi di masa-masa ini dan mencoba menata semuanya dari awal. Tentang satu keputusan. Tentang masa depan.
Besoknya setelah makan siang di rumah, aku yang sedang siap-siap kembali ke Jakarta, ditelepon oleh seorang kurator –yang sering menghubungi dan aku hubungi selama pameran. Dia mengatakan ada seorang perempuan yang ingin membeli fotoku.
“Gua udah bilang, ini gak dijual. Tapi dia ngotot,” kata kurator itu, “gimana?”
Perempuan?
“Namanya siapa?”
“Gak mau dia kasih tahu. Dia cuma pengen beli. Transfer, langsung bawa.”
“Ciri-cirinya?”
“Hmmm,” kurator itu sepertinya berjalan sedikit menjauh, aku mendengar napasnya memburu, “Berjilbab, udah ibu-ibu sih. Tinggi, agak kurus, berkacamata,” dia menjelaskan dengan suara yang kecil.
“Enggak. Gak dijual. Sampein maaf gua ya, Kak.” Aku menolak karena tidak mengenal wanita dengan ciri-ciri seperti yang disebutkan. Bahkan, jika saja, jika saja perempuan itu sudah pasti Aruna, maka foto itu akan kuberikan saja. Menganggap foto itu sebagai hadiah perpisahan dan pelepasan.
“Oke, sip!” Jawab kurator singkat.
Telepon itu tertutup. Aku segera keluar kamar, mengetuk pintu Marwa yang sedikit terbuka, dia akan mengantarku ke Stasiun Bogor.
“Padahal kakak juga WFH, kan? Kenapa gak di sini aja sampai aku nikah?” tanya Marwa saat aku memasang sepatu dan dia mengeluarkan motor matic-nya dari garasi.
“Pengennya juga gitu,” kataku, turun ke garasi, membantu Marwa mengeluarkan motor dan menyalakannya, “cuma, yah gitu, kadang masih ada yang perlu dicek di kantor.”
Kami berdua berkendara menuju Stasiun Bogor dan Marwa kembali bahkan sebelum aku masuk kereta.
Baru saja kereta berjalan, Tyas menelpon. Dia di depan kost-ku dan tetanggaku mengatakan aku pergi.
“Iya, gua kemarin di rumah. Tidur di rumah. Kenapa, Yas?” tanyaku.
“Oh. Cuma mau bahas, kayaknya Midas udah bisa kerja seperti biasa. Gak perlu dari rumah lagi.”
“Oke. Besok gua ke rumah lu aja. Biar sekalian bicara sama Pak Adimas mengenai ini,” kataku lagi. Pelonggaran PPKM sudah dimulai sejak akhir September. Kuperhatikan melalui jendela, jalanan sudah mulai seperti kembali bernyawa, tidak pucat dan tidak suri lagi. Sudah cukup ramai. Bahkan kereta ini mulai penuh penumpang.
“Kalau gitu gua tunggu besok siang,” kata Tyas.
Telepon itu berakhir.
Tyas. Barangkali aku lancang, berani berasumsi bahwa keputusan sepihak dariku adalah satu jalan yang akan mengembalikan harapan dan kebahagiaannya. Aku bisa saja mendapat penolakan, atau justru diterima dengan tangan terbuka dan senyuman mengembang. Bagiku, keduanya sama saja; penolakan tidak akan mendatangkan kesedihan, penerimaan tidak akan mendatangkan rasa bangga. Aku hanya ingin sekuatnya bertanggung jawab atas apa yang telah terjadi padanya.
Aku mulai mengira-ngira, kapan sebaiknya niat ini kusampaikan pada ibu. Juga mengira-ngira bagaimana reaksi ibu terhadap apa yang akan dia dengar dari mulut anaknya tentang rencana ini, rencana menikahi Tyas. Aku mendesah lemah, mengatupkan bibir rapat-rapat, memejamkan mata. Perasaanku tidak nyaman, seakan-akan beban berat menekan dada. Dan aku hanya ingin tidur sebentar, istirahat sejenak dari rumitnya hidup pada usia dua lima.
Dua enam! Aku baru menyadari bahwa bulan lalu aku berulang tahun.
(Bersambung)
Restart ©2023 HelloHayden


 hellohayden
hellohayden




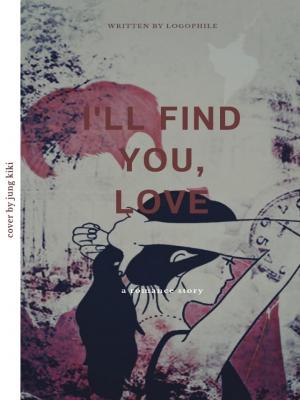





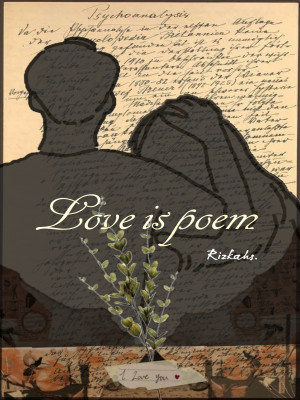


Baca cerita ini udah kayak masuk ke kedai all you can eat. Daging semua. Sbg cowok baca ini gk merasa aneh sama sekali untuk crita roman dan rasa kembali ke masa kuliah. Mantap lah
Comment on chapter Bab 14 (Cukup)