Aku duduk bersedekap, memandang nanar dinding yang sedang Ares kuas lem untuk dipasangi wallpaper. Jam dinding bulat besar dengan bingkai hitam bersandar di antara tumpukan kardus, menunjukkan pukul sepuluh malam. Aku duduk terdiam. Ingatan-ingatan pertengkaranku dengan Aruna susah dihilangkan. Gumpalan kesedihan mengganjal di tenggorokan, sedang hatiku sudah bukan lagi remuk, tetapi koyak. Sobek. Hancur.
-oOo-
Pagi ini, sambil berpakaian dan berkemas untuk ke Tangerang, aku tersenyum sendiri membayangkan betapa terkejutnya Aruna nanti saat bertemu denganku di klinik Bu Sarah. Dua hari lalu, Pak Purwa menelepon, mengatakan sedang membutuhkan desainer untuk poster acara promosi dan juga untuk meliput acara pembukaan sebuah klinik.
“Kamu inget gak orang yang pertama kali kita wawancarai pas acara kecap dulu?” tanya Pak Purwa.
“Ya.”
“Nah, saya ketemu lagi di dinsos beberapa bulan setelah itu. Mereka minta saya bikin konten menarik buat website,” jawab Pak Purwa.
“Hmmm,”
“Ya, terus temenan, karena sering ketemu.”
“Oohh.”
“Sarah, kalau Mas Gamma lupa namanya. Nah, dia itu sekarang buka klinik.”
“Oh? Jadi klinik itu bakalan grand opening?”
“Yap!”
Aku yang sudah tahu seminggu sebelumnya dari Aruna, lantas bersikap sewajarnya saja ketika mendengar berita itu dari Pak Purwa. Aruna mengatakan selain acara seremonial, akan ada acara promosi pemeriksaan kesehatan gratis dan pemberian lima puluh voucher diskon untuk warga sekitar yang hadir.
Kemarin siang saat aku sedang memilih poster paper untuk acara klinik, Aruna masuk ke kamarku, segera mengecup pipiku sambil mengatakan, “Acaranya besok, tapi aku harus bantu-bantu Bu Sarah juga, kan?” ujar Aruna menekankan kalimatnya, pada kata kan dia bahkan menaikkan kedua alis. Dia seolah meyakinkanku bahwa dia sangat dibutuhkan di sana.
“Ya. Aku tahu. Hati-hati,” kataku tanpa menunjukkan reaksi berlebihan. “Ketemu lagi besok malam,” katanya.
Besok siang. Batinku.
Sebuah mobil sedan hitam parkir di halaman dan Aruna naik segera sambil melihat sekilas ke jendelaku dimana aku berdiri sambil tersenyum padanya.
Sepanjang jalan menuju Tangerang, hatiku berdebar menerka-nerka entah bagaimana lakon Aruna melihatku hadir di tempat yang sama dengannya dalam satu acara. Ini mengingatkanku pada acara wisudanya dulu. Sedikit-sedikit aku terkikik.
Pak Purwa menyambut saat aku datang. Dia membantu meringankan beban ranselku dengan mengeluarkan gulungan poster dan dikepit diketiaknya. Kami berjalan beriringan. Klinik kesehatan itu menempati dua ruko besar dengan tiga lantai. Areal parkir yang cukup luas sudah dipasangi tenda berwarna oranye, kursi plastik putih yang didekorasi dengan pita oranye pula sudah rapi tersusun di bawahnya. Beberapa mobil pick-up tampak masih sibuk mengantar karangan bunga mengucapkan selamat, petugasnya tampak kesusahan menempatkan karangan bunga itu karena nyaris tidak ada lagi tempat, bahkan sebagian sudah memenuhi bahu jalan. Acara akan dimulai pukul satu siang, tapi dua jam sebelumnya setengah dari kursi-kursi ini sudah terisi oleh para tamu undangan. Aku tidak melihat Aruna diantara perawat-perawat atau praktisi (aku tidak bisa membedakannya sebab semuanya berpakaian putih) yang sedang mempersiapkan alat-alat pemeriksaan di atas meja yang berjejer sebanyak empat di depan kursi tamu. Sepertinya di sana nanti akan dilakukan pemeriksaan gratis. Seorang perempuan berpakaian putih tergopoh-gopoh membawa alat-alat itu dari dalam klinik, merundukkan badan saat melewati pita oranye yang melintang di pintu. Dari pintu kaca yang buram, Bu Sarah keluar dengan pakaian apik, berjalan menghampiri kami.
Dia tersenyum ramah padaku, “Ketemu lagi,” katanya sambil mengulurkan tangan.
Aku mengangguk, “Iya, Bu.” Aku menyambut tangannya dan kami bersalaman.
“Pak Purwa banyak bercerita tentang kamu. Kamu salah satu orang yang bikin Tugu Monas jadi lebih menarik saat tahun baru.” Bu Sarah memuji.
“Terima kasih, Bu.”
“Pekerjaan itu udah mendarah daging, mengalir dalam nadinya. Dia menyukainya. Kamu bisa lihat wajahnya saat bekerja. Cerah.” Timpal Pak Purwa yang semakin membuatku merasa tidak enak. Pujian berlebihan dari orang yang tidak terlalu aku kenal membuatku merasa harus membalasnya, sedangkan aku bukan orang yang ekspresif saat berbicara (kecuali dengan Aruna). Aku menunduk saja sambil tersenyum kikuk.
“Pernah. Aku pernah melihatnya dua kali saat bekerja,” jawab Bu Sarah.
“Yang pertama aku tahu, aku ada di sana juga, saat acara kecap, kan? Festival makanan?” tanya Pak Purwa, “lalu yang ke dua?” dahi pria dengan tatapan bersahaja ini mengernyit.
“Wisuda Aruna. Ya?” Bu Sarah menoleh padaku. Aku mengiyakan.
“Kebetulan juga Gamma ini tetangga Aruna, depan-depanan.” Tambah Bu Sarah lagi. Bibir Pak Purwa membentuk huruf O saat melihatku. Dari percakapan ini, aku sudah bisa menyimpulkan sedikit banyaknya Pak Purwa sudah tahu mengenai Aruna dari Bu Sarah dan mungkin juga sudah pernah bertemu sebelum acara ini.
“Ngomong-ngomong, Aruna mana, ya?” tanya Pak Purwa, kepalanya toleh kiri-kanan. Pertanyaan yang dari tadi aku simpan itu terwakilkan oleh Pak Purwa.
“Oh? Di atas, lagi diskusi sama MC. Ada Andre juga. Kamu mau nyusul mereka?” Bu Sarah menjawab cepat, jempolnya menunjuk ke belakang, mengarah ruko, “kamu coba cek, deh, teks MC-nya. Koreksi kalau perlu. Kamu lebih paham soal itu.” Pinta Bu Sarah pada Pak Purwa.
“Oke. Mas Gamma, ini saya bawa aja, ya? Biar dipasang sama tukang.” Pak Purwa menepuk-nepuk poster yang dia kapit. Lalu pergi.
Perasaanku tidak nyaman saat nama Andre disebutkan. Gaya sok intelektualnya langsung saja muncul dalam ingatan, lengkap dengan kulit wajah mulus yang aku yakini memiliki jadwal rutin ke dokter estetika setiap bulan, atau paling tidak dia punya satu merk andal untuk perawatan wajahnya. Aku menatap gedung klinik mengira-ngira mereka berada di lantai berapa.
“Mumpung acara belum mulai, Gam. Kita bisa foto-fotoin dulu untuk website klinik,” ajak Bu Sarah.
Klinik itu cukup besar untuk disebut sebagai perintis. Pelayanannya cukup lengkap. Selain dokter umum, terdapat spesialis kandungan, spesialis mata, spesialis THT dan dokter gigi. Saat berkeliling memotret, aku tidak bertemu Aruna. Hanya ada Pak Purwa yang sedang mencoret-coret kertas bersama seorang MC di lantai dua. Mereka serempak mengatakan Andre dan Aruna sudah turun sedari tadi membantu penataan tamu pada tenda saat Bu Sarah bertanya. Bu Sarah mengangguk, aku membuang muka untuk menghela napas. Jengkel.
Aku dan Bu Sarah memasuki ruangan dengan jendela besar, hampir seluruh sisi dinding itu kaca yang menampilkan sebingkai pemandangan kota Tangerang. Gordennya yang disibak kiri dan kanan membuat cahaya matahari masuk sempurna. Ruangan ini cukup luas dengan tiga meja kerja dan masing-masing komputer di atasnya. Ketiga meja tersebut membentuk huruf U dengan satu meja di tengah lebih besar. Aku perkirakan meja itu akan diduduki Bu Sarah. Berbeda dengan ruangan lainnya yang cenderung berwarna putih, dinding ruangan ini dipasang wallpaper berwarna beige dengan tekstur serat kayu.
“Ini warna pilihan Aruna,” ujar Bu Sarah lagi saat jarinya menyusuri dinding. Pantas saja, ini warna yang sama dengan cat dinding di kamar Aruna.
“Nanti dia akan duduk di sana,” Bu Sarah menunjuk satu meja di sudut. Botol minum yang aku belikan untuk Aruna berdiri tegak di samping komputer. Tas selempang Aruna tergeletak lemas pada kursi kerja. Aku tidak terkejut. Kontrak kerja Aruna di rumah sakit akan berakhir sebelum Maret mulai, lalu dia memutuskan untuk tidak memperpanjangnya meskipun ada tawaran dari pihak rumah sakit. Dia akan mengikuti jalur yang telah Bu Sarah siapkan untuknya: membantu mengelola klinik seperti rencana awal.
Aku mulai mencari sudut tepat untuk mengambil foto. Saat melewati meja Aruna, komputernya menyala dengan desktop bergambar standar yang telah windows sediakan. Ujung telunjukku menyusuri kepala kursi yang akan diduduki pacarku nanti. Aku berdebar membayangkan dia duduk dengan wajah serius mengetik sesuatu di komputer ini. Bu Sarah yang sedari tadi berjalan di depanku berhenti pada meja besar. Dia menarik kursi lalu duduk di sana.
“Ini nanti meja saya,” katanya sambil tersenyum puas dan mengusap-usap meja itu perlahan.
“Selamat, Bu,” ujarku sambil memotret dari belakang. Dia menoleh ketika mendengar bunyi jepretan, tersenyum, dan meminta foto ulang. Aku tertawa kecil karena momen ini terasa sangat familiar.
“Kenapa tertawa?” tanya Bu Sarah ikut tertawa.
Aku mengangkat bahu ringan, “Déjà vu.”
“Pasti gak sekali dua kali kamu mengalami momen seperti ini. Saya rasa yang buat kamu tersenyum bukan kejadiannya, tapi orangnya.”
Tebakan Bu Sarah tepat, namun aku diam saja sambil berusaha menyembunyikan kegembiraan karena mengingat Aruna.
“Pacar?” tanya Bu Sarah setengah mendesak.
Aku melirik meja Aruna sambil tersenyum singkat, “Ya, begitulah, Bu.”
Bu Sarah tersenyum. Lalu dia memintaku memotretnya lagi dengan posisi tadi, bedanya kali ini dia menoleh ke belakang, melihat kamera. Aku memotretnya dua kali. Saat aku memeriksa hasil jepretan, Bu Sarah membuka laci dan mengeluarkan dua foto berukuran 5R yang dibingkai kayu. Dia menata dua foto itu berdekatan dengan komputernya. Pada bingkai pertama, potret Bu Sarah dalam balutan kebaya jingga dipadukan dengan kain batik coklat tua. Jilbab yang dia kenakan ditata sedemikian rupa. Anggun. Lalu foto kedua, sepasang anak laki-laki dan perempuan, berseragam merah-putih SD lengkap dengan topi dan dasi. Dua anak itu tampak berdiri kaku. Wajah masing-masing tampak tegang dengan tangan mengepal di sisi kiri dan kanan dalam posisi siap. Yang laki-laki tampak lebih tinggi dan sepertinya juga berada pada usia lebih tua.
“Foto ini selalu berhasil membuat saya tersenyum,” ujar Bu Sarah sambil mengusap-usap foto itu.Aku menyipitkan mata, berusaha melihat jelas wajah dua anak dalam foto itu.
“Ini Andre, satu-satunya keponakan saya. Nanti dia akan duduk di meja itu,” Bu Sarah menunjuk meja di sisi kanannya, “nah, ini kamu tahu? Ini Ar-”
“Runa. Aruna.” Jawabku cepat memotong ucapan Bu Sarah. Bu Sarah langsung menoleh ke arahku, “Iya. Tetangga kamu. Bahkan kamu tahu, ya walau sebagian wajahnya tertutup topi.”
Mendengar kata tetangga dadaku terasa berat. Seolah Bu Sarah menegaskan hubungan kami seharusnya.
“Mereka berdua sudah menjadi penyemangat saat saya putus asa dan hampir menyera dulu.” Bu Sarah mencubit-cubit kecil ujung kemeja yang dia kenakan, seolah cerita itu masih membebaninya.
“Oh.” Hanya itu yang bisa aku katakan di tengah perasaan tidak menyenangkan yang menghimpit. Sesuatu dalam percakapan ini membuatku merasa ada yang tidak beres.
“Saya masih ingat kali pertama melihat Aruna di panti asuhan. Kunjungan rutin dari dinas sosial. Saat anak-anak lain sedang mengantre makanan yang kami bawa, dia duduk di luar, sendirian, sedang menggambar wajah manusia pada balon merah muda. Saya menghampirinya dan bertanya siapa yang dia gambar. Dia menjawab ibunya. Gambar itu selesai dengan goresan terakhir bibir tersenyum, dia menerbangkan balon itu sambil melambaikan tangan mengatakan tetaplah berada di langit seperti yang Bu Hafsari katakan. Saat itu saya memalingkan wajah, air mata saya menetes tiba-tiba. Usianya baru akan empat tahun saat itu. Saya merasa tertampar karena benar-benar hampir menyerah menghadapi cobaan. Tapi anak ini, dengan usia dibawah lima, memiliki jiwa tangguh menghadapi segala derita dengan penerimaan luar biasa.” Bu Sarah bercerita dengan pelan. Dia masih mengusap-usap foto itu pada bagian wajah Aruna. Suaranya bahkan terdengar lirih. Lara menjalari dadaku sehingga terasa semakin berat karena mendengar kisah sedih yang baru aku tahu tentang Aruna. Membayangkan Aruna kecilku yang harus menghadapi duka melebihi kesanggupannya. Namun, dia berhasil melaluinya.
Bu Sarah membersihkan tenggorokannya, “Foto ini diambil di depan sekolah, saat dia kelas tiga dan mendapatkan juara pertama. Andre dua tahun di atasnya, kelas lima, juara tiga. Saat itu saya mengambil rapor Andre dan secara kebetulan, Bu Hafsari berhalangan datang sehingga saya juga mengambil rapor Aruna. Mereka yang tadinya sedang bercanda, ketawa-ketiwi, pas saya bilang mau fotoin langsung pada berdiri kaku. Lucu! Lucu banget!” Bu Sarah tersenyum, “lihat, deh! Mereka langsung kayak nahan napas. Padahal kamu tahu? Selesai difotoin, mereka kayak biasa lagi. Ketawa-ketawa lagi, kejar-kejaran lagi.”
Sejujurnya cerita itu memang lucu, terlebih jika membayangkan Aruna kecil yang kikuk itu. Namun kenyataannya, jangankan ikut tertawa, tersenyum saja aku tidak bisa. Aku iri hati mengetahui mereka dulu sangat akrab lalu merasa cemburu sebab hingga kini mereka dikatakan cukup dekat. “Mereka akrab, ya?” tanyaku kemudian.
“Tentu saja. Mereka tumbuh bersama. Sebulan sekali saat Andre datang menginap, saya akan menjemput Aruna dari panti untuk bermain bersama Andre.”
“Sudah seperti kakak dan adik.” kataku lagi, sebenarnya juga untuk menenangkan perasaan cemburu tadi.
Bu Sarah berhenti mengusap-usap foto itu. Memutar kursinya menghadapku. Wajah Bu Sarah sempurna tersiram cahaya matahari dari jendela besar di belakangku. Dia tersenyum tanpa ragu, kelihatannya seperti menyeringai, “Ya. Dulu. Mereka seperti kakak beradik.”
Dulu? Aku mengerutkan dahi, tidak mengerti.
“Saat itu Andre baru naik kelas tiga dan Aruna baru masuk SMA tahun pertama, saya katakan kepada mereka bahwa tidak ada gunanya mencoba menyukai orang lain, apalagi sampai jatuh cinta karena mereka berdua akan menikah juga.”
Aku terkesiap. Kalimat demi kalimat yang diucapkan Bu Sarah dengan penuh kepastian ini berhasil mengguncang jantung. Bu Sarah mengangguk, “Sebulan lagi, Gam. Kira-kira sebulan lagi, kalau bisa gak lama setelah Aruna selesai kontrak kerja, mereka akan menjadi suami-istri.”
Aku bisa memastikan tidak ada satu garis keraguan pun dari wajah Bu Sarah saat mengatakan itu, terlebih kini sangat jelas penglihatanku dibantu oleh cahaya terang matahari.
Dadaku terasa panas terbakar seperti baru saja tersambar halilintar. Sensasinya merambat naik ke tenggorokan. Namun anehnya, punggungku yang menerima tembakan cahaya matahari terasa dialiri air sedingin es yang menyapu sepanjang tulang dan membuatnya terasa membeku. Aku panas dingin. Bu Sarah melanjutkan dengan yakin, menginginkanku mendesain undangan pernikahan, “Saya ingin teman Aruna sendiri yang turut serta membantunya mempersiapkan pernikahan. Dia pasti senang.”
Tetangga. Teman.
Lagi-lagi aku merasa didorong ke posisi seharusnya.
Lidahku kelu. Aku kehilangan kata-kata. Bu Sarah berdiri dan menepuk pundakku yang berdiri terpaku, “Ayok! Kok diem? Kita harus foto ruangan lain, kan?” Dia berjalan melewatiku. Bunyi ketukan sepatu hak tinggi pada lantai layaknya sebuah pisau yang menikam jantung. Tiap ketukan tiap tikaman. Saat pintu di belakangnya menutup saat itu juga jantungku sudah hancur lebur. Aku sempoyongan, perutku berpilin dan membuatku mual. Lutut tidak lagi mampu menopang badan membuatku terhuyung ke belakang dan membentur jendela besar. Mataku bergerak ke arah dua foto anak kecil dengan seragam SD berdiri bersisian dengan wajah tegang. Samar-samar foto itu berubah menjadi sepasang pengantin dewasa dengan pakaian serba putih dan terlihat bahagia.
Bukannya si Andre ini tahu aku pacar Aruna?
Kenapa Aruna gak pernah cerita apa-apa?
Mendadak udara terasa pekat. Gumpalan sebesar kepalan tangan menghambat rongga dada yang membuatku bernapas dengan dangkal. Aku mulai sesak dan meremas strap kamera yang memiliki bordir inisial GA & AG.
Pintu terdengar dibuka kasar, membuyarkan bayangan pengantin dalam bingkai foto itu.
“Mas Gamma! Ayok! Acara udah mau mulai,” ujar Pak Purwa yang berdiri sambil menahan pintu. Aku pun tersadar akan pekerjaan dan bergegas turun bersama Pak Purwa. Kami melangkah tergesa-gesa. Perasaanku semakin kacau saat melewati Aruna yang sudah berdiri bersebelahan dengan Bu Sarah di belakang pita oranye yang melintangi pintu. Dia sedang memegang gunting yang diberi hiasan bunga plastik putih. Aruna mendelik dengan raut terkejut yang tidak mampu disembunyikan saat menyadari kehadiranku. Mulutnya sedikit terbuka seolah ingin mengatakan sesuatu tapi sepertinya dia sadar dan langsung mengatupkan bibir. Jari-jemari Aruna meraba punggungku perlahan ketika aku menundukkan badan di bawah pita untuk melewati pintu. Aku tidak menoleh lagi ke belakang dan terus berjalan mengambil posisi, memasang tripod dan kamera, mendokumentasikan acara seremonial.
Suara MC terdengar lantang menyapa tamu-tamu yang datang. Acara bergulir dengan lancar. Kepala dinas kesehatan yang hadir sebagai tamu kehormatan sedang memberi kata sambutan saat Andre dengan kemeja biru mudanya muncul dari arah tangga. Kini dia yang berdiri persis di samping Aruna tengah berbisik lalu Aruna mengangguk. Mereka tampak tidak canggung sama sekali berdiri dalam jarak dekat, bahkan Aruna dan Andre terlihat telah terbiasa untuk saling bisik-berbisik. Darahku berdesir hebat dan benar-benar menahan diri untuk tidak meledak. Saat mataku dan mata Aruna bertemu, dia tersenyum canggung.
Pak Purwa yang duduk pada barisan bangku paling depan, hanya berjarak dua langkah dariku yang meliput acara, sesekali berdiri melihat pekerjaanku. Mic beralih ke tangan Bu Sarah, menyampaikan kata sambutan dan memperkenalkan kliniknya. Setelah itu, Aruna memberikan gunting kepadanya, dan dalam seketika, pita oranye yang tegang itu lemas saat terputus menjadi dua, diiringi tepukan tangan meriah para tamu. Banyak dari mereka yang berdiri karena antusias. Saat orang-orang bertepuk tangan sebab klinik baru telah resmi dibuka, aku bertepuk tangan merayakan keberhasilan seseorang menghancurkan perasaanku begitu saja. Dalam jarak ini, aku masih yakin bahwa tatapanku yang tajam untuk Aruna akan sampai kepada ulu hatinya. Benar, dia tampak gusar. Kini dia tahu banyak yang harus dia jelaskan padaku. Kakinya membawanya maju selangkah untuk mendekatiku namun Bu Sarah tiba-tiba mengambil tangannya dan menyerahkan gunting kembali pada Aruna. Saat itu juga aku pergi, mengambil posisi ke belakang untuk merekam tamu-tamu yang hadir. Bersama Pak Purwa, kami mewawancarai kepala dinas kesehatan dan kepala dinas sosial. Pak Purwa yang mendapat kepercayaan dari Bu Sarah untuk mengisi website klinik, tak kalah tampak semangat. Sepertinya, di antara puluhan orang, hanya aku yang kehilangan antusiasme dalam acara ini.
“Aman, Gam? Lemes amat!” Tanya Pak Purwa sambil mengulurkan air kemasan. Aku hanya mengembangkan senyuman dengan terpaksa, “Aman.”
Aruna dan tiga perawat lainnya sudah duduk pada meja pemeriksaan dan sudah sibuk melayani tamu-tamu yang mengantre untuk mendapatkan pemeriksaan gratis. Aku mendekat untuk mengambil video mereka. Saat di meja Aruna, dia sangat terlihat menghindari tatapan pada kamera. Dia hanya berusaha bersikap ramah pada orang yang sedang dia cek tekanan darahnya. Aruna terdengar sedang memberikan anjuran dan saran kesehatan saat menggenggam sekilas tanganku ketika aku akan beralih ke meja lain. Tangannya terasa dingin.
Setelah merekam keseluruhan rangkaian acara yang menghabiskan waktu kurang lebih tiga jam, aku pulang meninggalkan pelataran parkiran saat matahari sudah mulai tidak terang. Bu Sarah membungkuskan makanan karena aku menolak untuk hadir pada acara makan malam yang telah dia siapkan bersama Aruna, Andre dan Pak Purwa. Saat menyerahkan bungkusan itu, sekali lagi Bu Sarah memintaku untuk mempertimbangkan mengenai desain undangan. Aku dengan tegas menolak tanpa mengatakan alasan apapun. Bu Sarah tampak menerima dengan senyum yang aku tahu pura-pura. Saat aku berpamitan dan menolak ajakan makan malam bersama, Aruna hanya berdiri dari kejauhan dengan tatapan berat. Andre datang menepuk pundaknya dan mengajak ke meja dengan makanan yang sedang dihidangkan oleh beberapa gadis muda. Aku yang melihatnya lantas segera ingin pergi dari sana.
Langit sudah benar-benar pekat saat aku sampai di Jakarta. Pak Yahya masih duduk-duduk bersama beberapa tetangga. Aku menyapa seperlunya saja lalu setengah berlari menuju kamar. Menguncinya, meletakkan ransel pada meja dan segera menuju kamar mandi, menyalakan kran wastafel, menampung air dengan tangan, membasuh wajahku dengan kasar hingga ke leher belakang. Aku mengangkat wajah, melihat bayangan diri sendiri pada cermin, nyaris seluruh rambutku basah. Tetesan air dari rambut jatuh di bahu, membasahi flanel dan kaos. Semakin kuyup sudah dan memberikan kesan sedih yang berlebihan. Aku meraih handuk, mengusap wajah dan mengeringkan rambut, lalu menatap lagi pantulan diriku di cermin. Ternyata penampilan menyedihkan itu tidak jauh berkurang karena sumber sedihnya bukan pada kuyup basah, melainkan dari dalam hati yang memancar hingga ke wajah. Aku memejamkan mata, menghirup udara sebanyak-banyaknya.
Aku keluar, mengganti pakaian, menuangkan air ke dalam teko, dan menyalakannya. Menjelang air mendidih, aku merokok melihat langit yang berwarna kehitaman, mendung. Tidak ada bintang, bulan juga tampak samar bersinar.
“Aku kangen.” Itu kata pertama yang keluar dari mulut Aruna saat aku membukakan pintu. Dia mengetuk saat aku tengah mengerjakan sesuatu pada tablet. Kata kangen itu tidak membuatku senang sama sekali, tidak juga membuat tenang perasaanku yang sedang kacau. Aku membawanya masuk. Lalu kembali duduk melanjutkan pekerjaan. Aruna mengikuti, dia menempelkan jarinya –kecuali kelingking dan jempol—pada cangkir kopi di atas meja. Dia selalu begitu untuk memastikan apakah aku minum kopi masih hangat dan akan membuang kopi itu jika sudah dingin lalu kembali dengan kopi baru dengan asap mengepul.
“Makanan dari Bu Sarah udah dimakan belum? Mau makan bareng?” tanya Aruna lagi. Nadanya merayu. Aku tidak menjawab bahkan tidak menoleh padanya yang kini duduk di sofa.
“Gam? Kamu lagi kerjain apa?”tanya Aruna.
Aku berdiri dan tersenyum padanya sambil membawa tablet itu, menunjukkan apa yang aku kerjakan.
“Menurut kamu, bagus yang pertama atau yang kedua?” tanyaku sambil menggeser layar tablet berkali-kali. Dia melihatnya dan kemudian matanya terbelalak. “Gam ..., aku bakal jelasin.” Suara Aruna bergetar setelah melihat dua desain undangan pernikahan yang sengaja aku buat dengan template yang sudah ada. Entah atas dorongan apa, aku ingin memperlihatkan keteguhan dengan berpura-pura ikut serta dalam memeriahkan acara pernikahannya. Dia berdiri dan mengusap pipiku. Untuk pertama kali selama dua tahun ini, aku menghindar. Aruna terkejut saat aku dengan reflek menjauhkan wajah.
“Kamu memang berhutang penjelasan,” kataku.
Wajah Aruna mulai tegang. Dia menatapku lamat-lamat. Bibirnya yang bergerak ragu itu akhirnya hanya dia katup rapat. Setelah menunggu beberapa saat dia duduk lemas di sofa tanpa mengatakan apa-apa.
Aku kembali duduk di kursi kerja, memangku tanganku di atas perut, tidak memalingkan tatapan kemanapun selain kepada matanya cokelatnya yang kini tampak sendu, menantinya mengatakan sesuatu. Siap tidak siap, aku harus mendengar penjelasan yang masuk akal.
“Gam …,” Suara Aruna terdengar lebih tebal dari biasanya.
“Hm?”
“Sampai dua tahun lalu hidup aku datar aja. Aku gak punya keinginan apa-apa dalam hidup selain tetap hidup. Aku bersedia menjalankan cita-cita orang lain. Aku monoton.” Sepanjang kalimat selain bibirnya yang bergetar hebat, suaranya juga tercekat. Dia tampak sangat berusaha membuat kalimatnya terdengar jelas olehku walau beberapa kali suaranya nyaris tidak terdengar. “Aku gak tahu kalau hidup bisa terasa begitu mendebarkan sebelum-”
“Ketemu aku. Gitu?” timpalku segera. Kami bahkan mengucapkan kalimat itu nyaris bersamaan, namun suaranya lindap sebab suaraku lebih berat.
“Ya.” Aruna mengusap kasar kedua pipinya dan meninggalkan bekas kemerahan.
“Barangkali kamu cuma butuh gemparan untuk hidup kamu yang monoton. Kamu cuma butuh hiburan untuk hidup kamu yang datar. Kamu gunakan perasaan aku untuk seru-seruan, untuk kesenangan, sebelum akhirnya kamu kembali ke jalur yang udah pasti menjanjikan.” Kata demi kata meluncur begitu saja. Bahkan aku mengatakannya dengan cepat nyaris tanpa jeda.
Aruna menggeleng-geleng cepat, “Kamu tahu persis aku gak gitu.”
Aku bersandar dengan lemah, menarik napas dalam-dalam, “Gimana rasanya, Runa? Apa selama ini cukup menghibur? Apa udah cukup menyenangkan?”
“Gamma! Kamu gak paham apa-apa!” Aruna nyaris berteriak.
“TENTU!” Jawabku dengan nada tinggi sambil berdiri, aku bahkan sampai memukul lengan kursi. Aruna tersentak. Aku melihat kilatan mata yang ketakutan. Melihatnya begitu, aku langsung duduk kembali, berusaha mengatur emosi. “Tentu, Runa. Jelas aku gak paham. Kenapa aku dibiarkan gak tahu sendirian? Saat ini rasanya aku tiba-tiba dibangunkan dari mimpi. Dikagetkan. Dipaksa sadar diluar keinginan!”
Pada saat itulah air mata Aruna runtuh, dia mengepalkan kedua tangan di atas paha sambil menahan deru tangis. Bahunya naik-turun dengan cepat sedang badannya bergetar. Dia berkata maaf berkali-kali dan menunduk, sesekali menyeka air mata dengan bahunya.
“Bu Sarah tahu, Gam …,” katanya sambil tersedu.
“Apa? Tahu apa?”
Aruna menatapku ragu-ragu, “Desember lalu, gak lama setelah hari jadi kita …,” Aruna berhenti sebentar, sepertinya kata ‘hari jadi’ itu membuat perasaannya semakin kacau, dia membungkus lebih erat tubuhnya dengan jaket jeans yang belum dia lepaskan sejak datang, “kami sedang membicarakan, yaah… semacam alat-alat kesehatan yang akan dibeli Bu Sarah untuk klinik. Sebelum telepon itu berakhir, aku katakan aku akan ke Tangerang akhir tahun. Aku dan Andre. Kami akan membahas masalah pernikahan. Sepertinya kami tidak bisa menikah. Aku sampaikan begitu ke Bu Sarah.”
Ingin aku katakan pada Aruna bahwa aku tidak suka nama Andre keluar dari mulutnya, rasanya aku bisa gila. Tapi mau bagaimana? Kami tidak sempat menjulukinya seperti Reza si Culun.
“Itu yang jadi pertanyaan aku. Bukannya Andre tahu hubungan kita?”
“Tahu,” Aruna mengangguk, “bahkan dia orang pertama yang aku hubungi mengabarkan aku sudah punya pacar. Sejak awal, bahkan jauh sebelum ketemu kamu, kami sama-sama tahu kalau kami gak bisa menikah.”
“Kenapa? Apa?”
Aruna menarik napas, dia memijat-mijat pelipisnya sambil tertunduk, “Ada sesuatu. Andre punya alasan sendiri,” lalu memandangku beberapa saat, wajahnya terlihat kosong. Kemudian dia menelan ludahnya dan berkata lemah, “Anggaplah begini, dia punya alasan tersendiri dan aku sekarang punya kamu.”
“Kenapa kamu gak pernah ngomong apa-apa masalah ini ke aku?” tanyaku dengan putus asa, “Andre ini pernah kita bahas pas makan malam pulang dari Bogor, ingat?”
Aruna mengangguk, masih terisak, “Aku mudah kepikiran banyak hal, Gam. Apalagi yang mengganggu perasaan. Aku seringkali ingin menyelesaikan masalah, tapi malah berakhir kecewa. Aku takut saat itu, kamu bisa aja marah dan akhirnya kita selesai.”
Aku diam beberapa saat, menatapnya, “Kamu selama ini megang bom waktu, Runa,” kataku kemudian.
“Aku selama ini nurut aja, Gam. Aku pikir karena masih lama jadinya terasa gak nyata. Lalu aku ketemu kamu, kita pacaran. Aku kira ini akan jadi lebih mudah karena akhirnya–seperti Andre, aku punya alasan sendiri untuk menolak,” dia menatapku dengan tatapan penuh rasa bersalah dan menggigit bibir bawahnya sebelum bicara lagi, “tapi ternyata aku salah. Justru semakin sulit setelah aku membawa kamu ke dalam masalah ini.”
“Jadi aku dibawa ke dalam masalah ini, dimasukkan ke dalam rencana kamu tapi tanpa bilang apa-apa ke aku?” tanyaku yang tiba-tiba teringat pesan yang dikirim Bu Sarah saat Aruna sakit.
Aruna menunduk, dia memain-mainkan ujung jaket jeans, “Aku panik karena waktu semakin dekat. Tapi aku gak berdaya untuk ngomong ke kamu, terlebih lagi saat studio kebakar. Lebih lagi Andre kayaknya belum mampu mengutarakan alasannya. Jadi aku mencoba mengulur waktu biar kamu selesai dulu masalah studio dan ngasih Andre waktu. Tapi ternyata benar, bom waktu yang aku pegang meledak bahkan masih dalam genggaman. Aku seharusnya gak boleh main-main sama waktu.”
“Dan aku.” kataku cepat.
Wajah Aruna tampak benar-benar basah oleh air mata. Sorot matanya menyiratkan perasaan bersalah yang besar.
Aku mengacak-acak rambut. Aku sangat marah tapi juga merasa merana di saat yang sama. Aku memalingkan wajah keluar jendela, walaupun hanya terlihat pantulan cahaya lampu saja, aku menghibur hatiku seolah sedang melihat pemandangan luar biasa.
“Gam? Aku cuma pengen kita baik-baik aja.” Ujar Aruna kemudian.
Dadaku terasa nyeri. Sepertinya aku menangis dalam hati.
Bagaimana mungkin semuanya akan baik-baik saja setelah ini?
Ponselku berdering, tidak kuhiraukan. Siapa lagi yang akan menelepon pada malam begini? Tidak mungkin pekerjaan. Lalu setelah deringan itu berhenti, nada tanda pesan masuk berbunyi. Aku meraih handphone, mengetuk layarnya. Ares, orang yang menelpon dan juga mengirimkan pesan. Aku tidak membuka pesan itu, hanya membaca potongan kalimat pertama Ares tentang wallpaper dinding yang dimintanya. Lalu meletakkan handphone lagi di atas meja.
Aku kembali menatap Aruna dengan wajah tertekuk duduk di sofa. Dia bahkan tidak menyandarkan punggung, seperti seorang terdakwa yang sedang tegang menunggu vonisnya dibacakan.
“Runa, hingga tiga jam lalu aku menyesal udah pergi ke Tangerang. Tapi setelah aku pikir-pikir ulang, sepertinya itu bukan hal yang seharusnya aku sesalkan, mungkin juga jadi salah satu keputusan terbaik mengambil pekerjaan itu.”
Aruna mendongak menatapku.
“Kamu tahu? Awalnya aku pengen buat kejutan ke kamu. Tanpa kamu tahu aku di sana juga dan kita bekerja pada satu acara yang sama. Sepanjang jalan aku berdebar kegirangan. Nyatanya, situasi terbalik. Aku terkejut setengah mati sampai di jalan pulang aku gak bisa gak kepikiran.” Kataku lagi, mataku mulai terasa panas.
“Gam …,” Aruna menggeleng khawatir. Dia membuka mulut untuk berbicara tapi aku mengangkat tangan untuk menghentikannya.
Dia diam dan kembali membungkus tubuhnya lebih erat dengan jaket jeans.
“Aku bisa aja mati berdiri kalau tiba-tiba kamu kasih undangan pernikahan seminggu sebelumnya. Karena tampaknya juga kamu gak bakalan ngomong apa-apa. Kalau gak ada kejadian hari ini, kalau bukan dari mulut Bu Sarah, aku masih mikir ada kita di masa depan.” Kegetiran merambati suaraku.
Alis Aruna terangkat tinggi saat aku menyelesaikan kalimat terakhir. Bola matanya yang membesar itu bergerak pendek-pendek dan cepat menatap kedua mataku seolah sedang mencari jawaban.
“Gam …, aku sedang berbicara dengan Bu Sarah tentang kita. Percayalah.” Aruna mencoba meyakinkan, namun bagiku terdengar sebagai bujukan murahan, rayuan basi dan janji kosong.
“Kamu minta aku percaya setelah dibohongi selama dua tahun?”
“Aku bukan bohong, aku cuma gak ngomong.”
“Buatku sama aja. Sama-sama menyakitkan.” Aku menyela cepat.
“Aku sedang mencoba un—”
“Mencoba?” Aku tersenyum pahit dan berdiri segera, “Aku tahu sekarang, aku jadi objek percobaan. Kalau gagal bisa dicampakkan. Toh bagaimana juga akan ada penggantinya, ya, kan?!” Aku yang gagal mengendalikan diri kini sedang menghampirinya dengan luapan kemarahan, “Saat kamu uji coba, aku dengan naifnya mencintai sungguh-sungguh! Aku dengan bodohnya percaya bahwa ada kita di masa depan. Kamu tahu, kan! Kamu tahu gak pernah sekalipun aku mikir untuk coba-coba! Didn’t I really try?” Dia bangkit, mencengkeram erat pangkal lenganku, menahanku yang terus mendesaknya. Tangan itu, tangan mungil itu, bergetar dengan telapak terasa dingin. Atau mungkin suhu tubuhku yang sedang naik karena darah berdesir lebih kencang dari biasanya. Dia tersedu, menggeleng dengan raut cemas, menatapku setengah takut setengah khawatir. Kesedihan luar biasa terpancar dari sepasang mata cokelat Aruna. Bagiku, dan selalu, mata itu bagai lautan yang mampu menenggelamkan. Kini aku berusaha menghindari tatapannya sebab aku khawatir tidak mampu berenang ke permukaan untuk menghadapi kenyataan. Bahaya. Aku tidak ingin tenggelam. Aku buru-buru menunduk, “Habislah aku, Runa,” kataku pelan, “aku pikir kita memiliki mimpi yang sama.” Bibirku bergetar mengatakan kalimat itu. Aku tidak sadar sedang meneteskan air mata sampai Aruna menyeka pipiku.
Aruna menarik napas di sela-sela isakannya, “Kita memang memiliki mimpi yang sama.”
“Sebulan lagi kamu menikah,” kataku memegang kedua lengannya, mendorongnya pelan agar menjauhiku. Cengkramannya yang kuat kini terlepas lemah. Aku meraih ransel, memasukkan kamera, tripod, tablet dan laptop. Aku tidak tahu kenapa, tanganku seperti sudah memiliki jiwa tersendiri, bergerak begitu saja.
“Aku gak tahu lagi siapa yang kamu anggap kekasih. Sejak siang tadi aku juga gak tahu siapa aku bagimu.” Aku melewati Aruna yang kepalanya bergerak-gerak melihat arah berjalanku. Aku mengambil flanel yang tergantung pada sebalik pintu. Mengenakannya.
“Kamu mau kemana?” tanyanya cemas.
“Aku gak bisa di sini. Aku butuh waktu sendiri.” Kataku sambil menyandang ransel dan mengenakan slip-on.
“Gam?” dia menyergap pergelangan tanganku sambil menggeleng seolah mengatakan jangan begitu. Sorot matanya sungguh mengisyaratkan kesusahan hati. Mungkin jawabanku setelah ini terdengar defensif dan menyakiti perasaannya. Tapi pada saat ini, aku rasa aku berhak marah dengan mata terbuka. “Harga diriku di sini,” ucapku sambil mengangkat tangan tinggi, “jauh di atas kepalaku. Lebih tinggi dari kepala.”
Isakan Aruna terdengar kembali. “Kamu bilang Bu Sarah tahu hubungan kita, jadi aku rasa tadi siang dia bukan sedang memberitakan pernikahan tapi sedang mengejekku, menghina dan menginjak-injak apa yang aku pertahankan tetap tinggi selama ini. Harga diri.” Aku berhenti sebelum melewatinya untuk keluar, sebelah tanganku memegang pipinya, jempol mulai mengusap-usap bekas air matanya, “Pikiranku sedang keruh, Runa. Aku bisa aja keliru kalau hanya mengikuti perasaan. Kali ini, biarkan aku sendiri mikirin masalah ini.”
“Gam … Please?” Aruna memohon. Dia bahkan menarik lenganku.
Aku menggeleng, “Aku ini laki-laki. Aku akan mengambil keputusan sebelum orang lain melakukannya untukku.” Perlahan aku melepas pagutan tangannya. Saat dia hendak mengatakan sesuatu, aku sudah memalingkan badan dan melangkah besar-besar untuk segera menuruni anak tangga. Aku menahan diri sekuat hati untuk tidak menoleh ke belakang saat mendengar tangisnya terpecah lemah. Kejadiannya begitu cepat hingga aku sudah sampai di parkiran. Ares datang saat motorku sudah menyala.
“Woi! Telpon gua gak diangkat! Mau kemana lu?” katanya memarkirkan motor. Aku diam saja.
“Wallpaper, wallpaper!” ujarnya. Dia yang sejak dua hari lalu sudah menemukan ke kost baru, meminta dua gulung wallpaper yang tidak pernah aku pakai.
“Di bawah kasur.” Jawabku singkat.
“Mau kemana?”
Aku kembali diam.
“Eh! Ntar kalau udah, susulin gua di kost, ya!” Suara Ares tergilas knalpot motorku yang mengerang. Aku mengangguk dan pergi.
Lalu lintas ramai sebab akhir pekan. Saat kepalaku tidak terpikirkan akan kemana, tanganku –yang lagi-lagi seperti memiliki jiwa–justru membawa motor ini parkir di ruko bekas studio. Aku menghela napas lemah saat melihat ruko itu kini beralih menjadi PKBM. Pandanganku menyeberangi jalan dan melihat kedai minuman dengan mbak penjual yang sibuk membersihkan etalase.
“Eh! Orang lama muncul …,” candanya sambil tersenyum lebar melihatku datang.
Aku duduk, “Mana yang lain, Mbak?” tanyaku melihat kursi kosong.
“Pada sibuk ngebawa penumpang kali. Gak tahu juga. Minum apa, Mas?”
“Es kelapa aja.”
“Abis.”
Aku memandangi deretan minuman sachet yang bergelantungan, mataku menyisir satu-satu dan berhenti pada bungkus minuman berwarna merah muda.
“Yang pink itu apa?”
“Ini?” Mbak penjual memegang bungkus sachet yang aku tunjuk.
“Iya.”
“Ini?” tanyanya ragu.
“Iya, Mbak. Iya.”
“Strawberry. Ini ya?
“Iya. Astaga …”
“Yakin? Gak boleh ganti loh kalau ini udah saya gunting.”
“Iya iya sip!”
“Yaa saya mastiin, tho.” ucapnya setengah merungut.
Suara mesin blender menderu-deru menghaluskan es saat mbak ini menanyakan sesuatu yang membuatnya tak terdengar jelas. Hanya kata ‘Aruna’ saja yang terdengar olehku.
“Ya, Mas?” katanya lagi dan menoleh padaku saat deru mesin itu sudah berhenti.
“Gimana?” tanyaku memastikan.
“Ini minuman yang sering dipesan Mbak Aruna. Apa mau dibungkus bawa pulang?” tanyanya lagi.
Aku tersentak, “O-oh, ya? Enggak. Mau diminum sekarang aja.”
“Oalah! Tumben banget minum pink!” Celetukan Mbak ini membuatku menatap lama minuman yang aku genggam. Memikirkan kenapa tindakanku sungguh simbolis. Aruna dan minuman merah muda. Lantas aku menertawakan diri sendiri.
“Tuh! Studionya udah ganti jadi tempat kursus loh, Mas.” Seloroh Mbak penjual minuman.
“Iya, baguslah daripada kosong.”
“Loh? Gak sedih apa?”
“Sedihnya udah lewat, Mbak. Lagian juga kelihatannya ruko ini lebih terang sekarang. Lebih hidup.”
Aku tersentak, terkejut karena apa yang meluncur dari mulutku tanpa sadar.
Aku memikirkan Aruna, bisa saja dia jauh lebih baik jika bersama Andre. Bisa saja dia jauh lebih bersinar. Dia akan menikah dengan sahabat baiknya, Andre juga tampaknya mapan dan Aruna akan bekerja di tempat yang baik sesuai potensinya. Dia juga akan dekat dengan ibu sambungnya. Sama sekali tidak ada celah buruk yang aku dapati selain alasan klise: tidak cinta.
Handphone-ku berdering singkat. Pesan dari Ares berisikan alamat kost-nya. Lalu karena sedari tadi aku tidak memeriksa handphone, aku mencoba mengalihkan pikiran dengan membuka notifikasi satu per satu. Pesan dari kakaknya Fahmi, pesan dari Marwa yang dia kirim berkali-kali hanya untuk menanyakan merk kamera polaroid yang bagus, lalu satu e-mail yang membuatku semakin ditelan harapan. Aku tidak lulus seleksi perekrutan pegawai BUMN.
Aku mendesah lemah.
Saat ini rasanya seluruh isi bumi bertolak belakang dengan impian dan harapanku.
Aku membayar minuman dan pergi meninggalkan es merah mudah yang masih tersisa banyak menuju kost Ares.
-oOo-
“Lu ada masalah apa sama Aruna?” itu kalimat pertama Ares saat aku masuk ke kost-nya yang ternyata sebuah rumah kontrakan kecil di dalam gang. Lebih kecil dari rumah Cak Son. Hanya memiliki satu kamar, satu kamar mandi, dapur seadanya dan ruang tamu mungil.
Aku menggeser-geser kardus dengan kaki untuk duduk,“Gak mungkin lu main cewek, kan?” Ares yang sedang membersihkan dinding dengan kain lap menoleh ke belakang, ke arahku. Cengar-cengir.
Aku berdecak kesal.
“Pas gua nyampe kamar lu, gua kaget. Aruna duduk di sofa. Nangis. Gua ragu masuk. Tapi dia buru-buru berdiri, nyamperin gua. Dia bilang suruh nyari lu. Ada apa, sih?” tanya Ares lagi dengan dahi mengerut.
Aku mengangkat tangan melihat arloji, sudah jam setengah sepuluh. Apa Aruna gak berangkat kerja?
“Nyet! Lu apain anak orang? Diem aja dari tadi!” desak Ares.
Aku menghela napas sebelum menceritakan secara singkat apa yang Ares ingin dengar. Sepanjang cerita Ares menganga, terlebih saat mendengar Aruna akan menikah dalam waktu sebulan, matanya berkedip-kedip tak percaya. Untuk beberapa saat dia mematung berdiri membelakangi dinding yang tadi dibersihkannya. Kemudian dia melempar ke sembarang sisi kain lap yang dipegangnya dan menghampiriku, duduk disampingku dan terus mendengarkan dengan ekspresi iba. Dia merogoh-rogoh rokok dari kantong celana pendeknya dan menawarkan padaku. Aku mengambilnya, dia memantikkan api untuk rokok yang sudah terjepit diantara bibirku. Kami merokok bersama. Aku melanjutkan cerita diantara kepulan-kepulan asap.
“Jadi gimana? Lu pertahanin apa lepasin?” tanya Ares setelah ceritaku selesai.
“Itu dia. Gua mau mikirin gimana baiknya.” Aku menekan-nekan puntung rokok ke asbak. Bukan asbak sebenarnya, hanya sebuah cangkir kecil yang Ares gunakan sembarangan.
Ares berdiri, berjalan menuju satu kardus di sudut ruangan dan kembali membawa dua kaleng bir, “Nih! Minum dulu. Kebetulan gak ada air putih!” katanya sambil menyodorkan kaleng berwarna hijau itu.
Aku tersenyum pasrah.
“Bir itu minuman terbaik buat laki-laki patah hati!” Ujar Ares berseloroh. Aku menelan bir yang bahkan sudah tidak ada rasanya lagi di lidahku. Hambar. Suasana di sekitarku mendadak terasa pucat seluruhnya. “Ternyata pepatah bilang, ‘apa yang kau tanam akan kau tuai’ itu gak sepenuhnya benar,” ujar Ares lagi berkesah.
“Yah, mungkin karena gua menanam di tanah yang salah. Tanah yang sejak awal bukan punya gua.”
“Tapi tanamannya tumbuh baik pas sama lu, kan? Bisa aja lu angkut tanamannya, lu pindahin ke tanah lu sendiri.”
Belum sempat aku menjawab, tiba-tiba handphone-ku berdering. Pesan dari Tyas, menanyakan apakah aku lulus tahap seleksi pekerjaan yang kami incar bersama. Aku tertawa getir,“Tanah gua gersang, Res. Gua belum bisa janjiin dia tumbuh baik. Kemungkinannya fifty-fifty, tumbuh subur atau justru layu.”
Ares meremas botol birnya hingga remuk, dia diam sebentar sebelum menatapku dengan sorot mata bersalah,“Maafin gua. Mungkin kalau studio masih ada, lu bisa aj-”
“Udahlah …,” ucapku lemah, dan berharap dia tidak lagi membahasnya.
“Yah, gitu lah kira-kira.” Dia menepuk bahuku.
Kami duduk cukup lama, tidak ada lagi obrolan. Ares kembali mengerjakan dindingnya setelah menghabiskan satu kaleng bir lagi.
Aku duduk bersedekap, memandang nanar dinding yang sedang Ares kuas lem untuk dipasangi wallpaper. Jam dinding bulat besar dengan bingkai hitam bersandar di antara tumpukan kardus-kardus menunjukkan pukul sepuluh lewat. Aku duduk terdiam. Ingatan-ingatan pertengkaranku dengan Aruna susah dihilangkan. Tenggorokanku perih menahan sedih. Hatiku sudah bukan lagi remuk, tetapi koyak. Sobek. Hancur.
Ares melongok padaku sebentar, dia menggelengkan kepala dengan resah. Aku tidak bereaksi apapun. Tetap diam, memeluk lututku di lantai marmer putih yang dinginnya menjalar hingga tulang punggung. Dan terdengar berlebihan tapi memang benar, seluruh dingin yang merayap itu berhulu pada jantung, dingin dan membeku.
“Lu mau di sini? Gak balik? Gak cek kondisi Aruna?” Suara kibasan wallpaper yang kuat terdengar di antara suara Ares yang bernada prihatin.
Aku diam saja. Kejadian hari ini sungguh mengguncang sehingga masih sulit untuk dicerna kepala.
Tidak lama terdengar lagu yang sepertinya sengaja Ares pilih entah untuk mengejekku atau justru mendukung. Aku tidak tahu.
Aku mendongak dan mengernyit padanya saat mendengar lirik pertama lagu itu sudah benar-benar menyindir.
“Nikmatilah proses katarsis ini, Bung!” kata Ares kemudian. Senyum semringah terkembang pada wajahnya yang kini sudah tidak kumal. Dia sudah berpenampilan seperti Ares yang sebenarnya.
“Taik!” seruku sambil melemparnya dengan kain lap.
Ares menghindar dan tawanya menggema di ruangan yang masih kosong dan berantakan.
Lagu yang dibawakan oleh band indie asal Inggris ini terus melantun. Liriknya menceritakan tentang kerentanan dalam cinta. Aku diam-diam menyimak lagu ini. Benar kata Ares, aku mengalami katarsis. Aku merasa mendapatkan sokongan, suaraku diwakilkan, emosiku tersalurkan oleh lagu ini. Begitu lagu itu selesai, aku bertanya pada diri sendiri. Haruskah aku melepas Aruna? Oh, bukan. Lebih tepatnya bisakah aku melepas Aruna?
(Bersambung)
Restart ©2023 HelloHayden


 hellohayden
hellohayden



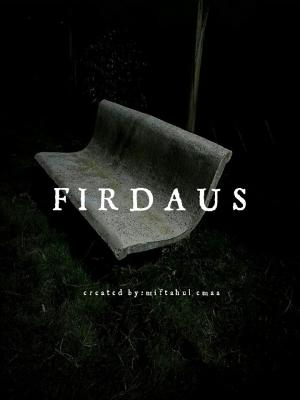


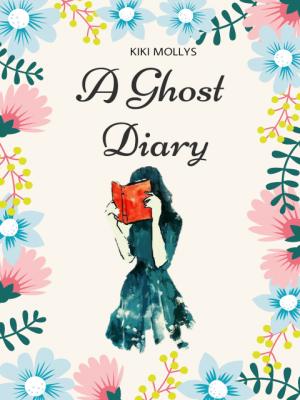






Baca cerita ini udah kayak masuk ke kedai all you can eat. Daging semua. Sbg cowok baca ini gk merasa aneh sama sekali untuk crita roman dan rasa kembali ke masa kuliah. Mantap lah
Comment on chapter Bab 14 (Cukup)