Aku, Aruna dan Ares sedang berada di ballroom salah satu hotel mewah di Jakarta, tengah menikmati bermacam lukisan pada festival seni rupa. Handphone Ares berdering, salah satu klien kami –yang baru saja tadi siang membuat MoU, membatalkan perjanjian kerjasama sebab mendadak membutuhkan uang untuk membantu saudaranya di Lombok yang baru saja dilanda bencana gempa.
“Gempanya jam delapan WITA. Berarti baru aja,” ucap Ares setelah menutup telepon dan kini melihat arlojinya. Aku cukup terkejut, sebab akhir Juli lalu sudah terjadi gempa di daerah yang sama, kini berjarak kurang dari seminggu, gempa itu datang lagi dengan magnitudo lebih tinggi.
“Duh, kasihan,” aku berkomentar dengan suara pelan, “Simpan lagi aja produknya biar besok dia tinggal ambil,” ujarku pada Ares.
Ares diam, lalu tersenyum kikuk sambil menggaruk-garuk alisnya, “Tapi tadi udah gua cobain satu,” ujarnya cengar-cengir, dia memakan produk cumi kering pedas buatan rumahan milik klien.
Aku berdecak, “Ya lu ganti deh, ntar!” sambil memukul kepalanya pelan.
Lalu kami bergabung pada program art talk dan mendapati banyak wajah yang kami kenal duduk di sekitar, baik pengajar di kampus maupun teman-teman serta seniman terkenal di negara ini. Tiba-tiba Trisna menghampiri, dia datang bersama Voni yang terlihat malas-malasan bertemu kami dan banyak membuang wajah saat Trisna sedikit-sedikit berbalas kata dengan Ares.
“Dih? Padahal dia yang dulu datengin kita, minta api, duduk bareng, udah gitu narik-narik rambut gua segala! Tengik!” bisik Ares kesal saat mereka menjauh. Lalu entah bagaimana, Aruna akan duduk bersama mereka. Saat mereka beranjak pergi, aku menahan Aruna sebentar, mengerlingkan mata pada Voni dan menggeleng kecil dengan cepat, Aruna memahami bahwa itu isyarat padanya untuk tidak terlalu dekat dengan Voni, sebagai jawaban Aruna mengangguk pelan. Mereka duduk dua baris di depan, sedang aku, Ares dan teman laki-laki lain duduk dalam satu baris, termasuk Galih dan Fahmi. Aruna sesekali menoleh ke belakang, melihatku yang mendengarkan diskusi ini dengan khidmat.
Diskusi berjudul Seni Rupa, Teknologi dan Budaya Populer sangat menarik, terlebih disampaikan oleh narasumber yang kompeten. Malah sejujurnya, suatu saat aku ingin duduk di panggung itu sebagai narasumber juga. Tahu-tahu aku tersenyum membayangkannya lalu surut seketika saat Ares melihatku dengan tatapan heran. “Dih? Ngapa lu senyum sendiri?” tanyanya menaikan satu alis tinggi. Aku menggeleng.
Pulang dari festival itu, entah karena akhir-akhir ini aku telah mengisi materi pada seminar kreatif atau memang karena dorongan hati nurani, hingga azan subuh berkumandang alih-alih tidur, aku justru menjelajahi website jurnal-jurnal ilmiah untuk mempelajari modernisasi seni seturut berkembangnya teknologi. Dengan iseng aku mencatat keinginan yang masih aku anggap angan-angan itu pada buku bersampul cokelat: menjadi praktisi pada event seni.
Karena masih semangat, beberapa minggu setelahnya, aku mengajak Aruna mendatangi sebuah pameran fotografi di Bentara Budaya. Setiap kali datang ke pameran seni Aruna senang sekali. Dia bertanya bagaimana cara mengambil foto seperti yang dipamerkan. Walau aku tahu Aruna tidak akan mengingat detailnya, namun semangatku dalam menjelaskan tetap sama setiap kali dia bertanya.
“Suatu saat, karya kamu bakalan terpampang di sini.” Ujar Aruna.
Aku tersenyum saja, bukan hal mudah agar hasil foto bisa masuk dalam pameran seperti ini. Banyak tahapan seleksi, belum lagi tim kurator yang akan saling memperdebatkan kelayakan suatu karya untuk dipamerkan.
“Kalau itu kejadian berarti kamu pendorongnya, kayak yang udah-udah,” jawabku.
“Tapi kamu kan suka foto.” Aruna memandangku segera.
“Ya. Tapi kurang suka memamerkannya,” jawabku segera. Kami kembali berpindah untuk melihat satu foto architectural street photography suasana malam hari. “Lagipula untuk sampai ke sini, aku mesti belajar banyak lagi.” Ujarku menunjuk foto itu. Aruna tersenyum, “Kamu gak perlu banyak belajar,” dia menatapku sambil mengusap lembut pelan lenganku, “Kamu hanya perlu membidik subjek dengan perasaan.” Dia mengatakan itu dengan penuh keyakinan, seolah percaya beberapa tahun kemudian aku bisa berdiri di sini bukan sebagai pengunjung lagi, tetapi sebagai salah satu tamu kehormatan, seniman yang berkontribusi.
Dia dengan tulus mengungkapkan pendapatnya dan memberikan motivasi terhadap minat yang aku selami. Dia tidak setengah hati dalam memahami. Kini, di bawah lampu sorot putih, dengan kulitnya yang cerah, bibir merah dan rambut hitam berkilau indah, dia tampak seperti ibu peri dalam film animasi, kurang sayap bulu putih saja. Tiba-tiba aku teringat cincin permata putih yang aku beli. Bisa saja aku memberikan cincin itu saat ini andaikata aku membawanya.
Ah! Pantai lebih baik.
Pikirku kemudian.
Aruna membalas tatapanku dengan heran,“Apa?” katanya. Sudah lama aku tidak mendengar komentar seperti itu.
“Gak ada. Gak kenapa-napa.”
Aku merangkulnya dan kami berkeliling sedikit lagi sebelum akhirnya keluar untuk makan malam di restoran sekitar. Dia melangkah riang dengan tangannya aku genggam masuk ke dalam jaket hoodie, sedikit lebih lama berada di sini maka kami akan membeku, dingin.
“Sebelah lagi masukin ke saku jaket kamu,” ucapku. Dia gadis yang penurut, tangannya segera diselipkan ke saku jaket jeans yang sudah menjadi miliknya selama satu setengah tahun terakhir.
Akhir bulan Juli lalu kami mendapatkan kabar dari Tyas bahwa Trisna bergabung dalam tim desainer untuk merchandise resmi Asian Games. Tahun ini Indonesia menjadi tuan rumah untuk perhelatan pesta olahraga terbesar Asia dengan dua kota berbeda; Palembang dan Jakarta. Trisna yang memang sudah jarang terlihat, kini sibuk dengan tugas negara, tidak mengangkat telepon sama sekali saat aku lagi-lagi meminta bantuannya membuat copywriting.
“Tanya Tyas, deh! Bisa kali dia. Kan anak IKOM.”
Usulan Ares aku terima dan segera menghubungi Tyas yang sudah kembali ke Jakarta sejak wisuda awal Juli.
Dengan sangat memenuhi harapan, Tyas langsung datang dan mengerjakan copy sesuai materi. Hasilnya memuaskan. Dia juga menawarkan jasa voice talent jika suatu materi iklan membutuhkan narrator atau voice over. Gammares sangat beruntung mendapatkan teman baru yang percaya diri dan cekatan seperti Tyas.
“I'm free now, hit me up anytime and I'm down!” ujarnya di sela-sela bekerja.
Tim kreatif ini akhirnya terbentuk dengan format yang nyaris tetap. Aku, Ares dan Tyas. Lalu Pak Adimas sesekali berceloteh dengan semangat mengenai bantuan dana yang akan ia kucurkan. Dengan pengetahuan hukum bisnis dan tata kelola perusahaan yang dimilikinya, dia menjanjikan Gammares akan menjadi perusahaan agensi periklanan. Aku dan Ares awalnya hanya berbalas pandang dan tidak membahas lebih lanjut gagasan mengenai investasi Pak Adimas. Namun lama-kelamaan, seturut dengan seringnya berulang, celotehan itu akhirnya berubah menjadi desakan. Dua bulan terakhir, terlebih sejak Tyas menjadi tim kreatif di Gammares, Pak Adimas seolah merongrong kami untuk menerima gagasannya.
“Bukan apa-apa, Nyet! Ini mimpi kita. Dari awal Gammares ini dibangun atas keringat dan kerja keras kita. Gua males aja kalau harus berbagi kendali atas apa yang udah kita capai sampai hari ini. Lagian kita gak kekurangan modal.” Terdengar kemarahan dan kesedihan dalam nada bicara Ares. Aku pun merasakan hal yang sama. Namun bayang-bayang Gammares akan menjadi perusahaan periklanan besar juga tidak terelakkan. Sebab angan-angan besar itu pula, akhirnya aku membujuk Ares untuk mempelajari investasi. Kemudian pada suatu kesempatan, kami bertiga bersama Marwa sebagai konsultan finansial dadakan, dalam panggilan video menjelaskan bagaimana hubungan bisnis antara investor dan co-founder. Mulai dari tim manajemen, kebutuhan modal, kepemilikan dan struktur perusahaan, metrik dan tolak ukur, strategi akuisisi hingga resiko. Aku garuk-garuk kepala tak memahami, Ares mual hingga ingin muntah mendengar penjelasan Marwa. Marwa hanya tertawa setelah melihat wajah kami yang pucat pasi. “Yah, emang harus dipikirin semuanya. Meminimalisir resiko manajemen.” Tutup Marwa menyudahi penjelasan sebab Ares sudah menjambak rambutnya pertanda tidak sanggup berpikir keras lagi.
Setelah perbincangan yang menimbulkan pusing berkepanjangan, akhirnya demi kesehatan dan umur yang panjang, aku dan Ares bersepakat untuk menahan saja gempuran celotehan Pak Adimas tentang dana permodalan.
“Anggap angin lalu dulu, deh!” Kata Ares.
Sejak setelah lebaran Aruna juga makin terlihat riang. Mungkin karena akhirnya masa percobaan dua bulan akan selesai dan bisa berlanjut kontrak kerja enam bulan, mungkin juga sebab satu lubang besar pada hatinya telah tertutup sempurna –mengenai ayahnya, yang kini sesekali saling bertelepon menanyakan kabar. Setelah kunjungan terakhir, Pak Ari belum datang lagi, tapi beberapa kali dia mengirimkan Aruna bingkisan melalui jasa pengiriman. Isinya bermacam, satu waktu pakaian, terkadang alat tulis, sampai pernah mengirimkan kebutuhan sabun dan shampo. Beberapa diantaranya diselipkan uang saku. Aku ingat sekali Aruna menitikkan air mata melihat amplop itu pertama kali. Bahkan dia tidak membuka amplop itu hingga hari ini.
Ini aku anggap barang, sama seperti barang-barang lain yang ayah kirimkan, harus disimpan dengan benar, katanya.
Ayah dan anak ini bersepakat untuk merahasiakan pertemuan mereka dari Bu Sarah. Ngomong-ngomong Bu Sarah, Aruna mengatakan bahwa dalam waktu dekat klinik yang sedang dibangun Bu Sarah sejak tiga tahun belakangan akan mulai beroperasi secara resmi. Bu Sarah kini lebih sering bertelepon untuk menanyakan pendapat Aruna tentang alat-alat kesehatan. Setelah lebaran, Aruna hanya pernah satu kali pulang ke Tangerang, pada bulan Agustus, saat dia diberi libur Idul Adha.
Pagi ke malam aku sibuk di studio, bulan ini ada satu proyek yang cukup besar dari salah satu BPD. Aruna juga sibuk pada jam dinasnya yang memakan waktu kurang lebih tujuh jam sehari, tidak jarang saat aku tidur lelap dia sedang berjibaku di rumah sakit, mengabdikan diri. Walau begitu, akhir-akhir ini terasa menyenangkan. Saat Minggu, studio buka setengah hari, aku akan menjemput atau mengantar Aruna. Lalu jam-jam setelah atau sebelum dinasnya dimulai, kami menghabiskan waktu berdua. Kami ke Ancol, kami ke Mall, atau tempat-tempat lain yang ingin dikunjungi, tapi lebih sering menghabiskan waktu di kamar saja, menonton film, mendengar lagu sambil berjoget. Sesekali Aruna akan belajar menggunakan kamera, sebagai gantinya –yang aku tidak minta, dia mengajarkan keterampilan pertolongan pertama dasar, walau aku dengan malas-malasan mendengar dan mengikuti instruksinya.
“Basic first aid skill itu penting banget, tahu!” Aruna memukul pahaku saat aku mulai bosan dengan plester luka, alkohol, dan segala macam yang ada di kotak P3K miliknya.
Tidak jarang juga kami akan berada pada dapur umum lantai dua. Bu Dewi yang selepas Idul Fitri dibanjiri pesanan untuk arisan sekitar, bahkan hajatan kecil-kecilan meminta izin penghuni lantai dua untuk menggunakan dapur mereka, sebagai imbalan Bu Dewi akan memberikan hasil masakannya. Aruna sering diajak untuk membantu. Terlepas dari upah yang diterima, tentu dengan senang hati Aruna datang mengulurkan tangan kepada bahan-bahan makanan itu. Dia hanya melakukan pekerjaan kecil seperti memotong sayuran atau mencuci ikan, daging atau ayam. Sesekali ikut ke pasar jika tidak sedang dinas pagi. Aku juga akan hadir untuk membantu (baca: mencicipi) dan memotret kegiatan mereka untuk akun berjualan Bu Dewi jika mereka masih di sana saat aku pulang dari studio.
“Ciehh, jadi asisten koki!” aku berseloroh pada Aruna yang tengah sibuk mengiris daun bawang.
Aruna menimpali buru-buru, “Ciehh, food taster doang!”
Bu Dewi tertawa.
“Ini semua karena kamu, Gam. Hasil foto-foto kamu menggiurkan, jadinya pada pengen nyoba eh, keterusan!” Ujar Bu Dewi kemudian.
“Foto doang ya gak menjamin apa-apa, Bu. Tetap rasa makanan yang jadi penentu. Ini semua hasil nge-live konten masak ibu.” Ucapku jujur.
“Emang, ya. Apa-apa tuh di awal pasti bersusah payah dulu,” Ucap Bu Dewi, sesekali dia mencicipi kuah kari yang mengepul di dalam kuali.
“Iya, Bu. Gak sia-sia kemarin drop sampai dirawat,” aku mengulum senyum usil.
Dia segera menoleh dengan kecut, “Anak Bu Seruni ada-ada aja!” Ujarnya lagi sambil berdengus, setelahnya nyengir.
Sejak itu Ares ikut-ikutan mampir setiap Minggu dengan alasan bosan di rumah. Alih-alih berada di kamarku, Ares justru lebih sering melipir ke dapur lantai dua dan tugas mencicipi itu akan dilakukan oleh dua orang. Begitulah kira-kira grup memasak ini terbentuk dengan Ares sebagai personil cadangan.
Sarung tinju, sebagai hadiah iseng dulu, dengan alasan agar tidak alih fungsi menjadi dekorasi akhirnya digunakan sesuai tujuannya –melindungi diri. Kini Aruna belajar boxing dasar dimana aku adalah mentor sekaligus samsak tinju yang lama-kelamaan menjadi korban kekerasan. Berawal dengan mengikuti gerakan dari youtube, berakhir dengan aku dipukuli dan jatuh pasrah di lantai. Sudah beberapa kali berlatih dan aku yakin Aruna semakin mahir –dalam ukuran amatir, sebab pukulannya tidak main-main.
“Aku udah gak khawatir kamu pulang malam di godain abang-abang lagi,” ujarku terengah-engah, terkapar. Tanganku merentang lebar dengan kepala menengadah berusaha bernafas dengan mulut sebab udara yang dihirup melalui hidung tidak mencukupi kebutuhan paru-paru di saat nafas memburu.
Aruna tertawa puas.
“Tapi ingat, mukulnya ngira-ngira, jangan sampai mati juga abang-abangnya!” Candaan yang terdengar seperti peringatan itu lagi-lagi membuat Aruna membanggakan dirinya, dia tegak pinggang dengan dagu naik. Senyum kesombongan tampil pada wajahnya. Tawaku mulai berderai diantara helaan nafas.
Dia menghampiriku, lalu berada tepat di atas bertumpu dengan kedua lengannya. Entah sejak kapan tapi sarung tinju merah menyala itu tidak lagi menggulung kepalan Aruna. Dari bawah sini dia terlihat semakin indah, bahkan butiran keringat yang menempel pada dahinya membuat wajahnya berkilauan. Aku mengecup pergelangan tangannya yang tepat berada di sisi kiri kanan wajah secara bergantian. Lalu dia membisikkan kalimat jahil nan mesra sembari bibir lembutnya menyentuh pelan telinga. Cara itu selalu berhasil membuat bulu romaku meremang seluruh badan. Lalu aku merasa tergelitik karena bulu matanya yang panjang itu menyapu pipiku. Sesekali aku tergelak menerima perbuatannya yang menyenangkan sekaligus mendebarkan. Namanya juga dua manusia yang sedang terbuai cinta, usia dewasa muda pula, tentu kalian tahu bagaimana geloranya. Kami tidak berhenti sampai di sana. Kami saling menatap penuh kasih, saling memberikan sentuhan lembut dan saling mengecup. Pada kecupan tertentu Aruna mengeluarkan suara manja yang membuat darah berdesir lebih kencang daripada saat berlatih tinju bersamanya. Kami menikmati momen intimasi ini hingga aku pastikan kami berhenti pada titik yang kalian pikir akan kami lakukan. Walau sebenarnya keputusan berhenti itu tidak mudah bagiku, bersusah payah , harus kuat menggulung keinginan dengan niat besar.
–oOo–
Suatu sore di hari Rabu, terlihat dari balik pintu kaca tetesan air turun dari langit seperti sebuah jarum: tipis dan tajam. Aku dan Tyas sedang berdiskusi mengenai isi narasi sebuah iklan untuk produk minuman kemasan. Ares yang tengah mengambil materi minuman kemasan itu pada ruang kerja dengan segera bergabung bersama kami di sofa. Wajahnya terlihat gusar dan matanya tidak lepas dari layar ponsel seolah sedang menunggu pesan penting dari seseorang.
“Trisna di rawat. Tipes!” ujar Ares panik setelah mendapat balasan dari seseorang di layar ponselnya.
“Tahu dari siapa?” aku heran. Tyas yang jelas-jelas sepupu Trisna saja tidak mengatakan apa-apa. Justru Tyas tampaknya tidak kalah terkejut.
“Abangnya. Gua kan dulu minta tolong masalah anak-anak skateboard sama abangnya. Dia buat status WA.” jelas Ares, “Gua cabut, ya! Mau ke sana.” Ares berdiri dan segera mengambil helmnya di bawah meja reservasi.
“Ikut!” Tyas juga bangkit.
Lalu seolah tahu apa yang ingin aku katakan, Ares segera mencegah kata-kata itu keluar, “Lu di sini aja. Kali ada klien datang. Ntar gua kabarin gimana-gimananya.”
Aku mengangguk cepat dan diam saja melihat mereka bergegas menaiki motor menerima dengan rela jarum-jarum air menghujam tubuh demi Trisna.
Masalah lain muncul setelahnya. Ares yang kembali sendirian dengan lemas menceritakan kejadian di rumah sakit. Belum sempat Ares masuk ke kamar rawatan, dia sudah dicegat oleh abang Trisna, mengatakan bahwa Rian sedang di dalam bersama Trisna. Hanya Tyas yang dipersilahkan masuk. Lalu abang Trisna mengajak Ares untuk turun ke cafe kecil di lantai bawah. Tristan, abang Trisna menceritakan bahwa adiknya kelelahan selama hampir tiga bulan sebab selain mengerjakan proyek merchandise Asian Games dia juga bekerja sebagai digital marketer pada sebuah perusahaan pembiayaan. Lalu sudah empat hari demam tinggi dan nyaris pingsan saat dibawa ke rumah sakit. Kemudian wajah Ares masih menyisakan keterkejutannya saat dia bercerita bahwa Tristan mengetahui perkelahian antara dia dan Rian di bar.
“Terus?” tanyaku tak kalah penasaran.
“Tristan bilang, walau dia keberatan adiknya dipermainkan, tapi dia gak bisa mematahkan impian ayahnya yang ada di pundak Trisna, jadinya mereka bungkam. Gak cerita apa-apa ke orang tua.” Ares menghembuskan nafas melepaskan sesak dadanya.
Aku sebagai kakak dari adik perempuan juga merasa iba pada posisi Tristan. Sangat disayangkan jika dia merelakan adiknya suatu saat menerima perlakuan tidak menyenangkan demi menjaga martabat keluarga. Aku turut menghela nafas panjang sambil berdoa semoga Marwa dijauhkan dari hal-hal yang akan menyakitinya.
“Yah, masa gua menjenguk sebagai teman aja gak bisa?” Ares masih menyambung keluh kesahnya sambil mengacak-acak rambut yang sedikit basah.
Tidak lama, handphone Ares berdering, telepon dari Trisna.
Tadi, sepanjang bercerita, raut wajah temanku ini cenderung kuyu, tidak bersemangat. Tapi saat baru mendengar kata hallo saja dari Trisna, tebalnya mendung yang menyelimuti hatinya raib seketika. Mereka berbicara. Ares bersandar pada sofa, menengadahkan kepalanya menatap plafon. Dari pembicaraan yang terdengar satu arah, aku menangkap bahwa Tyas dan Tristan telah menyampaikan Ares sempat datang. Lalu sepertinya Trisna meminta maaf atas segala kendala. Sebagai penutup sepertinya Trisna mengatakan dia baik-baik saja sehingga tidak perlu khawatir dan tidak perlu datang lagi.
Selama bertelepon, Ares tampak risau namun pada bagian penutupan sepertinya raut Ares kembali kesal.
“Hah~” ujarnya lemah seraya meletakkan handphone di meja.
Walau begitu, besoknya saat aku menjemput Aruna selesai dinas pagi, kami pergi ke rumah sakit tempat Trisna di rawat. Trisna tampak lemah terbaring di ranjang pasien, namun tetap tersenyum saat melihat kami datang.
“Gua baik-baik aja. Mas Rian sama bokap gua praktek di sini. Jadi gak kesepian juga,” ujarnya pelan.
Aruna menggenggam tangan temannya sambil menyemangati.
Trisna belum keluar dari rumah sakit, kini nenek Ares yang keadaannya tidak baik. Nyaris bersamaan dua wanita yang secara lebih Ares sayangi jatuh sakit. Siang itu dia bergetar setelah menerima telepon dari Tante Suryani, kamera yang dipegangnya hampir saja jatuh. Tante Suryani mengatakan batuk nenek tak kunjung berkurang malah semakin parah hingga kesulitan bernafas. Ares langsung memesan tiket pesawat dengan keberangkatan segera ke Yogyakarta, meninggalkan kedua orang tuanya yang susah mendapatkan cuti. Ares tidak mengemas apapun dan berangkat langsung dari studio. Aku mengantarnya ke bandara. Dia sempat terlihat limbung saat berada di barisan check-in. Aku menghampirinya lagi, merangkul dan menepuk pundaknya mengatakan bahwa nenek akan baik-baik saja. Ares diam, anggukannya tampak tidak yakin. Lalu dia berangkat dan belum kembali selama dua minggu lebih. Selama itu juga Gammares dijalankan oleh aku dan Tyas serta sesekali seorang freelancer. Klien lama terus memperpanjang kontrak, klien baru datang dengan membawa banyak permintaan mengenai bahan iklan. Ares mengatakan sebaiknya pekerjaan dibagi-bagi saja. Dia meminta bahan yang bisa dikerjakan dari jarak jauh, dengan memaksa. Sehari-hari Ares hanya berada di rumah sakit menjaga nenek bergantian dengan Tante Suryani.
“Biar gak magabut,” katanya sambil tertawa pelan pada sebuah panggilan video dengan Aku dan Tyas di studio.
Jelas sekali dia berusaha menekan sedalam-dalamnya kesedihan, tawa itu terdengar hampa, cenderung tak bernyawa. Sesekali dia juga menanyakan kabar Trisna yang sudah keluar dari rumah sakit. Tyas mengatakan bahwa Trisna baik-baik saja hanya perlu menjaga pola makan dan istirahat yang cukup.
Ares mengarahkan kamera ponselnya untuk memperlihatkan kondisi nenek. Jujur, kasihan sekali. Nenek yang biasanya selalu riang itu kini terbaring lemah dengan bantuan masker oksigen terpasang menutupi hampir seluruh wajah kecilnya. Mata nenek setia terpejam. Suara bip bip bip yang entah dari alat apa ikut andil dalam membuat suasana semakin memilukan. Melalui panggilan video ini aku bahkan bisa mencium aroma khas rumah sakit yang tajam.
Pada kesempatan lain, suatu malam di minggu ketiga, Ares menelepon. Diawali dengan menanyakan pekerjaan, berbincang sebentar mengenai materi dan bahan, lalu telepon itu berakhir bersamaan dengan gundah yang Ares rasakan, “Perasaan gua gak enak.” Ujarnya dengan suara parau dan beberapa kali berdeham membersihkan gumpalan kesedihan yang menumpuk pada tenggorokan.
Benar saja, Jum’at pertama bulan November, dini hari, Ares menelepon lagi. Dengan suara terbata dia mengatakan nenek sudah tiada. Aku terperanjat dan langsung bangkit. Mengusap-usap wajah mendengar Ares di seberang sana dengan gagap meminta perpanjangan waktu libur.
“Sampai urusan selesai.” Katanya.
Aku menekankan untuk tidak memikirkan tenggat kembali. Ares menutup teleponnya segera. Aku yakin jika telepon itu lebih lama akan terdengar suara tangisnya. Telepon ditutup dan aku segera mencari tiket pesawat, sayangnya aku tidak akan sempat turut serta mengantarkan nenek ke pemakaman. Tiket tersedia paling cepat akan membuatku berada di Yogyakarta saat siang dan taksi mengantarkanku sampai di Magelang saat sore hari.
Aku berangkat dari studio setelah menyelesaikan beberapa pekerjaan. Seorang freelancer baru saja pulang saat Aruna datang mengenakan seragam kerjanya. “Kamu lupa ini,” ucapnya setelah mengeluarkan sweater coklat tua yang aku tinggalkan tergantung di balik pintu kamar. Sweater itu berpindah dari tas selempang Aruna ke ranselku, “Bawa aja buat jaga-jaga.”
Kami makan nasi telur dadar yang dibawa Aruna. Aruna mengatakan dia meninggalkan pesan untuk Ares atas belasungkawa.
“Kamu turun di Yogya atau Semarang?” tanya Aruna.
“Yogya. Semarang paling cepat malah ntar sore.”
Aruna mengangguk.
Dua motor kini memenuhi ruang penerimaan tamu di studio, motorku dan motor Ares yang sudah tiga minggu keluar masuk saat studio ditutup dan dibuka. Sofa-sofa harus dipinggirkan agar dua motor ini muat. Aruna membantu banyak dalam urusan pengaturan ruangan saat aku sibuk di depan komputer untuk membuat pemberitahuan libur sementara pada website dan akun sosial media Gammares. Aku memastikan Aruna berangkat kerja dengan taksi online sebelum aku juga memesan taksi untuk ke bandara.
Aku yang sejak kecil tidak pernah bertemu dengan kedua belah pihak nenek dari bapak dan ibu merasa sedih sekali mengingat nenek Ares. Walau pertemuan kami singkat, tapi meninggalkan kesan. Nenek orang yang menyenangkan karena pandai mengatur sikap sesuai usia lawan bicara. Pengalaman hidup membuat nenek bijaksana dengan cara menakjubkan. Wanita tua yang sebelum jiwanya pergi dari dunia itu sempat memberikanku pengalaman mendengarkan cerita yang luar biasa.
Perjuangan seniman pada masa nenek muda adalah mengembalikan makna seni kepada fitrahnya. Kini perjuangan seniman di era kami berada pada masalah hak cipta, plagiasi, dan oversaturasi sebab kemajuan teknologi. Bahkan tidak jarang sesama kami tak sungkan senggol-senggolan dan sikut-menyikut demi apa yang dunia sebut ketenaran. Perjalanan ini kutempuh dengan iringan doa. Aku tahu diri ini masih jauh dari agama, tapi sedikit banyaknya aku berharap doa tulus untuk nenek akan sampai pada Sang Pencipta.
Saat aku sampai, rumah nenek penuh oleh pelayat. Ingatanku langsung terlempar pada suasana berkabung serupa yang pernah aku rasakan dua tahun sebelumnya. Sedih menyayat. Rumah bergaya art deco dengan furniture bernuansa hangat ini terasa kehilangan ketenangannya sebab ramai orang lalu lalang. Ares berdiri menyalami pelayat yang izin undur diri. Dia berusaha tetap tegap dengan mengenakan pakaian serba hitam mulai dari peci hingga kaos kaki. Mulutnya mengucapkan terima kasih dengan sudut bibir ramah tapi kulit bagian bawah matanya tidak mampu menutupi bahwa mata itu telah bekerja keras berminggu-minggu menahan air agar tidak keluar dari pelupuknya. Di sudut lain, tante Suryani sibuk menata air mineral kemasan, sedang tiga orang anak dari nenek, termasuk papi Ares tengah memeriksa lukisan-lukisan dan sayup terdengar olehku sepertinya beberapa akan dijual.
Saat mobil seorang dari firma hukum baru keluar pagar dan juga menjadi pelayat terakhir yang menjalankan tugasnya sebagai notaris untuk membacakan surat wasiat dari nenek, suara riuh berseru terdengar dari ruang keluarga. Aku berada di kamar Ares pada lantai dua, kamar lamanya jika menginap di Magelang, lengkap dengan segala robot Gundam dan mobil Tamiya koleksinya. Terdengar suara-suara yang bertikai dari lantai bawah. Semuanya saling bersahutan dan tidak seorang pun mau mengalah. Simpang siur dalam silang kata. Cukup lama begitu hingga akhirnya keributan itu bungkam seiringan dengan suara pecahan kaca. Aku yang sedari tadi menahan diri untuk tidak melihat apa yang terjadi diantara mereka sekeluarga, kini segera keluar kamar. Dari atas sini terlihat lima orang di ruang keluarga, lalu beberapa lainnya, termasuk mami, mengintip dari balik tembok ruang sebelahnya. Ares berdiri di samping lemari kaca dengan bingkai kayu. Kaca itu pada satu sisinya terlihat pecah dan beling berceceran di sekitar kakinya. Juga bunga artifisial berwarna kuning cerah berserakan dengan tetesan darah dari tangan Ares yang mengepal. Tante Suryani terduduk lemas di lantai sambil bertumpu pada meja kayu, memukul-mukul lemah meja, menangis putus asa sembari menyebut nama nenek dan Ares bergantian, “Buk Retno …, bangun, Buk. Mas Ares berdarah, cucumu luka …,” dengan sedu-sedan.
Sedangkan tiga orang lagi: bibi dan paman, serta papi Ares hanya diam mematung melihat anak keponakan mereka berdiri menahan luka.
“TUNGGU GUA MATI, BARU BISA JUAL SESUKA HATI!” Suara Ares yang berat itu berseru kuat sambil menunjuk mereka bergantian dengan tangan yang berdarah. Kini tetesan darah dari tangannya ikut serta memberi corak merah pada teraso abu-abu.
Suasana semakin mencekam saat aku turun untuk menolongnya. Manusia lain pada ruangan ini hanya diam, sebagian meringis, sebagian menutup mulutnya menahan ngeri dan sebagian lagi, yaitu papi Ares membelalakkan mata kepada anaknya, seolah pertikaian itu masih berlangsung dalam diam. “ANAK KURANG AJAR!” caci papi setelahnya.
Ares yang tidak gentar sama sekali justru membalas cacian papi dengan menatapnya penuh kebencian. Kakinya kuat menapak pada lantai seolah tertancap ratusan paku. Aku berusaha mendorong Ares untuk duduk pada kursi jati di belakangnya seiringan dengan paman, bibi dan papi meninggalkan ruangan. Aku tidak peduli yang lain berlalu entah kemana. Namun derap langkah cepat menghampiri dan membawa Ares masuk ke dalam dekapannya. Mami, tak disangka-sangka, orang yang selama ini tidak menunjukkan kasih sayang kepada anaknya, kini terisak-isak sambil memeluk kepala Ares. Mami kemudian mengambil tangan Ares yang luka untuk di gulung dengan bajunya tanpa peduli baju gamis putih itu terkena noda merah. Tubuh Ares bergetar, sesaat air matanya mulai mengalir dia membenamkan wajahnya ke dalam pelukan mami, lalu meraung.
Sudah digagah-gagahkan pada akhirnya anak tetaplah anak. Dia akan kembali kepada ibunya mengadukan perihal luka. Aku yakin sekali, luka yang ada pada tangannya bukan apa-apa jika dibandingkan dengan luka pada perasaannya.
Lalu, walau bagaimana pun dingin sikapnya, beku hatinya, ibu akan kembali kepada kodratnya, menghangatkan. Kini mami memeluk duka anak yang lahir dari tubuhnya, menghapus luka anak yang merupakan separuh jiwanya. Ibu dan anak yang selama ini berseberangan kini menyatu dalam tangisan yang menggetarkan perasaan.
Tangisan itu tidak datang serta merta dari satu perasaan saja. Ada perasaan-perasaan lain yang kemudian berkembang secara perlahan; kegelisahan, keterkejutan, kesedihan. Lalu semua itu saling bertumpuk seperti efek bola salju menjadi perasaan negatif besar dan menggumpal membentuk satu perasaan yang dominan, yaitu kemarahan. Mereka berdua marah dengan keadaan yang berbeda. Yang satu marah karena merasa tidak dianggap, satunya lagi marah sebab anaknya dibiarkan terluka dan tidak ada yang membela. Mereka menangis karena terlalu lelah menahan amarah.
Tante Suryani dan beberapa sepupu Ares berkumpul untuk memeriksa luka pada tangannya. Malam itu, Ares kami bawa ke klinik terdekat dan mendapatkan tiga jahitan sebab tangannya tersayat kaca yang menempel pada bingkai kayu. Lalu, setelah tenang dan masih duduk di ranjang, Ares bercerita dengan suara pelan. Dia sengaja memecahkan kaca dengan tangannya untuk menghentikan keributan.
“Gua gak dikasih kesempatan ngomong, Nyet!” Dia menahan seruannya dalam bisikan. Kemudian Ares bercerita bahwa nenek meninggalkan seluruh lukisan tangan yang berjumlah sebelas, termasuk potret kakeknya menjadi kepemilikan Ares, sedangkan rumah lengkap dengan isi akan dijual habis untuk membeli tanah yang akan diwakafkan untuk pemakaman dan jika bersisa akan disumbangkan untuk pembangunan masjid. Anak yang berjumlah tiga, yang nenek tahu tidak ada di antara mereka mengerti cara menyayangi orang tua, hanya mendapatkan emas dan uang tunai yang harus dibagi sama rata, itupun setelah dikeluarkan uang pesangon untuk Tante Suryani dengan jumlah fantastis untuk seorang yang pernah bekerja bukan dari kalangan keluarga. “Wajar segitu, udah hampir dua belas tahun jagain nenek dengan welas asih,” ujar Ares membenarkan keputusan mendiang neneknya. Untuk itulah mereka menginginkan lukisan-lukisan itu dijual demi menambah pembagian harta. Jelas Ares keras menolak. Yah, bagaimanapun juga lukisan-lukisan itu kini hak Ares sepenuhnya. Dia tahu benar perjuangan nenek agar tetap melukis sewaktu muda, dia tahu bagaimana dulu nenek sebagai seniman membela hakikatnya berdiri melawan negara. Sebab itulah kini giliran Ares yang berjuang mempertahankan harga diri neneknya dari orang-orang yang disebut keluarga.
“Res? Papi gak dirumah, milih nginep di hotel. Kita pulang sekarang?” Mami yang telah kembali dari kasir, menyibak tirai biru penghalang antar ranjang. Di belakangnya mengintip beberapa sepupu dan tante Suryani.
Ares mengangguk. Sepupunya yang berjumlah dua itu tampak setengah-setengah dalam memperlakukan Ares. Desas-desus yang aku dengar dari tante Suryani adalah semasa hidupnya nenek memang lebih menyayangi Ares daripada cucu lainnya. Tidak mengherankan jika sekarang sepupu-sepupu itu juga pilah-pilih sikap terhadap Ares.
Sebelum tidur, aku menemani Ares merokok untuk menenangkan diri dan kami bersiap tidur saat nyaris pukul dua dini hari. Ares berbaring sambil memeluk boneka dinosaurus berleher panjang. Benar-benar menggelikan melihat dia dengan perawakan preman kini tidur dengan memeluk boneka menggemaskan. Tapi mengingat situasi saat ini, aku berusaha mati-matian untuk tidak menatapnya dengan cara menjijikkan. Tapi percuma, Ares menghela nafas seolah tahu apa yang aku pikirkan.
“Argentinosaurus. Dinosaurus paling besar. Fosilnya ditemuin di Argentina. Ini kado ulang tahun dari nenek pas gua masih TK.” Jelas Ares dengan suara malas.
“Oh? Oke … “ Jawabku kikuk, mungkin juga dengan wajah canggung. Dia membalikkan badan segera menghadap dinding. Anehnya lagi, dia meringkuk memeluk boneka itu dengan manis.
Astaga!
Diam-diam aku tertawa dari balik punggungnya.
Aku memilih tidur di bawah. Tante Suryani sibuk membawa kasur tambahan dan menatanya agar bisa aku gunakan. Benar kata Aruna, malam menjadi sangat dingin. Sepanjang malam aku mengenakan sweater yang telah Aruna siapkan. Kami sempat saling berkirim pesan perihal sweater yang berguna sesuai fungsinya dan juga perihal Ares dengan lukisan neneknya.
Menjelang subuh aku terbangun karena haus dan turun ke dapur untuk segelas air. Baru saja turun tangga, aku mendengar paman dan bibi Ares tengah berbincang serius mengenai hotel yang sedang dibangun oleh salah satu kenalan mereka di kota Sabah, Malaysia. Sepertinya dua lukisan akan dikirim ke sana.
Hausku hilang tanpa minuman dan berganti dengan sesak yang menghantam. Aku kembali naik dan berbaring, tidak bisa tidur lagi karena berfikir apakah sebaiknya aku beritahu Ares atau tidak. Tapi aku menegur diri sendiri mengingat ini masalah keluarga, tidak sepatutnya aku turut serta. Selama tiga hari aku mengikuti acara tahlilan dengan khidmat. Lalu kembali ke Jakarta sendirian karena Ares masih harus menyelesaikan beberapa urusan.
(Bersambung)
Restart ©2023 HelloHayden


 hellohayden
hellohayden







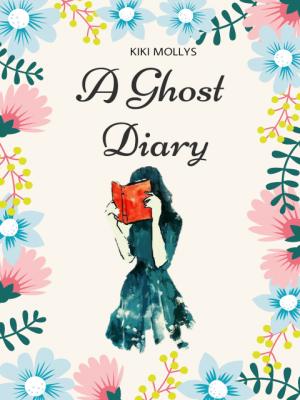



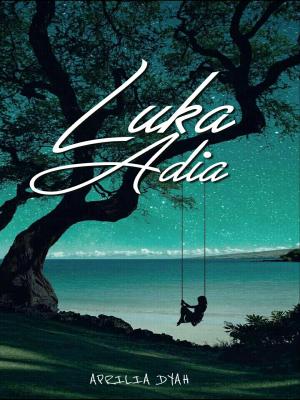

Baca cerita ini udah kayak masuk ke kedai all you can eat. Daging semua. Sbg cowok baca ini gk merasa aneh sama sekali untuk crita roman dan rasa kembali ke masa kuliah. Mantap lah
Comment on chapter Bab 14 (Cukup)