Ares mengeluh. “Katanya gua anak gak guna, tapi masih juga hobi ngenalin gua sana-sini ke teman-temannya.” Ares mengistirahatkan leher, menyandarkan kepalanya pada sofa, matanya dipejamkan. Sudah hampir dua jam dia menekuk menatap layar tablet untuk membuat animasi. Selain itu dia sedari tadi juga mengeluhkan ingin merokok tapi tidak bisa sebab berpuasa.
“Lu jadi, kan, ntar ke rumah?” tanya Ares masih dengan mata terpejam. Hari ini setelah studio tutup aku akan bertolak ke rumahnya, memenuhi undangan mami untuk berbuka puasa bersama seperti tahun-tahun sebelumnya. Sekali setahun dalam bulan Ramadhan, rumah Ares ramai oleh rekan, teman, keluarga bahkan tetangga memadati halaman belakang rumah Ares yang memang luas lengkap dengan kolam renang. Menurut Ares acara yang seharusnya khidmat itu hanyalah sebuah aksi subliminal untuk keuntungan papi dan mami. Lalu, Ares menjadi satu-satunya korban yang paling rela setiap acara ini ada, sudahlah tidak ada untung baginya, malah Ares selalu diukur keberhasilannya, tentu secara finansial, oleh orang-orang yang bertamu ke rumahnya.
“Aneh! Tuan rumah kok dipertentangkan tamu!” celetuk Ares kesal yang kini jakunnya bergerak naik turun melihat deretan kopi dingin yang terpajang menggoda di display cool case.
“Mami lagi ngebangun relasi buat lu kali?” hiburku.
“Ngebangun relasi? Ngebandingin kali! Dikumpulin tuh orang-orang yang katanya hebat,” dengus Ares, “kita kurang hebat apa sih, Nyet? Hobi kita dibayar. Kita happy,” ujaran Ares justru terdengar seperti justifikasi.
Aku mengangguk saja, enggan berkomentar lagi. Menjaga keabsahan puasa Ares juga agar tidak emosi.
Lalu Ares dengan semangat mengatakan akan memberi kejutan untuk mami nanti. Aku yakin sekali bahwa kejutan itu tidak akan menyenangkan mami atau siapapun yang hadir, sebab raut Ares saat mengatakannya terlihat sangat jahil dan … jahat.
Manuver apalagi kali ini?
Pukul dua siang, jam studio tutup di hari Minggu tapi Ares tidak segera pulang. Malas, katanya. Dia lebih memilih melanjutkan pekerjaan. Lalu aku menjemput Aruna di rumah sakit. Sudah dua minggu dia bekerja di sana, hari pertama bekerja tepat hari pertama puasa dengan dua bulan masa percobaan. Ibunya Tyas kini dirawat oleh Gina atas rekomendasi dari Aruna.
Dua puluh menit sebelum adzan maghrib, aku dan Aruna sudah sampai di rumah Ares.
Ares dengan wajah riang menyambut kami yang masih memarkirkan motor, Aruna bahkan belum melepas helm, “Gua tungguin dari tadi. Lama amat kalian!” Langkah Ares besar-besar untuk mendekati kami lebih cepat.
“Macet.” Jawabku.
“Lu harus liat kejutan gua!” Ujarnya lagi sambil tergesa-gesa mendorongku masuk ke rumahnya hingga duduk di ruang keluarga. Aruna mengikuti di belakang dengan wajah tak kalah penasaran tentang apa yang Ares katakan sebagai kejutan.
Walaupun acara makan nanti akan berlangsung di taman belakang, namun ruang keluarga tidak kalah disesaki oleh keluarga dan teman-teman dekat papi mami. Ares segera masuk kamar setelah aku dan Aruna duduk dengan benar. Tidak lama dia keluar dengan mengganti pakaian: kaos dan celana ripped jeans. Gaya berpakaian yang mami tidak pernah suka jika Ares kenakan. Berandal, begitu mami katakan. Terlebih saat ini kaos yang dia kenakan bertuliskan ‘Tetaplah Hidup Walau Tak Berguna’, namun Ares memakainya dengan bangga dan senyum lebar terkembang tepat di hadapan mami yang ternganga. Mami sangat terkejut melihat tingkah laku anaknya sampai-sampai salah meletakkan donat yang berakhir di piring kari kambing.
Keluarga Ares terdiam.
Rekan mami menatap mami dengan heran.
Aruna mati-matian mengatupkan bibir agar tidak tertawa dan meremas kuat lenganku sebagai pelampiasan.
Aku menghela nafas melihat kelakuan teman sendiri.
Satu-satunya orang yang terkekeh hanyalah nenek Ares sambil mengatakan, “Ganteng!” membuat Tante Suryani serba salah, dilema apakah harus menghentikan nenek atau tidak.
Mami dengan menahan malu menunjuk kuat ke arah pintu kamar Ares sambil mengatakan, “GANTI!” dengan nada tinggi. Ares tersenyum puas, “Siap, Mami!” lalu masuk. Tidak lama dia keluar lagi, memang dengan pakaian lebih rapi dan agamis: sarungan, peci dan kaos hitam bertuliskan ‘Rumahku Istanaku’.
Kali ini Aruna tidak tahan untuk tidak tertawa, begitu juga seisi ruang keluarga. Terlebih nenek Ares yang kesehatannya membaik melihat ulah cucu kesayangannya. Hanya mami yang diam-diam aku perhatikan wajahnya mulai merah. Marah dan malu bersamaan merubungi dirinya. Berbanding terbalik dengan garis senyum yang melintang panjang pada wajah Ares menunjukkan kemenangan.
Untung saja papi Ares masih terjebak macet, kalau tidak entah apa yang akan terjadi.
“Alea iacta est!”
Seru Ares saat menghampiriku yang geleng-geleng kepala tidak percaya akan strategi subversif-nya. Kalimat berbahasa latin yang berarti dadu telah dilemparkan diucapkan oleh Julius Caesar ketika menyeberangi Sungai Rubicon. Penyeberangan tersebut menandakan dimulainya perang saudara di Romawi. Keputusan yang berisiko tinggi, sebab Julius Caesar telah melewati batas legal kekuasaannya. Oleh karena itu, alea iacta est sering digunakan untuk mengekspresikan sikap berani mengambil keputusan penting dan menghadapi segala konsekuensinya. Begitulah, strategi itu berhasil membungkam mami sepanjang acara. Akhirnya tahun ini mami sudah menyerah untuk menyadarkan anaknya. Mami sibuk memperbaiki reputasi yang seketika merosot akibat eksibisi Ares. Memang tidak salah disebut sebagai kejutan, nyatanya tidak hanya mami, Ares berhasil membuat semua orang terkejut walau dengan cara tidak menyenangkan. Entah karena tidak terlalu memperhatikan atau mungkin juga mami tidak bercerita mengenai tragedi pakaian, Papi Ares cenderung tidak acuh melihat perbedaan gaya pakaian anaknya yang bisa dilihat dengan sekilas berubah total. Dia sibuk berbincang dengan rekan dan kolega bisnisnya. Ares juga sama sekali tidak ada keinginan untuk berganti ke gaya pakaian biasa. Sepanjang acara dia dengan jelas dan gigih menunjukkan perbedaannya.
Namanya saja buka bersama, tapi yang terjadi setelahnya hanyalah makan dengan kelompok yang setara. Semuanya terbagi dalam beberapa kelompok sesuai kepentingan atau kedekatan. Aku, Aruna, Ares, Nenek dan Tante Suryani telah menjadi kelompok solid selama hampir dua jam. Duduk makan bersama dan bercengkrama, tidak jarang tertawa mendengar cerita nenek tentang Ares kecil yang sengaja menuangkan sirup berwarna merah ke dalam akuarium ikan hias nenek dengan alasan agar ikannya senang berenang sambil minum air manis.
Ares setia menyuapi nenek makan saat nenek kembali menceritakan masa mudanya yang menarik. Nenek adalah pelajar ASRI pada tahun 1950-an.
“ASRI itu akademi pertama seni rupa di Indonesia, cikal bakal ISI Yogya sekarang.” Walau suaranya pelan, tapi nyala semangat dalam mata nenek terlihat. Nenek menceritakan bahwa ayahnya yang juga seorang seniman lukis, turut memperjuangkan kemerdekaan melalui karyanya. Saat Belanda kembali ke Indonesia karena mundurnya Jepang, Yogyakarta menjadi ibukota sementara Republik Indonesia. Para seniman lukis Yogya dengan tema semangat nasionalisme dan anti-kolonialisme terus membuat coretan-coretan pada tempat strategis. Slogan-slogan yang memantik semangat perjuangan terus di sertakan dalam mural-mural. Pada Agresi Militer tahun 1947, seniman lukis mendapatkan peranan dari pemerintah untuk melukis segala bentuk perjuangan kemerdekaan. Ayah nenek peran serta.
Lalu saat nenek berusia 20-an, masalah yang muncul bagi seniman bukan lagi masalah kolonial, namun masalah internal dalam negeri. Presiden Soekarno menganjurkan dalam setiap partai politik untuk membuat sebuah lembaga kesenian dan kebudayaan. Kedekatan Ir. Soekarno dengan Partai Komunis Indonesia, membuat partai politik itu terlebih dahulu membuat LEKRA (Lembaga Kebudayaan Rakyat) beraliran realisme-sosialis. LEKRA memegang kendali jalannya seni lukis ke arah politik yang membuat seniman lukis Yogya menolak dominasi LEKRA. Di sanalah nenek berdiri, membela seni lukis agar kembali sesuai makna awalnya yaitu ekspresi diri, emosi dan komunikasi.
“Kami ini seniman, bukan politisi. Seniman tidak berpolitik!” Dari mata sayu nenek hidup bara api seolah masih menyimpan dendam dan kemarahan yang belum dibayar tuntas.
Nenek mengatakan bahwa LEKRA mendapat dukungan penuh oleh Presiden Soekarno. Gerakan perlawanan yang tergabung dalam Manikebu (Manifestasi Kebudayaan) dianggap melemahkan revolusi, sehingga dalam pidato Ir. Soekarno yang berjudul Vivere Pericoloso pada 17 Agustus 1964 menyerukan agar Manikebu diganyang habis. Akhirnya Manikebu hanya bertahan sembilan bulan setelah kalah berjibaku dengan kekuasaan besar.
“Kami kalah dalam tanding yudha. Semua seniman lukis saat itu dilanda kelam sebab kebebasan kreatif dihambat. Saat itulah nenek bersama seorang guru dipanggil oleh kesultanan Yogya untuk melukis di sana.”
Suara nenek terdengar pelan menelan sisa kesedihan. Aruna mengusap-usap matanya, aku tahu dia terenyuh mendengar kisah perjuangan nenek. Tante Suryani dan Ares tampaknya sudah sering mendengar kisah luar biasa ini sehingga mereka tidak menunjukkan reaksi berlebihan. Malah Ares cengar-cengir sambil terus menyuapi nenek puding mangga. “Sabar, Mas. Nenek masih ngunyah iki! Ntar keselek,” tegur Tante Suryani pada Ares. Nenek terkekeh dan batuk sesekali.
“Terus, LEKRA dibubarkan oleh penguasa orde baru sampai ceritanya benar-benar memudar sejak kejadian 30 September 1965. Nenek menjadi salah satu pelukis profesional keraton sampai menikah dengan Pak Dwiyono, insinyur muda yang bertandang ke alun-alun keraton pas nenek melukis kegiatan di sana.” Tambah Tante Suryani yang sepertinya sangat hafal alur cerita ini.
“Uhuy! Love at the first sight! Abis itu kejadian deh lukis-melukis kayak di film Titanic, kan, Nek?” celetuk Ares pada nenek lengkap dengan senyum jahilnya
“Kebalik bego! Ini nenek yang pelukis, bukan kakek!”Aku menukas cepat. Namun Ares tersenyum dengan cara menyebalkan, “Nah! Tuh tau!” serunya lagi. Garis penuaan pada wajah nenek tidak mampu menyembunyikan rona merah muda pada pipi dan senyum tersipu malu yang menyungging dari bibirnya.
Aku dan Aruna terperangah.
Menyampingkan celetukan provokatif Ares, cerita nenek muda terasa ekstraordiner sebab mendengarnya langsung dari pelaku sejarah, jika bisa aku katakan begitu. Pandanganku beralih dari nenek ke Ares bergantian dan terus-terusan. Tidak menyangka temanku yang ugalan cenderung blangsatan ini adalah cucu seorang wanita pejuang.
“Nenek udah kayak srikandi dunia seni,” komentar Aruna yang dibalas nenek dengan raut haru.
Tamu-tamu sudah banyak yang pulang, kami juga ingin berpamitan. Saat ditemui, mami mengeluh, “Ampun anak itu! Gak punya santun! Udahlah gak bisa dibanggakan, minimal kerjaan bagus!”
Ujaran itu walaupun tidak ditujukan untukku, tapi terasa cukup menyakitkan. Mami tahu benar aku dan Ares bersama menjalankan suatu usaha. Tapi lagi-lagi, aku diam saja. Aku tekan rasa sakit itu sekuatnya. Aruna yang paham segera menggenggam erat tanganku, berusaha menenangkan agar aku tidak mengeluarkan perkataan macam-macam. Tidak pun begitu, aku juga urung mengemukakan pendapat terhadap orang yang superfisial. Mereka cenderung menutup mata dan seolah merasa paling benar.
“Kami pamit, ya, Tante. Terima kasih hidangannya,” ujar Aruna memangkas perbincangan.
Kami pulang. Ares mengantar hanya sampai ruang tamu, sebab tahu-tahu nenek tersedak sesuatu dan Ares segera berlari menghampiri.
“Tadinya aku memang gak ngerti kenapa Ares sampai nyiapin rencana kejutan memalukan buat mami,” kataku pada Aruna sambil memasangkan helm dan merapikan jaket jeans-nya, “sekarang aku paham, itu caranya menegakkan pendapat di rumah sendiri. Bukan melawan. Itu bentuk pertahanan diri.”
“Kamu gak perlu pendapat mami. Kamu punya ibu dan adik yang sepenuhnya memahami,” hibur Aruna.
“Dan pacar yang selalu mendukung,” kataku segera. Aruna mengangguk dan tersenyum.
-oOo-
Sepanjang Ramadhan, perusahaan jasa perjalanan terus mengejar pembuatan materi iklan promosi untuk mudik lebaran. Industri fashion tidak kalah semangat. Usaha kue kering seperti milik Bu Lin juga sedang kejar-kejaran dan berlomba membuat materi iklan paling menarik. Bu Dewi juga ingin menjual makanan khas lebaran seperti opor dan rendang sehingga dia memintaku untuk memotret hasil masakannya untuk diiklankan di media sosialnya. Khusus untuk Bu Dewi, aku beri gratis, tidak perlu MoU atau legalitas lainnya. Toh juga Bu Dewi tidak banyak permintaan, dia hanya ingin foto yang cukup menjual untuk media sosialnya.
Aku dan Ares serta satu orang freelancer sering syuting di luar, menentang terik matahari siang. Entah kenapa setiap bulan puasa justru matahari sedang pada puncak-puncak panasnya, jangankan hujan, berawan saja jarang-jarang. Tidak dipungkiri, beberapa hari aku tidak berpuasa, begitu juga Ares. Lalu sering begadang dan tidak pulang ke kost sebab mengejar target masing-masing klien. Bulan Ramadhan terlewati dengan banyak pekerjaan yang selesai dengan baik. Benar-benar menyenangkan hingga kami melupakan lelah yang ditimbulkan.
Saat idul fitri, aku menghabiskan seminggu di Bogor. Ikhsan datang pada lebaran ke dua. Saat aku dan dia duduk di teras depan, dia menyampaikan bahwa pendidikan S2 Psikologi-nya sudah selesai dan sedang menunggu jadwal wisuda. Sesuai rencana awal, dia akan membuka klinik sendiri. Ikhsan dengan hati-hati sepertinya ingin mengingatkanku lagi tentang rencana menikahi Marwa jika klinik itu berjalan baik. Aku mengatakan padanya, sebaiknya adikku diberikan kesempatan bekerja setelah lulus kuliah. “Aku gak bermaksud sama sekali menghalangi niat baik, tapi aku ingin Marwa mengenal dunia kerja. Banyak yang bisa dia pelajari dari sana yang akan berguna nanti di waktu-waktu kedepan.” Jelasku. Ikhsan menyetujui dengan anggukan pasti. Setelahnya kami hanya mengobrol ringan khas laki-laki. Tidak ada topik yang dipentingkan lagi selain cerita menikahi adikku.
Lalu pada hari terakhir di rumah, Aruna datang dengan inisiatif sendiri tanpa memberitahuku sama sekali. Dia langsung berangkat dari Tangerang menaiki bus menuju Bogor. Aruna sampai dengan mengejutkan saat aku tidur siang dan terbangun sebab suara Marwa terdengar seru sekali di luar.
Ibu senang.
Marwa jelas kegirangan.
Aku? Jangan ditanya. Sudah pasti ingin segera memeluk Aruna tapi tidak bisa. Syarat utama kekasihmu akan diterima oleh ibu dan saudara perempuanmu adalah jangan terlalu memperlihatkan kepada mereka bahwa kamu sedang mabuk cinta. Tahan saja walau hampir gila. Hindari menciptakan suasana pertarungan sebab berebut perhatian antara sesama perempuan. Beruntungnya Aruna sangat paham, sejak kali pertama, Aruna mampu bersikap sewajarnya tanpa menimbulkan suasana persaingan. Sore sebelum aku dan Aruna kembali ke Tangerang, aku mengajak mereka semua makan siang bersama lalu jalan-jalan setelahnya. Aku yang kemana-mana sengaja membawa kamera dengan niat membidik jalanan, justru beralih banyak memotret mereka diam-diam. Lalu aku menyadari satu kesamaan pada tiga perempuan ini: sama-sama bisa mengatur hidupku, dengan cara yang aku sukai tentu.
Sore pukul lima, aku sudah siap berangkat bersama Aruna kembali ke Jakarta. Ada satu pemandangan haru yang aku saksikan sebelumnya. Saat aku menunggu di motor, Aruna masih berada di teras bersama Ibu dan Marwa untuk berpamitan. Aruna menundukkan kepala untuk mengantarkan tangan ibu ke dahinya, tanpa diduga ibu dengan cepat merangkul Aruna, memeluknya dengan penuh kasih sayang.
“Hei, udah-udah, ntar kalau lebih lama malah nangis-nangisan,” ujarku dengan hati riang. Mereka melihatku lalu mendengus bersamaan.
“Iri aja jadi orang!” celetuk Marwa kesal.
Saat kami mulai jalan, aku menanyakan mengenai libur Aruna yang hanya dua hari itu juga mendadak dikabari oleh kepala perawat di rumah sakit. Libur sangat singkat itu dia gunakan maksimal. Sehari dia habiskan di panti dan rumah Bu Sarah, sehari lagi dia habiskan bersama kami di Bogor. Tentu saja di antara dua hari itu tidak sedikit waktu yang dia gunakan untuk perjalanan.
“Kamu gak capek?” tanyaku, “mondar-mandir gitu dua hari ini.”
“Capek, tapi seneng. Jadinya gak gimana-gimana,” jawabnya. Wajah Aruna dengan senyum riang memantul dari kaca spion. Kemudian kepalanya bersandar pada punggungku serta kedua tangannya melingkari dan bertemu pada perutku.
“Runa, kalau ngantuk, kita berhenti.”
“Enggak, kok. Lagian mau berhenti dimana?” suaranya mulai sayup terdengar entah terbawa angin entah kantuk yang dia tahan.
“Di hotel.” Jawabku usil.
Aruna mencubit perutku, kuat, hingga aku tersentak. Lalu kami terkekeh bersama. Motor melaju dengan cerita-cerita seru, tawa riang berhamburan. Deru mesin kendaraan berseliweran tanpa kami pedulikan. Lampu perkotaan bagai kunang-kunang raksasa, menghiasi malam dengan kerlip ragam warna.
Kami sampai di Jakarta setelah dua jam di jalan, lalu makan malam di tempat bubur ayam favorit Aruna sambil kembali melanjutkan cerita ringan, tentang tamu-tamu yang datang ke rumahku selama lebaran –termasuk Ikhsan, tentang kemana saja aku bersama teman-teman SMA.
“Wih? Seru dong, ketemu mantan!” celetuk Aruna.
“Seru, lah! Masa engga,” jawabku yang dia tahu bercanda.
Aruna gemas sambil menyipitkan sepasang matanya, melihatku seolah dia cemburu. Aku mengusap seluruh wajahnya dengan telapak tangan untuk menghentikan reaksi kekanakannya, “Ah, udah …,” ujarku.
Dia tertawa, kemudian bercerita pengalamannya di IGD selama lebaran. “Banyak yang diare dan batuk-batuk di lebaran ke tiga,” kata Aruna.
“Kalau di panti dan rumah Bu Sarah gimana?” tanyaku lagi.
“Tahun-tahun lalu kan aku belum kerja. Kamu tahu aku kalau lebaran pulang ke Tangerang duluan, bantuin Bu Hafsari dekorasi, atau masak untuk lebaran. Kalau sekarang, aku datang-datang udah kayak tamu. Foto-foto sama adik-adik aku, makan. Terus sorenya ke rumah Bu Sarah, makan lagi. Tamu Bu Sarah banyak. Aku bantuin dia beres-beres. Udah malem banget aku balik ke panti,” jelas Aruna. Walau lelah dia tampak bahagia.
“Tepar, dong?”
“Banget! Sampai panti jam sebelas malam, langsung tidur.”
Lalu Aruna memperlihatkan foto-foto di panti. Dia perkenalkan satu-satu adiknya, banyak, sekitar dua puluh lima. Banyak orang dalam foto itu tapi pacarku paling bersinar dengan baju gamis putihnya.
Aku terus menggeser layar ponsel Aruna untuk melihat foto lainnya. Satu foto membuatku berhenti dan bertanya. Foto Aruna, Bu Sarah dan seorang pria muda.
“Ini siapa?” tunjukku pada wajah pria berkacamata bingkai titanium itu. Aku ingat jelas Aruna pernah mengatakan bahwa Bu Sarah tidak punya anak.
“Oh? Ini … ini keponakan Bu Sarah. Andre namanya,” jawab Aruna.
“Ooh. Kamu kenal?”
“Kenal.”
“Deket?”
“Kami satu sekolah dari SD sampai SMA, dia dua tahun di atas aku. ”
“Sempat pacaran, dong?” godaku.
Aruna berhenti menyuap bubur ayamnya, “Engga, kok! Malah gak sapa-sapaan lepas dari SD. Aku baru masuk SMP dia udah di akhir tahun. SMA juga gitu.”
Aruna sewot.
Aku manggut-manggut.
Lalu tanpa membahas itu lagi, kami menghabiskan makanan masing-masing. Seperti biasa, Aruna tandas, aku bahkan tidak menghabiskan setengah mi gorengku.
Kami memasuki kost yang kini sepi sebab banyak penghuni yang masih belum kembali dari mudik, termasuk Bu Dewi dan Pak Rully yang tahun ini kembali ke Palembang menemui anak mereka satu-satunya. Pak Yahya tidak tampak. Aruna mulai menguap saat menaiki tangga. Pada tangga di lantai dua aku berpapasan dengan seorang tetangga yang sama sekali belum pernah aku lihat. Bapak-bapak kurus tinggi dengan kulit cerah, mengenakan kacamata bingkai tebal berwarna hitam. Dia turun dengan tergesa-gesa sambil bersedekap tangan dalam jaket biru tua. Saat berpapasan, tatapannya beralih dari aku dan Aruna bergantian. Lalu dia berhenti menyandarkan punggungnya pada sisi dinding tangga untuk mempersilahkan kami naik duluan.
Aku menarik Aruna agar berpindah posisi ke paling kiri, menghindari dia berdekatan dengan bapak-bapak yang berhenti ini. Dia tersenyum melihat Aruna mengucek mata sebab mengantuk. Aku dengan sinis menatapnya dan dengan cepat merangkul Aruna. Setelah melewatinya, pria itu turun tergesa-gesa dari pada sebelumnya.
Tetangga lantai berapa?
Pernah lihat, tapi dimana?
Gumamku.
“Ngantuk banget,” ujar Aruna yang sedari tadi setengah tidur setengah berjalan.
“Iya, nih udah mau sam-”
Mataku terpaku pada kotak hadiah merah muda yang muncul lagi di depan pintu Aruna. Itu lebih besar dari sebelumnya. Aku berjalan cepat mendekati bingkisan itu. Aruna segera sadar sepenuhnya saat aku melepas rangkulan.
Jantungku berdegup kencang merasa dalam cengkraman ancaman.
“Masuk kamar sekarang, kunci!” Aku meyakinkan Aruna dan segera berlari mengejar pria berkacamata tebal berjaket biru tua tadi.
Suara kunci berputar terdengar saat aku menuruni tangga. Aruna aman.
Aku keluar gedung, melihat kiri kanan. Kosong.
Aku berlari ke jalan, menyisir pandangan. Kosong.
Brengsek! Harusnya masih dekat!
Aku pacu motor untuk segera mengejar entah kemana. Aku geram.
Harus dapat! Harus ketemu!
Sialan!
Umpatan-umpatan kasar sudah penuh bergumul di mulut sebab pria itu tidak juga aku temukan. Dia benar-benar seperti bayangan yang semakin hilang dalam gelapnya malam. Mataku terus waspada menelisik sudut-sudut gang. Tetap, dia raib entah kemana.
Setelah lima belas menit dan nyaris putus asa, aku kembali dengan sia-sia. Berhenti untuk membeli minum di minimarket, minum seperti kesetanan sebab kekesalan atas apa yang tidak aku temukan.
Aku duduk di kursi luar, memperhatikan jendela kamarku di seberang dengan lampu menyala. Aruna di sana.
Rokok sudah bertengger di bibir menunggu dinyalakan. Aku sibuk meraba setiap kantong celana, namun sayang, tidak ada korek dimana-mana.
Tiba-tiba, seorang pria mengulurkan tangannya dari samping untuk menawarkan korek, “Pakai ini,” ujarnya.
Aku menoleh segera dan nyaris melompat sebab apa yang aku lihat. Soda kaleng terdengar berderak karena tanpa sadar aku menggenggamnya kuat.
Benar. Pria berkacamata tebal berjaket biru tua sedang tersenyum padaku.. Anehnya senyum itu adalah senyum yang setiap hari aku lihat. Sangat familiar.
“Kalau kamu cari saya, saya dari tadi di sini. Gak kemana-mana,” jelasnya lagi.
Nafasku memburu cepat sebab terperanjat. Belum sempat aku menanyakan apa-apa, dia sudah memperkenalkan diri.
“Ari.” Katanya lagi sambil mengulurkan tangan.
Hah? Ari?
Ari?
Pak Ari!
Ayah Aruna!
Saat aku masih mencerna segala rentetan kejadian, dia menggoyangkan tangannya mengulur mengharap sambutan.
“Ayah Aruna.” katanya lagi.
Aku terkesiap, menjatuhkan rahang dengan segala ujaran terkejut yang hanya bisa dalam hati aku teriak kan. Tanganku bergetar menyambut uluran tangannya. Aku menelan ludah sebab merasa bersalah telah mengeluarkan umpatan terparah.
“Gamma.” Ujarku dengan nafas tertahan.
Dia mengangguk dan tersenyum lagi.
Benar. Itu garis senyum yang sama dengan milik Aruna.
GILA!
“Jangan cerita apa-apa ke anak saya. Saya belum ada muka menemuinya,” ujar Pak Ari lagi.
Aku kaku.
Lidahku kelu.
Pak Ari kemudian melangkah pergi setelah tangan kami tidak terpaut lagi. Banyak hal yang ingin aku tanya tapi aku terlalu bingung. Aku tidak menyangka dan tidak bersiap akan kenyataan yang aku ketahui dengan cara begini. Lalu yang lebih membuatku tidak enak hati, aku kurang ajar telah memaki ayah pacar sendiri, tadi.
Aku menoleh segera, melihat punggung Pak Ari yang menjauh.
“Pak!”
Aku hampiri dia, “Aruna menunggu,.”
Pak Ari berhenti.
“Selama dua puluh tahun dia menunggu,” ujarku lagi kini dengan suara nyaris parau.
Lama Pak Ari diam. Dia bergetar menahan tangis. Sambil menundukkan kepala dan mengepalkan kuat tangannya isakannya sayup terdengar. Semakin dekat, isakan itu terdengar semakin kuat. Aku merasakan kegagalan, kesedihan dan tekanan yang luar biasa yang dialaminya lalu semua itu hanya dilimpahkan dengan isakan tertahan.
“Pak? Dia akan senang. Bapak pasti lebih tahu dari saya kalau dia bukan orang pendendam,” kataku tepat berdiri di belakangnya. Isakan itu berubah menjadi tangisan berat menyayat. Kamu akan tahu bagaimana perihnya jika pernah melihat laki-laki dewasa menangis. Percayalah, bagi laki-laki, tangisan bukan tanda kelemahan, melainkan bentuk pertahanan terakhir. Namun, seringkali kami menolak untuk menangis karena budaya mengajarkan bahwa laki-laki kuat adalah mereka yang mampu menahan emosi, bukan justru berekspresi. Jika memang kami menangis, itu artinya sudah habis apa yang bisa kami lakukan selain menyerahkan air mata ke tanah.
Pak Ari berusaha kuat menenangkan dirinya. Aku mengajak duduk kembali di minimarket sambil minum kopi. Lampu kamarku masih menyala, lalu aku kirimkan pesan pada Aruna bahwa aku baik-baik saja dan hanya ingin istirahat di minimarket sebentar. Dia membalas dengan mengatakan akan kembali ke kamarnya sambil menunggu. Lalu dia bertanya mengenai pengejaran yang aku lakukan. Aku membalasnya dengan mengatakan semua aman.
Pak Ari mulai bercerita bahwa dia telah berpindah-pindah selama dua dekade tahun terakhir. Kabupaten Pesawaran di Kota Lampung adalah tempat dia tinggal sekarang. Hidup dengan bertani bawang dan sayur-sayuran bersama seorang istri yang sudah tujuh tahun ia nikahi.
“Dengan Aruna saja saya gagal. Saya tidak akan sanggup menghadapi kegagalan kedua,” ujar Pak Ari saat aku menanyakan apakah dia punya anak lagi. “Aruna adalah orang yang paling berhak atas kasih sayang seorang ayah,” jelasnya kemudian dengan suara lemah.
Aku tidak banyak bicara sebab tidak mau bersilang kata dengan Pak Ari yang berusaha mencurahkan perasaannya. Sepanjang cerita, aku banyak menahan sesak di dada. Sungguh hubungan ayah dan anak perempuan yang mengharukan. Yang anak menunggu, yang ayah menghindar karena malu.
Kemudian Pak Ari mengakui bahwa dia mengirim semua bingkisan itu. Lalu aku mengingat sesuatu, bahwa Pak Ari lah orang yang berbicara dengan Pak Yahya saat pertama kali aku ke minimarket bersama Aruna untuk membeli mi instan, begitu juga saat aku menerima paket dari Ibu dan casing handphone Aruna dari Pak Yahya, Pak Ari juga orang yang bersama Pak Yahya saat itu.
Dia diam. Aku diam.
Kami menyesap kopi panas.
“Saya bukan tidak datang saat dia di panti asuhan. Saya hanya tidak meninggalkan jejak apa-apa.” Jawaban Pak Ari saat aku bertanya kenapa dia baru datang sekarang.
Pak Ari menarik nafas kuat dan dalam, menghirup aroma kopi untuk menenangkan pikiran dan segera menyesapnya sebelum akhirnya menjawab.
“Saya berharap, anak saya itu biasa-biasa saja. Tidak tumbuh secantik itu dan tidak juga pintar sampai juara. Dengan begitu mungkin saya bisa dengan leluasa menjemputnya.”
Jawaban Pak Ari mengejutkan, tidak seperti kebanyakan ayah, dia justru ingin Aruna tumbuh serba biasa.
“Maksudnya, Pak?”
“Saya terlambat. Saya datang saat Aruna sudah memakan budi orang besar. Saat orang itu menyadari Aruna anak yang bersinar.” Suara Pak Ari mulai terdengar serak. Tatapannya nanar memandang gedung kost kami seolah menatap Aruna dari balik jendela.
“Bu Sarah?” tanyaku.
Pak Ari mengangguk lemah.
“Saya, sebagai ayah dengan keterbatasan keuangan, mungkin tidak bisa menyekolahkannya seperti sekarang. Untuk mengantarkannya tamat SMA saja saya yakin saya sudah berusaha habis-habisan. Bu Sarah mendapati saya yang memperhatikan Aruna dari kejauhan, lalu dia mendatangi dan mengatakan akan menyekolahkan Aruna dengan syarat saya tidak boleh membawanya. Biarkan Aruna menganggap saya hilang atau bahkan mati saja. Lama saya merenung bahkan setelah Bu Sarah pergi. Kesempatan selanjutnya, saya menyetujui dengan sangat berat hati. Saya pikir itu juga baik untuk masa depan Aruna. Anak saya sekolah, hidup anak saya terjamin. Lagipula saya lega, apa yang dijanjikan Bu Sarah telah ia tepati. Saya menyaksikan sendiri.”
Pak Ari menatapku yang kini ternganga.
“Jika sesuatu yang kamu inginkan melampaui batas kemampuan, harga bukan lagi tentang uang. Ada waktu dan jiwa yang harus kamu persembahkan. Itu lah sebenar-benarnya pengorbanan.” Pak Ari mengatakan itu sambil tersenyum. Jelas sekali dia mengikhlaskan apa yang telah dia korbankan. Lalu apa yang dia korbankan itu kini tampak hasilnya. Anaknya sekolah, lulus dengan nilai gemilang, hidup tanpa kekurangan dan senang. Mungkin bagian senang itu hanya dia yang menyimpulkan.
Aku mengangguk mulai memahami.
Kasihan sekali.
Anak dan ayah ini sama-sama dikendalikan oleh satu wanita: Bu Sarah. Setelah mendengar cerita ini, sangat tipis bagiku perbedaan antara jahat dan baik. Apa Bu Sarah jahat? Tidak. Dia mengerahkan tenaga dan uangnya untuk Aruna. Apa Bu Sarah baik? Tidak juga. Dia bahkan memisahkan hubungan darah antara ayah dan anak.
Cukup lama kami diam, menghabiskan kopi yang sudah mulai dingin terkena udara dini hari. Aku meyakinkan sekali lagi kepada Pak Ari bahwa Aruna benar-benar merindukannya. Bahwa Aruna akan sangat gembira mengetahui ayahnya baik-baik saja. Kalaupun menangis, itu pastilah tangisan haru bahagia.
“Saya sudah harus di pelabuhan Merak besok siang untuk balik ke Lampung,” ujarnya lagi.
“Bapak bisa menginap di kost saya malam ini,” tukasku segera, “sambil memikirkan menjelang pagi bagaimana sebaiknya kali ini. Apapun keputusan bapak saya hargai, baik itu menemui Aruna atau bahkan enggak. Tapi saya gak bisa janji akan diam aja mengenai hal ini padanya. Bagaimana juga, dia berhak tahu semuanya.”
Pak Ari mengangguk.
Malam itu akhirnya Pak Ari kembali masuk kost, menuju kamarku.
Aku memberikannya kasur sedangkan aku tidur di sofa. Terbesit sedikit-sedikit ini suatu bentuk menutupi kesalahanku atas ujaran kebencian dan cenderung kurang ajar yang bahkan tidak dia dengar. Aku malu sendiri karena telah salah paham selama ini. Tentu saja catatan ‘Menyayangimu selalu’ itu bisa saja dari ayah kepada anak perempuannya. Selayaknya ungkapan ‘Anak perempuan akan selalu menjadi putri kecil ayahnya tidak peduli berapapun usianya.’
Malam itu baik aku maupun Pak Ari, walaupun tidak saling berbicara, aku tahu bahwa kami sama-sama tidak bisa tidur sebab sibuk memikirkan pagi yang akan datang enam jam lagi.
-oOo-
Jam tujuh, Pak Ari sudah mandi dan segar. Aku masih setengah sadar saat dia membuka gorden. Cahaya matahari yang belum begitu terang masuk menyusup.
Ya Tuhan, bahkan kebiasaan bangun paginya pun sama.
Aku memaksakan diri untuk bangkit, membasuh wajah lalu menyeduh kopi hitam untuk Pak Ari lengkap dengan roti.
“Saya sarapannya begini, Pak. Kalau Bapak mau saya bisa pesankan yang lain,” ujarku.
Pak Ari menggeleng.
“Saya akan makan apa yang tuan rumah sediakan,” ujarnya lagi.
“Aruna bilang hari ini dinas malam, masuk jam sembilan.”
Pak Ari mengangguk.
Aku diam menunggu keputusan Pak Ari.
Dan seolah tahu aku tengah menunggu, Pak Ari tersenyum, “Saya akan menemuinya.”
Dia terdengar yakin.
Bahuku yang sedari tadi tinggi, kini jatuh lega seturut dengan helaan nafas. Ia sudah sampai menginap di sini, tentu saja tidak akan menyia-nyiakan kesempatan yang sepertinya tidak akan datang dua kali dengan cara yang lebih gampang daripada ini.
“Ya, Pak. Saya senang dengan keputusan itu,” jawabku sambil menyesap kopi, diikuti oleh Pak Ari. Senyum bahagiaku tersembunyi dari balik cangkir.
“Kamu tolong sampaikan pada Aruna bahwa saya di sini. Kalau dia bersedia, saya akan menemuinya. Kalau menolak, saya akan pergi dan akan memperhatikan diam-diam seperti biasa lagi.”
Aku mengangguk sambil menatapnya lagi.
Dia pasti mau. Ini waktu-waktu yang dia tunggu.
Kopi mulai habis, roti hanya menyisakan remah.
Sesekali Pak Ari menenangkan diri dengan menarik nafas dalam lalu mengeluarkannya pelan. Dia izin membuka jendela untuk merokok, pada akhirnya kami merokok berdua, melepaskan pandangan keluar menatap jalanan. Dengan ponsel lawas-nya, Pak Ari berbicara dengan istrinya mengabarkan berita ini dan menyampaikan betapa gugupnya dia menemui anak sendiri.
Setelah semua itu, aku segera keluar untuk menemui Aruna untuk mengabarkan semuanya tanpa ada yang tertinggal. Berbagai macam raut telah Aruna tunjukkan sepanjang cerita, tapi yang aku tahu pasti, tidak ada satupun raut kemarahan atau kebencian diantaranya.
Dia tersedu-sedu menangis memelukku.
Dia katakan ingin segera bertemu. Rindunya sudah sangat lama tertumpuk-tumpuk oleh waktu.
“Ternyata aku gak bertepuk sebelah rindu.” Katanya sambil terisak.
Aku tertawa mendengar kiasan itu. Aneh, tapi benar juga.
Pak Ari masuk ke kamar Aruna dengan gugup yang sangat jelas terlihat. Baru masuk saja air matanya sudah mengalir. Begitu juga Aruna yang pipinya sudah kering, kini basah lagi, malah air matanya lebih deras dari sebelumnya. Pak Ari mengusap kepala Aruna saat aku menutup pintu, membiarkan mereka mengatakan apa yang harus dikatakan, membicarakan apa yang harus dibicarakan dan melepas rindu yang menyesakan selama dua puluh tahun belakangan.
Setelah mengantar Pak Ari ke terminal, aku kembali ke kost saat hampir Maghrib. Aku mengetuk kamar Aruna dan dia membukakan pintu dengan mata sembab. Aku tertawa melihatnya. Aruna juga tersenyum dalam isakannya lalu kembali menghempaskan diri pada kasur dan membenamkan wajah pada bantal strawberry yang aku lihat juga tidak kalah basah.
“Masih mau nangis dulu atau udah bisa cerita gimana perasaan kamu?” godaku sambil duduk di meja belajarnya. Tas selempang yang kulitnya sudah terkelupas tergeletak di atas meja, cermin dekorasi sudah terpajang rapi di sudut meja serta jam tangan berkulit karet putih itu kini dia letakkan lagi bersisian dengan jam biasa dia kenakan.
“Gam?” panggil Aruna. Suaranya tertahan oleh bantal yang masih melekat bersama wajahnya.
“Ya?”
“Makasih.” Ujar Aruna lagi.
“Apa? Gak denger, kamu ngomong tapi mulutnya ketutupan bantal,” ujarku pelan-pelan mendekatinya.
“Makasih. Makasih, Gam,” katanya lagi sambil menjauhkan wajahnya dari bantal. Kini aku sudah tepat berhadapan dengan wajahnya.
Aku tersenyum sambil mengelus pelan dahinya.
“Kamu gak perlu bilang makasih,” ujarku pelan.
Aruna tersenyum dan membuat garis matanya makin lenyap sebab masih sembab.
“Kamu cukup diam dulu begini, aku mau foto wajah bengkak kamu! Lucu banget!” aku tertawa terbahak. Aruna yang kesal kemudian melempar secara beruntun dengan segala yang ada di atas kasur; bantal, selimut, dan jaket jeans. Walau setelah itu semua dia terbahak juga dan aku tetap memfotonya dengan kamera ponsel. Justru saat tertawa membuat wajahnya yang sudah lucu itu menjadi lebih jenaka.
Menjelang jam dinas malam, kami berdua sibuk mengompres mata Aruna dengan ice bag.
“Aku malu masuk kerja mata bengkak begini,” keluh Aruna.
“Kalau ditanya bilang aja nangis karena cuma dapat libur dua hari, jadi besok-besok dikasih lebih,” jawabku sambil bergantian menempelkan kantung es pada matanya.
“Ya, dikasih libur selamanya alias dipecat saya!”
Komentar sinis dari Aruna kembali membuatku tertawa.
–oOo–
“Kamu cintai dia sampai dia lupa bahwa dia tidak pernah merasa dicintai oleh ayah sendiri. Buat dia tertawa sampai dia melupakan rasa sedih yang menghantam hatinya selama dua puluh tahun terakhir. Jaga dia lebih baik dari yang pernah saya lakukan semasa dia kecil.”
Sambil berbaring kata-kata itu masih melekat di kepalaku.
Itu adalah pesan dari Pak Ari sesaat dia akan menaiki bus. Dia menepuk kuat bahuku sambil mengucapkan terima kasih. Aku mengangguk yakin padanya seolah mengatakan bahwa dia bisa mempercayaiku sepenuhnya.
Cincin emas permata putih ini aku perhatikan lamat-lamat. Mengangkatnya tinggi menutupi cahaya lampu. Terukir ‘AG&GA’ pada sisi bagian dalamnya. Aku tersenyum bahagia, atau mungkin senyum lega sebab terasa lapang di dada. Cincin ini akan melingkar indah pada jari mungil Aruna. Aku berhenti pada sebuah toko perhiasan setelah mengantar Pak Ari ke terminal. Sepanjang jalan nama Aruna selalu dalam kepala sehingga terdorong keinginan untuk memberikannya sesuatu yang spesial. Benar, cincin ini bukan simbol ikatan, bukan juga simbol kepemilikan. Ini benar-benar hadiah untuk orang yang aku sayang. Cincinnya sudah ada, hanya perlu membuat momen tepat untuk memberikannya. Katakanlah berlebihan, tapi diam-diam kini aku membayangkan suasana pantai malam dengan langit bertaburan bintang. Sinar bulan menerpa pipinya dengan lembut. Ombak bergulung manja saling mengejar tepian dan angin sepoi-sepoi membuat rambutnya berayun pelan. Saat memberikan cincin ini akan aku katakan padanya bahwa dia selalu memiliki tempat di hati, selamanya. Laut beserta segala apa yang ada di atas dan di bawahnya akan menjadi saksi.
Ah, Gila! Perutku geli!
Setelah puas membayangkan situasi romantis, aku menyadari bahwa seharusnya aku bisa saja bertindak lebih praktis. Memberikan cincin ini sembari sarapan bersama besok pagi, atau saat malam sedang menonton TV. Tapi, ya, lagi-lagi, dia Aruna, wanita yang bisa membuatku melakukan hal diluar kebiasaan.
(Bersambung)
Restart ©2023 HelloHayden


 hellohayden
hellohayden







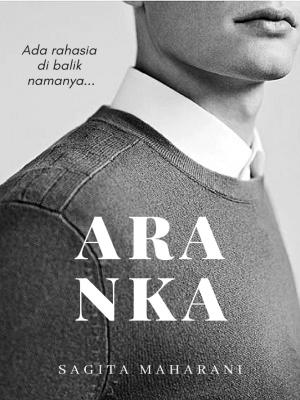





Baca cerita ini udah kayak masuk ke kedai all you can eat. Daging semua. Sbg cowok baca ini gk merasa aneh sama sekali untuk crita roman dan rasa kembali ke masa kuliah. Mantap lah
Comment on chapter Bab 14 (Cukup)