"Ambruknya balkon dari Gedung II ini setidaknya membuat 72 orang mengalami luka. Belum diketahui apakah jatuh korban jiwa.”
Televisi yang menggantung tinggi hampir menyentuh plafon di apotek ini sedang menyiarkan berita terkini, gedung Bursa Efek Indonesia ambruk pada selasarnya. Aku mengangkat tangan untuk melihat jam, pukul 12.20, kurang satu jam lalu kejadian itu terjadi. Aku yang sedang menunggu obat pada sebuah apotek di sekitar studio lantas memikirkan alternatif jalan lain untuk sampai ke rumah Cak Son tanpa melewati Jalan Sudirman, menghindari macet dan ramai-ramai akibat reruntuhan. Setelah mendapatkan obat itu –daftar obat dari Aruna, yang mengejanya saja aku tidak bisa, mendengarkan penjelasan aturan makan dari apoteker kemudian memotret kantong obat ini dan mengirimkannya pada Aruna dengan teks tambahan: Udah, nih. Skrg mau ketemu Cak Son.
Aruna membalas dengan emoticon wajah kuning dengan mulut maju seolah memberikan ciuman ditambah teks: Aku lagi makan bareng anak ibu ini. Kamu Jangan lupa makan siang.
Kemudian segera melesat ke rumah Cak Son menjemput pesanan kami yang entah keberapa sejak pertama kali. Makin bertemu Cak Son makin tampak pulih dan sepertinya dia berniat memanjangkan rambutnya lagi. Badannya sudah berisi, kulitnya yang agak coklat itu dulu pucat sehingga kusam kini tampak cerah dialiri darah, wajahnya berseri menampilkan semangat, yah, walaupun kesetiaannya pada bir belum berkurang. Dia pernah meminta dua krat bir botol sebab pesanan kami memiliki tingkat kesulitan yang tinggi.
Sesekali saat pekerjaan tidak banyak, aku dan Ares datang bersama ke rumah Cak Son. Dia menyebut Ares si Portugis, sebab secara umum Ares memiliki struktur wajah bak pria barat daya Eropa. “Gua yang setengah bule justru berwajah pribumi”, ujar Cak Son. “Inlander”, Ares menimpali. Tidak terima sebutan Portugis dilekatkan pada dirinya sehingga Ares membalas candaan Cak Son tak kalah historical dan terdengar kolonialis mengingat bangsa yang pertama kali menjajah Indonesia adalah Portugis. Aku sesekali ikut tertawa ketika Cak Son selalu menambah kata sifat di depan ‘portugis’ itu kepada Ares, sesuai hati Cak Son atau sesuai keadaan, misal, Cak Son tahu Ares sering bergonta ganti pacar, maka dia akan memanggil Ares si Casanova Portugis atau saat Cak Son tahu Ares suka mabuk walau tidak kuat minum alkohol maka namanya berganti menjadi si Bajingan Portugis. Orang Madura memang terkenal dengan humor mereka yang blak-blakan. Mereka sering menggunakan humor untuk mencairkan suasana atau untuk bercanda dengan orang lain. Walau begitu Ares sudah tidak menampiknya lagi, dia terima saja dan mulai terbiasa, selain memang Cak Son lebih tua dan senior kami juga. Setidaknya kami senang bahwa Cak Son sudah jauh lebih baik walau sampai hari ini penyakit yang menggerogoti jiwa dan raganya masih menjadi rahasia dan kami juga tidak pernah punya keinginan untuk bertanya.
Sampai di studio, kehadiran Kak Ami cukup mengejutkan sebab dia tampak emosional berbicara kepada Ares. Aku langsung duduk di samping Ares, mendengarkan keluh kesah Kak Ami tentang kurangnya interaksi pelanggan dengan sosial media pabrik garmen kini, sejak nyaris tiga bulan tidak bekerjasama dengan kami lagi. Akhirnya aku dan Ares memutuskan untuk melepaskan pabrik garmen karena sama sekali tidak menguntungkan, bahkan sebenarnya menekan Gammares. Aku paham benar bahwa keputusan itu bukanlah suara dari Kak Ami, keputusan perusahaan tidak hanya berfokus pada satu orang, walaupun dia bertindak sebagai kepala marketing perusahaan. Sedikit banyaknya melihat Kak Ami kalut nyaris berhasil mengesampingkan bahwa kami rekan kerja, dalam beberapa menit sebelumnya aku menganggap dia sebagai teman.
Ares banyak diam, tatapannya padaku mengatakan lu aja yang ngomong. Tentu aku hanya bisa memberikan saran yang terbatas. Bukan sebagai teman, tetapi sebagai orang yang pernah menjadi rekan. Kak Ami paham sepenuhnya bahwa jawaban dan saran yang aku berikan tidak memuaskan keluh kesahnya, lalu dia diam. Mengangguk dan dengan uluran tangan dia pamit kemudian mengucapkan terima kasih telah mendengarkan.
“Yah? Gimana, ya? Dana minimal tapi mau hasil maksimal. Kalau masih bisa dibantu sih gua oke aja. Tapi ini udah eksploitasi namanya.”
Kata Ares saat Kak Ami sudah melajukan motor matic nya.
Aku minum, haus, bertambah-tambah lagi sebab kopi pekat pahit yang disuguhkan Cak Son tadi kemudian kami makan nasi padang yang telah Ares belikan. Hampir saja aku lupa meminum obat kalau saja Ares tidak menanyakan.
“Widih! Manja amat! Tiga macem buat lambung doang!” ejeknya melihat aku mengeluarkan obat satu per satu.
“Nenek gua nggak begini-begini amat obatnya,” ujar Ares lagi sambil ikut membaca aturan makan obat-obat itu. Dia cengar-cengir.
“Gak tau, ini yang Aruna tulisin,” jawabku
Ares tertawa, “Lagian emang pedes, sih waktu itu. Gua aja sampe rumah bocor.”
Kami sedang membicarakan undangan makan tahun baru dari Pak Adimas. Saat kami datang, beberapa rekan Pak Adimas sudah hadir dan teman-teman Tyas yang semuanya perempuan juga hadir. Tidak banyak, hanya sekitar sepuluh orang di ruang private restoran. Hampir seluruh hidangan terasa pedas. Anehnya Pak Adimas dan keluarga menyantap dengan makanan hingga piring tandas, kecuali istrinya, toleransi lidah ibu itu terhadap pedas sepertinya tidak sekuat Tyas dan Pak Adimas. Tamu-tamu lain yang lebih tua tampak terpaksa mengunyah, malah kebanyakan diantara mereka hanya menyantap makanan penutup yang memang manis, memilih aman. “Enak”, jawaban para rekan Pak Adimas saat ditanya mengenai rasa tiap menu makanan. Aku dan Ares yang memang duduk bersebelahan saling tendang menendang di bawah meja, menahan gejolak tawa melihat wajah-wajah tua itu bercucuran keringat namun tetap berusaha tersenyum. Istri Pak Adimas walaupun sedikit lesu, tapi tetap berusaha ramah walau dia tidak meninggalkan kursinya saat kami dan rekan-rekan lain berjabat tangan kepadanya untuk pamit pulang.
Siang ini nasi padang terasa semakin pedas sebab cuaca panas. Handphone-ku berdering. Sebenarnya enggan berbicara saat sedang makan, terlebih saat ini aku benar-benar lapar. Namun pada layar tertera jelas nama teman sekelas yang jarang sekali menghubungi sehingga aku menganggap bahwa telepon ini penting. Dia yang kini mengajar multimedia di salah satu SMK swasta di Bogor akan mengadakan seminar kreatif untuk siswa pada bulan depan, tepatnya tanggal 15 Februari dan memintaku untuk menjadi pemateri.
“Bawa temen. Kalau bisa cewek biar murid gua yang cowok-cowok pada semangat,” ujarnya terkekeh.
“Lu atau murid lu?” godaku.
“Gua juga dong!” Lalu dia tertawa.
“Siap!”
Teman itu mengirimkan pesan berupa brief acara tersebut tidak lama setelah dia menutup telepon.
“Gua ikut!” kata Ares tiba-tiba bahkan sebelum aku menjelaskan apa-apa.
“Gua bakal ajak Trisna, bukan lu.”
“Justru karena gua tau lu bakal ajak Trisna makanya gua ikut!”
“Ah! Ntar Trisna malah gak mau kalau tau lu ikut!”
Ares menatapku dengan wajah dan mata penuh permohonan. Sebetulnya dibuat-buat. Melihat itu bulu-bulu wajahku berdiri. Geli.
“Dih!” seruku.
Ares tertawa memperlihatkan isi mulutnya: nasi dan lauk pauk yang sudah tidak berbentuk –cenderung menjijikkan. Melihat itu perutku terasa tidak enak, mual.
“Ntar, deh! Gua juga belum tau bisa atau enggak,” kataku sambil berdiri membuang bungkus makanan.
Sepanjang sore saat tengah sibuk dengan akuarium, air dan segala properti untuk foto ‘segar’ katalog brand parfum, Ares terus mengoceh dan setengah mendesak agar aku menyetujui untuk mengisi acara seminar tersebut, tujuannya sederhana: dia ikut. Dia sampai-sampai memeriksa tanggal 15 di bulan Februari, lalu mendapati bahwa sehari setelahnya adalah libur Tahun Baru Imlek yang jatuh pada Jumat. “Wah! Long weekend! Sayang banget gak liburan!” ujarnya seolah kalimat itu mampu mempengaruhi keputusanku –walaupun sebenarnya iya. Aku menyadari bahwa kami belum pergi kemana-mana lagi sejak terakhir aku dan Ares berlibur bersama teman-teman lain mendaki gunung Andon. Itu pada libur semester empat, lalu sebelum kembali ke Jakarta Ares mengajak menginap di rumah neneknya yang memiliki meja makan bak restoran. Saat datang tepat jam makan siang, dengan tampilan khas pendaki yang turun gunung: kumal, kurus dan kelaparan, kami berlima disambut dengan hidangan yang beragam dan enak. Sopan santun di meja makan sudah tak diindahkan, kami makan seperti orang kesetanan. Tante Suryani, seseorang yang menjaga nenek Ares sangat pandai memasak. Ares sangat menyayangi neneknya, begitupun sebaliknya. Mungkin neneknya lah satu-satunya keluarga yang selalu mendukung keputusan Ares mengambil jurusan DKV. Ares juga satu-satunya keturunan yang mewarisi darah seni dari neneknya. Selain meja makan bak restoran, dinding di rumah itu sudah seperti galeri seni. Bermacam lukisan lanskap kota atau bahkan seascape tidak sedikit terpajang dengan indah. Diantara lukisan yang menyuguhkan pemandangan, terselip satu potret kakek Ares sedang mengenakan atribut khas insinyur. Tanpa bertanya pun aku yakin itu adalah goresan tangan nenek Ares.
“Gua belum pernah ke Munasain. Deket kan dari rumah lu?” tanya Ares yang masih memegang ponselnya dengan getol mencari-cari tempat wisata. Ah! Ke museum boleh juga. Terbesit ide untuk mengajak Aruna mengingat kami sama sekali belum memiliki liburan bersama.
“Ntar aja, tuh. Bantuin gua, susah ini sendiri. Reflektor coba naikin dikit ke kiri,” pintaku setengah berseru sebab sedari tadi bolak-balik kamera dan set latar basah-basahan.
Ares berdiri, kemudian membantu menaikkan reflektor, “Tapi kayaknya masih kontras. Ntar ntar.” Ares meraih satu diffuser yang bersandar di dinding dekat dengan reflektor dan memegangnya persis di depan lampu tungsten.
“Majuin dikit, Res,” ujarku saat tengah fokus mengambil foto terbaik untuk produk parfum ini.
“Nah …, gini lebih halus cahayanya,” ujar Ares saat aku mendekatinya untuk memperlihatkan hasil foto produk. Walau setelah itu Ares yang belum puas dengan ceritanya mengenai museum masih meneruskan ocehannya dengan membaca review pengunjung pada google maps. Aku yang tidak ingin mematahkan semangatnya yang juga belum tentu tentu jadi pergi atau tidak, lantas memilih diam saja.
Tidak lama Tyas masuk.
Ocehan Ares terputus.
Tyas datang dengan membawa buku yang dia pinjam dariku untuk dikembalikan sebab lusa siang dia sudah harus berangkat ke Yogyakarta, libur semester telah berakhir.
“Thanks, Kak!” ujarnya tegas sambil mengulurkan buku tentang digital marketing. Tyas ini jarang tersenyum, dia hampir selalu serius bahkan saat bercanda. Rambut panjang sepinggangnya dia bawa ke belakang semua dan diikat tinggi. Signature style-nya sporty dengan pilihan warna netral. Gaya bicaranya walau serius, namun tidak kaku. Dia lebih sering menyelipkan kata dalam bahasa inggris. Entah kenapa kalau dia yang mengatakannya justru terdengar modern di saat orang lain malah terdengar sok keren. Misalnya, dia sering mengatakan “no biggie” untuk membalas ujaran terima kasih atau akan mengatakan “in a pickle” jika dia dalam situasi yang menyulitkan. Lebih seringnya aku mendengar dia berkata seperti itu jika seseorang menanyakan mengenai progres skripsinya. Secara umum, Tyas terlihat seperti perempuan mandiri yang penuh percaya diri. Aku berani taruhan, jika suatu saat alien menginvasi maka Tyas akan menjadi salah satu pejuang perempuan yang ikut menyelamatkan bumi.
“Tyas, mobil masih nyala deh kayaknya,” Ares mengingatkan Tyas karena lampu mobil merahnya masih berkedip.
“Oh. Iya. Trisna di mobil. Gak mau turun dia,” jawab Tyas ringan sambil memperhatikan pekerjaan kami.
Mendengar itu, Ares langsung berdiri dan berlari tergesa keluar, masuk mobil Tyas.
“Heh! Kenapa tuh Kak Ares?” tanya Tyas yang terkejut.
“Ada perlu sama Trisna kali,” jawabku sedikit terbata-bata tidak tahu akan memberikan alasan apa. Aku berusaha tenang walau sebenarnya khawatir jika Tyas bertanya lebih.
“Oh, oke. Fine.”
Jawaban Tyas melegakan. Setidaknya aku tidak perlu memutar otak memikirkan alasan yang tepat akan sikap Ares barusan yang lagi-lagi impulsif. Melihat respons Tyas, sepertinya keluarga Pak Adimas tidak mengetahui akar permasalahan antara Ares, Trisna dan Rian, pacar Trisna.
Cukup lama, sekitar lima belas menit, Ares baru keluar dari mobil. Ares masuk dengan wajah kusut kemudian dia minum dan menghempaskan diri pada sofa. Tyas tampak tidak begitu peduli dengan urusan mereka. Dia hanya heran melihat Ares yang kini diam. Aku keluar mengantar Tyas ke mobil, belum berbicara dengan Trisna mengenai rencana narasumber seminar, aku sendiri masih ragu bisa atau tidak.
Menjelang maghrib, Aruna tampak turun dari ojek online tepat di depan studio. Dia masuk seperti biasa, langkah yang ringan dan senyum mengembang. Kali ini dia menenteng bungkusan yang ternyata berisi es krim. Melihat Aruna, akhir-akhir ini suasana hatiku tidak baik, sejak dua minggu lalu, sejak aku menemukan bingkisan dari seseorang yang tidak aku tahu.
Siang sekitar jam satu, Ares masih pulas di sofa dengan mulut sedikit terbuka. Dengkurannya terdengar kuat. Aku sudah bangun dan sudah mandi, sedang duduk di kursi kerja sambil menatap bingkisan merah muda yang diletakkan seseorang di depan pintu Aruna. Kertas bertuliskan catatan itu masih aku pegang, dengan keyakinan besar bahwa ini adalah tulisan tangan laki-laki. Deretan hurufnya tegas, tidak rapi dan terkesan ditulis saat buru-buru. Berkali-kali aku memikirkan ulang untuk membuka bingkisan ini, melihat isi didalamnya apakah membahayakan Aruna atau justru menyenangkan bagi Aruna. Sayangnya, kedua pilihan itu tidak ada yang membuatku tenang. Cukup lama aku dilema moral antara membuka bingkisan ini atau tidak. Semakin aku meyakinkan diri untuk melihat isinya, aku semakin aku gusar. Tapi jika tidak, aku yakin aku akan mati penasaran. Kotak ini juga dihiasi oleh pita pengikat dengan warna senada. Tentu seseorang dengan tulisan sejelek ini bukanlah orang yang bisa menyimpul ikatan seindah ini. Simpulan pita ini sudah pasti hasil dari tangan lihai penjaga toko souvenir. Akhirnya dengan mengesampingkan moral dan membunuh gusar, aku mengangkat tutup bingkisan. Sebuah jam tangan digital berwarna putih dari merk yang terkenal namun tidak begitu mahal tertata rapi. Aku mengambil jam tangan itu segera, menelisik setiap sudutnya apakah ada semacam alat pendeteksi atau kamera tersembunyi. Nihil. Ini murni sebuah hadiah dengan catatan kasih sayang. Aku taruh rapi kembali jam itu, menutupnya, mengikat pita kembali dan menyelipkan catatan pengirimnya seperti sedemikian kala, sebisanya. Pertanyaan selanjutnya dan sudah menjadi pertanyaan pertama sejak bingkisan ini ada, dari siapa ini?
Sengaja bingkisan ini aku simpan untuk kemudian aku letakkan di tempat pertama kali ini ditemukan. Aruna tidak mengatakan apa-apa mengenai bingkisan ini, tidak menelepon untuk bertanya apakah ada sesuatu di depan pintu kamarnya. Aku juga memutuskan untuk tidak mengatakan apa-apa padanya mengenai hal ini. Berharap dia akan mengatakan sendiri pengirim hadiah ini atau malah lebih baik justru dia juga bertanya-tanya siapa pengirimnya. Aku menyempatkan mengambil kamera, memfoto bingkisan merah muda ini. Aruna akan kembali sore nanti. Sebelum aku pergi memenuhi undangan Pak Adimas, aku letakkan bingkisan ini di depan pintu Aruna. Ares sempat bertanya, aku menjawab seadanya bahwa itu sebuah kejutan.
Hal yang aku amati secara diam-diam dari kisah asmara teman-temanku adalah seseorang yang berselingkuh akan berubah menjadi salah satu dari dua sikap ini: lebih perhatian atau lebih cuek bahkan kasar. Kedua sikap itu tidak terjadi pada Aruna. Tidak ada yang berubah darinya baik sebelum atau sesudah menerima bingkisan itu. Perhatiannya tetap sama, tidak berlebihan, bahkan cueknya juga sama, tidak lebih abai. Masalah lain yang muncul beriringan dengan sikap Aruna yang biasa-biasa saja adalah mungkin dia sudah tahu siapa pengirimnya. Dia tahu bingkisan itu bukan dariku. Dia tidak bertanya dan tidak mengatakan apa-apa sama sekali. Entah bagaimana cara dia mengonfirmasi siapa pengirimnya.
Jam tangan itu tidak pernah dia kenakan kecuali hari ini. Kini pergelangan tangan yang menenteng bungkusan itu dihiasi dengan arloji putih pemberian dari seseorang yang masih menjadi misteri. Entah pria atau wanita, entah tua atau muda, entah teman atau sahabat, entah keluarga atau kerabat, atau kekasih? Entahlah.
“Wih! Es krim! Mau ya,” kata Ares sambil memeriksa bungkusan dari Aruna.
“Ambil aja. Emang buat kalian, kok!” jawab Aruna cepat.
“Nih, Gam …,” Aruna menyuapi es krim kepadaku.
“Kamu aja, aku kenyang,” jawabku kurang bersemangat. Aku gondok hanya dengan melirik jam itu.
“Oh, ya udah … aku abisin, ya?” Aruna menyuap es krim itu dengan kakinya bergoyang ringan, entah kepala atau kaki nya akan bergerak tanda keriaan sebab makananya enak.
“Kamu jam baru, ya?” tanyaku mengambil tangannya sesudah menyuap es krim. Aku mencoba menelisik.
“O-oh? Ini? Udah lama, baru pakai aja,” jawab Aruna sedikit terbata-bata. Dia segera menarik tangannya dan menyendok es krim lagi.
Bohong!
Aku dongkol.
“Oh, ya? Sejak kapan punya ini?” tanyaku lagi sambil berusaha menekan raut kekesalan.
“Udah lama, aku lupa.”
Bohong lagi!
Hah~
Jelas sekali Aruna berusaha tetap tenang disaat wajahnya mulai tegang. Dia tampak tidak siap dengan pertanyaan, sehingga saat dia menyendok es krim lagi menjadi salah tingkah. Keceriannya terhadap es krim itu drastis berkurang, kini dia mengaduk-aduk es dan terlihat sedang berpikir.
Aku membuang wajah dari Aruna yang makin dilihat makin gugup. Ares di depanku kini sedang sibuk mengais-ngais es krim dalam cup yang berubah menjadi susu coklat. Sendok kayu itu terlalu kecil untuk Ares. Lalu aku melempar pandanganku ke sisi lain, melepaskan raut kesal yang sedari tertahan, berdehem membersihkan gumpalan dongkol dari tenggorokan kemudian dan membuang nafas sedikit kasar.
Selama ini, setidaknya hingga dua puluh tiga tahun ini, aku berfikir bahwa tidak ada kesalahan orang lain terhadapku yang benar-benar meninggalkan perasaan mengganggu. Aku selalu mampu memaafkan dan melangkah tanpa ditahan oleh amarah. Tapi hari ini aku sadar dan menemukan hal yang mampu menguliti perasaan hingga berbiji benci: dibohongi. Perih tak terperi, terlebih kebohongan itu keluar dari mulut orang yang aku sayangi.
Mataku liar bergerak kanan dan kiri berkali-kali menggambarkan hati yang risau sebab pikiran buruk mulai merambat masuk. Bisa saja ini bukan yang pertama kali. Bisa saja. Bisa jadi?
Kebohongan Aruna mungkin saja untuk menutupi kenyataan lain yang lebih menyakitkan. Ketidaksukaan atas kebohongan menuntunku kepada kemarahan yang mengantarkan fikiran-fikiran buruk lain. Ada kemungkinan bahwa Aruna telah mencederai kepercayaan yang sepenuhnya aku berikan. Sebelum hari ini, selama dua minggu belakangan aku cukup tenang karena masih menganggap Aruna membuang jam itu lengkap dengan kotaknya dan catatan dengan tulisan tangan jeleknya, untuk menghindari kecurigaanku, untuk melindungi hubungan ini. Nyatanya bukan, itu semua hanyalah tindakan yang aku harapkan dari Aruna. Aku terlalu cepat menyimpulkan. Kini jam itu dia kenakan dan dengan entengnya berbohong padaku untuk melindungi jam itu. Oh, bukan! Mungkin untuk melindungi orang di balik jam itu.
Kacau!
“Gam?” telapak tangan kecil Aruna menepuk pundak, membuatku terkejut diantara badai pikiran dan perasaan yang secara masif bersamaan menyerang.
“Ya?” jawabku segera menoleh.
“Ares manggil, tuh, dari ruang kerja. Kamu lamunin apa?”
Aku melihat ke arah Ares duduk tadi, entah sejak kapan dia pergi untuk melanjutkan pekerjaan. Bahkan dipanggil pun aku tidak sadar.
“Aku ke Ares dulu.”
Aku bangkit, lalu segera menyusul Ares, melanjutkan pekerjaan dengan berusaha menepis pikiran yang menjerumuskan.
Selama perjalanan pulang, Aruna dan aku tidak banyak bicara bahkan sampai Aruna menyiapkan makan malam nasi goreng untuk kami berdua. Sesekali Aruna bercerita mengenai pekerjaannya, bahwa anak ibu yang dirawatnya sangat baik. Ibu itu terlihat lebih semangat sebab anaknya kembali dari luar kota.
“Seingat aku, anaknya perempuan, kan?” tanyaku memastikan, berusaha mencoret daftar-daftar orang yang aku curigai.
“Yang pulang yang perempuan. Aku gak pernah lihat anaknya yang laki-laki,” jawab Aruna lagi.
Aku mengangguk.
Bukan dia.
Tidak lama handphone Aruna berdering, dia mengangkatnya. Dari pembicaraan, sepertinya itu adalah urusan kampus atau pekerjaan, sebab hanya terlompat kata-kata yang hanya menjurus pada dua hal tersebut. Sesekali Aruna tertawa. Dadaku kembang kempis melihat Aruna seperti itu, bicara-bicara-tertawa-bicara-bicara-tertawa.
“Siapa?” tanyaku saat telepon itu ditutup.
“Reza. Reza si culun kalau kamu bilang.”
“Si culun udah jam sepuluh gini nelpon buat apa?”
Aruna sedikit terkejut mendengar pertanyaan yang selama ini hampir tidak pernah aku lontarkan. Aku tidak pernah mendikte Aruna mengenai siapa saja yang boleh berteman dengannya, jam berapa saja dia boleh menerima telepon, bahkan pertanyaan siapa yang menelepon mungkin hanya sekali atau dua kali sempat terucap, itu pun dalam keadaan santai, dan jawabannya selalu Bu Sarah. Kini aku bertanya seperti itu dengan dahi berkerut dan suara yang berat.
Aruna yang tadi tampak terkejut kini mulai menyunggingkan senyum, dia mengusap pangkal lenganku, “Tadi aku yang nelpon dia duluan, pas tungguin kamu di studio. Gak diangkat. Kami sama-sama masukin lamaran ke rumah sakit binaan kampus aku. Kamu tahu, kok. Tapi sampai sekarang belum ada kabar. Aku nanya, mungkin aja dia dapat kabar,” jelas Aruna panjang lebar berusaha menepis kekhawatiran yang mungkin tampak jelas pada wajahku.
Kami bertatapan, Aruna dengan tenang, aku dengan gusar.
“Kamu udah makannya?” tanya Aruna mengalihkan pandangannya ke piringku yang tidak tandas.
Aku mengangguk, lalu membereskan peralatan makan kami: piring Aruna yang tandas, satu gelas (sebab kami minum dari gelas yang sama), teko, dan piringku. Membawanya ke basin cucian piring. Aruna sudah siap dengan keran menyala, mencuci piring. Lalu aku kembali ke tempat kami makan tadi, membersihkan lantai dari remahan, noda minyak bahkan tetesan air menggunakan tisu. Kami selalu kompak dalam segala hal baik dari pekerjaan kecil seperti ini hingga paling besar adalah menjadi bahan praktik Aruna atau saat Aruna membantu pekerjaanku. Rasanya tidak mungkin kekompakan ini dikhianati dengan permainan kekanak-kanakan –perselingkuhan.
Tiba-tiba ujaran Robert Capa melintas di pikiran, if your pictures aren’t good enough, you’re not close enough. Aku sampai-sampai berhenti membersihkan lantai.
Secara harfiah, Capa mendorong para fotografer untuk mendekati subjek mereka secara fisik. Hal ini memungkinkan mereka untuk menangkap detail yang lebih intim dan emosional, serta membangun koneksi yang lebih kuat dengan subjek. Ini bukan hanya tentang jarak fisik, tetapi juga tentang kedekatan emosional. Aku menyadari, mungkin selama ini aku terlalu sibuk sehingga abai terhadap hal-hal trivial. Aku sudah terbiasa untuk tidak ikut campur apa-apa jika memang aku tidak turut serta di dalamnya. Aku bahkan tidak kenal teman-teman Aruna selain yang memang pernah datang atau bertemu, itupun secara tidak sengaja, seperti Si Culun Reza atau Gina yang kebetulan junior Aruna dan tetangga kami di lantai dua. Lantas seorang lagi, Si Rama, pria yang mengekori Aruna saat aku jemput dan yang dengan kurang ajar mengantar Aruna pulang menerjang hujan. Aku yang disibukkan dengan urusan pekerjaan dengan sepenuh hati mempercayakan hubungan ini kepada Aruna. “Gam? Obat nya nih yang sesudah makan,” panggil Aruna dari pantry.
Lagi-lagi lamunanku dikejutkan oleh suara Aruna yang memanggil. Aku bangkit, mendekati Aruna segera. Dia sudah siap dengan sendok berisi cairan hijau muda –obatku.
Aruna sedikit membuka mulutnya sambil menyodorkan sendok itu ke mulutku, berharap aku mengikutinya, membuka mulut dan menelan obat. Aruna mengulurkan segelas air setelahnya.
Jam putih itu tergeletak di rak berdampingan dengan bumbu-bumbu dapur. Aruna tadi mungkin saja buru-buru melepasnya dan menaruh sembarangan sebab segera ingin masak. Aku ambil jam itu lalu meletakkannya pada meja belajar Aruna, bersisian dengan jam analog bertali kulit coklat yang biasa dikenakan.
“Ini jam baru,” ujarku sambil meletakkan jam itu.
Aruna menghampiri dengan tanda tanya besar di kepala kemudian gugup setelahnya.
“Kamu gak mahir bohong, gak lihai sama sekali dan gak cocok bohong. Intinya kamu bukan pembohong,” aku menatapnya, “tapi kamu mungkin penyimpan rahasia yang andal,” kataku segera sambil berusaha mati-matian menekan emosi, meredam kekesalan dan rasa benci karena dibohongi.
Aruna terkesiap.
“Aku yang nemuin bingkisan merah muda itu duluan, pas kamu masih di Tangerang. Aku baca catatannya. Aku juga tahu isinya apa,” ujarku sambil kembali mengambil jam putih, “ini, kan?” memperlihatkannya ke wajah Aruna yang masih diam tegang membeku, cenderung tidak reaksioner.
“Dari siapa?”tanyaku.
Aruna diam seolah tidak percaya apa yang baru saja dia dengar.
“Siapa yang diam-diam ngasih kamu hadiah?” tanyaku kini duduk pada kursi belajarnya. Mendongak kepadanya yang berdiri di depanku.
Aruna mendekat. Aku mencari-cari apa yang terkandung dalam pikirannya dengan menatap lekat sepasang matanya.
“Siapa orang yang menuliskan catatan ‘menyayangimu selalu’ itu?”
Aku sudah tidak tahan dengan monolog lagi. Sedari tadi dia diam membiarkan kata-kataku berhamburan tanpa mendapatkan jawaban.
“Aruna, sebenarnya apa yang kamu rahasiakan?” tanyaku sambil berdiri sebab mulai tidak tahan dengan pilihannya untuk tetap bungkam.
“Gak tahu,” akhirnya Aruna mengeluarkan suara, walau parau dan hampir menangis.
“Kamu beneran gak tahu atau mau melindungi orang itu dengan cara bohong ke aku?”
Aruna menggeleng, “Aku gak bohongi kamu, Gam,” ucapnya lemah. Kemudian dia berjalan ke lemari, membukanya dan merogoh-rogoh bagian bawah dari baju yang digantung. Dia kembali dengan dua kotak dan meletakkannya di meja belajar. Dua kotak merah muda, berbentuk persegi panjang dan lebih besar dari kotak yang aku temukan.
“Notes nya ada di dalam,” jelas Aruna lagi sambil mempersilahkan aku membuka bingkisan-bingkisan itu.
Aku kembali duduk dan membukanya bergantian. Di dalam satu kotak terdapat tas selempang dari kulit berwarna coklat muda dengan tulisan nama Aruna pada talinya. Ini jelas sekali tas yang dibuat khusus dan terdapat satu catatan kecil dengan kertas putih selebar telapak tangan. Kulit pada tas itu sudah mulai terkelupas pertanda tersimpan lama di tempat pengap. Kotak lainnya berisi cermin dekoratif dan sebuah catatan dengan kertas berwarna merah muda. Keduanya ditulis dengan tulisan tangan yang sama jeleknya, kata ‘menyayangimu selalu’ itu selalu menjadi penutup pada setiap catatan, bedanya pada kertas berwarna putih yang aku perkirakan adalah bingkisan pertama yang datang, bertuliskan selamat atas diterima sebagai mahasiswi keperawatan sedangkan kertas berwarna merah muda bertuliskan selamat karena telah pindah ke tempat lebih baik.
“Paket itu aku temuin sore sebelum kita makan mi pertama kali di kamar aku,” tunjuk Aruna pada kertas merah muda.
Mendengar itu, aku semakin resah. Menghela napas dan menggaruk-garuk sebelah alis sambil melihat tiga benda dari pengirim misterius yang aku jejerkan di meja.
“Kamu gak pakai tas ini dan gak pajang cermin ini,” tanyaku pada Aruna yang berdiri di sisiku, “tapi kenapa kamu pakai jam ini?”
“Urusan mendesak. Jam aku tiba-tiba gak nyala, mungkin masalah baterai atau yah, memang rusak, udah lama juga, kan? Selama jam kerja merawat ibu itu, aku gak boleh pegang handphone kecuali pas makan siang dan sholat. Aku perlu jam untuk pantau tanda-tanda vital, waktu pemberian obat dan mencatat waktu aktivitas pasien,” jelas Aruna dengan tenang.
Tiga barang yang diterima Aruna bukanlah benda-benda personal yang butuh ukuran khusus si pemakainya. Bukan seperti baju atau sepatu. Ini berarti pengirimnya tidak terlalu dekat secara emosional dengan Aruna sehingga tidak bisa bertanya langsung dan tidak terlalu dekat secara fisik sehingga dia tidak bisa memperkirakan. Cukup melegakan mengetahui Aruna tidak memakai dua pemberian sebelumnya, kecuali jam tangan ini untuk urusan mendesak.
Bingkisan demi bingkisan tanpa identitas pengirim ini sudah menjelma menjadi teka-teki. Warna favorit Aruna, profesi perawatnya, alamat kost lamanya, bahkan kepindahannya—semua diketahui oleh si pengirim misterius ini. Siapa dia? Bagaimana dia bisa mengetahui tentang Aruna? Apa dia seseorang yang berada di sekitar Aruna? Atau mungkin penguntit yang membahayakan? Belum lagi setiap kertas dengan tulisan ‘menyayangimu selalu’ itu yang benar-benar mengganggu.
Rasa sayang katanya? Astaga!
Ini sudah seperti pergulatan dengan angin, tidak tampak dan tidak terjamah, namun terpaan yang diberikannya cukup kuat sehingga aku harus berusaha tetap tegap agar tidak terjatuh.
“Sejak bingkisan pertama datang kamu pernah dikirimi pesan atau ditelpon orang yang gak kenal?” tanyaku.
“Kalau konteksnya ini, gak pernah.”
Aku membawa semua rambutku kebelakang, tanganku berhenti pada tengkuk yang mulai tegang dan memijat-mijatnya. “Aku khawatir ini bakalan membahayakan suatu saat,” kataku, “kamu kenapa baru cerita?”
“Entahlah. Aku cuma gak mau nambah beban pikiran kamu. Kamu itu udah capek urusan studio. Lagian sejak awal ini masalah aku. Selama ini baik-baik aja, gak ada kejadian aneh sejak bingkisan pertama ada,” jelas Aruna lagi sambil menatap tiga hadiah itu.
“Ini masalah aku juga sekarang. Kamu gak boleh anggap ini masalah sendiri,” tegasku padanya. Matanya beralih kepadaku kemudian mengangguk-angguk pelan sambil mengatup rapat kedua bibirnya. Aruna tampak memikirkan situasi yang kami hadapi, pandangannya kesana-kemari sambil masih berkali-kali mengangguk pelan.
“Runa, setahun lebih ini kita pacaran, kan?” aku menatapnya khawatir.
Aruna yang paham kegelisahanku itu mulai tersenyum sambil mengangguk.
“Walau kamu pikir aku capek atau kamu anggap bukan masalah besar, kamu ceritakan aja. Seenggaknya aku merasa dipercaya dan diandalkan. Kita ini pasangan.” kataku sambil menggenggam erat tangannya. Aku mendongak melihat dia yang berdiri di depanku kini. Aruna membawa kepalaku ke dalam pelukannya, mencium kepalaku berulang kali, mengusap punggungku sambil menyampaikan permintaan maaf. Aku tahu permintaan maaf itu tulus dari hati sebab suaranya bergetar.
“Kamu gak suka kalau aku ejek pas nangis. Tapi dikit-dikit nangis,” kataku ikut melingkarkan tangan pada pinggangnya dan membuat diriku nyaman bersandar dalam pelukannya.
“Aku gak nangis!” ujarnya setengah berseru, setengah merajuk.
Aku tertawa pelan. Lalu beberapa saat kami diam menikmati hangatnya pelukan.
“Kamu tahu. Kita dua orang berbeda. Hal-hal sulit yang kita lewati juga gak sama. Pendidikan dan pekerjaan kita udah jelas gak saling berkaitan. Tapi semua perbedaan itu disatukan sama cinta. Kalau bukan kepercayaan yang menguatkan kita, apa lagi sisanya? Gak ada. Kita juga cukup dewasa untuk ta-”
Aruna menjauhkan kepalaku dari dekapannya, memegang kedua pipiku. Aku mendongak memandangnya dengan perhatian penuh. Lalu dengan cepat bibirnya menutup bibirku, “kamu bilang I love you aja pakai muter-muter segala,” bisiknya. Bibirnya yang basah menyentuh telinga dengan lembut dan berhasil membuat darahku mengalir seperti air bah ke segala penjuru. Nafasku berat terasa memburu.
“Kita cukup dewasa untuk apa tadi?” tanya Aruna dengan senyum penuh makna. Sungguh menggoda.
“Untuk melakukan lebih dari ini,” kataku cepat sambil mengangkatnya naik duduk di pangkuan.
“Pasti tadi bukan itu,” katanya sambil mengusap lembut leherku dengan jari-jari halusnya.
“Sekarang itu,” jawabku.
Kami berbalas pandang. Sepasang mata coklat itu menatap sendu merayu. Aku memagut bibir kecilnya. Bibir itu terasa bagai susu strawberry yang disuguhkan pagi hari. Manis, basah dan menghangatkan dada. Denyut kuat terasa di kepala, darah terdengar berdesir di telinga, wajahku panas. Rasanya seluruh tubuhku bergelora dan ingin meledak segera. Bibirku turun untuk menciumi lehernya yang putih bersih dan wangi. Entah sejak kapan tapi tanganku sudah berada di balik kaosnya, meremas pinggangnya. Aruna membalas dengan meremas rambutku. Dia mengeluarkan nafas dari mulut seturut dengan suara yang tidak aku dengar darinya sehari-hari. Suara tipis yang justru membuat api pada diriku menebal dengan cepat. Panas. Aku tidak berkutik lagi dan sudah tidak mampu mengendalikan diri. Terus aku ciumi lehernya sampai aku merasa ada sesuatu yang mengganggu: basah dan asin. Awalnya aku pikir itu adalah keringat Aruna, namun aku salah. Saat membuka mata aku baru sadar bahwa leher Aruna merah sebab darah. Lalu aku dengan cepat berhenti, menahan darah yang turun dengan melintangkan telunjuk di kedua lubang hidung. Aku mimisan.
“Runa …,” panggilku pelan.
Aruna melihatku lalu tertawa pelan. Dia turun dari pangkuan, meninggalkanku yang duduk dengan wajah menengadah menahan aliran darah. Aruna ke kamar mandi dan keluar dengan leher yang sudah bersih dari noda merah. Lalu membawa kain lap basah dan membersihkan hidungku segera.
“Gemesin,” katanya sambil tersenyum jahil dan menyentuh ujung hidungku dengan telunjuknya. Gelora-gelora yang tadi kuat sekali menjalari tubuh, kini perlahan memudar hingga akhirnya hilang. Akhirnya kami berbaring di kasur kecil Aruna. Aku menggenggam erat tangannya dengan tenang tanpa terganggu oleh denyutan kepala dan rasa ingin meledak lagi.
Kami berpelukan sambil menatap dinding yang kini dihiasi oleh bintang-bintang bergerak dari lampu tidurnya. Sesekali Aruna membawa punggung tanganku ke bibirnya dan memberikan kecupan. Kami saling bercerita. Aku menceritakan keraguan tentang undangan mengisi seminar, mengajak Trisna yang seturut dengan keinginan Ares ikut dan rencana liburan.
“Jadi pemateri itu kesempatan baik, Gam. Kamu bisa bangun reputasi dari sana. Nambah pengalaman juga. Lagipula bagus untuk Gammares, peluang karir dan bisnis jadi lebih luas.”
Itulah mengapa aku bisa menyimpulkan bahwa Aruna mampu menjadi tempat berbagi segala impian yang perlahan sedang aku wujudkan. Dia mampu menggenapkan pikiranku yang ganjil. Saat aku ragu dia mampu mendahului pikiranku dengan cara tidak merusak ego yang ada dalam diriku sebagai laki-laki.
“Masalah aku bisa ikut atau enggak, aku tanyain dulu. Kalau gak salah tanggal lima belas itu mereka sekeluarga mau ke Pekanbaru. Merayakan kelahiran cucu pertama mereka,” jelas Aruna lagi mengenai keluarga pasiennya.
“Semoga aja kamu gak harus ikut mereka. Kita belum pernah liburan bareng,” kataku setengah sedih setengah mendesak dan setengah merengek.
“Iya, semoga aja,” ujarnya terkekeh mengetahui rengekanku.
“Aku pengen ajak kamu nginep di rumah, Ibu dan Marwa pasti seneng,” kataku.
“Aku juga kangen sama mereka, Gam.”
Lalu Aruna bercerita dengan keluhan mengenai kelelahan kerja akibat pasiennya sering mengalami kecemasan dan perubahan suasana hati dengan cepat akibat terlalu memikirkan penyakitnya. “Itu ngaruh banget ke motivasi pemulihannya. Makin lama sembuhnya,” ujar Aruna berdengus kesal.
Mataku terpejam sebab mulai mengantuk, aku manggut-manggut sambil mencium aroma segar rambut Aruna. “Ya ada bagusnya, sih. Kamu bisa kerja lebih lama, kan?” ujarku ringan.
Aruna menepuk tanganku yang melingkar memeluk pinggangnya, “Ya jangan dong! Masa pengalaman aku kerja cuma menangani satu pasien, itupun sebagai caregiver. Aku juga pengen kerja di rumah sakit besar.”
“Makin besar kerjaan makin banyak tekanan. Ntar kamu lampiaskan ke aku. Marah-marah,” aku mendekapnya makin erat.
“Emang pernah?” tanyanya berusaha menoleh ke belakang.
“Enggak. Belum tepatnya.”
“Tunggu aja kalau gitu.” Kata-kata Aruna terdengar yakin.
“Aku bakalan cium tiap kali kamu ngomel,” kataku.
“Yah, percaya gak percaya omongan begitu keluar dari orang yang mimisan karena ciuman,” Aruna menahan tawanya hingga perutnya bergetar.
Aku malu sendiri mengingat kejadian beberapa menit sebelum ini.
Ah! Cupu, Gam!
Malu merubungi.
“Nantangin, nih?” tanyaku mulai menggelitik pinggangnya.
Aruna menggeleng cepat sambil menggigit rapat kedua bibirnya menahan tawa takut suaranya akan terdengar hingga kamar 302, kamar Bu Dewi.
“Tidur! Tidur! Udah mau jam dua belas, tuh!” Aruna menunjuk jam dinding di atas jendela.
“Ngarang! Mana keliatan gelap gini …,” kataku tertawa kecil.
“Ya udah, tidur aja. Ngantuk juga.”
Aruna mulai menguap, lalu benar-benar tidur setelahnya.
Aku meraih selimut dan menutup badan kami berdua hingga dada dan kembali memeluknya.
Aruna dengan nyaman memeluk bantal strawberry-nya.
Aku mencium kepalanya dan berusaha tidur walau kembali diterpa pikiran bagaimana cara menemukan orang yang mengirimkan hadiah untuk Aruna.
(Bersambung)
Restart ©2023 HelloHayden


 hellohayden
hellohayden












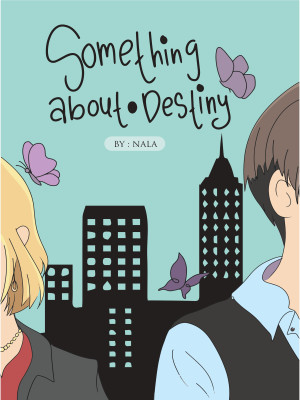
Baca cerita ini udah kayak masuk ke kedai all you can eat. Daging semua. Sbg cowok baca ini gk merasa aneh sama sekali untuk crita roman dan rasa kembali ke masa kuliah. Mantap lah
Comment on chapter Bab 14 (Cukup)