Hari-hari terasa cepat berlalu sebab aku kembali sibuk beberapa minggu terakhir. Beruntungnya setelah bertanya sana-sini, jangkauan pekerjaan lebih luas. Yah, walau tetap freelancer aku tetap bersyukur, setidaknya ini menghasilkan. Mulai dari pekerjaan kecil seperti acara ulang tahun sweet seventeen remaja-remaja yang gila tren sampai pekerjaan lumayan menyita tenaga seperti festival kuliner yang akan diadakan oleh salah satu brand kecap cukup terkenal. Acara itu nantinya banyak mengundang usaha kecil menengah untuk bergabung dan juga sebagai bentuk promosi usaha dagang mereka. Brand ini juga mengundang Kepala Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Pihak brand itu sendiri memintaku mencari rekan paling tidak dua orang lagi –sesuai kemampuan mereka membayar. Acara akan berlangsung dua hari, 19 dan 20 November, Sabtu dan Minggu ini. Aku berencana akan mengajak Ares dan Trisna pada pekerjaan kali ini.
“Lu ngajak Trisna?” Ares memastikan. Saat ini dia menemaniku bekerja memotret pakaian pada pabrik garmen. Sejak aku mengatakan akan mengajak dia dan juga Trisna siang tadi saat di kampus, Ares terus-terusan menghujam dengan pertanyaan yang sama. Tidak bosan-bosannya.
“Astaga. Iya! Lu budek apa gimana?” Aku sampai berhenti menekan tombol shutter kamera dan menoleh sebal ke arahnya yang duduk di lantai persis di belakangku. Dia terkekeh juga tersenyum girang, menaikkan kedua alisnya cepat. Usil. Aku tahu, dia sudah lama menyukai Trisna. Namun tidak seperti perempuan-perempuan lainnya yang berhamburan menghampiri Ares, Trisna seolah enggan berurusan dengannya.
“Lu ajak siapa, kek. Takutnya nih, gua berhasil jadian, nah, lu jadi nyamuk doang!” kata Ares lagi.
“Gak akan jadi nyamuk. Besok udah pasti sibuk. Awas aja kalo lu gak kerja,” ancamku, sambil sesekali melihat hasil jepretan.
“Dih, dibilangin. Tuh, ajak Aruna. Kemaren lu sampe gak nyusulin gua, hanya demi Aruna ….” Ada nada mencibir saat mengatakan hanya demi Aruna. Aku memang menceritakan kepada Ares alasan kenapa tidak jadi menyusulnya waktu itu ke AEON. Awalnya Ares kesal karena telepon dan pesannya tidak mendapat balasan, namun ketika mendengar saat itu aku bersama Aruna, Ares lantas senyum bangga. Gitu, dong! Sat set! Ujar Ares saat itu sambil menepuk pundakku.
Tentang usulan Ares untuk mengajak Aruna ke acara Sabtu besok, aku diam, seolah tidak mengacuhkan. Namun sebenarnya, pikiranku juga melayang ke arah yang sama. Sudah beberapa hari sejak makan mi instan bersama, tidak pernah lagi aku melihat Aruna. Belakangan ini aku pulang terlalu malam dan sepertinya dia berangkat kuliah lebih pagi. Bahkan sekadar berpapasan pun tidak. Aku ingin mengirim pesan padanya, namun khawatir akan terdengar berlebihan lantas aku memilih untuk membiarkan semuanya mengalir apa adanya.
Sebelum pulang, sambil beristirahat di sofa, aku menyempatkan menelepon ibu dan Marwa. Marwa bahkan sudah bisa tertawa lagi ketika aku menceritakan ulah Ares. Ares yang mendengar namanya disebut hanya bisa melirik sinis. Aku lega dan lapang mengetahui ibu dan adikku semakin dalam keadaan yang baik. Setelah aku mematikan telepon, terlihat pada layar handphone sebuah pesan masuk dari Bu Dewi :
‘Gamma, Saya bikin makanan. Punya kamu saya titip ke Aruna, ya? Ambil aja nanti’
Senyum lebar tidak terelakkan ketika membaca pesan itu. Seolah alam memberiku isyarat, mengetahui apa yang ada di pikiran. Tanpa ragu aku segera membalas pesan dari Bu Dewi, mengucapkan terima kasih atas makanan yang dititipkannya melalui Aruna. Namun, sejujurnya ucapan terima kasih itu lebih luas dari apa yang aku ketik, tidak hanya untuk makanan yang bu Dewi titip. Kata terima kasih itu jelas sekali sebagian besar karena Bu Dewi yang tahu saja, juga sepertinya sengaja mengikutsertakan Aruna.
“Res, gua balik!” ujarku buru-buru beangkit dan meraih ransel. Ares hanya menoleh sebentar karena tengah sibuk menggoda salah satu anggota tim di sana.
Selama perjalanan menuju kost, perasaanku terasa ringan, hatiku senang dan senyuman tipis juga tidak kunjung hilang. Sampai di parkiran dan sedikit berlari melewati Pak Yahya dan beberapa orang lain penghuni kost sedang kebingungan melihatku tergesa. Aku hanya melambaikan tangan pada mereka sambil berlalu. Terdengar salah satu berceletuk, “Lah? Mas Gamma buru-buru amat?”
Anak tangga kali ini terasa lebih banyak dari biasanya. Saat tiba di anak tangga terakhir di lantai tiga, mataku langsung menuju pintu kamar Aruna yang sedikit terbuka. Di depannya terdapat sepasang sepatu hak tinggi, dan entah bagaimana, aku yakin sepatu itu bukan milik Aruna. Kuperlambat langkah menghampiri kamarnya, dengan hati-hati, nyaris tanpa bunyi hentakan kaki. Senyumku terhenti bersamaan dengan langkahku, tepat di depan pintu yang setengah terbuka itu. Dari celah pintu yang hanya sejengkal itu, terlihat suasana di dalam kamar Aruna terasa muram. Aruna duduk di ujung kasur dengan wajah tertunduk. Seorang wanita –sepertinya Bu Sarah, sedang mengusap-usap pangkal lengan Aruna. Pada tatapan mata Bu Sarah memang tidak ada yang salah, tapi sesuatu dalam caranya menatap itu, aku tahu, terasa menekan. Mereka tidak berbicara, entah sudah selesai atau memang tanpa kata-kata pun mereka sudah paham maksud satu dan lainnya. Menyadari kehadiranku di ambang pintu, Aruna menoleh tepat saat aku memutuskan akan pergi. Mataku dan mata Aruna bertemu sebentar. Lalu entah kenapa, setelah itu dia memalingkan wajahnya ke arah lainnya, bukan kepada Bu Sarah, bukan juga menunduk. Dia seakan membuang muka. Bagiku, itu adalah sebuah kalimat tidak terucap, seolah-olah Aruna mengatakan bahwa dia tidak ingin aku berada di sana, memintaku untuk segera pergi dari tempatku berdiri. Aku memang akan pergi tanpa dia minta seperti itu. Tapi muncul rasa sakit sebab cara yang tidak aku sangka akan aku terima dari Aruna.
Aku segera masuk ke kamarku. Mengusap-usap wajah karena merasa sangat bodoh sempat berangan-angan akan bersama Aruna untuk menyantap makanan dari Bu Dewi, berandai-andai malam ini akan terlewati dengan bercerita ringan lagi.
Tidak lama terdengar suara langkah seseorang meninggalkan kamar Aruna, langkahnya semakin menjauh hingga terdengar menuruni anak tangga. Aku mengira-ngira Bu Sarah telah selesai berkunjung dan pulang. Aku menunggu, duduk di sofa, jika-jika Aruna akan mengetuk pintu kamarku maka akan cepat aku membukanya. Setidaknya aku berharap dia datang untuk menjelaskan semuanya seperti waktu itu, seperti waktu dia katakan handphone-nya mati dan tidak membalas pesanku, tapi kali ini dia bisa saja datang untuk menjelaskan situasi yang menjurus kepada salah paham. Juga akan aku katakan padanya bahwa aku tidak berniat mencuri dengar. Namun sayangnya dia tidak mengetuk, dia tidak datang.
Aku duduk di depan komputer mengedit beberapa foto untuk diserahkan besok. Karena belum mengantuk, aku bermain PES hingga jam pada layar komputer menunjukkan pukul empat dini hari. Tiba-tiba handphone-ku bergetar saat aku mematikan komputer dan bersiap tidur. Di layar tertera nama Ares. Tanpa pikir panjang aku mengangkat telepon itu.
Ares berbicara dengan suara terputus-putus, nadanya naik turun tidak teratur, bahkan dia tidak bisa mengucapkan kata-kata dengan jelas. Aku mengerti. Dia pasti sedang mabuk dan meminta untuk segera menjemputnya karena tidak mampu mengendarai motor untuk pulang. Sebenarnya hal seperti ini bukan sekali terjadi, sejak aku mengenalnya di kampus, ini sudah entah yang keberapa kali. Mungkin lima atau enam.
“Semanggi, Gam.” Hanya itu yang terdengar agak jelas olehku.
“Iya. Tunggu,” jawabku. Sejurus kemudian aku sudah berada di taksi menuju Semanggi, sebab tidak mungkin membawa motor dengan Ares yang mabuk dibelakang. Itu bisa berakibat kecelakaan. Akhirnya setelah menempuh perjalanan sekitar satu jam pulang pergi, kami sampai di kost lagi sekitar jam enam pagi. Susah payah aku membawanya turun dari taksi. Badannya yang lebih besar dariku, jelas-jelas terasa lebih berat karena dia sendiri tidak berdaya berdiri. Beruntungnya pagi itu ada Pak Yahya sedang menyapu halaman, dia membantuku membawa Ares yang sudah tidak mampu menapak dengan benar.
“Curang nih temennya, Mas! Masa mabuk sendirian," canda Pak Yahya.
"Mana nyusahin segala,” timpalku
Sambil memapah, kupukul kepalanya pelan karena kesal melihatnya yang cengar-cengir kegirangan.
Aku dan Pak Yahya akhirnya berhasil sampai pada lantai tiga. Lorong tampak temaram karena cahaya matahari belum masuk sempurna. Aku merogoh saku celana untuk mencari kunci pintu saat Pak Yahya mengajak Ares berbicara.
“Mas, jangan mabuk-mabukan lagi, ya? Susah nih bawanya ke atas,” Pak Yahya berseloroh pada Ares yang dibalas hanya dengan anggukan lemah dengan wajah yang cengengesan. Entah mengerti entah tidak. Entah dia sedang tahu situasi entah tidak. Yang jelas sedari bangun karena akan turun, Ares hanya cengengesan. Setelah meraba-raba setiap sudut kantong celana, aku meraih kunci pintu dengan jari-jari gemetar menahan berat badan Ares pada sebelah topangan. Pintu sedikit terhempas ke dinding di belakangnya sebab kami secara bersamaan masuk bertiga. Ares sudah terbaring di kasur. Cahaya matahari dari jendela yang setengah terbuka merambati wajahnya yang tetap berseri meski kehilangan setengah kesadarannya. Rambut panjangnya tergerai menutupi sebagian wajah, bulu-bulu halus yang selalu terbentuk rapi kini sedikit tampak lebih panjang dari biasanya.
“Terima kasih banyak, Pak,” kataku pada Pak Yahya yang pamit keluar.
“Sami-sami, Mas. Yo wes, saya lanjut nyapu lagi,” jawab Pak Yahya. Lalu, ia berjalan meninggalkan kami sambil mengecek dinding belakang yang terhempas oleh pintu tadi. Setelah memastikan tidak ada yang rusak, dia pun keluar sambil menutup pintu dengan perlahan seolah tidak ingin membangunkan Ares yang kembali tidur pulas sebab dengkurannya terdengar kuat. Aku mengunci pintu dan duduk di sofa, tidak lama, rasanya aku tertidur pula.
Klang!
Mataku terbuka tiba-tiba. Aku bangun karena dikagetkan oleh suara pegangan pintu yang memantul. Sepertinya seseorang di luar sedang berusaha membukanya. Aku langsung melihat Ares, dia masih tertidur di posisi yang sama. Lantas aku segera bangkit dari sofa dan membuka pintu segera.
Tergantung bungkusan makanan pada bagian pegangan pintu bagian luar. Tanpa mengambilnya, aku menunduk melihat apa isi didalam plastik transparan itu: nugget yang sudah digoreng dan masih panas. Lalu aku menoleh ke arah tangga, tampak dari belakang Aruna tengah mengenakan seragam kampusnya hendak turun.
“Runa!” dengan cepat aku memanggilnya. Aruna menoleh lalu kembali menaiki anak tangga yang baru satu atau dua dia turuni dan berjalan ke arahku. Melihatnya begitu, aku turut melangkah mendekatinya.
“Tadi aku yang gantungin bungkusan itu. Nugget dari Bu Dewi. Udah aku goreng sekalian,” kata Aruna, “makan ya, buat sarapan,” dia sempat menunjuk nugget yang tergantung.
“Oh…, thanks, Runa,” ujarku sambil berusaha tersenyum. Sebenarnya aku agak canggung berhadapan lagi dengan Aruna mengingat kejadian sore sebelumnya.
“Gam? Aku minta maaf, Bu Dewi ngasih kemarin, tapi aku gak sempat kasih ke kamu. Terus tadi juga bungkusannya agak nyangkut di handle pintu. Kamu kebangun, ya?”
“Enggak, kok. Gak apa-apa.” Aku menatapnya ragu, “Kamu ngampus? Aku anter, boleh?”
Aruna mengangguk, “Aku udah pesen ojek. Nih udah deket!” Dia menunjukkan layar handphone-nya yang menampilkan aplikasi ojek online.
Aku diam. Sejujurnya ingin mengatakan biar aku bayar ojeknya, dan dia pergi. Sedang kamu aku antar aja. Tapi itu terdengar memaksa dan sesuatu yang dipaksa tidak akan berjalan baik juga.
“Lagipula …,” ucap Aruna dengan suara pelan dan ragu, “kamu masih dalam pengaruh alkohol. Mabuk. Ntar kalau kenapa-napa di jalan, gimana?”
“Gimana?” Aku terkejut, “mabuk?”
Aruna tersenyum simpul sambil mengangguk yakin, “Mata merah kamu merah, terus wajah kamu … kelihatan capek banget.
Aku terperangah. Kalau mata merah dan wajah lelah memang menyetujuinya karena masih mengantuk dan juga tadi bangun karena terkejut. Tapi mabuk? Tidak. Aku tidak mabuk. Kamu salah paham.
Aku menggelengkan kepala. “Aku gak mabuk. Kamu kenapa mikir gitu?” tanyaku lagi. Kini mungkin terdengar mendesak.
“Tadi juga sempat dengar Pak Yahya, yang bilang kamu jangan mabuk, susah bawanya ke kamar. Itu pas aku lagi siapin bungkusan nugget kamu,” jelas Aruna.
Aku menghela napas, “Bukan aku yang mabuk, tapi Ares. Itu dia di kamar. Tidur.”
Aruna diam.
Aku diam, tapi tidak terlalu, sebenarnya sedikit merasa terganggu jika dia berpikiran aku yang mabuk ini berani-beraninya menawarkan tumpangan. “Oke, aku memang belum tidur semalaman, mungkin itu yang buat aku kelihatan capek.” Kini kalimatku terdengar seolah memaksanya agar dia percaya.
Tiba-tiba Aruna meraih pergelangan tanganku. Matanya memandang tajam namun penuh perhatian. Dia menekan dengan jempolnya urat nadi di pergelangan tanganku dengan sedikit kuat Detak jantungku berdenting di telapak tangannya. Dia membaca ritme yang tersembunyi, seperti seorang ahli. Pandangannya menyiratkan konsentrasi yang tidak tergoyahkan, tetapi aku bisa melihat kilatan yang lembut dari sebalik sorot matanya yang tajam. Aruna tampak tenang,memeriksa dan entah bagaimana, mendengarkan. Au tidak terlalu heran karena mengingat dia belajar ilmu keperawatan.
“Gak bisa, Gam. Tekanan darah rendah. Kamu butuh istirahat. Lagian aku udah pesen ojek,” ujarnya sambil melepas tanganku.
Aku melihatnya sekali lagi dengan tatapan penuh harap. “Coba sekali lagi, mungkin sekarang udah normal,” pintaku sambil mengulurkan tangan yang tadi dia pegang. Aruna tertawa kecil sambil menutup mulutnya yang membuatku akhirnya benar-benar menyerah.
“Pulang jam berapa? Aku jemput, ya?” tanyaku lagi.
“Belum tau. Aku ke bawah, ya. Buru-buru, nih!” ujarnya sambil membalikkan badan. Meninggalkanku dengan sebuah harapan yang tidak terpenuhkan.
-oOo-
”Gam! Oi! Lu ga kerja?”
Tubuhku digoyang-goyangkan. Suara Ares terdengar lantang tengah membangunkanku yang kembali tertidur di sofa.
“He'eh…” aku bergumam, mataku sangat berat untuk di buka.
“Kerjaan nelpon tuh!” Ares memberikan handphone yang berdering. Aku berusaha membuka mata, melihat siapa yang sedang menelpon. Kak Ami, seorang yang bertanggung jawab pada divisi pemasaran dan pengembangan bisnis di pabrik garmen tempat aku bekerja saat ini. Sejak awal bergabung pada perusahaan ini, Kak Ami yang selalu berkomunikasi mengenai materi pemasaran produk, baik video maupun foto. Aku menjawab telepon dan berbicara sebentar. Memang benar itu terkait pekerjaan. Aku bangkit sambil mengusap-usap wajah dan meregangkan tangan ke atas karena cukup pegal tidur dalam posisi duduk. Saat itulah mataku tertahan pada satu pandangan: Ares yang tengah menikmati makanan yang seharusnya hanya untukku. Nugget Aruna.
“Woy! Lu ngapain, Nyet! ” aku berseru kesal padanya.
Ares melihatku bingung dengan mulut yang penuh. Aku berlari dan meraih kantong plastik yang dia pegang, membuka bungkusan itu lebar-lebar untuk melihat nugget yang tersisa. Dan benar hanya tersisa satu potong nugget di dalamnya. Satu setengah, karena setengah lagi berhasil aku rampas dari tangan Ares satunya.
“Apaan! Kaget gua. Gorengan doang! Heboh amat, Nyet!!” ujar Ares tak kalah heran dan tak kalah lantang.
“Dari Aruna, Goblok!”
Ares terperangah dan diam sejenakmenyadari kesalahannya. “O-Oohh, ya … gak tahu. Kirain dari Bu Dewi lagi…,” kali ini suara Ares pelan dan sedikit gagap memperlihatkan rasa bersalah.
“Ya, hasil kolaborasi,” tukasku, “Lagian lu juga, ngira-ngira, dong! Ngambil kebanyakan!”
“Yaaa, maaf. Kagak tahu. Lagian gak pernah juga ada makanan spesial di sini, apa-apa biasanya boleh aja gua makan,” Ares berdiri menuju dapur untuk mengambil minum. Aku diam, kembali membuka plastik dan menatap nugget sisa dengan tatapan menyesal.
“Ah! Norak! Lu gak usah sok-sok sedih, gak pantes!” Ares menoleh lagi ke arahku. Meskipun dia terlihat lebih terkejut dan lebih marah, tapi aku tahu bahwa sebenarnya bahwa dia sungkan hanya saja enggan memperlihatkan.
Melalui telepon singkat tadi, Kak Ami mengingatkanku untuk mengirim materi katalog dan materi promosi sebelum pukul empat sore nanti. Aku mengatakan bahwa semua sudah selesai dan akan mengirimkan melalui e-mail. Pukul satu siang, aku sedang duduk di meja kerja memilih file yang akan dikirimkan.
“Pinjem baju.” Ares yang telah selesai mandi, mengibas-ngibaskan rambutnya agar cepat kering. Sedikit-sedikit cipratan air dari rambutnya mengenaiku.
“Ya,” aku membalasnya datar. Tidak terlalu memperhatikan sebab sedang melihat banyak file di layar monitor.
“Jadi Sabtu besok ke bazar makanan?” tanya Ares.
“Festival Kuliner. Jadi,” jawabku singkat.
“Trisna?”
“Udah. Oke katanya.”
“Aruna gimana? Jadi lu ajak?”
Pertanyaan Ares berhasil membuatku berhenti menggerakkan mouse. Mengingatkanku akan satu hal penting yang terjadi pagi ini. Aku menoleh ke arahnya dengan tatapan jengkel.“Noh, gara-gara lu, Aruna ngira gua ikutan mabuk. Makin susah deh gua.” .
Sambil mengemas tasnya, dia membalas tatapanku. Juga tampak berpikir. “Jago amat lu bikin gua makin ngerasa gak enak!”
Aku berdecak kesal.
“Terus?” tanyanya lagi dengan nada setengah menantang, setengah mencibir.
“Lha kok terus?” Aku kesal, “Yaaa …, belum apa-apa dia udah ngindarin gua.” Aku mulai tidak tahan dengan obrolan ini dan memutar kursi lagi menghadap monitor. Berusaha kembali fokus pada pekerjaan.
“Ya, paham. Cuma kan dari awal udah gitu. Gak deket-deket amat,” jawab Ares santai. “Lu yakin dia ngindarin karena salah paham? Bukan karena hal lain?” Ares mengajukan pertanyaan yang seketika menyadarkanku hingga aku tidak mau aku menoleh lagi ke arahnya dengan mata melebar. Ares merespon dengan menaikkan alis nya, mengangkat sedikit kepalanya dan tersenyum mengejek. Membuatku semakin sadar akan suatu hal yang harusnya sudah terpikirkan sejak awal.
“Bener juga. Gua emang gak pernah lihat dia bareng cowok. Tapi ya kan bisa aja ya?” ujarku sambil berpikir.
“Nah, itu dia maksud gua. Cari tahu dulu lah. Liat situasi. Jangan main pepet aja,” Ares berdiri untuk bersiap pergi menjemput motornya yang sengaja ditinggal di parkiran Plaza Semanggi.
Pikiranku mulai bergeliat, jari telunjuk mengetuk-ngetuk meja. Aku segera meraih handphone, mulai membuka sosial media, berusaha menemukan akun Aruna. Nama Aruna muncul dalam berbagai variasi, membuatku harus memeriksa satu per satu mengingat aku belum mengetahui nama panjangnya. Di antara berbagai akun yang tampaknya tidak sesuai, akhirnya aku menemukan satu akun (yang sepertinya) milik Aruna. Tidak ada postingan yang mencolok, hanya berisi sebagian besar foto-foto dari tempat-tempat yang pernah dia kunjungi. Namun ada satu foto menarik perhatian. Potret tubuh yang berdiri membelakangi kamera di ruangan kosong. Siluet tubuh perempuan itu identik dengan Aruna, dari gaya rambut hingga cara berdirinya. Aku bernapas lega saat melihat tidak ada tanda-tanda kehadiran seorang laki-laki di akun itu. Ares mengintip dari belakang saat dia meraih jam tangannya di meja.
“Lu jangan senang dulu, kali aja sengaja. Privasi,” ujar Ares menegurku agar tidak terlalu bersemangat.
“Ah! Iya! Pergi deh! Ambil motor sono!” timpalku.
“Yeee di bilangin juga. Tanya langsung lah! Aruna sayang, kamu udah ada cowok atau belum? Sini sama Aa aja. Gitu! Lama amat! Di ambil orang, tahu rasa.” Ares tampaknya lebih kesal, “atau gua aja?” tanyanya sambil memakai sepatu.
“Lu aja yang nanyain?”
“Gua aja yang sama Aruna.”
“Sialan!”
Ares tekekeh, “Kalo gak salah, lu punya nomornya kan?” tanya Ares lagi.
“Punya”
"Lah? Si Anying! Goblok!” Kesal Ares semakin menjadi-jadi. “Gimana lu aja, deh! Mau lu pelototin tuh nomor juga terserah. Gua balik. Thank you,Nyet!”
Saat sudah sendirian, aku kembali tertegun, menyadari kebodohanku. Aku pun melirik layar ponsel, sudah pukul dua siang. Harusnya Aruna sudah selesai kuliah, pikirku. Dengan mengumpulkan keberanian, aku mencoba mengiriminya pesan. Meskipun penuh degupan di dalam dada yang gelombangnya membuat jari- jemari bergetar. Aku berusaha menembus batas ketidakpastian antara aku dan dia. Antara kami berdua.
-oOo-
“Yuk!” ajakku pada Aruna sambil menurunkan pijakan kaki motor untuk memudahkannya naik. Aku berhasil mengirimkan pesan dan mendapatkan balasan yang baik darinya. Jantungku meletup-letup saat membaca pesan singkatnya.
Aruna tampak malu-malu saat menaiki motor. Dia sedikit kesusahan karena kursi penumpang di belakang lebih tinggi.“Udah …,” ujarnya pelan saat berhasil naik dengan memegang pundakku.
“Helm nya, nih.”
“Kok ?” tanyanya bingung melihat helm berwarna merah muda.
“Pinjem punya Bu Dewi tadi,” aku menukas cepat lalu terkekeh singkat yang dibalas Aruna dengan senyum lebar, nyaris tertawa.
“Yuk, balik!” ujar Aruna setelah memakai helm itu.
“Yah? Jangan balik dulu, lah…,” ucapku setengah merajuk, “kita jalan-jalan, yuk?” tanyaku yang langsung merubah raut menjadi kekanak-kanakan.
Rona wajahnya memerah, “Tapi aku masih pakai seragam. Emang kita mau kemana?”
Aku tahu dia mau. Juga sebagaimana aku tahu dia mau, maka seperti itu jugalah dia tidak ingin memperlihatkan keinginannya. Dia gengsi menyetujui segera hingga membuat-buat alasan.
“Nih, pakai aja. Soalnya aku gak yakin kamu mau keluar lagi kalau udah sampe kost.” Kataku sambil emmbuka jaket jeans yang kukenakan. Jaket itu diterima Aruna. Dia memakainya sambil tersenyum padaku. Aku pun ikut tersenyum. Hanya satu hal yang aku harapkan, degupan dada ini jangan sampai terdengar hingga keluar.
“Kamu udah pake kemeja flanel panjang, pake jaket segala. Denim pula. Gak gerah apa?” Aruna bertanya heran saat dia melihat kemeja flanel di balik jaket jeans. Aku tertawa kecil mendengarnya.
“Demi, deh,” bisikku pelan nyaris tidak terdengar sambil menertawakan diriku yang sebegitunya tidak ingin melewatkan kesempatan bersama Aruna.
-oOo-
Sore itu, alam seakan paham benar keinginanku. Udara yang terasa lebih sejuk membuat angin berhembus lebih dingin. Meskipun lalu lintas Jakarta tetap padat, terutama pada jam-jam seperti ini, namun hatiku kali ini terasa lapang. Sesekali aku melirik spion, Aruna duduk di belakang terlihat sangat senang. Matanya bergerak melihat keramaian, senyumnya tetap merekah. Saat dia sadar aku memperhatikannya dari balik kaca, dia langsung menoleh ke arah lainnya sambil mengatupkan bibir. Salah tingkah yang menggemaskan.
Motor kuhentikan pada satu coffe shop setelah tiga puluh menit berada di jalan. Kami berdua berdiri berdampingan di konter pemesanan. Aruna membaca setiap menu yang tertera, namun tiba-tiba Aruna mendekat dan sedikit berjinjit ke arahku. Dia menarik kemeja di pangkal lengan sehingga membuat tubuhku sedikit condong ke arahnya. Dia berbisik pelan sambil menutup dengan satu tangan yang justru membuat jantungku melompat tidak keruan. “Kamu aja yang pilih, aku gak paham kopi, takutnya salah pilih malah pahit,” ujarnya dengan santai tanpa rasa bersalah sudah berhasil membuatku hampir tidak bisa berdiri tegap karena menahan jantung yang melompat-lompat ingin keluar. Tiba-tiba pikiranku buyar, tidak bisa fokus pada pilihan menu yang ada. Seharusnya aku sudah hapal dengan setiap menu di sini sebab tidak sekali dua kali aku membeli kopi dari gerai ini. Kali ini bukannya memesan dengan benar seperti yang Aruna harapkan, aku malah menyebutkan menu espresso yang terkenal pahit dan aku baru menyadarinya setelah menu itu dihidangkan ke meja kami. Tak tanggung, aku memesan dua. Tolol!
“Aruna, maaf aku salah pesan. Ini pahit banget,” aku berusaha mencegah Aruna untuk minum espresso itu dengan menjauhkan kedua gelas kecil itu dari Aruna.
“Ooh, gitu?” Aruna tampak bingung melihatku, “kamu juga gak paham kopi?”
Tolong jangan nanya-nanya dulu, aku malu!
“Ini aja dulu minum buat makan nasi gorengnya.” Gelas berisi air mineral yang selalu disediakan jika memesan espresso sebagai penetral aku dorong dekat ke Aruna.
“O-oh? Ya, oke,” dia terdengar ragu, “Kamu makan roti aja?” Aruna melirik makanan yang aku pesan: roti berbalut selai coklat.
“Iya, belum laper. Aku pesenin minum kamu lagi, ya.” ujarku sambil berdiri menuju meja pesanan. Aruna berusaha menahan. Dia mengatakan sudah cukup dua gelas air ini saja. Namun aku katakan aku tetap memesan minuman lain untuknya, akhirnya dia mengalah.
Selama di coffe shop, kami bercerita ringan, dia perlahan-lahan menyantap makanan dan minumannya. Aku mengamatinya. Terkadang dia sadar bahwa pandanganku tidak lepas dari wajahnya sehingga Aruna menjadi malu. Walau wajahku tampak tenang, namun pikiranku sedang bergerilya kemana-mana, mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan yang ingin aku utarakan padanya. Terlebih jika mengingat perkataan Ares. Entah bagaimana caraku memastikan bahwa Aruna tidak memiliki seseorang yang sedang dia sukai atau pun sebaliknya. Cerita-cerita yang sudah dia sampaikan hingga detik ini sebagian besar hanyalah tentang kegiatan kampusnya atau dengan Bu Dewi yang sebenarnya juga tidak terlalu sering dia jumpai. Tidak ada yang bisa memberikan petunjuk apapun untuk menjawab satu pertanyaan penting itu. Terkadang aku bertanya bagaimana panti asuhannya, namun Aruna menjawab sekedarnya, seolah tidak ingin membahas hal serupa atau justru dia belum bisa terbuka.
Makanan dan minuman habis, begitu juga cerita. Aruna meminta pulang ke kost saja. Aku menuruti keinginannya, tidak ingin memaksakan kehendakku yang sebenarnya masih ingin bersama hingga malam.
“Beli jajanan dulu, yuk!” ajakku padanya sambil membelokkan motor ke minimarket.
Kami masuk bersamaan. Aruna diam saja, tidak memilih apapun. Hanya mengikuti langkahku yang sedang memilih cemilan.
“Kamu mau yang mana?” tanyaku.
“Engga ada. Oh ya, kamu gak makan lagi? Kok malah beli cemilan?” katanya. Sejujurnya jika ingin menuruti kehendakku, aku akan menjawab aku ingin makan, dan ditemani olehnya. Aku sangat siap jika harus pergi lagi ke tempat makan atau kemana saja yang dia inginkan. Namun kali ini tidak bisa sebab Aruna tampak lelah dan sedikit gelisah yang membuatku merasa bersalah. Dia sudah kuliah sejak pagi, bukan membawanya pulang untuk beristirahat, aku malah membawanya main hingga malam hari hanya atas keinginanku sendiri. Betapa egoisnya aku ini.
“Aku nanti aja makannya. Agak maleman. Tadi juga abis makan roti, kan?”
Aruna mengangguk-angguk. Juga sepertinya dia tidak terlalu bersungguh-sungguh, dia hanya berusaha bersikap baik, atau justru sekadar basa-basi.
Aku segera ke kasir, membayar. Sejurus kemudian kami sudah sampai kost. Di parkiran, tampak Pak Yahya yang sedang duduk bersama Bang Tigor. Bang Tigor sedang memainkan gitar sedang Pak Yahya menyanyi dengan asal-asalan tapi kepercayaan dirinya luar biasa tak terkira.
“Cieeeh. Mas Gamma sama Mbak Aruna abis jalan-jalan, ya?” goda Pak Yahya yang diikuti oleh petikan gitar Bang Tigor yang mendesak-desak seakan mengerjai kami berdua.
Aku langsung menoleh kepada Aruna, menunggu jawabannya akan seperti apa. Namun sayangnya, aku lupa sesaat bahwa dia adalah Aruna, yang tidak banyak bicara, hanya terbiasa melempar senyuman saja.
Aku tekekeh, “Iya, nih.”
Pak Yahya kegirangan dan Bang Tigor tersenyum usil.
“Kami masuk dulu, Pak, Bang!” kataku lagi.
“Monggo!” jawab Pak Yahya masih sambil menggodaiku. Aku tersenyum saja.
Aku dan Aruna meninggalkan mereka. Kami berjalan bersisian hingga sampai ke depan kamar masing-masing. Tidak ada percakapan lagi hingga kami sampai di depan kamar masing-masing.
“Runa, nih. Aku sengaja beli emang buat kamu.” Aku memberikan sekantong cemilan yang tadi aku beli.
“Loh? Kok buat aku, sih?” tanya Aruna tampak keberatan.
“Iya, aku emang beli buat kamu. Cemilan aku masih ada di kamar,” jawabku, “Jangan ditolak, ya?”
Aruna tersenyum, kali ini senyumannya di iringi dengan tatapan yang sulit aku tafsirkan. Tatapan seperti seorang yang menyimpan kesalahan, tapi juga terlihat sendu.
“Gam, ini kebanyakan. Kamu udah jemput, udah ajak aku makan juga. Sekarang kasih aku banyak cemilan,” ujarnya sambil menerima cemilan itu. Sepertinya dia enggan berlama-lama hanya karena berbasa-basi menolak sekantong cemilan. Lantas dia memangkas keadaan yang terasa memberatkannya, maka dia menerima saja.
“Aku juga mau minta maaf, kamu jadi capek, ya? Harusnya tadi kita langsung pulang aja,” ujarku pelan.
“Enggak, aku gak capek,” Aruna menghela napas. “Aku seneng kok udah jalan-jalan. Cuma tadi tiba-tiba aku kepikiran sesuatu. Keliatan banget, ya?” ujarnya lagi, kali ini dia terlihat berusaha mencairkan suasana.
Memikirkan sesuatu?
“Oh, gitu.”
Lucu. Aku bahkan gak bisa mikirin hal lain saat bersamamu, Runa.
Hening sesaat. Aruna juga belum masuk ke kamarnya. Dia seperti menunggu aku pergi dulu. Mungkin dia akan masuk kamar setelah aku membuka pintu kamarku.
“Hmmm, aku baru bisa bilang sekarang, maaf kemarin aku sempat lihat kamu sama Bu Sarah. Aku gak bermaksud ngintip atau nguping. Aku cum—"
“Ya. Aku paham,” Aruna langsung memotong kalimat yang belum sempat aku selesaikan, dia juga dengan segera menepis udara di antara kami berdua. “Aku juga gak marah. Situasinya aja kurang baik kemarin. Itu jangan dibahas lagi, ya?” pinta Aruna.
“Oh, oke.” Jawabku yang sedikit terkejut.
Lalu dengan senyuman terakhir yang tampak dipaksakan Aruna menutup pintu kamarnya. Membuatku semakin banyak bertanya-tanya. Tapi dari semua pertanyaan itu yang paling menonjol dalam pikiranku adalah, Apa aku bisa jadi lebih dekat dengan Aruna?
(Bersambung)
Restart ©2023 HelloHayden


 hellohayden
hellohayden





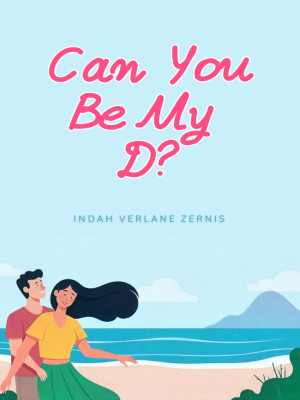







Baca cerita ini udah kayak masuk ke kedai all you can eat. Daging semua. Sbg cowok baca ini gk merasa aneh sama sekali untuk crita roman dan rasa kembali ke masa kuliah. Mantap lah
Comment on chapter Bab 14 (Cukup)