Sekumpulan remaja laki-laki yang tadi itu, yang telah membuat Zahra berusaha untuk terus mengingat dan mengingat. Namun sayang, Zahra tak mampu menguak semua cerita, dan semua kisah yang seolah-olah terkesan fiksi baginya, untuk saat ini.
“Siapa dia?” batin Zahra—masih mempertanyakan hal yang sama.
Lantas sebab hal ini, oretan rangkaian kata pun mulai ia tujukan, untuk seseorang yang masih ia ragukan. “Aku hanyalah seorang yang ingin mengetahui tentang diriku sendiri, tapi mengapa aku tak mampu mengingat akan hal itu? Kebersamaan yang dulu mungkin pernah tercipta, bagaikan tulisan lama, yang telah pudar walau masih tersisa, dan benar-benar sulit rasanya, untuk bisa aku baca. Sebenarnya, inti dari segalanya, aku hanya ingin mengetahui siapa dia? Ya, hanya dia yang selalu berhasil membuat hatiku terus bertanya.
“Sinar mentari berganti gelapnya hari, tetapi aku tetap tak mampu akannya. Apa ia telah sebegitu lamanya menghilang, untukku terus mencoba, sampai akhirnya, waktulah yang telah memanduku untuk segera melupakannya? Siapakah yang ingin melupakan kisah yang kini tak diketahui, akan peristiwa yang telah dijalani? Entah bahagia, runyam, atau pun menyakitkan. Aku sama sekali tak mengetahui akan hal ini.
“Jika itu bahagia, mungkin aku mampu untuk mempertahankannya—sesuai dengan apa yang aku inginkan, dan yang Sang Rahman inginkan. Namun, jika itu runyam, aku akan berusaha untuk tak mempertahankannya, sembari memperbaiki dari kejadian itu dengan segera. Lalu jika itu menyakitkan, aku akan berusaha, untuk bisa bangkit, tapi tetap tak akan melupakan tentangku dan hidupku—sebagai pedoman untuk tetap kuat—melawan kisah duniaku yang menyakitkan itu.
“Namun kini apa? Nyatanya aku hanya bisa menghela nafas, di saat pikiranku mulai membayangkan yang buram, tapi meskipun begitu, aku yakin ... aku sangat yakin, siapa pun dirinya—inilah takdirku untuk sejenak melupakannya, dan inilah hal yang terbaik untukku. Ya! Aku harus bisa selalu mengatakan hal ini. Aku harus selalu bisa mengatakan, bahwa segala hal yang telah terjadi kini, itu adalah hal yang terbaik, untuk siapa pun itu :),” kata Zahra, dalam oretannya.
***
Sesaat setelah itu, Zahra pun memutuskan untuk segera membuka ruangan lama, yang telah terkunci rapat oleh orang tuanya.
Sejak dulu, ia sangat ingin membuka lemari yang terletak pada ruangan itu. Namun sayang, ia tak bisa menemukan satu kunci pun, yang mampu membuat gembok pada lemari itu terbuka.
Sering kali ia bertanya kepada kedua orang tuanya mengenai hal itu. Namun respons yang ia inginkan, tak kunjung hadir dari ucapan sang ayah dan sang ibunya.
Ada apa? Mengapa? Kiranya, pertanyaan itulah yang selalu hadir di dalam benaknya, sejak ia berusia yang ke-12 tahun—pada saat itu.
***
Beberapa saat kemudian.
“Ada apa lagi, Nak? Kamu mau cari apa di sana?” tanya Ibu-nya Zahra.
“Zahra cuma mau tahu, Bu!” balas Zahra.
“Ibu kan udah bilang, kalau lemari itu kosong. Nggak ada isinya, Nak,” bantah ibu-nya kembali.
“Ibu nggak bohong?” Zahra berharap, bahwa ibunya mau memberikan banyak penjelasan, yang jauh bisa terdengar realistis.
“Ibu nggak bohong. Mana mungkin, mana mungkin Ibu bisa bohong sama kamu.”
“Tapi menurut Zahra, di lemari itu ada sesuatu yang berharga, Bu. Boleh ya Bu, Zahra buka?”
“Bukannya Ibu nggak ngebolehin, tapi lemari itu penuh debu, Nak. Ibu nggak mau, kalau kamu sampai sakit, batuk-batuk, karena itu. Udah, mending sekarang, kamu makan aja sana. Ibu udah siapkan makanan kesukaannya kamu, di meja makan.”
Lagi dan lagi, itulah kalimat yang selalu Zahra dengarkan dari sang ibu-nya. Apa yang bisa di kata? Mana mungkin, Zahra akan terus-menerus menekan ibu-nya untuk bisa berkata jujur. Sementara Zahra, ia sama sekali tak ingin sampai melawan ibu-nya sendiri—seorang ibu yang telah ia sangka, telah melahirkannya dengan susah payah.
Alhasil sebab hal ini, Zahra pun hanya mampu tertunduk—menahan rasa ganjal di hatinya. “Iya Bu.” Ya, hanya kalimat persetujuan itulah yang bisa ia tuturkan.
Lalu setelahnya, ia pun lekas berjalan di mana arah meja makan berada, dengan raut wajahnya yang tampak murung—tepat setelah ia berbalik arah—berharap ibu-nya sama sekali tak melihat ekspresi spontanitasnya ini, yang secara jujur, begitu sulit ia halau akan kesetaraannya, dengan apa yang kini tengah ia rasakan—mengenai isi hatinya yang paling dalam.
***
Sepuluh menit telah berlalu, tepat setelah Zahra selesai makan, di dalam kamarnya, ia tampak kembali termenung—benar-benar merasa bingung, akan siapa dirinya yang sebenarnya, dan mengapa rasanya, ada begitu banyak rahasia tentang dirinya sendiri, yang sejatinya turut tak ia ketahui secara jelas dan detail.
“Andai aja ... aku bisa baca pikiran orang lain, dan bisa memahami isi hati seseorang dengan benar, sekalipun itu, tanpa mereka kasih tahu. Kalau aja itu bisa terjadi, pastinya aku bisa tahu apa yang lagi mereka pikirkan tentang aku, dan dengan kayak gitu, pastinya aku juga bisa sesegera mungkin tahu, siapa diri aku yang sebenarnya,” batin Zahra—kembali terlihat merasa sedih.
Beberapa saat setelahnya.
“Zahra ...,” panggil ibu-nya—dengan langkah kakinya yang telah lebih dulu sampai, tepat di depan pintu kamarnya Zahra.
“I-iya, Bu?” Zahra lekas menyahut kala itu—turut beralih posisi—berusaha untuk bisa terlihat baik-baik saja, tentunya.
Creck.
“Ada teman kamu di depan.” ucap ibu-nya Zahra, setelah ia membuka pintu kamarnya Zahra.
“S-siapa, Bu?” tanya Zahra dengan tampak gugup, sambil berupaya mengulas senyuman pada bibirnya, yang tadinya sempat seratus persen menghilang.
Untungnya, ia telah tak lagi dalam posisi melamun saat itu. Untungnya, Zahra telah lebih dulu siap siaga—sebelum nantinya, ia malah akan melihat raut wajah sedih dari ibu-nya kembali. Ya, tentunya Zahra sama sekali tak ingin, melihat ibu-nya kembali bersedih—tepat di saat, jika saja ibunya malah turut melihat ekspresi sedihnya itu, dalam beberapa saat sebelumnya.
Setelah ibu-nya mendengar kalimat tanya itu darinya, lantas ia pun lekas berkata, “Kamu ke depan aja, ya. Dia udah nungguin kamu ‘tu di depan.” Ibu-nya Zahra.
Melihat senyuman dari satu-satunya putri kesayangan yang ia punya, lantas tak ada cara lainnya dalam berekspresi, selain ikut menampilkan senyuman—meski yang sebenarnya, ibu-nya Zahra telah paham, bahwa putrinya itu masih saja ingin mengetahui suatu hal, yang sejatinya telah lama ia rahasiakan.
Katanya, sesuatu yang telah lama ia rasakan ini, adalah suatu hal yang terbaik untuk Zahra—suatu hal yang sejatinya akan lebih baik, jika Zahra sama sekali tak mengetahuinya.
Semacam rahasia apakah yang di maksud? Apakah benar, jika hal ini memang suatu perkara yang terbaik bagi Zahra, jika akan terus menerus ‘tuk dirahasiakan?
Ataukah hal ini, hanya sebagai bentuk keegoisan dari seseorang, yang telah Zahra anggap sebagai seorang ibu, layaknya dia?
***
Beberapa saat kemudian, di saat Zahra telah sampai melangkah menuju ke ruang tamunya, ia pun lekas mendapati Karina. “Karina,” sapa Zahra, tampak merasa terkejut. Lalu kemudian, ulasan senyuman pun tampak tertampil dengan indahnya—merasa terhibur, dengan kehadirannya seorang Karina.
“Hai ...,” sapa balik Karina—turut menampilkan senyuman terbaik yang ia punya.
“Udah lama?” tanya Zahra.
“Baru sampai,” jawab Karina.
“Owh, gitu.” Zahra.
“Mmm, aku ke sini, mau ngasih kamu ini.” Setelah selesai mengatakan kalimatnya ini, Karina pun lekas mengulurkan sebuah benda, yang ingin ia berikan itu kepadanya.
“Itu apa?”
“Buka aja.”
Sesuai intruksi darinya, Zahra pun lekas membuka bungkusan dari benda itu.
Beberapa saat setelahnya. “Wah, buku sastra?” Zahra tampak semakin melebarkan senyumannya. Ia benar-benar tampak merasa bahagia kali ini.
“Iya, kamu suka buku itu, ‘kan?” Karina—merasa ikut bahagia.
“Suka banget! By the way, kamu tahu dari mana, kalau aku juga ngincar buku ini?” tanya Zahra, masih dalam senyuman.
“Ya tahulah. Masa iya aku nggak tahu. Ya ... walaupun kita baru-baru ini ketemu, terus dalam waktu yang singkat juga, kita baru menjalin hubungan persahabatan ini, tapi apa kamu lupa? Kalau aku ini super duper peka? Hmm?” Karina lekas berucap demikian dalam meresponsnya. Ia berkata demikian, sambil tak luput dari senyuman.
“Iya deh, iya! Kamu itu paling the best! Best friend-nya aku, pakai kata banget yang super duper double.” Zahra kembali tersenyum puas—bahagia, seraya melihat ke arah Karina.
Tak hanya Zahra, Karina pun turut menampilkan ekspresi yang sama. Ia juga benar-benar terlihat tersenyum puas, dan ikut merasa bahagia.
“Kamu bisa aja. Kamu juga the best, buat aku,” balas Karina, masih dalam ekspresi yang sama.


 thirtyrs
thirtyrs







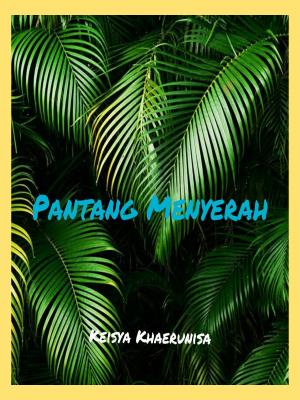


Muncul fakta lainnya. Next up, Kak 🙏🏻🤍
Comment on chapter Chapter 10. Dea?