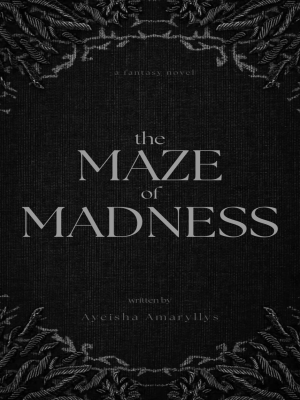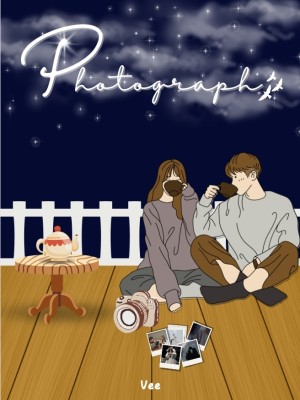Hari pelantikan telah tiba. Annika berdiri di samping Sheila. Mengucapkan sumpah yang dipimpin oleh Kak Regina (Ketua prefek selalu dipilih saat pembagian rapor di akhir semester dua), menerima emblem prefek, dan menahan silaunya jepretan kamera yang diarahkan ke wajahnya.
Seharusnya ia senang. Bulan September yang cerah telah tiba bersamaan dengan dirinya menduduki jabatan yang bergengsi. Namun, sebenarnya bulan September tahun ini adalah September yang paling kering yang pernah Annika temui. Pasir di area Aqiela Ru’ya jadi berdebu, membuat matanya sering kelilipan. Begitu pun halnya dengan menjadi prefek. Tak semenyenangkan yang dipikirkan orang lain. Pefek kebudayaan rupanya anggotanya tak sebanyak yang ia bayangkan. Bahkan hanya dirinya dan tiga orang kakak kelas lima. Ia tak terlalu dekat dengan kakak kelas, dan mulai membayangkan hal-hal mengerikan apa yang harus ia lalui nanti.
Bagaimana reaksi mereka kalau tahu alasannya mendaftar prefek? Oh, oh, sebaiknya ia rahasiakan sampai mati nanti.
Annika tenggelam dalam pikirannya meskipun mulutnya sibuk bernyanyi mars prefek dan mars Aqiela Ru’ya bersama para anggota lain. Ia tidak tahu Kiara duduk di kursi bagian mana, namun, ia bisa membayangkan kalau Kiara saat ini tengah menatapnya dengan dingin.
Ia bahkan sudah mengirim surat pada Kiara. Surat yang memuat penjelasan menyedihkannya soal pemikirannya waktu itu. Ia menulis tentang betapa ia ingin mereka bisa lebih dekat lagi dengan aktivitas yang sama, serta bagaimana rasa insecure-nya melihat teman-teman baru Kiara dari Klub Sastra, salah satu hal yang membuatnya terjaga di beberapa malam. Seperti, ‘Oh, Kiara kayaknya melupakanku? Dia lebih banyak menghabiskan waktu dengan Ashna dan Lumi. Nggak heran, sih, mereka pintar dan berprestasi. Sementara aku enggak.’ Ia begitu yakin teman-teman Kiara lolos dalam pemilihan prefek, hingga tak bisa membayangkan kalau suatu hari harus mengakui bahwa ia tidak terpilih pada Kiara. Itu hanya akan membuatnya semakin rendah dari teman-teman baru Kiara.
Annika telah menulisnya dengan pelan dan hati-hati. Ia bahkan menyelesaikannya dalam dua malam. Namun, Kiara tetap menghindarinya. Bila bertemu, ia hanya memasang wajah dingin dan menganggapnya seakan tidak ada. Permusuhan mereka telah menjadi topik hangat di asrama Manna.
Annika menghela napas. Setelah ia begitu jujur pada Kiara, dan gadis itu tak merespon apa pun, rasanya menyakitkan. Kiara sekarang tahu perasaan rendah dirinya yang … tidak menarik, menambahkan efek negatif pada kepribadian Annika.
Suara tepuk tangan menggema di auditorium. Annika dan para prefek lain menuruni panggung. Annika berjalan gontai dan memaksa senyumnya pada teman-teman yang ingin mengobrol padanya. Ashna, tentunya, dia terpilih jadi prefek akademik. Lumi terpilih jadi prefek keagamaan. Sheila menjadi prefek perpustakaan. Mereka menyampaikan selamat padanya.
“Selamat, ya, Nik!” kata Lumi semangat, ia memang selalu bersemangat. Ia merangkul bahu Annika dan bertanya, “Kok kamu kepikiran jadi prefek, Nik? Aku engga nyangka, loh. Wah, mau jadi apa, nih, asrama kita ada prefek kebudayaannya!”
Sementara Annika sedang mencari-cari jawaban yang tepat, Sheila berkata, “Wajar, deh, Lum. Semua murid kan harus berjuang buat ngembangin diri. Alhamdulillah Annika dipilih sama Ustazah Soraya.”
“Tapi menurutku masih … aneh banget. Semangat, ya, Annika, kerjanya nanti!”
Annika tersenyum lemah. Ia benar-benar banyak pikiran seminggu ini dan tak punya sisa kekuatan lagi untuk tersenyum cerah seperti biasa. “Iya, makasih, Lum.”
Lumi jadi mengerutkan dahi. “Kamu lemes banget, Nik. Kamu ngga sakit, kan?”
Suara tawa terdengar, asalnya dari balik masker Ashna. Meskipun tertawa, tapi sorot matanya tajam dan menatap langsung ke arah Annika. “Selamat, ya, Annika. Aku engga sabar lihat kerja kamu nanti,” katanya. “Ayo, Lum. Oh iya, anak kelas empat yang lolos prefek, nanti sore kumpul di kantin, ya.”
Ashna dan Lumi berlalu meninggalkan Annika. Suara tawa Ashna menggema di telinganya. Gadis itu ‘sangat’ jarang tertawa, dan dia tak akan tertawa tanpa ada alasan yang kuat. Selera humornya pun sangat gelap. Oh, oh, bagaimana kalau surat itu—
Tidak. Kiara tidak sejahat itu. Seperti saran Danila, ia hanya perlu membiarkan Kiara dulu supaya Kiara bisa menenangkan diri dan memikirkan semuanya. “Kiara biasanya anaknya lumayan rasional. Dia mungkin ada sesuatu, Nik. Tapi kamu engga tahu. Karena kamu engga tahu, berarti udah bukan wilayah kontrol kamu. Insya Allah, biar Kiara selesaiin dulu masalahnya, nanti pasti mau bicara sama kamu lagi. Dia udah kenal kamu engga setahun dua tahun, loh. Dia pasti udah kenal banyak sama banyak sisi diri kamu. Engga perlu terlalu khawatir,” begitu kata Danila waktu itu.
Annika merasa seseorang mengelus bahunya. Ketika ia menoleh, rupanya Sheila, yang tengah memasang senyum manisnya. “Yuk, ke asrama. Eh—atau kamu mau lihat-lihat booth dulu?”
Sekolah selalu libur ketika ada acara pelantikan prefek. Para murid dibebaskan untuk mengunjungi berbagai booth dari luar sekolah yang tersedia di sepanjang taman. Annika ingat menghabiskan waktu di sana pada tahun-tahun lalu dengan Kiara, membuat piring tanah liat, membuat gelang manik-manik, atau belajar menjahit sapu tangan. Annika masih mengingat tawanya saat melihat piring tanah liat Kiara yang lebih mirip yeti alih-alih bebek yang ia harapkan. Good old times, pikir Annika. Lalu berjengit mengingat hubungan mereka yang retak sekarang.
Annika amat menyayangi Kiara. Ia selalu berpikir bahwa Kiara adalah teman terbaik baginya, setelah mengalami hal-hal yang tak menyenangkan dalam pertemanan di masa TK dan SD. Rasanya, ia tidak bisa membuat memori dirinya yang sedang kesepian mengunjungi booth kreativitas yang ramai. Itu akan sangat menyedihkan.
“Nggak, Shei. Kamu juga engga?”
“Enggak. Uangku lagi tipis. Umi belum kirim. Mau ke kamar aja. Yuk,” kata Sheila.
Mereka berjalan keluar dari auditorium. Matahari bersinar amat—amat terik. Menakjubkan bahwa ia, Sheila, dan anak-anak lain belum terpanggang. Musim hujan yang dinantikan belum juga tiba. Untungnya jarak auditorium ke asrama tak begitu jauh. Tak lama kemudian mereka akhirnya tiba di teras asrama. Annika merasakan kulit tangannya yang menghangat.
Azan Zuhur masih satu jam lagi. Sheila langsung menenggelamkan diri dalam novel sastra tebalnya setelah mengganti seragamnya. Tak ada orang lain di kamar selain mereka. Annika tidak betah sendirian, dan rasanya mengganggu sekali kalau sebentar-sebentar mengajak Sheila mengobrol. Oh, gadis itu merespon dengan baik, seakan-akan ia punya lebih dari satu otak untuk mencurahkan perhatian. Tapi …kalau ia jadi Sheila, pasti sudah sangat kesal.
Maka, Annika meraih kalimbanya. Musik selalu membuatnya tenang. Aliran listrik di otaknya yang tadinya tak beraturan, rasanya lebih lancar apabila mendengar alunan musik. Ia berjalan menuju balkon.
Balkon kamar empat mengarah ke ladang para murid. Mengingatkan Annika bahwa ia lupa belum menyiram kentangnya tadi pagi. Biarlah, ia tak akan mati kalau ia lupa menyiram satu kali saja. Annika memetik kalimbanya, memainkan musik yang pernah ia pelajari, yaitu ‘Roadside Yellow Butterflies’. Annika selalu menyukai musik itu. Bukan karena mengingatkannya pada kupu-kupu kuning yang sering ia temui di pinggir jalan di kota kelahirannya, tapi karena seorang guru. Karena ialah, ia menyukai bermain musik.
Saat kecil, Annika pernah dirundung oleh teman-teman sekolahnya. Suatu kali seorang anak mendorongnya ke dalam sawah berlumpur dan menertawakannya. Hujan yang turun dan petir yang menyambar membuat anak-anak nakal itu ketakutan, hingga meninggalkan Annika sendirian. Tepian sawah yang tinggi dan licin itu sulit untuk dinaiki. Annika menangis dan mengira ia akan mati tersambar petir. Saat ia berhasil naik ke atas, ia tak bisa berdiri lagi karena kehabisan tenaga.
Beruntungnya, ada seorang wanita yang lewat. Ia berusaha membangunkan Annika dan menggendongnya menuju UKS sekolah. Setelah Annika mendapat perawatan, wanita itu menunggunya sampai orang tuanya menjemput. Sore itu, Annika ingat ia berulang kali bermimpi buruk. Salah satunya adalah perjuangannya naik dari sawah seperti siang tadi, dengan tambahan lumpur yang menggelegak dan siap menerkamnya. Mengerikan sekali. Namun, melodi-melodi indah menggantikan lumpur itu, membuat Annika memimpikan hal-hal menyenangkan.
Saat Annika bangun, ia melihat wanita itu tengah memainkan sebuah alat musik. Melodinya sama persis dengan yang ia dengar di mimpinya. Annika penasaran dan bertanya beberapa hal tentang alat musik itu. Kelihatan manis, mungil, dan unik. Wanita itu membiarkan Annika memainkannya.
“Namanya kalimba. Kamu suka?” tanyanya.
“Hum, suka.”
Wanita itu mengelus rambutnya. “Mama kamu ke sini sebentar lagi, sudah ditelepon. Kamu engga pusing?”
Annika menggeleng. “Engga.”
“Alhamdulillah. Tadi kenapa kamu bisa ada di sawah?”
Jari Annika yang menekan-nekan tuts kalimba berhenti, teringat dengan jahatnya wajah teman-temannya saat menertawakannya. “… Di—didorong sama teman.”
“Oh. Siapa namanya?”
Annika menyebutkan nama-nama mereka. Awalnya, Annika tidak tahu kenapa wanita itu memintanya. Ia mendapatkan jawaban saat penerimaan murid baru SD Salsabila. Teman-teman yang merundungnya tidak diterima. Padahal sebelumnya murid-murid TK Salsabila selalu diterima apabila melanjutkan ke SD-nya. Rupanya, wanita itu adalah guru kesenian SD Salsabila. Ia selalu bersikap baik pada Annika. Sayangnya, Annika belum sempat diajar langsung olehnya, karena ia harus menikah. Bu Aira memberikan sebuah kalimba akrilik kepada Annika sebagai tanda perpisahan, kalimba yang saat ini tengah dimainkan oleh Annika.
Annika mengelus kalimba itu. Mengingat dentingan musik ‘Roadside Yellow Butterflies’ yang seakan mengusir mimpi-mimpi buruknya setelah tragedi itu. Sampai sekarang, nadanya selalu memberikan efek menenangkan bagi Annika.
Annika berhenti bermain ketika melihat seseorang masuk ke kamar. Danila rupanya. Baru masuk kamar, gadis itu langsung berlutut dan membuka semua laci dan bawah kasurnya. Penasaran, Annika pun masuk, dan melihat boneka-boneka rajut Danila yang diletakkan di lantai.
“Dan—ngapain?”
Mata Danila bersinar ketika menatapnya. Keringat yang mengalir di tepi wajahnya memperlihatkan bahwa ia buru-buru saat ke asrama (atau hanya menandakan cuaca September yang sangat panas). “Ada mbak di salah satu booth yang katanya tertarik sama gantungan kunciku. Katanya mau lihat karya-karyaku yang lain, kalau suka, dia mau beli. Oh, menurut kamu yang mana, Nik?”
“Bagus, Dan. Alhamdulillah. Tapi lucu-lucu semua, aduh, sayang kalau dijual,” keluh Annika, melihat satu persatu boneka yang telah dibuat oleh Danila dengan susah payah.
“Harus dijual, Nik. Mau buat beli benang lagi. Oh, aku bisa beli yang brand Nekomimi dan koleksi semua warnanya,” kata Danila, terpukau dengan mimpinya sendiri. Brand Nekomimi adalah brand benang rajut dari Shinriku yang terkenal dengan kualitas tinggi dan pilihan warna yang banyak.
Annika membantu Danila memilih, hingga akhirnya pilihan mereka jatuh pada boneka Lulu Fox, salah satu tokoh dari serial Aquatrix Little Sleuth Society, dan boneka rusa. Danila mengembalikan keenam boneka-boneka lain ke dalam laci. Sebelum gadis itu keluar dari kamar, Annika memperingatkan Danila, “Ingat, ya, minta harga yang masuk akal. Jangan mau kalau dibeli harga yang murah,” katanya, mengingat kadang-kadang Danila bisa bersikap amat polos—oh, bukan polos, tapi gadis itu punya pemikiran sendiri yang sulit ditebak. “Kalau mbaknya engga mau—nggak apa-apa, banyak yang mau beli kok, anak-anak di sini.”
Danila mengedipkan satu mata dan menyatukan ujung jari telunjuk dan ibu jarinya. “Iya! Dah, Annika!”
Annika tersenyum. Mencapai kelas empat di Aqiela Ru’ya dan sebentar lagi semua anak akan berumur enam belas tahun, rasanya ia sudah jauh lebih dewasa daripada tahun lalu. Ia penasaran apakah Danila akan tetap berfokus pada kegiatan merajutnya sampai lulus nanti. Kalau dirinya sendiri … apa, ya, yang akan ia lakukan? Apakah impiannya akan tercapai? Pasti menyenangkan kalau ia bisa memberikan pelajaran pada para murid tentang musik.
Tiga tahun lagi mungkin ia akan menemukan jawabannya—dan saat ini, ada sesuatu yang tampaknya lebih gigih dalam menarik perhatiannya. Sesuatu seperti tumpukan pakaian dan mesin cuci yang berputar. Oh iya, cuciannya menumpuk!
Setiap kamar di Aqiela Ru’ya telah disediakan mesin cuci masing-masing. Sebenarnya bukan pekerjaan yang sulit. Tapi kalau sedang malas, rasanya hanya memasukkan pakaian ke mesin cuci saja membutuhkan tenaga yang besar. Sebelum rasa malas menariknya untuk rebahan di kasurnya yang nyaman, Annika segera pergi ke area kamar mandi.
Area kamar mandi itu terdiri dari empat kamar mandi, tiga wastafel, dan ruang mencuci yang lumayan luas. Cahaya matahari masuk melalui jendela tinggi, sehingga ruangan itu lebih terang daripada kamar mandi biasanya. Setelah pakaiannya kering, Annika memasukkannya ke dalam ember dan membawanya ke lantai empat.
Panas sekali. Rasanya hanya sekali mengutarakan kalau hari ini panas sangat tidak cukup. Tapi Annika tetap menerjang rooftop yang panas itu. Ia mencari tempat yang luang, dan menemukannya berada di dekat gazebo. Ia membawa embernya ke sana. Saat akan menjemur jilbabnya, ia melihat seseorang di dalam gazebo.
Kiara.
Oh, ia tak menyangka akan bertemu dengan Kiara di tempat ini, saat semua anak-anak sedang berada di taman. Kiara tengah melihatnya dengan datar, entah apa yang ia pikirkan, di hadapannya terdapat buku-buku yang berserakan. Tapi kali ini ia tidak kelihatan akan kabur, seperti sebelum-sebelumnya.
“Kiara, kamu di sini.”
“Iya. Nggak apa-apa, kan, kalau aku engga ikut festival di taman?” tanya Kiara. Nadanya terdengar menyebalkan saat ia bertanya seperti itu.
“Nggak apa-apa, bukannya ngga wajib, kan?”
“Oh, iya ya. Aku jadi tenang setelah ‘prefek kebudayaan’ yang bicara.”
Annika mengerutkan dahi. Hatinya seakan dipanah. Sikap Kiara saat ini begitu menyakitkan untuk dihadapi. Kiara yang pengertian, ceria, penyayang, dan menyelamatkannya dari pertanyaan tidak nyaman yang dilontarkan oleh teman-teman lain telah menghilang. Digantikan oleh Kiara yang garang dan siap menyerangnya kapan saja dengan sarkasme penuh … kebencian?
Situasi telah berbalik saat ini. Namun, Annika masih yakin kalau ini belum terlambat. Ia menahan emosinya, dan berkata, “Aku sudah minta maaf, Ra. Aku tahu aku salah. … Apakah kamu bahkan membaca suratku?” tanyanya, ia telah meletakkan surat yang ia buat dengan penuh hati-hati di kasur Kiara kemarin.
“Nggak,” kata Kiara singkat. “Surat itu enggak mengubah apa pun, kan? Aku tidak akan repot-repot membacanya.”
Annika mengepalkan tangan. “Kalau kamu marah karena kamu tidak dipilih jadi prefek, harusnya bukan ke aku, Ra. Harusnya kamu protes ke Ustazah Soraya. Selama ini aku kira kamu marah karena aku tidak memberitahumu kalau aku mendaftar prefek. Aku sudah memuat penjelasanku di sana. Dan—banyak hal yang aku nggak bisa ucapkan secara langsung—kalau kamu nggak mau baca, atau kamu buang, aku harap kamu membakarnya dulu supaya enggak ditemukan oleh orang lain. Dan aku sama berhaknya dengan kamu untuk mendaftar sebagai prefek kebudayaan. Hasilnya sudah bukan di kontrolku lagi, jadi kamu harusnya enggak mendiamkanku separah ini!” serunya dengan suara bergetar. Matanya memanas, dan ia merasa sebentar lagi ia akan menangis. Rasa putus asa menggerogoti hatinya, melihat Kiara yang duduk di hadapannya dengan ekspresi yang sedingin es.
“Aku tahu kamu boleh mendaftar jadi prefek, bagian apa pun yang kamu mau. Tapi Ka, mau aku pahami seperti apa pun, aku nggak bisa menghindarkan diri kalau kamu sangat licik. Kayaknya engga ada teman yang sepertimu, rasanya semua teman yang baik engga akan merahasiakan pilihan bagian prefekmu, apalagi kalau sama sepertiku. Itu tuh kayak etika dasar. Tapi sikapmu yang diam-diam seperti seekor rubah itu sungguh mengesalkan! Kamu bilang karena kamu akan malu kalau engga keterima, tapi itu artinya kamu lebih mementingkan image baikmu sendiri dibandingkan persahabatan kita. Kamu lebih ingin muncul dengan semua kejayaan dan menyembunyikan kekalahanmu. Aku harap kamu melakukannya bukan karena ingin menunjukkan padaku kalau kamu bisa merebut semua yang aku usahakan, apalagi kamu selalu berkata kamu tidak berminat menjadi prefek. Melelahkan, engga mau terlalu sibuk, begitu katamu. Kamu engga tahu betapa kerasnya aku berusaha supaya aku bisa dipilih menjadi prefek. Kalau kamu bilang aja kemarin, rasanya engga akan kayak gini. Annika, aku selalu berpikir kalau kamu lebih baik dari ini!”
Annika terpaku mendengar kalimat demi kalimat menusuk yang dilontarkan padanya oleh Kiara (dari semua anak di kelas empat). Pada satu malam mereka pernah mengobrol sambil minum susu bersama di rooftop ini, tapi di malam lain, mereka saling melontarkan kalimat-kalimat penuh amarah yang terpendam. “Aku enggak berniat kayak gitu, Ra. Berhenti menuruti jalan pikiran burukmu sendiri! Aku kan sudah bilang kalau aku—sebenarnya, sangat sedih saat kamu berulang kali enggak nepatin janji dan lebih banyak main sama ‘teman-teman baru’ kamu. Aku hanya kepikiran kalau makrab bareng bisa bikin kita lebih deket lagi. Tapi kayaknya itu hanya impianku, ya? Aku rasa aku sendiri yang berusaha mempertahankan pertemanan kita.”
Pupil mata Kiara bergetar. Gadis itu tengah tergoyahkan oleh perkataan Annika, namun tak membiarkan hal itu menguasainya. “Harusnya kamu kalau merasa kayak gitu bilang aja, tapi kamu malah bikin plot tersembunyi. Banyak hal yang bisa diselesaikan asal kamu mau bicara langsung, bukannya menebak-nebak, lalu berencana diam-diam, dan akhirnya … kamu juga yang kena batunya. Annika, apa yang mau kamu lakukan dengan jabatan bergengsi yang enggak kamu inginkan ini?”


 floricialy
floricialy