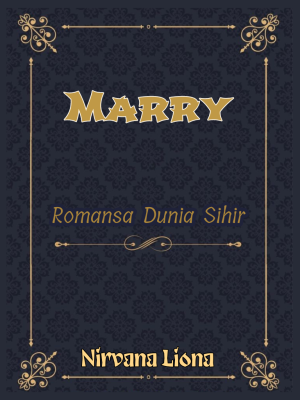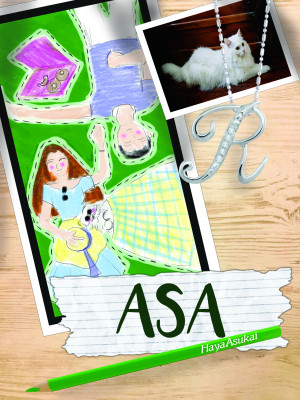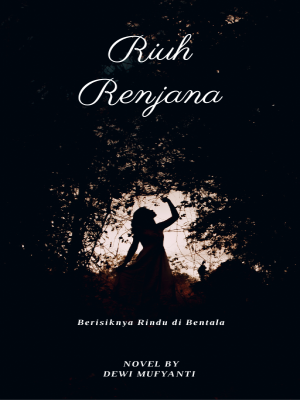“Jeff? Belum pulang?” tanyaku saat berjalan di koridor lantai satu usai mampir dari ruang Paskibra yang terletak di belakang sekolah.
Seperti biasa Jeff tersenyum padaku. Dia memasukkan ponselnya ke dalam saku kemeja seragam.
“Belum. Aku sedang menunggu jemputan. Kamu sendiri?”
Bukannya melanjutkan niatan untuk pulang, aku justru memilih ikut duduk di koridor bersamanya.
“Ini mau pulang, tapi daripada kamu sendirian, aku temani ya.”
Keputusanku untuk menemaninya memang tidak didasari oleh pemikiran yang panjang. Lebih tepatnya berpikir panjang mengenai bagaimana jika ada orang yang melihat kami berdua? Kemudian tercipta gosip yang makin menjadi-jadi di antara aku dan Jeff. Bagaimana jika aku makin disebut sebagai perusak hubungan orang? Karena akhir-akhir ini kedekatanku dengan Jeff sempat dijadikan alasan mengapa dirinya dan Mia putus. Padahal mereka berdua terlihat sangat cocok dan sudah menjalin hubungan hampir satu tahun.
Namun, aku tidak peduli dengan hal kekanak-kanakkan semacam itu. Aku hanya ingin berteman dengan Jeff. Tidak ada yang salah dengan niat baikku itu.
Kami pun berbincang apa adanya. Jeff bertanya padaku apa ekskulku menyenangkan, sebab sewaktu di kelas X dulu, dia sekelas dengan Bowo yang satu ekskul denganku dan Jeff mendengar darinya bahwa Paskibra sangatlah sulit. Mendengar itu aku tertawa. Tidak tahu ingin menjawab apa.
“Jujur … memang sulit awalnya, tapi sekarang menyenangkan kok,” ungkapku dimana kedua mata lebih mengarah pada sekumpulan anak lelaki yang tengah bermain basket di lapangan. Di waktu pulang sekolah, lapangan memang tidak pernah langsung sepi. Selalu saja ada yang menggunakan.
“Menurutmu, sesuatu yang sulit di awal, apa selalu menyenangkan di akhir?” tanya Jeff dengan raut wajah yang tampak sedih. Wajahnya menunduk menatap kedua kaki. Belum pernah aku menemukan Jeff murung seperti ini. Biasanya dia selalu ceria dengan caranya sendiri.
Aku berpikir sejenak sebelum menjawab.
“Mungkin. Soalnya ada peribahasa yang mengatakan berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Jadi menurutku, kurang lebih itu juga bisa diartikan kalau kamu ingin mendapatkan kesuksesan, kesenangan, kamu harus berjuang menghadapi kesulitannya dulu,” jelasku sebaik mungkin agar Jeff bisa mengerti.
Jeff mengangkat wajahnya. Dia menatapku dengan bibir serta kedua mata yang tersenyum.
“Benarkah? Apa itu ada di buku Bahasa Indonesia? Kelihatannya aku melewatkannya,” ujarnya tertawa.
Lihat. Jeff memang tidak cocok jika dipasangkan dengan wajah yang muram.
“Kamu bisa temukan itu di kamus peribahasa, Jeff.”
“Ternyata aku masih harus banyak belajar. Akan aku minta Ibuku untuk membelikannya.”
Kami berdua pun tertawa. Sekilas kurasa ada seseorang yang melihatku, tapi mungkin hanya perasaanku saja.
“Ana, apa kamu tahu?” Pertanyaanya menarik perhatianku. “Saat aku pindah ke sini, kupikir aku akan diterima dengan mudah, tapi ternyata aku salah. Selama dua tahun ini aku sudah berusaha, tapi aku rasa aku masih jauh tertinggal. Aku ingin berteman, tapi seperti ada syarat-syarat tertentu yang dimiliki setiap kelompok. Dan sampai sekarang aku tidak menemukan di mana kelompokku.”
Aku bersyukur dia berhenti bicara. Ucapannya barusan terdengar menyedihkan dan memang ada benarnya. Jangankan di ruang lingkup sekolah, di kelas pun sebagian dari kami memang tampak seperti membuat kelompok-kelompok. Mereka mungkin tidak menyadarinya, melainkan orang lain yang melihatlah yang menyadari. Dan bagi orang yang menyadari dirinya tidak memiliki kelompok, di situlah dia akan merasa tertekan akibat merasa sendiri.
Mungkinkah di mata Jeff aku juga termasuk ke dalam orang yang berkelompok itu? Aku tidak berani bertanya.
Jeff belum bicara lagi. Dia justru menatap sekumpulan lelaki yang bermain basket di lapangan. Seolah-olah aku bisa membaca apa yang ada di pikirannya, aku tahu jika saat ini Jeff sedang berpikir, anda saja dia dapat bergabung untuk bermain bersama mereka.
Keberadaanku di sampingnya terasa tidak berguna apabila terus membiarkannya muram seperti ini. Aku harus melakukan sesuatu untuk mengembalikan keceriaannya.
“Jeff, jangan pesimis. Di saat kamu berpikir kalau kamu ngga memiliki kelompok, tanpa kamu sadari mungkin ada kelompok lain yang justru sedang mencari bahkan menanti anggota seperti kamu. Jadi kamu hanya tinggal tunggu waktu dan jangan berhenti berusaha. Karena faktanya ngga ada di dunia ini orang yang benar-benar sendirian.”
Jujur saja aku tidak tahu apa yang lucu dari perkataanku. Namun, anehnya Jeff justru tertawa geli. Aku merasa seperti baru saja menjadi seorang motivator yang gagal.
“Kamu benar, Ana,” katanya setelah akhirnya berhenti tertawa. “Kenapa aku bisa memiliki pikiran menyedihkan seperti itu?”
Aku senang jika ternyata aku tidak gagal. Senang juga bisa membantu dan melihatnya melepas rasa sedih.
“Tunggu deh. Kamu kan pernah jadi pacarnya Mia, Jeff. Dan banyak dari kita yang sebenarnya sangat mendukung hubungan kalian. Kenapa kamu masih berpikir kamu sendirian?”
Lagi-lagi lengkungan senyumnya berangsur memudar.
“Tapi kenyataannya Mia tidak benar-benar menerimaku,” jawabnya kembali menunduk.
Ini salah. Tidak seharusnya aku membahas hal yang lalu. Susah payah aku menghilangkan kemurungan Jeff, kini aku pula yang mengembalikannya. Bagaimana lagi caranya aku memperbaiki keadaan?
Tiba-tiba saja sebuah bola basket bergulir dan berhenti di samping kakiku.
“Ngga perlu diambil!” seru seseorang dari tengah lapangan sewaktu tanganku baru saja ingin menyentuh bola.
Randa datang dengan kondisi yang sudah bersimbah peluh. Kalung rantainya, serta bulir-bulir keringat di permukaan rambut plontosnya berkilau. Dia mendekat, membungkuk untuk mengambil bola, dan berdiri sejenak tepat di hadapanku. Kedua matanya bergerak secara bergantian melihatku dan Jeff.
“Ternyata emang lo sendiri yang buat masalah," katanya, kemudian pergi tanpa memberi penjelasan lebih.
Sungguh otakku tidak mampu mencari tahu maksud dari ucapannya. Aku hanya terus memperhatikan sosoknya yang tak lagi ikut bermain basket di lapangan. Dia mengambil tas ranselnya yang tergeletak di podium upacara, lalu pergi mengarah keluar gerbang. Saat itu juga tidak sengaja kulihat Eca, Yogi, dan Dino sedang berdiri mengobrol di depan ruang UKS. Entah kenapa mataku cukup lama tertuju pada Yogi, bahkan bibirku sedikit melengkungkan senyuman. Aku tahu dia sempat melihatku, tapi tidak kuduga wajahnya langsung berpaling tanpa membalas senyumku dan mereka pun pulang bersama.
Aneh. Tidak biasanya Yogi bersikap dingin seperti itu.


 elhrln
elhrln