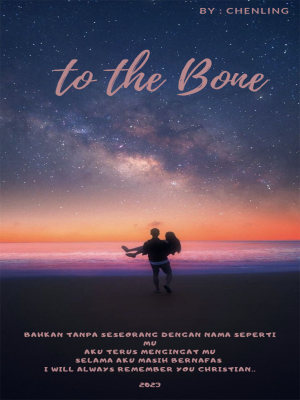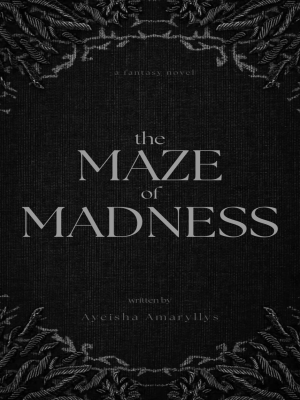Waktu belum tengah hari, tetapi Sawala sudah menggandeng tangan kiri Tisha untuk melewati gerbang. Di hari kesebelas mereka memang pulang cepat. Setelah istirahat, semua siswa dibubarkan karena guru harus mengadakan rapat.
Begitu tiba di pinggir jalan, Sawala melambai-lambaikan tangan untuk memberhentikan sebuah angkot. Kemudian, Sawala mengode Tisha untuk naik lebih dulu, sementara dia mengikuti. Tadi pagi motor Sawala mogok, tepat beberapa meter dari sekolah. Sekarang masih diperbaiki di bengkel dekat sana dan katanya baru akan selesai besok, jadilah mereka harus pulang naik angkot.
Ternyata di dalam angkot itu sudah ada banyak penumpang, sebelas orang, mereka duduk berdempetan, menyisakan sedikit bagian kosong di ujung bangku panjang dan sebuah bangku pendek pengganjal pintu pintu.
Sebenarnya Tisha ingin duduk di bangku pengganjal itu, tetapi karena telanjur masuk lebih dulu dia terpaksa mengisi sisa bangku panjang, bersisian dengan seorang ibu yang memegangi seorang balita perempuan yang berdiri di dekat kakinya.
Setelah Sawala duduk, angkot pun melaju. Berbeda dengan Tisha yang memasang wajah datar, Sawala malah memamerkan senyuman lebar. Sawala tak segan mengangguk sopan pada penumpang lain yang bertemu tatap dengannya. Bahkan Sawala juga mencandai balita yang tadi dilihat Tisha.
Balita itu tampak kesenangan, sampai tertawa malu-malu. Sayangnya itu tak bertahan lama, karena tiba-tiba dia berbalik menghadap sang ibu dengan wajah sayu.
“Mau duduk ....” Meskipun suara balita itu tak terlalu keras, tetapi karena berada dalam jarak yang begitu dekat, maka Tisha dan Sawala dapat mendengarnya.
Dari sudut matanya, Tisha melihat sang ibu menggeleng kemudian mengusap perutnya yang membuncit, ternyata sedang hamil dengan usia yang Tisha perkirakan sudah mendekati waktu lahiran karena ukurannya cukup besar.
“Pegal, Bu.” Mengabaikan kondisi sang ibu, balita itu masih terus merengek, bahkan kini wajahnya sudah memerah dan matanya berkaca-kaca.
Mungkin karena tak ada pilihan lain, akhirnya sang ibu hanya bisa menghela napas, kemudian menyelipkan jemari tangannya ke ketiak sang anak, bersiap mengangkatnya ke pangkuan.
Namun, suara Sawala menginterupsi. “Coba sini sama Kakak, Dek.”
“Eh?” Si ibu terkesiap.
Sawala menggerak-gerakkan tangannya untuk menarik perhatian si anak, sehingga balita itu memandang bergantian pada ibunya dan Sawala. “Enggak apa-apa, ya, Bu? Biar sama saya aja adeknya.”
Si ibu tersenyum segan, tetapi kemudian melepaskan jemarinya, membiarkan sang anak beralih mendekat Sawala. “Terima kasih, Nak.”
“Sama-sama.” Sawala tersenyum. Setelah balita itu nyaman di pangkuannya, dia kembali mencandainya sambil menunjuk-nunjuk ke arah luar, menjelaskan apa saja yang dilalui.
Lagi-lagi Tisha dibuat tertegun karena aksi Sawala. Kenapa kakak kelasnya itu mudah sekali menawarkan bantuan? Kenapa terlihat tidak memiliki rasa keberatan atas apa pun yang dilakukannya?
Menit berlalu, angkot terus melaju. Satu per satu penumpang mulai menyerukan kata 'kiri' dan kemudian turun, termasuk pasangan ibu-anak itu, mereka pun turun setelah berterima kasih pada Sawala. Kini, lengang, hanya tersisa Tisha dan Sawala.
“Kamu sering naik angkot, Dek?” Sawala memecah keheningan. Kini dia sudah berpindah ke sebelah Tisha.
Tisha yang belum lama merasa lega karena turunnya penumpang lain, harus kembali menahan napas, tegang karena kedekatan tubuhnya dengan Sawala. Sembari menggosok-gosok kedua telapak tangan, Tisha menyahut pelan, lebih seperti cicitan. “Enggak terlalu.”
“Kalau boleh tahu biasanya kalau pergi ke mana kamu naik angkot?”
Tisha terdiam. Mengingat kenangan ketika masih duduk di bangku sekolah dasar, saat orang tuanya masih ada. Dulu Tisha pernah beberapa kali naik angkot untuk bermain dan mengerjakan tugas dengan Fathan. Namun, Tisha tidak terlalu menyukainya. Baginya yang dulu sangat manja, naik kendaraan pribadi adalah kenyamanan yang tidak mau dia lepaskan.
Seketika sesak kembali menyeruak ke dada Tisha. Ah, andai dulu dia bisa sedikit berusaha untuk menyukai naik kendaraan umum ini dan pergi ke rumah Fathan sendiri, mungkin orang tuanya tak akan tiada setelah mengantarnya. Ah, Tisha benci diri sendiri.
Namun, kata Riana tidak ada yang pantas disalahkan. Ah, Tisha galau.
“Dek!”
Tisha terkesiap karena tepukan di pundak. Ternyata dia terlalu larut dalam perenungan sampai melupakan Sawala.
“Kamu nangis?” Sorot khawatir terpancar dari tatapan Sawala karena melihat sudut mata Tisha berair.
Tisha membuang pandangan. Cepat mengangkat ujung kerudung untuk mengusap muka. Sial. Kenapa dia tidak bisa mengendalikan diri? Biasanya dia selalu bisa menyembunyikan segala perasaan, terlebih di hadapan orang yang tidak dianggap dekat. Bagaimanapun menyentuhnya suasana atau perkataan orang lain, Tisha senantiasa memasang ekspresi datar. Lalu kenapa dia sekarang?
“Duh, maaf kalau pertanyaan aku bikin kamu enggak nyaman. Tidak perlu dijawab.” Suara Sawala sarat rasa bersalah. “Maaf banget, ya, Dek.”
Tisha memejam sesaat, mengembuskan napas panjang, kemudian menggeleng. “Enggak ada yang salah dengan pertanyaan Kakak.” Meski masih bingung dengan apa yang terjadi pada dirinya sendiri, tetapi Tisha tak mau membuat Sawala merasa tak enak dengannya.
Usai berdeham dan menetralkan mimik, Tisha melanjutkan, “Aku hanya pernah naik angkot saat SD. Ini baru naik lagi.”
“Tapi kamu enggak apa-apa, kan? Maksudku, kan kamu udah lama enggak naik angkot, sekarang gimana perasaan kamu?”
Sendu, bikin kangen ortu, balas Tisha dalam hati.
“Enggak pusing?” Sawala kembali bertanya melihat Tisha hanya bungkam. “Kalau pusing kita naik ojek saj–”
“Aku baik, Kak.” Tisha memotong tegas.
Sawala memundurkan wajah. “Oke, oke.”
Tisha panik. Mendapati raut Sawala yang seperti itu mengingatkannya pada beberapa hari lalu, saat Sawala seperti cuek padanya. Seketika Tisha menelan ludah susah payah. Tidak! Jangan sampai itu terjadi lagi. Dia kan kini memiliki tantangan tambahan dari Riana, jika Sawala cuek maka langkah Tisha akan terganggu.
Kepala Tisha bercabang. Memikirkan topik yang mungkin dia ucapkan untuk mencegah Sawala menjadi jutek. Beberapa detik kemudian dia mengerjap, lalu memandang lekat Sawala yang sedang memperhatikan tautan tangannya di atas rok.
“Uhm ..., Kak.” Tisha menahan gugup.
“Kenapa, Dek?’
“Kakakkenalibutadi?” tanya Tisha merepet sambil memejamkan mata.
“Hah?” Sawala mengernyit. “Minta tolong pelan-pelan bicaranya, Dek.”
Tisha menggigit bibir bawah, perlahan membuka kelopak mata. “Kakak ... kenal ibu tadi?”
Sejenak Sawala mencerna. “Yang barusan turun?”
Tisha mengangguk.
Sawala menggeleng. “Baru pertama bertemu sekarang. Kenapa memangnya? Kamu kenal, kah?”
“Enggak!”
“Jadi, kenapa bertanya?”
“Itu ....”
“Sebentar, Dek!” Sawala menepuk paha Tisha, sementara kepalanya melongok ke dekat supir. “Kiri, Mang!” serunya begitu mendekati pertigaan daerah Tisha.
Tisha baru sadar bahwa perjalanan mereka hampir selesai. Dia turun lebih dulu atas perintah Sawala, sementara kakak kelasnya itu membayar ongkos. Sawala memang akan mampir ke rumah Tisha karena bibinya, Bu Santi, bilang akan menjemput di sana.
“Ini, Kak.” Tisha mengangsurkan uang lima ribu saat mereka mulai menapaki pinggiran jalan menuju rumahnya.
Sawala menggerak-gerakkan telapak tangan. “Enggak usah, aku traktir,” katanya sembari memamerkan senyuman. “Waktu di angkot tadi, kamu mau ngomong apa?”
“Itu ... kalau Kakak enggak kenal Ibu tadi, kenapa Kakak mau bantu mangku anaknya?”
Sawala mengangkat kedua sudut bibir. “Membantu itu tidak perlu memandang siapa orangnya, kan, Dek?”
Tisha tetap merapatkan bibir. Dia tahu itu pertanyaan retoris. Sedikit membaca arahnya, perasaan Tisha mulai tak enak.
“Selama bukan untuk sesuatu yang buruk, kita boleh membantu siapa saja yang membutuhkan, terlepas dari kenal atau tidak.”
Nah, kan ... ini tentang kebaikan. Seperti yang selalu Riana ceramahkan. Sebab, sudah beberapa tahun ini luput–ah lebih tepatnya sengaja Tisha lupakan–dari hari-harinya. “Lalu, untuk yang lainnya?”
Sawala menyatukan alis. “Gimana?”
Tisha berdeham. Sebenarnya dia segan membahas ini, tetapi mungkin memang sudah saatnya mewawancarai Sawala untuk memenuhi tantangan tentang alasan aksi Sawala. “Sikap Kakak saat membantu orang-orang di perpus, beresin mukena, ngasih makan kucing, dan ... mengunjungi panti. Apa alasan Kakak melakukan itu semua? Kenapa Kakak mau bantu banyak orang, yang kadang enggak semuanya tahu terima kasih?”
Sawala menghentikan langkah sejenak. Kepalanya mendongak pada langit biru tengah hari. “Itu semua aku lakukan sebagai upaya mengejar mimpi tertinggi.”
Tisha turut menengadah dengan raut bingung. “Memang apa mimpi Kakak? Menggapai langit?”
Sawala terkekeh renyah. “Langit memang tinggi, tetapi aku menginginkan yang lebih dari itu.”
“Apa?”
“Menjadi ... sebaik-baiknya manusia, yang bermanfaat. Aku enggak mengharap balasan terima kasih dari manusia. Aku hanya mengharapkan keberkahan dari Allah SWT. Aku sangat-sangat berharap bisa meraih itu.”
Bagi Tisha, waktu seakan berhenti. Kata-kata Sawala menggaung keras dalam kepalanya. Kenapa bisa ada yang bermimpi seperti itu?


 salwariamah
salwariamah