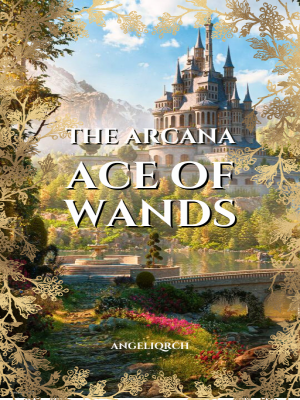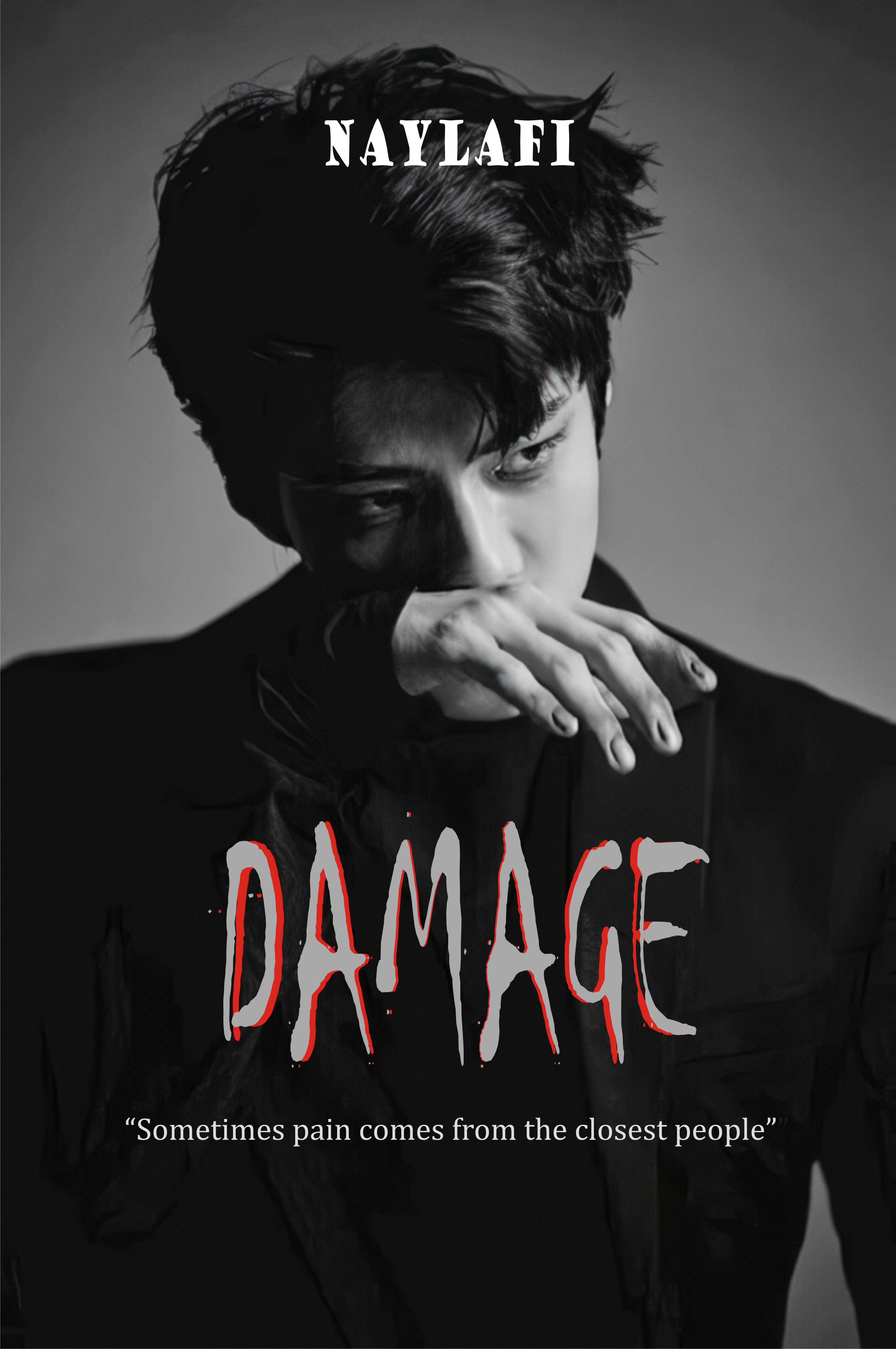Mereka tiba di depan rumah Tisha bersamaan dengan berkumandangnya azan Zuhur. Sambil membuka gerbang, Tisha menimbang, haruskah menawarkan Sawala untuk salat di rumahnya? Mengingat bagaimana taatnya gadis itu dalam melaksanakan ibadah tepat waktu, Tisha jadi merasa takut jika Sawala akan telat.
“Mau salat, Kak?” ucap Tisha akhirnya.
Sawala yang semula memperhatikan tanaman di pekarangan rumah Tisha, menoleh. “Boleh?”
Tisha menahan diri untuk tidak berdecak. Menurutnya sahutan Sawala barusan terlalu basa-basi. Jika Tisha sudah menawarkan, maka jelas dia memperbolehkan. “Mari ke musala.” Tisha mendahului ke bagian pinggir rumah, menuju ruangan di belakang garasi.
Sawala mengekor sambil mengeluarkan sesuatu dari tasnya.
Tisha baru menyadarinya setelah membuka pintu musala. “Kakak bawa mukena?” Eh, Tisha ingin mencubit diri sendiri. Tadi dia mengatai Sawala yang bertanya basa-basi padahal sudah tahu jawabannya, tetapi ternyata kini dia juga tak jauh beda. Sungguh memalukan.
Sawala mengangguk. “Kebetulan ada di tas.”
Tidak mungkin hanya kebetulan. Tisha mencibir dalam hati. Pasti Sawala memang mempersiapkannya. Mengingat seminggu ini dia selalu salat di sekolah dengan menggunakan mukena sendiri, bukan tidak mungkin bahwa itu adalah benda yang wajib Sawala bawa ke mana-mana, sehingga selalu ada dalam tasnya.
Rasa lega menyelusup hati Tisha. Setidaknya pilihan untuk membawa Sawala ke tempat ini tidak terlalu salah. Dengan begini, dia tidak akan membuat Sawala berdosa karena melalaikan ibadahnya.
“Berjamaah?”
Tisha mengerjap. Memandang penuh tanya Sawala yang ternyata sudah mengenakan mukena. Oh, pasti Sawala sedang menjalankan kiat meraih mimpinya, mengejar pahala terbesar. Kalau tidak salah ingat, Tisha pernah mendengar bahwa pahala orang yang salat berjamaah lebih bagus 27 derajat daripada yang salat sendirian.
Jadi, Tisha segan untuk menolak, tidak mau menghambat Sawala meraih mimpinya. Akhirnya. Tisha pun mengangguk dan setelah berwudu dia mengambil tempat di belakang Sawala, menjadi makmumnya.
Sekian menit kemudian, dua salam terdengar, menandakan salat selesai. Seperti biasa, sementara Sawala masih terlihat berdoa, Tisha sudah cepat-cepat melepas mukena kemudian menggulung-gulungnya. Dia tak merasa perlu terlalu rapi, toh musala ini juga jarang digunakan. Hanya
Sawala menoleh pada Tisha sambil memajukan tangan, hendak bersalaman. Tepat saat Tisha menyambutnya, terdengar suara khas perut. Keduanya tertegun.
“Kakak lapar?” tanya Tisha begitu tangan mereka terlepas. Menyadari suara itu berasal dari Sawala.
Sawala menyengir di tengah kegiatan melipat mukena. “Hehe, sedikit.” Wajahnya bersemu malu.
“Yuk, makan!” ajak Tisha tiba-tiba. Entahlah ada apa dengannya, dia hanya merasa harus melakukannya. Mengingat waktu sudah masuk tengah hari. Tiba saatnya makan siang.
“Eh?” Sawala yang baru selesai membenahi kerudung agak terkejut. “Di mana?”
“Di sini.” Tisha bangkit dan menuju meja kecil di sudut ruangan, tempat meletakkan alat-alat salat.
Refleks Sawala ikut bangkit. “Gimana?” Masa makan di sudut musala?
“Maksudku di rumahku!”
“Tapi, Dek ....” Sawala merasa tak enak.
“Ayo!” Tak membiarkan Sawala membantah, Tisha segera menggandeng Sawala ke luar.
Begitu memasuki rumah, Tisha baru menyadari pergerakannya yang di luar kebiasaan, segera saja dia melepaskan Sawala. “Maaf,” ungkapnya tak enak.
Selama ini Tisha tidak pernah melakukan hal seperti itu. Dia tidak pernah memaksa apalagi menyeret sembarang orang, kecuali Riana. Ah, Tisha makin tidak mengerti dengan dirinya sendiri.
Setelahnya, Tisha memilih diam. Bahkan saat sampai ruang makan, dia hanya menggunakan tangan dan kepala untuk mengisyaratkan Sawala duduk, sementara dirinya memanaskan makanan sebentar, kemudian menghidangkannya di hadapan Sawala. Mereka pun melahap dalam keheningan.
“Alhamdulillah.” Sawala mengusap bibir dengan tisu setelah menghabiskan isi piring. “Makanannya sangat-sangat enak. Terima kasih, ya, Dek.”
Tisha mengulum senyum. “Sama-sama.”
Sawala terpana melihatnya. Sangat menggemaskan. Membuatnya mengingat seseorang yang berharga baginya.
“Maaf, ya, Dek.”
Tisha mendongak. Untuk apa lagi Sawala meminta maaf?
“Maaf aku pernah bersikap agresif ke kamu, karena kamu ... mengingatkan aku pada adikku.”
Tisha menaikkan sebelah alis. “Adik?”
Sawala mengangguk. “Maaf sebelumnya, tapi menurutku kamu ... seperti adikku yang sudah meninggal.” Jeda sejenak, Sawala mengambil napas. “Senyummu entah kenapa membuatku merasa memiliki tarikan khusus untuk berdekatan dengan kamu. Aku jadi senang bersama denganmu.”
“Me-meninggal?”
“Iya, dia meninggal dua tahun lalu bersama orang tuaku karena longsor yang menimpa rumah kami.” Sawala mengembuskan napas sejenak. “Aku benar-benar minta maaf karena sudah lancang menyamakan kamu dengan orang yang sudah tidak ada.”
“Eh, enggak!” Tisha menggeleng cepat. “Enggak apa-apa. Kakak boleh menganggap aku ... adik Kakak.” Oh, lagi-lagi Tisha tidak bisa mengendalikan diri. Entah apa yang mendorongnya memberikan tawaran itu.
“Terima kasih, Dek.” Sawala tersenyum haru. Bahkan tangannya naik mengusap sudut mata.
“Itu ....” Ragu-ragu Tisha menunjuk tangan Sawala.
Sawala mengusap tangan. “Iya, ini bekas kejadian itu. Aku juga tertimpa reruntuhan, tapi enggak sebanyak keluarga yang lain karena aku baru pulang ngaji, baru sampai teras. Jadi, alhamdulillah aku selamat.”
“Sekarang ... Kakak tinggal dengan siapa?” Tisha sebenarnya tidak enak mengeluarkan tanya itu. Namun, dia tidak bisa lagi menahan rasa penasaran. Kepalang tanggung sudah mendengar sedikit cerita latar belakang Sawala, jadi sekalian gali sebanyak-banyaknya saja. Toh tujuannya mencari tahu juga bukan untuk melakukan kejahatan.
“Kakek dan Nenek, orang tua ayahku dan Bu Santi.”
“Jauh dari sini?”
“Enggak terlalu. Rumahku ada di desa sebelah. Daerah kamu ini kelewatan kalau mau ke sekolah.”
Tisha bernapas lega. Setidaknya dia tidak terlalu merasa bersalah karena harus membuat Sawala bolak-balik memutar jalan saat mengantar jemputnya.
“Eh!” Sawala merasakan getaran dari ponsel yang ada di saku rok.
Tisha heran. “Kenapa, Kak?”
“Bu Santi udah di luar.” Sawala kembali mematikan ponsel. “Maaf, ya, kayaknya aku mau SMP.”
“Hah?”
Sawala terkekeh. “Sudah makan pulang. Aku mau pamit, ya.”
“Oh, iya, Kak. Silakan.” Tisha pun bangkit, menemani Sawala ke halaman.
***
Setelah kepergian Sawala, Tisha kembali masuk dan menuju ruang keluarga. Dia merebah di sofa dengan tatapan tertuju pada langit-langit ruangan. Embusan napas panjang Tisha keluarkan. Ternyata latar belakang Sawala mirip dengannya. Sama-sama yatim piatu, telah kehilangan orang-orang tersayang. Bedanya Sawala juga kehilangan saudara, sementara Tisha masih memiliki Riana di sisinya.
Perbedaan lainnya, Sawala tidak terlihat muram. Sorot wajahnya senantiasa cerah. Keberadaannya selalu memancarkan aura positif pada orang-orang di dekatnya. Berbeda dengan Tisha yang senantiasa bersikap dingin, kaku, membatasi interaksi, menunjukkan kegelapan.
Ah! Tisha menjambak rambut. Sebenarnya dia tak ingin terus seperti ini, dia juga lelah berkubang dengan rasa sakit karena masa lalu. Dia ingin sembuh dan menjalani hari dengan lebih baik. Namun, Tisha terlalu bingung. Tak tahu bagaimana langkah awalnya.
Mungkinkah harus dengan membenahi tujuan hidupnya? Namun, untuk apa?
Selain mencari kenyamanan sendiri, hidup ini untuk apa?
“Menjadi ... sebaik-baiknya manusia, yang bermanfaat.”
Ucapan Sawala tiba-tiba terngiang.
“Meraih keberkahan dari Allah SWT.” Tisha terpejam. “Allah ... Allah ....” Untuk beberapa saat Tisha terus mengulang-ulang kata itu sembari meremas dada. Sampai tanpa sadar sebulir air mata jatuh ke pipi. Allah, Tuhannya, yang seharusnya menjadi tujuan hidupnya.
Namun, Tisha merasa hidupnya telanjur gelap. Terbelenggu luka, sampai jauh dari Sang Pencipta. Tisha menangkup muka. Bisakah ... dia memperbaiki diri dan kembali ke jalan-Nya?


 salwariamah
salwariamah