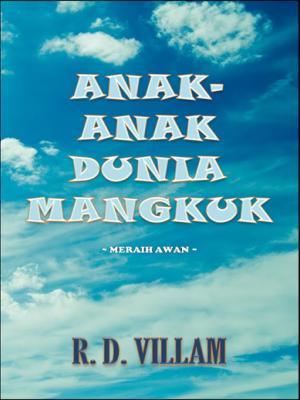Semester enamku sudah hampir berakhir dan setelah libur semester nanti, kelasku akan menjalani kerja praktik di apotek dan di rumah sakit. Aku sangat menanti-nantikan liburan yang kali ini, karena di tahun ketigaku aku hanya sempat pulang saat libur Natal dan libur pertengahan semester lima. Beberapa anak asrama sudah duluan pulang kampung, karena jadwal ujian akhir semester tiap kampus berbeda-beda. Elena juga sudah pulang, sedangkan Kristin dan aku yang satu kampus termasuk yang masih tinggal.
Obrolanku yang terakhir kali dengan si Bocah Hakim masih terngiang-ngiang di pikiran, dan aku jadi ingin membaginya dengan Kristin, tapi belum ada waktu yang tepat bagi kami untuk saling bercerita. Proyek penelitiannya dengan dosennya betul-betul melahap habis waktu dan tenaganya. Kudengar, dia bahkan harus banyak bepergian untuk meliput berita, dan bisa saja sampai seharian belum dapat.
Akhirnya, momen itu pun kami dapatkan di hari Minggu tepat sebelum ujian akhir semester enam. Kamarku kosong, tinggal aku sendiri yang belum pulang kampung, dan Kristin tiba-tiba bertamu malam itu.
“Hei. Masih belajar?”
Aku mendongak dari buku-bukuku yang terhampar, tersenyum senang melihatnya seolah lama tak bertemu (yang kenyataannya memang demikian). “Iya, sih. Nggak apa-apa, sini. Ada apa, Tin?”
“Pengen ngobrol aja, Ra. Nggak papa, nih?”
“Boleh. Tuh, pakai aja kursinya Elena.”
Kristin menempatkan diri di kursi itu dan kudapati bahwa wajahnya agak pucat. Barangkali karena kecapekan menjalankan proyek, yang kudengar juga bisa dilanjutkannya sebagai penelitian skripsi semester depan.
“Kamu ikut karaokean PSM yang kapan lalu itu, Ra?”
Aku agak terkejut karena Kristin memilih topik itu. Sudah seminggu berlalu sejak hari itu.
“Iya. Kenapa?”
Nada suaraku pasti kedengaran defensif karena Kristin cepat-cepat berujar,
“Maaf, aku nggak bisa ikut waktu itu. Dan, maaf ... aku cuma denger kabar simpang siur dan aku mau memastikan ke kamu.”
“Kok malah minta maaf?” sahutku bercanda, tapi Kristin masih serius meski tampak ragu. Perasaanku tak enak. “Ya udah, bilang aja.”
“Oke. Katanya waktu karaoke itu kamu melamun terus dan tiba-tiba ketawa sendiri.”
Aku mengernyit tapi diam saja. Kristin melanjutkan,
“Katanya vertigomu kumat, dan aku tahu kamu memang pernah sakit vertigo, tapi mereka bilang kamu kayak kena waham.”
“Kok, bisa gitu?” tanyaku dengan sepercik nada gusar.
Kristin sedang mencari-cari kata yang tepat, jelas sekali melihatku mulai tersinggung. Dia seperti cerminku, demikian pula sebaliknya. Jadi dia mestinya sudah menduga bakal seperti apa reaksiku bahkan sebelum dia mulai cerita. “Kata mereka, kamu seolah ... bertingkah seolah orang penting yang minta diperhatikan baik-baik.”
“Mana ada aku yang kayak gitu?” Aku tertawa sinis. “Kristin, kamu tahu sendiri aku orangnya kayak apa. Mending aku nyungsep ke bawah tanah daripada disuruh maju pidato. Buat Dies Natalis kemarin, sih, pengecualian, ya.”
“Makanya, Ra. Aku nggak percaya. Tapi, yang ngomong tentang ini ada lebih dari tiga orang.”
Sekarang aku tertegun. Bahkan Markus tidak bilang apa-apa padaku. Atau dia memang tak tahu, dan kabar ini tersiar di antara teman-teman seruangan waktu itu? Tapi bahkan Kristin yang tidak ikut karaoke pun bisa tahu.
“Gini, Tin. Biar kuluruskan.” Kutatap Kristin dengan sama seriusnya.
“Ya, aku ke sini memang minta diluruskan.”
Aku mendengus geli. Kristin bisa begitu lucu sekaligus serius di saat yang sama. “Waktu itu, Fidelia muncul.”
Kristin tampak terperanjat sekaligus lega. “Oh,” ucapnya. Ceritaku pun tercurah, bagaimana aku memperkirakan jatah waktu untuk karaoke sudah habis dan si Pengingat memang muncul, lalu baru belakangan tahu bahwa ada yang mengambil uangku. Sampai sekarang aku tak tahu siapa yang mengambil, tapi bukti nyatanya ada, dompetku berantakan dan aku ingat terakhir kali masih ada sejumlah uang di dalamnya.
Kristin terpekur lama setelah aku selesai bercerita.
“Kalau aku jadi kamu, Ra, kayaknya aku juga nggak tahu harus bertindak apa. Mungkin aku juga bakalan bingung.”
Aku senang Kristin bisa memahamiku. Tapi, perasaan tak nyaman bahwa teman-teman di PSM menganggapku aneh membuatku sebal ....
“Ya sudah, sih. Semester depan kayaknya aku off dulu dari PSM. Aku ada kerja praktik soalnya,” ujarku akhirnya. Kristin tersenyum simpul dan kulihat kelopak matanya agak menghitam.
“Yeah. Semangat, ya, Ra. Aku juga mau off, mau fokus ke penelitian.”
“Kamu tidur yang cukup, ya, Tin. Belakangan sering begadang?”
“Nggak juga. Cuma memang hampir tiap hari keluar seharian tuh, jadi pas sampai asrama bawaannya pengen langsung terkapar di kasur aja.”
Kami sama-sama tertawa, tahu benar sensasinya capek secapek-capeknya dan kapan saja aroma bantal serasa bagai surga. Kuurungkan niatku untuk bercerita tentang kesengsaraan si Hakim. Sepertinya Kristin perlu segera tidur.
*
Soal ujian semester enam, tak ada perbedaan yang cukup berarti. Aku masih mendengar terompet Fidelia ditiup di ruang ujian, tapi pelan dan singkat, lagipula tidak ada si Hakim yang bernyanyi di tiap kesempatan setelahnya. Mestinya orang sudah sadar diri untuk tidak berbuat curang, apalagi setelah apa yang dialami Dian waktu pertengahan semester.
Di akhir semester, biasanya digelar beberapa kuliah tamu di fakultasku. Sebelumnya, pengajar merupakan praktisi dari rumah sakit, dari badan pengawasan obat, maupun dari pemerintah. Rupanya di kuliah tamu kali ini, yang diselenggarakan di hari terakhir tahun ajaran seusai ujian semester, pengajarnya lain dari yang lain.
Pria itu seorang wirausahawan. Pengusaha tanaman obat dan pengelola pabrik jamu dengan cabang di mana-mana di seantero nusantara. Istilah hibrida kerennya, pharmapreneur.
Dia memulai kuliahnya bukan dengan how to become a great pharmapreneur, sesuatu yang dinanti-nanti dan diantisipasi banyak orang melihat titel pada namanya. Tapi tidak. Malahan dia mengawali dengan how NOT to become a bad one dengan pertanyaan-pertanyaan yang menggiring keingintahuan.
“Di sini ada yang mau kerja di pabrik obat?” Dia bertanya. Banyak yang mengiyakan, mayoritas teman-temanku yang berminat di farmasi industri. Selanjutnya pria necis berdasi itu memancing,
“Mau bikin pabrik obat sendiri? Produksi sendiri?”
“Mauuu.” Sahutan antusias berkumandang di dalam kelas.
“Mau produksi dan jualan morfin, fentanil?” Dia menyebutkan sederet obat-obatan narkotika, pereda nyeri berefek kuat yang diawasi pemerintah. Para mahasiswa masih semangat menyahut. “Gimana lorazepam, alprazolam?” Selanjutnya dia menyebut obat-obat penenang. “Pasarnya luar biasa besar kalau di situ. Banyak sekali yang mencari, terutama yang di luar instansi legal. Orang bisa kaya-raya hanya dari berjualan psikotropika.”
Pada kalimat itu seisi ruangan jadi ragu untuk menanggapi. Kami semua tahu bahwa obat-obat yang disebutkan tadi diatur secara ketat oleh pemerintah, mulai dari bahan bakunya, produksinya, distribusi dan penjualannya, serta peresepan dan pemakaiannya. Hanya distributor tertentu yang boleh mengedarkan, dan hanya pabrik tertentu juga yang boleh memproduksi. Tak sembarang dokter boleh meresepkan dan kalau sampai ada yang menyeleweng ....
“Wah, jelas banyak itu. Yang mau beli bukan untuk berobat, tapi dipakai buat nge-fly. Dan imbalannya juga nggak sedikit.” Sang wirausahawan mengusap-usapkan jarinya, menyebutkan nominal uang yang sangat besar untuk kubayangkan. Teman-temanku sudah mulai berbisik-bisik.
Pengajar tamu kami tersenyum mengamati reaksi kelasku. “Kalian mau dapat segitu? Ya, boleh aja. Tapi, pertanggungjawabannya sama Tuhan di liang kubur nanti.”
Seorang temanku mengacungkan jari untuk bertanya. “Pak, kita nanti bekerja di bawah organisasi profesi. Apa hal seperti itu pernah terjadi dan apa tindakan dari organisasi profesi?”
“Sayangnya memang pernah,” jawab si pembicara, membuat bisik-bisik semakin ramai. “Yang bersangkutan dicabut izinnya, otomatis dikeluarkan dari organisasi profesi, dan masuk penjara.”
“Nggak ada bantuan atau perlindungan dari organisasi profesi, Pak?” tanya temanku di deret terdepan.
“Masalahnya orang tersebut melanggar sumpah profesi. Organisasi nggak bisa berbuat apa-apa dan, kalaupun bisa, coba bayangkan sendiri. Apa kalian mau membantu orang yang sudah mengingkari janjinya? Ini bukan sekadar janji, pula. Kalian nanti kalau sudah lulus, juga akan mengucapkan sumpah profesi dengan berjanji pada Tuhan masing-masing.”
Hatiku bergetar mendengarnya. Janji kepada Tuhan, apa jadinya kalau dilanggar?
Sang wirausahawan meraih spidol lalu berjalan ke papan tulis. “Kebanyakan pengusaha zaman dulu berfokus pada ini.” Dia menggambar sebentuk lingkaran dengan sebuah tulisan di dalamnya,
PRODUCT-ORIENTED.
“Yang penting produksi jalan, hasilnya bagus, penjualan bagus. Zaman sekarang, ini bergeser kepada ...”
Dia menghapus huruf D-U-C-T dan menggantinya dengan F-I-T.
“PROFIT. Sekarang orang fokus pada profit. Pada keuntungan, pada uang semata. Padahal, kalian mestinya sudah belajar apa saja isi sumpah tenaga kesehatan.”
Mendengarnya, aku merasa bernostalgia. Dosenku di semester satu pernah bertanya, “Kenapa kalian memilih jurusan farmasi?” Sebagian menjawab dengan setengah bercanda, “Karena nggak diterima di Fakultas Kedokteran,” yang artinya mereka tetap ingin jadi tenaga kesehatan meski bukan dokter. Ada yang menjawab, “Suka meracik obat,” yaitu mereka yang memang hobi masak-memasak.
“Nggak ada yang kuliah di farmasi karena pengen jadi bandar narkoba, ‘kan?”
Pertanyaan guyonan sang dosen disambut tawa seisi kelas.
“Sama seperti dokter, hakim, dan banyak profesi lainnya, kalian nanti kalau lulus akan mengucapkan sumpah profesi. Hampir semua isinya mirip, tapi, pada intinya adalah mengedepankan kejujuran.”
Memori kilas-balikku berjalin menjadi satu dengan pengajar saat ini yang seorang wirausahawan. “Kejujuran itu tandanya orang profesional. Apalagi tenaga kesehatan. Pekerjaan kalian nanti berhubungan dengan nyawa orang. Dan orang yang dimaksud adalah pasien.”
Dia menghapus huruf R-O-F-I-T sehingga hanya tersisa huruf P, lalu menambahkan A-T-I-E-N-T.
“Patient-oriented. Pekerjaan kalian adalah berfokus pada pasien. Di satu sisi, product dan profit juga harus sejalan, karena kalau tidak begitu, bisnis akan mati. Tapi tetap saja, dedikasi utamanya adalah untuk pasien. Nah, di situlah letaknya perbedaan pharmapreneur dengan enterpreneur lainnya. Orang berjualan, ‘kan, tidak terikat sumpah profesi, sedangkan kita ada. Meskipun, ada juga undang-undang perlindungan konsumen dan semacamnya.”
Selanjutnya sang wirausahawan menampilkan potongan-potongan kasus di luar negeri maupun di negara sendiri tentang penyalahgunaan obat. Dari hampir semuanya, selalu ada orang dengan latar belakang pendidikan farmasi yang terlibat. Mulai dari yang memang sengaja menyalahgunakan, yang tidak sengaja dan tidak tahu tapi dimanfaatkan oknum, maupun yang tahu apa yang benar tapi diancam, rupanya profesi yang kupelajari ini punya banyak risiko. Aku membayangkan bahwa seandainya dulu Kristin jadi masuk akademi polisi, tantangannya mungkin tidak akan sekompleks ini. Komplikasi dari tiap perbuatan tidak bisa diduga, sama seperti reaksi obat terhadap tubuh.
Obat dan racun itu sejatinya sama, demikian ungkap Paracelsus, Bapak Toksikologi. Yang membedakannya adalah dosisnya: The dose make the poison. Parasetamol obat demam dan pusing yang banyak diiklankan di televisi itu pun bisa jadi racun kalau orang meminum sepuluh tablet sekaligus atau sebotol sirupnya dalam satu waktu. Obat masuk ke dalam tubuh, melakukan tugasnya secara tersembunyi terhadap sel-sel dan organ, persis seorang agen rahasia atau pembunuh bayaran. Lalu sama seperti target pembunuhan, ada yang tangguh dan ada yang lemah, demikian pula tubuh yang diserang oleh racun. Ada reaksi perlawanan, tapi tubuh malang itu sendiri tak tahu akan akhir riwayatnya yang sudah digariskan si pembunuh.
Ambil contoh sianida alias cyanide. Assassin yang satu ini akan bersaing dengan oksigen untuk berikatan dengan butiran sel darah merah yang mengandung hemoglobin. Alih-alih oksigen yang diedarkan sampai ke seluruh tubuh, sianida membuat semua sel kehabisan napas dan tidak bisa bekerja. Sel-sel yang panik akan mengirim sinyal kepada otak untuk memberi titah pada jantung dan paru-paru untuk menambah suplai oksigen, dengan meningkatkan denyut serta tekanan darah dan tarikan napas, tapi semua akan sia-sia ketika sianida sudah merajalela. Yang ada malah tubuh manusia itu mati membiru. Sesuai namanya, cyan.
Aku mempelajari Toksikologi di semester enam ini, dan dari sanalah aku tahu cara kerja sianida dalam kopi yang baru-baru ini menjadi kasus di tanah air. Kupikir teman-teman sekelasku juga pasti sedang membayangkan ragam pembahasan mata kuliah yang satu itu karena paling relevan dengan penuturan sang pengajar tamu. Tapi barangkali hanya aku sendiri yang memandangnya lewat kacamata yang lain dari yang lain.
Banyak orang yang bertanya padaku apa motivasiku memilih kuliah di jurusan farmasi akan mendapat jawaban klise semacam, aku takut darah, suka Biologi dan Kimia, tertarik dengan hal medis, dan masih banyak lagi variasinya. Kemampuanku menulis kadang menuntunku menjadi pengarang berjuta alasan. Bukannya alasan-alasan itu tidak benar; semua yang sudah kusebutkan itu memang menjadi latar belakangku memilih jurusan ini. Tapi, pendorong utamanya bukan itu semua.
Suatu hari di masa SMA aku menemukan sebuah novel di perpustakaan. Pembunuhan atas Roger Ackroyd, karya Agatha Christie. Sungguh sebuah mahakarya di dunia fiksi kriminal terutama karena plot twist-nya yang bikin aku geleng-geleng kepala, dan berikutnya aku tahu bahwa pengarangnya pernah belajar Farmakologi. Agatha Christie sang Ratu Kriminal—demikian orang-orang menyebut wanita Inggris itu—punya bekal pengetahuan tentang racun dan dia menulis sebagian besar ceritanya berdasarkan ilmu itu. Christie mengandalkan reaksi mematikan dari obat yang diutak-atik dosisnya, membuat apa yang diyakini para ilmuwan surveilans obat sebagai Reaksi Obat yang Tak Diharapkan alias ROTD (atau istilah bahasa Inggrisnya, adverse drug reaction) berkurang satu kata menjadi Reaksi Obat yang Diharapkan. Biasanya ROTD berkaitan dengan efek samping obat, dan, seperti yang kusebutkan sebelum ini, orang bereaksi berbeda-beda terhadap obat yang sama.
Kalau aku jadi pembunuh, aku pun akan setuju pada metode Christie untuk melenyapkan nyawa orang dengan cara yang paling tidak berantakan, menyerangnya dalam tidur dan membuatnya tak bisa bangun lagi, modus operandi yang bahkan tak terasa seperti kematian bagi korbannya.
Saat pikiran semacam itu melintas di benakku, terompet si Pengingat Fidelia berbunyi-bunyi dengan keras. Tiupannya banyak diberi jeda, mengetuk-ngetuk seperti menyambut bangsawan kerajaan—atau sebaliknya, sedang meledek seorang rakyat jelata yang tak pantas disamakan dengan bangsawan. Aku tahu persis apa yang sedang diperingatkan oleh Fidelia hingga aku menoleh dan melotot, mendesis ke arah si pria gempal yang berdiri di sebelahku,
“Berisik!”
Kuarahkan pandangan kembali pada pengajar tamu sambil menggerutu dalam hati. Apa yang kupikirkan barusan bukan untuk betulan kulakukan, kok. Mana mungkin aku bercita-cita jadi seorang assassin seperti dalam film-film atau anime? Aku hanya sedang merancang cerita fiksiku yang berikutnya dan kupikir menarik untuk mempelajari metode Christie.
Lagipula, tambahku dalam hati seolah sedang berdebat langsung dengan si Fidelia, aku punya ambisi besar dengan memahami bahwa obat adalah racun yang dikendalikan dosisnya. Dengan menyadari bahwa apa yang kuberikan kepada pasien tak lain tak bukan sebuah racun, aku akan lebih mampu menghayati profesi seperti yang disampaikan si pengajar tamu. Bekerja dengan hati nurani.
*
Asrama sudah sangat sepi, hanya tersisa beberapa orang yang memang tinggal di asrama semasa liburan karena tak ada biaya pulang, saat akhirnya aku sendiri mengepak barang secukupnya untuk pulang kampung. Aku tidak berniat membawa banyak barang kalau pulang ke rumah. Namun, karena kepulanganku yang terakhir adalah setengah tahun yang lalu, aku menyempatkan diri belanja makanan tradisional Kota Pelajar sebagai oleh-oleh.
Karena, tiap kali aku kembali dari rumah ke asrama, aku selalu membawa oleh-oleh dari kota asalku—Elena jelas yang paling bersyukur jadi teman sekamarku, karena paling sering kecripatan rezeki logistik. Jadi, kali ini, gantian aku yang membawa oleh-oleh untuk orang di rumah.
Hanya ada Papa dan Mama sepertinya. Kak Faber mungkin bisa pulang sebentar kalau tahu aku ada di rumah, tapi kabarnya Kak Jaeger sedang sibuk di kantor. Aku juga tidak akan lama-lama di rumah, paling banyak hanya dua minggu, karena harus pembekalan kerja praktik. Tapi, aku tak ingin mengisi liburan singkatku dengan belajar—untuk itu sudah ada waktunya. Aku sedang memikirkan kegiatan apa yang cocok untuk kulakukan selama kerja praktik nanti. Karena jadwalnya sudah tetap dan semua kegiatan seperti UKM dan kepanitiaan dianjurkan untuk diberhentikan sementara selama semester tujuh, aku yakin aku bakal punya banyak waktu luang. Selama ini, aku masih sanggup menulis di blog di sela waktu kuliah yang juga diisi PSM, BEM, acara beasiswa, dan kegiatan asrama. Aku membayangkan diriku akan duduk melongo di ranjang kalau tak kucari kegiatan lain yang bisa mengisi kekosongan padatnya aktivitas yang direnggut.
Malam itu adalah malam terakhirku sebelum pulang dengan kereta pagi-pagi. Aku sudah menemukan calon kegiatanku selama libur di rumah lewat penjelajahanku di internet: menjadi penulis lepas alias freelance writer. Kelihatannya mudah dan sesuai dengan bakatku, lagipula itu memang jenis pekerjaan yang bisa dilakoni dari rumah dengan waktu yang diatur sendiri.
Rupanya, Papa sudah punya rencana sendiri untukku, yang memang sudah bilang hanya ada di rumah untuk dua minggu. Papa akan membelikanku sepeda motor, tapi mau memastikan aku benar-benar menguasai kendaraan itu sebelum betulan bertransaksi. Aku memang sudah beberapa kali didampingi Kak Jaeger belajar mengendarai motor saat pulang sebelum-sebelum ini, baru di sekitar rumah saja, tapi aku belum cukup percaya diri untuk terjun ke jalan raya. Sekalian mengurus Surat Izin Mengemudi, kalau bisa.
“Lha, tapi, ‘kan, Kak Jaeger katanya nggak pulang?” kataku di telepon malam itu. “Kak Faber juga katanya cuma pulang bentar.”
“Iya, nanti yang ngajarin kamu Papa aja,” balas suara di seberang sambungan.
Aku tertawa kecil, merasa senang akan dibimbing Papa lagi seperti waktu aku pertama kali belajar naik sepeda. “Oke deh, Pa. Oh iya, sebelum itu, temenin aku periksa mata, ya Pa. Udah waktunya ganti kacamata.”
Kemudian Papa sibuk menyusun jadwalnya bersamaku dan obrolan kami sampai ke mana-mana. Lalu, sembari mendengarkan Papa bercerita singkat tentang mahasiswanya yang lucu-lucu—Papa selalu punya segudang kisah jenaka soal polah tingkah anak didiknya yang seumuran denganku—samar-samar kudengar isak tangis. Aku memang menelepon di luar kamar, tepatnya di halaman tengah yang berbentuk persegi itu, karena dengan begitu aku bisa mendengar suara keluargaku sambil menatap langit bertabur bintang. Syahdu itu nikmat. Tapi tidak nikmat ketika ada yang menangis, dan seketika kucari-cari sumber suaranya di sekitar halaman. Tampaknya Kak Prita, yang rumahnya memang daerah pelosok dan baru akan pulang kampung nanti setelah wisuda—memberinya motivasi kuat untuk segera lulus. Namun, dia sedang duduk di pinggir teras, sebelah tangannya tampak memegang telepon dan tangan satunya menutupi muka. Kulihat siluetnya yang mungil, punggungnya berguncang dan dia sedang berusaha menahan guncangan yang lebih keras, mungkin karena tahu ada orang di seberangnya.
“Pa, udah dulu, ya.” Aku mengakhiri pembicaraan, merasa tahu diri bahwa harusnya aku memang undur ke kamar duluan. Kak Prita masih bergeming di seberang. Rupanya di kamar, si Bocah Hakim duduk di kusen jendela, seolah menungguku masuk. Tapi dia diam saja di situ, tak bernyanyi, tak mengeluarkan suara apa pun.
“Ada apa?” tanyaku waspada. Keberadaan Fidelia selalu membuatku merasa cemas. Si Hakim membuka mulut,
“Seniormu barusan. Orang tuanya pengusaha obat tradisional dan bangkrut karena ditipu orang.”


 roux_marlet
roux_marlet