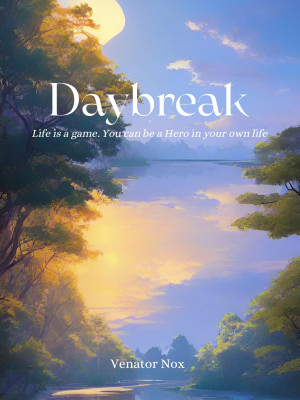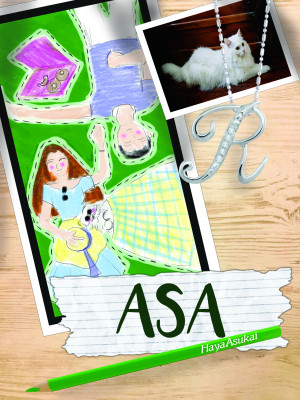Reynaldo
Aku membenci akhir minggu.
Akhir minggu yang aku habiskan di rumah utama Gautama Group selalu membuat kepalaku pening. Pertemuan makan siang keluarga yang mungkin saja seharusnya diberi judul pesta topeng. Karena semua orang menyembunyikan niat busuk di balik senyum yang mereka berikan. Sudah delapan belas tahun aku menjalani rutinitas ini dan aku semakin membencinya.
“Rey, always the wallflower. Kenapa kamu malah bersembunyi di pojok ruangan? Kamu sudah makan, Nak?”
Aku menatap wanita lanjut usia yang seharusnya kupanggil Bunda setelah aku diangkat sebagai anak mereka. Panggilan yang tidak pernah aku sematkan padanya setelah melihat mata licik yang selalu mencari kesempatan untuk menjatuhkan kepercayaan Bapak padaku.
“Sudah, Bu Tari.”
Ia mendesah halus lalu sengaja membesarkan suaranya. “Entah kapan kamu akan memanggilku Bunda, Rey. Padahal aku sudah merawatmu sejak berumur dua belas tahun. Bahkan kamu tidak akrab dengan Dwi.”
Sosok yang ia bicarakan langsung datang di belakangnya. Seperti Ibu, seperti anak. Dwi melihatku sinis dari balik punggung Ibunya. Seakan aku baru saja menyakiti wanita itu.
“Oh ya, Dwi baru saja diangkat menjadi ketua tim logistik di pabrik makanan ringan Gautama Group. Baru dua bulan, lho.” Mata wanita itu menyipit ke arahku seakan ingin menekankan posisiku dalam keluarga ini. Hanya anak angkat yang tidak memiliki hak waris. Namun rasanya mereka selalu menganggap aku ancaman untuk posisi eksekutif incaran mereka.
“Tante Tari, Dwi. Selamat untuk pencapaiannya.” Punggung lebar familiar menyusup ke tengah perang mata Bu Tari dan aku. “Katanya Mama mau membicarakan sesuatu dengan Tante. Dia ada di teras luar, Tan.”
“Oh, hampir saja aku lupa tentang arisan klub masak dengan Arini. Terima kasih sudah mengingatkan ya, Daniel.”
Wanita itu mendengus pergi membawa anaknya yang masih menempel setia di balik punggungnya. Aku menarik napas lega melihat kepergian mereka.
Daniel memutar tubuhnya hingga bertatapan denganku. Tanpa sadar aku menepuk pundaknya bangga. Salah satu keuntungan berteman dari Daniel adalah ia selalu bisa mengendalikan situasi dan menjauhkanku dari gangguan yang hadir.
“Lo selalu saja meladeni mereka. Gue sudah bilang lo bisa menolak hadir di acara rutin ini, kan?”
Aku menghela napas. Dan salah satu kerugian berteman dengannya adalah ia selalu saja ikut campur menasihati urusan hidupku.
“Gue nggak pernah mengerti kenapa lo selalu merasa harus hadir di acara keluarga kalau tahu bakal diganggu.”
“Setidaknya gue bisa menunjukan rasa hormat dan terima kasih pada Bapak dengan cara seperti ini.”
Ia memandang jauh ke ballroom luas rumah utama. “Itu yang gue nggak pernah paham.”
Dan dia memang tidak harus memahami hubunganku dan bapak angkatku, Putra yang juga adalah pewaris utama Gautama Group. Aku merasa harus mengungkapkan rasa terima kasih karena sudah ia angkat sebagai bagian keluarganya. Sebuah keputusan yang ia ambil setelah selamat dari kecelakaan yang menghilangkan nyawa Ayah kandungku.
Aku menghormatinya sebagai Bapak yang membimbingku langsung untuk memastikan tumbuh kembangku, juga mentalku saat harus kehilangan satu-satunya figur orang tua yang kumiliki. Di mata Bapak, aku adalah tanggung jawab yang harus ia penuhi sampai aku cukup umur. Itulah mengapa aku langsung keluar dari rumah keluarga setelah lulus kuliah.
Namun sepertinya bimbingan langsung dari Bapak dulu menyulut api cemburu istrinya yang mengira aku akan merebut posisi anaknya sebagai pewaris utama. Sejak saat itu ia mulai menyebarkan rumor buruk di belakangku hingga semua anggota keluarga Gautama membenciku.
Masa remajaku penuh kesepian sampai Daniel pindah dari sekolahnya di Bali ke SMP tempatku bersekolah. Entah apa yang ia lihat dariku, tapi Daniel tidak pernah terpengaruh perkataan anggota keluarga Gautama tentangku.
Suatu saat aku bersikap dingin padanya agar ia menjauh dariku. Aku tidak ingin ia terkena imbas buruk dari keluarga karena aku. Namun ia malah balik menasihati sikapku dan berkata, “Gue ingin berteman dengan lo, karena gue rasa lo adalah teman seperjuangan yang cocok untuk gue. Meski, Mama selalu bilang lo membahayakan posisi yang akan Kakek kasih ke gue. Tapi, posisi gue sekarang adalah hasil kerja gue sendiri. Meski diberi posisi dengan gaji tinggi pun, gue masih berencana untuk memulai dari bawah.”
Sifatnya yang keras kepala membuat Tante Arini, ibunya, sempat bertengkar dengan Daniel karena ia tidak mau menduduki posisi General Manager di kantor pusat Gautama Group. Saat itu aku tahu kalau Daniel akan menjadi teman seperjuanganku membangun karir dari nol. Dan awal mula persahabatan kami.
“Jadi, gue belum cerita soal cewek incaran gue.”
Aku segera tersadar dari nostalgia dan menatap Daniel di sampingku.
Apakah aku takut mendengar fakta bahwa Daniel menyukai wanita dalam pikiranku? Mungkin begitu, karena Daniel tertawa hebat saat melihat ekspresi wajahku yang menurutnya seakan ia ketahuan mencuri sesuatu yang berharga dariku.
“Gue tahu! Lo juga mengincar salah satu dari mereka kan?”
“Mereka?”
“Karyawan baru di lantai lo. Cewek-cewek yang selalu menempel berempat itu.”
Jantungku berdebar lebih cepat. Apa Daniel benar-benar mengincarnya? Sifatnya yang terlalu akrab setiap kali berbicara dengan wanita itu membuat aku makin curiga. “Gue nggak tertarik dengan siapa pun. Lo tahu prioritas gue.”
“Ya, ya, ya… Mengumpulkan uang untuk membayar hutang lo ke Om Putra, I know.” Ia memutar matanya, terlihat bosan mendengar alasanku bertahan di keluarga ini.
“Tapi setahu gue Om Putra juga nggak mempermasalahkan itu. I mean, lo bisa keluar dan mendirikan agensi PR seperti yang lo inginkan. Persetan dengan omongan Tante Tari atau keluargaku yang lain tentang kewajiban lo membalas kebaikan Om Putra. Lo bisa lebih santai dan hidup buat diri lo sendiri, Rey. ”
Aku mengedikkan bahu, tidak ingin meladeni perkataan Daniel.
“Balik lagi ke lo. Jadi lo suka salah satu dari mereka?”
Ia terkekeh pelan. “Ya. Sejak pertama kali gue bertatapan dengan mata polos cewek itu, gue sudah jatuh hati. Apalagi saat lihat dia tersenyum, gue nggak bisa berkata-kata. Manis banget.”
Daniel terlihat berbinar saat membicarakan wanita incarannya. Aku memilin ujung gagang kacamataku. Seingatku Daniel selalu suka wanita yang terlihat cantik saat makan dan memiliki senyuman manis. Meski aku tidak mengetahui penggambaran cantik atau manis menurutnya.
“That’s too general, Dan. Gue kira lo suka dia karena sesuatu yang spesifik.”
“Lo nggak pernah aja merasakan jatuh cinta pandangan pertama. Apa-apa yang lebih spesifik bisa gue kenal setelah jalan sama dia, kan?”
“Well, you do you.”
“Jadi gue minta tolong buat chat gue setiap lo lihat mereka turun makan siang, ya?”
Aku mengangguk pelan.
Daniel tersenyum puas, memukul pelan punggungku. “I know you will always support me.”
Aku memandang pintu besar di depanku setelah tersenyum singkat pada Daniel. Entah mengapa aku tidak ingin berlama-lama berada di dekat Daniel sekarang. Tidak saat sosok wanita itu yang muncul setelah membayangkan tipe Daniel.
Almira. Senyum manis dan mata berbinar wanita itu saat memilih makanan kembali terngiang dalam benakku. Apakah semua itu akan ia tunjukkan juga ketika jalan berdua dengan Daniel? Apakah ia akan bercerita tentang rahasia di balik warna matanya yang cantik itu?
Tidak. Harusnya aku bersyukur setidaknya ia tidak akan muncul lagi dalam pikiranku. Setidaknya aku tidak meladeni sifat manjanya untuk melakukan semua hal yang seharusnya ia bisa lakukan sendiri.
“Lo kenapa, Rey?”
“Oh. Nggak, gue cuma kepikiran Bruno di apartemen. Gue balik duluan ya, takut kemalaman.”
Mata Daniel kembali berbinar senang mendengar nama anjing ras golden retriever peliharaanku itu. “Now you mention him. Gue juga kangen sama Bruno. Minggu depan gue main ke apartemen lo, ya!”
Aku hanya mengangguk singkat lalu melesat keluar dari rumah keluarga Gautama. Saat ini aku berharap Daniel lupa dengan janjinya mengunjungi apartemenku.
Aku hanya tidak ingin ia merebut perhatian Bruno dariku. Atau karena aku tidak nyaman karena apa pun nama perasaan yang muncul setiap kali aku memikirkan wanita yang disukai Daniel.
Setengah jam perjalanan dari perumahan di daerah Bintaro ke kompleks apartemenku di Cilandak terasa panjang. Kemacetan tiap malam minggu membuatku harus bertahan di dalam mobil menyusun perasaanku lagi. Kenapa aku merasa kesal?
Aku menghembuskan napas frustasi. Setelah memarkirkan mobil di gedung parkir apartemen, aku segera masuk ke lobi dan menunggu lift turun. Lagi-lagi pikiranku mulai memunculkan pertanyaan lain, seperti kenapa aku tidak memastikan terlebih dahulu siapa yang Daniel bicarakan tadi?
Lift terbuka membuatku buru-buru masuk dan menekan kasar tombol menuju lantai unitku. Dua menit berada di dalam lift menuju lantai dua belas terasa lama. Aku mencoba memikirkan Bruno yang akan segera menyambutku di pintu masuk. Tapi yang muncul lagi-lagi adalah, apakah Daniel benar-benar menyukai Almira?
Kenapa aku merasa terganggu jika wanita yang diceritakan Daniel adalah Almira?
Selain ekspresinya saat kesal denganku, aku tidak pernah berpikir kalau aku tertarik dengan wanita itu. Benar, selain wajahnya yang berubah merah seperti lobster rebus setiap kali aku membuatnya kesal. Atau matanya yang membulat saat aku menatap warna di iris matanya. Coklat terang lalu berubah keemasan di bawah cahaya, seperti dua batu amber. Lalu senyumnya yang muncul tiba-tiba selalu mengejutkanku.
Tunggu. Kenapa pikiranku malah terus memutar ingatan dengan wanita itu di dalamnya?
Suara Bruno yang berlari menyapaku ke pintu depan unit apartemenku tetap membuatku berkutat pada pikiranku. Rasanya kestabilan emosiku selalu terganggu setiap memikirkan Almira. Kenapa? aku bahkan tidak menyukai dia?
Aku berjalan menuju ruang tengah diikuti dengan Bruno. Ia menggonggong sekali lagi untuk mendapatkan perhatianku. Kegigihannya berhasil membuatku beralih menariknya ke pangkuanku dan mengelus bulu coklat lebatnya.
“It will always be you and me. Right, buddy?”
Ia melihatku dengan mata bundar hitamnya. Lidahnya terjulur keluar membuat mulutnya membentuk senyum. Sepertinya Bruno setuju untuk terus hidup berdua bersamaku. Benar, aku tidak perlu memikirkan perhatian seorang wanita yang akan teralihkan dariku. Aku hanya menginginkan perhatian anjing kesayanganku ini.
Suara dering ponsel menghentikan waktu bermainku dengan Bruno. Lantas aku meraih ponsel di kantung jaket denim yang masih kukenakan, memikirkan pekerjaan apa lagi yang mengganggu waktu istirahatku. Tanganku terhenti di depan layar saat melihat nama Daniel muncul.
Setelah menimbang sesaat, aku akhirnya membuka pesan darinya. Sebuah link dan emoji mengedip. Diliputi perasaan ingin tahu, aku pun segera menekan link kirimannya. Kalimat pertama yang aku baca membuatku menyesal.
“Penampilan Debut Almira Pradnyani, Salah Satu Pewaris Pradnya Group, di Kegiatan Bakti Sosial Panti Asuhan Happiness.”
Senyumnya dalam artikel itu kaku seperti dipaksakan. Ia seakan terpaksa berada di sana dan bercengkrama dengan orang-orang yang tidak sebanding dengannya.
Senyum manis Almira dalam ingatanku lenyap bagaikan ilusi.
Pewaris perusahaan. Manja. Palsu. Almira benar-benar mencentang semua kriteria tipe orang yang paling aku benci.
Aku menyesali waktu yang sudah aku buang untuk memikirkan dan mengatur perasaanku untuk wanita itu.


 wrtnbytata
wrtnbytata