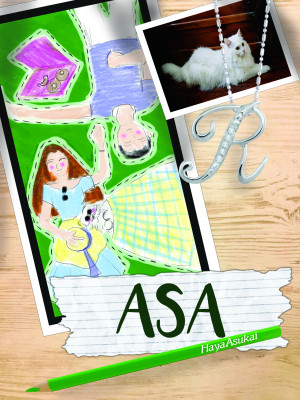Almira
Agni seperti api yang membakar semangat para wanita untuk bebas dari kekangan.
“Saya ingin menyampaikan pesan tersebut pada para pembaca.” tukasnya mengundang decak kagum dari semua orang dalam Ruang Eyre pagi ini.
Sosok perempuan bertubuh mungil dengan rambut ikal terikat rapi di belakang itu tersenyum ramah. Tidak akan ada yang menyangka kalau wanita ini adalah penulis “Perempuan Berambut Api” dengan tokoh Agni yang berapi-api dan keras kepala. Bahkan suaranya terdengar halus, bertolak belakang dengan karakter Agni.
Aku pun terkejut saat melihat wajah polos wanita tiga puluh tahun ini lewat layar video meeting. Kalau Kak Felice tidak menyodok lenganku, aku mungkin akan tetap menganga melihat perbedaan image yang ia gambarkan dalam naskahnya dengan sosok dirinya di dunia nyata. Setelah rapat pertama kami di hari Senin lalu, aku sudah menantikan reaksi terkejut anggota tim proyek buku ini saat melihat sosok Dewi Lilia sebenarnya.
“Oke, untuk agenda rapat akan kita lanjutkan dengan pemaparan rencana dari masing-masing tim.” Suara Kak Felice mengembalikan kesadaran kami ke dalam ruang rapat.
Hari ini tugasku hanya melihat cara mentorku memimpin jalan rapat dan menjadi notulen. Sementara perwakilan masing-masing tim akan memaparkan konsep atau rencana mereka terkait penerbitan dan promosi buku Mbak Dewi. Objektif kami semua sama. Konsep buku yang dibawa oleh penulis alias Mbak Dewi dan elemen dari buku yang dicetak dan kegiatan promosinya harus sejalan.
Reynaldo mengangkat tangan terlebih dahulu. Raut wajahnya terlihat serius seperti biasa, yang baru-baru ini aku sadari adalah wajah normalnya. Suaranya yang berat dan tegas memenuhi ruangan meski pun ia duduk cukup jauh dari bagian depan ruangan.
Rencana dari tim PR yang ia paparkan akan berjalan tiga minggu sebelum waktu penerbitan yang akan meliputi acara bincang buku online dan offline di toko buku Gautama area Jabodetabek, lalu acara fansign di toko buku pusat Gautama, dan press conference selama satu minggu sebelum buku rilis.
“Highlight untuk press release akan kita buat fokus dengan pesan buku yang Mbak sampaikan. Apa ada koreksi untuk rencana ini?”
“Saya rasa tidak apa jika menggunakan kalimat lain asalkan maknanya tetap sama.”
Reynaldo mengangguk lalu membubuhkan catatan di tabletnya. Tangan kirinya sibuk memainkan gagang kacamatanya, satu lagi kebiasaan pria ini yang aku temui.
“Selanjutnya. Kita sudah membuat daftar penulis dengan genre serupa dengan buku Mbak untuk membaca terlebih dahulu dan memberikan komentar mereka untuk kita masukkan dalam jaket buku.”
“Apa penulis terpilih hanya penulis yang pernah menerbitkan buku di Gautama? Apa memungkinkan untuk menambah penulis di luar itu yang saya tahu pernah membuat buku dengan genre sama?”
“Tentu. Daftar penulis memang hanya mencakup penulis yang bukunya pernah terbit di Gautama, jika Mbak ada tambahan bisa memberikan daftar namanya ke email kami. Setelah itu saya dan tim marketing akan melakukan sortir lagi berdasarkan buku yang pernah mereka tulis dan berapa kopi yang pernah terjual. Juga untuk memastikan catatan bersih penulis.”
Mbak Dewi mengangguk, mengizinkan Reynaldo untuk melanjutkan.
“Selain itu, kita mungkin akan menargetkan 20 ARC untuk penggemar Mbak yang bersedia untuk membuat review berupa post dan video. Persyaratan dari reviewer yang akan dipilih akan saya kirimkan bersama dengan daftar isi dari PR Package. Sejauh ini apakah ada yang ingin Mbak tambahkan?”
Aku turut menulis rencana yang dipaparkan di notebook putihku. Entah mengapa aku bisa merasakan perasaan berdebar pengikut karya Mbak Dewi di platform menulis online mau pun di sosial medianya saat mendengar berita bukunya diterbitkan. Mereka mungkin akan membanjiri semua situs Gautama Books yang membuka pendaftaran reviewer untuk menerima buku Mbak Dewi sebelum rilis alias Advanced Readers Copy. Such an effective mouth-to-mouth campaign!
Sepertinya Mbak Dewi juga senang mendengar rencana melibatkan pengikut karyanya, karena ia terlihat langsung mencatatnya dalam memo di laptopnya.
“Oh iya. Pak Reynaldo, saya memiliki beberapa konsep dan contoh merchandise yang ingin saya masukkan dalam PR Package. Apa bisa?”
“Tentu. Mbak bisa mengirimkan konsep merchandise ke thread email yang sudah Almira buat. Setelah itu Ali di sebelah saya ini yang akan mengirimkan beberapa contoh desain sesuai konsep yang Mbak buat. Kalau sudah fix, saya juga akan meminta Mbak Dewi memeriksa mock up PR Package untuk konfirmasi sebelum diproduksi dalam jumlah banyak.”
“Baik, kita bisa ikuti rencana dari Bapak.”
Diskusi dilanjutkan dengan diskusi untuk melihat target konsumen potensial dari pengikut penulis serta data penjualan genre buku penulis. Pada akhirnya kami sepakat untuk mencetak 5,000 kopi buku serta distribusi lewat aplikasi baca milik Gautama Group dan beberapa perpustakaan yang bekerjasama dengan perusahaan dalam sesuai dengan durasi kontrak penulis.
Melihat senyum puas Mbak Dewi saat mendengarkan tiap pemaparan membuatku yakin ia akan melanjutkan kontrak dengan Gautama Books untuk menerbitkan karya selanjutnya. Dan itu pun yang aku inginkan karena selain karyanya yang ditulis dengan baik, ia juga sudah memiliki konsep matang untuk promosi bukunya.
Terlihat selama diskusi Mbak Dewi beberapa kali mengajukan ide berdasarkan data yang ia cari sendiri. Meski bisa dibilang proyek ini adalah pengalaman pertama kali buku karyanya diterbitkan, namun ia sudah mempersiapkan banyak hal secara detail. Baik konsep merchandise, daftar penulis dengan genre serupa, maupun sejumlah toko buku indie yang ia ajukan untuk mengadakan acara buku karena sering dikunjungi pengikutnya di sosial media. Berkat itu juga, rapat bisa selesai dalam tiga jam.
Target pertama untuk aku dan Kak Felice satu minggu kedepan adalah memastikan tidak ada plot yang berlubang, detail yang terlalu banyak diceritakan atau jika ada pendalaman karakter dan konflik yang perlu ditambahkan. Beberapa rapat editorial dengan Mbak Dewi mungkin akan diadakan online secara intens sebelum naskah masuk ke pemeriksaan Fandi.
Selain itu, di rapat tim Jumat depan, Bang Ali juga berencana mempresentasikan beberapa mock up desain cover buku untuk di evaluasi anggota tim dalam hal kesesuaian cover dengan jalan cerita dan tema buku. Sementara yang lainnya akan mulai menghubungi media pers dan distributor buku nantinya.
Aku bisa merasakan kupu-kupu yang menari riang dalam hatiku. Satu langkah masuk ke dalam dunia yang aku selalu impikan.
Abuela pernah berkata dalam hidup ini kita bisa merasakan kebahagiaan selama satu detik berganti menjadi penderitaan yang lebih lama.
Aku mengira semesta tidak mungkin menyiksa manusia dengan merampas kebahagiaan sesaatnya. Tapi pikiran itu berubah saat nomor tidak dikenal muncul di layar ponselku.
Aku baru saja sampai ke kamar indekosku setelah menerjang macetnya Kota Jakarta. Kelelahan dan stress yang bertumpuk selama perjalanan di belakang ojek motor yang kutumpangi membuatku lekas membersihkan diri lalu menghempaskan tubuhku di kasur. Leherku mulai terasa lembap dari bantal yang basah karena rambutku. Tapi aku tidak peduli, sebentar saja aku ingin mengistirahatkan punggungku yang mungkin saja bisa remuk kalau terjebak macet lebih lama lagi.
“Ini baru jam delapan, Ami. Kamu harusnya bisa melakukan hal lain daripada bersantai di atas kasur.” Aku menggumamkan kalimat itu beberapa kali dengan mata terpejam. Ketiga kalinya aku bergumam, lantunan melodi dari ponsel membuatku terduduk.
Aku berpikir sesaat untuk mengangkat nomor tanpa nama itu. Namun bisa saja ada urusan penting dari kantor atau temanku di Bali, mengingat kebiasaanku untuk tidak menyimpan nomor orang di luar keluarga intiku. Setelah aku menyapa orang di balik telepon, suara wanita nyaring terdengar dan langsung membuatku menyesali semuanya.
Nadanya meninggi saat tahu aku tidak mengenali nomor ponselnya. “Almira. Kamu tidak menyimpan nomor Tante?”
“Maaf, Tante Ari. Sepertinya Ami lupa.” Aku menjawab dengan malas. Aku menarik tubuhku ke posisi duduk, suara tanteku itu telah mengembalikan kesadaranku sepenuhnya.
Dalam hati, aku mulai merutuki jariku yang menekan tombol menerima panggilan.
“Tante baru saja dapat info dari Yulia kalau kamu lagi di Jakarta. What a coincidence, karena Tante besok akan mengadakan acara volunteer di panti asuhan seperti biasa. Kamu datang ya bantu-bantu, nanti Tante kirimkan alamatnya.”
And there goes my weekend. “Baik, Tante.”
Salah satu sifat Tante Ari yang selalu membuatku menghindari dia adalah kamu tidak bisa menolak perintahnya. Bahkan Mama selalu memilih menghindar tiap kali kakak tertuanya ini muncul, meski usaha Mama tidak selalu berhasil. Daripada urusan semakin rumit sampai melibatkan Mama, lebih baik aku mengikuti perintahnya dan menunda rencanaku untuk jalan-jalan keliling Jakarta atau memulai buku sejarah baru yang aku bawa dari rumah.
***
Satu hal mengarah ke hal lain. Satu kesalahan mengarah ke penderitaan lainnya.
Pipiku kaku setelah menahan senyum selama dua jam terakhir. Kilatan flash kamera dan microphone yang disodorkan ke depan wajahku. Semua kepura-puraan ini membuatku ingin kembali meringkuk di atas kasur kamarku yang meski pun kecil namun aku bisa bebas menjadi diriku sendiri. Bukan boneka harus mengikuti arahan orang lain.
“Almira, cepat bantu pegawai Tante di belakang. Waktunya membagi makan siang. Kamu sebaiknya ada di sana supaya bisa dimasukkan dalam publikasi perusahaan kita di majalah,” bisik Tante Ari dengan gigi mengatup membentuk senyuman.
Aku mengangguk mengikuti perintahnya. Sambil berjalan ke belakang rumah panti asuhan di daerah Jakarta Barat ini, aku berpikir kalau wanita yang hampir setengah abad dan kupanggil Tante itu bisa meniti karir di dunia ventriloquism.
Sekumpulan anak kira-kira berumur tujuh tahun sampai remaja yang masih mengenakan seragam SMP masuk ke dalam ruang makan membentuk antrian. Aku lantas mengambil tempat di belakang wadah alumunium berisi capcay goreng dan kulihat pegawai lain sudah berdiri di deretan lauk lainnya. Dengan malas aku menyapa reporter yang sudah menunggu di ujung ruangan. Namun segera tersenyum lebar lalu melayani anak-anak yang sudah menyodorkan piring mereka ke hadapanku. Sahutan polos mereka menyapaku atau sekedar menanyakan apakah mereka bisa makan tanpa sayuran menaikkan suasana hatiku.
“Almira!” Suara nyaring Tante Ari membuyarkan ketenangan sesaat dalam hatiku. Langkah cepatnya terdengar dari ketukan sepatu hak tingginya yang membentuk irama. Saat sampai tadi pagi aku sempat mempertanyakan kualitas stylist tanteku ini, karena siapa yang melakukan kegiatan volunteer dengan mengenakan tidak hanya sepatu hak tinggi, tapi juga gaun ketat ditambah jaket bulu bermerek.
“Almira, kita sudah selesai. Ayo temani Tante makan siang,” perintahnya segera setelah sampai di hadapanku.
“Kita tidak makan siang disini saja, Tante?”
Ia melihatku seakan aku baru saja berkata sesuatu yang menyinggung harga dirinya. Of course, Keluarga Pradnya dan harga diri mereka yang tinggi.
Pantas saja Mama memutuskan untuk kawin lari di Argentina dan memisahkan diri dari keluarga besarnya ini. Kalau saja Ninik tidak sakit keras, Mama tidak akan pernah kembali ke Bali demi merawat ibunya. Dan aku tidak akan pernah masuk dalam kekangan mereka.
Akhirnya aku hanya bisa mengikuti semua perintah mereka demi menjaga wajah Mama di hadapan mereka. Seperti boneka tali dalam pertunjukan boneka yang tadi pagi ditampilkan anak-anak panti asuhan di depan kami.
Tidak lama lagi, Ami. Sebentar lagi kamu akan membuktikan kemampuanmu untuk hidup tanpa embel-embel keluarga Pradnya.
Seketika suara dalam kepalaku berhenti saat langkah Tante Ari terhenti di depan pintu mobil Benz putihnya di parkiran panti asuhan. Seharusnya aku sudah mengetahui kalau kegiatan hari ini hanya untuk publikasi saja. Menjaga image-nya sebagai wanita karir yang peduli sosial. Aku semakin ingin cepat pulang ke kamar indekosku bersama tumpukan buku-buku yang lebih nyaman, meski hanya seluas kamar ganti Tante di apartemen mewahnya.
“Almira, Tante hanya ingin mengarahkan kamu ke jalan yang lebih baik…”
Aku membeku, rasanya darahku mengalir deras ke jantung membuatku bernapas pendek. Karena aku sudah mengetahui lanjutan dari perkataan Tante Ari.
“Tante rasa kamu tidak akan lama di perusahaan sekarang. Jadi lebih baik kamu segera berhenti bermain-main di sana dan mengisi cabang restoran Tante di Menteng. Kebetulan ada bukaan di posisi Marketing Communication. Gimana, lebih sejalan dengan jurusan kuliahmu kan?”
Mereka memang tidak pernah berubah. Setelah gagal membuat Mama bekerja di lini bisnis makanan Pradnya Group, lalu sekarang mereka beralih pada anak tunggal Mama. Terkadang aku membenci Mama yang tidak bisa membela impianku bekerja di dunia literasi, tetapi aku juga mengerti posisinya yang harus menjaga perasaan ibunya.
Maka di saat seperti ini, yang bisa aku lakukan hanya tersenyum dan menolak dengan halus. “Ami masih ingin melebarkan karir di perusahaan sekarang Tante. Terima kasih untuk tawarannya.” Aku menahan bibirku untuk mengatakan, sebaiknya Tante menawarkan ini pada anak Tante yang sibuk berpesta pora sampai lupa kuliah.
Ia mendelik dari kursi belakang yang berlawanan dariku. “Kamu terlalu santai seperti Antuan.”
Selalu saja menyalahkan Papa. Aku menahan gerutu yang seperti akan meledak jika ia meremehkan aku atau keluarga kecilku sekali lagi.
“Sudahlah. Tante tahu kamu akan seperti ini. Jadi nenekmu sudah menyuruh Tante untuk memasukkan resume dan ijazahmu ke perusahaan. Supaya bisa anak HR proses kalau kamu sudah bosan dengan pekerjaanmu sekarang.”
Ia memijit keningnya seakan baru saja memberikan solusi atas kesalahan berat yang aku perbuat.
Padahal aku hanya meminta kebebasan mengambil keputusan dalam hidupku sendiri. Apa kah permintaanku seburuk itu hingga mereka selalu menghalangiku? Selalu berkilah ingin mengarahkanku ke jalan yang baik menurut mereka?
Apanya yang jalan lebih baik, saat aku menyerahkan takdirku dalam perusahaan mereka, aku akan kehilangan diriku yang seutuhnya. Rasanya aku ingin memukul keluar semua rasa kesal ini ke kaca mobil Tante Ari.
Tapi aku menahannya. Selalu seperti ini. Aku menahan amarahku keluar hingga menggerogotiku dari dalam. Seperti api yang terjebak membakar diriku dari dalam. Menunggu waktu yang tepat untuk bebas dari kekangan.


 wrtnbytata
wrtnbytata