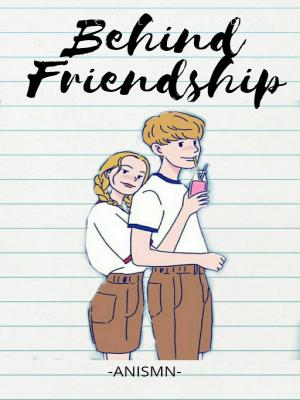Kenapa dunia terlihat gelap?
Ternyata kacamataku belum
dilepas. —Andira
⋇⋆✦⋆⋇
Pernah saat kelas lima SD, aku dan Jo berjalan-jalan menggunakan sepeda untuk mencari kecebong. Orang-orang mungkin akan menggelengkan kepala karena besar sepeda daripada yang mengendarai, lagian yang kami pakai adalah punya Bundanya Jo, dan itu memang terlihat seperti memaksakan keadaan.
Namun, kami berdua menikmatinya. Aku yang hanya haha-hihi di belakang, dan Jo yang memintaku berhenti banyak bergerak karena keseimbangan kami tergantung pada dua manusia yang menungganginya. Kalian tahu saja 'kan, sejauh ini terlihat siapa yang suka menguji kesabaran dan siapa yang harus selalu menahan emosi. Sebenarnya saat itu aku juga tidak sengaja, botol aqua yang berisi kecebong jatuh dari genggamanku, demi berusaha mempertahankannya, aku memiringkan badan ke kanan hingga buyarlah sudah keseimbangan Jo.
Tanaman kaca piring milik Pak RT, adalah saksi bisu bagaimana tragisnya tubuh kami mendarat di atas situ. Tidak cuma Jo yang lecet, sebab aku juga harus menahan perih karena siku yang berdarah. Tapi tetap saja Jo yang paling parah. "Sakit?" Dan ia justru lebih mengkhawatirkan diriku yang mulai menangis, padahal nyata-nyata lututnya tengah berceceran darah.
"Kaki Jo luka." Itu kataku, dan saat mendengarnya, Jo justru tergelak.
"Jo enggak apa-apa," katanya.
Saat itu kami pulang jalan kaki saja, sebab sebelumnya Jo mencoba memakai sepedanya lagi tapi terlihat tidak bisa. Padahal ban masih aman, rantai juga tidak putus, bahkan stang pengendali tidak copot. Aku memang tidak mengerti kenapa kami hanya menyeret benda itu, tapi setelah apa yang terjadi kepada kami, Jo tidak pernah mau naik sepeda lagi.
"Lu yang di depan." Jo mendorongku mendekati motor saat sampai di parkiran, dan aku cukup heran karena perlakuan ini. "Gue nebeng," ujarnya lagi.
"Lu gak bawa motor, Jo?" tanyaku. Dia hanya menggeleng, dan penolakan itu membuatku jadi semakin iseng padanya. "Enggak mau, lu aja kali yang di depan."
"Ini 'kan motor lu," tolaknya.
"Jo, pala gue habis kebentur bola tadi. Gimana kalo gue tiba-tiba pusing dan kita oleng?" tanyaku, "Nih perut gue juga nyeri gara-gara lagi datang bulan."
Jo tampak berpikir, tidak lama sih, sebab setelahnya ia menghela napas, dua tas yang ada padanya diberikan kepadaku. Jo tampak setuju. Namun sebelum kami meninggalkan tempat parkir, kehadiran Anan membuat suasana berubah sekejap. Mereka berdua masih punya tatapan sama seperti kemarin, tentang bagaimana tidak sukanya aku melihat hal seperti ini.
"Anan ...." Sebelum aku berhasil menyampaikan sesuatu, motornya melaju lebih dulu meninggalkan kami. "Pulang bareng yuk," cicitku pelan.
"Naik." Aku tahu kalau Jo mendengar saja ucapan kecil itu. "Anandra bukan sahabat kecil lu lagi, Dir. Dia udah berubah, bukan lagi sosok anak kecil yang bakal nurutin semua mau lu," ujarnya.
Aku tidak bicara apa-apa setelah itu, motor pun berjalan setelah kami berdua sama-sama siap untuk pulang. Akan tetapi anehnya, Jo mengendarai motor seperti tidak begitu benar. Kami berjalan pelan sekali, bahkan paman penjual mainan yang menyeret sepedanya mampu membalap kami.
"Lu kenapa anjir?" tanyaku memukul kepalanya.
"Apaan sih, Dir? Gue lagi fokus!" sahutnya.
FOKUS APANYA?
Ini kami lamban tau, biasanya dia kalau bawa motor seperti mau membawaku ke akhirat. "Motornya kenapa jalan kayak gini?" tanyaku lagi.
"Yang penting jalan, 'kan?" tanyanya balik.
Jujur aku tidak mengerti kenapa semua orang mendadak aneh akhir-akhir ini, tapi dari apa yang kulihat pada penarikkan gas, tangan besar itu tampak gemetar. Tidak satu saja ternyata, sebab tangan satunya juga begitu. "Kenapa lu gemetar?" Dan sungguh aku tidak bisa diam saja meski melihat kutu beras di kepala Jo, misal.
Motor berhenti mendadak, bahkan tubuhku menabrak bagian punggung belakangnya. "Gue gak bisa," ujarnya. "Lu bisa pulang sendiri kalo gak mau bawa gue, gue bisa naik angkot." Dan dia turun begitu saja dengan ingin meninggalkanku.
"HOEY LU KENAPA SIH?" teriakku mengejarnya.
"Gue takut jatuh lagi, Dir! Kalo kita berdua jatuh, entar lu luka dan nangis!" jawabnya, tidak membentak sepertiku tadi, hanya saja ucapannya terdengar begitu putus asa.
"Gue di depan." Itu kataku sambil menarik tasnya untuk ikut jalan ke dekat motor juga, hingga akhirnya akulah yang membawa motor sampai ke rumah. Tanpa adanya percakapan berbobot atau nyeleneh. Tanpa ada adegan saling memukul, mencubit, menjitak. Tanpa ada tawa ceria yang biasanya kulakukan. Bahkan Jo turun tanpa mengucapkan apa pun setelah berhenti, dan sembari ia melangkah masuk ke rumah, sosok motor baru yang masih terparkir di halamannya membuatku menghela napas.
Di sinilah aku tahu kenapa Jo tidak pernah mau naik sepeda lagi.
⋇⋆✦⋆⋇
Tidak kusangka kalau rutinitas bulanan yang biasa dilakukan oleh para ibu-ibu yang saling bertetanggaan akan terus dilaksanakan sampai sekarang, contohnya di rumahku. Saat masuk, ada Mama Anan dan Bunda Jo di dapur, mereka memasak. Bahkan ketika melepas sepatu di pelataran pun, aku bisa mendengar kalau Mama sedang menggosipi kesombongan Tante Anggi dan emas sejibunnya. Astaga, pohon tumbuh tidak jauh dari buahnya yang jatuh. Pantas saja anaknya bisa lebih parah kelakuannya, ternyata memang dari bibit sudah begitu.
Kucium-cium sepertinya bau bakso, meski tidak kuperiksa dulu, tapi khas masakkan Mama memang sudah kuhapal begini. Bahkan saat aku mandi, baunya masih mampu masuk ke dalam kamar mandi, bayangkan saja.
"Andira, sudah pulang, Sayang?" teriakkan Mama membuatku bergegas keluar kamar, menghampiri tiga wanita paruh baya yang sibuk menyiapkan sesuatu di mangkuk. "Panggilkan Anandra sama Jondara ya, kita makan," lanjutnya.
"Oke!" Dengan semangat aku mengiyakan, bahkan saking senangnya aku berlari untuk menghampiri satu demi satu rumah sahabatku. Pertama tempat Jo dulu, aku masuk tanpa permisi dan membuka pintu rumahnya begitu saja. Lagian sih Bunda Jo bilang kalau rumah mereka adalah rumahku juga, jadi ya aku tidak salah.
"Anjir! Mesum ya lu!" Nyatanya kami berdua sama-sama kaget karena Jo baru keluar dari kamar mandi, masih pake handuk, masih bercucuran air dari ujung rambutnya, bahkan dada dan perutnya yang berbentuk tampak jelas kulihat.
"Ya elu ngapain keluar kayak gitu?" tanyaku sembari berpaling darinya.
"Ya gue habis mandi, lu yang salah main masuk aja," katanya sambil menutup pintu kamar dengan keras.
"Habis pake baju ke rumah, kita makan kata Mama."
"Males!"
"ADA EMAK LU JUGA YA, KAMPANG!"
"YA UDAH SIH, SANA LU. ENTAR GUE NYUSUL!"
Nyatanya, meski rumah Jo dianggap seperti rumahku juga, kami tidak bisa hidup dalam satu atap yang sama. Mungkin keributan akan menjadi dua kali lipat daripada keributanku saat bersama Kak Novan. Sambil melangkah menuju rumah yang lain, tidak seperti awal kalau aku bakal lari-lari, sebab untuk menuju rumah Anan aku hanya jalan kaki. Entahlah, rasanya tidak sesemangat saat menuju rumah Jo tadi.
Sebenarnya aku tidak begitu yakin apakah Anan bisa kuajak bicara? Atau apakah dia mau bertemu denganku? Namun kalau tidak dicoba masa aku harus pulang dengan kabar bahwa tidak mendatangi Anan, apa kata para Mama yang berkarya di dapur sambil mencibiri tetangga yang lain?
Sebelum mengetuk pintu, aku menghela napas sebab tangan mendadak sulit digerakkan. Aku jadi tidak yakin haruskah memanggilnya sekarang. "Tapi Renata, aku cuma pakai motor, enggak punya mobil." Pergerakkanku terhenti saat suara Anan terdengar begitu dekat. "Masa kamu diajak naik motor sebentar aja enggak bisa? Kamu enggak bakal gosong cuman gara-gara kena sinar matahari, Renata."
Aku terdiam.
"Kamu enggak kayak Andira ya, dia meski kita ajak berjelajah di got pasti mau, bahkan kamu suruh mandi lumpur buat senang-senang juga enggak bakal nolak. Sedangkan kamu, aku harus prioritaskan kecantikan kamu buat menikmati hari. Kenapa? Kenapa kamu enggak kayak Andira yang bisa diajak untuk semua situasi?"
Semakin membisu aku dibuatnya.
"Bukannya mau membandingkan kamu sama Andira, tapi kamu emang berlebihan bahkan jauh lebih berlebihan dari semua cewek, iya kali sampai segitunya jaga diri. Mau kayak gimana pun kamu tetap cantik di mata aku, Ren. Jangan bilang kalo digigit nyamuk kamu langsung koma tiga tahun."
Sepertinya bukan waktu yang tepat untuk memanggil Anan, jadi kuputuskan untuk balik saja dan kembali beberapa saat lagi. Lagian tidak enak 'kan mengganggu perseteruan antara dua orang yang sedang kasmaran baru-baru ini. "Mau ke mana?" Tapi langkahku terhenti saat mendengar teguran itu.
Kukira hanya pendengaran saja, namun sosok laki-laki yang muncul di depan pintu membuktikan kalau Andira memang sedang dalam keadaan tercyduk. "A-anu ... Mau manggil lu buat makan, hehe," ujarku kikuk.
"Terus kenapa enggak manggil?"
Tolong, rasanya mau cosplay saja jadi pohon mangga di depan rumah Jo sana. Cara Anan memperlakukanku seperti baru mendapatkan maling, dan tingkahku yang mendadak gugup ini semakin mendukung hal itu. "Karena ... gue mau ... lepas sendal, heee." Lagi-lagi aku bicara begitu sambil meletakkan sendal di tanah.
Kontak mata kami tidak putus, aku berjalan menyusuri pelataran rumahnya untuk mendekat. Entah kenapa, ada debaran aneh yang tiba-tiba membuatku ingin jungkir balik saja. "Ke rumah kata Mama," ujarku saat berdiri tepat di depannya.
Anan memiringkan posisi wajah, ia menatapku begitu serius sambil mengusap bibir bagian bawahnya. "Ngapain?" tanyanya.
Aku tidak tahu apa yang terjadi, menatap Anan yang beraura beda begini, sungguh membuatku mau kayang, salto belakang, lari di tempat, dan terpeleset sampai ke RT sebelah. "Makan." Semakin ke sini, semakin singkat bicaraku. "Ditunggu!" Aku berbalik dengan langkah tergesa, dan tololnya memasang sendal kenapa harus terbalik.
MALU WOEY LAH! Pergerakanku jadi tertunda.
"Lu denger percakapan gue sama Renata?"
Dan ucapan itu membuatku merasa dikutuk jadi batu.
Tbc;


 sunht06
sunht06