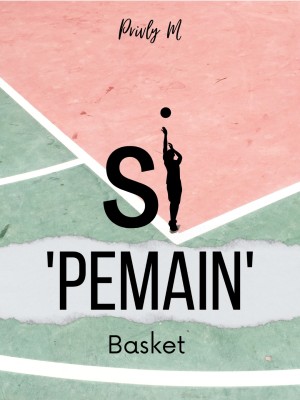Bila diibaratkan film hantu, mungkin saat ini nyawaku yang kembali ke tubuh hanyalah setengah. Karena meskipun kudapatkan kesadaranku, mataku sama sekali menolak untuk terbuka. Bunyi dering ponselku meraung-raung mengisi kesunyian kamar. Aku ingin mengumpat dan menyumpah serapahi deringan menganggu itu, namun aku benar-benar ingin melanjutkan tidurku untuk saat ini.
Ranjang bergerak sejenak ketika Dirja mengubah posisinya menjadi tengkurap seraya mengerang tertahan. Tangannya memukul kepalaku dan membuatku mengaduh. “Hapemu jancuk, berisik.”
Bunyi dering berhenti, seketika membuatku kembali rileks. Namun, dalam hitungan beberapa detik, ponsel itu kembali mengeluarkan suara berisik yang benar-benar menjengkelkan. Dengan perasaan kesal, kuulurkan tanganku meraba-raba ponsel di atas meja. Tanpa melihat nama pemanggil, kujawab panggilan itu dengan kernyitan di dahi. “Siapa sih? Ganggu orang tidur aja.”
“What?! Kamu mau mampus ya?” Oh, suara Ara. Gadis ini tak pernah berhenti merepotkanku rupanya. Apakah ia memiliki semacam dendam kesumat padaku sehingga tak rela membiarkanku bersantai barang sedetik saja? “Bangun, Di! Cepet mandi. Hari ini ikut aku.” Kudecakkan lidah tanpa mengatakan apa pun. “Kamu dengar nggak sih?”
Percayalah, otakku sepertinya benar-benar lelah sehingga seluruh tubuhku rasanya tidak ingin merespons apa pun dan segera pergi tidur saja. Kudengar gumamanku sendiri dalam separuh kesadaran. Lantas, panggilan diputus secara sepihak. Baguslah. Kini aku dapat melanjutkan tidurku yang tertunda. Berbalik, kuangkat kaki menimpa tubuh Dirja yang tertidur pulas sekali.
Kini, ruhku tinggal sedikit lagi pergi melanglang buana meninggalkan ragaku. Aku bahkan mulai tidak menghitung kecepatan detak jantungku sendiri. Namun, detik berikutnya, darahku benar-benar mendidih ketika kudengar ketukan di pintu. Untuk beberapa saat aku membiarkannya, berharap siapa pun ia yang mengetuk akan segera enyah. Namun, suara ketukan itu berubah menjadi gedoran. Spontan, aku beranjak bangun dengan mata membelalak lebar.
“Siapa lagi, sih, anjir.” Mengernyitkan dahi, kuturunkan kaki menjejak lantai dingin dan beranjak ogah-ogahan menuju pintu. Sosok Ara yang melipat tangan di depan dada dengan wajah seram melebihi hantu-hantu membuat mataku terbuka sepenuhnya. Aku seperti dihadapkan dengan malaikat pencabut nyawa untuk menyusul ruhku yang baru saja menempati ragaku.
Ara menerjang ke depan dan menjambak rambutku. “Bagus ya disuruh bangun malah lanjut ngorok!”
Aku berdiri dengan susah payah lantaran ia mengerahkan seluruh tenaganya untuk menghabisiku saat ini. Kuangkat lengan berusaha menahan serangannya. “Ya maap dong. Habisnya kamu pagi-pagi nelepon kayak orang nagih utang aja.”
“Oh, jadi sekarang nyalahin?” Ia kembali menerjangku dengan cubitan kukunya yang panjang-panjang mirip kuntilanak.
Dirja yang melempar bantal pada kami menghentikan serangan Ara padaku. “Kalian pagi-pagi udah ribut aja, sana. Cari kamar lain. Aku nggak bisa tidur nih!”
Kemurkaan gadis di hadapanku sepertinya beralih pada Dirja. Detik berikutnya, Ara naik ke atas ranjang dan memukul tubuh Dirja dengan guling. Lengan Dirja terangkat menangkisnya. Dari tempatku, kutarik tubuh Ara sebelum kamar ini benar-benar menemui kekacauannya. Setelah tubuh kami terjatuh dengan ia yang menimpa tubuhku, kakinya beranjak turun dan menyeret paksa tanganku.
“Mandi.”
“Iya, Ra. Tapi masa kamu mau gabung mandi sama aku.”
Di depanku, ia mendesis sebelum keluar dan membanting pintu kamar mandi. Dari dalam sini dapat kudengar suara keributan mereka sebelum teredam bunyi kucuran air dari shower. Anak itu sepertinya memang jelmaan dewi kematian. Usai membersihkan diri dengan air hangat, kutepuk jidat melupakan pakaian gantiku lantaran kedatangan Ara yang tiba-tiba. Terpaksa aku harus mengenakan pakaian yang tadi sebelum membuka pintu dan keluar. Dirja dengan segera memberondong masuk.
“Cewekmu udah gak waras.”
Di atas ranjang, Ara duduk menyilangkan kaki dan menatapku dengan pandangan dingin. Mendadak bulu kudukku meremang. Menghampiri ia, kudaratkan kecupan yang cukup lama pada dahinya. Usai menjauhkan wajahku darinya, sebuah tamparan menyambar pipiku dengan tiba-tiba. Sama seperti malam itu, panas merambat dan menyemut menciptakan nyeri.
“I hate you.”
“Maaf, Sayang.” Ia melirikku dengan pandangannya yang seolah-olah siap menebas leherku. Lantas, aku beranjak menjauh dan menatapnya dengan bersedekap. “Nggak mau maafin?”
Matanya membelalak. “Kurang ajar!” Hendak ia berdiri untuk menerkamku, kudorong tubuhnya dan menahan tangannya ke atas. Napasnya memburu menahan kekesalannya sendiri. Di atasnya, aku terkekeh. Air dari rambutku yang basah menetes jatuh dan berakhir di lehernya. Mendekatkan wajah, kubersihkan air itu dengan lidahku. Detik berikutnya kurasakan tendangan tepat mengenai perutku. Aku berguling ke samping seraya mendengking kesakitan. Sialan. Bahkan menggodanya saja tak lantas membuatnya menyerah dan takluk. Kini, kami berganti posisi dengan ia yang berada di atasku. Matanya sempat bersipandang denganku sebelum aku memejam lantaran pagutannya.
“Ra, ada Dirja,” bisikku di sela-sela pagutannya. Meski berusaha menahan bahunya, ia sama sekali tak menyerah. Justru aku yang memilih untuk menyerah dan membiarkannya menggila. Sebelum menarik bibirnya dariku, ia menggigit keras-keras bibir bawahku dan membuatku meringis kesakitan. “Kamu kira nggak sakit apa?”
Ia menjatuhkan kepala di atas dadaku detik berikutnya. “I hate you.” Kuurungkan niatku untuk mengomel, beralih mengangkat lengan dan memeluknya. Sekarang aku mulai sedikit mengenal caranya menghadapiku. Meskipun ia marah, ia akan lebih memilih menyerah pada akhirnya. Ia sama seperti anak kucing yang mencoba menjadi singa betina, tidak akan pernah bisa menghilangkan jati diri anak kucingnya yang telah melekat.
“I hate you too.” Spontan, ia mencubit pinggangku lagi. “Oke, oke. Damai ya. Ini sakit.” Menggulingkan badannya ke samping, kukecup sudut bibirnya sebelum beranjak berdiri. Melepas baju, kuambil pakaian ganti dari dalam ransel. Mataku melirik ia yang tak berhenti mengawasiku dari atas ranjang. Merasa risih ditatap seperti itu, kubalikkan badan dan membuka satu-satu kancing kemeja di tanganku. Terdengar pintu kamar mandi yang dibuka, disusul kemunculan Dirja yang tengah menggosok-gosokkan rambut.
“Ja, aku boleh terkam dia di depan kamu, nggak?”
Spontan, aku berbalik dan menatapnya setengah gila. Sedangkan Dirja melongo di tempatnya berdiri. Melihat kami berhasil menampakkan ekspresi tolol, ia terbahak-bahak di atas ranjang.
*
Kutatap beberapa orang yang berlalu lalang di sekitarku dari atas kursi santai. Fotografer di depan sana tengah mengatur pose orang yang akan ia potret, dibantu oleh beberapa timnya. Sedangkan Ara tengah mengobrol bersama kawan selebritinya yang kebetulan memiliki janji photoshoot di sini pula.
Kudengar desahan napasku sendiri ketika perempuan di depanku ini tengah mengatur rambutku entah seperti apa. Ketika kawannya itu pergi, Ara melabuhkan perhatiannya lagi padaku setelah membisikkan sesuatu di telinga Dirja. Tak lama, ia duduk di atas kursi sampingku seraya menyorotku dengan kameranya.
“Kamu ngapain?”
“Boomerang.” Lantas, wanita lain datang menghampiri Ara dan menyodorkan pakaian padanya dan diriku. Kutatap gadis itu dengan alis terangkat naik. Sebelumnya, ia menolak mengatakan tujuan kami. Namun ketika kudapati banyak sekali kamera dan segala tetek bengeknya, aku tahu apa yang akan ia lakukan kali ini.
Usai mengenakan pakaian yang diberikan wanita tadi, aku melangkah keluar dari ruang ganti dan langsung dihampiri wanita yang mengatur rambutku. Ia merapikan dan menambahkan aksesoris apa saja pada penampilanku. Dari sudut mataku, Ara tampak diperlakukan sama.
“Mas ini cocok lho kalau jadi model. Serasi pula sama Mbak Zeline. Katanya, kalian berlibur bersama ya?” Wanita di depanku membuka suara. Aku terkekeh-kekeh selagi memutar otak.
“Yaaa, begitulah.” Pada akhirnya hanya itu yang bisa kupakai untuk menjawab pertanyaan basa-basinya. Baiklah, selamat datang diriku sendiri di dalam lubang penuh tipu muslihat seperti ini.
“Saya sempat lihat lukisan karyanya Mas. Bagus banget lho.”
“Ah, ahaha, makasih.”
Setelah siap, aku digiring pergi ke lokasi photoshoot bersama Ara. Sang fotografer yang mungkin kenal sangat baik dengan Ara sebagai fotografer paling laris di kalangan selebriti, mengatur pose kami. Namun kami juga diberi kebebasan untuk berekspresi. Sesekali Ara terbahak-bahak bila aku melakukan hal bodoh, tak jarang pula ia menjotos bahuku ketika tertawa. Meskipun begitu, keceriaannya hari ini begitu menular.
Bila hari ini Ara tak mengajakku kemari untuk kebutuhan gosip jagat media sosial, aku tidak akan pernah tahu bahwa kegiatan seperti ini butuh lebih dari satu jam agar selesai. Aku bahkan perlu mendesah lega ketika sesi pemotretan berakhir. Setelah mengganti pakaian, kutemukan keberadaan Ara yang tengah mengobrol bersama Dirja. Mereka bangkit berdiri setelah aku datang menghampiri.
“Capek, nggak?” Tangan Ara bergerak merangkul lenganku.
“Ya iyalah.” Lantas, tawanya dan Dirja membahana. Kami perlu berpamitan dengan fotografer bernama Gio dan bermata sipit itu sebelum kembali pulang. Hari ini, Ara tidak membawa mobil sendiri. Ia datang bersama pria tua pendiam yang Ara panggil Pak Jaka. Dirja duduk di depan atas permintaan Ara. Sehingga gadis ini bisa ongkang-ongkang kaki seraya menempatkan kepala di atas pangkuanku. Tanganku ia tarik, memain-mainkan jemariku dan ia kecup berkali-kali. “Aku udah booking Gio jauh-jauh hari lho. Karena ada kamu, ya udah sekalian ajak kamu.”
“Melelahkan banget. Mending tadi tidur aja.”
“Heh!” Matanya melotot di bawah sana. Lantas, ia mainkan telunjuknya menekan-nekan perutku. “Kayaknya bentar lagi lukisan kamu membludak. Apa kita perlu beli studio sendiri?”
“Iya. Nanti uangnya bakal aku kumpulkan.”
“Nggak usah. Aku belikan aja ya.”
“Ra, tolong deh.”
“Iya deh, iya. Iya.” Dengan bibir mengerucut kesal, ia mengubah posisi menjadi menyamping. Kuembuskan napas melihatnya yang bertingkah seperti anak kecil. Kuulurkan tangan untuk mengusap kepalanya. Bukan maksudku untuk menolak permintaannya. Apa pun akan kulakukan, tapi tidak dengan sikapnya yang akan membuatku terlihat bergantung padanya. Aku bersedia ikut dengannya kemari untuk menambah peruntungan, bukan malah dimanja seperti bocah kecil.
Mobil berhenti di depan lobi hotel. Ara tidak ikut turun, karena ia harus bekerja. Sebelum pergi, ia memeluk tubuhku dan masuk ke dalam mobil. Kulambaikan tangan seiring mobil itu berjalan menjauh. Di samping, Dirja menatapku dengan raut tak terbaca. Kubalas pandangannya seraya menyengal sentimen, “Kenapa sih?”
“Auramu semakin hari semakin bagus. Dia bawa pengaruh baik buat hidupmu sampai akar-akarnya.”
“Maksudmu, selama ini auraku jelek, gitu?” Kutekan tombol bertuliskan nomor 4 ketika mencapai lift.
“Iya.” Sebelum aku membalas, Dirja melanjutkan, “Semenjak ditinggal Ayahmu, kamu itu boneka hidup. Ibaratnya makanan, kamu itu ada tapi hambar. Tapi, semenjak kedatangan Zeline di hidupmu, perlahan-lahan hidupmu yang pucet itu punya rona. Udah sejak lama aku sadar ini lho, Di. Nggak nyangka kalian beneran sampai sejauh ini.” Terdengar denting pelan sebelum pintu lift terbuka. Ada beberapa tamu yang menunggu di depan pintu. Beberapa dari mereka bahkan sempat melabuhkan perhatian padaku.
“Gitu ya?”
Kurasakan tendangan pelan pada kakiku. “Aku ini serius, cuk.”
“Iya, iya, yaelah.” Kuputar kunci pada lubangnya, lantas membuka pintu. Masuk ke dalam, pintu kamar otomatis tertutup. Dirja menghambur menuju kamar mandi. “Tapi, Ja, kamu yakin nggak sih aku sama dia ini nggak buang-buang waktu?”
“Apa?” Suara Dirja terdengar meski ia berada di dalam kamar mandi. “Kamu itu lho mbok ya mikir, Di. Kalau kamu lagi buang-buang waktu, kamu nggak lagi ada di kamar hotel ini dan sibuk menye-menye sama cewek itu di sana. Kamu nggak bakal berani maju, kamu nggak bakal berani melangkah dan ambil keputusan jauh-jauh ke sini. Sekalipun ternyata nanti kamu nggak berhasil sampai pelaminan sama cewek itu, setidaknya kisah cintamu punya cerita manis untuk dikenang. Itu yang kamu sebut buang-buang waktu?” Pintu kamar mandi dijeblak terbuka, diikuti kemunculan Dirja yang tengah menarik ritsleting celana. “Goblok.”
“Ya maap. Aku kan gak tahu.”
“Bukannya gak tahu. Kalau kamu ini ya memang goblok.” Menyingkap tirai, ia lantas membuka pintu kaca yang membatasi kamar dengan balkon seraya berkata, “Di, nggak ada penulis yang menulis dari satu kalimat ke kalimat lain di dunia ini bisa disebut buang-buang waktu. Karena dia nggak berhenti di kalimat pertama, tapi dia melanjutkannya. Sama kayak hubungan, nggak ada kisah cinta yang buang-buang waktu. Kecuali kalau pacaranmu nggak menghasilkan apa-apa, tapi malah bikin dungu!”
*
Seluruh barang-barangku untuk keperluan melukis datang keesokan paginya. Dirja ternyata setia melacak sampai di mana ekspedisi membawa barang-barang yang baginya mahal itu. Beberapa pegawai membantu menurunkan barang dan meletakkannya di atas luggage trolly untuk kemudian diletakkan di dalam kamar. Kuberi tip kepada pegawai hotel yang membantuku tadi.
Di dalam, Dirja yang paling semangat membuka paket. Kubantu ia dan meletakkan semua lukisan di beberapa sudut yang terlihat longgar. Kugerakkan mata memandangi seantero tempat usai menatanya. Kamar ini seolah-olah berubah menjadi studio mungil untukku. Dirja kembali menyibukkan diri tenggelam dalam ponsel dan sibuk mencatat yang bahkan aku sendiri tak tahu. Setelah itu, ia beranjak berdiri dan mencari beberapa lukisan jadi. Oh, ternyata ia berusaha melayani pesanan yang sempat tertunda.
“Di, empat lukisan yang aku taruh di depan TV ini pesanan orang ya. Yang lain, hm, aku atur janji temu sama pelanggan yang minta jadi model untuk daerah sini aja. Ada… dua. Terus, dua yang lain minta aliran lukisan yang berbeda.” Barulah ia mengangkat kepalanya dan memandangku. “Aku bakal minta pegawai hotel buat packing empat ini lagi ya. Besok kita tinggal beli kanvasmu aja.”
“Aku masih ada dua kanvas premium kosong sih.”
“Ya terus yang buat ngelukis model langsung? Jangan tolol deh ya.” Kepalanya kembali menunduk dan tangannya sibuk mencatat sesuatu. Lantas ia menyerahkannya padaku. “Aku saranin deh. Request yang satu ini aja pakai kanvas kosongmu itu. Aku mau panggil room service buat angkut empat lukisanmu ini.” Dirja mulai menyibukkan diri memanggil layanan kamar. Kuputar kepala mengamati langit biru di luar sana, lantas kuembuskan napas berat.
***
Nyaris melewati jam makan siang mobilku baru mencapai hotel. Langkahku tergesa-gesa ketika berjalan melalui lobi. Aku bahkan belum sempat mengabari Radi. Pemotretanku berjalan lama tadi, namun aku kembali membawa sebuah kabar gembira.
“Zel!” Suara orang yang sangat kukenal terdengar. Celingukan, kutemukan keberadaan Dirja yang mengangkat tangan sebelum berjalan cepat ke arahku.
“Ngapain di sini?”
“Ada. Tadi. Minta bantuan buat packing kanvas.”
“Oh, udah datang?”
“Iya. Tadi pagi.” Kami melanjutkan berjalan menuju lift untuk mencapai kamar. Beberapa tamu yang mungkin mengenaliku sempat menengokkan kepala padaku bahkan setelah memasuki lift. “Gila, Zel. Yang angkut lukisan Radi makin membludak. Ada beberapa seleb yang minta jadi model.”
Mendengar itu, telingaku menajamkan kepekaannya tiga kali lipat daripada biasanya. Kulesatkan tatapan tajam pada Dirja yang memainkan ponsel. “Model? Siapa? Cewek?”
“Enggak. Eh, iya sih.” Ia mengangkat kepalanya dari ponsel, lantas melabuhkan perhatian padaku. “Iya lho. Aku baru sadar modelnya cewek semua.”
Mendengus, kulengoskan muka menatap pintu lift yang seolah-olah jauh lebih menarik. Mungkin beginilah perasaan Radi ketika melihatku dengan Marcell. Suara denting terdengar sebelum pintu lift terbuka. Melangkah keluar, koridor lantai empat terlihat sepi. Ketika mencapai depan pintu bertuliskan 222, kuketuk pintu dan menunggu Radi membukanya. Ia muncul dengan kaus putih dan celana sebatas lutut. Lirikanku berlari menuju kanvas yang terpasang pada standing frame di balkon.
“Aku bawa makanan. Makan dulu. Kalian belum makan, kan?” Kuletakkan dua kantung plastik berisi tiga boks makanan dan tiga minuman dalam cup yang kupesan secara delivery di atas meja.
“Bentar ya, aku selesaikan dulu—”
“Aku bilang makan dulu, Dewangga Fajar Pradipta.” Kutatap ia seraya berkacak pinggang. Sedangkan di depanku, ia berkedip beberapa kali seraya melongo. Kudengar pergerakan Dirja yang menjamah makanan dengan sangat perlahan seakan-akan tengah menghadapi seekor macan betina.
Mengangkat bahu, ia mengembuskan napas pasrah. “Ya. Oke, oke, makan ya.” Ia berjalan menghampiri meja dan membawa satu boks. “Nih, aku makan.” Sedangkan Dirja tengah menahan senyuman di sampingnya. Menjamah satu boks yang tersisa, kujitak kepalanya dan membuatnya mengaduh. Lantas kuposisikan diri di atas kursi dekat jendela kaca besar, duduk menyilangkan kaki dan menyuapkan makanan ke dalam mulut.
“Katanya kamu dapat model baru.” Ia mengangkat kepala dan memandangku dengan mulut penuh makanan. “Cewek pula.”
“Iya. Dirja yang atur urusan waktu.” Di sampingnya, Dirja terbatuk dan dengan cekatan menjamah minuman. “Lumayan sih. Empat lho. Aku jarang-jarang dapat request khusus sampai empat.”
“Lumayan ya?” Kusuapkan makanan ke dalam mulut dengan ledakan emosi. “Lumayan ya, soalnya mereka punya badan macam gitar spanyol.”
“Hah? Masa? Aku gak tahu sih.”
Di sampingnya, Dirja melebarkan mata dan menendang kaki Radi, lantas tertawa membahana. “Di, hahaha, makan dulu ya. Itu nasimu masih banyak lho.” Menoleh kepadaku, ia meringis. Sedangkan Radi hanya mengangkat alis dan mengangkat bahu sebelum melanjutkan makan.
“Ada satu temanku minta dilukis. Tapi aku bilang buat nunggu konfirmasi dari kamu, takutnya kamu sibuk.”
“Wah, bagus tuh,” Dirja menyahut dengan mulut penuh makanan. “Nanti aku kabari aja ya kalau Radi lagi nggak ada jadwal.” Mencebikkan bibir, kuangkat bahu sebagai jawaban.
Usai itu, Radi mencuci tangannya untuk kemudian kembali berkutat bersama kanvas lukisannya di balkon dengan angin bersahabat hari ini. Selama kudengar ocehan Dirja yang tengah menelepon di atas ranjang, aku memesan room service dan memesan dua cangkir kopi untukku dan Radi. Bahkan setelah pesanan itu datang ke kamar, Dirja masih sibuk tertawa-tawa bersama seseorang yang mengobrol dengannya. Bila kudengar dari bahasanya yang tiba-tiba manis dan sesekali ia selipkan Bahasa Inggrisnya yang amburadul, seseorang yang ia ajak bicara adalah gadis bule tempo hari.
Aku duduk di atas kursi dengan secangkir kopi dalam genggaman, seraya memandang Radi yang memusatkan perhatian penuh pada lukisannya. Caranya mengeksekusi kanvas, caranya memberi cat, caranya mengernyitkan dahinya, semuanya tak luput dari perhatianku. Kuusap sisa krim kopi dari sudut bibirku, dan menjilatnya dari jari. Aku tak yakin akan bertahan tanpa memikirkan apa pun ketika melihat kernyitan dahinya itu ketika aku duduk diam menjadi modelnya.
Bila wanita di luar sana mengatakan seorang pria bisa dikatakan hot ketika ia memiliki badan kekar dan bokong seseksi bokong Michele Morrone, lengkap dengan bulu-bulu di dadanya yang bidang, aku akan berseru tidak membenarkan kehaluan mereka yang melangit itu. Radi jauh lebih seksi ketika sedang mengeksekusi kanvas lukisannya.
Beranjak berdiri, kuusap pelan bahunya dari belakang. Lantas mengecup daun telinganya. Ia menggeliat sejenak dan terkekeh. “Bagus. Itu aliran apa?”
Kularikan lidahku menyusuri belakang telinganya, sedangkan tanganku yang satu merayap membelai dadanya. Lagi-lagi ia menggeliat. “Surealis.” Kukecup tengkuknya sekilas dan mengembuskan napas di sana. “Ra, aku lagi ngelukis.”
“Kenapa? Aku kan gak ganggu.”
“Gak ganggu?” Kepalanya terputar dan menatapku dengan alis terangkat naik. Kuulas senyuman lebar sebagai balasan untuknya. Lantas ia mengembuskan napas tanda menyerah sebelum kembali berkutat bersama lukisannya. Kulingkarkan lenganku memeluknya dari belakang.
“Jangan capek-capek.”
“Aku nggak bakal merasa kapok merasa capek selama aku melukis, Ra.” Kutenggelamkan wajahku pada ceruk lehernya dan menghirup dalam-dalam aroma surgawinya. Ia terkekeh geli. “Tapi ya jangan begini dong, anjir.”
Tak kusangka, tawanya akan menular padaku. “Kenapa sih?”
“Geli, Ra. Stop it.”
“No.” Tak memedulikan larangannya, semakin kutenggelamkan kepala pada lehernya dan mengecupnya berkali-kali. Ia semakin tertawa di depanku. “Kalau nggak boleh ndusel begini, ya udah aku ke Dirja aja.” Sebelum aku berlalu pergi, ia mencekal pergelangan tanganku.
“Ngapain?” Tatapannya ia larikan kepada Dirja yang tengkurap di atas ranjang, masih mengobrol melalui panggilan telepon.
“Katanya aku ganggu.” Decakan lidahnya terdengar, lantas menarikku mendekat. Mengulum senyuman, aku duduk di atas pangkuannya dengan posisi menyamping sehingga ia dapat melukis. Kubagi pandangan antara dirinya dengan lukisannya. “Di,” panggilku detik berikutnya.
“Hm?”
“Kamu dulu jutek banget, kenapa sekarang berubah haluan?”
Tanpa melepaskan perhatiannya pada lukisan, ia berkata, “Kenapa? Maunya aku jutek aja begitu?”
“Ish! Ya nggak begitu, Di. Aku lagi tanya ini.”
Tawanya terdengar merdu di siang ini. Berhenti sejenak, ia menatapku dengan matanya yang seindah batu permata. “Kamu gila soalnya.”
Apa ia bilang? Spontan kujambak rambutnya dari belakang dan mendengar umpatannya dalam bahasa Jawa. “Kok gila?”
“Ya pokoknya gitu deh. Masa harus aku jelasin pakai rumus matematika dulu?” Mengembuskan napas, aku memilih melabuhkan perhatian pada lukisannya di samping. “Kerjaanmu gimana tadi?”
“Biasa aja. Sama membosankannya.” Ia mengangguk-anggukkan kepalanya mengerti. Merangkul bahunya dari samping, kuposisikan pipiku di atas rambutnya. “Manusia itu kayak burung, Di. Bedanya, ada burung di dalam sangkar. Dan ada yang di alam liar. Kamu berada di opsi kedua. Aku mencintai kamu dan segala kebebasanmu.”
Tangannya berhenti memberi warna pada kanvasnya. “Segala kebebasanku? Dengan segala risiko bersama orang bebas, dong?”
“Ya tapi jangan dijadikan alasan buat ngelirik cewek lain ya. Itu namanya bukan bebas, tapi berengsek.”
Kudengar kekehan panjangnya. Mengangkat kepala, kutatap ia dengan wajahnya yang mendamaikanku secara tak langsung. Perlahan, tawanya berhenti. Matanya menyorotku dengan sama bersahabatnya. “Ra, hidup itu segalanya tentang pilihan. Kita bukan boneka yang bisa dikendalikan. Tuhan saja nggak mengendalikan kita, Dia nggak pernah melarang kita mengambil keputusan. Dan hasil dari keputusan itu, adalah dari pilihanmu sendiri. Bisa aja, waktu di mana kamu mengambil sebuah keputusan malah sudah ditentukan jauh sebelum kelahiranmu. Itu yang dinamakan takdir.”
“Berarti Tuhan emang beneran mengendalikan kita, dong?”
“Tuhan nggak mengendalikan, Ra. Kalau urusan keputusan manusia ada di tangan Tuhan, manusia berdosa udah pasti masuk neraka tanpa pernah sempat bertobat. Tuhan nggak akan berlaku menjerumuskan seperti itu. Manusia yang melakukannya sendiri, dan manusia pula yang menggenggam hasil itu sendiri.” Kutatap ia bersama keheningan yang merambat. Mengulas senyuman simpul, ia melanjutkan kegiatannya yang sempat tertunda. Untuk beberapa waktu, aku menikmati suasana menenangkan ini di atas pangkuannya. Detik berikutnya, ia berkata, “Seseorang pernah bilang ke aku, bahwa sejak pertemuan kita malam itu, kamu udah memilihku. Sejak awal, pilihanmu memang jatuh buatku.”
Kudengar kekehanku sendiri, melempar pandangan pada Dirja yang setia tengkurap di dalam sana. “Siapa?”
“Dirja.” Sudah kuduga. Mengangkat kepala, Radi menatapku dengan tatapan mendamaikan penghuni surga. Kutemukan semua kedamaian di dalam kedua bola matanya. “Kamu bahkan udah memilih. Termasuk pelarianmu hari itu, semuanya adalah bentuk dari pilihanmu.”
Kularikan tanganku menyusuri pipi dan rahangnya, untuk kemudian berhenti di sudut bibirnya. Lantas kudekatkan wajah padanya. Berhenti sejenak, kutatap matanya yang juga menatapku sebelum kubawa ia dalam pagutan. Lembut, tidak menuntut, seolah-olah membiarkan waktu berjalan melambat di sekitar kami.
***
Aku tengah menyusuri kumpulan kanvas dalam berbagai ukuran ketika dering ponsel Dirja terdengar. Di sampingku, Dirja menjawab panggilan itu tanpa beranjak pergi. Kudengar suaranya seraya melarikan pandangan pada kanvas-kanvas di depanku.
“Ah, iya, Kak. Tidak bisa besok?” Matanya melirik padaku. “Hari ini? Eh, ya, bisa, Tuan Radi luang dari nanti siang hingga sore. Baik, bisa dikirimkan alamatnya di kontak saya ya.” Begitu sambungan berakhir, ia menatapku dengan kedikan bahu. “Nanti sore, salah satu klienmu minta dilukis hari ini.”
“Hari ini?” Dirja menjawabnya dengan cebikan bibir dan alis terangkat naik.
Memilih empat kanvas berukuran sama, kami mengeluarkan biaya sekitar empat sampai lima juta. Jangan kaget, para seniman bahkan tahu semahal apa kanvas lukisan. Oleh karena itu, menjadi seorang seniman tidak memiliki sebuah kepastian tetap seperti gaji karyawan kantoran. Namun bila satu lukisan berukuran besar, apalagi dilukis langsung dengan modelnya, jangan pernah meremehkan harga yang dibandrol tinggi itu. Lukisan seniman-seniman besar di luar sana saja ada yang dijual dengan harga satu triliun. Bayangkan berapa banyak benda yang dibeli untuk menghabiskan jumlah uang sebanyak itu.
Kami menaiki taksi untuk mencapai hotel. Sebenarnya, aku dan Dirja sempat meminta pegawai hotel untuk mengirim tagihan pada rekeningku atau milik Dirja. Namun mereka menolak dengan alasan takut bila Ara mengetahuinya. Alhasil, kami menetap di sini masih dengan perlindungan gadis itu. Namun, aku berencana mengumpulkan uang untuk kemudian menyewa apartemen dan membuat studio miniku sendiri di sana.
Aku dan Dirja menyempatkan makan siang setelah meletakkan kanvas-kanvas di dalam kamar. Di sela-sela obrolan kami, klienku menghubungi lagi dan mengatakan bahwa akan ada sebuah mobil yang dikirim untuk menjemput kami. Aku dan bocah ini saling berpandangan, sebelum melepaskan tawa bersama-sama. Menertawai kehidupan kami yang benar-benar terasa berbeda.
Usai bersiap-siap dan menenteng kanvas selama turun dan melewati lobi, sebuah mobil dengan plat nomor kendaraan yang telah dikatakan melalui panggilan tadi berjalan pelan dan berhenti di depan kami. Seorang pria berbadan gemuk keluar dari dalam, kuasumsikan ia sebagai sopir mobil tersebut.
“Tuan Radi dan manajernya?”
“Ya. Kami, Pak,” Dirja menyambar di sampingku.
“Mari, silakan.” Pria itu menuntun kami dan membantu meletakkan kanvas ke dalam bagasi sebelum memosisikan diri di balik roda kemudi dan menjalankan mobilnya.
Aku tidak mengedarkan pandangan ke luar sana lantaran tak akan kupahami nama jalan di provinsi ini. Yang kurasakan pada akhirnya hanyalah mobil yang berbelok melewati pagar tinggi dan berhenti di halaman serba luas. Turun dari mobil, kudapati rumah—mansion mungkin lebih tepat—terpampang di hadapanku. Ketika kami dituntun masuk ke dalam, Dirja tak berhenti mencolek-colek pinggangku. Kupelototkan mata menyuruhnya agar diam.
Sampai di taman luas dengan seorang wanita di atas kursi marmer panjang, kuedarkan pandangan menatap betapa rapi desain taman buatan ini. Menyadari kehadiran kami, ia berdiri dan menjabat tangan kami bergantian. Memperkenalkan diri sebagai Fiona Suzan. Aku tidak tahu dan aku tidak peduli. Aku hanya melaksanakan tugasku di sini sebagaimana seharusnya.
“Aduh, Di. Lupa bawa standing frame!” Dirja berbisik gaduh di sampingku.
“Hah?”
“Ah, tidak masalah. Kakek saya memiliki satu semacam itu di kamarnya. Sebentar.” Wanita itu lantas mencari sebuah nomor di dalam ponselnya dan mengatakan kepada seseorang di seberang sana untuk mengambilkan standing frame kemari. Memutus sambungan, ia tersenyum manis madu. “Tunggu ya, masih diambilkan. Silakan duduk dulu, Mas.” Mengangguk, aku dan Dirja memosisikan diri masing-masing pada kursi yang telah disediakan. “Mas Radi ini sudah lama menggeluti seni?”
“Ya, sudah lama. Memang pekerjaan saya.”
“Saya sempat terkejut mendengar gosip mengenai Zeline dan Anda. Ketika saya dengar kata seniman, saya mencari tahu tentang karya Anda. Dan ternyata memang luar biasa.” Fiona mengulas senyum simpul sebelum berkata, “Semenjak Kakek saya pergi, saya merindukan hal-hal yang berbau seni. Lukisan-lukisannya masih tertata rapi di dalam kamarnya.”
“Ah, maafkan saya.”
Tak lama, seorang wanita berdaster datang dengan standing frame yang ditenteng kedua tangannya. Aku mendirikan benda ini dibantu dengan Dirja. Detik berikutnya, aku tenggelam bersama lukisan dan model di hadapanku.
Di sela-sela waktu, Dirja beranjak pergi setelah dering ponselnya terdengar. Ia berbicara dengan seseorang di seberang telepon seraya sesekali melesatkan tatapannya padaku. Sekembalinya ia di sampingku, aku tak bertanya apa pun. Selama satu jam entah lebih berapa menit itu, aku berhasil menyelesaikan lukisan itu dengan sempurna. Beranjak berdiri, Fiona menjabat tanganku dan memberikan sebuah cek kepada Dirja.
“Terima kasih atas waktu luangnya ya, Mas. Mari, saya antar ke depan.” Fiona memilih berjalan bersama kami menuju pintu utama, di mana sopirnya setia menunggu. “Kalau saya butuh lukisan keluarga, saya bisa dong ya kapan-kapan meminta bantuan Mas.”
“Tentu. Boleh sekali.”
Memasuki mobil, wanita itu tersenyum manis madu sebelum mobil berjalan pergi. Di samping, baru kusadari ekspresi Dirja yang tidak biasanya. Mengernyitkan dahi, kutepuk perlahan pahanya, “Kamu kenapa sih?”
Ia menyugar rambutnya ke belakang, lantas mengeluarkan ponselnya dan mengetikkan sesuatu di sana. Mataku membulat lebar membaca apa yang ia tulis.
50 juta, cuk!
*
“Gila sumpah! Kenapa nggak dari dulu aja ya kita ke sini. Nggak lumayan lagi, udah lebih-lebih.” Dirja berbicara menggebu-gebu di balkon seraya merokok. Aku sempat kaget pula melihat nominal cek yang tertera di sana. Ini kali pertamaku mendapatkan harga seperti itu. Harga goals saja paling tinggi dua juta. “Tapi, Di. Kalau nggak ketemu Zeline, ya mana bisa lukisanmu dikenal khalayak umum. Anak itu juga ikut andil.”
“Ya iyalah. Makanya, jangan senang dulu. Lima puluh juta bisa habis dalam sedetik kalau kamu maunya foya-foya.” Matanya melirik padaku, lantas meringis.
Ponsel Dirja meraung-raung meminta perhatian. Melirikkan mata, kudapati nama Paula yang terpampang di layar. “What? Kamu ada di sini? Okay, okay, stay there. I’m on my way.” Sejak kapan Bahasa Inggrisnya lancar seperti itu? Meski sedikit amburadul, ia sudah memiliki kemajuan. Menutup telepon, ia beranjak berdiri dan menyambar jaket. “Di, Paula ngajak aku party di rumahnya. Aku tinggal gak apa-apa ya?”
“Halah, iyaaa. Sana sana, minggat yang jauh.”
Ia memberi ciuman jauh berlebihan yang mampu membuatku ingin segera muntah saat ini. “Baik-baik ya di sini, Sayang. Jangan nangis ya aku tinggal.”
“Bacot.”
Lantas, tawanya membahana sebelum ia lenyap di balik pintu yang perlahan tertutup. Keadaan kembali sunyi tanpa suara berisik khas Dirja. Hanya sisa-sisa aroma rokoknya yang belum sempat ia lumat di atas asbak. Menjamahnya, kuisap panjang satu kali dan membiarkan paru-paruku dikepung asap sebelum melumatnya sampai padam.
Beranjak, aku merogoh ransel dan mencari buku sketsa serta pensil dan drawing pen. Lantas kembali duduk di balkon dengan pemandangan langit gelap di atas sana, lengkap bersama gemerlap lampu-lampu bangunan tinggi. Kularikan tanganku membentuk sketsa bunga teratai yang ditambah coretan lain sebagai penghias.
Ranupatma artinya bunga teratai. Indah, sama indahnya dengan pemilik nama itu.
Sangat singkat tanpa membutuhkan waktu setengah jam, sketsa itu selesai. Warna hitam dari drawing pen menambah keindahannya. Tak lama, suara ketukan di pintu terdengar. Pasti Dirja melupakan sesuatu sampai harus berjalan kembali kemari. Membukanya, bukan sosok Dirja yang kutemukan. Justru keberadaan Ara yang mengenakan hot pants dan kardigan untuk atasannya.
“Astaga, Ara.”
“Kok astaga? Kenapa?”
Baiklah. Memang seperti ini dirinya. Aku perlu menarik napas panjang dan mengembuskannya perlahan demi menjaga kesabaran. Ia mengintip balkon dan duduk di atas ranjang. “Dirja mana?”
“Diajak pacarnya party.”
“Pacar? Yang katanya bule itu?”
“Yaaa, kayaknya.” Sepertinya memang benar bila kulihat dari namanya. “Kamu baru pulang kerja?”
Bibirnya digigit sekali sebelum meringis. “Enggak. Aku dari rumah.” Mendengar suara pintu yang diketuk, ia beranjak turun dan membukanya. Seorang pegawai laki-laki mengantar pesanan Ara. Mataku membulat melihat tiga botol wine dan tiga gelas berkaki. “Aku nggak tahu ya kalau Dirja bakal keluar. Ya udah dua ini buat kita berdua.”
“Satu, Ra. Ngapain banyak-banyak.”
Gadis itu menuangkan isinya ke dalam dua gelas berkaki, lantas menyerahkan satu kepadaku. Kutatap ia yang menyusuri lukisan-lukisan dan beberapa kanvas kosong dari atas ranjang. “Kamu mulai kapan melukis model langsung yang katanya Dirja itu?”
“Tadi udah, satu,” ujarku dari balik gelas kaca.
Ia memosisikan diri di sampingku. “Tadi? Siapa?” Tatapannya yang serupa cakram ia lesatkan.
Melempar pandangan ke langit-langit, aku mencoba mengingat siapa kiranya nama wanita itu. “Ah, ya, Fiona Suzan.”
“Fiona Suzan?” Ara memekik di sampingku. “Yang cantik itu? Kamu nggak baper melukis model sebohay dia?”
“Apaan sih? Ya enggak kali.”
Gadis itu tak menjawab dan membiarkan keheningan merambat di antara kami. Wine di dalam gelasnya tidak lagi ia cecap, melainkan ia tenggak habis. Beranjak berdiri, ia meletakkan gelasnya di atas meja, lantas meminum langsung dari mulut botol. Melebarkan mata, kuhampiri ia setelah meletakkan gelasku. “Kamu ngapain sih?” Mencoba merebut botol itu dari tangannya, ia menjauhkannya dari jangkauanku. Lantas, ia lingkarkan lengannya di sekitar leherku. Aroma anggur fermentasi menguar di indra penciuman.
“Kamu nggak lupa, kan, kalau kanvas-kanvasmu datang, lukis aku.” Meletakkan botol wine di atas meja, ia menghambur menuju balkon dan membawa masuk satu kursi, meletakkannya di depan ranjang. Lantas, ia memasang standing frame beserta satu kanvas besar yang kubeli bersama Dirja hari ini. Usai itu, ia beranjak menaiki ranjang dan duduk memeluk lututnya secara menyamping. Kepalanya ia pangku di atas lututnya, membuat rambutnya menjuntai ke depan. “Ayo. Hari ini gelap, jadi nggak pakai background langit dulu ya.”
Mengembuskan napas, kuambil cat dan bersiap untuk melukisnya. Seorang seniman harus dituntut membaca dengan jelas objek yang ingin ia lukis. Dan melalui mata gadis itu, dapat kulihat adanya kesenduan di sana. Selama satu jam itu, ia tetap pada posisinya. Tanpa bergerak, tanpa berbicara. Menyelesaikannya, kuembuskan napas dan menghampirinya. “Udah ya.”
“No. Again, Darling,” rengeknya seraya mendongakkan kepala menatapku.
“Again?” Mataku berkedip dua kali mengulang permintaannya. Sedangkan ia mengangguk, lantas beranjak untuk mengganti kanvas yang baru. Merosotkan bahu, aku duduk memosisikan diri di depan kanvas dan menunggunya memilih pose. Namun gadis itu bergerak melepas kardigannya, disusul kausnya. Mataku membulat lebar. “Ra, kamu ngapain? Astaga.”
“Apa? Kamu nggak lihat aku lagi ngapain?” Setelah menanggalkan pakaiannya, tangannya bergerak melucuti kain yang menutupi sebagian kecil pahanya itu. Sebelum aku berdiri untuk menghentikan kegilaannya, ia berseru dan melarangku bergerak mendekat. Lantas, gadis itu melepas satu-satunya hal yang tersisa di tubuh bagian bawahnya. Tuhan, apa yang aku lihat ini? Perlu aku memalingkan muka dan memilih tak memandangnya yang tanpa tertutupi sehelai kain itu. Ia benar-benar sudah gila. “Paint me.”
“No.”
“Paint me, Dewangga Fajar Pradipta.” Nadanya penuh penekanan ketika menyebutkan nama lengkapku. Perlahan, dengan jantung berdebar hingga rasanya ingin meloncat keluar, kutolehkan kepala menatapnya yang telah menopang kepalanya dengan posisi menyamping. Hingga dapat kulihat tubuhnya yang polos itu. Aku tahu, aku bahkan melihat lukisan karya Goya berjudul La Maja Desnuda’. Tapi, bila menghadapi situasi langsung seperti ini, namanya sudah gila!
“Ra, bisa kita hentikan untuk hari ini?”
“Aku tidak akan mengulangi permintaanku, Sayang.”
Ia menatapku dengan keberadaan senyuman samar yang membuatku merinding. Kuembuskan napasku yang tertahan sebelumnya, lantas memilih untuk menuruti permintaannya. Toh, ini tidak akan memakan waktu lama.
Namun, nyatanya, tidak semudah itu! Ketika sampai di bagian tubuhnya, aku benar-benar berharap untuk menghilang dari hadapannya saat ini juga. Jangan kau tanya mengapa. Bila kau menjadi aku, kau akan tahu bagaimana tersiksanya diriku. Kurasakan tanganku sendiri bergetar ketika aku hampir menyelesaikannya. Memberi sentuhan terakhir, tidak kudapati lagi kengerian yang kurasakan selama kurang lebih satu jam itu. Kupandangi lukisan di hadapanku, tidak kutemukan apa pun selain dari sebuah keindahan. Setitik keindahan dari alam semesta.
Kurasakan usapan pada bahuku, lantas Ara memosisikan diri di atas pangkuangku dengan posisi menyamping. Sama seperti ketika aku melukis di balkon dengannya yang berada di atasku. Ia telah membawa kembali gelas berisi wine dalam genggamannya. Matanya mengamati lukisan yang baru jadi. “Hm. Bakal kamu namai apa? La Zeline Desnuda’?” Ia meledakkan tawa.
“Nggak tahu. Cantiknya sebuah kelahiran?”
“Apaan? Nggak nyambung.”
“Ada definisinya dong. Bayi lahir tanpa busana, mereka cantik sebagaimana seharusnya. Sebelum mengenal pakaian, manusia juga berjalan telanjang tanpa menutup alat kelamin mereka. Dan telanjang pun memiliki arti keindahan atas sebuah kelahiran.” Mengangkat kepala, kutangkap kedua bola matanya yang mengikat pandanganku.
“Tadi kamu menolak melukis. Kenapa sekarang biasa aja?”
“Karena dengan melukismu, aku menjadi berani. Ah, nggak, sepertinya bukan dimulai dari melukis. Justru yang sebenarnya adalah, sejak kedatanganmu atau bahkan kelahiranmu sebagai bayi yang telanjang, mungkin memang takdirmu agar membuatku berani dalam hal apa pun. Termasuk lukisan ini.”
Senyumannya terulas sangat manis di sana. Lantas, ia memutar tubuh menghadapku sepenuhnya. Menenggak habis minumannya, ia mendekatkan bibir kepadaku dan membagi minuman itu agar masuk ke dalam mulut. Sisa-sisa minuman jatuh merambat ke leherku. Menjauhkan wajah, kulihat bibirnya yang basah. Lantas kusambar gelasnya untuk kuletakkan di atas meja belakangku tanpa melepaskan tatapanku padanya. Detik berikutnya, ia menyambar bibirku dalam lumatan panjang. Kucecap rasa manis dan pahit melalui bibirnya yang memesona. Tangannya bergerak liar melepas kaus yang melekat di tubuhku.
“Kali ini jangan bermain-main denganku, Di,” ujarnya dengan napas terengah-engah. Kubelai sebelah pipinya sebelum membawanya kembali dalam pagutan. Aku beranjak berdiri, membawa serta tubuhnya dalam gendongan. Kakinya bergerak melingkar di sekitar pinggangku sebelum kurebahkan tubuhnya di atas ranjang.
“Is this right? Or is it wrong?”
Matanya yang sayu memandangku. Tangannya terulur dan membelai sebelah pipiku dengan kelembutan luar biasa. “As long as with you, everything will be the right thing.” Mendengar jawabannya, kutenggelamkan wajah ke dalam ceruk lehernya. Selama lidahku menjelajah di sana dengan tanganku yang bermain di bawahnya, kudengar napasnya yang tercekat sebelum meloloskan desahan tertahan.
Untuk malam ini, Tuhan, biarkan kami melakukan dosa yang kami benarkan. Seperti kalimatnya baru saja, selama itu bersama-sama, segalanya menjadi benar.


 valentina
valentina