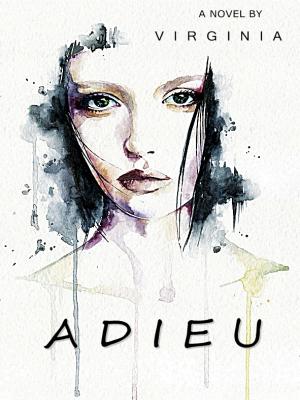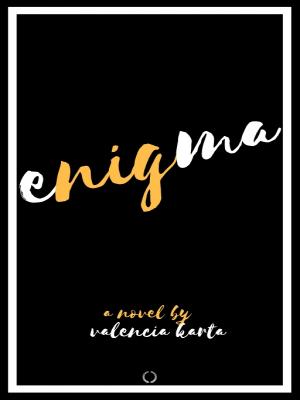“Tapi kenapa bisa? Setidaknya saya harus tahu apa pekerjaan Ayah saya sampai ia tewas.”
“Maaf. Tapi, beliau tidak meninggalkan catatan apa pun sebelum ia bunuh diri. Perusahaan juga tidak mengetahui latar belakang dari kasus ini. Mohon pengertiannya.” Kutatap Ibu dan Kumala yang menangis sesenggukan di depanku sambil berpelukan. Mendengar tak ada sahutan dariku, suara dari seberang telepon kembali berkata, “Mobil yang mengantar jenazah sedang dalam perjalanan dari Jakarta menuju tempat Anda sejak beberapa jam yang lalu. Mohon ditunggu, terima kasih.” Dan sambungan terputus.
Ibu dan Kumala semakin menangis menjadi-jadi berdua. Dari tempatku berdiri, satu air mataku menetes, disusul butiran lainnya. Perlahan aku mendekat dan memeluk dua malaikatku yang tersisa saat ini. Tangan Ibu bergetar oleh tangisnya sendiri. Kukecup puncak kepala Ibu dan Kumala. Sejak saat itu, mereka berdua telah menjadi tanggung jawabku.
Lalu, beberapa jam setelah kabar itu, sebuah mobil datang ke desaku membawa jenazah Ayah, dengan luka tembak di bagian kepala yang sudah dibersihkan. Sementara aku bersama pengantar jenazah yang saat itu mengenakan jas hitam resmi, berbincang secara pribadi. Mereka ada empat orang, termasuk sopirnya. Dua lainnya menurunkan barang-barang untuk keluargaku. Sembako, peralatan rumah tangga, termasuk barang-barang yang Ayah tinggalkan, dan beberapa tambahan barang pemberian bos Ayah terdahulu. Pria yang di hadapanku, menyerahkan dua amplop cokelat padaku.
“Uang kompensasi mendiang Ayah Anda, dan uang untuk kebutuhan sehari-hari keluarga Anda, Tuan Pradipta.” Kuterima kedua amplop berisi uang itu masih dengan kondisi tidak memahami apa yang terjadi, mengabaikan fakta bahwa pria tak dikenal ini mengetahui namaku.
Ingatan itu beralih pada situasi hening di dalam rumah setelah pemakaman Ayah. Ibu dan Kumala tertidur di kamarnya masing-masing. Tetapi Ibu tidak benar-benar tidur. Ia menangis, lirih sekali. Namun masih dapat terdengar di telingaku. Mendengar tangisannya, hatiku ikut merasakan sakitnya. Tetapi aku tahu, menangis adalah hal yang paling Ibu butuhkan saat itu.
Lalu, ingatanku beralih lagi ketika aku tengah membuka kotak persegi panjang pemberian pria asing berjas hitam. Isinya adalah beberapa berkas-berkas pribadi yang Ayah bawa ketika berangkat merantau ke Jakarta.
Dan kini di tanganku terdapat beberapa foto. Di tempat yang sama, dengan foto-foto yang sama. Hanya dengan cara ini aku dapat melihat wajah Ayah. Sudah berulang kali kulihat foto-foto di tanganku, tak dapat kuhitung termasuk hari ini. Ayah yang memakai jas hitam rapi sambil berbincang dengan seorang pria di depannya, Ayah yang membaca surat kabar, Ayah yang difoto bersama tiga orang pria berjas sama dengannya, dan Ayah yang bersama seorang gadis kecil dalam rengkuhannya. Di foto terakhir selalu membuatku termenung. Foto itu diambil di taman bermain. Banyak anak kecil sebagai latar foto itu, dan seorang pria yang tengah berbincang bersama wanita yang tengah ia rangkul.
Aku tak tahu mengapa, tetapi aku selalu berhenti pada foto terakhir. Siapa gadis ini? Dan apa yang Ayah lakukan di sana bahkan sampai ia tewas?
Namun seiring berjalannya waktu, pertanyaan tanpa jawaban itu seolah-olah tenggelam ke dasar lautan. Tidak pernah muncul kembali, kecuali bila aku sedang melihat-lihat potret Ayah. Bahkan meskipun rasa penasaranku melebihi segalanya, aku tidak akan pernah bisa menjawab pertanyaanku sendiri.
Sudah lebih dari setahun sejak Ayah memutuskan meninggalkan pekerjaannya di pabrik dan memilih untuk merantau ke Jakarta. Meski jauh, pria itu selalu melaksanakan tugasnya sebagai tulang punggung keluarga. Kumala juga dapat mengerti dan memahami keputusan Ayah.
Mengembuskan napas, kutaruh semua berkas serta foto-foto Ayah di kotak tempatnya tersimpan rapi selama ini. Hari ini aku ada janji dengan Dirja. Menemui Pak Giyana, salah satu anggota politik yang terkenal akan kekayaannya di desa kami. Dirja bilang, pria itu membeli dua lukisanku untuk kantor cabangnya di Pasuruan, tanpa menawar. Jadi, kubungkus rapi dua pesanan lukisan tersebut dan menelepon Dirja untuk segera menjemputku.
Di teras, kudapati Kumala yang tengah menyapu. Ia melihatku, kemudian lukisan di tanganku, dan kembali menatapku. “Orderan lagi?”
“Iya nih.”
“Siapa?”
“Mr. Giyana,” kekehanku lolos mendapati Kumala yang memutar bola mata.
“Tumben banget orang desa ada yang mau pesen? Biasanya bodo amat.”
“Jangan ngedumel. Doa aja biar banyak yang order setelah ini.”
Kumala menarik napasnya dalam-dalam dan mengembuskannya dengan kesal, lantas menatapku dengan pandangan malas. “Mas, Kumala bilangin nih ya, eksistensi orang kaya di desa kita bisa dihitung jari.”
Sekian detik aku termangu mendengar kalimat adikku itu. Berkedip dua kali, kusemburkan tawa di depan mukanya. “Wah! Lihat betapa sinisnya dirimu, Sayang. Belajar dari mana? Pasti hobi ghibah ya kalau sekolah?”
Tak terima, Kumala memukulku dengan sapu sambil melotot. Mengapa pula sikapnya sudah mirip dengan Ibu? Sebelum anak itu menghabisiku dengan sapunya, suara deru motor Dirja terdengar, diikuti kemunculannya. Kuacak-acak rambut Kumala sebelum berpamitan. “Mas nggak lama. Nyapunya yang bersih ya.” Gadis itu hanya memutar bola mata sebagai responsnya, membuatku terkekeh geli.
Tak perlu memakan waktu lama bagi kami untuk sampai di rumah Pak Giyana. Melihat motor Dirja terparkir di depan pagar rumahnya, satpam penjaga membuka pagar untuk kami. “Mas Dirja toh?”
“Iya, Mas.”
Satpam itu mempersilakan kami masuk. Rumah besar ini memiliki taman kecil yang sebagian besar diisi kandang-kandang hewan yang mungkin jarang dipelihara warga kampung. Merak, misalnya. Kulirik hewan dengan bulu-bulu indahnya itu. Ia bersuara, keras sekali. Melihat bulu-bulunya, aku tak tahu mengapa selalu teringat sosok Kresna.
“Duduk dulu, Mas. Bapak sedang ada telepon penting. Ditunggu ya,” ujar pembantunya setelah mengantarkan minuman kepada kami berdua. Sudut mataku menangkap keberadaan lukisan kubisme yang tergantung di dinding. Di titik lain terdapat pula lukisan surealisme. Dan aku, seolah disihir oleh tangan-tangan semu, beranjak berdiri untuk mengamati sebuah lukisan yang menarik perhatianku.
Di dalam kanvas itu, terperangkap sepasang kekasih dengan tubuh telanjang di bawah selimut. Namun bukan itu yang sebenarnya menarik perhatianku. Tetapi keberadaan sebuah pisau di masing-masing tangan mereka. Kepala si wanita berada di atas dada pria, sedangkan lengan pria itu dijadikan bantal bagi wanitanya. Bibir mereka menyatu dalam posisi itu. Namun tangan mereka saling menghunuskan belati di tubuh pasangannya. Kukatakan padamu, belati!
Di bawah lukisan itu terdapat tulisan mungil sebagai keterangan singkat dari pelukisnya: Parfois, l'existence de l'amour existe pour conduire à la fin elle-même.
Keningku mengernyit dalam, bertepatan dengan suara berat seorang pria terdengar memecah lamunanku.
“Saya dapatkan itu ketika berkunjung ke Prancis.” Pemilik rumah ini muncul dan berjalan menghampiriku, lantas berdiri di sampingku. Memandangi lukisan yang ia pajang di dinding rumahnya ini. “Itu kali pertama saya dibuat jatuh cinta oleh lukisan, langsung dari negara seni itu sendiri.”
Kubaca ulang kalimat bahasa Prancis itu di dalam hati. “Keterangan di bawahnya, apa artinya?” gumamku, lebih kepada diriku sendiri, serupa bisik angin pada musim gugur.
Ia menoleh menatapku sejenak, tersenyum simpul, lantas kembali melabuhkan perhatiannya lagi pada lukisan itu. “Terkadang, eksistensi cinta ada untuk menuntun kepada akhir itu sendiri.”
“Apa?”
Pak Giyana terkekeh-kekeh di tempatnya. “Artinya, Nak Pradipta, artinya. Kamu tadi menanyakan artinya, kan?”
Baiklah. Kini aku yang bertindak tolol lantaran tersihir ruh lukisan di hadapanku ini. “Ah, ya. Maaf.”
“Sang pelukis hendak memberikannya pada saya secara cuma-cuma. Namun saya tahu, karya-karya seni seperti ini tidak boleh dimiliki secara gratisan. Apalagi lukisan magis yang sudah jarang ditemukan di era ini.” Pria di sampingku menoleh menatapku lagi, “Menurutmu, apa yang berusaha dikatakan oleh lukisan ini?”
Mataku kembali menyetubuhi lukisan di hadapanku, seolah-olah ikut menyelam ke dalam dunianya. Kepalaku terteleng ke satu sisi. “Manusia selalu terjebak dalam paradoksal antara cinta dan benci, juga dendam. Ada cinta yang sanggup berdiri sendiri, cinta yang menemui obsesi, cinta yang mencumbu keegoisan. Tapi, di dalam lukisan ini, cinta itu… menuju mati.” Aku bahkan tidak tahu dari mana kalimat—sok—puitis itu kudapatkan. Atau memang ruh lukisan ini menunjukkan kehebatannya.
Tak kudengar apa pun selain suara tawa Pak Giyana beberapa detik berikutnya. Ia menepuk bahuku bersahabat dan mengajakku duduk kembali di sofa ruang tamu, di mana terdapat keberadaan Dirja yang tadi kutinggal. Namun, sebelum kami benar-benar duduk di atas sofa ruang tamu, suaraku menghentikan langkah Pak Giyana. “Apa pelukisnya memang benar orang Prancis? Saya ingin sekali bertemu dengannya.”
Ia menoleh, menatapku dengan pandangan yang… entahlah. “Tidak. Pelukisnya berdarah Indo-Prancis, bukan le parisien asli. Dan, ia sudah mati.” Lantas ia kembali berjalan meninggalkanku berdiri mematung untuk beberapa detik lantaran keterkejutanku sendiri.
Dirja mengulas senyuman lebarnya menyambut kedatangan Pak Giyana. Detik berikutnya, kami bertiga terlibat obrolan di waktu-waktu transaksi kami. Lantas, pada akhirnya aku dan Dirja pamit undur diri ketika dering ponsel Dirja terdengar dengan nama Pras terpampang di layar. Barulah saat itu kudapati diriku kembali sepenuhnya.
*
Aku dan Dirja berakhir di Jagad Kopi setelah panggilan Pras tadi. Ia berencana mengajak kami begadang semalaman sambil bermain catur di dalam kafe, sebelum kedatangan seorang perempuan yang menghampiri Pras sambil uring-uringan dan mengharuskan mereka berdua menyelesaikan masalahnya di dalam.
Hari sudah menuju larut. Suhu mulai mendingin. Namun kafe semakin dipadati tamu. Kuhampiri Dirja yang berdiri di luar seraya menyulut pemantik pada rokoknya. Ia menoleh menyadari kehadiranku. “Masalah perempuan emang selalu berujung ribet ya. Heran.”
Aku terkekeh menanggapi kalimatnya baru saja. “Biarin aja lah. Kayaknya masalah duit, atau… ranjang?”
Praktis Dirja menoleh menatapku dengan alis terangkat. “Tumben otakmu itu?”
“Kenapa?”
“Bener.”
Kutendang kakinya dan membuatnya mengaduh. Tak lama, pintu kafe dibuka, disusul kemunculan perempuan yang kuasumsikan sebagai pacar Pras itu keluar dan menuju mobilnya seraya menghentak-hentakkan kaki. Setelah mobil itu berlalu, barulah sosok jangkung Pras muncul dari balik pintu kaca.
“Siapa?” tanya Dirja.
“Pacarku. Ngamuk dia, soalnya aku nggak ngabarin kalau aku ke sini.”
“Gitu doang?” Dirja menghirup panjang rokoknya sebelum ia jatuhkan untuk dilumat sepatunya. Ia melakukan itu tanpa terbatuk sama sekali. “Halah taik. Cewek selalu ribet.”
Tawa Pras membahana. “Beruntung kalian yang nggak ngerasain betapa susahnya menghadapi perempuan.” Pemuda itu menarik kunci mobilnya di saku celana, “Ayok.”
“Lah? Ke mana?”
Pras berbalik dan menyeringai lebar kepada kami. “Dugem.”
Lagi?
***
Dengan koper yang kuseret di belakang dan tudung jaket yang kupasang menutupi kepala, aku mencoba mencari taksi di depan bandara. Sialnya aku lupa membawa masker dan kacamata hitam atau bedebah lainnya yang memungkinkanku untuk menyembunyikan diri. Sepanjang aku berjalan, kurasakan tatapan orang-orang bagaikan mengulitiku hidup-hidup. Mungkin mereka tak asing dengan postur tubuh ini. Dan dalam hati, aku benar-benar berharap bahwa aku tidak mudah dikenali di sini. Apalagi oleh paparazzi. Bisa bahaya kalau ketahuan, apalagi aku tidak memiliki kenalan di sini!
Dengan mata menyorot malas, kudapatkan taksi setelah setengah jam lebih berdiri di sini. Masuk ke dalam mobil, kukatakan kepada si sopir agar ia mematikan pendingin.
“Ke mana, Mbak?”
Kepalaku bersandar lemah. Ke mana aku harus pergi? Ini bahkan kali pertama aku ke Jawa Timur. Aku benar-benar butuh mengistirahatkan kepalaku.
Ah, ya, minum. I need to drunk tonight!
“Club ya, Pak.”
“Diskotik ada banyak, Mbak.”
Kudesahkan napas berat di tempatku duduk. “Terserah. Yang paling terkenal kek, yang paling sepi, yang paling rame. Terserah pokoknya.”
“Oke.”
Lantas, mobil dilajukan perlahan. Kukeluarkan ponsel dari dalam saku jaket. Mematikan GPS, kudapati puluhan pesan dan missed call dari nomor Kenzo, Mama, dan juga Papa. Tak terkecuali Marcell. Menyadari bahwa aku online, panggilan suara dari Kenzo muncul di layar smartphone. Untuk beberapa detik aku menimbang-nimbang, sebelum kuputuskan untuk menjawab panggilannya.
“Zel?” ia bersuara di seberang sana. “Are you ok? Kamu di mana, Zeline? Kami khawatir di sini.”
Kutekan pelipisku seraya membuang napas. “I’m fine. Nggak usah berusaha cari aku, atau aku bakal kabur ke tempat terjauh.”
Beberapa detik hanya ada keheningan, sebelum Kenzo kembali membuka suara. “Zel, please. Pulang ya?”
“Enggak.”
“Zel—”
“Aku butuh waktu sendiri, Zo. Aku capek jadi boneka semua orang. Buat kali ini aja, biarkan aku dapat kesempatan bebas. Ya?”
Embusan napas kakakku itu terdengar. Ia menyerah dengan kekeraskepalaanku. “Fine. Jaga diri ya. Kita akan bicara ke media kalau kamu lagi liburan.”
“Oke.” Lantas, panggilan kututup secara sepihak. Aku kembali offline agar tidak ada lagi panggilan yang berbondong-bondong masuk. Aku harap kalian mengerti, menjadi orang terkenal yang melakukan hal apa pun untuk menjaga citra baik adalah hal yang tidak menyenangkan. Meski aku tahu ini adalah bagian dari pekerjaanku. Tidak Anastasia, tidak Ibuku. Mungkin di dunia ini yang tidak menyetirku adalah Papa dan Kenzo.
Mobil kurasakan berhenti. Mengintip dari balik jendela, alisku terangkat. “Plaza?”
“Ada di dalam.”
Untungnya, aku selalu membawa dompet mini untuk berjaga-jaga di saat seperti ini. Sebelum memberikan uang seratus ribuan kepada sopir taksi, aku membuka suara dan bertanya, “Maaf, Pak. Lantai berapa ya?”
“Lantai 5, Mbak. Baru sekali ke Surabaya ya?”
“Yaaa, begitulah pokoknya. Makasih ya, Pak. Kembaliannya buat Bapak aja ya.”
Setelah mendengar ucapan terima kasih dari si sopir, aku keluar dari mobil dan disambut dinginnya udara malam Surabaya. Kurapatkan jaketku, selain untuk menghangatkan diri, juga bersembunyi. Security yang tengah bertugas di depan pintu masuk menahanku. Memangnya aku salah apa?
“Boleh tahu isi koper itu apa?”
Ah, ya. Mungkin ia curiga aku adalah anggota kelompok teroris yang membawa bom di dalam koperku ini. Memutar bola mata, aku menyengal sentimen, “Pakaian dalem. Mau lihat?”
“Bisa dititipkan di information center, Mbak, biar tidak merepotkan.”
“Ya anterin, dong. Aku kan nggak tahu.”
Pemuda berbadan taruna itu melenggang menuntunku menuju meja pusat informasi. Ia mengatakan kepada wanita di balik meja bahwa aku perlu menitipkan koper. Setelah itu, satpam tadi mengulas senyuman singkat sebelum enyah dari hadapanku.
“Atas nama siapa?” suara staf informasi membuyarkan lamunanku. Aku mengedip dua kali. Nama siapa?
“Arabella… Ranupatma.” Kukatakan padamu, nama belakangku adalah Ranupatma. Tak ada marga, hanya nama belakang. Semenjak menjadi model dan selebriti, aku terpaksa menggunakan nama panggung Zeline Arabella. Daripada harus menerima nama panggung aneh-aneh. Misal, Zeline Ting-Ting? Kembang Zeline? Zeline Serigala?
Aku bergidik ngeri setiap mengeja nama-nama absurd itu.
“Baik. Atas nama Arabella Ranupatma ya.” Lantas ia menerima koperku dan disimpan di balik meja. Tidak ada kunci, kukatakan kepadamu. Karena tidak akan muat loker dengan koper sebesar itu.
Memasuki lift, aku menekan tombol lantai 5. Aku tidak pernah mengunjungi mall di jam-jam seperti ini sebenarnya, dan aku baru tahu tidak seramai siang hari. Terdengar bunyi ding pelan sebelum pintu lift terbuka. Di depan sana, kutangkap sepasang kekasih berjalan sempoyongan seraya tertawa. Mataku mengekori tempat di mana mereka keluar tadi. Segera, aku berjalan cepat ke sana.
Dengan mengeluarkan biaya masuk, aku melenggang menuju ke dalam. Tanpa dress mini, tanpa sepatu hak. Hanya pants sebatas paha dan tank top yang kulapisi jaket, juga sandal santai. Ironis sekali, tapi memang itu kenyataannya.
Suara ingar bingar musik memekakkan telinga. Aku pergi dan duduk di kursi bartender. tiket masuk itu sudah diberi gratis satu minuman. Kuputar kepala ke sekelilingku sementara bartender menyiapkan minumanku. Lautan manusia bergerak liar di lantai dansa dan di depan meja DJ. Ada banyak om-om tua berperut buncit yang tengah merangkul wanita dengan segelas minuman di tangannya. Kubulatkan mata dan menelan ludah. Hei, ini kali pertamaku memasuki diskotik! Sendirian, di provinsi lain pula. Kurang gila apa lagi diriku.
Kupusatkan perhatianku kepada gelas kristal berisi minuman di depanku. Lantas, kutenggak habis masuk ke dalam kerongkongan. Panas dan getir menyambar tenggorokan dan lidahku. Aku mengernyit merasakannya. Hariku pahit, dan terasa pula di dalam minumanku. Lain kali, bila suasana hatiku sedang baik, aku akan pergi minum. Pasti kepahitannya berubah menjadi manis.
Kepalaku mulai pening. Di sampingku, hadir seorang pria berumur akhir dua puluhan berbisik dengan bartender, namun masih tertangkap pendengaranku.
“Yang termahal dan profesional ya.”
“Kamu pintar mengeksekusi, Darling. Tunggu sebentar ya.” Lantas ia menghilang ditelan kegelapan.
Pria itu menoleh ke arahku, tersenyum, “Hai. Wajahmu… nggak asing.”
Cepat-cepat kualihkan kontak mata darinya. Mampus kalau ketahuan. “Stay away from me.”
Kudengar suara tawanya yang meledak di samping. “Oke.” Tak lama, dari sudut tempat lain muncul seorang pelacur pesanan pemuda di sampingku ini. Ia mengenakan gaun merah menyala sebatas paha dan tanpa lengan. Dada sintalnya membusung di balik gaunnya. Ia melimbai dan bergelayut di lengan pemuda asing itu. Sebelum mereka enyah melakukan transaksi fisiknya, pemuda itu mengerlingkan mata padaku. Tak kulihat lagi batang hidung mereka setelah lenyap ditelan pintu.
Dalam keadaan setengah sadar, kuperhatikan lagi sekelilingku. Semuanya sama saja. Sepatu, jam, uang, outfit, dan mata-mata mesum. Benar, memang begitu. Justru aku akan lebih kaget bila menemukan pemuda bermata polos berkeliaran di tempat macam begini. Baru saja pikiranku mengatakan itu, di kursi lain kutangkap eksistensi pemuda aneh. Kukatakan aneh karena wajahnya yang tolol—atau polos?—tentu saja. Ia celingukan memandang dunia di sekitarnya, seperti seorang bocah kecil yang tersesat di dalam keramaian. Memangnya ia datang bersama siapa sampai kebingungan seperti itu? Wanita-wanita berbaju seksi yang menghampirinya saja ia tolak. Di atas mejanya terdapat beberapa botol bir yang sama sekali tak ia lirik.
Kugigit bibir bawah, lantas menelengkan kepala ke satu sisi. Melepaskan jaket, kuikatkan jaketku menutupi paha bawah dan membiarkan bahuku terekspos. Aku turun dari kursi tinggi dan berjalan mendekat padanya, masih berusaha menjaga keseimbangan agar tidak tersandung lantaran mabuk.
Ah, rasanya, malam ini akan menjadi malam yang panjang.
***
Baru saja melangkah memasuki tempat ini, telingaku yang ndeso meresponsnya dengan kurang menyenangkan. Pasalnya, musik yang dimainkan DJ terlalu menggelegar di telingaku sendiri. Berbeda denganku, Dirja menyambutnya dengan teriakan senang lantaran banyak wanita-wanita seksi di sekitar kami.
Pras berjalan menghampiri setelah mengambil tiga botol bir seraya tersenyum lebar. Membuka tutup botol, Pras menuangkan isinya ke dalam gelas kristal. Kali ini, ia tak mengeluarkan vape yang selalu ia bawa ke mana-mana. Kedua kawanku itu menatap keramaian berlebihan ini dengan mata berbinar. Memajukan wajah pada kami, Pras membuka suara, agak keras untuk mengalahkan kebisingan, “Kalian mau sewa kamar?”
“Hah?”
“Bisa?” Sahut Dirja antusias. Kutolehkan kepala menatap keparat ini.
“Bisa, dong. Kalau ada duit sih.” Pras berdiri dari kursinya dan tersenyum lebar. “Tapi aku enggak. Aku lebih pilih dugem daripada nyewa. Ayok.”
Dirja berdiri, bersiap bergabung bersama Pras di lantai dansa tempat orang-orang menggila. Sedangkan aku tetap di tempatku duduk dan mengundang tatapan tanya dari mereka berdua. Kugelengkan kepala pelan, “Aku tunggu di sini aja. Kalian joget-joget dulu sana.” Tawa Pras membahana merespons kalimatku baru saja. Lantas, ia dan Dirja berjalan pergi menuju lantai dansa dan ikut menggila di sana.
Sepeninggal mereka, aku tidak tahu harus apa. Kutatap tiga botol bir di depanku, tidak berminat untuk menjamahnya. Kupandang keadaan sekitar dan terus membatin. Jadi ini surganya dugem. Tempat orang-orang melepaskan penat atau hanya sekadar bersenang-senang. Sebenarnya, aku ingin menjamah sebotol bir di depanku itu. Namun, aku tidak sedang berminat mabuk. Daripada itu, yang paling menyebalkannya lagi adalah kedatangan perempuan-perempuan berbusana kurang bahan di sampingku dan berusaha menggodaku. Kudorong perlahan bahu mereka agar segera menyingkir. Menyerah, mereka memilih pergi.
Gila. Meski mereka telanjang pun, aku tak akan menyentuhnya! Aku tak pernah melakukan hubungan intim, dan aku ingin melakukannya atas dasar cinta. Bukan transaksi tubuh.
Belum beberapa menit aku bernapas lega, datang seorang gadis yang berjalan sempoyongan ke meja tempatku duduk. Bahunya hanya dihiasi tali tipis tank top yang menggantung, membiarkannya terekspos. Jaket yang biasanya digunakan di tubuh ia ikat di pinggang dan menggantung di atas pahanya yang hanya tertutupi short pants. Dari bahasa tubuh, ia adalah pelanggan di sini. Bukan golongan wanita-wanita tadi.
Ia duduk di kursi depanku dan menatapku intens. Ada apa dengannya?
“Kamu siapa?”
“Aku?” kutunjuk diriku sendiri dengan ekspresi tolol.
Mengabaikan pertanyaanku, ia mendekatkan wajahnya dan seketika kucium aroma bir ketika ia berbicara. “Kamu bukan bocah kecil yang lagi tersesat, kan?” Ia mabuk rupanya. Tak menjawab pertanyaan melanturnya, kualihkan kontak mata darinya dan mengarahkannya pada tempat lain. Kesal kuabaikan, ia berdecak dan beranjak berdiri. Kukira ia akan enyah, namun ia berjalan mendekatiku. Mendorong meja di belakangnya dengan satu kaki. Lantas memosisikan dirinya di atas pangkuanku.
Apa-apaan ia?
“Aku benci diabaikan, Darling.” Mata kami saling bersinggungan. Aroma alkohol dan sedikit esensial melon tercium dari jarak dekat seperti ini. Bila aku waras, aku akan mengusir gadis asing yang secara sembarangan duduk di atas pangkuanku seperti ini. Namun, kurasa memang aku sedang tidak waras. “Untuk apa kamu datang ke sini kalau bukan untuk menggila bersama manusia-manusia kurang kerjaan di sini, hm? Aku yakin kamu bukan anak kecil yang sedang ditinggal orang tuanya di sebuah pasar malam.”
Wajahnya semakin mendekat, membuat rambutnya menjuntai membingkai sebelah wajahku. Dan seperti lelaki tolol, suaraku justru tergagap menjawab kalimat-kalimatnya. “Aku… datang bersama teman.” Detik berikutnya ia menghempaskan kepalanya ke belakang dan meledakkan tawa. Secara instingtif, tanganku terulur menahan punggungnya agar tidak jatuh.
Sebenarnya ia—aku—ini sedang apa?
Gadis itu kembali mendekatkan wajahnya padaku. Tangannya menangkup pipiku. “Kamu itu polos, atau memang goblok? Kamu di sini cuma mau observasi tanpa ikut menggila untuk kebutuhan sebuah novel emangnya?” Ia semakin merangsek padaku dan berbisik tepat di depan bibirku, “Tapi, itu menjadi sebuah daya tarik tersendiri dalam dirimu, tahu.”
Apa ia bilang?
“Aku lihat wanita-wanita tadi menyerah. Dan aku bertanya-tanya, kamu ini siapa? Apa keteguhan hatimu itu bisa bertahan di depan Succubus itu sendiri?” Ia kembali melantur. Aku penasaran, apakah ia sedang berpuisi? Tanpa sadar, bibirku tersenyum samar. Membiarkan gadis asing ini mengoceh di atasku. Aku bahkan tak tahu mengapa tak kutendang saja ia agar segera enyah dan tidak mengganggu diriku. “Apa keteguhanmu itu… bisa berlaku juga untuk diriku sendiri?” bisiknya. Detik berikutnya, lidahnya melumat bibirku. Kurasakan tubuhku mengejang dan mataku melotot. Waktu seakan berhenti di sini, dan tak kudengar lagi ingar bingar di sekitar. Ketika ia menjauhkan bibirnya dariku, ia menyeringai. “I win. Kamu tidak mengusirku.”
Ia sudah gila?!
Sebelum sempat tanganku mendorong tubuhnya menjauh, kepalanya jatuh di atas bahuku. Ia bergumam lirih, “Biarkan aku menggila sehari saja. Kamu—kamu nggak bakal berlaku sama kayak mereka, kan? Untuk sekali ini saja. Biarkan aku… hidup.” Lantas kepalanya bersandar sepenuhnya di atas bahuku.
Mendengar kalimat janggalnya baru saja, membuatku mengurungkan niat untuk mengusirnya. Sebaliknya, justru tanganku terulur menepuk-nepuk punggungnya.
*
“Menang banyak kamu, Di, Di. Kenapa tadi bukan aku aja ya yang di sana?” Suara Dirja yang duduk di kursi depan terdengar. Pras yang tengah menyetir tanpa mabuk sama sekali itu hanya mendengus dan tertawa. Kulirik gadis di sampingku yang kini tertidur. “Bakal kamu bawa ke mana?”
“Rumahku aja. Aku bakal jelasin ke ibu. Aku yakin dia pasti ngerti.”
Jalanan mulai lengang ketika melewati Tanggulangin dan terus menuju Porong. Ini sudah masuk dini hari. Pras bersedia mengantar kami ke rumah masing-masing. Mobil sampai di depan rumah setelah mengantarkan Dirja pulang. Kukatakan terima kasih kepada Pras sebelum mobilnya melaju pergi. Merogoh mencari kunci rumah di saku celana, satu tanganku menahan tubuh gadis asing itu agar tak terjatuh. Setelah berhasil membuka pintu, sebisa mungkin aku masuk tanpa menimbulkan suara ribut.
Kugendong gadis ini dan membawanya menuju kamarku. Memosisikannya di atas kasur, kuambil jaketnya dan menutupi tubuhnya dengan selimut. Sebelum aku beranjak berdiri, kuamati wajahnya yang damai. Sesuai mata lelaki pada umumnya, kukatakan kepadamu bahwa ia cantik. Sangat cantik malah. Kusingkirkan anak rambut yang menghalangi wajahnya. Ingatanku berputar pada kejadian tadi, di mana ia melumat bibirku dengan lidahnya tanpa permisi.
Kugelengkan kepala merasa ngeri bila mengingat kembali hal itu.
Aku mengambil satu bantal dan keluar untuk tidur di ruang tamu.
*
Mataku terbuka dengan rasa pedih luar biasa ketika kudengar bisikan gaduh Ibuku ketika membangunkanku yang tertidur di kursi ruang tamu. Keningku mengernyit merasakan kepalaku pening.
“Aduh, Di, mbok ya bangun! Itu siapa yang kamu bawa pulang? Dasar anak ndableg. Dari mana kamu semalem?”
Spontan aku melesat bangun dan menyuruh Ibu memelankan suara. “Jangan berisik. Nanti dia bangun, Bu.”
Masih dengan bisikan gaduh kami, Ibuku menoyor kepalaku gemas. “Ya jelasin itu siapa, Radiii. Pacarmu?”
“Ngawur ah! Kemarin aku main sama Dirja dan Pras. Gak tahu deh tiba-tiba dia nyamperin aku, terus gak sadar.” Aku memilih tidak mengatakan bagian dugem kepadanya atau pagi ini ia akan jauh lebih mengamuk lagi. Ibu berdecak sekali lagi dan duduk di sampingku.
“Ah, kamu mah. Nanti kalau tetangga tanya gimana?”
“Kita bisa bilang… saudara jauh? Gampang mah kalau tetangga juga.”
Ibu menunjuk mukaku dengan telunjuknya, “Awas ya. Itu tugas kamu.” Lantas, ia beranjak berdiri untuk kembali berkutat di dapur. Sebelum ia benar-benar pergi, wanita itu berbalik dan berbisik di dekatku, “Tapi, dia cantik. Gak apa kalau mbok pacarin.”
“Apaan sih, Bu. Sana-sana.” Ia pergi seraya memberengut kesal lantaran kuusir. Setelah Ibu lenyap menuju dapur, kudecakkan lidah sekali.
Setelah menetralkan kepalaku yang pusing lantaran dibangunkan tiba-tiba, kusambar bantal yang kubuat tidur dan beranjak ke dalam kamar. Kuletakkan benda itu secara hati-hati di sampingnya. Namun, sepelan apa pun aku bergerak, sayangnya mata gadis itu terbuka tepat ketika wajahku berada di hadapannya. Sebelum aku berhasil menarik kepalaku menjauh darinya, telingaku harus rela mendengar teriakan heboh gadis yang bangkit dari tidurnya dengan gerakan cepat. Tak lama, Ibu dan Kumala melongokkan kepala mengintip kami di daun pintu. Aku memberi kode kepada mereka agar pergi saja.
“Kamu siapa?!” Bentaknya. “Kamu habis ngapain aku?”
Justru kau yang mengapa-apakan diriku, dasar gadis aneh. Kutelan jawaban itu ke dalam kerongkongan. Memilih untuk bersabar.
“Dengar. Aku nggak kenal kamu siapa. Kamu tiba-tiba datang ke aku dan nggak sadarkan diri semalam di club.”
“Terus seenak jidat kamu bawa aku ke sini? Ini di mana?!” Suaranya menggelegar hingga aku harus menempelkan telunjukku di bibirnya, menyuruhnya memelankan suara. Ia menghempaskan telunjukku dengan kasar.
Tahu begini kutinggalkan saja ia di sana, terserah akan diapakan oleh para lelaki hidung belang di tempat itu.
Kudesahkan napas berat, “Kamu nggak ingat apa pun?” ia mengernyit mencoba mengingat-ingat apa yang terjadi di club malam itu. Melihatnya mengaduk-aduk otak tanpa titik temu, kubuka suara menyuruhnya berhenti saja. “Udah deh. Nggak usah diingat juga. Gak penting. Sekarang aku tanya, rumahmu di mana? Aku bisa antar. Sidoarjo? Surabaya? Pandaan? Trawas? Malang? Mana?”
Ia menggigit bibir bawahnya dan mengerutkan alisnya. “Jakarta.”
“Hah?!”
“Iya,” gumamnya lirih.
“Ada keluarga di sini?”
“Nggak ada.”
“Sama sekali?”
“Sama sekali.”
“Lah?”
Ia menatapku dengan mata cokelat cerahnya. Menolehkan kepala, matanya bergerak liar seperti mencari sesuatu. Ia melongokkan kepala, berputar, mengintip dari balik bahuku dengan gerakan gusar. Kenapa lagi ia?
“Koper aku mana?!”
“Etdah, koper apaan?”
“Koperku mana, Mas? Nggak kamu ambil?”
Merasa kesal, aku beranjak berdiri. Kuurungkan niatku memaki-maki anak orang pagi-pagi begini. “Mana aku tahu ya, Mbak. Masih untung kubawa pulang. Mau digrepe laki-laki hidung belang di sana?” Ia menatapku seraya mendesis. Ibu datang mengatakan bahwa sarapan sudah siap sebagai penengah dan mengakhiri perdebatan kami. Kutatap ia sekali lagi sebelum enyah dari hadapannya. “Makan sana.”
Sampai di meja makan, Ibu mencolek-colek pinggangku dan berbisik bertanya apa yang kami perdebatkan tadi. Hanya kugelengkan kepala sebagai respons padanya. Tak lama, gadis itu keluar dari kamarku dengan langkah perlahan. Kutuang air putih di dalam gelas dan menyodorkan padanya. “Minum dulu. Biar sakit kepalamu ilang.”
“Makasih.”
Baguslah ia tahu caranya berterima kasih. Selama sarapan, kukira hanya akan ada keheningan. Tetapi justru sebaliknya, suara Ibu dan Kumala memenuhi meja ini.
“Nama Kakak siapa? Orang mana? Sejak kapan pacaran sama Mas Radi?”
Gadis itu menatapku kebingungan, seolah-olah menyuruhku untuk menjawab pertanyaan adikku. Mengabaikan ia, kulanjutkan sarapanku dan membuatnya memberengut kesal.
“Benar kamu pacarnya Radi, Nduk?”
Gadis itu menggeleng cepat. “Bukan, Tante. Maafkan saya karena merepotkan anak Tante.”
“Iya. Ngerepotin banget,” sambarku dan langsung disambut cubitan Ibu di pahaku. “Aduh, Bu! Sakit.”
“Oh ya. Nama kamu siapa?”
Di tempatku duduk, kupasang telinga menunggunya menjawab. Karena tak ada jawaban, kuangkat kepala dan menatap wajahnya yang diliputi kegelisahan. Gadis ini benar-benar mudah ditebak. “Zeline,” katanya pelan.
“Zeline? Kenapa aku nggak asing sama nama itu ya? Wajah Kakak juga.” Sambar Kumala di kursinya. Aku hanya mencebikkan bibir, merasa sama sekali tidak familier perihal apa pun tentang gadis aneh ini. Adikku itu kembali menampakkan ekspresi berpikir, mencoba mengingat-ingat kiranya di mana ia pernah bertemu atau bahkan melihatnya. Detik berikutnya, ia terpekik seraya membekap bibir. “Masa sih? Kakak ini… Zeline Arabella yang itu? Pemain film itu?”
Gadis yang menyebutkan namanya sebagai Zeline itu meringis kecil. “Jangan bilang siapa-siapa ya.”
Di sampingku, Ibu menampakkan ekspresi bingung sama sepertiku. Mungkin lantaran kami berdua tidak mengikuti artis-artis lokal yang terlalu banyak sensasi. Sementara itu, Kumala kembali mengoceh.
“Waaah, keren! Aslinya jauh lebih cantik ya.” Ia menepuk pahaku dan tertawa. “Masa Mas Radi nggak tahu? Dia Zeline Arabella model dan pemain film itu lho, Mas. Nggak nyangka orangnya bakal ada di sini. Kakak ada urusan bisnis di daerah sini? Atau mau main film baru?”
“Kumala, jangan membuat repot orang lain,” ujar Ibu memberi peringatan.
“Saya di sini bukan berlibur atau ada urusan bisnis. Saya meninggalkan rumah untuk sementara.”
Mendengar jawaban yang terlontar darinya, suasana berubah canggung. Kuinjak kaki Kumala di bawah meja lantaran menyebabkan suasana seperti ini.
“Gak apa,” suara Ibu memecah keheningan. “Kamu boleh tinggal di sini selama yang kamu mau. Dan ndak perlu formal ya. Panggil Ibu saja sudah cukup.” Gadis itu tersenyum manis madu, lantas mengangguk patuh.
Usai sarapan berakhir, aku beranjak pergi ke halaman belakang seraya memainkan ponsel. Dilanda penasaran, kuketikkan nama Zeline Arabella di kolom pencarian. Aku nyaris tersedak ludahku sendiri menyadari ocehan Kumala tadi ternyata bukan omong kosong. Ia, gadis asing yang kubawa pulang dalam keadaan mabuk itu, adalah seorang model yang baru terjun pula dalam dunia perfilman. Tapi, mengapa ia sampai di sini? Otakku memutar kembali percakapan di meja makan tadi. Ia kabur dari rumah? Tapi, mengapa?
“Heh, kamu.” Baru saja kupikirkan, suara orangnya terdengar di belakangku. Cepat-cepat kukunci layar ponsel yang menampakkan foto-fotonya di internet. Ia berjalan menghampiriku. “Makasih ya udah bawa aku ke sini. Seenggaknya aku nggak dikenali dan bikin media heboh.”
“Kenapa?” Suaraku menyambar mewakili otakku yang didera penasaran akut.
Ia menatapku sejenak, lantas melemparkan pandangan ke air tambak yang memantulkan cahaya matahari dan hamparan ilalang serta rumput-rumput panjang di seberang sana. “Nggak apa. Cuma sedikit masalah.” Ia terdiam beberapa detik sebelum kembali membuka suara, “Namamu Radi?”
“Hm.”
“Cuma Radi aja?”
Kutolehkan kepala dan mengerutkan alis sebagai respons. “Kamu intel ya?” sedangkan ia hanya tertawa renyah menanggapi pertanyaan sarkastisku. Kudesahkan napas sebelum menjawabnya. “Dewangga Fajar Pradipta.”
“Kenapa bukan Angga aja nickname kamu? Bagus loh.”
“Kenapa bukan Arab aja nickname kamu? Bagus tuh,” balasku membalikkan kalimatnya. Sekali lagi ia tertawa.
“Oh ya. Kemarin aku berlaku memalukan, nggak? Apa aku sempat muntah?”
Iya! Kamu menciumku secara tak sopan dan nyaris membuat jantungku jatuh ke lantai. Ingin kuteriakkan kalimat itu di depan mukanya seandainya aku tak memiliki kesabaran. “Kamu nggak ingat?”
“Enggak sih…” sedetik kemudian ia terpekik dengan matanya yang melotot ngeri. Nah, rupanya ia sudah mengingat semuanya. “Mampus.”


 valentina
valentina