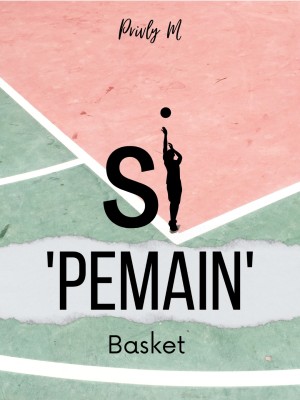Usai pemotretan, kubereskan isi tas tanganku di atas sofa. Di belakang, para kru membereskan berbagai kamera dan tripod. Kudengar dari salah satu kru, akan ada sesi pemotretan oleh bintang model catwalk sesuai jadwal untuk mengisi majalah fashion. Nah, beres sudah semua urusanku di sini. Waktunya untuk pulang dan bersantai. Hendak kulangkahkan kaki keluar, suara Joanna memanggil.
“Elin, ponselmu ketinggalan.” Ah, hampir saja kulupakan benda terpenting satu itu. Mengambil dari tangan Joanna, kuucapkan terima kasih dan berpamitan untuk pulang.
Suara ketukan sepatu hak merahku terdengar. Beberapa staf berpapasan denganku dan tak lupa untuk menyapa. Melewati lorong, kubuka sebuah pesan masuk dari Papa.
Sweety daddy: Kalau udah selesai pemotretan, jangan lupa mampir ke kantor ya, Sayang.
Tanpa membalas pesan itu, kukunci layar ponsel dan berjalan melewati pintu keluar, disambut hangat oleh dua satpam muda berbadan tegap. Terkadang aku berpikir semuda dan sebagus itu badan mereka, mengapa memilih untuk menjadi satpam daripada masuk ke taruna? Sampai kapan pun, aku tak akan mengerti alasan mereka. Padahal jika dari postur tubuh, dua satpam itu sudah memenuhi kriteria.
Di depan lobi utama, mobil hitamku sudah menunggu. Pak Jaka yang berdiri di depan kap, segera membukakan pintu mobil sambil tersenyum. “Padahal saya bisa sendiri.” Ujarku, namun ia hanya membalasnya dengan senyuman. Seakan mengatakan, ‘Sudah tugas saya, Nona.’
Pak Jaka adalah sopir pribadiku yang sering mendapatkan curhatan dan keluhan sampahku ketika diriku mulai lelah dengan pekerjaan. Meskipun hubungan kami sebatas majikan dan sopir, Pak Jaka selalu kuanggap sebagai ayah kedua. Beliau dengan tenang akan mendengarkan ceritaku dan tetap diam bila aku sedang tak ingin berbicara.
“Ke kantor Papa dulu, ya, Pak.”
“Oke, Nona.”
Begitulah. Untuk selanjutnya aku tetap diam, sesekali menatap luar jendela dan memandangi langit mendung tanpa hujan. Hanya mendung, tetapi kota tidak pernah mati dengan kesibukannya. Denting ponselku terdengar, kubuka layar kunci dan mendapati satu pesan dari salah satu produser film yang dua hari lalu datang ke rumah. Menawariku untuk memerankan tokoh utama dalam film terbarunya. Ia masih ngotot untuk membujukku mengambil perannya dan bersedia menandatangani kontrak. Karena beberapa alasan, aku juga sedang malas debut film terbaru.
Produser Fahlefi Alterio: Bagaimana, Zeline? Sudah kau putuskan? Peran ini akan sangat berpengaruh untukmu.
Mendesah kecil dan memutar bola mata, kuketikkan balasan padanya.
Reply: Akan kupikirkan lagi nanti.
Mengambil airpods dari dalam tas dan memasangnya di telinga, kumainkan beberapa lagu agar aku mengantuk barang sedikit saja. Kunaikkan volume sampai batas maksimalnya dan mengambil bantal di kursi belakang. Kuubah posisiku telentang, lantas kupejamkan mata dengan harapan bisa tertidur. Rasanya punggungku lega sekali bisa berbaring sejenak meski hanya di dalam mobil. Aku akan membuat lemon hangat ketika sampai di rumah nanti. Semoga saja aku tidak melupakannya.
Sengaja aku memilih tidur saja daripada melihat lalu-lalang kota yang setiap hari selalu sama. Tidak ada yang berubah. Maka kuputuskan untuk mencoba tertidur. Seiring melantunnya lagu yang kuputar, kubawa berbagai pikiran yang bernaung dalam otakku. Membawa tubuhku lebih santai lagi.
Aku berhasil menidurkan mata walaupun hanya tiga puluh menit selama perjalanan ke kantor Papa. Mataku terjaga ketika kurasakan mobil berhenti. Segera kulepaskan airpods dari telinga dan memasukkannya ke dalam tas berbarengan dengan Pak Jaka yang membukakan pintu untukku. Kuucapkan terima kasih sebelum berlalu memasuki lobi. Lagi-lagi disambut beberapa pegawai dan satpam yang berjaga.
Memasuki lift, kutekan tombol lantai lima. Semua pekerja Papa berpakaian secara formal. Ada banyak pria mapan di sini jika aku menginginkannya. Namun, aku tidak mudah jatuh cinta dan masih ingin menghabiskan sisa-sisa kebebasanku sebelum semuanya direnggut waktu. Sampai di lantai yang tertuju, pintu lift terbuka. Segera kulangkahkan kaki menuju ruang presiden direktur. Ada dua pegawai yang duduk di kursi depan meja Papa. Melihatku masuk, Papa segera memberi kode agar mereka keluar. Mereka mengangguk dan menyapaku sejenak sebelum melangkahkan kaki keluar.
Menghambur memeluk Papa, ia memberiku kecupan singkat pada dahi. “Gimana pemotretannya? Lancar?” tanyanya sambil menggiringku duduk di sofa cokelat ruangannya. Ada banyak koran dan majalah bisnis di atas mejanya.
“Biasa aja, Pa. Bosen.”
Ia tertawa. Tawa yang sama setiap kali mendengarku berkomentar tentang dunia entertainment. “Mau apa? Kopi?”
“Nggak usah. Aku di sini bentar kok. Habis ini pulang. Ngantuk soalnya.”
“Oh iya, Elin,” Papa berjalan menuju meja kerjanya dan mengambil sesuatu, lantas menyerahkannya padaku, “kolega Papa kasih undangan ini. Karena Kenzo masih di Jerman, jadi kamu yang hadir ya. Mama juga ikut kok.”
Kutatap undangan pesta ulang tahun pernikahan dari salah satu teman bisnis Papa. Undangannya ada di bagian dalam sejenis amplop kaku cokelat dengan ukiran yang entah apa namanya. Menatapnya sekilas, kuletakkan kembali di atas meja dan mengangguk pada Papa. Ia tersenyum melihatnya.
“Bagus,” gumamnya. “Kenzo udah lulus skripsi. Besok dia terbang ke sini.”
Kukernyitkan hidung mendengar kalimat Papa, “Kok tumben nggak bilang aku?” Kenzo? Cecunguk itu tidak bilang-bilang padaku? Biasanya ia paling sering mengabariku tentang kesehariannya. Bahkan aku yang pertama. Kalau ia pulang nanti, akan kusiapkan satu bogeman khusus untuknya.
Papa tertawa melihat responsku. Menepuk-nepuk kepalaku, ia berkata, “Udah, pulang sana. Mamamu nunggu. Papa juga masih banyak kerjaan numpuk.”
Mendesah, kubereskan tas dan beranjak berdiri. Memeluk Papa dan berpamitan untuk kembali pulang.
*
Memasuki halaman depan rumah, baru kusadari adanya mobil putih yang familier di mataku. Segera kulangkahkan kaki memasuki rumah dan mendapati Marcell, model majalah fashion yang cukup digemari para wanita. Seingatku ia berada di London untuk pemotretan dan tak menyangka ia akan kembali secepat ini.
Menyadari keberadaanku, ia berdiri dan menyambutku dengan pelukan. Seperti biasa pula ia mencium pipiku. Walaupun kami termasuk teman yang memiliki hubungan dekat, aku tetap merasa risih bila ia melakukannya padaku. Melepaskan pelukan, kuposisikan diri di sampingnya. Ia menatapku dengan mata cokelat cerahnya yang sangat menawan. Ayah Marcell adalah orang Turki. Tidak heran bila wanita-wanita di luar sana rela bertekuk lutut padanya.
“Kapan balik? Cepet amat.”
“Iya lah. Ngapain lama-lama di London.” Ia tersenyum sambil melingkarkan lengannya pada bahuku, “Tell me, how’s your days tanpa aku satu minggu terakhir.”
“Biasa aja.”
“Wah, gak adil nih. Padahal aku kepikiran ngajak kamu jalan-jalan ke sana berdua.” Ia mulai membeo.
Kurebahkan tubuh dengan kaki di atas pangkuan Marcell sambil meregangkan badan, “Udah pernah, Marcell. Yang belum pernah itu ke daerah kutub. Pengen ketemu beruang dan bawa pulang satu.”
Ia tertawa mendengar kalimatku, lantas mulai memijit kakiku. Ia teman yang pengertian. Tanpa bertanya apa pun, ia akan bersedia melakukannya untukku. Tapi terkadang sifatnya yang perfeksionis membuatku kewalahan. Sering bila ia menemaniku belanja, ia akan mengomeli penjaga tokonya apabila tidak melayaniku dengan baik. Seleranya pada wanita salah satunya juga, banyak sekali model wanita dan artis-artis lokal maupun berdarah campuran. Bahkan ada beberapa yang secara terang-terangan mencoba mencuri cintanya. Namun Marcell selalu bersikap masa bodoh. Apabila kutanyai, jawabannya hanyalah, “Males. Gak ada yang pas di hati.”
“Satu minggu di London udah nemu bule cantik buat dijadiin bini?” aku angkat bicara menanyainya.
“Boro-boro keliling nyari cewek, tiap hari direkturnya bacot nyuruh tepat waktu ke studio. Sisanya aku buat tidur di hotel karena capek. Mana ada waktu buat enak-enakan.”
“Kamu mau jadi jaka tua ya? Harusnya model kayak dirimu begini udah ada calon pasangan hidup.”
Marcell menatapku lama, lantas, “Jangan tanya aku. Kamu sendiri juga begitu.”
Kudesahkan napas berat, menatap tepat pada manik mata Marcell. “Ya kali kamu sebenernya playboy, kayak artis-artis yang hobi bikin sensasi lewat isu pacaran. Tapi nggak lama putus, cari baru lagi. Lumayan tuh namamu makin melambung.”
“Sialan.” Kusemburkan tawa melihat ekspresinya ketika mengumpat. “Aku nggak begitu, Babe. Sembarangan aja. Yang ada malah image-ku di mata fans rusak dong. Bikin sensasi itu punya boomerang sendiri buat orang-orang seperti kita yang setiap detik hidupnya selalu terekspos.”
Beranjak duduk, kutepuk-tepuk pelan sebelah pipi Marcell, “Bagus deh kalau kamu masih punya akal sehat.”
Mama muncul bersama Ika pembantu rumah tangga kami dengan nampan berisi tiga gelas jus apel beserta camilan. Marcell memang pecinta jus apel sejak kecil. Mama dan aku sudah hafal sekali kebiasaannya yang satu itu, sehingga setiap kali kemari Mama akan menyuruh Ika membuatkan menu minuman kesukaan Marcell.
“Sudah dikabari Papa, kan, Sayang?” tanya Mama yang ikut duduk di atas sofa.
“Sudah, Ma.” Kulirik jam di pergelangan tanganku. Masih ada waktu beberapa jam sebelum siap-siap datang ke pesta tersebut. Sebenarnya aku malas bila dihadapkan dengan para kaum borjuis dan kapitalis dalam acara-acara sampah seperti itu. Acara dengan ajang pamer kekayaan berdalih jalinan persaudaraan. Bertahun-tahun hidup dalam lingkungan seperti itu membuatku muak. Asal kau tahu, pejabat dan para pebisnis itu memiliki banyak topeng di balik punggungnya. Mereka adalah predator yang memangsa uang rakyat. Namun, aku tetap memilih bertahan. Bagaimanapun juga, takdir memilih kehidupan macam ini untuk diriku. Hanya tinggal bagaimana aku menjalaninya dan lolos setiap harinya.
“Apaan, Tan?” Marcell yang tidak mengerti bertanya dengan kerutan di dahinya.
“Kolega Papanya Zeline mengadakan pesta ulang tahun pernikahan. Kebetulan kita diundang.”
“Hm. Kehidupan para pebisnis dan selebriti itu nggak jauh beda ya. Pada dasarnya sama aja.”
Mendengar kalimat yang mewakili isi pikiranku itu, aku berusaha agar tidak memutar bola mata dan berteriak bullshit. Kupanggil Ika yang kemudian muncul, mengatakan padanya agar menyiapkan air mawar dan susu di dalam bathtub. Usai itu, ada pesan masuk dari manajerku, Anastasia Roxel, yang sudah satu minggu ini meminta cuti liburan bersama suami dan anaknya yang baru berumur empat tahun. Aku akan membebaskan mereka yang bekerja denganku. Meski terikat kontrak, aku tak akan mengekang mereka, maka berlaku sebaliknya pula. Karena bagiku, hak tertinggi menjadi manusia adalah kebebasan.
Anastasia: Hi, durl. Besok aku udah sampai di Indonesia. Gimana tawaran film dari si ganteng Alterio?
Ganteng ia bilang? Sudah gila rupanya.
Reply: Aku gantungin. Tapi aku kepikiran buat nolak. Ogah banget dikejar-kejar macam buron.
Anastasia: Kok ditolak? Doooon’t do thaaat, ok?? Zeline, film ini bakal melambungkan namamu. Pikirkan lagi baik-baik.
Reply: Akan kupikirkan lagi. Besok kita atur jadwal ketemu Fahlefi untuk bahas isi naskah dan peran yang dia tawarkan.
Setelah itu, tidak ada pesan balasan dari Anastasia. Wanita muda itu termasuk wanita perfeksionis kesekian yang kukenal dalam lingkaranku. Anastasia tidak akan pernah mau membeli pakaian bila tidak langsung ke mall atau ke produsennya sendiri. Ia mencintai uang, sama sepertiku. Namun Anastasia terlalu mendewakan kertas yang kita sebut sebagai uang. Menurut Anastasia, uang adalah segalanya. Bahkan dalam kehidupan pernikahannya, ia mengaku padaku bila masih belum mengerti apa itu cinta. Aku bisa memahaminya lantaran pernikahannya terjadi karena alasan perjodohan. Lagi-lagi alasan klise yang membuatku muak.
Ika datang kembali ke ruang tamu untuk mengatakan padaku bahwa bak mandi telah siap. Maka, aku beranjak berdiri dan berpamitan pada Mama serta Marcell untuk menyiapkan diri. Namun, Marcell memilih pamit pulang agar Mama dapat bersiap-siap. Ia mencium pipiku dan Mama sebelum benar-benar hilang di balik pintu utama.
Menaiki anak-anak tangga, kutenteng sepatu hak di tangan. Rasanya hari ini aku butuh minuman saja. Terlalu melelahkan bagiku, namun aku harus melakukannya karena semua ini adalah bagian dari pekerjaanku. Tetapi aku tidak perlu resah, toh, nanti juga akan ada banyak minuman yang disediakan pemilik pesta. Inilah salah satu alasanku bersedia menghadirinya meskipun enggan.
Menaruh tas dan sepatu secara serampangan, langkahku terseok-seok menuju lemari yang khusus kuisi gaun-gaun pesta. Kutarik gaun apa pun yang terjamah tanganku. Setelah itu, lekas kupandangi gaun silver dengan bagian memanjang di belakangnya. Tidak berlengan, hanya bagian yang menutupi kedua bahu di masing-masing sisi.
Bibirku mencebik, “Hm. Not bad.”
Masuk ke kamar mandi, kulepaskan seluruh kain dan perhiasan yang melekat di tubuhku. Sebelum memasukkan diri ke dalam bathtub, kuputar lagu instrumen yang menenangkan pikiran. Semerbak aroma mawar memenuhi indra penciuman. Kupejamkan mata meresapi ketenangan ini untuk sementara. Untuk beberapa waktu, tidak ada sesuatu yang mampir di kepalaku. Segalanya benar-benar malas hinggap untuk kupusingkan. Terlalu banyak hal dan persoalan.
Setelah beberapa menit, kuputuskan untuk mengangkat diri dari dalam bak mandi. Aku melangkah keluar kamar mandi dengan handuk melilit. Lantas duduk di depan meja rias untuk memoleskan berbagai bahan kosmetik di mukaku. Aku adalah wanita yang lebih memilih berdandan lebih dulu daripada memakai gaun. Alasannya sederhana, agar tak mudah merasa kegerahan padahal pendingin ruanganku tak pernah mati. Entahlah, kebiasaan memang sulit dihilangkan.
Setelah berkutat dengan riasan, kupakai gaun pesta silverku yang kugantung di gagang pintu lemari. Tak lama, Mama datang dengan penampilan yang sempurna dan siap untuk bersinar di depan para tamu kolega lainnya. Gaunnya berwarna krem panjang dengan lengan di satu sisinya. Ia membantu menarik ritsleting gaunku. Lantas, ia menyuruhku duduk dan menata rambutku.
“Papa udah pulang, Ma?” tanyaku sembari memilih perhiasan mana yang akan kupakai.
“Udah. Ada di bawah tuh. Udah siap orangnya.” Melihat ke kaca, aku dapat menebak model rambut apa yang Mama buatkan untukku. Ia memilih bentuk low updo untuk rambutku agar tidak merasa kegerahan nantinya. Lantas, ia menyematkan hiasan kecil berbentuk kristal di bagian tengah lipatan. “Done. Ah, cantik sekali. Mama tunggu di bawah ya.” Kuanggukkan kepala sebagai jawaban untuknya.
Membuka lemari sepatu, kukeluarkan sepatu hak dengan warna senada. Sebelum melangkah keluar kamar, kugantung tali selempang tasku di atas bahu. Lengkap sudah, malam ini tubuhku serba warna perak.
Menuruni anak-anak tangga, dapat kulihat Papa dan Mama yang berbincang sebelum menengadah ke arahku.
“Cantik sekali permataku. Nanti, semua tamu akan memandangmu.” Ujar Papa sebagai kalimat pembuka. Kubalas pujian itu dengan senyuman paksa yang kubuat-buat.
***
Ada sebuah kalimat yang mengatakan bahwa dalam berseni, kedamaian hati adalah segalanya. Maka, aku membenarkan kalimat itu. Dua jam terakhir kuhabiskan dengan palet yang telah penuh oleh cat. Di hadapanku kini adalah kanvas ketiga yang kutorehkan warna. Pakaianku kotor seperti biasa, dipenuhi warna di mana-mana. Sengaja kupilih halaman belakang yang sunyi untuk tempat melukisku saat ini.
Meski aku tidak memiliki galeri, sebagian lukisanku kujajar rapi di kamar. Apabila tidak lagi ada tempat, maka kutitipkan lukisan-lukisan itu ke kawanku di desa barat, sekalian ia bantu jualkan pada kenalan-kenalannya. Dari mana aku mendapatkan uang untuk membeli kanvas? Tentu saja dari honorarium tulisan-tulisanku. Di usia ini, aku hidup dari dua kemampuanku. Meski ingin sekali aku merantau untuk mencari pekerjaan, rasa trauma selalu berhasil menaklukkan diriku. Sialan sekali memang.
“Mas. Ada Mas Dirja tuh di ruang tamu.” Nah, baru saja dibicarakan, suara Kumala terdengar mengabarkan bahwa orangnya ada di rumah.
Kutolehkan kepala sebentar dengan alis terangkat sebelah. “Suruh ke sini aja, La. Mas lagi males berdiri ini.” Tanpa basa-basi, Kumala beranjak ke ruang tamu untuk membiarkan Dirja kemari. Biasanya, bila Dirja sudah kemari, ia akan mengajakku keluar ke berbagai tempat. Terkadang pula tidak ada alasan penting, hanya tidak ada pekerjaan saja di rumah.
Suara gesekan sandal terdengar. Tanpa menoleh pun aku tahu bahwa itu Dirja.
“Nggak capek apa ngelukis terus?” ia bertanya sambil mengepulkan asap rokoknya ke udara.
“Kalau udah sibuk sama warna, punggung ini gak bakal capek. Tahu sendiri tabiatku gimana.” Kusunggingkan senyum tipis sebelum menoleh untuk melihat Dirja dengan kaus kesukaannya yang bertuliskan kata mutiara milik Pramoedya. “Ada apa? Ngajak main?”
“Loh, kalau mau ya ayo. Ke hawa dingin.” Katanya disusul cengiran mesum seperti biasa.
Kudecakkan lidah sekali, lantas kembali menekuri lukisanku yang hampir jadi. “Halah Dir, Dir. Hobi kok ke hawa dingin. Nyewa cewek aja gak ada duit.”
Mendengar itu, logat Jawanya keluar memaki diriku, “Heh, heh, jancuk. Pikiranmu itu yang kotor ya. Siapa yang mau nyewa. Nggak ada salahnya kan menikmati indahnya ciptaan Tuhan di daerah pegunungan begitu.”
“Bagus banget kalau berdalih.”
Dirja terkekeh-kekeh, lantas melumat puntung rokok di bawah sandalnya. “Mbuh, Rad. Ngomong karo kowe iki kalah tok aku.[1]”
Aku hanya bisa tertawa mendengar gerutuannya dalam bahasa Jawa. Selesai dengan lukisanku, kuperhatikan hasilnya sambil berdecak kagum, lantas segera kubereskan peralatan melukisku ke dalam sementara Dirja masih di halaman belakang sambil bermain smartphone. Usai merapikan kanvas, palet, dan segala peralatan lainnya, kuhampiri Dirja yang menolehkan kepala mendengarku datang.
“Eh, ada yang mau beli lukisanmu nih,” katanya.
“Yang mana?”
Dirja menunjukkan foto salah satu lukisanku dengan tema melankolis. Seorang gadis berkebaya lama dengan kepang rambut dua yang berjalan di tengah sawah. Jangan bertanya-tanya ia siapa, karena pada dasarnya sebagian lukisanku adalah murni dari alam imajinasiku sendiri. Meskipun lahir dari imajinasi, aku sempat mengagumi kecantikan paras gadis fiksi lukisanku sendiri waktu itu. Oleh karena keindahannya yang unik, lukisan itu kubandrol dengan harga tinggi dibanding lukisan-lukisan yang lainnya.
“Dia nggak nawar sama sekali, Radi. Rejekimu nih. Kita paketin apa COD aja?” Dirja terlihat sangat antusias. Hendak kubuka suara untuk menjawabnya, ia memutuskan secara sepihak, “COD aja deh ya. Pulangnya kita ke bar Surabaya. Traktir lukisan termahalmu laku bro.”
Bocah tengik. Namun, kuiyakan saja permintaannya itu. Selain sahabat, Dirja sudah seperti saudara bagiku. Kami tumbuh bersama di desa barat selama enam tahun. Bahkan meski masa-masa nomadenku dahulu, aku dan Dirja tak pernah kehilangan kontak. Sesibuk apa pun, kami selalu menyempatkan dan menyisihkan waktu untuk bertemu.
Kutepuk pundaknya bersahabat, “Tunggu di ruang tamu sana. Aku mau mandi dulu.”
*
Kami segera berangkat setelah aku membersihkan diri dan berpamitan pada Ibu. Dengan motor miliknya, kedua tangan Dirja siap di atas setir. Sedangkan aku membawa kardus tempatku mengemas lukisan pesanan orang dari Surabaya tersebut. Karena Dirja menyanggupi cash on delivery, pembeli memberikan sebuah alamat pada kami. Dari namanya, aku menduga bahwa tempat itu adalah coffee bar yang terletak di perbatasan antara Sidoarjo dan Surabaya.
Jalan raya tidak semacet biasanya karena musim hujan, mungkin orang-orang memilih berdiam di dalam rumah daripada harus hujan-hujanan dan berakhir jatuh sakit. Melihat jalanan lengang, Dirja mengebut dan berhasil membuatku memaki-maki dirinya. Bagaimana tidak? Aku sedang membawa pesanan orang!
“Ojo ngebut, jancuk!” Kukeraskan suara dan membuatnya tertawa. Lantas ia lajukan motornya dengan kecepatan sedang. Tidak ada obrolan dalam perjalanan kami hingga di tempat tujuan.
Benar seperti dugaanku, alamat yang diberikan pembeli itu adalah sebuah kafe. Dirja berhenti di depan kafe yang berdindingkan kaca. Di depan kaca toko, tertulis nama dari kafe tersebut: Jagad Kopi. Tak lama, muncul seorang pemuda bertubuh jangkung dengan kacamata yang bertengger di pangkal hidungnya. Bentuk lingkaran hitam di bawah matanya tidak bisa disembunyikan meskipun ia mengenakan kacamata. Sekilas aku mengira tidak ada hal menarik darinya. Namun, ketika ia mendekati kami, dapat kulihat cengiran lebarnya menyimpan kejahilan. Matanya berkilat jenaka.
“Maaf ya udah bikin nunggu. Sesuai harga, ya?” ia mengambil beberapa lembar uang seratus dan menyerahkannya pada Dirja, lantas menerima pesanannya. “Mau masuk dulu?”
Dirja menoleh padaku sambil menunjukkan seringainya. Aku berusaha untuk tidak memutar bola mata. “Boleh, Mas, boleh.” Turun dari motor, ia melepas jaket dan helmnya sebelum masuk ke dalam kafe. Usai melakukan hal yang sama, kususul Dirja yang menyerbu masuk terlebih dahulu.
Baru saja masuk ke dalam, aroma kopi yang menguar di udara merangsek masuk ke indra penciuman. Kuedarkan pandangan ke seantero tempat. Sama seperti kafe-kafe lainnya, suasana di sini temaram. Ada beberapa lampu dinding yang menjadi penerangan di dalam. Pemuda itu menggiring kami ke meja di mana sudah terdapat satu cangkir kopi dan vape di atasnya. Sementara ia berpamitan untuk meletakkan lukisan itu ke dalam. Dari caranya berbicara, aku menduga bahwa ia memiliki hubungan dengan kafe ini. Tak lama, ia kembali sambil membawa buku menu.
“Pesan dulu.”
Dirja memesan espresso sedangkan aku cukup dengan kopi hitam biasa karena aku tidak tahan dengan pahitnya espresso. Usai memesan, pemuda itu kembali ke meja bar. Ia terlihat mengatakan beberapa kata sebelum berjalan lagi ke meja kami.
“Nah, kita belum kenalan ya? Panggil aku Pras. Kalian?”
Dirja yang membuka suara, “Aku Dirja. Dan dia temenku yang pendiam, Radi.”
Pras mengangguk-anggukkan kepalanya. “Makasih ya udah diantar sampai sini. Karena kebetulan aku lagi nggak di Surabaya, sekalian aja aku suruh kalian ke sini. Kalau boleh tahu, siapa pelukisnya?” Dirja di samping serta-merta menunjuk padaku. Senyuman lebar Pras tersungging di bibir. “Aku suka, loh, lukisan-lukisan kamu. Apalagi yang aku pesan tadi. Karena kafeku temanya harus ada unsur budayanya, aku pesan aja satu.”
“Kafemu?” akhirnya aku angkat bicara setelah lama terdiam.
“Iya. Ayah yang ngasih aku cabang kafenya yang ada di sini. Padahal aku juga lagi sibuk kuliah.”
Ekor mataku menangkap beberapa pemuda yang tengah memasang lukisan yang tadi kami antar untuk dipajang di dinding. Sekarang aku mengerti mengapa ia terlihat mengenal para pelayan-pelayan tadi. Ternyata ia pemiliknya.
“Sering main ke Sidoarjo juga?” Dirja membuka percakapan.
“Ah, Sidoarjo nggak seru. Nggak ada bar kayak di Surabaya. Monoton. Kalau ke daerah Prigen sama Trawas sering.”
Tawa Dirja menggelegak di samping. Aku mengerti ke mana arah pembicaraan mereka. “Kapan-kapan kita ke sana bareng.”
“Kenapa nggak sekarang?”
“Hari ini kayaknya nggak bisa. Aku sama Radi mau nyari bar di Surabaya. Mau ikut sekalian?”
Pras mengangkat kedua alisnya, “Boleh. Aku tahu bar rekomendasi terbaik di Surabaya. Dijamin betah.”
Tak lama, seorang pelayan datang sambil membawa nampan dengan pesanan kami di atasnya. Ditambah roti yang mengembang dan menguarkan aroma harum, serta kentang goreng dan satu porsi penuh berisi sosis bertopingkan mozzarella. Siapa lagi yang memesan kalau bukan Pras.
“Kuliahmu semester berapa, Pras?” kutanya ia sekadar mengakrabkan diri.
“Ah, aku? Aku mahasiswa semester lima jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia.”
“Wah, anak sastra.” Dirja menimpali. “Nggak kayak kita. Pengangguran sejati. Ha ha ha.”
“Pengen kuliah pun nggak ada biaya. Kerja juga kayaknya mustahil.” Kulirik keadaan di luar yang gelap dikarenakan mendung. Pohon-pohon bergerak tertiup angin kencang. Sebentar lagi akan turun hujan. Kuraih cangkir kopi di depanku dan menyeruputnya.
“Kenapa mustahil?”
“Trauma. Ayahku pernah merantau ke Jakarta dan pulang dengan bekas tembakan di kepala. Sejak saat itu, bayangan untuk merantau di tempat orang terasa macam mimpi buruk yang bakal jadi nyata. Jangankan merantau, kerja di sekitar sini atau di Surabaya aja aku nggak mau. Karena aku sendiri saksi betapa sulitnya dunia kerja yang dialami Ayah selama bertahun-tahun. Aku mikir, mungkin dalam dunia bisnis, iblis berwajah manusia selalu berkeliaran.” Kucengkeram cangkir di tanganku, terlintas kembali bagaimana bekas luka tembakan itu di kepala Ayah.
“Dunia bisnis memang kayak begitu, Di. Orang-orang berduit bakal dengan mudah menyingkirkanmu kalau kamu berlaku macam lalat pengganggu. Sorry to remind you.”
“Halah, nggak apa. Mau dilupain kayak apa pun, ingatan itu nggak bakal hilang. Kecuali kalau aku amnesia.”
Kekehan Pras terdengar. “Terus, kamu nggak mau gitu cari tahu apa yang sebenarnya terjadi sama Ayahmu sampai mati tertembak?”
“Ayahku bunuh diri.”
Seketika suasana mendadak hening. Namun Pras kembali bersuara dengan kerutan di dahinya. “Bunuh diri? Aku pikir, itu mustahil. Apa alasan dia dengan gegabahnya bunuh diri?”
Kukedipkan mata menatap Pras. Tertegun dengan pertanyaannya. Benar, mengapa aku tidak pernah memikirkannya? Dari pekerjaan apa yang Ayah lakukan saat itu, hingga apa alasan di balik kematiannya—bunuh diri—yang masih misterius. Tenggelam dalam kesedihan berkepanjangan, aku sampai-sampai tak pernah berpikir segala sesuatu yang mungkin disembunyikan dari riwayat kematiannya, malah menyalahkan diri sendiri.
“Tapi, mana mungkin ada caranya?” suaraku mirip desing peluru yang dimuntahkan pada siang hari.
Pras bergerak memperbaiki posisi duduknya, menusuk kentang goreng dengan garpu. “Kalau ada teka-teki, selalu ada jawabannya. Meskipun caranya harus masuk ke dalam lubang tikus terlebih dahulu.”
***
Kutinggalkan Mama dan Papa yang sibuk dengan kolega-koleganya. Sedangkan aku menghampiri meja panjang dengan cangkir-cangkir kurus berisi white wine yang ditumpuk. Di sampingnya ada chocolate fondue fountain yang menggoda setiap mata agar segera menjamahnya. Tetapi aku lebih memilih untuk menyambar satu white wine yang lebih menggoda imanku. Aku menghabiskannya dalam sekali tenggakan, lantas merasakan panas yang menyemut di tenggorokan. Tak lama, seorang pelayan dengan baki berisi botol anggur merah melimbai mendekat. Kuhentikan ia dan mengambil satu gelas, lantas mengisinya setengah penuh.
Kuamati satu-satu para tamu, terutama wanita-wanita yang berlomba-lomba untuk tampil glamor. Hendak bibirku bersinggungan dengan pinggiran gelas, suara seseorang memanggil namaku.
“Zeline ya?” Menolehkan kepala, keningku praktis mengerut lantaran tidak merasa pernah mengenal pemuda berjas dengan tampang-tampang yang aku yakin mampu menaklukkan sepuluh wanita mata duitan sekaligus. Menyadari wajahku yang penuh tanda tanya, ia terkekeh-kekeh. “Ternyata benar. Aku Kevin. Kevin Sanjaya, anak pertama dari presdir Jaya Group.”
Oh, Jaya Group. Salah satu perusahaan ternama di negara ini.
“Kamu kenal aku?”
Kevin kembali terkekeh-kekeh, memasukkan tangannya pada saku. “Ya iya lah. Nama kamu itu udah melambung, Zeline. Putri dari pebisnis pula. Parasmu juga masuk ke daftar salah satu model menawan di sini. Aku yakin kamu tahu itu.”
Kepalaku mulai ringan. Mendengar ocehan Kevin, praktis kuputar bola mata. Namun aku yakin ia tak melihatku. Karena tatapan kami sama-sama terpaku pada jubelan orang-orang yang memadati aula. Kulempar pandangan pada Papa dan Mama yang masih tertawa bersama kawan-kawan bisnisnya. Seandainya di sini ada Kenzo, suasana tak akan terasa membosankan.
“Kamu ke sini sama orang tuamu juga?” akhirnya kulempar pertanyaan padanya setelah lama terdiam.
Tangannya yang menggenggam gelas berkaki berisi anggur setengah menunjuk tepat pada tempat di mana terdapat orang tuaku di sana. “Yang pakai gaun hijau, itu Mamaku. Di sampingnya, Papaku.”
Praktis aku berjengit kaget. Memang, selama ini aku hanya mendengar perihal nama perusahaannya tanpa mencari tahu tentang anggota keluarga Jaya Group. Seperti manusia kurang pekerjaan saja mencari tahu tentang kehidupan mereka.
Bersamaan dengan telunjuknya yang menunjuk pada mereka, detik berikutnya wanita yang ia sebut sebagai Mama menolehkan kepala dan mengatakan sesuatu kepada kawan-kawannya. Lantas mereka semua serentak menoleh pada kami, tak terkecuali Mama dan Papa. Ibunya Kevin menunjuk pada kami berdua dan memberi kode agar menghampiri mereka. Kevin menoleh padaku sejenak sebelum melangkahkan kaki, kuikuti ia detik berikutnya.
“Wah, kayaknya kalian sudah saling mengenal ya?” ujar ibu Kevin ketika kami sampai dalam lingkaran mereka.
“Baru aja kok, Ma.”
Wanita itu tertawa, “Gak apa kok. Siapa tahu nanti kalian jadi cocok dan bisa menyatukan dua keluarga.”
Praktis aku tersedak anggur yang baru saja meluncur pada tenggorokanku. “Maaf ya, Tante. Tapi kalau boleh jujur, bukannya pernikahan atas dasar cinta lebih baik daripada perjodohan?”
“Zeline.” Suara Mama menginterupsi agar aku bisa menjaga sopan santun.
“Ah, gak akan ada perjodohan. Kalian bisa saling mengenal kalau mau.”
“Kalau saya gak minat?”
Gerombolan kawan-kawan kolega Papa menatapku canggung, sesekali beberapa dari mereka terkekeh-kekeh untuk mencairkan suasana yang sayangnya gagal dilakukan. Pada akhirnya Mama terkekeh pelan, “Ah, Zeline memang suka bercanda kok, Tania.”
“Aku serius, kok.” Mama mendelikkan matanya ke arahku. Merasa suasana berubah menyebalkan, aku membuka suara, “Permisi ya. Mau pulang lebih dulu.” Lantas kubalikkan badan dan melimbai pergi. Kutaruh gelas anggurku di sembarang meja sebelum benar-benar berlalu pergi melalui pintu utama. Sampai di lahan parkir, kukatakan kepada Pak Jaka untuk mengantarkanku pulang dan kembali lagi kemari untuk Papa dan Mama.
Kepalaku ringan dan mulai merasa pening. Aku tahu sikapku keterlaluan, namun aku memang membenci perjodohan. Ayolah, ini sudah zaman modern. Perjodohan adalah hal terkonyol kesekian yang pernah aku dengar di muka bumi ini. Kupijit pangkal hidungku, lantas mengembuskan napas berat.
[1] Gak tahu, Rad. Bicara sama kamu ini kalah terus aku.


 valentina
valentina