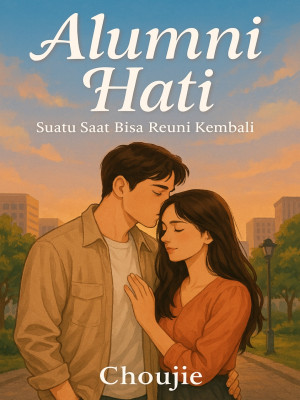Daun morning glory kering yang berjatuhan menyambut Damian. Sudut bibirnya terangkat membentuk bulan sabit ketika menyadari pengunjung yang cukup ramai. Sepertinya roti cokelat dan kopi Arabika itu menarik perhatian banyak pelanggan lama. Lelaki itu segera memasuki A Latte dan menuju ruangannya. Namun, alih-alih ke kantornya, ia naik ke balkon. Lantai atas hanya dipakai bila ada pertemuan atau pesanan dari pelanggan. Saat sepi, tempat ini cocok untuk menyendiri. Langkahnya menuju sebuah kursi rotan dengan bantal hati di atasnya. Dari tempatnya ia bisa sejenak menenangkan pikiran setelah pertemuannya dengan Laras. Wanita itu sepenuhnya berubah dan terlihat lebih bahagia. Damian tahu batasnya dan perlahan berjalan menjauhi Laras. Lelaki itu mengembuskan napas sebelum mengeluarkan laptop dari tas dan kembali bekerja.
Tak lama, perutnya berbunyi seiring matanya yang tertuju pada kotak makan di dekat tas. Ia segera mengambil dan membukanya. Harum mayonaise dan saus tomat yang berpadu dengan roti menyerbu hidungnya. Damian mengulas senyum sebelum menggigit setengah bagian roti. Padatnya isi roti dengan sayuran dan sosis sejenak membuatnya lupa dengan tugasnya.
"Lahap banget makannya, Pak. Lapar, ya?"
Damian berbalik menemui Dhisti yang menatapnya geli. Lelaki itu mengambil beberapa tisu dan mengelap mulutnya.
"Kamu ngapain di sini, Dhis? Kerjamu kan, di bawah," jawab Damian. Namun, ia berdecak teringat instruksinya untuk memberi sedikit pengarahan tentang kerjasama itu.
"Saya mau memastikan ruang meeting siap dipakai, Pak," ujar Dhisti sambil membenarkan apronnya.
Damian beranjak dari tempatnya dan menatap wanita itu dalam. Sejenak ia teringat penggalan kalimat Laras.
"Akhirnya kamu sadar walau terlambat, Dam. Aku harap ada seseorang yang memang pantas denganmu. Tapi jangan pernah memintaku, Dam," ujar Laras sebelum berjalan pergi.
Lambaian tangan Dhisti yang memanggil namanya mengembalikan Damian pada apa yang sedang ia jalani.
"Bapak kenapa? Ada yang aneh sama sandwichnya?"
Damian menggeleng pelan. Semilir angin menerbangkan daun morning glory yang belum dipangkas sekaligus rambut sebahu Dhisti. Wanita itu refleks merapikannya tapi kencangnya angin membuat pekerjaannya sia-sia. Damian yang menyadari itu berjalan mendekat dan menyisipkan sebagian rambut Dhisti ke belakang telinga.
Lelaki itu kadang tidak mengerti dengan hatinya yang selalu bersorak penuh kedamaian saat berada dekat Dhisti. Apa mungkin wanita itu adalah jawaban segala keresahannya?
Dhisti terdiam, merasakan kehangatan yang berpadu dengan rasa nyaman di hati.
Damian menggeleng pelan sebelum mengalihkan pandangan pada meja dan kursi yang berderet rapi. Penghalang itu kembali datang dan segera menggantikan rasa nyaman tadi.
"Dhis, bisa kan lain kali jangan datang tiba-tiba? Kamu itu ganggu privasi saya terus."
Wanita itu menggeleng pelan sebelum menghembuskan napas. Dhisti tidak tahu harus menjawab apa.
Damian menggeleng. "Oh, dan saya nggak ada maksud lain tadi. Makannya kamu ikat rambut yang bener. Udah, balik kerja lagi sana."
Damian berbalik dan berjalan menuju kantornya. Dhisti mendesah pelan, tak percaya dengan perilaku Damian. Wanita itu memutuskan untuk kembali bekerja. Rania yang baru datang dari teras memanggil Dhisti.
"Dhis, itu Pak Bos kenapa lagi? Abis dari balkon mukanya kayak tertekan banget. Atau lo abis ngobrol sama dia?"
Dhisti mengangkat bahunya. "Mungkin dia lagi ada masalah lain, Ran. Gue cuma kasih tahu soal ruang rapat."
Rania memperhatikan raut wajah sahabatnya. "Yakin? Apa mungkin Pak Bos mau nembak lo tapi masih ragu?"
Dhisti menaikkan alis tak pernah menduga Rania membahas hal ini. "Kadang gue nggak tahu harus bersikap gimana sama dia. Nanti dia baik. Terus, nggak lama jutek lagi seakan-akan gue abis ngelakuin kesalahan."
Rania mengangguk. "Lo nggak mau tanya dan bicara dari hati ke hati? Biar gimanapun, lo juga perlu kejelasan, kan?"
Dhisti terdiam mencerna perkataan sahabatnya. "Apa itu nggak papa, Ran? Maksudnya, hubungan kami lebih banyak jadi rekan kerja."
Rania menatap manik hitam Dhisti dalam mencari kebenaran dari perkataan sahabatnya. "Dhis, please. Lo udah melangkah sejauh ini sampai terlibat ke keluarganya. Pak Bos pasti ada rasa, Dhis. Bukannya dari awal lo berharap banget sama dia?"
Dhisti mendesah pelan menatap lukisan petani kopi di dinding. "Nggak sampai di tahap itu, Ran."
"Oke, tapi makin kemari Pak Bos itu hampir selalu mengitari lo. Masak lo nggak peka?" ujar Rania penuh semangat.
Wanita bermata almond itu terdiam lama, menyadari dirinya tidak mungkin lagi mengelak.
"Well, gue balik kerja dulu. Saran gue, lo harus jujur sama perasaan lo."
Dhisti menatap punggung sahabatnya yang menjauh. Kadang ada saatnya Dhisti harus belajar untuk mengenal dirinya lebih jauh lagi.
**
Dhisti memandang rumah minimalis itu sebelum mengetuk pintunya.
“Mama mau check up, jadi kamu tolong jagain Satria. Ada Bi Narti yang masak dan beres- beres rumah nanti,” ujar Damian pagi tadi di telepon.
Dhisti tidak bisa menolak permintaan lelaki itu, apalagi Nadia yang menyarankan Dhisti untuk merawat Satria.
"Sebentar," ujar Narti sambil berjalan tergopoh-gopoh. Narti mengulas senyum pada Dhisti sebelum menuntunnya ke kamar Satria. “Mbak di sini aja, ya. Kata Mas Dami, Mbak nggak boleh keluar kecuali ada yang penting.”
Dhisti mengembuskan napas menyadari ada proteksi terselubung dalam perkataan Damian. Namun, wanita itu tidak ingin menyelam lebih dalam dan jujur dengan perasaannya. Tak lama, Dhisti berjalan perlahan menuju tempat tidur Satria dan menatapnya lembut.
“Good boy, baik-baik ya, hari ini.”
Dhisti tidak menemui kesulitan saat menjaga keponakannya. Namun, tangisan Satria yang tiba-tiba membuat Dhisti terlonjak dari duduknya. Cepat, ia memeriksa Satria dan mendesah pelan. Hampir saja ia lupa memberi anak itu susu. Mengambil botol yang sudah ia isi, Dhisti mendekatkan ujung botol pada keponakannya. Wajah Satria terlihat lucu dengan pipi yang menggembung. Dhisti mengulas senyum lebar melihatnya.
“Mbak Dhisti cocok banget gendong Den Satria. Kalau ada Mas Dami, mirip seperti keluarga,” ujar Narti yang baru datang.
Dhisti menoleh pada wanita paruh baya yang mengenakan kain panjang itu. ”Bibi bisa aja.”
Narti mengulas senyum tipis. “Benar kata Ibu Nadia. Mbak dan Mas Dami pasti saling melengkapi.”
Dhisti hanya menggeleng, tidak ingin terlalu berharap pada ekspektasi orang lain. Walau ia menyembunyikan rasanya, ada harapan yang ia simpan untuk Damian. Gawai yang bergetar di sakunya mengalihkan perhatian. Dhisti meminta tolong pada Narti untuk mengambil alih Satria. Wanita bermata almond itu menggeser ikon telepon dan menyapa Damian.
“Satria nggak papa, kan? Mama dari tadi nanyain.”
Dhisti menoleh pada keponakannya sebelum menjawab pertanyaan lelaki itu. “Lagi minum susu, Pak. Semua aman, Pak. Tenang aja.”
“Ah, syukurlah. Dhis, kamu jangan sungkan buat melakukan hal lain. Dami kadang berlebihan. Kamu nggak perlu selalu ada di dekat Satria. Kan, ada Bi Narti juga,” ujar Nadia.
Dhisti mengulas senyum sambil mengusap dahinya. Perkataan Nadia sedikit menenangkan hatinya.
“Iya, Tan. Tante juga semangat ya, check up nya. Semoga Tante tetap sehat.”
Nadia mengangguk sebelum memberikan gawai pada anaknya.
“Kamu jangan senang dulu, Dhis. Nanti siang kamu harus bantuin Fino buat packing croissant. Oh, satu lagi. Saya baru cek blog A Latte. Kamu juga belum kirim apapun. Gimana sih, Dhis? Itu kan aspek penting juga buat menarik pelanggan.”
Dhisti menepuk keningnya, tersadar ia melupakan tanggung jawabnya. “Aduh, terima kasih udah diingatkan, Pak. Nanti saya kerjakan setelah Satria tidur.”
“Kamu memang selalu melamun, Dhis sampai hal kecil aja harus sering dikasih tahu,” balas Damian ketus. Namun, sudut hatinya bersorak tatkala mendengar suara Dhisti.
Wanita itumemajukan bibir mendengar pernyataan Damian yang membuatnya kesal. Lelaki itu sedang tidak bisa dibantah. Namun, Dhisti bisa merasakan Damian sebenarnya memberi perhatian padanya. Mengetahui hal itu, ia tersenyum simpul dan berharap ada jalan buat membahas perasaan mereka yang sesungguhnya.
**


 yulilavender
yulilavender