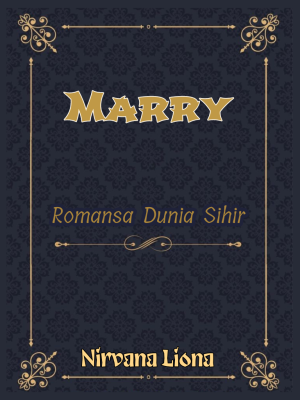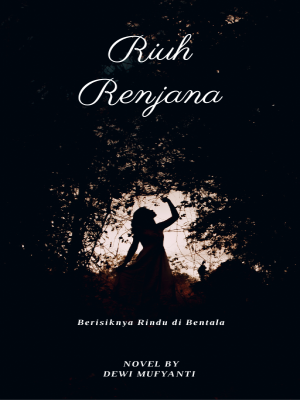“Bu Damay harus di-ospek!” Menteng membenarkan tas keranjangnya. Dia berjalan sambil memegang ranting. Di pinggulnya tersemat mandau.
“Ospek?” tanyaku. Tidak heran Menteng tahu soal ospek. Buku bekas yang dia baca rata-rata majalah SMP. Mengherankannya, apakah saat di-ospek harus memakai caping bertuliskan namaku besar-besar dan tas karung goni?
“Iya, dulu Hamak Fian juga di-ospek!” jawab Menteng, sesekali dia berhenti, berpikir, lantas berjalan lagi.
Dia tertawa renyah. “Ko ospek Hamak tak masalah. Asal Hamak Kalimantan. Lah, ini Bu Damay, asalnya jauh dari Pulau Jawa. Masih lelah. Kalian tega?”
“Tega!” Acel, Nico, dan Menteng menjawab serentak.
“Lagipula, tak susah pun ospek-nya. Serius.” Nico menjawab sambil mengamati pepohonan sekitar.
Acel hanya mengangguk. Tumben, dia pendiam. Biasanya cerewet.
“Acel sedang sakit hati pada Menteng, Bu.” Nico terkekeh, tahu apa yang aku pikirkan.
Acel hanya mengangkat bahu. Dia membawa tas cukup besar. Berisi bumbu-bumbu, tali temali, dan botol air mineral. Sebenarnya, dia sudah menawarkan untuk membawa, tapi Acel bersikukuh tidak mau dibantu. Dia bisa sendiri.
Sepagi tadi, suara anak-anak memanggil dari luar. Inak Bunan membangunkanku—aku tidur lagi setelah bangun. Inak menyuruhku bergegas mandi, sedang anak-anak dan dia masuk, duduk di ruang tamu. Inak menyiapkan peralatan dan bumbu-bumbu yang disiapkan. Nico memberi spoiler ‘berburu’. Seru juga, belum pernah aku merasakan berburu secara langsung. Berangkatlah kami ke hutan.
“Itok tak ikut?” tanyaku.
“Jangan, Bu. Nanti kepalanya yang penuh cahaya bulan membuat mataku silau. Susah fokus untuk berburu,” jawab Menteng dengan muka datar.
Acel dan Nico tertawa bersamaan. Aku bingung, tapi tertawa juga karena melihat dia tertawa.
“Kau bisa tertawa sekarang, Cel? Itu gurauan Menteng!” Nico jahil bertanya pada Acel.
Acel menatap sinis Menteng. Mengangkat bahu sambil melihat pepohonan sekitar. Ada hal menarik yang aku saksikan sendiri di depan mata. Para warga gotong royong menebang pohon, memindahkan pohon-pohon lantas membersihkan rumput belukar yang sudah meninggi.
“Itu, untuk membuka lahan?” tanyaku.
“Iya. Ladang padi,” jawab dia di sampingku.
“Bukankah sawah mereka banyak?” tanyaku sambil menoleh ke arahnya. Hari ini dia memakai kaos biru dengan celana kain pendek. Rambutnya basah karena keringat, tapi tetap keren.
Dia menoleh, tersenyum. “Betul. Sawah yang tidak subur akan ditinggalkan, lalu mencari tanah yang subur, dibukalah ladang kembali. Seperti sekarang.”
“Bukankah itu membuat kerusakan lingkungan?”
Dia terkekeh lebar. Anak-anak menyimak sembari berdiskusi. Aku tidak tahu yang mereka bicarakan. Merek asyik menggambar sesuatu di tanah.
“Ada betulnya, ada salahnya. Betulnya, bisakah dikatakan merusak lingkungan, sedang mereka tidak menggunakan sama sekali pupuk kimia?”
Mataku membulat. Serius tidak menggunakan pupuk kimia sama sekali? Hebat!
“Salahnya, bisalah dikatakan pemindahan lahan itu kerusakan lingkungan. Tapi, kau perhatikan baik-baik sawah yang mereka tinggalkan.” Dia menunjuk ke sawah yang sudah tidak terpakai lagi. Tanahnya memang sudah tandus, tapi ada beberapa orang membuang kotoran hewan dan sampah organik ke tanah itu.
“Mereka tidak meninggalkan tanah itu sepenuhnya. Dibiarkan tanahnya subur kembali, menumbuhkan rerumputan liar, satu dua menanam pohon kembali, seperti itu terus siklusnya. Mereka mengandalkan tanah yang subur, tetapi tetap bertanggung jawab atas tanah yang pernah mereka gunakan.” Dia tersenyum melihat sawah yang sudah dipenuhi kotoran dan sampah organik.
“Yang benar-benar salah itu, pembakaran masal ke seluruh wilayah hutan. Serakah hanya untuk pertumbuhan ekonomi saja. Tanpa tahu keseimbangan alam dan sekitarnya.” Dia meghela napas panjang.
“Warga di sini hanya membakar hutan seperlunya saja. Batang pohon itu mereka simpan, lantas nanti bergotong royong lagi untuk membangun rumah warga yang rusak. Saling membantu saat musim menanam dan panen padi.” Dia mengacak rambutnya. Keren bagiku, sepertinya tidak baginya. Mukanya begitu kesal.
“Kita berpisah di sini!” Nico membalikkan badan. Dia mengambil mandau di samping pinggangnya. Aku menelan ludah. Anak kecil sudah berani memegang mandau, memang hebat sekali desa ini.
Menteng sudah jongkok di bawah. Acel kembali sambil membawa ranting dan daun, lantas jongkok di dekat Menteng. Tentu, masih suasana canggung. Nico ikut berjongkok. Mereka seperti membuat perangkap dengan cara tradisional.
Nico menoleh ke belakang. “Hamak Fian paham maksudku, kan?”
Dia mengangguk. “Biarlah Bu Damay melihat kalian memasang perangkap. Siapa tahu, Bu Damay akan membuat perangkap untuk muridnya yang bolos sekolah.”
Aku menoleh padanya. “A-aku tidak sekejam itu, Pak,”
Dia tertawa keras sekali. Anak-anak ikut tertawa.
“Bu Damay serius sekali,” seru Acel sambil tertawa. Memberikan dedaunan di atas perangkap.
“Ayo, ikuti aku, Damay!” Dia berjalan mendahuluiku.
Deg! Jantungku berdebar begitu cepat. Pertama kalinya, dia memanggil namaku. Tanpa ‘bu’ pula. Aku belum bergerak sama sekali. Melihat punggungnya yang semakin menjauh dan aku masih bergeming terdiam. Lebih tepatnya, menahan teriak saking senangnya.
Dia berhenti berjalan. Menoleh ke belakang. “Ayo, Damaylia!” ajaknya lagi sambil tersenyum.
Tanganku terasa dingin di cuaca terik pagi menjelang siang. Jantungku semakin berdebar tidak karuan. Bibirku bergetar, tapi secara otomatis tersenyum lebar. Mengangguk pelan, mengikuti jejak langkahnya dari belakang. Hanya berdua.
***
“Kita mau kemana, Pak Fian?” tanyaku sembari melihat sekitaran.
Masih di dalam hutan. Pepohonan rindang, semak-semak yang masih tinggi, bebatuan besar terkadang terlihat, matahari yang masih terik, dan punggungnya. Punggung yang masih sama saat pertama kali aku bertemu dengannya. Aku memegang erat tanda pengenalnya di saku. Entahlah, belum tahu waktu yang tepat untuk memberikannya sembari mengucapkan dua kata yang selama ini aku pendam.
Dia menoleh ke belakang. “Apakah aku sudah mempunyai anak?” tanyanya.
“Eh? Aku tidak bertanya itu.”
Jujur, tidak bisa berbohong. Selama lima tahun aku selalu berpikir. Apakah dia sudah mempunyai pacar? Menikah? Ekstrimnya, apakah suidah mempunyai anak? Lima tahun belakangan aku seperti orang gila. Tertawa sendiri melihat Wacebook-nya, sekian menit bermuram durja terpikir pertanyaan yang belum terjawab.
“Umur kau berapa?” tanyanya.
“Dua puluh satu tahun.”
Dia menepuk dahi. “Alamak! Macam mana kau panggil aku Pak? Hanya tertaut enam tahu saje.” Dia tertawa kecil.
Dia menatapku lamat. Membuatku harus membuang muka. “Janganlah kau panggil aku Pak, panggil Bang, Mas, atau terserahlah. Asal, jangan Kak, nanti macam Kakak Senior PMR!”
Aku tertawa kecil. Benar juga. Iya, candaannya memang garing, tapi kalian pasti bisa menebak alasanku bisa tertawa begitu lega. Yes, sepertinya dia belum menikah. Dilihat dari jarinya belum ada cincin terpasang. Eh, sebentar. Belum menikah tapi kalau sudah mempunyai pacar? Aku menunduk, kenapa overthinking-ku harus hadir disaat menyenangkan bersama dia?
“AWAS!” Dia menarik tanganku ke samping. Jarak kami hanya satu kilan tangan. Mata kami saling bertatap. Mata bening cokelatnya semakin terlihat menawan. Gila, jantungku berdetak tidak karuan. Aku berharap dia tidak mendengarnya. Mukaku mulai memanas.
“Kau ni, masih muda banyak melamun. Ada ranjau di depan kau itu!” Dia menunjukkan daun hijau yang menggerumbul. Di sampingnya ada kayu yang sengaja ditancap. Kudengar dari cerita Inak Bunan, apabila ada manusia sampai terkena ranjau, maka yang memasang ranjau harus kena denda sesuai aturan adat.
“M-maaf, Pak, eh, Bang.” Aku memilih memanggilnya bang, sesuai panggilan lokal di daerah Kalimantan.
“Sepertinya, jiwaku memang seorang bapak-bapak.” Dia tertawa sembari meniru pose bapak-bapak saat berfoto. Menunjukkan jari jempolnya.
Aku tertawa kecil sambil menggeleng. “Bukan, aku takut tidak sopan,”
Dia mengibaskan tangan. “Apa kau akan minggir, melangsak ke sawah demi pejabat Pak Alfian lewat? Santai saja.” Dia berjalan lagi.
Aku membuntutinya dari belakang. Dia memotong ranting yang menghalangi. Sedang aku melihat jejak kakinya. lantas kuikuti jejak kakinya yang besar. Tersenyum sendiri.
“Apa yang kau pikirkan ketika melihat seorang dokter?” tanyanya.
Kamu. Eh? Ini otakku nge-lag atau hang? Katrok sekali.
Dia menoleh ke belakang. “Ei? Kau kepanasan?” Dia merogoh sesuatu di saku tasnya.
“Tidak, Bang, ak—” Aku menatap lamat padanya.
Dia sempurna memakaikan topi berwarna biru muda di atas kepalaku. Tersenyum lebar. “Pakailah topiku. Bersih, baru dicuci kemarin. Tenang, anti ketombe.” Dia menghadap ke depan, berjalan lagi.
Aku menunduk, takut mukaku yang semakin panas terlihat.
“Cuaca panas memang ciri khas di pulau Kalimantan. Alasannya pasti kau tahu. Pulau yang tepat dengan garis khatulistiwa.”
Aku belum berani menjawab. Di dalam dada masih ada genderang yang selalu berbunyi, ditambah muka panas, dan tanganku yang mulai mendingin. Aku berharap dia tidak mengetahuinya. Kami terus berjalan ke depan, entah berbelok ke kanan atau ke kiri. Aku terlalu fokus pada jejak langkahnya. Tidak tahu ini di mana, atau apa yang akan terjadi. Bersama dia, aku merasa aman. Padahal, baru beberapa hari bertemu dengannya.
Lagi, aku menatapnya lamat dari belakang. Jarak kami sangat dekat, tidak dengan empat tahun terakhir. Jarak yang jauh, dan aku tidak berani memberi pesan padanya lewat Wacebook. Menambahkan teman saja tidak berani, apalagi mengirim pesan.
Setiap malam aku selalu menerka. Bagaimana suaranya? Apakah lembut seperti Eno? Apakah tegas dan lantang? Atau cempreng seperti ompreng? Sekarang, aku sudah tahu suaranya. Lantang dan receh. Tidak seperti yang kubayangkan.
Empat tahun terakhir, saat aku melihat rombongan dokter berjalan di depanku, aku selalu bertanya. Apa yang dilakukannya saat ini? Sekarang, dia di depan mataku sendiri, melihat kesibukannya. Memangkas ranting-ranting dan rerumputan yang menghalangi jalan. Memberikan perlayanan terbaik, sekalipun hanya berpetualang bersama anak-anak. Walau, katanya ospek untukku.
Aku membenarkan topi. Menatap punggungnya lamat. Apakah ini nyata atau mimpi?
Suara gemericik air mulai terdengar. Duniaku berubah kembali ke semula. Penuh dengan warna warm yang klasik. Waktu melambat. Hutan bukan tempat menakutkan. Melihat rambutnya yang sedikit berkibar ke belakang, membuatku semakin mudah menghapalnya dari belakang. Di antara ribuan manusia, aku yakin, bisa tahu dia lewat punggungnya.
Rerumputan mulai merendah. Jejak langkahnya terakhir. Aku berhenti mendadak, takut menabrak punggunya.
“Damay, kita sudah sampai. Sepertinya, ini sungai yang cocok.” Dia berseru. Berjalan lagi.
Aku tidak menjawab. Berjalan di belakangnya. Jalanan setapak tanah mulai berganti dengan tanah keras dan licin. Arus sungai mulai terlihat lebih sempurna. Suara gemericik lebih terdengar. Dari atas, terlihat aliran mengalir ke bawah dengan empat terjunan. Ditambah, sungainya lebih jernih.
Dia mengulurkan tangan. “Mau kubantu?”
Aku menatapnya. Telingaku tidak salah dengar, kan? Dia mau membantuku dengan memegang tanganku, begitu? “A-anu, tidak usah,” Aku kembali ke jalan tanah, mencari sesuatu. Ah, ada ranting. “Aku memakai ranting saja, bagaimana?”
Dia tertawa renyah. “Baiklah, ulurkan ranting itu!”
Aku menurut. Dia memegang kuat ranting. “Entahlah, aku khawatir kau terpeleset, ikut aliran sampai bawah, kau tidak bisa berenang.”
“Aku bisa berenang, sungguh!”
Dia tetap memegang erat ranting itu. Menghadap ke depan. “Kau siap?”
“Ya!”
Dia mulai melangkah. Setiap batu, dia lewati dengan lincah. Aku ikuti setiap gerakannya. Sesekali dia menoleh ke belakang, lalu menghadap depan lagi. Aku fokus dan berhati-hati melewati bebatuan. Sayang, langkahku terlalu kecil melompat ke batu selanjutnya.
“BANG FIAN!” Aku reflek berteriak. Sempurna, aku terpleset, memegang batu. Ampun, musuh bebuyutan bagiku!
Dia langsung ikut menyebur di pinggirku. Tertawa terkekeh, “Kau bilang, kau bisa berenang?”
Aku mengerutkan kening. Dia saja bisa berjalan santai, berarti ... astaga! Sumpah! Aku ingin menutup mukaku dengan karung beras sekalian. Sungainya dangkal, aku saja yang terlalu khawatir, berpegangan pada batu.
“Kau bisa berjalan biasa, aku tuntun saja, ya? Bahaya nanti kalau sampai terseret,” Dia nyengir—nyengir setengah meledek.
Aku menghembuskan napas kesal. Malu banget rasanya. Dia mulai berjalan, memegang tangan kananku. Aku berjalan di belakang dengan menahan badan dari arus yang sedang. Dia memanjat batu di tengah-tengah sungai. Permukaannya rata dan luas. Mungkin, diibaratkan seluas papan tenis meja. Dia membantuku memanjat batu itu.
“Kita letakkan barang-barang di sini, pasti aman.” Napasnya tersengal.
Aku duduk tersengal juga. Mengambil botol mineral dari tas, menyerahkan padanya tangan bergetar. Dia menerimanya sembari tersenyum lebar. Duduk di sebelahku. Jangan tanya, aku tidak berani melihatnya sedekat ini. Belum terbiasa.
Dia membuka tas, mengambil jaket berwarna abu-abu. Memakaikannya padaku. Aku menoleh padanya. Dia tersenyum lebar.
“Untuk yang mengaku bisa berenang akhirnya tercebur dan panik juga.” Dia tertawa terkekeh. Lama-lama, kok, dia menyebalkan, ya?
Dia menunjuk aliran sungai. “Itu, kita akan mencari ikan di sana.”
“Mencari ikan? Apakah kita membawa pancing?”
Dia tersenyum seribu makna. “Ah, sudah biasa itu.”
“Lalu?”
Dia membuka tabung hitam, tingginya mungkin dua kali penggaris. Mengacungkan tongkat dengan ujung lancip. Terkekeh. “Pakai ini.”
Aku melongo. Gara-gara sifat menyebalkannya, aku mulai terbiasa. “Ini?”
Dia mengangguk meyakinkan. “Apakah kau bisa?”
Aku mendengus. Sepertinya dia mulai mengejek. “Siapa takut?”
Dia tertawa. “Let’s go!”
Dia mulai turun dari batu. Berdiri, menungguku turun. Aku melepaskan jaket, meletakkannya di atas tasku. Turun dengan bantuan tangannya. Baik, aku tahu kalian penasaran. Kuberi alasan saja, kan air membuat tangan dingin. Alasan penutup kegrogian.
Kita berjalan, perlahan mencari persembunyian ikan. Dia memberi kode jangan berisik, aku mengangguk. Aku mulai serius mencari ikan. Tidak mau diledek untuk dua kali lipat olehnya. Dia berdiri di atas batu, aku ikut berdiri di atas batu, tepat di sampingnya. Dia serius menatap setiap sudut ikan. Aku, hehe, ikut-ikutan.
“YAK!” Dia mengacungkan tombak ke arah tiga puluh lima derajat. Diangkat tinggi-tinggi tongkat. Diujungnya ada ikan sebesar dua tangan besar laki-laki. Entah, aku tidak tahu nama ikan itu. Dia segera kembali ke tempat asal, diletakkan saja di atas batu itu. Lah, sudah mati ikannya, mana mau kabur?
Dia kembali lagi. Nyengir padaku. “Satu kosong!”
Aku mengeluh. Baiklah, fokus. Aku tetap melihat setiap sudut sungai. Kenapa mataku menjadi tidak fokus seperti ini. Lebih baik melihatnya daripada melihat di mana ikan berada. Lihat, baru beberapa menit saja, dia sudah mendapatkan ikan lagi. Aku? Nol besar. Lebih menyakitkan daripada mendapat nilai nol ulangan matematika.
“May, apakah aku harus membagikan ikanku untuk kau? Sudah berapa jam tidak ada ikan yang mendekatimu. Atau, kau tidak mandi selama tiga hari?”
“Abang memang juaranya kalau soal membuat lawan jengkel!” Aku mendengus kesal.
Dia hanya nyengir. “Baiklah, aku tunggu setengah jam lagi, Bu Guru yang tidak mau kalah dan tidak mau didekati ikan.” Dia berbalik, melangkah ke batu awal. Tempat barang dan setumpuk ikan yang dia dapat. Dia duduk sambil tertawa kecil. Aku mendengus kesal. Sial, aku tidak bisa menggunakan perumpaan gender.
“Oi, Damay! Sudah satu jam kau tetap berkutat pada tombak yang tidak mengarah kemanapun. Matamu hanya awas dan tidak melihat ikan ada di mana?!” Dia berseru.
Aku menoleh padanya, menatap sebal. Mentang-mentang sudah dapat ikan setumpuk, selalu saja meledek. Oke, dipastikan aku akan mendapat ledekan dua kali lipat.
“Ayolah, Damay, lebih baik kau bantu aku membersihkan kotoran ikan!”
“Oh, jadi, kalau kalah disuruh membersihkan kotoran, begitu?”
Dia tertawa keras. “May, sensi sekali kau! Alamak, hanya perkara ikan dan tak bisa berenang saja sudah marah.”
“Siapa yang marah?”
“Kaulah! Ayo, nanti kau sakit. Lucu bukan? Kau berpetualang dengan seorang dokter, tapi kau sakit. Nanti, aku dikira dokter KW!”
Aku tertawa kecil. Berjalan menuju ke arahnya. Dia mengulurkan tangan, membantuku naik ke atas batu. Iya, aku memang sebal melihat ikannya sudah bertumpuk di depan mata. Mungkin, ada puluhan. Aku menghela napas, kecewa.
Dia memberikan pisau lebar dan tipis. “Kau bantu membersihkan sisik saja, aku yang membersihkan kotoran ikan.”
Aku sudah terbiasa membersihkan ikan. Ibu yang mengajariku. Namun, seorang dokter yang selalu dipandang hanya pandai bermain stestoskop bisa membantu membersihkan ikan adalah nilai plus untuknya. Dokter, pandai menulis, ditambah terampil memainkan pisau untuk membersihkan kotoran hewan. Sepertinya, dia juga pandai membuat bumbu untuk memasak.
“Apa anak-anak tahu kita ada di sini?” tanyaku.
Dia mengangguk. Serius membersihkan kotoran ikan yang ke sepuluh. “Mereka kalau diikutkan lomba pramuka, kuyakin jadi juara soal pengembaraan.” Dia menunjuk dari kejauahn ranting yang patah. “Aku memotong ranting, bukan hanya sekedar menghilangkan penghalang, tapi memberi petunjuk kepada mereka.”
Dia tersenyum. “Mereka sudah terbiasa hidup di tengah hutan. Berteman dengan hutan. Tahu seluk beluk hutan. Tahu cara bertahan, bahkan, kalau mereka mengembara saja di hutan selama seminggu, aku yakin mereka akan baik-baik saja.”
Aku mengangguk. Membersihkan sisik ikan kembali. Hening. Sesekali, aku menoleh ke ujung jalan tanah, menanti anak-anak datang. Gugup rasanya bersama dia, hanya berdua, mau mengambil percakapan apalagi?
“Apakah kejernihan sungai di sini sama dengan di kotamu?”
Aku pura-pura berpikir, “Tergantung.”
Dia mengangkat alis. “Tergantung?”
Aku mengangguk. “Kalau melihat di air terjun, pasti jernih. Kalau melihat di pinggiran jauh dari kota, sampah menumpuk di pinggiran sungai.”
Dia menoleh. “Serius?”
Aku mengangguk. “Menyebalkan memang orang-orang yang membuang sampah sembarangan.”
“Kalau nol kilometer sekarang bagus?”
Aku mengangkat alis. Bukankah, dia pernah bertempat tinggal dua tahun di Yogyakarta? Mungkin, hanya sebagai obrolan saja. Aku mengangguk, tersenyum lebar. “Bagus, Bang. Banyak bangunan klasik di sana.”
“Dulu, aku pernah tinggal tetap selama dua tahun di sana.”
DEG! Aku menahan napas. Duh, jangan sampai tahu kalau kita pernah bertemu.
“Oh, em, ya? Ngapain, Bang?”
Dia tersenyum lebar. “Praktik di Puskesmas dan Rumah Sakit.”
Aku menatapnya. “Kok, dua tempat, Bang?” Ini hal baru yang aku tahu dari dia.
Dia mengangguk. “Salah satu Dokter di Puskesmas ada yang baru meninggal, jadilah meminta bantuan pada Rumah Sakit. Nah, kebetulan, Dokter yang membimbingku itu sebagai pengganti sementara. Jadilah, aku yang dimintai bantuan ke sana.”
Aku manggut-manggut sok paham. Aku berpikir keras untuk mengalihkan pembicaraan soal Puskesmas. Aku belum siap mengakuinya.
Dia menatap ke langit. Tersenyum lebar. “Sangat menyenangkan, ya, ke kotamu. Ingin aku ke sana, bila ada kesempatan.”
Aku menatapnya lamat. Betapa, aku menyukai tatapannya. Betapa, aku menyukai cara menatap langit dengan tulus. Betapa, aku menyukai bagaimana mencari obrolan yang menyenangkan. Bubar sudah pikiranku soal mengalihkan topik.
“HOI, Hamak Fian, Bu Damay!” teriakan anak-anak dari seberang terdengar. Mereka melambaikan tangan. Nico menjunjung tinggi babi kecil buruannya. Acel mengangkat tinggi-tinggi ayam buruannya. Menteng, hanya membawa tas kecil, mengangkat bahu.
“Kalau mereka mau membawa, kenapa aku harus repot?” Begitulah kira-kira yang dia katakan.


 lu_r_an
lu_r_an