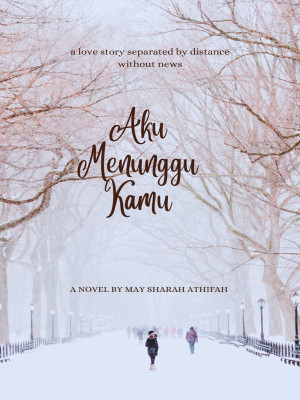“Jatahku usus dan paha babi!” Menteng menunjuk bagian babi yang dia mau.
“Memang, kau ikut berburu?” Acel bertanya sambil memotong daging babi.
Nico yang menyembelih babi itu sendirian. Sedangkan dia, menyembelihkan ayam untukku dan untukknya. Menteng hanya mengipasi api unggun yang dia buat. Kami berpindah tempat. Menyeberang sungai, lalu memilih tempat di bawah pohon rindang. Memutuskan memasak di tempat ini. Tempat yang nyaman dan sejuk.
“Ikut! Buktinya, akalku lebih jenius daripada kau, mengada-ada bahasa babi. Memang, babi bisa bicara?” tanya Menteng sambil mengangkat satu alis.
Acel mengangkat bahu. “Begitulah kalau manusia hanya mengandalkan otak untuk hapalan bacaan. Sekali-kali sajalah kau pakai hati. Hewan juga punya perasaan.”
Menteng mendelik. “Dasar bual besar. Buktinya, kau makan juga daging babi!”
Acel mendelik. “Setidaknya, aku membunuhnya sekali hentak. Jadi, tak merasa sakit.”
Aku tertawa melihat Acel dan Menteng saling mendengus jengkel. Mereka mengerjakan tugas masing-masing dengan wajah mengkal. Aku menoleh, melihatnya. Dia sedang membersihkan bulu-bulu ayam bersama Nico. Toleransi yang begitu menganggumkan. Saat aku dan dia tidak memakan daging babi, anak-anak tetap memburu ayam, membersihkan kotoran dan bulu.
“Bu Damay, dapat berapa ikan?” Acel bertanya. Potong-memotong daging babi sudah selesai. Aku berhenti mengiris bawang. Menelan ludah. Gawat, apa kata anak-anak kalau aku tidak mendapat ikan satu pun?
“Berapa, Bu?” Menteng bertanya juga.
“Bu Damay dapat banyak ikan. Sekali pelupa tetaplah pelupa. Dia mencampur buruan ikannya dengan ikan Hamak.” Dia mengangkat bahu.
“Alamak, tak seru, Bu Damay! Kita jadi tak tahu siapa pemenangnya!” Acel berseru kecewa. Menteng mengangkat bahu, melanjutkan kipas-kipasnya.
“Bu, apakah bumbu sudah siap?” tanya Nico.
Aku mengangguk. Nico mengambil mangkok bumbu, mengoleskan ke potongan daging. Aku menatap dia menyiapkan beberapa bilah bambu panjang, lantas memotong dadu daging ayam, menusukkan ke bilah bambu. Aku menoleh padanya. Kenapa dia mau berbohong? Padahal, satu ikan pun tak kudapat.
Dia menoleh. “Oi, Damay, kalau kau hanya melamun, lebih baik bantu aku sini!”
Aku mengangguk gagu. Ketahuan. Dia menyerahkan beberapa bilah bambu. Membantu menusukkan daging ke bilah bambu.
“Bu Damay, pasti tak dapat ikan satu pun!” Menteng mengibaskan perapian lebih cepat.
“Oi, kau bisa tak lebih pelan? Debu menempel semua di mukaku.” Acel mendengus kesal.
“Kau itu macam nenek-nenek, sebentar-sebentar marah, sebentar-sebentar kesal!” Menteng ikut mendengus.
“Kalau ribut terus, jatah kalian kotoran babi!” Nico mendelik pada Acel dan Menteng. Mereka berdua langsung terdiam, saling lirik, saling melotot dengan kesibukan mereka.
Dia tertawa kecil. Merapikan tusukan-tusukan daging di atas perapian sederhana yang dibuat. “Lama-lama, kalian nanti pasti akrab. Hamak Fian jamin itu.”
“TAK!” Acel dan Menteng menjawab bersamaan. Saling melihat, membuang muka kembali.
“Selesai. Mari kita membakar daging,” seru Nico riang.
Kami berlima duduk melingkar mengelilingi bebakaran daging. Dia terampil membolak-balik daging serta mengoleskan bumbu. Nico juga. Acel dan Menteng menahan air liurnya, sepertinya mereka sudah lapar.
“Ini milikku.” Menteng menunjuk tusukan daging yang paling banyak potongan daging babi. Tentu, daging ayam dan daging babi dibakar terpisah. Daging ayam ada di depan dia, daging babi ada di depan Nico.
“Kerjaan kau hanya kipas-kipas, berarti ini milikku!” Acel ikut menunjuk potongan daging itu.
“Itu milikku!” Nico menatap tajam bergantian ke Acel dan Menteng. Mereka mendengus pelan, takut pada Nico.
“Terpenting, daging ayam ini milik Hamak dan Bu Damay.” Dia ikut berebut.
Aku tersenyum kecil. Dia lucu juga kalau merajuk seperti anak kecil. Aku menoleh ke Dia diam-diam. Rambutnya basah keringat, bahkan peluh terkadang mengalir di pelipisnya. Wajahnya lelah, tapi muka tetap riang.
Gemeletuk api menjadi nada di dalam keheningan kami. Sibuk membolak-balik daging, atau sekedar melihat air terjun dengan empat aliran. Melihat Menteng dan Acel saling lirik jengkel. Melihat Nico serius menunggu daging matang. Setelah daging sudah matang. Kami mengambil jatah masing-masing.
“Amboi, bumbu dari Bu Damay enak betul!” Acel tertawa renyah. Menteng mengangguk setuju. Dia mengangguk sambil melihat riak sungai.
“Kenapa melihat riak sungai, Bang? Mau mencari ikan lagi?” tanyaku.
Dia menggeleng. Menyantap potongan daging. “Terpikirkan sesuatu saja.”
Anak-anak langsung mendekatinya. Aku mengangkat alis.
“Pasti, Hamak mau cerite. Iya tak?” Mata Acel membulat.
Dia mengangguk, tersenyum.
“ASYIK!” seru mereka serentak. Oalah, itu alasan mereka mendekat. Berarti dia sudah terbiasa bercerita pada anak-anak.
Dia menghela napas pelan. “Pernah mendengar pepatah, ‘Air tenang menghanyutkan’. Kita tidak asing dengan pepatah itu. Pasti setiap orang tahu artinya.”
“Artinya, orang yang dalam ilmunya pasti tenang perangainya,” jawab Acel semangat.
“Kalau tak tenang airnya, artinya tak dalam ilmunya.” Menteng menambahkan jawaban.
Nico diam menyimak. Aku juga. Belum tahu arah pembahasan obrolan.
“Apa pendapatmu benar, Menteng?” tanyanya.
Menteng menggaruk kepala. “Ya, sepertinya benar. Sungai tenang artinya berilmu dalam. Kalau tak tenang, ya kebalikannya. Tak punya ilmu banyak. Contohnya, ada anak membaca puisi sampai tercebur. Banyak cakap ditambah banyak gerak. Nilai matematikanya jelek.”
Acel melotot pada Menteng. Merasa itu dirinya. Menteng hanya mengendik, lantas bersiul.
Dia tertawa kecil. “Bagaimana kalau kita bermain perumpamaan?”
Anak-anak mengangguk kompak. Aku semakin menatapnya lamat. Penasaran dengan cerita selanjutnya. Dan, terlebih anak-anak ini tahu soal perumpamaan.
“Pernah kalian gugup, saking gugupnya tidak tahu harus berbicara apa?”
“Aku pernah,” jawab Nico.
“Bukankah menjadi hening keadaannya?” tanyanya.
Nico mengangguk.
“Apakah, Bu Damay mengajari kalian dengan bahasa isyarat? Tanpa suara?”
Acel menggeleng cepat. “Bagaimana tahu ilmu kalau Bu Damay mengajari tanpa suara?”
Dia tersenyum simpul. “Kita sudah paham, bukan? Di saat semua orang menganggap kita tenang di luar, belum tentu dia tahu semua hal. Saat di luar berkecamuk, tapi bisa jadi dia tahu banyak hal. Tidak bisa kita hanya mengandalkan si anak pendiam pasti cerdas, si anak banyak bicara pasti tidak cerdas.”
Dia menghela napas. “Bukankah kita tahu, ada guru, ada pembawa acara, ada pengacara, ada hakim, dan masih banyak lagi pekerjaan yang membutuhkan kemampuan untuk berbicara dan bergerak ke manapun?”
Menteng dan Acel menggaruk kepala. Nico menggeleng, mungkin belum mengerti.
“Tenang dalam artian cara menghadapi suatu permasalahan, betul, Bang?” tanyaku.
Dia mengangguk. “Betul.”
“Maksudnya?” Acel mengangkat alis.
“Mari, dengarkan pendapat Bu Damay.” Dia terkekeh.
Aku menghela napas perlahan. “Diibaratkan, saat Acel mau belajar sepeda, kalau dari awal sudah gugup, maka akan mudah terjatuh, kan?”
Acel mengangguk.
“Sebaliknya. Kalau Acel dari awal sudah tenang, maka akan lebih mudah belajar naik sepeda. Betul?” tanyaku.
Acel mengangguk.
Aku tersenyum. “Semakin kita tenang menghadapi sesuatu, entah saat tes, saat lomba, atau saat keadaan yang membuat kita ketakutan, kesulitan, dan membuat ingin mundur, percayalah akan lebih mudah menghadapi itu. Tarik napas panjang, keluarkan perlahan. Itu salah satu cara membuat pasien agar lebih tenang.”
Aku mengangguk. Anak-anak menunduk, berusaha mencerna perkataannya.
“Kalian ingin tahu, kenapa Hamak bercerita tentang ini?”
“Festival penangkapan babi!” celetuk Menteng.
Dia tertawa. “Apa hanya babi yang ada di pikiranmu, Menteng?”
“Lagipula, daging babi enak.” Menteng mengambil dua tusuk lagi. Jangan tanya Acel, dia sudah habis lima tusuk.
Dia mengeluarkan lipatan kertas dari tas. Membuka lipatan itu. “Kita diberi kesempatan untuk maju.”
Anak-anak mengerubung. Membaca fokus. Aku ikut membaca di sebelah Acel. Anak-anak menatap dia dengan tatapan tak percaya.
“Bagaimana kita bisa ikut, Abang Fian? UKS saja tidak ada.” Aku bertanya sambil menatapnya tidak percaya.
Dia tersenyum. “Gampang, nanti kuceritakan bagaimana sekolah di sini bisa lolos. Aku juga sudah memberitahu Kepala Sekolah, beliau setuju. Mungkin, besok pagi, kau akan diberi mandat.”
Aku menelan ludah. “Memang, siapa saja yang ditunjuk, Bang?”
Dia menunjuuk Acel, Nico, dan Menteng. Yang ditunjuk berhenti makan daging, saling tatap satu sama lain.
“Ya, kalian. Aku sudah memutuskan. Lagipula, bukankah kalian sudah terbiasa bersama? Yang kebetulan, perjalanan kalian dari rumah ke sekolah harus menggunakan longboat, bukan? Hamak juga mendengar, kalian rangking tiga besar.” Dia tersenyum lebar. Matanya bercahaya.
Anak-anak menelan ludah. Mengedipkan mata bersamaan.
“Hamak harap, saat kalian ikut lomba ini, salah satu di antara kalian bisa membantu Hamak menjadi tenaga kesehatan di desa ini. Kita bangun besar-besar Balai Kesehatan, tanpa harus menunggu berjam-jam untuk sampai di Rumah sakit pusat.”
Dia menatapku. Tersenyum. “Aku bantu. Kita bekerja sama.” Dia mengadukan kepalan tangan ke arahku.
Aku menatapnya lamat. Kenapa? Kenapa dia selalu membuatku terkagum, Tuhan? Ketika kami berjarak, lewat tulisannya saja bisa membuat hatiku bergetar. Bisa membuatku berani mengambil resiko, menjadi seorang relawan. Sekarang, dia ada di depanku. Hanya berjarak satu lengan.
Kenapa? Kenapa dia selalu membuatku ingin selalu berlari meraihnya yang tinggi seperti bintang? Tampan, senyum yang manis, perangai yang tulus dan ramah, dan niat yang baik. Apakah, dia tercipta seperti malaikat? Yang tidak mempunyai sedikitpun kekurangan, atau aku saja yang belum tahu?
Aku tersenyum lebar, membalas senyumnya. Senyum yang paling berani, bertaruh pada degup jantung yang terus berbunyi. Mengepalkan tangan kananku, beradu dengan kepalan tangannya. Pertama kali, kami saling tatap, tersenyum lebar.
***
Benar kata dia. Aku langsung diberi mandat dari Kepala Sekolah untuk mendampingi dan melatih anak-anak lomba. Tentu, anak-anak pesimis mendengar kata lomba. Baru pertama kali, SD ini melakukan lomba soal kesehatan. Lomba dokter kecil.
“Bu, Acel tak ingin menjadi dokter, mengapa ditunjuk?” protesnya sambil berjalan. Sesekali dia menendang bebatuan kecil, mengkal.
“Iya, aku juga, Bu. Aku kan ingin jadi peternak bebek, bukan dokter bebek.” Menteng menjawab sambil membaca buku pelajaran IPS—dia pecinta Ilmu Pengetahuan Sosial.
“Memang ada, dokter bebek?” tanya Acel penasaran.
“Cari tahu sendirilah, kata kau sendiri suka bahasa, membaca saja malas.”
Acel melotot. Menimpuk bahu Menteng dengan buku antologi puisi.
“Kalau kuh, bangga.” ucap Nico. Mengabaikan pertengkaran Menteng dan Acel.
“Kenapa, Nico?” tanyaku sambil tersenyum. Berbelok ke kiri, menuju ‘Puskesmas Kecil’.
“Artinya, kuh dipercaya untuk mewakili sekolah. Betul, kita tak tahu menang atau kalah. Bukan masalah, terpenting kita bersungguh-sungguh belajar. Bukan begitu, Acel, Menteng?”
“I-iya, tapi, sungguh aku lebih menyukai bahasa daripada IPA,” jawab Acel.
Menteng mengangguk. “Walau, tak masalah menghapal banyak-banyak, lagipula aku memang cerdas soal hapalan. Bedanya, IPS lebih luas dan terbuka. Mau menerima soal pendapat. Aku tak yakin kalau pelajaran IPA. Ini ya ini. Rumus ini, ya ini. Menyebalkan.” Menteng mengangkat bahu.
“Tenang saja, aku ada cara agar kita tak gugup dan bisa bekerja sama.” Nico tersenyum. Membuat Acel dan Menteng saling tatap. Nico Berjalan lebih cepat menuju ‘markas’nya. Nico berhenti. Kami ikut berhenti di samping Nico. Eh?
“Oh, hai kalian, kemari bantu Hamak! Nah, Bu Damay juga.” Dia melambaikan tangan.
Nico naik bersama Menteng dan Acel. Aku belum, berdiam diri. Puskesmas ramai dengan ibu-ibu membawa balita dan anak-anak kecil. Mereka mengantre ditimbang dan diberi susu. Para lansia yang antre diperiksa oleh dia.
“Bu Damay? Mau jadi patung pemberi nomor antre?” tanya Menteng dari atas panggung—markasnya juga terbuat dari rumah panggung.
Nico menjitak kepala Menteng. Aku tertawa kecil, melangkah ke atas. Saat ini, dia memakai baju kemeja ungu kotak-kotak dengan jas berwarna putih. Apapun yang dia pakai, selalu luwes. Membuatku selalu memujinya.
“Ah, Bu Damay, bisa bantu memberi susu ke dalam gelas, lantas memberinya ke semua yang datang?” tanyanya sambil tersenyum.
Aku mengangguk. “Siap.”
“Itu, di panci besar.” Dia menunjuk, lalu sibuk menulis resep untuk pasien yang datang.
Aku bergegas menuju panci, menuangkan susu ke dalam gelas. Beruntungnya, orang-orang mengantre di depan meja, jadi aku tidak kerepotan jalan untuk memberi susu. Anak-anak disuruh membantu memberi vitamin kepada anak-anak kecil. Dia juga meminta anak-anak untuk mengamatinya saat bekerja. Aku paham. Dia pasti sedang membiasakan anak-anak di dalam lingkup kesehatan. Sangat liniear dengan sekolah SD yang belum ada UKS.
Dua jam berlalu. Puskesmas sudah sepi. Penduduk pulang ke rumah masing-masing. Anak-anak duduk menjeplak di atas lantai kayu. Dia melepas jas putihnya. Semakin terlihat berwibawa dan tampan.
“Untung aku tak pernah bermimpi menjadi seorang dokter,” keluh Menteng sambil menyeka keringatnya.
Acel mengangguk. “Saat ini, aku percaya pada ko, Menteng. Ini masih Posyandu, Macam mana setiap hari bertemu pasien di rumah sakit?” Acel menggelengkan kepala.
Aku memberi segelas susu ke anak-anak. Dia mengangkat bahu. Lantas meminum air putih. Dia sama lelahnya, tapi tidak mengeluh. Terlihat dari keringat di seluruh wajahnya.
“Bukan itu yang penting, tapi apakah kalian mengamati Hamak saat menangani pasien?” Dia bertanya.
Nico mengangguk. Meletakkan gelas susu di lantai. “Kuh mengamati. Cara Hamak bertanya pada pasien, lantas menulis semua keluhan, lantas memeriksa menggunakan alat itu.” Nico menunjuk stetoskop, “lalu, Hamak bisa menentukan sakit apa. Hebat!”
Mukanya sedikit merona. Oh, ternyata dia malu juga kalau dipuji.
“Apakah ada yang masih ingat percakapan Hamak dengan pasien?”
Menteng mengusap mulutnya. Sekali teguk, susunya habis. “Sakit apa, Hamak? Apakah akhir-akhir ini nafsu makan berkurang? Apakah perut sebelah kiri bawah sakit? Apakah akhir-akhir ini batuk terus-menerus? Apakah ada dahaknya atau kering? Masih banyak sekali pertanyaan dari Hamak Fian.”
“Bukan main.” Dia nyengir, mungkin bangga dengan Menteng. “Bagaimana kau bisa menghapal pertanyaan sebanyak itu, padahal hanya sekali dengar?”
Menteng membusungkan dadanya. “Siapa lagi? Master ingatan. Bahkan, aku masih ingat letak upil Acel di setiap meja sekolah.”
TAK! Acel memukul bahu Menteng dengan buku tebal—buku daftar hadir.
“Oi, apa yang kau lakukan?” Menteng berseru galak.
“Kalau bercerita jangan mengarang. Bualnye!”
Menteng mendengus kesal. “Kau bilang aku bual? Oi, hari Senin kau mengupil dan ditempelkan di bawah meja sebelah depan. Selasa, kau mengupil ditempelkan di samping meja sebelah tengah. Mana ada Menteng pembual?”
“Aku menempelkan di kertas. Makanya, bertanya dahulu baru berujar!” jawab Acel dengan muka sedikit merona. Malu, perempuan, kok ngupil di kelas.
“Mana kutahu? Haruskah aku bertanya, oi, Acel, itu upil kau diletakkan mana? Padahal, Bu Damay sedang mengajar, begitu?” Menteng berseru tak mau kalah.
“Kalau kau tak tahu kebenarannya, lebih baik diam!” Acel mendengus kesal.
“Ekhem.” Nico berdeham.
Acel dan Menteng menatap takut Nico. Aku sendiri sebenarnya, takut bila Nico sudah berdeham. Dia sosok yang serius, tapi santai. Sosok yang bisa diandalkan. Sosok yang bisa menganulir keadaan.
Dia mengusap mukanya. Tertawa kecil. “Astaga, perseteruan yang hebat soal upil.”
Aku ikut tertawa lepas. Betapa lucunya anak-anak. Namun, ada yang aneh. Aku tertawa sendiri, anak-anak dan Dia justeru melihatku lamat. Membuat mukaku merona.
“Eh? Anu, em, Bu Damay salahkah tertawa?” tanyaku.
Mata Acel berbinar. “Bu Damay, cantik betul saat tertawa terbahak.”
Mukaku terasa panas. Melirik sedikit ke Dia. Mukanya masih sedikit merona.
“Eh, ahaha, eh, Bu Damay, ya, hanya ingin tertawa saja.”
“Kalau jadi bintang iklan pasta gigi, Bu Damay pemenangnya, tapi ....” Menteng menggumam.
“Tapi apa? Kau mau bilang Bu Damay jelek?” Acel berseru galak. Menatap takut-takut pada Nico.
Menteng mengangkat bahu. “Tak. Gigi Bu ada cokelat. Nanti, iklannya seperti ini. Pasta gigi rasa cokelat, bisa membuat gigi anda penuh dengan bintik cokelat.” Menteng memeragakan diri sebagai bintang iklan. Dia dan Nico tertawa. Acel melotot pada Menteng—tidak terima aku diledek.
Yang sempurna membuat mukaku merona. Termasuk Dia.
***
Dia membawa lima buku tebal ke atas meja. Membuat Acel dan Menteng melongo. Nico mengangguk, tahu ini adalah mandat yang cukup berat.
“Tidak, kalian tidak membaca lima sekaligus buku ini. Nanti, aku ringkaskan bersama Bu Damay. Nah, tugas kalian hari ini adalah ....” Dia memberi tiga lembar kertas berklip ke masing-masing anak. “Kalian baca tiga lembar kertas ini selama lima belas menit, setelah itu, kita akan main kuis. Bagaimana?”
Menteng cengar-cengir. Dia yakin sekali akan menang. Acel menelan ludah, hapalannya tidak buruk amat, tapi tak sesempurna Menteng. Nico, jelas dia akan memilih memahami setiap kalimat, masuk ke otak, melekat dengan lama. Aku tahu karakter anak-anak dari Dia dan salah satu guru di sekolah. Juga pengamatanku saat mengajar tiga minggu ini.
“DIMULAI!” Dia berseru. Anak-anak memilih tempat masing-masing. Acel di pojok depan, sambil melihat pemandangan. Menteng di bawah tangga, membaca keras-keras sambil menghapal. Nico diam takzim, membaca dengan tenang. Asli, kalau aku boleh menduga, dia cocok sekali menjadi dosen atau seorang peneliti. Tenang dan fokus.
Dia melambaikan tangan, mengkode untuk mendekat. Aku mengangguk.
“Kita bagi tugas. Aku akan membaca buku tebal ini, nanti aku tandai, kau bahasakan yang mudah dipahami anak-anak. Tenang, jarang ada bahasa latin. Kau pasti bisa.” Dia sudah sibuk membuka buku.
Aku menghela napas pelan. Mengamati cara dia membaca secara dekat. Dia membaca cepat sekali. Mungkin, karena sudah hapal yang ada di dalam buku, tinggal mengulang dan masih ingat letak setiap kalimat.
“Nah, satu buku selesai. Silakan, kau seorang guru pasti paham cara-cara bahasa yang lebih mudah dimengerti anak. Ditambah, kau seorang psikolog. Baguslah.” Dia tersenyum lebar, membuka buku kedua. Aku tersenyum simpul, mengambil buku panjang, menuliskan apa yang dia mau.
“Amboi, tulisanmu rapi betul, Damay!” Dia melongok tulisanku. Dekat sekali! Hanya berjarak satu jari kelingking. Aku menahan napas. Bau parfumnya, bau shamponya, aku bisa menciumnya. Dia kembali ke posisi semula. Aku bisa bernapas lega.
“Kau kursus tulisan?”
Aku tertawa kecil. “Kalau ada kursus tulisan tangan, aku yakin ilmu psikolog akan berkurang teorinya.”
Dia mengangkat alis. “Bisanya?”
“Melihat tulisan orang, lantas tahu kepribadian orang itu termasuk ilmu psikolog, bukan?”
“Oh, iya juga.” Dia tertawa renyah. Kembali membaca buku tebal-tebal itu. Menunjuk tulisan-tulisan yang harus kutulis. Aku mendengarkan penjelasannya, menuliskan sesuai bahasa anak—saat pelatihan diajari cara membuat pembelajaran sesuai dengan bahasa anak.
Mendengar cara dia menjelaskan, hatiku mulai berdegup lagi. Perasaanku sangat bahagia. Sesekali, dia memberi candaan, sesekali dia mengulang tiga kali memberi penjelasan—bahasa ilmiah tepatnya.
“Keren ....” Ups! Aku langsung menutup mulutku. Mukaku memerah.
“Apa, Damay? Kau bilang apa?”
Beruntung! Dia tak mendengarnya. Aku menggeleng sambil nyengir. “Enggak, tadi bahasa ilmiahnya, apa? Terdengar rumit.”
“Kuyakin kau pasti anak IPS.” Dia terkekeh.
Aku nyengir. “Kok tahu?”
“Lah, bakteri Escherichia coli sering sekali dibahas. Apa di kelas lima belum sampai pelajarannya?”
Aku menghela napas pelan. Duh, sial betul aku terlihat tolol di depannya. Benar kata Ruki, penyetaraan pengetahuan. Aku tahu bakteri itu, hanya mengalihkan topik saja. Bahaya nanti kalau dia tahu aku memujinya.
Dia mengibaskan tangan. “Lagipula, di ilmu psikolog, aku yakin tak mempelajari itu. Betul?”
Aku mengangguk. “Lanjut?”
“Lanjut apa?”
Aku menepuk dahi. Menunjuk ke buku tebal. “Lanjut meringkas materi.”
“Oh, iya juga.” Dia mulai membaca lagi.
Aku meliriknya sebentar. Tersenyum simpul. Lanjut menuliskan yang dia ajarkan. Sungguh, kalau waktu bisa diulur seperti permen karet, aku mohon untuk hari ini saja, ulurkanlah lebih terasa lama, seperti saat aku merindukannya. Saat aku jauh darinya, saat lima tahun waktu serasa melambat, merangkak slow motion, dan akhirnya takdir yang mempertemukan. Yang menjadi pertanyaanku. Apakah ini pertanda baik atau sebaliknya?
“Hamak Fian, kapan dimulai? Aku sudah hapal, gampang!” Menteng berseru sambil menjentikkan jari.


 lu_r_an
lu_r_an