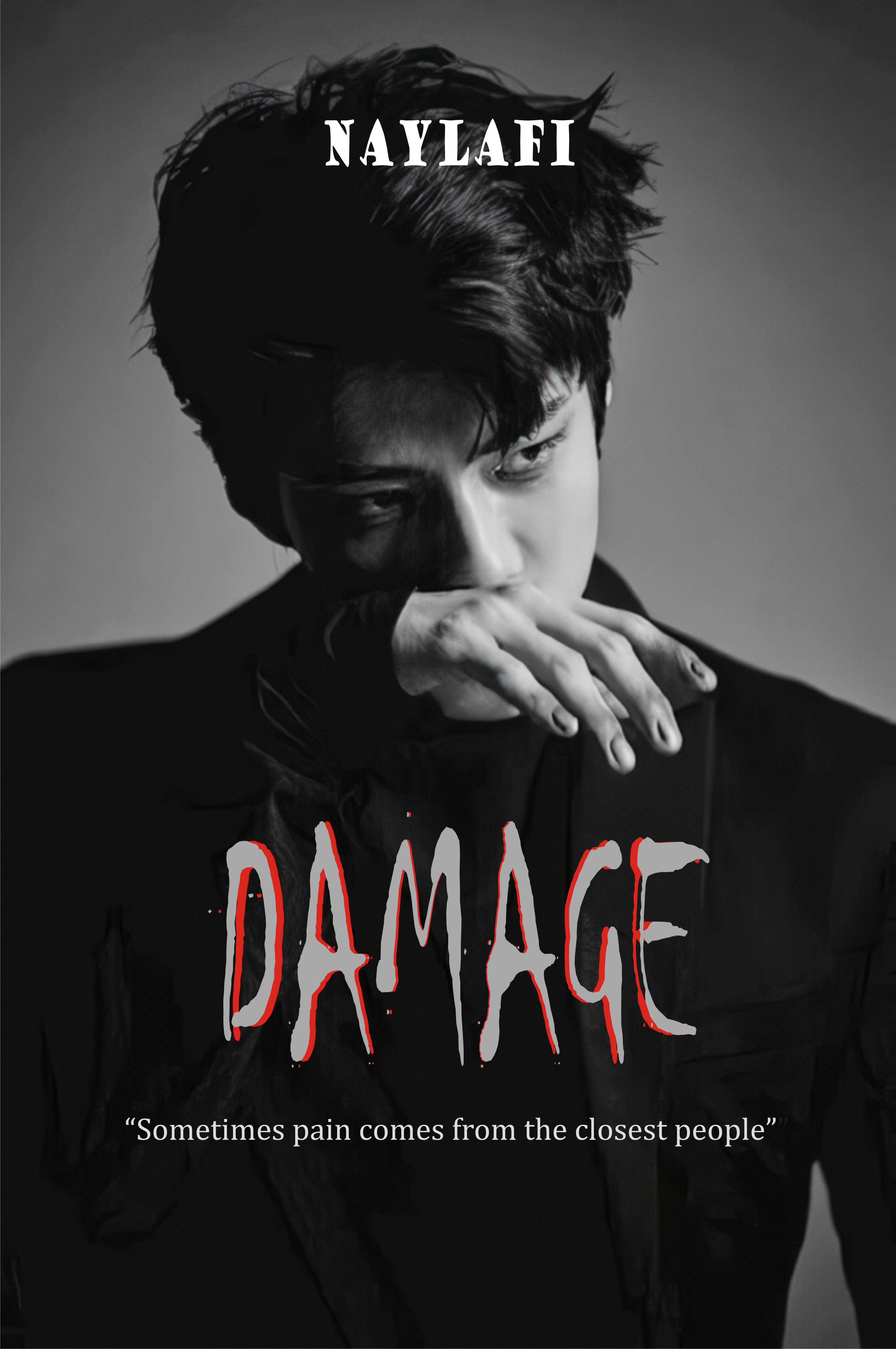4 tahun kemudian.
“LIMA METER!” teriak salah satu pegawai kain. Aku mengelus telinga, keras banget teriaknya. Ruki tidak berhenti memegang satu kain, pindah lagi, memegang lagi, pindah lagi, melambaikan tangan, mengode untuk mendekat. Aku memutar bola mata. Aku yang mencari kain, kenapa dia yang rempong. Selalu.
“May, sini!” Ruki melambaikan tangan—kode untuk mendekat.
Dia merentangkan kain ke kulitku. “Hem, kamu cocok warna biru muda. Kenapa, sih, harus abu-abu? Sudah muka sendu, kebaya abu-abu. Sekalian hitam, biar berkabung.” Ruki mendengus. Mencari kain kebaya yang lain.
Empat tahun berlalu. Empat tahun juga memendam soal pertanyaanku. Atas pertemuan dengannya. Atas rindu. Atas semangat motivasi. Atas apapun tentangnya. Bahkan, memengaruhi jurusan kuliah yang aku ambil. Psikologi.
Di saat sela-sela kuliah, aku selalu memperhatikan rombongan mahasiswa kedokteran berjalan. Memakai jas putih, tertawa riang sembari membawa tumpukan buku super tebal. Disaat itu pula pertanyaanku muncul. Apakah sekarang dia sudah menjadi dokter di Rumah Sakit? Atau di Puskesmas? Atau palah membuka praktik sendiri?
Usaha selalu kulakukan agar bisa ke kotanya. Naas, belum beruntung. Mulai dari KKN, perlombaan ilmiah, atau penelitian, tetap saja tidak bisa. Alasannya sederhana. Ibuku belum mengizinkan dan belum beruntung menang. Terakhir, aku mencoba mengirim berkas ke program pengajar di pelosok, tapi tidak ada kabar. Baiklah, nanti akan ada kesempatan lebih baik.
Waktu yang akan memberikannya secara tepat.
Ruki dan aku satu kampus, tapi beda fakultas. Dia masuk jurusan Biologi murni, melanjutkan kesukaannya semasa SMA. Coba, sesekali kalian berjalan saja di samping Ruki. Maka, hanya lima menit kesempatanmu. Dia sibuk sekali sejak kuliah. Ikut lomba karya limiah, menjadi asisten dosen, terpilih mahasiswa berprestasi, ditambah sibuk mengurus untuk persiapan lanjut S2.
Bagaimana kabar Eno? Aku tidak pernah tahu kabarnya.
Sejak pertemuan di pinggir trotoar, buku-buku itu aku simpan. Aku buka satu persatu. Dia tidak omong kosong. Tanda tangan dari penulis favoritku, bahkan pulpen yang bertanda tangan langsung ada. Yang mengejutkan, ada motivasinya.
“Oi, temanmu bernama Eno, benar-benar kalap meminta tulisan motivasi langsung dariku. Baiklah, kuberikan padamu, Damaylia. Nama yang unik. Semoga, tercapai semua impianmu. Salam damai, Damaylia. Luin.”
Hatiku terasa sedih. Kenapa tidak Eno? Justru seseorang yang antah berantah. Ditambah terus bertahan sampai sekarang. Ruki sampai bosan mendengar keluhanku, mendengarkan puisiku yang jauh lebih mirip curhatan, kerepotan mencegahku makan seblak banyak-banyak, dan rela tidak tidur mendengar tangisanku.
Hanya untuk cerita tentang dia. Hanya karena dia.
Saat ini, aku sedang membeli kain kebaya untuk persiapan wisuda. Tentu, kalian pasti bisa menebak, mengapa aku memilih kebaya berwarna abu-abu? Adalah warna bajunya saat pertama bertemu di Puskesmas sederhana itu. Jelas, seminggu sekali aku masih mengunjungi Puskesmas itu. Hanya menatap bangunannya dari kejauhan.
“Damay! Aku yakin ini pasti cocok, sini!” Ruki melambaikan tangan lagi. Aku mengangkat bahu, mendekat.
Dia merentangkan kain kebaya itu di tanganku. “Nah, cocok! Sederhana dan berwarna abu-abu. Bagaimana, kamu suka?”
Aku mengamati kebaya dengan aksen renda bunga berwarna ungu kecil-kecil bagian pinggirnya. Sederhana dan elegan. Aku mengangguk, tanda setuju.
“Nah, bawahnya berarti jarik warna abu-abu dan ungu, ya?”
Aku mengangguk saja. Menurut.
“Oke, siap! Mbak!” Ruki melambaikan tangan ke salah satu pegawai toko. Dia mendekat, segera mengurusnya. Aku menatap lalu lalang jalan. Hari semakin sore. Kubuka lock screen ponsel. Beberapa menit lagi acara di mulai.
“Ruki, setelah ini kita langsung ke acara, ya?”
“Beres, Bu Bos!”
Urusan membayar selesai, aku dan Ruki bergegas naik motor berboncengan. Jelas, aku di depan dia di belakang. Mana ada seorang Ruki mau di depan mengendarai motor? Kami mulai melaju pelan di jalan raya yang mulai macet.
“Kan, biar ada cowok yang ngelirik, May. Kamu harusnya berterima kasih sama aku, kalau nanti kamu enggak jomblo!” jelas Ruki seolah tahu bahwa aku sebal padanya.
Terlalu lama memilih baju, membuat kami harus bertempur dengan jam padat pulang kerja. Ditambah, aku paling tidak suka soal dijodoh-jodohkan. Padahal, dia tahu betul hatiku untuk siapa, tapi selalu saja menjodohkan aku dengan A, B, C, dan huruf-huruf lainnya. Yang jelas, aku tolak dengan tidak memberi respon berlebihan.
“May, kita pakai jalan pintas. Ke kiri!” perintah Ruki. Aku sangat berterima kasih untuk seseorang genius yang membuat aplikasi penunjuk jalan anti macet.
Jalanan sepi, tapi tetap macet. Tidak macet-macet amat, sih. Aku terus fokus mengendarai motor, menuju gedung JEC. Siapa lagi kalau bukan menonton kak Nata? Dia memberi undangan langsung untukku. Ruki tidak dapat, aku yang mengajaknya.
“Nah, keliatan, tuh, gedungnya!”
Siapa coba yang tidak tahu gedung JEC di Yogyakarta? Bersebelahan langsung dengan perpustakaan megah—tempat favoritku menugas. Bangunannya mewah dan keren. Halaman luas dengan arsitektur yang memukau.
Kami tiba tepat waktu. Suara gong bertabuh. Pertunjukkan meriah dan tepuk tangan penonton bergemuruh. Aku menarik lengan Ruki, berlari lalu berjalan sepatutnya mencari tempat duduk. Demi menonton kak Nata lebih dekat.
Acara ini diadakan untuk memperingati Hari Budaya di Yogyakarta. Kak Nata diundang langsung oleh pada seniman level atas. Dia juga menjadi pemeran utama dalam pentas seni teater ini. Bisa dibilang, kak Nata adalah seniman level atas yang umurnya masih muda.
Kak Nata sudah berdiri di tengah-tengah panggung dengan cahaya sorot. Memakai kemben jarik, dengan rambut panjang tersampir di bahu. Dia menari lemah gemulai, mulai bermonolog. Sesekali kami tertawa karena monolonya yang lucu, sesekali kami terdiam, sesekali kami terharu. Kak Nata keren sekali pembawaannya. Setelah bermonolog, mulailah diisi oleh peran-peran yang lain. Ada tiruan kuda, seorang pria dewasa—yang meminang kak Nata, ada Rama, suasana saat peperangan, tembak menembak, saling bertarung satu sama lain.
Jadi, ceritanya dia adalah seorang perempuan di zaman dahulu yang harus menikah terpaksa. Melepas mimpi besarnya yang ingin menjadi seorang wanita handal panahan dan berkuda. Orang tua wanita itu tidak setuju, tetap memaksa menikah. Alasannya klasik, bertentangan dengan kodrat wanita. Yang diakhiri, si wanita ini mati dengan memegang panah, untuk mengusir penjajah yang semena-mena pada wanita. Mimpinya terwujud dalam satu detik di ambang kematiannya.
Standing aplouse dari tamu VIP. Aku ikut berdiri, bertepuk tangan. Tidak kaleng-kaleng memang. Pantas, kak Nata juara tingkat Nasional, bertemu langsung pak Presiden. Kak Nata memberi hormat dengan anggun, tersenyum ke setiap penonton. Termasuk tersenyum ke arahku dan Ruki.
Sesudah pentas, mantan tim lomba Jumbara sepakat berkumpul di kedai kecil milik salah satu tim. Kedai makanan khas Jepang. Aku bersalaman ‘khas anggota PMR’ satu persatu. Semuanya sudah berubah, raut muka yang tidak polos lagi. Tim tidak lengkap juga sih, karena ada yang melanjutkan kuliah di luar provinsi.
“May, kok, kamu cakep sekarang?” celetuk salah satu cowok berambut kribo.
“Bilang aja kamu naksir, woi!” seru teman sebelahnya.
“WUUU! Playboy akut!” sorak yang lain sambil menyorong kepala si cowok kepala kribo itu. Aku menanggapinya dengan tersenyum.
“Kak Damay, mau tanya-tanya sikap seseorang apakah mencintai kita enggak, Ayolah!” rengek adik kelas—yang dulu meminta maaf saat lomba.
Aku menggeleng. “ENGGAK! Aku bukan dukun!”
Dia merengut sebal. Memakan takoyaki sampai pipinya penuh.
“Uhuy, May, itu anggota PMR baru, ya? Cakep juga!” celetuk cowok berambut kribo itu lagi.
Ruki melotot. “Aku sekelas sama kamu tahu, awas aja!”
“Uhuy, sekelas, jodoh memang tak akan ke mana!” jawabnya.
“HUU, SADAR YA! Dasar buaya kingkong!” seru teman-temannya melembar kemasan.
“Heh, jangan mentang-mentang kalian temanku, buang sampah sembarang. Ayo, segera punguti sampah kalian!” Si pemilik kedai berseru galak.
Kami bercengkrama, termasuk Ruki—dia anak yang mudah berbaur. Bercerita masa lalu saat kegiatan PMR, masa-masa SMA, masa-masa konyol, bahkan cerita soal aku mengundurkan diri dari Pramuka tidak pernah terlupakan.
“Widiw, nggosip apa, nih?” seseorang merangkulku dan Ruki dari belakang.
“KAK NATA!” seru salah satu anggota.
“Jangan heboh gitu, dong, ketemu artis,” canda kak Nata. Pakaiannya sudah berubah, tidak memakai kemben.
Cowok-cowok merapat ke meja kami. Soal pemimpin, memang kak Nata pemenangnya. Lah, buktinya kak Nata datang saja mereka langsung merubung tanpa disuruh.
“Artis sekarang kamu ya, Nat!” celetuk salah satu cowok.
“Jam terbang tinggi, mari kita diskusi perihal penting.” Kak Nata mulai ‘aktingnya’.
“Bubar, yok, bubar!” canda salah satu cewek.
Aku tertawa perlahan. Kak Nata apalagi. Tawanya selalu menyenangkan. Kami mulai bercengkrama. Lebih banyak mewancarai kak Nata. Mulai, bagaimana kuliah di bidang kesenian? Karier ke depannya, bagaimana bisa kenal dengan seniman level atas, dan soal acara malam ini.
Kak Nata menoleh ke kanan dan ke kiri. Melongok ke segala arah. “Oh, iya, ngomong-ngomong bule dadakan udah datang?” tanya kak Nata.
Aku menoleh ke Kak Nata.
Kak Nata mengerlingkan mata ke Ruki, “Kamu pasti tahu kan, Ki?”
Ruki tampak berpikir sejenak. Matanya membulat. “Serius, Kak?”
Kak Nata mengangguk mantap. Aku mengangkat satu alis. Mengkode ke teman-teman lain. Jawaban mereka hanya mengangkat bahu. Seketika, aku terpikirkan satu nama.
“Halo, aku telat nggak, nih?”
Aku menoleh ke belakang. Suara yang sudah menghilang empat tahun ini.
Eno kembali.
Sumpah, perawakannya berbeda jauh dibanding saat dia sekolah. Tingginya bertambah, kulitnya putih bersih—sebenarnya kulit Eno aslinya putih, tapi makin putih karena pengaruh suhu di luar negeri dingin, badanya tegap gagah, dan penampilannya keren. Bila disandingkan dengan aktor Indonesia, dia hampir sama dengan Darius Sinathria. Malah, tampan Eno.
Sejak pertemuan malam itu, awal-awal kami memang canggung. Kak Nata dan Ruki berperan sangat besar di sini. Mereka pintar membaur, membuat suasana lebih menyenangkan. Termasuk, membuatku bisa ngobrol dengan Eno. Kami perlahan tertawa bersama, sesekali meledek satu sama lain.
Setelah perkumpulan tim, Eno mengajakku dan Ruki—Kak Nata sebenarnya diajak, tapi ya, tau sendirilah jam terbang tinggi, ke titik nol kilometer Malioboro. Kami menggunakan mobil Eno. Kendaraan membelah jalanan malam Yogyakarta.
“Aku rindu kota ini,” gumam Eno. Dia tersenyum lebar, tetap fokus mengendarai mobil.
“Di Denmark ada kota aestetik nggak, No?” tanya Ruki.
“Ada, tapi lebih unik Yogyakarta, kok!” jawabnya sambil terkekeh.
Aku menatap ke luar jendela mobil. Kelap-kelip lampu kendaraan tampak menggerumbul.
“Ada manusia pelamun, nih?” Eno nyeletuk.
“Biasa, No. Dia emang kaya gitu. Kesurupan hantu indie,” celetuk Ruki.
Aku melotot ke Ruki. “Enak aja! Keren tau kelap-kelip lampunya!”
“Kalau kamu ke Denmark, di sana ada danau yang berhiaskan kelap-kelip lampu kuning. Cantik.”
“Siapa yang cantik, No?”
Eno terdiam sejenak. Lantas tertawa. “Lampu-lampunya, Ruki.”
Mobil berbelok, memposisikan untuk parkir. Kami keluar dari mobil, lantas berjalan menuju ke titik nol kilometer. Ramai. Banyak manusia-manusia berlomba foto demi mendapatkan posisi antik.
“Eh, beli gembus dulu buat cemilan di sana!” seru Eno.
“Bukan main. Eno, seorang cowok keren yang kendaraannya mobil, pengennya makan gembus di pinggiran jalan Malioboro,” ledek Ruki. Eno dan aku tertawa kecil.
“Ya, emang salah? Gembus menurutku enak, kok. Gak seru kalau cuma di restaurant. Kamu hanya duduk, mendengarkan lagu, lantas menikmati makanan. Selesai. Kalau di pinggir jalan, kamu bisa menikmati suasannya, banyak sudut pandang, enak, murah lagi!” jawab Eno dengan terkekeh. Selalu, hatinya rendah hati dan lembut.
Setelah membeli gembus, kami duduk di trotoar langsung. Dibersihkan dulu memakai daun. Sesi mengobrol dimulai.
“Eh, kamu sementara di sini atau lama, No?” tanyaku.
“Belum tahu juga, May,” jawabnya sambil menikmati gembusnya.
“Kamu udah lulus berarti, No?” tanya Ruki.
Eno mengangguk. “Aku kembali karena rindu. Dan ingin berkunjung ke dua tempat.”
“Aku tebak. Pasti sekolahan?” Ruki terkekeh.
“Salah,” jawab Eno nyengir.
“UKS?”
“Lah, kan, UKS di sekolah?” tanya balik Eno.
“Oh, iya, tempat kemah Jumbara?”
“Bukan,” jawabnya terkekeh.
Ruki mendengus kesal. “Jangan bilang sungai yang banyak sampah popoknya itu?”
Eno tertawa. Mengangguk perlahan. “Itu salah satunya.”
Ruki menatap Eno tidak percaya. “Bisa-bisanya, No? Aku aja nggak mau kalau diajak lagi ke sana. Enggak mau membersihkan popok-popok, iyuh!”
Aku tertawa melihat ekspresi Ruki. Eno apalagi, langsung tertawa keras.
“Aku tebak, tempat satunya lagi pasti Toko Bunga Kapem. Betul?” tanyaku.
Eno menatapku. Tersenyum lebar. “Betul!”
Aku menghela napas pelan. “Kita tidak akan pernah bisa kesana lagi, No.”
“Why?” Muka Eno kaget.
“Setelah lulus SMA, aku berniat ke sana untuk mengucapkan terima kasih. Tapi, saat aku tiba di sana, bangunan toko bunga berganti jadi toko kelontong. Tanpa bekas dan jejak. Toko Kapem telah dijual.”
Eno menghela napas panjang. “Padahal, aku sedikit tahu soal cerita dongeng-dongeng itu.”
Aku dan Ruki menatap Eno bersamaan. “Serius, No?”
Eno mengangguk. “Tulisan mereka sederhana dan filosofis. Aku selalu kepikiran. Saat kuliah, aku memberanikan diri bertanya pada temanku, dosenku, atau ahli yang berhubungan dengan filsafat. Ternyata, itu menunjukkan suatu tempat.”
Aku dan Ruki menghela napas keras. Andai, toko itu masih ada. Pasti kami bertiga langsung lari ke sana, menebak, dan menunggu jawaban dari pak Satu soal cerita-cerita dongeng itu.
“Besok, maukah kalian menemaniku ke sungai itu?”
Aku mengangguk. Ruki menggumam.
***
Ruki sibuk, ada dua kemungkinan. Dia datang terlambat atau tidak sama sekali.
Sungai masih tetap bersih. Relawan Penjaga Sungai pandai membujuk dan mengajak warga sekitar untuk ikut menjaga kebersihan sungai. Saat masa kuliah, aku tetap ikut komunitas ini. Sebulan sekali rutin, yang pada akhirnya aku diangkat menjadi salah satu anggota tetap.
Relawan Penjaga Sungai (PJS) tidak hanya satu fokus pada satu daerah. Komunitas akan fokus ke sungai-sungai yang tidak bersih dan memang ‘layak’ mendapat penanganan. Sekitar sebulan sekali kami akan keliling ke sudut-sudut Yogyakarta, sepakat dengan daerah tersebut, lalu akan dilakukan pembinaan selama sebulan.
Daerah yang pertama kali aku, Ruki, dan Eno datang saat SMA, sudah dikatakan berhasil dalam pembinaan. Bahkan, pemuda di lingkungan sekitar sungai membuat perkumpulan pembersihan sungai, melanjutkan dari RJS. Hari ini, kami berkunjung ke sungai itu dengan naik angkot dan berjalan kaki. Eno tidak tertarik membawa mobil. Dia yang memberi usulan. Katanya, lebih menyenangkan daripada mobil. Banyak sudut pandang,. Selalu saja, dia membahas soal ‘banyak sudut pandang’.
Sesudah melewati jembatan, Eno berhenti sejenak. Aku juga ikut berhenti. Ada segerombolan anak-anak tanggung—mungkin berumur sepuluh tahun, menatap kami. Sepertinya, Eno yang menjadi pusat perhatian—terkadang, aku mampir ke sini.
“K-kak, Eno?” tanya salah satu di antara mereka. Anak perempuan berambut pendek.
Eno tersenyum lebar. “Wah, kalian sudah besar sekarang?”
“Kak, Eno jahat banget enggak pernah ke sini!”
“Kak Eno, kenapa kakak enggak pamit kalau mau pergi jauh?”
“Aku kangen banget sama Kak Eno!”
Sebanyak lima anak memeluk Eno. Dia tertawa, sesekali mengusap kepala mereka satu persatu. “Maafkan Kak Eno, ya?”
Mereka tidak menjawab. Masih memeluk Eno dengan erat.
“Kak Eno, kenapa Kak Eno sekarang ganteng?” tanya salah satu anak.
“Emang dulu Kak Eno enggak ganteng?” canda Eno.
“Ganteng, tapi enggak banget.”
Aku tertawa mendengar jawaban anak itu. Eno juga. Usai acara peluk memeluk, anak-anak itu mengajak kami keliling di sekitar sungai. Eno asyik meledek dan bermain bersama anak-anak, sedangkan aku duduk bersama ibu-ibu yang menonton keseruan mereka.
“Itu Mas Eno?” tanya salah satu ibu-ibu.
Aku mengangguk. Tersenyum.
“Tampan sekali. Pacarmu, ya? Waduh, perpaduan pas. Yang satu tampan yang satu manis. Yang satu pintar bermain dengan anak-anak, yang satu galak pada anak-anak,” ledek salah satu ibu. Iya, yang galak pada anak-anak itu aku.
“Eh, itu temanmu bukan?” tanya ibu-ibu yang lain.
Aku menatap arah jari yang ditunjuk ibu-ibu. Ruki berlari tergopoh-gopoh membawa bendelan kertas. Dia langsung menghampiriku.
“Dah, Dah, May, haus, ada air?” Ruki bertanya sambil terengah.
Aku menyerahkan botol ke dia.
“Baiklah, ada kabar penting banget buat kamu!”


 lu_r_an
lu_r_an