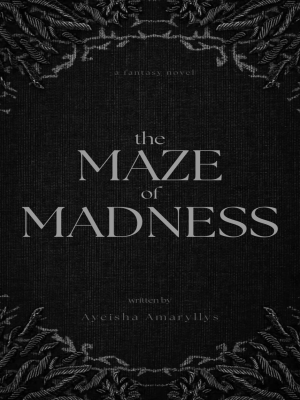Ibu memelukku erat. Tangisnya sudah habis tadi malam. Atas kabar penting yang diberitahu Ruki.
“Jaga diri baik-baik di sana, ya, Nak?” Ibu mengelus pipiku.
Aku menatap bola mata Ibu. Wajah teduh nan lelah, tapi selalu ada untukku. “Pasti, Bu!”
“Bapakmu, pasti sangat bangga di sana. Ibu yakin, kalau Bapakmu masih ada, Ibu akan kalah telak. Dia pasti mengizinkanmu pergi,” jawabnya lagi. Belum rela atas kepergianku.
Ruki mendekat. Merangkul bahu Ibu. “Tenang Tante, ada Ruki. Biarkan Damay melalang buana biar nggak kalah sama monyet.”
Ibu mulai tertawa kecil. Aku mendengus kesal pada Ruki. “Apa-apa monyet memang korbannya.”
“Kamu tak usah risau, Damay. Sesekali, nanti aku akan berkunjung ke rumah Ibumu.” Eno tersenyum lebar. Meyakinkan langkah yang kuambil.
Setelah Yudisium, Ruki membawa formulir pendaftaran. Program Pengajar Pelosok atau disingkat 3P. Satu provinsi incaranku terdaftar di dalam formulir. Saat itu juga, aku langsung mengangguk tanpa izin ibu terlebih dahulu. Bahkan, alamat surat kutujukan ke kampus.
Tibalah pengumuman. Aku lolos administrasi. Ruki membantu mengantarkanku ke Jakarta saat itu. Tentu, kami pamit pada ibu hanya pergi karena ada suatu keperluan. Mau ke perpustakaan pusat demi menunjang penelitian Ruki—serius ini tidak bohong. Berbekal uang saku seadanya dan menumpang menginap di kos teman Ruki, hasilnya membuahkan hasil. Aku lolos tahap tes. Rangking tujuh puluh dari seratus yang dibutuhkan.
Panitia memang pintar memanajemen waktu. Seusai tes, hari berikutnya langsung seleksi wawancara. Jadi, yang rumahnya jauh—termasuk aku, tidak perlu bolak-balik. Lagi, Ruki ikut membantu. Mempersiapkan daftar jawaban dan cara menjawab yang baik. Dia rela diceramahi dosen—karena saat itu, Ruki juga sedang lomba karya ilmiah. Katanya, “May, aku enggak bisa membantu apapun saat kamu curhat-curhat nangis cuma karena ada seseorang yang ada di hatimu, yang mirisnya jauh. Ini kesempatanmu!”
Seusai wawancara, kami bisa menyempatkan untuk berkunjung ke Monas dan Perpustakaan Nasional. Lumayan, sambil menyelam mampir berwisata, bersantai ria—nah, berarti aku tidak bohong pada ibu, kan? Makan kerak telor di pinggir jalan seru juga. Hampir samalah sensasi-nya saat makan angkringan di Yogyakarta.
Berkabar baik, kemarin saat apes ponselku mati, Ruki rela memohon izin dosen, hanya untuk menemuiku—padahal sedang di kampus untuk mengurus karya ilmiah sekaligus S2-nya yang dibiayai langsung oleh Dosen. Langsung ngacir mengendarai motor, padahal dia juga tidak suka mengendarai motor. Demi menyampaikan berita penting bahwa aku lolos tiga tahap. Panitia menyiapkan semua kebutuhan untuk berangkat ke Jakarta. Pelatihan tiga bulan sebelum berangkat ke tempat pengajaran.
Aku memeluk Ibu lebih erat. Ruki ikut memelukku dan Ibu. Eno menatapku sembari tersenyum. Kami melepas pelukan.
Ibu mengelus kepalaku. “Semangat, Ibu guru dadakan.” Ibu terkekeh.
“Jangan fokus ke bunga anggrek mulu, May. Makan yang tertatur, nggak usah sok-sokan seblak terus. Nggak ada juga di sana. Kamu tepar, murid bubar,” canda Ruki. Kami semua tertawa lebar.
Eno mendekat. Menatapku lamat. Tersenyum. “Aku yakin, kamu bisa bertahan di sana. Ingat, tanggung jawab utamamu adalah mengajari anak-anak. Jangan sampai kamu punya tujuan tertentu, lupa tanggung jawabmu. Siap?”
Aku mengangguk mantap. Mengacungkan jempol. “Siap banget, No.”
“Terbanglah. Selamat mendatangi pulau dan suasana baru,”
Aku mengangguk. Menghirup napas dalam, menghembuskan perlahan. Mulai berjalan meninggalkan Ibu, Ruki, dan Eno. Melambaikan tangan terakhir sebelum masuk ke boarding pass. Menarik koperku, melangkah pasti. Memegang erat kardus panjang, berisi tanaman anggrek hitam beserta potnya. Mari bertanggung jawab, mari menuju kotamu.
***
Sudah tiga jam perjalanan dari Putussibau menuju lokasi penempatan. Tiga temanku sudah beranjak di lokasi penempatan. Tinggalah aku sendiri, mendapat lokasi paling ujung di Kalimantan Barat. Kawasan yang dekat dengan hutan belantara, Hulu Sungai Kapuas, dan perbukitan.
Soal informasi Provinsi Kalimantan Barat, aku tidak perlu risau. Masih ingat dengan Ranaya? Beberapa bulan, kami mulai aktif saling berkirim pesan satu sama lain. Bertanya banyak hal kebudayaan provinsi yang kutuju, bagaimana orang-orangnya, keadaan geografisnya, dan masih banyak lagi. Itu sangat membantuku dalam hal mendalami dan mengenal daerah yang kutuju. Bahkan, Ranaya memberikan rekomendasi buku untuk kubaca sebagai salah satu pengetahuan tentang daerah itu.
Aku diantar oleh salah satu pegawai kecamatan. Bersama penumpang lain—yang prediksiku, mereka warga asli lokasi penempatan. Kami berdesakan di angkot buntung. Mereka membawa bakul-bakul dan karung yang berisi bahan pokok dan peralatan rumah tangga. Aku, yang belum pandai berbasa-basi harus mencocokkan waktu yang tepat untuk mengajak ngobrol.
“Kamu darimana kah?” sapa seorang ibu, mukanya lelah tapi terpancar kebahagiaan. Dia menepuk bahuku.
Aku tersenyum, mengangguk. “Dari Jawa, Bu.”
Pegawai kecamatan menyalami ibu-ibu tadi. “Selamat siang, Inak. Perkenalkan, anak muda ini akan jadi pengajar sekolah SD di tempat Inak selama satu tahun.”
Ibu itu tertawa keras sekali. Satu penumpang menengok ke arah kami. “Oh, seperti tahun lalu?”
Pegawai kecamatan mengangguk. “Nah, Damay. Silahkan mengobrol dengan Kakak Kepala Suku.”
Aku menelan ludah. Pantas saja wibawanya sudah terlihat. Ibu-ibu saja sudah terlihat bersahaja, apalagi nanti kepala sukunya?
“Kau tampak malu-malu,” seru ibu itu.
Aku mengulurkan tangan. Tersenyum. “Nama saya, Damaylia, Bu. Bisa dipanggil Damay.”
Ibu itu menyambut salamanku. “Banun, kau bisa panggil Inak Banun. Inak artinya Ibu.”
Aku mengangguk. Bahasa baru untukku. “Inak baru jualan di pasar?”
Dia mengangguk. “Di sini, bergantung sekali pada hasil hutan dan kebun untuk dijual. Nanti, kau akan selalu makan ikan, ikan, dan ikan,” ledek Inak Banun.
Aku tertawa kecil. Selanjutnya, Inak Banun menceritakan betapa indahnya sungai Hulu Kapuas yang berada di kawasan desanya. Aku menatap sekitar. Memang, di sini masih asri. Pepohonan masih rimbun, suara hewan hutan masih terdengar, dan udara yang begitu sejuk. Walau cuaca panas, suasana hutan sangat terasa.
Inak Banun berhenti bercerita, dia mengantuk. Mulai tertidur dengan posisi duduk—sama posisinya saat aku mengantuk di kelas. Aku tersenyum. Menatap wajah lelah Inak Banun. Mulai tersenyum pada satu-dua warga yang melihatku. Sepertinya aku harus mulai belajar basa-basi.
Pegawai kecamatan ikut tertidur di sebelah Inak Banun. Angkot buntung berjalan lambat. Kurasa, karena beban lumayan berlebih. Jalan tanjakan mulai terasa. Aku harus berpegang erat pada pinggiran angkot.
Sesampai di pinggir ‘terminal kapal motor’, kami semua turun. Benar dugaanku, mereka semua warga lokasi di desa penempatanku. Kapal motor sudah menunggu di pinggir dermaga kecil berpapan kayu. Aneh, aku tidak asing dengan pemberhentian kapal motor ini.
Aku mengamati sekitar sungai yang sangat lebar. Dua kali lipat lebarnya dari sungai yang kutemui di Yogyakarta. Arusnya deras. Di pinggiran sungai ada rimbunan pohon lagi. Seolah, pepohonan mengakui dan berdiri memberi hormat, kepada aliran Sungai Hulu Kapuas. Kapal motor merapat. Kapal yang mirip dengan kapal nelayan biasanya. Tapi, ini lebih rendah dan panjang. Satu-persatu warga mulai melangkah, duduk di kapal motor. Aku dan pegawai kecamatan memilih akhiran, mengalah pada yang lebih tua.
“Nah, ini sudah termasuk sungai. Tapi, nanti ada yang indah lagi.” Inak Banun memberitahuku.
Aku tersenyum. Dia memilih berada di dekatku. Mesin kapal mulai menderu. Dengan gaya lincah, pengemudi naik di belakang. Petualanganku berlanjut.
Sumpah, seru banget! Aku belum pernah sebelumnya naik kapal seperti ini. Apalagi, ini melawan arus. Sesekali mukaku terciprat. Aku tertawa riang. Warga ikut tertawa, mungkin menertawakan betapa bahagianya aku, padahal hanya air sungai. Entahlah, hidupku mengapa selalu berhubungan dengan sungai.
Sungai ini banyak sekali batu-batu besarnya. Jelas, pengemudi sudah hapal mati. Tau di mana yang ada batunya, di mana yang arusnya lebat, dia canggih, bisa meliukkan kapal, membuatku menjerit. Padahal, penumpang lain biasa saja.
Lagi, semakin masuk ke dalam, hutan semakin rapat. Pepohonan mulai meninggi. Bahkan, kalau aku tidak salah lihat, sesekali mendengar lolongan orang utan. Jadi, diibaratkan, sungai inilah yang membelah belantara hutan. Kamu melaju, maka di pinggiran sungai penuh dengan pepohonan yang rindang.
Air sungai Kapuas memang sedikit keruh. Berwarna cokelat muda. Penjelasan Inak Banun, saat musim penghujan memang seperti ini. Tapi, saat nanti tiba di tempat lokasi, warna sungai berubah. Lebih jernih, bahkan bisa mandi di sana. Aku belum pernah mandi di sungai, kecuali saat terseret.
Saat naik kapal, aku teringat dia lagi. Apakah, seperti ini rasanya saat dia masuk ke pedalaman memberikan kesehatan gratis? Saat aku scroll Wacebook-nya, setahun lalu, dia mengunggah foto bersama orang lainnya—sepertinya itu warga asli penduduk sana, di atas kapal. Dia menuliskan, akan segera ke tempat pelosok. Aku tersenyum lebar.
Kapal motor merapat di ‘dermaga’ berpapan kayu. Aku melongok ke jam tangan. Enam jam perjalanan dari ‘dermaga’ pertama. Total perjalanan, apabila mau ke kota sekitar sembilan jam. Bukan main.
Senja tersemburat. Aku masih duduk di kapal. Melihat bahu dan hati kokoh para warga. Menciptakan bayangan, antara semburat senja dan siluet. Kalau bisa menggambar, kugambarkan sudah suasana luar biasa yang tercipta. Mereka tidak mengeluh. Bahkan, saling dorong, tertawa satu sama lain.
Eh, tunggu.
Aku melihat siluet bayangan lumayan banyak. Seperti bayangan badan pria. Eh, apakah aku salah? Mungkin ada satu, dua, oi, sepuluh orang?
Pegawai kecamatan menepuk bahuku. “Kau sudah disambut, Damay.”
Aku menatap pegawai kecamatan dalam remang senja. Tidak mengerti.
“SELAMAT DATANG, Ibu Damaylia!” suara besar dan penuh wibawa mengumandang.


 lu_r_an
lu_r_an