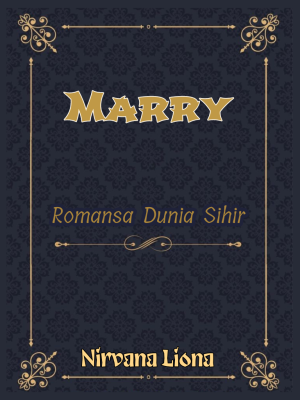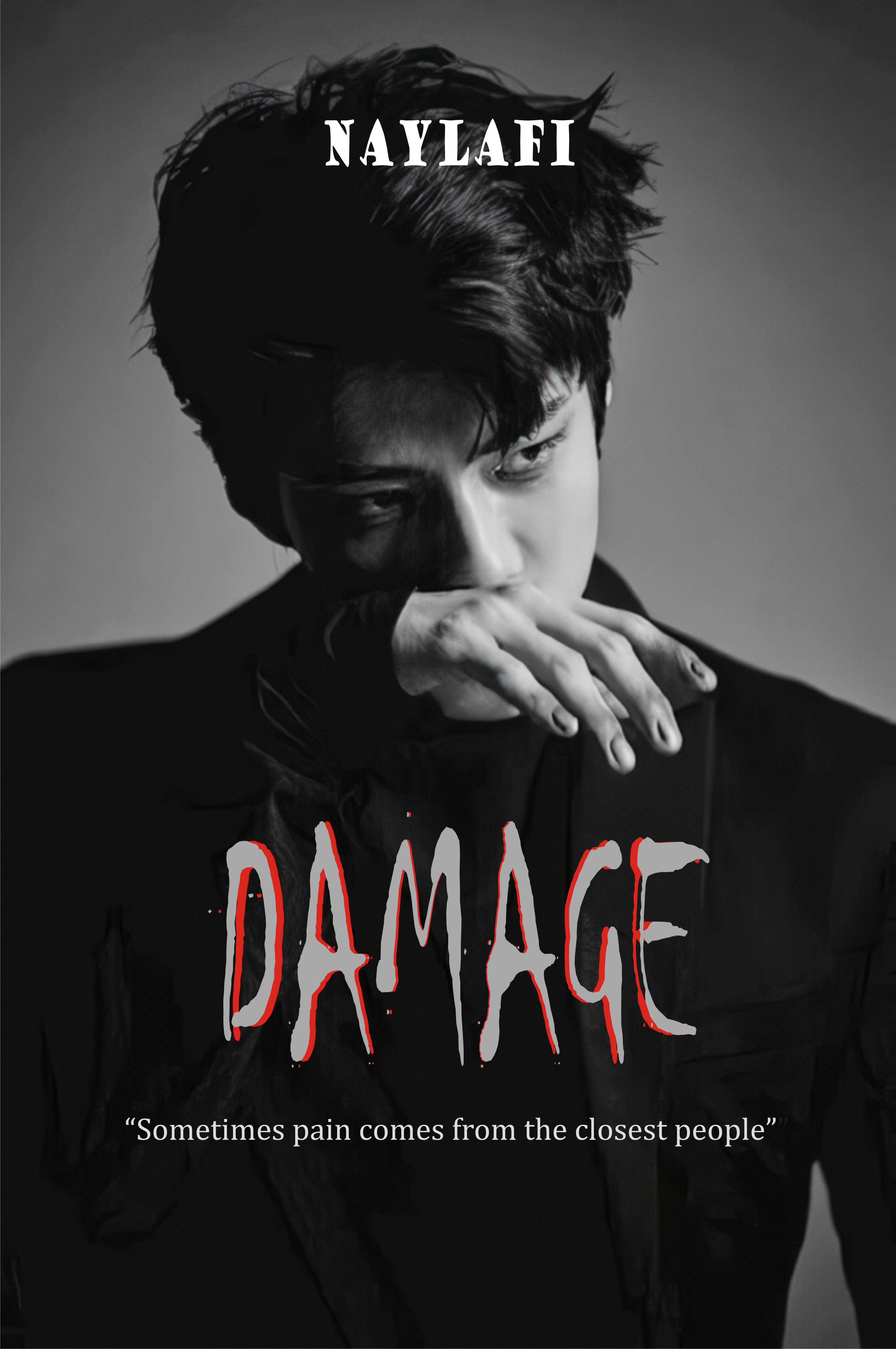Di dalam kamar yang nyaman.
Kertas penuh coretan. Pulpen hitam dan merah sebagai penari di atas kertas. Dan seseorang manusia aneh sedang memaksakan diri membuat puisi. Jelas, manusia aneh itu aku. Menatap coretan aneh itu, aku mendengus. Jelek banget setiap diksinya. Lagi, kucoba menulis lagi.
“Di sendumu aku melihat ….” Aku mencoret tulisanku. Mulai menulis lagi.
“Di senjamu aku berteduh ….” Aku mencoret lagi.
Aku menghela napas, mencoba menulis lagi.
“Air beriak tanda tak dalam ….” Eh? Kok jadi peribahasa?
Aku beranjak dari kursi, ambruk terlentang di atas kasur. Menatap langit-langit kamar. Ternyata, menulis itu tidak segampang yang aku pikirkan. Dari zaman bahuela sampai sekarang, keterampilan menulisku memang selalu pas-pasan. Mepet KKM.
Aku tidak seambisius itu. Ada alasan, aku berusaha mencoba menulis. Ada rahasianya. Karena puisi paling pendek, jadi kupilih saja tanpa pikir panjang. Kalian ingin tahu? Berawal dari sosial media.
Sepulang dari menonton, terdiam menatap langit-langit kamar—seperti sekarang. Aku memandang tanda pengenalnya. Terlintas ide untuk mencoba menemukan sosial medianya. Aku berdiri, mengambil ponsel yang biasanya hanya aku pakai untuk mendengarkan lagu. Membuka salah satu media sosial, Antagram.
Search: Alfian Firdaus.
Aku menelan ludah. Jari telunjukku bergetar. Menarik napas dalam, mengeluarkan perlahan.
Klik!
Nah, kalau kalian ingin melihat orang kurang kerjaan mencari ratusan nama yang sama di media sosial demi tahu media sosialnya, akulah orangnya. Tidak mudah mencari dia. Satu nama, aku klik, menatap fokus mencari identitas yang mudah dikenali. Fotonya. Namun, nihil. Tak ada foto profilnya. Tidak menyerah, kucari lagi sampai ke seluk beluk ke foto yang ditandai.
Satu jam kemudian.
Aku melemaskan jari. Masih fokus ke layar ponsel. Sudah ada sekitar dua puluh lima nama sudah kutelusuri. Nihil, belum ada.
Dua jam kemudian.
Piring makan malam ada di meja belajar. Aku tetap fokus mencari namanya. Sekitar lima puluh nama sudah kutelusuri. Nihil.
Tiga jam kemudian.
Mulut penuh remahan roti. Aku mengunyah sampai pipi menggelembung, tetap mencari. Benar-benar susah mencari sosial medianya. Sekitar seratus nama sudah kutelusuri. Sama saja. Aku meletakkan ponsel sejenak. Memijat mata yang blereng melihat tulisan. Menghela napas keras. Keras kepala sekali diriku. Bisa jadi, kan, dia bukan tipikal orang yang suka ber-medsos ria? Gugur sudah harapan untuk tahu asalnya.
Sebentar ....
Bukankah dia calon dokter? Okey, umurku sekarang enam belas tahun dan perkiraan dia berumur— aku menghitung menggunakan jari. Mungkin sekitaran dua puluh dua tahun. Aku menelan ludah. Berarti saat aku lahir, dia sudah kelas satu SD? Saat aku kelas satu SD, dia sudah kelas satu SMP? Oi, gila betul kamu Damay.
Yang masih menjadi pertanyaanku adalah: mengapa jantungku berdegup cepat? Padahal baru bertemu pertama kali. Semua tampak klise. Warm. Lembut. Dan dia berlari melambat ke arahku—walau sebenarnya dia fokus ke Ranaya. Matanya bening, menatap tulus.
Apa itu yang namanya jatuh cinta pada pandangan pertama?
Dia memang cukup tampan. Tapi kalau dibandingkan Eno, yang setiap hari berusaha mendekati, sampai rela berpanas ria menonton festival, memberiku minuman sari jeruk, bahkan mau menemani membeli buku, kurasa Eno pemenangnya. Dengan postur yang tinggi, anak ekskul sepak bola, ditambah dia satu kelompok dengan Ruki di ekskul KIR, lengkap sudah. Pintar, baik hati, tidak sombong, rajin memberi makanan untukku—serius ini, dia selalu memberi setengah jatah untukku.
Apakah Ruki bisa menjawab kebingunganku ini?
Aku menggaruk kepala. Mana mungkin dia paham? Yang dia paham spesies tumbuhan apalah, atau memotong daun di sampah lah, membawa jambu busuk lah, membawa katak untuk dibelah lah, dan lah lah lainnya. Ya, masa aku bertanya soal perasaan, nanti jawabannya, “Sini, aku teliti, tapi hatimu dibelah dulu pakai pisau bedah. Pasti aku kaji secepatnya.”
Buruk.
Baiklah. Aku beralih mencari namanya bukan di Antagram lagi, melainkan di salah satu media sosial yang memang sudah sejak lama tercipta—sejak aku SD sudah ada. Wacebook.
Search: Alfian Firdaus
Aku menghela napas pelan. Semoga ada.
Klik!
Masih sama, banyak deretan nama yang persis. Namun, tidak sulit kali ini. Deretan ketiga dari atas, aku menemukannya dengan foto profil asli. Menyelidiki sampai dalam. Tersenyum tipis.
Akhirnya aku tahu media sosial dan tempat tinggal asalnya.
***
Bel istirahat
Jaket menutupi kepalaku, memutuskan untuk tidur. Tadi malam, mataku baru bisa terpejam pukul empat pagi. Sial. Imbasnya, aku terlambat dan harus dihukum memunguti daun-daun di sekitaran gerbang. Hukuman telat selesai, urusan lain belum selesai.
Satu jam pertama, guru sejarah killer—tapi aku tetap suka sejarah menyuruh maju ke depan untuk ulangan lisan, biasanya aku bisa menjawab semua pertanyaan. Kali ini gagal. Hanya betul delapan. Gugup dan lelah adalah alas an paling masuk akal.
Satu jam sebelum istirahat, kesialan berlanjut. Pelajaran Matematika. Menyebalkan enggak, sih, kalian masuk jurusan IPS untuk menghindari atas nama matematian—plesetan Matematika, eh, bertemu lagi. Guru Matematika di jurusanku sebenarnya menyenangkan, terkadang bercerita perihal yang belum kita tahu. Namanya saja Damaylia. Mau seserius apapun belajar, pasti selalu remidi. Sudah biasa rapotnya atas nama Matematika selalu diambang KKM.
Sudah tahu seperti itu, aku datang kesiangan, dapat bangku paling depan, persis di depan meja guru. Ditambah materi ini sangat aku hindari.
Tahu pelajaran limit, kan?
Iya, materi paling susah, paling memuakkan, paling aneh. Lah, coba kalian bayangkan, kenapa harus dibuktikan dengan panjang sekali seperti jarakku dengannya (eh?) padahal sudah jelas jawabannya seperti itu. Ambigu. Sialnya, aku tertidur saat pelajaran limit. Mejaku diketuk oleh guru—panggil saja pak Dadang menyuruhku maju mengerjakan soal limit. Mukaku cengok. Tidak tahu apa-apa.
Jurus andalan: nyengir.
Alhasil, aku dihukum mengerjakan PR dua kali lipat daripada yang lain. Mereka cuma cekikikan, meledek, bahkan ada yang memberikan jaket di kepalaku.
“Tidur May, jangan kencan sama Eno mulu!” Ketua kelas meletakkan jaket di kepala.
Aku meliriknya. Ketua kelas, kok, pintar gossip. Enggak benar lagi
“CIE ... uhuy, pasangan baru, nih!” Geng ciwi-ciwi kompak banget kalau soal gossip.
Aku menghela napas, mengangkat bahu. Terserahlah. Mulai melakukan ritual tidur.
“DAMAYLIA ….” teriak Ruki dengan suara lengkingannya itu.
Aku menjerit lirih dalam hati. RUKI SIALAN!
“Oi, Damay, ngapain tidur? Temani aku ke perpustakaan, dong, bawain buku, kek!”
Aku semakin menutup kepalaku dengan jaket. “Ruki, aku mau tidur, nanti setelah istirahat ada pelajaran Ekonomi, gawat kalau aku tidur lagi!”
“Kok, kamu gitu sama teman sendiri?” Ruki merajuk. Menarik-narik lenganku agar bangun.
“Kan, aku bukan tim KIR, kamu minta bantuan sama Eno sa—”
“CIE ..., Damay ingat Eno lagi?”
Aku menghela napas keras. Bangun, membuka jaket ke belakang, melotot ke ciwi-ciwi manja mania itu. Mereka lalu terdiam, sok sibuk mengobrol lagi. Ya, apalagi kalau bukan gossip.
“Iya, iya, iyaa, IYA aku temani!” seruku sebal.
Ruki tersenyum lebar. “Nah, gitu, dong! Eno juga ikut, loh!”
Aku melotot. Lantas kenapa dia mengajakku? Sebelum ciwi-ciwi mulai meledek lagi, aku sudah melotot ke mereka.
“Galak banget kamu, May, bisa-bisanya Eno suka sama cewek galak kaya kamu!” Salah satu geng ciwi-ciwi berseru meledek. Aku tahu itu becanda.
“Iri? Bilang bos!” sahut Ruki. Mereka tertawa bersama.
Aku memutar bola mata, beranjak lesu.
Ruki menggaet lenganku. “Yuk!”
Nyawaku belum komplit sebenarnya. Beberapa langkah dari kelas, mataku mulai membuka perlahan. Berhenti sejenak. Menatap tertegun ke depan. Musim ‘gugur’ itu datang. Biasanya, sekolah itu terdiri lorong-lorong dengan ada atap kanopi di atasnya. Sekolah kami unik. Saat musim ‘gugur’ atap otomatis ‘masuk’. Penggantinya pohon-pohon rambat markisa sebagai peneduh. Di sisi pinggir pohon rambat markisa, ada berbagai macam bunga dengan pot semen kokoh. Melati paling dominan. Kalau hujan, kanopi otomatis ‘keluar’ kembali. Canggih yang tidak fenomenal. Lantas, apa yang fenomenal?
Saat gugur daun kekuningan itulah yang paling fenomenal.
Kita seolah berjalan dengan tebaran daun yang menguning di bawahnya. Saat musim itu kita akan menemui para cewek sibuk selfi, kita menonton seolah dia pemain filmnya. Ada yang bengong, melihat daun-daun berguguruan. Mungkin, menghitungnya satu-satu. Ada juga yang bahkan bersih-bersih—biasanya anak pecinta alam. Kalau aku dan Ruki cukup menikmati saja.
Perpustakaan juga cukup unik. Entahlah, siapa arsitek di balik ini. Ada minuman boba di dalam perpustakaan. Serius. Dinding depan berbahan kaca bening, lengkap dengan tempat duduk bak cafe di dalamnya, ya walau menunya hanya minuman boba. Sekitar lima meter ke belakang, ada rak khusus koran, majalah, dan tabloid harian. Jadi, kalau kalian menemui para guru membaca duduk santai saat istirahat sembari menikmati kopi, itu sudah biasa.
Masuk sekitar tiga meter, ada lorong kecil yang tembus ke ruangan selanjutnya. Ruangan dengan buku yang super lengkap, duduk lesehan, ditambah AC. Kalau aku mengantuk, kadang pura-pura membaca lantas tertidur di ruangan itu.
Eno sudah menunggu di ruangan depan sembari membaca koran. Mendongak, melambaikan tangan. “Eh, Damay ikut?” sapanya ramah.
Aku tersenyum sekenanya.
“Aku sama Eno nyari buku dulu, ye? Kamu duduk terserah, eh, atau kamu yang mau bantu?”
Aku menggeleng. Kesempatan bagus untuk melanjutkan pikiranku yang buntu tadi malam.
“Jangan panas, loh, ya?” Ruki mengerling. Muka Eno merona.
Aku tidak menggubris, langsung menuju rak buku khusus karya sastra. Macam-macam jenisnya. Ada novel, kumpulan cerpen, teori sastra, kumpulan puisi, anekdot, dan masih banyak lagi. Aku mengambil buku bersampul putih dengan cover pohon linden warna-warni. Kumpulan sajak.
Play on: Letter from the Forest by Depapepe.
Aku menarik napas, menghembuskan perlahan. Membaca sedikit demi sedikit. Asli, sih, ini tulisannya unik. Dia tidak berjibaku soal puisi yang harus penuh diksi, penuh analogi, perumpamaan, kata-kata baku yang sulit. Mengalir saja. Magis-nya, bisa membuatku trenyuh sampai ke hati.
Aku mengangguk, mengambil kertas terlipat rapi dari saku. Membaca ulang puisi yang kutulis. Kesannya terlalu memaksa memang. Karena yang kutahu, ya, puisi itu penuh kata-kata mujarab yang aduhai permai nian. Penuh metafora, personifikasi, ya, begitulah. Ternyata tidak juga.
Apapun yang kamu tulis, kalau memang dari hati akan sampai ke hati.
Mukaku mulai merona. Eh? Kenapa tiba-tiba aku teringat status yang dia buat di Wacebook?
Iya, saat itu juga aku langsung stalker apapun yang dia tulis di dinding Wacebook. Ada salah satu status yang membuatku tertarik. Ternyata dia suka menulis artikel kesehatan dan perjalanannya dalam memberikan edukasi kesehatan.
Saya itu tak pandai menulis. Dari berbagai tulisan, saya yakin tulisan yang saya buat masih awam, masih mentah, bahkan mungkin juga tidak layak dibaca. Sayangnya, tujuan tulisan saya bisa tersebar untuk kebermanfaatan. Seseorang bisa membaca tulisan saya dan menjadi tahu bahwa kesehatan itu penting.
Keren.
Entah kekuatan magis apa, aku jadi tertarik untuk mencoba menulis. Ya, jelas bukan artikel kesehatan, mana kutahu soal begituan, bukan bidangku. Mulai dari yang kecil dulu. Tahu sendiri, aku sendiri kesusahan soal tulis menulis, yang aku sendiri selalu nilai pas-pasan untuk soal perpuisian.
Mencoba hal baru dengan berani keluar dari zona nyaman, itu keren. Kamu akan dapat belajar banyak hal.
Sumpah, dia lebih pantas menjadi penulis daripada dokter. Baiklah, dia dokter oke, penulis oke, tampan oke, eh? Aku menggelengkan kepala. Fokus Damay, fokus!
Aku mulai membaca buku lagi. Manggut-manggut. Menatap ke luar jendela. Manggut-manggut. Mulai menuliskan sesuatu di kertas.
“Nulis apaan?” tanya Ruki. Dia membawa tumpukan buku. Eno menyusul di samping Ruki. Sama, membawa tumpukan buku.
Aku mengangkat bahu. Menyembunyikan tulisanku.
“Apaan, sih?” Ruki menyerahkan tumpukan buku ke Eno, membuat Eno agak terhuyung ke belakang.
“Kepo!”
Ruki menarik lenganku, mencoba merebut kertas puisiku. Aku beranjak, bersembunyi di balik badan Eno. Ruki tetap berusaha mengambil.
“Aku, kan, sahabatmu, May. Jadi, aku harus tahu dong!”
“Belum jadi, oi!” teriakku sambil berusaha mengambil kertas coretan puisiku. Bisa gawat kalau Ruki, si pintar analisis tahu soal yang kurasakan akhir-akhir ini. Terlebih, kalau soal 'Dia'.
Kami saling berkelit, membuat Eno hilang keseimbangan, sudah berat membawa buku, ditambah perseteruan kami, membuatnya limbung.
BRAK! Sudah jatuh, tertimpa buku pula. Eno rekornya.
Aku dan Ruki menatapnya bersamaan. “ENO!”
Kami berusaha membantu menyingkirkan buku. Dia mengaduh kesakitan di pinggang.
“No, kamu gapapa kan?” Aku bertanya cemas.
Muka Eno merona lagi. Meringis sembari mengelus pantatnya. “Gakpapa, kok!”
Ruki mana peduli. Dia langsung merebut kertas puisiku. “Widiwaw, puisi!”
Aku tidak menggubrisnya, membantu Eno berdiri.
“Kembaliin!” ketusku.
Ruki merapikan rambut. Mengulurkan tangan ke depan. Berdeham keras. “Jauh ….”
Sialan. Dia malah mau membacakan di perpustakaan. Aku berusaha mengambil, tapi dia pintar berkelit.
“Aku tidak bisa bicara. Itu karenamu ….”
“Aku tidak bisa berkedip. Itu karenamu ….”
“Aku tak bisa tertidur pulas. Itu karenamu ….”
Ruki menoleh ke arahku. Sempurna, mukaku merona.
“Oi? Apa sebegitu bucinnya kamu sama Eno?”
Aku merebut kertas itu. Kesal. Sumpah kesal banget rasanya. Kini, semua anak yang ada di perpustakaan menoleh ke arahku. Siapa yang tidak malu coba? Aku meninggalkan Ruki bergitu saja, berjalan keluar dari perpustakaan. Menuju kelas dengan hati bercampur aduk. Dasar Ruki sok tahu, sok yes, tukang kepo! Aku menghentakan kaki ke bawah. Menghela napas keras. Lagipula, siapa, sih yang suka sama Eno dalam hal perasaan?
***
Rekor, aku bisa menahan kantuk sampai pulang sekolah.
Iya, setengah hati mengikuti pelajaran, setengah hati sebal bukan main. Bukuku penuh coretan tidak jelas, bukan catatan dari guru bicara. Gampanglah, besok aku salin atau fotokopi dari catatan temanku yang paling rapi. Aku lebih fokus untuk mengendalikan emosi daripada guru yang sedang menjelaskan materi akuntansi. Terus kulakukan hingga bel pulang berbunyi.
Aku bergegas menata rapi buku dan tas. Emosi seperti ini enaknya makan es krim tung-tung yang biasa lewat. Atau sekedar membuat sandwich sederhana di rumah. Saat melewati UKS, Eno berdiri, bersandar tembok di depan ruangan. Masih libur, diberikan kelonggaran setelah perlombaan. Mulai kegiatan rutin minggu depan. Dia terus menyilangkan tangan di depan, menatap bawah. Dia menoleh, tahu aku menatapnya.
“Hai, May?” sapanya ramah.
“Sudah nggak sakit?” tanyaku, tersenyum tipis.
Dia menggeleng. Tersenyum. “Enggak, kok, kamu mau pulang?”
Aku mengangguk. Malas menjawab.
“Aku boleh—” Eno menggaruk belakang leher.
Aku menunggu Eno berkata.
“A-aku boleh mengantarmu pulang?” Muka Eno sempurna merona.
“Aku bisa sendiri, maaf, ya!” Aku melangkah pergi.
Eno menjajariku berjalan. “B-bukan, aku ingin bicara soal Ruki—”
Aku melotot padanya. Dia menelan ludah. Menggaruk kepala.
“Aku mau pulang!” seruku.
Eno tetap berjalan menjajariku. Dia pantang menyerah.
“Kamu itu bawa motor, ngapain ikut mau naik angkot!” seruku galak.
“Ya, makanya dengerin aku dulu!” Eno memberi penawaran.
“Loh? Memang itu urusanmu? Bukan, kan?”
“Iya emang bukan urusanku, tapi—” Eno menghela napas pelan.
Sopir angkot menungguku naik. Aku melambaikan tangan, tidak jadi naik. Menunggu Eno berkata lagi. Gawat kalau dia nekat ikut di belakang angkot.
“Masa, sih, cuma karena soal perpuisian, kamu semarah itu ke Ruki?” Eno berusaha mencegahku untuk pergi. Dia benar-benar serius untuk membicarakan soal Ruki.
Aku diam. Menatap tajam Eno. “Dia membaca puisiku keras, No! Itu ,kan, privasi dan aku sampai dilihat teman-teman di perpus. Malu!”
“Iya, aku tahu, tapi Ruki, kan, emang iseng anaknya dari dulu?” bela Eno.
Aku diam. Melengos.
“Bisa aja dia membaca keras di depan teman-teman karena dia bangga sama kamu?”
Aku tidak menjawab.
“Begini, deh, aku ada usul. Menurutku, puisimu menarik. Bagaimana kalau besok aku kirimkan ke redaksi majalah sekolah?”
Aku melotot padanya.
“May, Dengarin dulu! Kamu pakai nama samaran aja. Lah, buat apa coba, kamu menulis tapi enggak dibaca orang banyak?”
Aku diam. Menatap Eno lebih bersahabat.
“Aku yakin, Ruki emang sengaja membaca puisimu lantang biar orang tahu, kamu bisa menulis puisi,” ujarnya berusaha meyakinkanku.
Aku diam tidak menjawab.
“Bagaimana?” tanya Eno menatapku lekat.
Aku menghela napas keras. “T-tapi aku mau memaafkan dia kalau memenuhi syaratku!”
Eno menggelengkan kepala. “Terserah. Terpenting kamu mau memaafkan Ruki.”
Aku diam, mengangguk perlahan. Melanjutkan berjalan menuju keluar gerbang sekolah. Di kejauhan Eno menggaruk kepala. Bingung dengan perangaiku.


 lu_r_an
lu_r_an