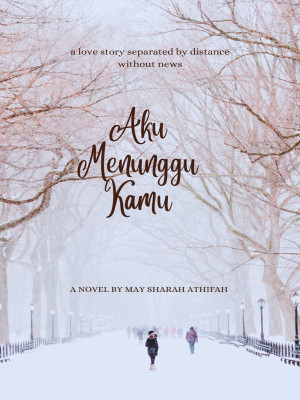Kampus menjadi rumah bagi Wanayasa, mahasiswa jurusan Teater yang sudah molor waktu wisuda selama dua tahun. Kini, ia sudah masuk ke tahun keenam kuliahnya. Memandang ke arah langit membuat Wanayasa tiba-tiba saja teringat pada sosok Sastra kecil yang membuatnya merasa ada di dunia ini. Manik mata itu mengatakan kalau ia tak takut padanya.
“Yas!” panggil seseorang dari arah kanan. Wanayasa seketika menoleh pada seorang laki-laki sebayanya.
“Eh, ada apa, Yo?” Aryono, anak jurusan Seni Murni itu menatap Wanayasa dengan tatapan cermat.
“Dicariin anak-anak Teater. Katanya mereka butuh lo!”
“Oh soal itu. Udah tau, kok. Ini gua ngampus.”
Wanayasa tersenyum kecil sambil berjalan memasuki kawasan kampus. Mengenang setiap detik percakapannya dengan Sastra, Wanayasa seperti dikembalikan pada memori yang sama ketika usianya pun sekian. Ia pernah mengatakan dengan bangganya kalau ia akan menjadi seorang aktor panggung yang hebat, ia akan pergi ke Jakarta untuk memperluas jalan karirnya, ia akan melebarkan sayapnya selebar bentangan langit. Atau kalaupun tidak bisa, ia hanya ingin jadi seorang penulis terkenal, seorang penulis naskah, seorang sutradara hebat yang memandu terciptanya sandiwara yang epik bertabur bintang.
Nahasnya, ia bahkan tak mampu menyelesaikan kuliah empat tahunnya. Malah menjadi mahasiswa lumutan yang tak memiliki prestasi apa pun selain olok-olokan dosen soal usia dan keberadaan dirinya yang membuat suasana kampus jadi sumpek. Bekerja hanya membungkus serpihan dauh teh ke dalam kantong-kantong kertas. Tidak ada yang dirinya bisa lakukan. Namun, melihat Sastra, anak laki-laki asing, iya, orang asing yang ditemuinya hanya beberapa menit saja. Wanayasa merasa diakui, ia bahkan ingin mengalahkan pandangan mata percaya dirinya kalau ia akan menggantikan perkerjaan ayahnya. Padahal, Wanayasa sendiri tidak tau pekerjaan seperti apa yang ayah anak itu lakoni.
Wanayasa memasuki sebuah ruangan kecil yang gelap, terdengar banyak suara dari dalam sana. Namun, hanya ada satu suara yang membuatnya terdiam sambil menahan perasaan takut setengah mati. Suara Pak Supandji.
“Wanayasa Wanara, ke mana saja kamu? Tumben sekali tidak ngampus, biasanya ngalor-ngidul di kampus. Sudah tidak menganggap kampus sebagai rumah lagi, nih?” desak Supandji menyentuh bahu Wanayasa.
“Eh, Bapak. Seminggu ini saya sibuk mendiskusikan teh ke berbagai angkringan. Nggak ada waktu buat ngampus,” balas Wanayasa dengan senyuman kecut.
“Kamu sudah membaca surat dari pihak kampus?”
“Sudah. Ini saya datang untuk menandatangani surat itu.”
Dada Wanayasa menyempit, tidak lagi ada rasa hormat pada dunia. Semuanya selalu mencekik. Wanayasa sadar diri kalau ia memang telah membuat kampus jadi sumpek. Namun, haruskan … haruskan dunia mengucilkan dirinya? Bukan, lebih tepatnya ia yang mengucilkan dunia di atas dunianya.
“Kamu yakin? Kamu tidak akan berargumen dulu soal projek-projek barumu bersama anak-anak teater yang lainnya, Wana?”
“Nggak, Pak. Saya memang sejak semester dua berniat meninggalkan kampus. Sayangnya, saat itu saya masih terikat kepengurusan HIMA karena anggotanya sedikit.”
“Masih ada satu tahun lagi … untukmu menyelesaikan kuliah, Wana. Kamu harus menyelesaikannya.”
“Nggak perlu, saya merasa kalau mengerjakan sesuatu yang nggak kita sukai, hanya buang-buang waktu dan tenaga.” Wanayasa melengos tanpa senyuman, ia bahkan tidak mengindahkan apa pun di balik punggungnya. Meski mereka menganggil namanya.
Jogjakarta terlalu terik, es teh di kantong plastik yang besarnya hampir sepenuhnya wajah Sastra itu tak urung membuat dahaga enyah. Di samping Dimas, anak tukang roti kukus di depan sekolah itu, Sastra sibuk memikirkan Wanayasa. Sosok mas-mas misterius yang membuat dirinya penasaran dan ingin cepat-cepat jadi dewasa.
“Dim, katanya menjadi orang dewasa itu bikin gila!” seru Sastra menyeruput sedotan sampai pipinya kempis.
“Memang, Mas Parlan bilang padaku kalau menjadi anak SMA itu capek, Sastra. Soalnya banyak tugas!”
“Mas-mu tahun ini lulus, ya? Mau kuliah?” cicit Sastra mendadak cengengesan.
Dimas menggulirkan kedua manik mata hitamnya yang belo sempurna. Teman sekelas Sastra itu mengangkat bahunya dengan cepat. “Nggak akan katanya, mau kerja di rumah aja bantuin Ibu dan Bapak ngadon roti!”
Bibir Sastra membuat dengan sempurna. Ia kembali menyeruput sedotannya sampai semua isi kantong plastik minumannya habis tak bersisa. “Kenapa? Mas Parlan bukannya selalu juara umum, ya? Bukannya dia juga kemarin baru lolos sepuluh besar kompetisi duta bahasa Indonesia?” tanya Sastra kepo.
Dimas manyun dengan sempurna. “Aku nggak tau, kata Mas kuliah itu capek, teman-temannya juga begitulah … Mas bilang kalau dia mau kuliah saat nanti siap. Sekarang belum siap soal biaya dan ini!” kata Dimas mendaratkan telunjuknya di pelipis. “Otaknya udah berasap duluan.”
Kedua anak laki-laki itu tertawa bersama sambil sesekali menyeka setiap peluh yang basahi kening.
*****
Garudha, nama galeri kecil di antara besarnya Jogjakarta. Galeri yang dulunya garasi dari rumah merah yang pada sepuluh tahun lalu dilahap si jago merah. Galeri kecil yang tidak lagi dirawat, hanya dijadikan gudang tempat kanvas-kanvas usang tidur.
Wanayasa baru saja pulang dari kampus, setelah menyelesaikan pengunduran dirinya dari semua kehidupan kampus. Wanayasa berpikir kalau ia sudah tidak tertarik dengan kehidupan di sana. Ia hanya ingin hidup dengan dunia dan harapan baru. Mungkin menjadi seniman, iya, seperti yang disangkakan oleh Sastra, anak kecil ingusan, orang asing yang membuatnya merasa ketar-ketir perasaan aneh.
Wanayasa menyalakan layar gawai lipat, sambil menikmati lintingan tembakau yang ia racik sendiri, tangannya tanpa henti menari di atas papan ketik yang tersambung pada komputer layar tabung yang terlihat penuh debu.
Suara pintu diketus begitu lembut, Wanayasa meletakkan lintingan tembakau di asbak. Berjalan laki-laki itu ke pintu. Tampak seorang anak laki-laki berdiri dengan tubuh kuyup. Iya, hari ini dan kemarin bahkan esok menurut ramalan, Jogjakarta akan diguyur hujan lebat. Padahal, Jogjakarta bukan Kota Hujan.
“Weh, Sastra.”
“Halo, Mas.”
“Ayo, masuk. Kebetulan aku butuh orang untuk membereskan kamar, mau bantu, ta?”
“Boleh. Tapi … Mas bisa buatkan aku puisi, nggak? Aku ada tugas. Kemarin Mas bilang kalau Mas itu penulis naskah?” cecar Sastra menatap dengan lincah.
“Bisa.”
Sastra tidak berniat serius. Ia hanya ingin bertemu dengan Wanayasa saja. Mahasiswa Teater yang membuat dirinya ingin cepat dewasa. Meskipun katanya menjadi dewasa itu gila.
Sastra juga ingin menikmati setiap lukisan yang ada di galeri tua yang sejak pertama singgah hingga kedua kalinya ini selalu aromarik teh tubruk. Sastra suka dengan semua yang dilihatnya, apalagi timbunan buku-buku bahasa Indonesia dan bahasa daerah yang disimpan dekat rak menyimpan karung daun teh.
Wanayasa menyuguhkan teh tubruk yang diseduhnya pada teko tanah liat. Sastra merasa tertarik, tetapi ia ingat pesan Ibu, boleh menemuinya, tapi tidak untuk makan dari apa yang disuguhkannya. Kedua manik mata Sastra meredup.
“Kenapa?”
“Nggak.”
Wanayasa tertawa kecil, ia pun duduk di depan Sastra sambil membolak-balik sebuah buku berjudul Puisi Lama, cetakan 1997. “Bukan, maksud Mas kenapa kamu datang saat hujan. Pagi tadi terang padahal … aku juga tadi baru selesai melukis kanvas di sana!” ujar Wanayasa melirik ke arah lukisan payung hitam dekat jendela.
“Aku sekolah, Mas. Biar dapat beasiswa lagi. Biar meringankan beban Ayah dan Ibu.”
“Aku mengulang pertanyaan tempo hari, kamu nggak takut dengan orang asing sepertiku? Bisa jadi aku jahat.”
“Kita satu kelurahan, lho. Rumah aku ini ada di balik rumahmu, terhalang dua atap ada sepertinya. Dan Ayah juga menengalmu, katanya Mas anak mendiang Tresnadi, ya?” beber Sastra menatap cermat.
“Siapa nama ayahmu?” tanya Wanayasa mengerutkan dahinya.
“Purnama. Ayahku Purnama, ibuku Kinanti. Aku cucunya Pramudiyo.”
Wanayasa tertawa renyah sambil menepuk-nepuk pahanya. “Le, Le … cucu Eyang Kakung rupanya … masih produksi tapestri? Dulu Eyang Kakung menjual tapestri buatannya sebagai hiasannya dinding dan meja.”
“Ibuku masih membuatnya, tapi nggak dijual.” Sastra tersenyum lebar. “Kenapa Mas memanggil kakekku dengan sebutan eyang kakung? Memang kenal?” tanya Sastra.
“Kenal dong. Kan, kakekmu teman kakekku. Mereka satu sekolah dulu. Dan sepertinya sepuluh tahun lalu, mungkin kamu belum lahir, kali … kakekmu membantu kakekku juga kakek buyutku yang sudah sangat sepuh membangun kembali garasi ini.” Wanayasa tersenyum.
“Itu … hiasan dinding di sana sama cantelan gorden itu buatan kakekmu,” kata Wanayasa.
“Tapi aku nggak pernah melihat Mas selama sepuluh tahun main di daerah sini?!” Sastra heran dibuatnya.
“Aku besar di Jakarta, dua taun sempat tinggal di Bandung dan empat tahun ini aku kost dekat kampus dan jarang datang ke sini. Pulang hanya untuk memastikan apakah pondasi kayunya masih kokoh atau nggak. Niatnya bahkan tempat ini mau kujual ke orang yang butuh. Kemarin udah ditawar untuk dijadikan kedai kopi tapi aku sibuk kuliah jadi belum bicara lebih serius dan belum deal-deal-an juga.”
“Begitu, ya … kalau begitu Mas bukan lagi orang asing. Toh, orang kita saling kenal rupanya. Meskipun Ibu tetap berpesan agar tetap hati-hati dan nggak makan atau minum sembarangan dari orang asing, hehe.”
Wanayasa mendaratkan tangannya di pusat kepala Sastra. “Aku nggak nyangka akan bertemu tetangga sepertimu, bocah ingusan yang punya mata menyeramkan.”
“Mataku kenapa emangnya?”
“Indah. Ketika besar nanti … Mas yakin musuhmu pasti banyak.”
“Nah, lho … kenapa?”
“Soalnya kamu karismatik, cewek-cewek pasti suka dan cowok-cowok pasti merasa tersaingi!” Wanayasa tertawa ngakak sambil memegangi perutnya.


 another_jejakava
another_jejakava