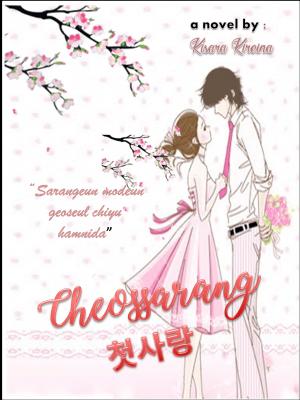Bunyi jarum jam dinding di atas whiteboard terdengar seperti bunyi alarm kematian di kelas X IPS 1 dan akan terus begitu hingga lima menit ke depan. Tatapan pada deretan soal-soal matematika terlihat bagai sorot ketakutan di mana dalam kurun waktu lima menit tersebut akan datang bencana besar.
"Bagi yang sudah selesai, boleh kumpulkan dari sekarang jika kalian ingin mendapatkan meja kantin lebih cepat dari kelas lain."
Salah seorang gadis di kelas itu mengangkat tubuhnya. Dia mengejutkan seisi kelas dengan melangkah percaya diri menghampiri guru matematika yang setia mengawasi. "Saya sudah selesai, Bu," ujarnya dengan menyematkan senyum manis.
"Bagus, Nita. Kamu boleh istirahat duluan."
"Terima kasih, Ibu."
Suara kasak-kusuk mulai terdengar; ada yang sibuk menggoreskan bolpoin ke lembar kosong khusus coret-coret, ada yang berusaha keras mencari jawaban dengan mengusak rambut, bahkan ada yang dengan berani mencolek-colek teman di depannya untuk dimintai pertolongan.
Guru matematika yang tengah mengawas kelas X IPS 1 itu tak melarang perbuatan mereka, toh waktu akan habis dalam hitungan detik saja.
Sementara diam-diam, di balik jendela kelas yang rendah itu, seorang anak laki-laki dengan perawakan tinggi tengah berusaha mengintip ke dalam ruangan. Selang delapan detik mencari, pandangannya terfokus ke satu kursi kosong. Bibirnya melengkung sempurna, dia menegakkan tubuhnya, lalu berlari menyusuri koridor.
Jejak langkah besarnya bermuara ke taman belakang sekolah yang sepi. Selalu seperti itu, Nita akan terlihat sangat nyaman makan sepotong roti dari bekal yang dibawanya tanpa perlu bercengkerama dengan teman-teman yang lain.
Kursi berderit kala anak laki-laki itu duduk tanpa pemberitahuan. Nita menoleh dengan raut terkejut, sedangkan anak laki-laki itu tersenyum lebar. Keduanya berpandangan dengan raut wajah masing-masing, lalu berhenti ketika tangan si anak laki-laki itu menarik pipi bulat Nita.
"Aw, sakit tahu!"
"Habisnya kamu lucu, masa lihat akunya kayak lihat maling sih!"
"Lepasin, Tuan muda!" erang Nita.
"Heh, kenapa manggilnya gitu? Nggak akan aku lepasin!"
"Maaf, kebiasaan."
"Ya udah buruan bilang, tolong lepasin dong Fathir sayang," goda si anak laki-laki dengan wajah malu-malu.
Nita menghela napas pelan, tapi tak menepis keinginan itu. Daripada pipinya akan lebar sebelah, lebih baik dia turuti dengan segera. "Tolong lepasin dong, Fathir."
Fathir merasa menang, dia menurunkan lengannya setelah mengusap bekas cubitannya di sebelah pipi Nita.
"Sayangnya mana?"
"Nggak ada ya!"
"Kalau nggak ada fiks aku cubit lagi—"
"Sayang!" teriak Nita spontan.
Fathir tertawa karenanya. Anak laki-laki itu langsung memalingkan wajahnya yang sudah memerah agar Nita tidak melihat itu. Namun, nyatanya diam-diam Nita menoleh ke arah Fathir dan ikut tersenyum.
"Aku bisa jawab semua soal matematika tadi. Berkat belajar bareng kamu, makasih, Tuan—ups, makasih, Fathir." Nita bersuara kembali sambil mengulurkan roti selai kacang yang masih utuh di tempat bekal. "Mau?" tawarnya.
Fathir memutar tubuh menghadap gadis itu. Pertama, dia meraih kotak bekal yang diulurkan Nita. Kedua, dia memandanginya dengan tatapan bersinar seolah roti berselai kacang di hadapannya adalah sebuah karya paling langka di dunia. Ketiga, dengan senyum paling manis yang pernah Nita lihat, Fathir menggigit roti selai kacang itu dengan potongan besar.
"Enak?" tanya Nita mencari pendapat.
"Buanget."
"Apaan? Lebay, kan cuma roti tawar biasa yang dioles selai kacang."
Fathir menggeleng kecil, "jangan lupa dibuat pakai cinta oleh tangan yang cantik."
"Dih," kekeh Nita.
"Aku pulang malam hari ini. Habis les nanti mau ke rumah Ganta, dia ulang tahun."
Nita mengangguk-angguk. "Hati-hati, jangan lupa makan yang banyak di pesta."
"Siap, Bu komandan!" seru Fathir.
Setelah potongan roti miliknya habis, Nita beranjak dari duduknya untuk menghampiri makhluk kecil di atas daun tanaman merambat yang menyelimuti tembok besar sekolahnya. Bukannya takut, gadis itu malah tersenyum lebar melihat makhluk kecil berwarna hijau itu berjalan pelan sekali.
"Lihat apa?" Fathir ikut beranjak karena rotinya juga habis. Dia berdiri di sebelah Nita, melirik arah pandangan gadis itu.
"Ulatnya lucu."
"Iya deh, kayak kamu."
Nita melayangkan tatapan tajam pada Fathir dan menunjuk wajah anak laki-laki itu. "Kamu ngatain aku kecil, bulet, kayak ulat ini? Hijau lagi."
"Nggak dong, maksud aku dia kayak kamu karena lucu dan menggemaskan."
Harusnya bagi sebagian perempuan seusianya, Nita merasa senang dipuji semanis itu oleh anak laki-laki setampan Fathir, tetapi rasanya Nita malah sedih. Gadis itu selalu merasa ada sebagian nyeri di dadanya ketika menghabiskan waktu bersama Fathir.
"Aku juga berharap bisa kayak ulat yang suatu hari nanti bisa terbang tinggi dengan sayap indahnya."
Fathir menarik tangan Nita, menggenggamnya erat. Dalam diamnya Fathir mengamini kalimat gadis itu dan berjanji pada dirinya bahwa dia akan selalu mendukung Nita.
###
"Akh! Sudah berapa kali saya bilang, kamu harus hati-hati membersihkan barang-barang saya!"
"Maaf, Nyonya. Maaf, saya benar-benar tidak sengaja."
"Maafmu tidak akan bisa mengganti guci itu, gembel!"
Duakh.
Sang nyonya besar menendang keras bahu pembantu di rumah besarnya dengan emosi meluap-luap. Bahkan menurutnya tendangan tadi sama sekali tidak cukup untuk membuat perasaannya membaik setelah melihat guci mahal kesayangannya hancur berkeping-keping.
"Saya akan berusaha mencicilnya, Nyonya. Potong saja gaji saya setiap bulannya, Nyonya."
"Selalu seperti itu. Karena utangmu itu saya jadi tidak bisa memecatmu, bodoh!" Pembantu yang ringkih itu terhuyung lagi karena kepalanya ditoyor kasar oleh si majikan. "Bereskan semuanya!" ujar nyonya besar itu seraya berlalu menaiki tangga.
Sembari menangis tanpa suara, wanita ringkih itu telaten mengumpulkan pecahan guci untuk dikumpulkan jadi satu. Beberapa pelayan yang lebih muda darinya hanya menonton dengan tatapan puas, padahal mereka berdua yang menyebabkan guci mahal itu pecah.
Nita menyaksikan ibunya menangis. Dia berdiri di balik sekat ruang tengah sedari ibunya ditendang oleh majikannya. Gadis itu ingin berlari membantu, tetapi kakinya seperti tertanam di lantai. Demi Tuhan, hatinya sakit sekali menyaksikan hal itu.
"Bersihkan sampai tidak ada satupun serpihan tajam di lantai ya, Bu Sita." Dengan cekikikan puas, salah satu pelayan muda mengejek wanita ringkih bernama Sita itu.
Yang lainnya ikut tertawa pelan, menunjuk serpihan kecil di lantai. "Itu tuh, masih banyak, bersihkan yang benar."
Nita berlari mendekat, lalu berjongkok di depan ibunya. "Biar Nita aja, Bu," usulnya.
Para pelayan muda langsung undur diri begitu Nita hadir karena tidak ingin berurusan dengan gadis itu.
Sita mendongak pada sang putri, senyumnya mengembang. "Oh, kamu sudah pulang, Nak? Makan sana, Ibu sudah menyiapkan makanan di dapur, ini biar Ibu yang selesaikan."
"Nita aja, Bu. Ey, Ibu kan tahu kalau mata Nita lebih jeli dari mata Ibu. Nita bisa ngumpulin serpihan yang kecil-kecil lebih cepat dari Ibu," kata Nita dengan nada ceria. Sebisa mungkin dia menutupi rasa sedihnya dari sang ibu.
"Tapi, Nit—" Sita menghentikan ucapannya kala Nita meraih kedua telapak tangannya yang kasar itu. Tetapi sebenarnya bukan karena kedua tangannya yang disentuh Nita alasan Sita terdiam, melainkan karena ia melihat hidung dan kedua mata anak gadisnya yang memerah. Nita habis menangis, atau mungkin dia menahan tangisannya.
"Bu, Nita mau Ibu angetin lauknya. Nanti selesai bersihin ini Nita langsung ke dapur. Ya, Bu? Ayo, Bu, biar cepat."
Sita menepuk punggung tangan Nita sambil mengangguk setuju, daripada dia menangis di depan anaknya. "Iya, sayang. Makasih ya, Ibu ke dapur dulu."
"Iya, Bu."
Maka seperginya sang ibu ke dapur, lelehan likuid sukses membanjiri kedua pipi Nita. Gadis itu menangis tanpa suara seraya mengumpulkan serpihan kecil guci di lantai. Andaikan mendiang ayahnya tidak berutang pada keluarga Amartha itu, Nita dan ibunya pasti tidak akan menderita setiap hari seperti ini.
Selesai membersihkan pecahan guci, Nita ke dapur untuk makan dan lanjut membantu ibunya mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Ibunya, Sita, sudah bekerja di rumah besar keluarga Amartha setelah sang suami meninggalkan banyak utang pada keluarga itu. Selain ditinggalkan pergi, Sita dan anaknya juga ditinggalkan banyak uutang. Karena itulah, dia dan putrinya harus tinggal di sana dan menjadi pembantu untuk waktu yang tidak menentu.
###
Fathir turun dari mobil yang sudah dibukakan oleh sekretaris pribadinya setelah sampai di depan rumah. Anak laki-laki itu berjalan tegak memasuki pintu utama, namun berhenti sejenak kala teringat sesuatu. Dia menoleh pada sekretarisnya yang beberapa tahun lebih tua darinya itu.
"Ada perlu sesuatu, Tuan muda?" tanya sang sekretaris.
Fathir mengangguk pelan. "Mami ada di rumah?"
"Beliau sedang makan malam di luar bersama Tuan besar sejak tiga puluh menit yang lalu, Tuan muda."
Fathir melepaskan dasi yang terasa mencekik lehernya, lalu diserahkan kepada sekretaris pribadinya. "Masih ada sisa berapa menit, Kak?"
"Mm... untuk menghindari kecurigaan, anda memiliki dua puluh menit saja, Tuan muda."
"Itu lebih dari cukup, thank you, Kak." Fathir langsung berlari menjauh dari pintu utama rumahnya dan menyusuri jalan setapak kecil menuju bangunan paling kecil di samping rumah besarnya.
Sesampainya di bawah pohon besar yang menghadap langsung ke air mancur, Fathir merogoh ponselnya dan mengirimi Nita pesan agar menemuinya di sana. Hanya butuh tiga menit, gadis itu sudah berdiri di depan Fathir.
"Bahkan dengan kaos kebesaran ini saja kamu tampak sangat cantik sekali di bawah guyuran sinar rembulan,” goda Fathir.
Nita memukulkan kepalan tangannya ke dada Fathir. Dengan mendengus kecil, gadis itu memilih tak menanggapi kalimat tuan mudanya dan duduk di kursi panjang.
"Kamu tuh harusnya senang aku puji kayak tadi, bukannya mukul. Nggak romantis banget sih," protes Fathir.
Nita tergelak sesaat, lalu memutar kepalanya untuk menatap Fathir yang malam ini terlihat sangat tampan. Tidak, Fathir memang sudah tampan sejak lahir, namun malam ini ketampanannya bertambah berkali-kali lipat dengan tatanan rambut yang memperlihatkan keningnya itu. Nita terpanah, dia akui itu, dia memang mencintai Fathir bahkan sampai hari ini.
"Aku makan banyak di pesta Ganta, sesuai saran kamu." Melihat Nita yang diam dan tak berkata apa-apa, Fathir menipiskan bibirnya. "Jangan lihatin aku kayak gitu, malu tahu. Iya tahu aku ganteng banget, kan?"
"Banget, sampai aku sadar kalau kamu udah sama kayak bulan di atas itu." Akhirnya Nita berkata setelah puas memandangi wajah Fathir.
"Dan kamu bintangnya?"
"Ya, kecil sekali dibandingkan denganmu."
Fathir terdiam mendengar jawaban Nita. Bukan itu maksudnya menyamakan si gadis dengan bintang. Maksud Fathir bukan untuk membandingkannya, tetapi entah mengapa jawaban itu spontan membuatnya merasa bersalah. Fathir menarik punggung tangan Nita untuk ia genggam. Si empunya menoleh lagi padanya dengan ekspresi datar.
"Aku udah bilang belum hari ini kalau aku sayang banget sama kamu?"
"Aku sayang banget sama kamu, Fathir."
Fathir mengayunkan tautan tangan mereka. "Bukan kamu, maksudnya aku yang bilang. Aku sayang banget sama kamu." Tersenyum lebar, Fathir mengecup lama punggung tangan Nita. "Maaf, aku nggak maksud buat kamu tersinggung. Maksud aku tuh, kalau aku bulan, maka kamu adalah bintangku. Kamu akan selalu menemaniku dengan taburan sinarmu yang cantik, hingga aku tidak akan kesepian."
"Indah," lirih Nita.
Seindah itu cara Fathir mencintainya, Nita tahu. Meskipun usianya baru beranjak 15 tahun, dia merasa cinta Fathir akan cukup untuknya seumur hidup. Akan tetapi, kenapa setiap rasa cinta itu tidak pernah membuatnya lega? Kenapa Nita selalu merasa haus akan cinta Fathir? Kenapa selalu ada bagian yang retak di hatinya?


 indriyani
indriyani