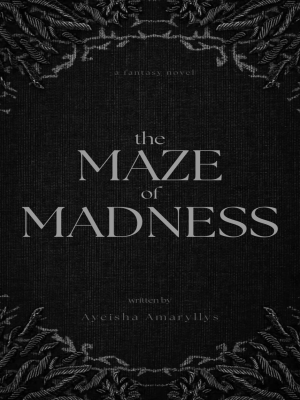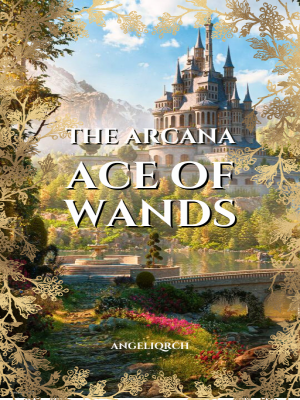Dedaunan meliuk diterpa Bathara Bayu yang mengudara membawa semburat jingga dari balik pepohonan. Pranaja terjaga sejak beberapa menit lalu. Pupil matanya tampak kecokelatan terkena senja yang menyelinap masuk melalui celah dinding gedhek.
"Aku hendak bertemu Ki Suro." Lelaki itu beranjak dari amben.
"Besok kan bisa," jawabku.
"Tidak. Kita harus lekas pulang dan aku yakin pria sepuh itu tahu sesuatu."
"Kenapa harus sekarang? Toh, aku pun tidak bahagia hidup di masa depan," kataku.
"Oh ya? Coba kamu pikirkan. Apa alasan kita terlempar ke sini?" tanya Pranaja.
"Entah. Mungkin ada seseorang yang mencintaiku lalu mengharapkanku berada di sini," jawabku asal.
"Itulah kalau kamu terpatok pada novel. Bukan itu alasannya, tapi karena kita telah berbuat dosa besar."
"Dosa apa? Terlalu banyak jenis dosa yang manusia timbun."
"Dulu, aku kerap membohongi orang tuaku. Uang yang mereka berikan untuk keperluanku di kampus, malah kubuat clubbing. Tak jarang juga aku mencomot uang milik Ayah tanpa izin." Pranaja menerawang jauh sebelum melanjutkan, "inilah karma yang kudapatkan, Na. Bagaimanapun, aku harus kembali dan mengubah diri."
Hatiku tertohok mendengar kata-kata pemuda kurus bertelanjang dada di hadapanku ini. Aku pun tak lebih baik darinya. Aku sadar, ganjaran anak durhaka macam diriku sedang menjalankan darmanya.
"Apa kamu juga merasa punya dosa besar di zaman kita berasal?" tanya Pranaja.
Aku diam sejenak, merangkai kalimat untuk menggambarkan betapa kurang ajarnya diriku.
"Aku sering membentak orang tua, nenek-kakek, serta adikku. Aku selalu merasa paling benar dengan membantah apa yang dikatakan orang-orang terdekatku. Aku cuma anak manja yang egois. Kurasa kau benar alasan kita di sini. Mari cari rumah Ki Suro." Aku memapah Pranaja yang lumayan berat di sepanjang jalan.
Setapak menuju persimpangan Alas Ringin mulai tertutup alang-alang yang siap sedia menggores kulit kami. Aku tidak hafal betul jalan ini, hanya mengandalkan insting Nayaviva yang terasah lebih kuat.
Setelah melalui bulakan penuh alang-alang itu, tibalah kami di persimpangan Alas Ringin. Tepat di tengah cabang jalan, berdiri rumah kayu yang tampak reyot. Kami mengetuk pintu dan dengan cepat pintu terbuka, menampakkan sosok Ki Suro dengan udeng hitam di kepalanya.
"Mari masuk."
Di dalam rumah itu, teronggok sejumlah ukiran klasik dari kayu. Kursi-mejanya pun tampak antik dan nyaman. Rumah yang dari luar tampak reyot itu amat berbalikan dengan dalamnya. Aura magis menguar dari gunungan kecil menyan yang dibakar di pojok ruangan. Lukisan-lukisan makhluk buruk rupa-mungkin buto menghiasi dinding.
Kami dipersilakan duduk di kursi antik berukir kenanga. Seperti halnya kebiasaan rakyat Wilwatikta, tersajilah pinang, jeruk nipis, serta daun sirih di meja. "Begini, Ki. Kami sebenarnya bukan berasal da-" Ucapan Pranaja terpotong.
"Aku tahu, Ngger. Kalian hanya perlu menuntaskan urusan duniawi di sini. Banyak orang yang terlibat di kehidupan kalian. Selesaikanlah," kata Ki Suro.
Aku dan Pranaja bertemu pandang sejenak, kemudian kembali menghadap Ki Suro. Namun, orang itu terlebih dahulu menghilang dari pandangan. Kami memanggilnya berulang kali dengan debaran jantung tak keruan. Sebenarnya siapa kakek itu? Kenapa beliau acap kali menghilang, bahkan di rumahnya sendiri?
Pranaja menyeretku untuk meninggalkan tempat aneh ini. Aku menyempatkan diri menoleh, mendapati padang ilalang dan lenyapnya rumah Ki Suro.
"Ja, lihat ke belakang!" seruku.
Ia berpaling dan tetap menarikku untuk berlari lebih cepat.
Kami menginjakkan kaki di dalam pondok Pranaja dengan napas megap-megap kemudian minum dengan tangan gemetar. Ini bukan mimpi.
"Na, pokoknya kita harus cepat-cepat pulang. Lingkungan ini sudah gak wajar lagi."
"Ya. Tapi sebelumnya, kita harus menuntaskan urusan di sini."
Pranaja menaikkan sebelah alisnya.
"Mungkin yang dimaksud Ki Suro tadi, kita tidak boleh terikat lagi dengan manusia dari masa ini," jelasku.
"Aku tidak punya hubungan dengan siapa pun di sini selain kamu," jawab Pranaja.
"Iya, tapi aku? Masih ada tiga orang yang mempunyai hubungan erat denganku."
"Siapa?"
"Emak, Dadari, dan Ki Darwanto." Aku memandangnya yang juga menyorotkan kecemasan. "Mungkin sebaiknya aku jujur pada mereka tentang asal-usul kita."
Pranaja segera menggeleng tak setuju. "Kecil kemungkinan mereka percaya. Terutama emakmu. Ia takkan membiarkanmu pergi karena kau masih menempati jasad Viva."
Aku baru ingat kalau tubuhku ini milik Nayaviva. Aku menjadi ragu, apakah kami berdua benar-benar bisa pulang dengan selamat? Pranaja tidak menempati raga orang lain seperti halnya diriku. Apakah jalan pulang kami sama?
"Mungkin ada cara lain. Kau bisa menghabiskan waktu bersama mereka dan membuat mereka bahagia," usul Pranaja.
"Bukankah lebih baik membuat mereka semua membenci diriku? Dengan begitu, mereka akan melepasku." Aku tercenung sejenak. "Sama seperti perbuatan tercelaku pada orang tua."
"Kau mau jadi anak durhaka lagi? Kamu bisa saja dikutuk Mak Lastri dan bakal jadi legenda Renjana anak durhaka."
Kemudian aku menggeplak bahunya. Ia selalu saja membuatku gemas oleh gurauan yang memancing emosi padahal situasi sedang tak beres.


 orenertaja
orenertaja