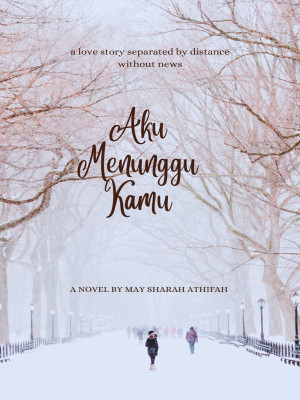Kepalaku terus tertunduk meski kuupayakan sekuat tenaga untuk mendongak dengan angkuh. Nyatanya hati kecilku masih tak siap menghadapi realitas. Tiba di ambang pintu ruang bernuansa kayu jati ini, aku tak kuasa melihat rupa jalang yang mengotori rumah tanggaku.
"Viva, angkat kepalamu dan sapa Tavisha!" Biyung menyentuh bahuku. Oh jadi namanya Tavisha, sungguh tanganku gatal ingin menonjok perut pembawa sial itu.
"Hai, bitch."
Mereka bertiga memandangku heran, tak memafhumi kata kasar yang terlontar.
"Bitch itu artinya cantik." Jiwa sesatku mencuat ke permukaan.
"Terima kasih, Kakangmbok."
Cih, suaranya diperhalus segala. Atmaku menggerutu sementara kepalaku berdenyut menahan gejolak emosi yang campur aduk.
"Aku tahu kau sakit hati, Viva. Tapi semua telah terjadi. Pesanku, perlakukan Tavisha dengan baik," kata Biyung.
Aku memandang Tavisha dengan sinis. Perempuan dengan rambut lurus sepinggang serta garis muka khas Jambhudwipa itu memiliki lekuk tubuh indah. Perutnya yang agak membuncit tak menutupi kemolekannya. Pantas saja Arya tak kuasa menahan hasratnya.
Aku keki akan kejelitaan perempuan berhidung mbangir itu.
"Tavisha, kau pun mesti hormati kakangmbok-mu," tutur Arya sembari menarik pinggangku supaya lebih dekat dengannya.
Mimik Tavisha mengeruh sesaat sebelum memajang senyum dengan terpaksa.
🌼
"Kakangmbok, maafkan aku yang telah memberantakkan kemesraanmu dengan Arya," lirih Tavisha seraya membuntutiku.
Kami tengah menikmati semilir senja di kebun dekat sumur. Jalur setapak kami susuri di antara pohon mahkota dewa yang berderet serta memantulkan kilau keemasan dari Batara Surya. Aku terpaksa mengiakan wejangan Biyung untuk mengakrabi Tavisha sampai ia mampu beradaptasi dan memahami lingkungan Bagorejo.
Aku terus melangkah, melewati candi bentar yang tampak seperti Gapura Waringin Lawang versi lebih kecil. Aku baru pertama kali mengetahui adanya gapura tanpa atap ini setelah sekian lama tinggal di dekatnya. Secara, bangunan meruncing ke atas itu berada di sebelah utara rumah, sementara aku tiap hari melalui sisi selatan. Batu batanya tampak lawas karena lumut yang menyelimuti. Jika Waringin Lawang punya tangga undakan, gapura yang barusan kulewati tak memilikinya. Aku belum pernah mendengar keberadaan gapura ini di masa depan. Mungkin kelak aku bakal mengusulkan pada arkeolog untuk menggali bekas-bekas bangunan itu.
"Ini kesalahanku, aku sungguh minta maaf," kata perempuan itu lagi. Aku berbalik, sebal karena angan-anganku dibuyarkan, tapi aku terenyuh melihat rautnya yang menyedihkan. Aku tak kuasa mencicik apabila mendapat tatapan yang berkaca-kaca itu.
Tavisha tak sepenuhnya bersalah. Jika Arya kala itu bisa mengontrol birahinya, pasti perkara itu tidak akan terjadi. Buat apa aku memupuk kebencian pada perempuan malang itu? Seharusnya aku dapat melawan angkara murka yang berambisi untuk menggelapkan hatiku.
"Kalau Kakangmbok masih membenciku, biarkan aku menggugurkan kandungan ini. Pasti Arya bakal menyisihkanku." Tavisha mulai terisak dengan bahu semakin bergetar.
Aku tidak bisa melihatnya seperti itu. Kudekati ia lalu berkata, "Sudahlah, jaga dirimu dan bayimu. Anakmu ialah anakku juga."
"Tapi akulah penyebab Kakangmbok sakit hati."
Aku termangu. Apakah ucapannya benar? Apakah perempuan itu penyebab sakit hatiku? Kurasa bukan, karena Arya-lah penyebabnya.
Kucoba tepis murkaku dan berdamai dengan perempuan itu, tapi sesuatu terasa mengganjal di sanubariku. Aku masih tak berkenan jika Arya jatuh hati padanya.
🌼
Tiga bulan berselang dengan lekas dan keseharianku hanya itu-itu saja—memasak, mencuci, menganyam tikar, dan kegiatan lain yang dilakukan kaum perempuan. Kadang kala aku harus memenuhi keinginan Tavisha yang katanya sedang mengidam. Ia semakin dimanjakan oleh Arya dan Biyung yang sepertinya masih diliputi rasa bersalah kepada perempuan Jambhudwipa yang sebelumnya tinggal di pemukiman Mleccha itu.
Aku masih ripuh menganyam pandan untuk dijadikan tikar saat Arya memanggilku.
“Viva, tolong buatkan warna merah dari akar mengkudu itu,” titahnya.
Kulirik ia sekilas, sekonyong-konyong merindukan saat ia masih menekuni pekerjaannya sebagai angukir, yang piawai membuatkanku gelang berukir naga yang sampai sekarang melekat di tanganku. Kupikir pekerjaan itu berpenghasilan lebih menjanjikan daripada menjadi anglukis. Penduduk desa kurang berminat pada seni lukis yang maknanya amat tersirat dan sulit diterka. Mereka lebih suka akan pahatan dan ukiran yang bisa dipajang di luar maupun dalam rumah mereka. Seni lukis cuma diminati keluarga kerajaan di Trowulan maupun di pusat kerajaan bawahan. Namun, aku tak menghakimi Arya selagi ia masih dapat memenuhi kebutuhanku.
Setelah mengembuskan napas kasar, kubuat juga cairan merah dari akar mengkudu yang sebelumnya dibubuk. Sementara tanganku sedari tadi bekerja tak ada waktu istirahat, Tavisha duduk manis di dipan sembari menontonku.
"Kau tidak ada pekerjaan selain menatapku?" sindirku.
"Ah iya, sini biar aku yang mengaduk," sahut Tavisha sembari beranjak.
Aku tersenyum miring, akan tetapi segera tergantikan dengan benak yang membara. Bagaimana tidak? Arya mencekal lengan Tavisha dan menyuruhnya duduk kembali.
"Jangan banyak bekerja dulu, kasihan anak kita," ucap Arya, dibalas anggukan dan senyum manis Tavisha.
Aku membanting adukan, melengos pergi setelah menendang kayu bakar di tungku sementara pandanganku buram oleh air mata. Dengan entengnya Arya menyebut "anak kita" dengan perempuan lain yang aleman itu. Ia pikir keren membuatku cemburu serta pamer bahwa ia bajingan akut sampai-sampai perempuan dari luar Jawa Dwipa pun tunduk padanya.
"Ada apa, Viva?" tanya Biyung yang baru masuk rumah, membawa tampah berisi beras.
Tanpa menyahut, aku terus melangkah lebar menuju pondok Pranaja. Sesampainya di sana, aku menyelonong lewat pintu yang dibiarkan terbuka. Si tuan rumah sedang terlelap dengan mulut membuka dan iler yang mengering di sudut bibir.
"Pranaja, aku sudah tidak kuat," ucapku sambil menepuk pelan lengannya.
Ia meregangkan tubuh sambil menguap sebelum duduk di sebelahku.
"Viva, kenapa kemari pas aku ileran begini sih?" gerutu Pranaja dengan mata sipit yang setengah terbuka.
Aku memandang muka bantal yang awut-awutan itu. Rambut sebahunya acak-acakan, hidungnya tak terlalu mancung dan bibirnya tipis. Ketampanannya tak kalah dari Arya. Hanya saja ia keras kepala.
"Ada apa?" tanya lelaki itu membuyarkan pikiranku.
Aku bingung, rasanya mau berteriak mengingat Arya yang menyayangi Tavisha tanpa memikirkan perasaanku.
"Kenapa tadi nangis?" Aku tertawa kecil mendengarnya, tiba-tiba malu dengan diriku sendiri yang mirip anak kecil. Pranaja terkekeh kemudian melanjutkan, "Bayi besar ada konflik lagi sama suami?"
"Aku jenuh. Arya seenak jidat memerintahku sementara istri mudanya dilarang kerja meski cuma mengaduk cat.” Aku bersungut-sungut dengan kepala yang kian memanas.
"Kamu masih cinta padanya?"
Aku mengangkat bahu. "Akhir-akhir ini risi tiap kali dia menatapku. Tidak ada lagi perasaan berbunga-bunga kayak dulu."
"Kamu bisa meninggalkannya," usul lelaki bermata sipit itu.
"Enggak! Aku gak mau menyerah begitu saja. Nanti Tavisha yang kesenangan," bantahku.
"Tapi kamu nyiksa diri kamu sendiri, Viva! Sikap Arya ke kamu juga mulai beda, kan? Ini baru awal dan kamu sudah kejer begini, gimana ke depannya saat anak mereka lahir?" celoteh Pranaja menghakimi.
"Viva, suami kamu sudah membagi hati. Semua pria kalau punya istri muda juga pasti lebih sayang padanya, termasuk Arya yang selama ini kamu puja-puja."
Aku membisu. Benar kata Pranaja. Arya pasti lebih sayang kepada Tavisha. Perempuan itu jelas mempunyai fisik jauh lebih baik dibanding aku, apalagi ia mengandung keturunan Arya. Mungkin tiga purnama lagi ia akan melahirkan, dan pasti aku bakal disuruh membantu mengurusi anak mereka. Ih! jangan sampai terjadi.
"Renjana Maheswari, turunkan egomu dan kita cari jalan keluarnya."


 orenertaja
orenertaja