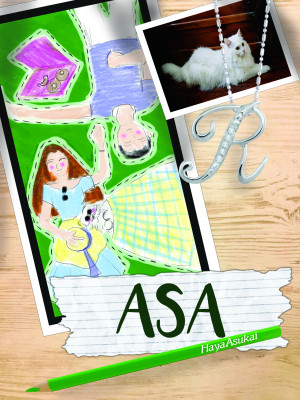"Bukankah ini terlalu banyak?" tanyaku, masih sangsi untuk menerimanya. Dua tupai dan satu ayam bakal lama habis jika hanya dimakan olehku dan Emak nantinya.
"Bagaimana kalau beberapa kita masak di sini? Aku lapar, akan lebih lama kalau pulang dan menunggu Biyung memasaknya," ujarnya kemudian terdengar suara keroncongan dari perutnya, membuatku terkikik.
Aku mengiakannya. Kukumpulkan ranting-ranting kayu sementara Arya menyalakan api dengan menggesek batu. Karena tidak ada kendil atau alat lain untuk memasak, kami menusuk tubuh ayam alas yang ukurannya cukup besar dan pastinya akan kenyang kalau hanya kami berdua yang menyantapnya.
Ayam bakar sudah matang, aku pun menunggu sampai kepulannya mereda sembari menahan liur agar tidak menetes. Sementara itu, Arya melangkah menuju semak belukar entah hendak ke mana. Ternyata dia kembali membawa beberapa buah jeruk yang warna kuningnya membuat mataku kian cerah.
Ia mengupas kulitnya, memakan buah itu bersamaku sembari menunggu ayam bakar menghangat.
Anak dapur itu menggosok-gosokkan kulit jeruk ke bagian kulitku.
"Untuk apa?" tanyaku heran.
"Menangkal nyamuk," sahutnya. Aku membulatkan mulut sambil mengangguk.
"Terima kasih.” Aku mendongak, mendapati senyum tipisnya tersungging oleh bibirnya yang gelap kemerahan. Lagi-lagi dadaku berdesir saat matanya bertemu mataku di bawah alis yang tampak seperti ulat bulu.
Ia menyodorkan secuil daging bakar di depan bibirku. Aku sungguh merutuki diriku yang tersipu bak remaja puber menerima suapan itu.
“Aku bisa sendiri.” Aku mencabuti daging-daging ayam dengan gegabah demi menyamarkan kegugupanku sementara ia geleng kepala.
Aku tak pernah puas untuk memandangnya. Wajah rupawan itu mampu membuatku kenyang sekalipun ayam bakar tak kumakan. Diam-diam pun aku mencuri pandang padanya yang melumerkan hatiku dari samping. Hidungnya mbangir seperti paruh burung gagak. Dan terpikir bahwa ungkapan gaya rambut menentukan ketampanan seseorang itu benar adanya.
“Arya, jangan kau potong rambutmu itu, ya.”
Ia menaikkan sebelah alis sembari memegangi rambut ikal lebatnya di balik udeng sewarna delima.
🌼
"Mak, lihatlah apa yang kubawa," seruku seraya melangkah cepat ke dapur.
Emak yang tengah meniup api di luweng atau tungku yang terlalu kuno di mataku, sedikit terlonjak mendengar suara cempreng dari raga yang kudekami.
"Dari mana kau mendapatkannya?" tanyanya, menilik tupai pemberian Arya dengan dahi mengerut.
"Tentu saja Arya, memang siapa lagi?"
"Ya sudah, aku akan memasaknya. Nanti kau antarkan sebagian kepada Dadari." Aku mengangguk.
Mengawasi pelataran bak taman sari yang penuh bunga, lambat laun cairan bening menetes di jarik yang melilit tubuhku. Dadaku berdenyut nyeri, teringat ayahku suka sekali berburu. Aku ingin kembali ke asalku, tapi terlalu berat meninggalkan Mak Lastri, Dadari, juga ... Arya. Jadi, aku akan membiarkan diriku menikmati setiap perkara di sini sebelum takdir membawaku kembali ke masa depan.
Sesudah mengantar masakan Emak kepada Dadari dan Ki Darwanto, aku kembali ke rumah dan makan bersama Emak di antara semburat lembayung senja yang menerobos celah-celah dinding bilik bambu.
Suasana ini mengingatkanku pada masa di mana aku masih kanak-kanak. Bermain mainan tradisional sampai senja tiba bersama teman-teman. Dulu kehadiran gawai masih langka di desaku, itu malah bagus karena anak-anak tidak disibukkan oleh game maupun media sosial. Kegiatan belajar pun tidak terganggu dengan adanya gawai.
Senja juga mengingatkanku pada kakekku, di mana menjelang sandekala, aku selalu mengikutinya pergi ke hutan mengambil nira untuk dijadikan gula jawa.
Aku menutup pintu rapat-rapat meninggalkan kenangan yang menghampiri. Batara Candra telah menggantikan posisi Batara Surya yang tengah mengecup pertiwi. Malam gulita tiada gemintang yang menyaksikan para jasad di bentala. Aku menggigil kedinginan sementara bambu berderak tertiup angin dari sebelah rumah.


 orenertaja
orenertaja