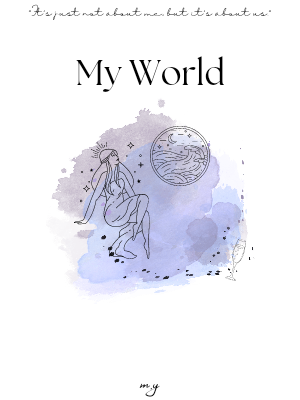Bangun tidur, tahu-tahu aku meratap karena rupanya aku masih terkapar di alam antah berantah ini tanpa membawa bekal apa-apa dari masa depan. Emak yang mendengar ratapanku langsung tergopoh-gopoh menuju ranjang dengan risau.
Aku mencubit lenganku sekuat tenaga dan itu sakit, tandanya aku tidak sedang bermimpi. Aku skeptis bisa hidup tanpa ponsel.
"Kenapa? Ada yang sakit?" tanya Emak khawatir.
Aku menggeleng sembari mencari jawaban yang masuk akal.
"Aku hanya mimpi buruk," dustaku, tersenyum simpul terhadap sosok berbusana kemban cokelat di hadapanku ini.
"Ya sudah kalau begitu, Emak mau mususi* di belakang."
*Mencuci beras.
"Mak, apakah aku boleh berkeliling di sekitar rumah?"
"Terserah. Kalau tersesat jangan salahkan Emak."
Bibirku mengerucut mendengar kalimat tak acuh itu. Kulangkahkan kaki yang terbalut kain jarik merah ini melewati pintu yang langsung menyajikan panorama perdesaan. Persawahan membentang di balik halimun yang disoroti mentari. Telapak kakiku bersentuhan langsung dengan tanah dingin yang menjalar ke seluruh tubuhku. Mungkin karena pada masa ini belum terjadi pemanasan global maupun polusi dari kendaraan.
"Sedang apa?" Seseorang tiba-tiba berseru dari belakangku, dan aku baru insaf bahwa telah berjalan jauh meninggalkan rumah.
Aku menoleh lalu mendongak untuk melihat wajahnya karena dia jauh lebih tinggi dariku. Memalukan, tinggiku hanya sebatas dadanya.
Tubuhku meradang ketika melihat wajah rupawan dengan ikat kepala merah itu. Aku segera menunduk malu karena kedapatan menatap wajahnya dengan membelalak. Sekilas mataku menangkap gagang keris yang diselipkan pada ikat pinggangnya.
"Sedang apa kau?" tanyanya sekali lagi sembari menarik daguku dengan jemarinya. Aku risi dengan sentuhan itu dan tak lagi terpana akan ketampanannya.
"Hanya jalan-jalan." Kutepis tangan lancangnya kemudian berlalu.
Dia seperti menahan tawa, membuatku tambah tak nyaman dan ingin cepat-cepat hilang dari pandangannya.
"Seperti tidak pernah keluar saja. Jadi, siapa namamu?" Ia menyusul langkahku. Kulirik dengan sinis sosoknya yang kekar memakai rompi merah itu.
"Nayaviva Citrakara," jawabku ala kadarnya. Aku tidak tahu harus bersikap bagaimana lagi mendapati sosok tampan tetapi lancang itu.
"Arya Buntara," katanya sembari mengulurkan tangan, aku pun membalasnya dengan setengah hati. Sengatan hangat yang berpusat di dadaku menjalar. Tidak mungkin aku jatuh cinta pandangan pertama pada pria purba yang lancang ini.
"Baiklah, sampai jumpa." Aku masih ketus padanya, berharap ia tak tertarik untuk berbincang lebih lama denganku sehingga sengatan tadi takkan berkembang.
"Sebentar, duduklah denganku. Katanya sedang melihat pemandangan?" Arya menarik tanganku menyusuri pematang sawah dan duduk di bawah pohon pisang.
Di hadapan kami, talang atau pipa saluran air dari bambu mengucurkan air jernih dengan deras, yang kemudian jatuh merebah ke lumpur yang dihuni keong serta belut.
"Kau tinggal di mana?" tanyanya sembari memetik beberapa buah pisang.
Aku membisu cukup lama, mengingat-ingat barangkali emakku sudah memberitahu nama desa yang kini menjadi tempat tinggalku. Namun, sepertinya ia belum memberitahu.
Pemuda itu menatapku sambil menaikkan sebelah alis tebalnya bingung, kemudian ia menyodorkan sebuah pisang. Arya duduk di sampingku dengan jarak satu jengkal, membuat jantungku lagi-lagi maraton tanpa bisa dicegah. Aku tak boleh tertarik pada Arya, lelaki itu pasti garangan yang gemar mendekati wanita.
Wajahnya amat tampan, kulit kecokelatannya eksotis ditimpa matahari. Ditambah lagi surai bergelombang yang panjangnya hampir menutupi telinga. Keelokan itu pasti menjadi santapan puluhan wanita.
Aku harus cepat pergi dari sini.
"Kenapa wajahmu merah? Apa kau demam?" Ia mendapatiku yang tengah mencuri pandang pada tubuhnya.
"Aku cuma kepanasan." Itu hanyalah sebuah bualan karena sebenarnya aku malu dengan pikiranku sendiri yang melanglang buana dengan liar sejak aku melihat tubuh kekar pemuda itu. Sementara di sisi lain aku tak nyaman dengannya yang seperti mencari celah untuk bersentuhan denganku.
🌼
"Ini sudah siang. Aku harus kembali," ucapku setelah sekian lama basa-basi dengan Arya.
"Baiklah. Sengatan matahari tidak baik untuk kulitmu," sahut Arya dengan nada menyindir.
"Bukan begitu, aku hanya tidak ingin Emak khawatir dan mencariku," jelasku dengan nada tinggi dan ia malah tergelak.
"Aku tahu, lagi pula memang kulitmu harus dijaga, jangan cemberut seperti itu."
Aku segera berjalan meninggalkan tempat ini, tetapi lenganku dicekal tangan besarnya, membuatku berbalik badan dengan waswas. "Pakai ini, besok datang ke sini lagi. Aku akan menunggu," ucapnya sambil memakaikanku gelang berukir naga dari kayu, sama dengan gelang yang dipakai Arya sendiri.
Aku mengangguk sambil tersenyum dan menatap mata kelamnya yang juga menatapku. Lagi-lagi jantungku bertalu-talu mendapati paras yang bisa mencuci mata itu.


 orenertaja
orenertaja