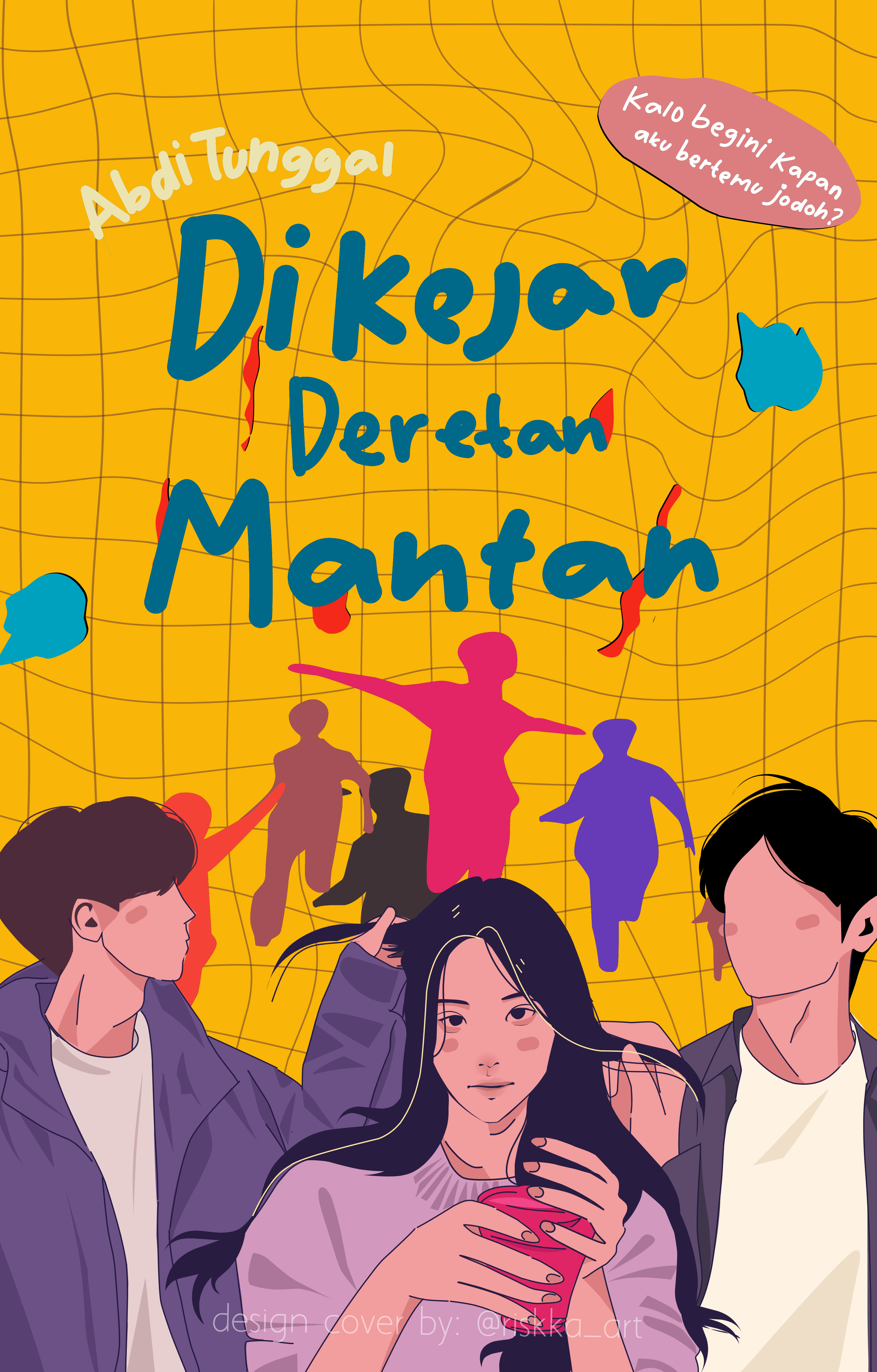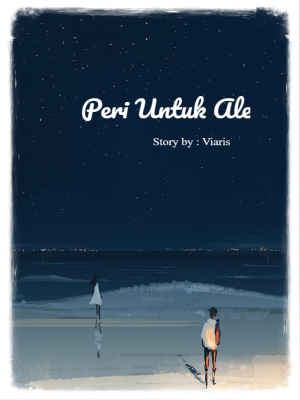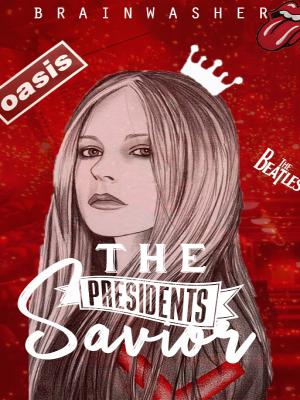Sebulan sudah setelah pertemuanku dengan Rudi di Waroeng Kenangan. Selama tiga puluh hari itu pula aku tidak mendapat kabar apa-apa dari Rudi. Bang Mul sebagai mak comblang hubungan kami juga tidak berkata apa-apa. Sebagai perempuan pula aku memilih diam dari pada memulai sebuah percakapan dengan Rudi. Kesannya, aku terlalu buru-buru dalam mendapatkan laki-laki yang mau menjadi pendamping hidupku.
Aku kembali pada aktivitas sehari-hari. Suara sumbang Mak Sari masih terus berhimpitan antara ada dan tiada. Dara pun sudah jarang sekali kulihat mukanya setelah senja itu. Aku pun tidak perlu mencari tahu kegiatan Dara, karena bagiku, sebagai pegawai negeri Dara sudah banyak aktivitas seharian, walaupun kutahu Dara hanya ke Puskesmas dari pagi sampai siang, selebihnya Dara akan di rumah atau bersama pacarnya.
Semua orang di Kampung Pesisir pernah melihat mantan pacar bahkan pacar Dara di depan rumahnya. Mak Sari sangat berbangga saat Dara dijemput pacarnya di depan rumah. Bangga Mak Sari tentu berbeda-beda, sesuai kendaraan yang dikendarain pacar baru Dara. Jika dijemput menggunakan sepeda motor matic, Mak Sari akan cemberut walau tetap membesarkan hati anaknya. Jika dijemput dengan sepeda motor besar, Mak Sari berseri-seri sepanjang hari. Dan jika dijemput dengan mobil mewah, Mak Sari akan jingkrat-jingkrat di kedainya sepanjang waktu. Selama Dara masih berhubungan dengan pacar punya mobil, selama itu pula Mak Sari membuang kata-kata pada siapa saja yang ditemui.
Haikal benar. Selama aku pulang ke Kampung Pesisir, sudah beberapa kali pula Dara berganti pacar. Aku tidak melihat dengan sengaja, di hari minggu pagi selalu kuketemui laki-laki berbeda di depan rumah Dara. Kadang Mak Sari sendiri yang monyong kiri kanan memamerkan calon menantu dengan suara cukup keras. Sengaja dibuat-buat bahasa segemulai mungkin supaya terdengar sampai ke rumahku.
Karena kesibukan juga, aku tidak sempat bersua dengan Asma, Irus, Misan maupun Risma. Hampir tiap hari aku pulang sore bahkan menjelang magrib dan malam hari. Aktivitas padat membuatku lupa harus berinteraksi dengan kegiatan lain di Kampung Pesisir. Namun aku tidak punya pilihan, aku berada di lingkaran yang menginginkanku sibuk akan hal-hal tertentu. Apalagi kampus tempatku mengajar sedang dalam proses menuju status negeri, sebagai orang yang memiliki pendidikan luar negeri dan bisa bahasa Inggris dengan lancar aku kerap dipakai dalam berbagai aktivitas. Aku mensyukuri posisi ini, semua orang di luar kampus, seperti kata Ibu, berlomba-lomba mencari kesempatan untuk dapat masuk ke dalam lingkaran yang sudah kusebutkan barusan. Sebuah lingkaran menghanyutkan bagi banyak kalangan, tentu saja dilihat dari segi finansial.
Benar kata banyak orang, sibukkan diri dengan aktivitas maka kita akan melupakan waktu yang berlari kencang. Di pertengahan bulan kedua setelah pertemuan kami, Rudi menghubungiku, sekadar bertanya kabar. Aku berharap lebih, ditelepon mungkin, atau berbalas pesan, tetapi Rudi tidak melakukannya. Di hari setelah itu, Rudi kembali mengirim sebuah pesan, kali ini lebih panjang, selain kabar juga menanyakan kondisi kesehatan dan keadaan kampus. Seminggu kemudian, Rudi sudah sering mengirim pesan dan aku pun membalas sesuai pertanyaan yang diberikan dan balas menanyakan pertanyaan yang sama. Sebatas itu, aku dapat menebak sosok lak-laki yang sedang kuhadapi. Rudi tidak pernah mengirim pesan lebih dari tiga kali. Jeda waktu antara satu pesan dengan pesan berikutnya bisa memakan waktu sampai tiga puluh menit. Padahal, aku langsung membalas pesan yang dikirimnya. Mungkin, memang ada tipikal orang yang tidak langsung membalas pesan dengan cepat. Berbeda dengan Haikal, seakan belum selesai aku menekan Tombol Kirim, balasan dari Haikal sudah kuterima.
***
Senin terakhir di bulan kedua setelah pertemuan kami, Rudi mengirim pesan singkat saja.
Ada waktu? – Rudi.
Aku jadi bertanya-tanya, tidak biasa-biasanya Rudi demikian. Rudi lebih sering menanyakan kabar, kesehatan dan pekerjaan. Menanyakan kesempatan artinya Rudi ingin mengajakku bertemu. Berdua saja begitu?
Aku tidak langsung membalas, kubiarkan seperti Rudi membiarkan pesanku selama ini, tidak langsung dibalas saat menerima pesan. Kudiamkan pesan Rudi sampai pukul lima sore, dan laki-laki itu tidak mengirim pesan lagi dan bahkan tidak mencoba memanggil namaku melalui jaringan seluler. Benar-benar laki-laki yang entah, sulit sekali kudefinisikan watak laki-laki itu.
Setelah kubalas pesan Rudi, lima menit kemudian balasan darinya muncul. Tidak ada basa-basi pula. Rudi membalas singkat saja.
Saya tunggu di Waroeng Kenangan ya. – Rudi.
Begitu saja?
***
Aku meluncur ke Waroeng Kenangan sesuai perjanjian. Rupanya laki-laki itu tidak mau macam-macam dan tidak membawa kesan gombal sedikitpun. Rudi membuat perjanjian seperti keinginannya saja, padahal aku juga ingin mengenal lebih dekat dengan pribadi laki-laki itu. Diana pernah mengatakan, duduk bersama selama lima menit saja kita akan memahami karakter lawan bicara kita. Pertemuan pertama kami bersama Bang Mul hanya sebatas memperlihatkan fisik satu sama lain. Bang Mul seakan ingin mengatakan, inilah adik kesayangannya.
Rudi sudah duduk di meja menghadap ke laut. Semilir angin menusuk rasa ingin tahuku akan keterbukaan laki-laki itu. Waroeng Kenangan tampak sepi sore ini, barangkali karena hari pertama setelah libur.
Aku menyapa Rudi seadanya saja, layaknya seorang teman lama yang sudah lama tidak bertemu. Rudi pun memposisikan dirinya sebagai seorang teman dan bersikap lebih santun dari yang kukira.
“Sudah lama?” tanyaku sambil duduk di hadapan Rudi.
“Baru saja,” Rudi memberi senyum kecil. Pandanganya lurus ke depan, menghadap laut, sesekali menatapku.
Kami diam dalam waktu yang lama, selama pesanan yang kami pesan tidak sampai dalam waktu lima belas menit. Waktu hampir menunjukkan pukul enam sore, sebentar lagi matahari akan tenggalam. Dari pelabuhan dapat kulihat beberapa orang mondar-mandir menanti matahari terbenam. Ada juga yang sudah duduk menikmati jagung bakar bersama orang-orang tercinta.
Aku kembali berpaling lurus ke depan, Rudi sedang meniup kopi panas. Wajahnya menunduk dalam-dalam memperlihatkan anak-anak rambut dibelah dua. Rudi berpenampilan lebih santai hari ini, celana jeans, baju kaos oblong waktu putih, dan sendal kulit yang hampir usang.
Waroeng Kenangan hanya menyisakan beberapa muda-mudi yang sibuk di depan laptop mereka. Aku menduga-duga, mereka lebih fokus berselancar di jejaring sosial dibandingkan mengerjakan suatu proyek. Namun, ada juga mungkin yang sedang menulis di blog pribadi atau membuat sesuatu yang lebih bermanfaat dari pada sekadar mengupdate status maupun chatting.
Aku menunggu, ibarat kencan pertama, siapa tahu Rudi akan memaparkan isi hatinya padaku. Atau Rudi akan langsung menanyakan kesediaanku menerima pinangannya. Aku yakin, Rudi bukan laki-laki yang tidak dewasa, dari caranya saja dapat kutangkap keseriusan dalam sebuah hubungan.
“Saya lahir dari keluarga kurang berada, Ayah dan Ibu sama-sama bekerja di sawah. Kami pun tidak memiliki sawah sendiri, hanya beberapa petak saja kami sewa dari orang lain untuk digarap,” ujar Rudi di sela-sela meniup panasnya kopi di cangkir kecil itu. Aku menghembuskan nafas berat. Laki-laki ini, entahlah.
“Setelah Ayah tiada, Ibu sudah tidak kuat lagi ke sawah, akhirnya saya fokuskan diri menjadi petani saja,” lanjut Rudi. Petani? Apa Bang Mul tidak salah memilih laki-laki untukku. Setidaknya aku harus bersabar sampai Rudi membuka dirinya lebih jauh lagi. Bang Mul sudah pasti menjelaskan perkenalan kami kepada Rudi. Dan inilah saatnya Rudi membuka dirinya kepadaku, agar aku bisa menerima kelebihan maupun kekurangannya.
“Saya bekerja di sawah, sawah orang lain, seperti yang saya katakan tadi,” Rudi seakan terbata. “Kamu tahulah petani itu bagaimana, kami hanya cukup untuk makan sehari-hari dan tidak lebih untuk membeli keperluan mewah lainnya. Ibu sudah saya minta untuk istirahat saja, kasihan beliau lelah bekerja sejak muda. Sebagai anak tertua pun saya tidak ingin menaruh beban kepada beliau. Sudah waktunya pula saya menuruti semua keinginan Ibu karena beliau ingin sekali bahagia di usianya kini. Hal itu pula menjadi satu alasan saya belum menikah, selain kebutuhan lain,”
Terjawab sudah pertanyaanku kepada diri sendiri saat pertama bertemu Rudi. Rudi meneguk kopi sedikit saja sebelum melanjutkan penjelasan tentang dirinya. Aku pun sudah mempersiapkan diri mempresentasikan diriku kepada Rudi setelah dia selesai. Aku harus sadar diri juga, Rudi datang ke sini hanya untuk memperjelas kedudukannya sebelum serius datang ke rumah.
“Saya punya seorang adik, laki-laki,” Rudi memposisikan duduknya lebih tenang dari sebelumnya. “Adik saya sedang menempuh pendidikan di Banda, baru melewati semester empat sebulan lalu. Karena kami dari keluarga pas untuk makan sehari-hari saja, tugas saya selanjutnya adalah membiayai pendidikan adik sampai dengan selesai. Ibu sudah tentu tidak akan mampu menyekolahkan adik sampai ke Banda, karena kami tidak punya harta apa-apa yang ditinggalkan Ayah sebagai warisan selain tanah tempat rumah kami berdiri sekarang,”
Sebagai pendengar, aku tidak dibutuhkan menanya bahkan memberi pendapat. Rudi mengulurkan senyum penuh arti. Tatapan matanya meneduhkan pandangan. Sulit kuartikan makna yang tersirat dari bola mata hitam tersebut.
“Saya pernah kuliah di Banda,” lanjut Rudi. Benarkah? Aku semakin tertarik dengan laki-laki di depanku ini. “Saya kuliah di pendidikan keguruan, kuliah sambil kerja, Ayah dan Ibu sudah mengatakan tidak pernah bisa mengirim biaya sedikit pun waktu itu. Tetapi, seiring waktu, mana ada orang tua yang sanggup menahan derita anaknya. Walau tidak dalam sebulan sekali, satu semester dua atau tidak kali saya pernah mengecap hasil keringat Ayah Ibu di kampung. Selain itu, Ayah selalu mengirim beras walau saya tidak pernah memintanya.”
Serius demikian?
“Ya,” Rudi seperti menjawab pertanyaan yang tidak kutanyakan. “Saya bekerja apa saja, kuli bangunan pernah saya kerjakan sampai malam hari, jadi kernek labi-labi[1] juga pernah saya lakoni di sela-sela waktu kuliah yang padat, mengajar di bimbingan belajar pun saya jalankan karena dari situlah nyawa saya bisa bertahan sampai sekarang!”
Aku membulatkan mata. Rasa kagum menjalar ke seluruh tubuhku. Aku tahu, aku juga mengalami nasib serupa dengan Rudi. Mungkin karena aku perempuan jadilah pekerjaanku lebih ringan, aku juga mengajar dan pernah bekerja di lembaga swasta luar negeri waktu masa transisi Aceh ke arah lebih baik.
“Bahkan, tambahan ngajar privat malam hari,” ujar Rudi terkekeh. Ah, yang benar saja? Bagaimana membagi waktunya. “Saya tidak memiliki kepintaran dalam bahasa asing dan tidak lues seperti orang lain, jadi saya kerja apa saja yang saya sanggupi.”
Tidak lues? Mana mungkin. Orang yang tidak lues itu duduk diam di rumah kontrakan, menunggu awal bulan dan akhir bulan. Orang-orang yang lues itu tidak pernah mau berdiam diri tanpa mengerjakan sesuatu yang berarti. Teman-temanku rata-rata orang berada, tiap bulan mendapat jatah hidup dari keluarga mereka, tetapi mereka tetap bekerja untuk menambah tabungan. Paling tidak mereka bisa membeli ponsel bermerek maupun baju bagus.
“Begitulah dinamika hidup,” Rudi menghamparkan pandangan ke arah matahari yang sudah berubah warna menjadi orange. “Pintar-pintar kita menyiasati tujuan dan membangun kesabaran. Saya terlahir sebagai orang kurang berada, saya harus bersyukur dengan apa yang saya dapatkan sampai ini!”
Benar. Bang Mul tidak salah pada pilihannya. Bang Mul sudah mengetahui lebih banyak tentang Rudi dibandingkan denganku, kami baru bertemu dua kali dengan ini. Tidak mungkin aku langsung bertanya macam-macam kepadanya. Lagi pula, Rudi cukup terbuka dengan keadaan ekonomi keluargnya dan karakter dirinya.
“Semula saya berniat menjadi guru sesuai ijazah terakhir,” Rudi kembali memulai perkenalan dirinya, padahal aku merasa sudah cukup untuk hari ini. Jam sudah menunjukkan pukul setengah tujuh, tak lama lagi azan magrib akan menggema di seluruh Kota Pesisir Barat. “Dua kali ikut ujian pegawai tidak lulus juga, sampai akhirnya saya ikut ujian di tahun berikutnya bukan sebagai guru. Ternyata di sinilah kemudahan dalam hidup saya. Saya berkantor di luar kemampuan latar belakang pendidikan saya sebelumnya. Namun pengalaman selama di Banda membuahkan hasil saat saya sudah bekerja di sini. Saya tidak diizinkan menjadi guru seperti cita-cita Ayah dan Ibu. Pokoknya saya bekerja sebagai pegawai negeri di lembaga pemerintah yang mengurusi proyek jembatan dan jalan misalnya,”
Aku sudah tahu. Ujarku girang. Hanya di dalam hati saja. Mana berani aku teriak di depan Rudi. Sebagai kesimpulan, sebenarnya Rudi ingin mengatakan dirinya sebagai pegawai negeri. Itu saja. Rudi suka jalan-jalan dulu dalam kata-kata panjang dalam mengenalkan dirinya. Bagiku sangat penting, karena aku akan mengetahui lebih banyak tentang laki-laki yang akan mendampingi hidupku dalam waktu sangat lama.
“Ohya, saya terlalu banyak bicara,” ujar Rudi sambil melirik arlogi di lengan kirinya. “Kita harus segera pulang, terima kasih sudah mendengarkan cerita hidup saya,” Rudi tersenyum dan memberi isyarat kepadaku untuk meninggalkan tempat ini.
Kesempatanku bercerita kapan?
Mulutku seperti sudah terkunci, aku menuruti saja langkah kaki Rudi ke luar Waroeng Kenangan.
“Lain kali mungkin kita bisa melihat matahari terbenam ya,” Rudi kembali tersenyum di saat kami sudah mencapai kendaraan masing-masing. “Hati-hati di jalan ya,”
“Terima kasih,” hanya itu. Aku bagai seorang manusia lugu yang telah terhipnotis. Dalam gamang aku menarik pintu mobil dan membenamkan diri di atas empuknya kursi di belakang kemudi. Aku melihat Rudi juga mengendarai mobil meninggalkan arena parkir Waroeng Kenangan. Aku pun tidak perlu khawatir lagi akan kondisi ekonomi jika pun Rudi menjadi suamiku. Syarat mapan dalam segi ekonomi sudah terlewati sesuai kriteria Ibu dan abang-abangku. Syarat lainnya, hanya aku yang paham bagaiman Rudi bersikap.
Sebelum aku menghidupkan mesin mobil, sebuah pesan masuk. Dari Rudi.
Saya sudah mengetahui kondisi kamu dari Bang Mul. – Rudi.
Sudah. Cuma itu.
***
[1]Kendaraan umum di Banda Aceh.


 bairuindra
bairuindra