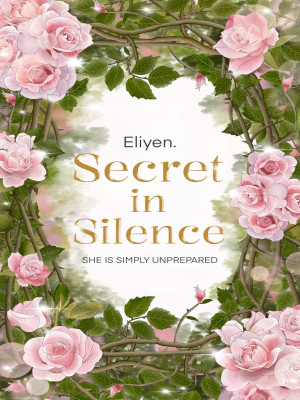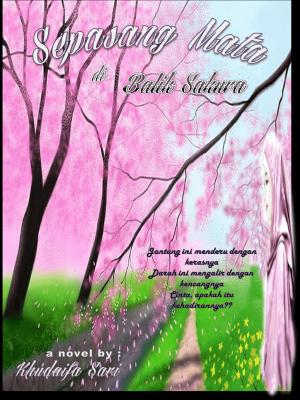Maya Kamila melirik hiruk pikuk kemacetan ibukota dari kaca bening lantai 5 gedung perkantoran. Mobil, motor, dan bus kota berjajar di jalanan dan bergerak lamat-lamat. Bunyi klakson bersahut-sahutan terdengar dari tempat ia duduk sekarang. Perempuan 27 tahun itu bergidik ngeri membayangkan betapa menyebalkannya menggunakan kendaraan ditemani kombinasi terik matahari dan antrean panjang kendaraan roda dua hingga empat.
Seseorang meletakkan segelas americano hangat dengan asap yang masih mengepul. Maya hanya melirik sekilas minuman yang terletak di atas meja. Belum punya suasana hati yang cukup baik untuk menyeruputnya.
“Minumlah!’ seru lelaki seusia dengannya.
Lelaki itu mengenakan jas hitam, celana hitam, dan dasi merah maroon. Pakaiannya rapi khas orang kantoran. Rambut undercut miliknya tertata rapi dengan polesan minyak rambut. Parfum citrus seketika menyerbak saat lelaki itu menjatuhkan diri di atas kursi tepat di depannya.
Maya Kamila menghela napas panjang. Susah payah ia menahan gemuruh di dadanya yang semakin lama semakin sesak. Lelaki di depannya, yang sudah tiga tahun menjadi suaminya, meliriknya menunggu jawaban.
“Terakhir kali, aku katakan, aku tidak melakukannya.”
Lelaki itu beringsut mundur, menurunkan tatapan tajamnya. “Kamu tahu, sulit bagi aku untuk percaya?”
“Aku tahu.” Maya mengangguk pelan. “Tapi, aku mau bertanya satu hal.”
Perempuan itu tidak sanggup lagi menahan sepasang matanya yang sekarang sudah berkaca-kaca.
“Mana yang lebih kamu takutkan, nama baik keluarga kamu tercemar atau kehilangan aku?”
Lelaki itu mendengus. Dari hati yang paling dalam, ia tahu sulit baginya untuk memilih. Ia dilahirkan turun temurun dari keluarga berdarah biru yang terkenal sebagai pemilik bisnis-bisnis raksasa seantero negeri. Keluarganya cukup terpandang. Satu rumor saja menyebar, seluruh nama baik keluarga akan tercemar. Namun, perempuan yang kini hampir menangis di depannya, sama berharganya dengan nama baik keluarganya yang sudah terlanjur terang benderang.
Rumor perselingkuhan Maya Kamila selaku kuli tinta sebuah media, dengan narasumbernya yang kebetulan salah satu investor perusahaannya, resmi membuat hatinya kini tercabik-cabik. Rumor yang ada tidak hanya dari mulut ke mulut, melainkan bukti fisik peretemuan-pertemuan mereka yang sudah sampai dengan selamat ke tangannya.
“Kamu memberikan dua pilihan itu seakan-akan kamu nggak salah!” Lelaki itu menatap kecewa. “Kamu tahu apa yang aku sesalkan? Mengizinkan kamu jadi jurnalis!”
“Dia narasumberku. Wajar kalau beberapa kali aku harus ketemu dengannya. Tapi, foto-foto di kamar hotel itu, aku berani bersumpah itu direkayasa!”
“Siapa yang mau merekayasa? Nggak ada untungnya bagi siapapun soal rumor ini! Baik pihak kita dan juga pihak mereka!” Suara lelaki itu mulai meninggi. “Dan satu lagi, pernikahan kita tersembunyi. Aku masih dikenal lajang sekarang. Jadi, menghubungkan masalah ini dengan bisnis, sangat tidak masuk akal bagiku.”
Mengingat bahwa ia dinikahi secara diam-diam, membuatnya sontak memecahkan tangis. Mengapa baru sekarang wanita itu sadar bahwa ia sangat bodoh? Mengapa baru sekarang ia sadar kalau dalam hubungan, cinta saja tidak cukup, tetapi kelas sosial juga perlu? Dunianya dan dunia lelaki di depannya sangat jauh berbeda. Wanita itu tahu bahwa keluarga lelaki itu tidak akan pernah bisa menerimanya, kenapa ia masih memutuskan untuk maju?
Bahkan, ketika lelaki itu ingin membuangnya detik ini juga, Maya tidak bisa apa-apa selain menelan ludah dan pergi dengan tahu diri.
“Bukan salahku terlahir miskin. Bukan salahku juga terlahir sebagai anak dari ayah yang kini mati overdosis karena memakai narkoba. Aku nggak bisa milih untuk ambil jalan lain.” Perempuan itu mengusap air matanya. Nada suaranya menampakkan kemarahan terhadap dunia. “Tapi, aku punya pilihan untuk menolak kamu tiga tahun lalu. Sebenarnya.”
“Kenapa sekarang kamu yang merasa jadi korban?”
Maya menarik napas panjang. Menenangkan diri. “Langsung to the point saja, apa yang keluarga kamu pengen?”
Perempuan itu menatap lelaki di depannya dengan sepasang matanya yang sembab. Semburat rasa lelah sangat tampak. Sudah satu minggu ia di usir dari rumah keluarga besar suaminya. Sudah satu minggu pula ia mendekam di kamar hotel. Sendirian.
Lelaki itu membisu. Rahangnya mengeras. Tatapannya tajam. Ia tidak mengatakan apa-apa. Namun, Maya cukup tahu apa yang setelah ini akan terjadi. Perempuan itu cukup sadar diri untuk menerima kenyataan bahwa hubungannya mungkin saja akan berakhir. Detik ini juga. Di ruangan suaminya yang nyaman dan mewah sebagai direktur utama.
“Kamu....” Dadanya sesak menanyakan sesuatu yang bahkan sebelumnya tidak pernah ia bayangkan. “Kamu mau cerai?”
Lelaki itu mendongak seketika. Terkejut dengan pertanyaan perempuan yang paling ia cintai. Maya sangat kecewa menyadari bahwa lelaki itu tidak kuasa lagi dengan tegas untuk menahannya pergi. Ia semakin sesak menyadari perjuangan lelaki itu hanya sampai di titik ini. Di titik dimana ia lebih memilih untuk lari daripada percaya kepadanya meski hanya sekali.
Maya mengusap air matanya sekali lagi. Kemudian bangkit berdiri tanpa menyentuh americano yang kini telah bersuhu ruangan. Ia melangkah pergi. Lagi-lagi, hidup tidak memberikannya pilihan selain menerima dan tahu diri.
“Maya....” lelaki itu menyahut sambil menahan pergelangan tangannya.
Ia merogoh saku celananya, kemudian menyerahkan satu buah kartu debit dan satu kunci apartemen di telapak tangan Maya.
“Kamu bisa tinggal di apartemenku selama kamu mau. Dan kamu bisa pake uang di kartu itu. Kalau kurang, akan aku transfer lagi.”
Maya mendengus. Menggenggam kedua benda yang terselip di telapak tangannya kuat-kuat. Tanpa mengucapkan terima kasih, ia mengibaskan tangan kekar lelaki yang masih mencengkeramnya, kemudian berlalu.
Tepat di depan pintu keluar, Maya membalikkan badan. Sepasang matanya melirik pria yang sangat ia sayangi dengan tatapan kecewa. Kunci apartemen dan kartu debit sudah cukup menjawab bahwa lelaki itu lebih takut nama baiknya tercemar dibandingkan dengan kehilangannya.
Perempuan itu melemparkan kunci apartemen dengan keras ke lantai, kemudian mematahkan kartu debit dengan penuh amarah. Sudah cukup tiga tahun ia bertahan karena satu kata konyol itu—cinta.
“Aku memang tidak bisa memilih dilahirkan dari keluarga miskin atau kaya raya seperti kamu. Tapi inget satu hal!” ujarnya tegas sembari mengacungkan jari telunjuk, “Aku punya kendali penuh untuk memilih jalan hidupku sendiri! Aku bisa berdiri dengan kakiku sendiri!” Lelaki itu hanya terperangah kaget dan membisu. Selama lima tahun saling mengenal, ia tidak pernah sekalipun melihat Maya Kamila semarah dan semurka ini.
“Tidak ada yang aku syukuri atas pertemuanku dengamu. Kecuali...” Maya sekuat tenaga menahan isak tangisnya. “Kesempatan menjadi seorang ibu.”
Setelah mengatakan itu, Maya melangkah keluar dengan cepat, kemudian membanting pintu ruangan direktur utama dengan keras. Tekadanya sudah bulat. Ia akan pergi. Berlari jauh sejauh-jauhnya. Tanpa pernah berpikir untuk menoleh ke belakang.
***
Maya merengkuh erat bayi perempuannya yang kini belum genap berusia satu tahun. Ranselnya yang tadi hanya berisi alat tulis, dompet, laptop, dan ponsel, kini sudah bertambah dua benda baru tepat dua jam lalu—surat pemutusan hubungan kerja dari kantor dan pesangon dengan jumlah yang tidak besar. Kini ia sudah resmi mengundurkan diri. Ia bukan lagi seorang jurnalis. Alasannya sudah jelas, ia sendirian. Tidak ada yang mengurus bayinya, sedangkan membawa bayi ke kantor adalah hal terlarang yang sering diam-diam ia lakukan. Perempuan itu juga tidak punya penghasilan yang cukup untuk memperkerjakan pengasuh.
Hujan rintik-rintik tepat di depan wajahnya. Maya sendirian di halte yang sekarang sudah gelap dan sepi. Ia memeluk erat bayinya yang kini terlelap. Semakin deras rintikan hujan, semakin pecah pula tangisnya. Hal yang ia syukuri di kondisi ini hanya satu. Setidaknya bayinya tertidur, memberikan ruang bagi ibunya untuk merengek sendirian.
Semua realita di depan mata sontak membuat tulang belulangnya ngilu, pikirannya kusut, dan kecemasan akan hidup semakin menjadi-jadi. Maya perempuan yang cerdas dan berprestasi di fakultas hukum. Tapi mimpinya terhenti seketika saat ayahnya—orang tua satu-satunya yang ia miliki—tertangkap sebagai pengguna dan pengedar narkoba. Beberapa bulan kemudian setelah di tangkap, ayahnya meninggal karena overdosis. Dunia runtuh seketika, kuliahnya putus, perempuan itu terluntang-lantung.
Kedatangan lelaki itu bersama janji-janjinya, membawa Maya mulai membayangkan masa depan yang cerah dan bahagia. Ia mulai berani membuat rencana. Ia mulai berani untuk hidup. Dan mulai berani menyerahkan diri dan ketergantungan kepada satu orang.
Satu orang yang kini kembali menghempaskannya ke dasar jurang. Satu orang yang paling ia percaya, kemudian mematahkan harapannya begitu saja.
Isakannya terhenti ketika melihat mobil jazz merah berhenti tepat di depannya. Kaca mobil terbuka, seorang perempuan seusia dengannya melirik dirinya sambil terus mencengkeram kemudi.
“Maya?”
Maya terperangah kaget menemukan teman dekatnya di masa putih abu-abu yang seketika menghilang selepas mereka lulus. Maya mencarinya, namun tak kunjung bertemu. Siapa sangka, mereka bertemu kembali 10 tahun kemudian. Bertemu kembali di kondisi semenyedihkan ini.
“Maya, ayo naik dulu!”
Maya tidak punya pilihan lain selain menurut. Sembari merangkul ranselnya, ia menyelimuti tubuh bayinya dengan jaket. Langkah kakinya menerobos hujan yang kini meluncur sangat deras, membuka pintu mobil, kemudian duduk di bangku penumpang.
Mobil kembali melaju setelah ibu tunggal itu menutup pintu dengan cukup keras.
“Kamu kenapa duduk disitu? Anak kamu bisa sakit! Mana suami kamu?”
Maya tak kuasa untuk memecahkan tangis yang kesekian kali. Bahunya bergetar. Lagi-lagi, bayinya sangat mengerti bahwa ibunya sedang butuh waktu dan tidak terbangun dari tidur lelapnya.
“Raisa, aku....” Maya mengusap wajahnya setelah perempuan bernama Raisa itu menyodorkan tisu. “Aku nggak nyangka harus ketemu kamu lagi di kondisi kayak gini.”
“Maaf ya, May, kalau dulu aku ilang.” Raisa berujar sembari tetap fokus mengemudi. “Aku langsung menikah setelah tamat SMA. Anakku udah tiga sekarang, dua laki-laki dan si bungsu perempuan. Anak bungsuku mungkin seumuran sama anak kamu.”
Maya manggut-manggut. Mencoba untuk tidak pecah tangis lagi. Ia cukup lega mendengar kehidupan Raisa yang kini membaik. Setidaknya, bertambah hal yang harus ia syukuri.
“Ke rumah aku aja, ya? Suami aku lagi ke luar kota. Kamu bisa cerita sepuasnya.”
Langit sangat pekat malam ini. Warna kehitaman yang mendominasi tak mengizinkan bintang dan rembulan sama sekali tampak. Gemuruh bersahut-sahutan seakan-akan berkompetisi siapa yang mampu mengeluarkan bunyi paling keras. Rintik-rintik berjatuhan dengan deras, membuat Raisa sedikit kewalahan melihat jalan-jalan di depannya.
Namun, diantara semua kepekatan malam ini, Maya mampu melihat setitik cahaya dari pertemuan dengan Raisa setelah 10 tahun mereka berpisah.


 gigikelinci
gigikelinci