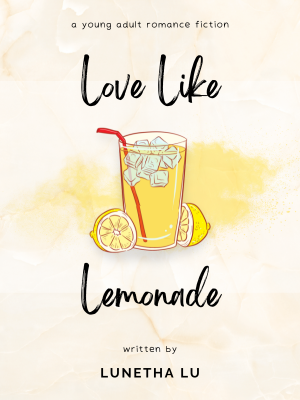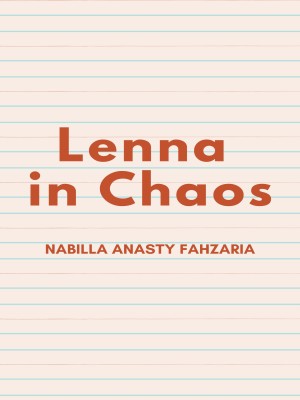Sekitar setengah jam akhirnya kami tiba di tepi Sungai Walanae. Kami turun dari ketinting lalu berjalan menuju mobil Enre. Aku dan Puang Kasii berjalan beriringan di belakang Enre. Langkahku tak terlalu cepat. Namun debar jantungku berdetak seperti tiga kali lipat. Jika biasanya rumah menjadi tempat ternyaman untuk pulang bagi kebanyakan orang tetapi berbeda dengan yang kurasakan. Berjalan menuju rumah masih menyisakan rasa ketidaknyamanan persis seperti belasan tahun lalu saat hidupku dipenuhi dengan penderitaan. Ragaku berjalan dengan terpaksa untuk pulang tetapi entah hatiku tertinggal di mana.
“Ikhlas, Wellang,” ucap Puang Kasii yang duduk di sebelah Enre di kursi depan saat perjalanan mengantarku pulang, “ikhlaskan segala kepahitan di masa lalu. Itu obatnya agar hatimu menjadi lapang dan bahagia.”
Aku tahu apa seharusnya kulakukakan. Telah berkali-kali nasihat itu masuk ke dalam telingaku dari Raya, Enre. Kali ini Puang Kasii pun memintaku hal yang sama. Namun rasanya tak semudah itu hatiku menghapuskannya. Semua sudah terlanjur mengendap dan menghitam dalam relung hati paling dalam.
“Sulit memang,” lanjut Puang Kasii, “ini bukan semudah perkara meminum susu untuk menghilangkan rasa pedas di lidah.”
“Berat, Puang.”
Puang Kasii mengangguk.
“Ikhlaskan lah semampumu,” ucap Puang Kasii sambil menunjuk ke arah dadanya, “Sejenak tenangkan diri dan berbaik sangka bahwa mungkin lelaki itu tidak tahu cara mengungkapkan perasaannya. Lupa bahwa anaknya berwujud manusia bernyawa yang perlu diajak bicara. Sejenak berpikir yang baik-baik saja bahwa ia tak sempat memelukmu dengan manja sebab lelah bekerja. Ia tak ingin bau anyir tubuh usai menangkap ikan mengotori anak kesayangannya.”
Sekitar lima menit akhirnya kami tiba di depan gang rumahku di jalan Andi Paranrengi. Mobil Enre tak bisa lewat karena jalan masuk yang sempit. Ia memarkirnya di tepi jalan lalu kami masuk ke dalam gang berjalan kaki menuju rumah. Tujuh tahun tak pulang masih tak banyak yang berubah. Para tetangga masih sama, hanya satu dua rumah kontrakan saja yang sudah berganti pemiliknya. Aku masih mengenali mereka satu persatu wajah mereka. Namun mereka sepertinya sudah tak mengenali wajahku.
Kami berhenti di salah satu rumah yang di depannya ada warung kecil yang letaknya berbeda lima rumah dari rumahku. Aku membeli minum air mineral dan beberapa jajanan ringan. Aku tersenyum sambil membayar belanjaanku pada ibu penjualnya lalu ia menyapa Puang Kassi dan Enre. Penjual itu berbincang basa-basi pada Puang Kasii. Sekilas kudengar ia berbisik pada Enre menanyakan orang asing yang baru saja belanja di warungnya yang tidak lain adalah aku. Rasanya ingin tertawa saat ibu itu tak mengenaliku. Padahal dulu aku sering sekali jajan di warungnya. Bahkan ia dulu juga sering memberikanku jajanan secara cuma-cuma. Apa benar seperti yang Enre bilang kalau penampilanku sudah berubah hingga mereka tak sadar kalau aku ini adalah tetangga lamanya.
“Coba ibu lihat dalam-dalam, masa nggak ngenalin?” ucap Enre.
Aku tersenyum saat melihat ibu itu mengerutkan dahinya.
“Masya Allah … Wellang? Anaknya ibu Tenri Sanna yang buruh tenun sutera itu? Iya kamu Wellang, ibu hafal senyuman manis itu dan sekarang jadi makin tampan.”
“Tapi masih lebih tampan saya kan, bu?” ucap Enre tak mau kalah.
Ibu penjual itu tampak kegirangan. Ia melihatku dari ujung kaki hingga kepala. Ia mencubit kedua pipiku gemas dan tak menyangka kalau yang di depannya ini adalah Wellang yang dulu sering jajan di warungnya.
***
Beberapa langkah lagi kami akan tiba di rumah. Aku berjalan dengan gelisah. Aku tak tahu bagaimana rasanya nanti saat aku bertemu dengan bapak dan betatap muka dengannya. Nasihat Puang Kasii tentang ikhlas beberapa saat lalu terasa menjadi beban yang sangat berat. Hati dan pikiranku berkecamuk. Bagaimana bisa aku menumpahkan kasih sayang kepada orang yang tidak pernah memberikan tanggung jawab dan perhatiannya?
Akhirnya kami tiba tepat di depan rumah. Entah mengapa jantungku makin berdetak tak karuan. Aku mematung sejenak melihat rumah tempatku dilahirkan dan dibesarkan. Mataku berkaca-kaca saat terlintas lagi kenangan-kenangan pahit yang kualami sekian lama di sebuah rumah yang ada di depan mata. Puang Kasii menepuk pundakku untuk menguatkan hati seraya meminta agar aku melangkah menuju ke teras rumah.
Setibanya di teras kudengar suara ibu dan Uleng dari dalam rumah. Aku tersenyum mendengar suara. Sekilas kudengar mereka sedang membahas acara pernikahan Uleng yang rencananya akan dilaksakan minggu depan. Hatiku terasa sedikit lega karena tak mendengar sedikit pun suara bapak. Aku yakin hanya ada ibu dan Uleng di dalam rumah. Semoga saja perkiraanku benar. Aku berharap ingin melihat wajah ibu dan Uleng saat pertama kali pintu terbuka.
Aku tak sabar ingin mengetuk pintu lalu bertemu dengan dua orang perempuan kesayangan. Tak lama kudengar ibu meminta Uleng untuk membelikan beberapa bahan makan di warung depan. Aku urung mengetuk pintu. Aku ingin membiarkan Uleng yang membuka pintunya. Aku ingin melihat raut wajah bahagia saat tahu aku memenuhi janji untuk menjadi wali nikahnya. Tak berapa lama pintu rumah pun terbuka. Kekembangkan senyumku yang paling indah. Aku makin tak sabar melihat reaksi Uleng saat melihatku ada di depan rumah.
***
Mendadak senyumku hilang. Napasku pun menjadi tak beraturan saat pintu terbuka dan melihat sosok yang muncul dari baliknya. Bapak dengan langkahnya yang tertatih berjalan keluar rumah. Aku mematung. Sesaat kami saling berpandangan. Kini aku berdiri di hadapan sosok lelaki yang telah membuat hatiku terluka. Ingin rasanya membalas semua sakit hati ini agar hatiku menjadi lega. Namun lagi-lagi aku teringat lagi pesan Raya bahwa aku tak perlu membuat perhitungan atas kesalahan yang telah dilakukannya. Biarlah itu menjadi urusan bapak kelak untuk mempertanggungjawabkan semua di hadapan Tuhan semesta raya.
“We ... We ... Wellang?” ucap bapak terkejut dengan suara tergagap tak segagah dulu saat melihatku ada di depan rumah.
Seketika jantungku pun serasa berhenti berdetak. Kulihat matanya berkaca-kaca. Jala dan peralatan menangkap ikan yang ada ditangannya jatuh ke lantai. Mulutnya bergetar dan seperti hendak mengucapkan kata-kata tapi tertahan. Aku membalikkan badan. Rasanya ingin lari saja dan tak ingin menjejakkan lagi kaki di rumah ini untuk selama-lamanya.
“Maafkan bapak karena tidak bisa menjadi bapak yang baik untukmu. Tidak bisa seperti bapak yang baik hatinya seperti bapaknya teman-temanmu,” ucap bapak terbata sementara aku berpura-pura tak mendengarnya.
Aku tak percaya dengan apa yang baru saja kudengar. Kata 'maaf' terucap dari mulut lelaki yang kukenal bengis hatinya. Sebuah kata yang hampir tak pernah kudengar sepanjang hidupku bersamanya. Memang tak akan pernah ada kata terlambat untuk meminta maaf dan aku pun tahu memaafkan adalah suatu perbuatan yang mulia. Namun hati ini begitu berat untuk melupakan segala keperihan yang pernah kurasakan. Terlalu sulit bagiku untuk mengikhlaskan semua yang telah dilakukannya. Bulir air mata pun jatuh tak bisa kutahan. Air mata yang keluar dari rasa sakit hati atas perlakuan kasar seorang bapak kepada anaknya. Puang Kasii menghampiriku dan memegang kedua pundakku. Aku menunduk dan enggan menatap wajah bapak. Lalu turun gerimis dari kedua mataku.
“Jadikanlah hatimu seperti air sebab jika ada luka tertulis di sana ia tak akan pernah meninggalkan bekas luka,” ucap Puang Kasii lembut sambil membalikkan tubuhku menghadap bapak, “Allah telah mengabulkan doa-doamu, Lang. Lihat di hadapanmu itu. Dia adalah doa-doa tulusmu saat meminta seorang bapak yang baik hatinya.”
Aku mengangkat wajahku dan melihat bapak yang semakin tua. Kulihat air mata mengalir di matanya yang mulai tua. Bapak melangkah mendekat. Hari ini untuk pertama kalinya dalam sejarah hidupku bapak memelukku. Aku merasakan tangisnya di dadaku. Aku merasakan tangannya makin erat memelukku. Aku biarkan tanganku menjuntai tak merespon pelukannya. Tak berapa lama ibu dan Uleng keluar dari dalam rumah dan melihat sebuah drama antara anak dan bapaknya. Aku bergeming tanpa rasa iba.
Aku berusaha tak mempedulikannya meski mataku basah. Ibu dan Uleng hanya bisa menyaksikan dari dekat pintu rumah. Kulihat ada air mata yang tumpah di pipi mereka. Aku berusaha melepaskan pelukan bapak lalu ia tersungkur di kakiku sambil terus memohon maaf dengan tangisnya yang semakin pecah. Pada saat itulah hatiku luluh dan tak tega melihatnya. Meski sebetulnya masih ada rasa perih atas segala perlakuannya. Namun aku teringat ucapan Puang Kasii saat tadi kami di Danau Tempe bahwa seburuk apapun kelakukannya dia tetaplah bapakku. Dalam nadiku mengalir darahnya. Kemarin ia pernah melakukan kekhilafan hingga begitu membekas diingatan. Namun bukan berarti dia berhati baja. Dia tetap manusia yang hatinya bisa berubah. Maka memaafkan dan mengikhlaskan adalah obat mujarab untuk membuat hati menjadi lapang dan bahagia.
“Pak ... aku sudah memaafkanmu bahkan sebelum kau menyakitiku. Aku menyayangimu sebagaimana aku menyayangi diriku. Bagaimana aku bisa tidak memaafkanmu sementara darahmu dan darahku adalah satu.”
***


 hadismevlana
hadismevlana