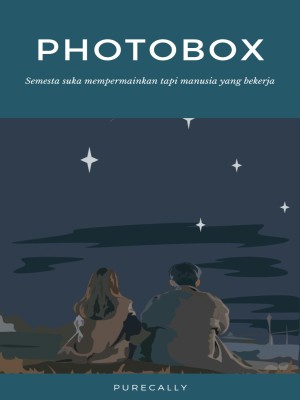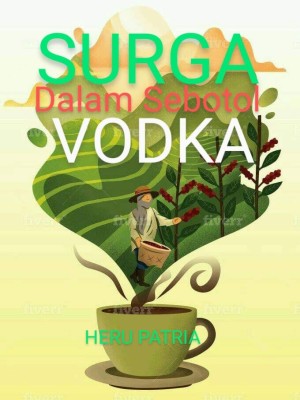Tepat di salam kedua di akhir salat isya tadi aku segera beranjak. Aku bergegas meninggalkan saf jamaah salat. Aku tak ingin bapak mengetahui kehadiranku di sini. Aku tak ingin bapak sadar bahwa aku berada di sebelahnya sejak salat tadi. Doa kulantunkan sambil berjalan dengan tergesa menuju mobil Enre. Aku berjalan lurus sambil menunduk tanpa mempedulikan orang-orang di sekitar yang juga mulai meninggalkan masjid. Setibanya di mobil aku langsung masuk dan bersembunyi di kursi belakang.
Sekitar lima menit berlalu aku mengintip ke arah pelataran masjid. Kulihat jamaah salat mulai banyak yang meninggalkan masjid. Tak berapa lama kulihat Enre pun keluar dan terlihat kebingungan, mungkin ia mencari-cariku yang tiba-tiba menghilang tak memberinya kabar. Enre celingak celinguk melihat sekitar masjid yang mulai sepi. Aku meneleponnya untuk memberi tahu kalau aku sudah berada di mobilnya.
“Kau tak menemui bapakmu dulu, Lang?”
“Hah … ada bapak?” ucapku pura-pura tak tahu.
Kulihat dari kejauhan Puang Bahar menghampiri Enre. Tak berapa lama kulihat bapak dan Puang Kasii menyusul di belakangnya. Mereka berempat berdiri di pelataran masjid sambil berbincang-bincang. Sekilas terdengar suara dari ponsel Enre kalau bapak menyebut-nyebut namaku. Mungkin Puang Bahar sudah menceritakan pada bapak kalau hari ini ia menjemputku di bandara dan sejak magrib tadi sudah tiba di Sengkang. Sekilas aku mendengar suara bapak meski terdengar tak begitu jelas. Aku mendengar betapa gembiranya bapak saat mendengarku pulang dengan suara tergagap-gagap dan pelafalannya yang kurang begitu jelas. Kulihat Enre berjalan menjauh dari mereka lalu kembali melanjutkan teleponnya.
“Sudahlah tak usah pura-pura tidak tahu. Ini bapakmu mau bertemu denganmu, Lang?”
“Please, Re, jangan sekarang,” pintaku memelas, “aku belum siap.”
“Terus aku harus bilang apa pada bapakmu?”
“Terserah kau bilang apa ke dia, yang jelas please jangan sekarang. Aku butuh waktu,” ucapku memohon, “Kau mengertikan?”
Aku menutup telepon lalu mengintip lagi ke arah mereka. Kulihat Enre sedang berbicara dengan bapak. Entah apa yang dikatakan Enre pada bapak sebagai alasan kalau aku belum bisa menemuinya. Wajah bapak yang semula terlihat gembira mendadak muram setelah Enre berbicara denganya. Bapak menundukkan kepalanya lalu Puang Bahar menepuk pelan punggung bapak sambil mengucapkan sesuatu yang entah apa padanya. Puang Kasii terlihat meraih tangan bapak dan mengajaknya pulang. Puang Bahar dan Enre berjalan ke arah mobil sementara Puang Kasii dan bapak berjalan berdua ke arah pulang. Aku pun keluar dari persembunyian di kursi belakang saat kondisi mulai aman. Baru beberapa langkah saja meninggalkan pelataran masjid, aku kaget saat bapak tiba-tiba membalikkan badannya dan melihat ke arah mobil Enre. Jantungku berdetak tak karuan dan segera bersembunyi kembali di balik kursi. Semoga ia tak melihatku.
***
Hari makin gelap. Pukul delapan malam akhirnya aku sudah tiba di rumah Enre di jalan Budi Utomo dan beristirahat di kamarnya. Sangat beruntung mempunyai teman seperti Enre. Lebih beruntung lagi aku bisa bertemu dengan keluarganya yang sejak dulu sudah menganggapku sebagai bagian dari keluarganya. Ayah dan ibunya sudah menganggapku seperti anaknya sendiri. Bahkan adik-adiknya sudah menganggapku seperti kakaknya sendiri. Bahkan setelah bertahun-tahun tak bertemu perlakuan mereka tak berubah kepadaku. Seperti yang tadi mereka lakukan saat menyambutku dengan hangat saat baru tiba di rumahnya.
Sepanjang perjalanan pulang dari masjid tadi tadi tak ada obrolan. Suasana terasa dingin tak sehangat saat perjalanan dari bandara yang di isi dengan obrolan-obralan santai. Entah apakah mungkin mereka memahami perasaanku saat ini yang masih belum bisa memaafkan bapak. Entah mungkin apakah Puang Bahar dan Enre marah dengan caraku memperlakukan bapak saat di masjid tadi. Enre membuka kaca mobilnya tepat saat mobilnya melewati bapak dan Puang Kasii. Puang Bahar dan Enre mengucapkan salam dan pamit pulang lebih dulu sementara aku tetap bersembunyi di kursi belakang. Aku hanya memberanikan mengintip dari jendela.
Kulihat mata bapak tak lepas tertuju ke arah mobil Enre sambil berjalan pelan tak segagah dulu beriringan dengan Puang Kasii. Ia berjalan agak pincang. Sesekali kulihat Puang Kasii membantu memeganginya berjalan. Mobil Enre terus berjalan pelan. Tak ada rasa iba sedikitpun di hatiku meski tadi kulihat ada kesedihan di raut wajahnya. Bahkan aku hanya bisa tersenyum sinis saat melihat ada sedikit basah di kedua matanya.
“Kau marah, Re?”
Aku membuka pembicaraan malam ini pada Enre yang baru saja menyudahi bacaan Alquran-nya. Enre dari dulu memang tak pernah berubah, sebelum tidur ia selalu menyempatkan membaca beberapa ayat Alquran. Sementara aku sudah mulai tidak konsisten lagi. Bahkan hampir sudah melupakan kebiasaan itu sejak tujuh tahun lalu.
“Kenapa kau bisa berpikir seperti itu?” jawabnya dingin sambil meletakkan Alquran yang baru saja ia baca di atas meja belajarnya.
“Dari tadi kau diam saja. Aku sudah seperti orang asing. Kau tak suka kalau aku menginap di sini? Ok aku bisa menginap di tempat lain.”
“Wellang … Wellang … dari dulu sifatmu nggak berubah, mudah berburuk sangka.”
Enre berjalan menghampiriku yang kesal sambil mengemasi kembali baju-bajuku ke dalam koper lalu menepuk pundakku. Enre meraih tanganku yang sedang memasukkan kembali baju-baju yang sudah ku keluarkan dari koper. Ia mengajakku duduk di tepi tempat tidurnya. Sejenak kami hening lalu tak berapa lama Enre menatapku. Aku yang semula tertunduk kesal akhirnya menatap wajahnya. Enre memperlihatkan wajahnya yang bersahabat. Tak berapa lama ia tersenyum padaku dan aku pun tak kuat untuk membalas senyumnya.
“Kau tak lupa dengan kenangan-kenangan yang kita lalui bersama di kamarku ini kan, Lang?”
Aku mengangguk lalu mataku menyisir setiap sudut kamar Enre yang masih belum berubah warna cat dindingnya. Tempat tidurnya pun masih belum berubah, spring bed kecil dengan kasur tambahan di bawahnya. Kamar kecil ukuran tiga kali tiga bercat putih ini merekam kenangan yang begitu banyak dalam hidupku. Enre mengingatkanku pada kenangan masa-masa lalu. Sedih dan bahagia pernah kami jalani bersama.
“Sejak kapan aku pernah berbuat jahat padamu, Lang? Tapi kau selalu berburuk sangka padaku. Bahkan setelah tujuh tahun kita tidak bertemu kau tak ada berubah sedikit pun.”
Aku tersentak dengan ucapan Enre. Kali ini dadaku terasa sesak karena rasa bersalahku padanya. Aku beristigfar dalam hati mengevaluasi segala sifatku yang mudah berburuk sangka. Kulihat Enre melihat lurus ke dinding yang ada di hadapannya. Banyak foto-foto kami terpasang di sana. Posisinya belum berubah, masih di letakkan dekat meja belajarnya. Bedanya kini foto-foto itu tersusun rapi dalam sebuah figura.
“Kau berhak bahagia dengan hidupmu. Kau masih ingat kan caranya berbahagia?” Tanya Enre sambil menunjuk ke arah dadaku.
Aku mengangguk. Enre terus bercerita tentang arti hidup yang bahagia. Ucapan Enre benar bahwa bahagia bukan semata perkara materi. Bahagia bukan sebab pujian dan kedudukan. Bahagia adalah saat di mana hati kita menyikapi segala takdir-Nya dengan lapang dada. Ikhlas atas setiap takdir baik dan buruk yang telah di tetapkan-Nya. Bahkan tak ada seorang pun yang boleh merebut kebahagian itu dalam hati ini kecuali kita yang mengizinkannya. Bukan orang lain yang membuat hati kita sengsara tapi karena kita yang telah mengizinkan keburukan mereka mengobrak-abrik hati kita.
Jangan pernah berkecil hati, jangan mengeluh saat ujian itu hadir. Jangan berburuk sangka pada Allah saat Dia mengadirkan kesulitan apalagi mengira Allah telah meninggalkan kita. Jika emas dan perak diuji keampuhannya dengan api maka manusia diuji dengan musibah yang menimpanya. Sesungguhnya Allah Maha Adil dan telah menakar ujian manusia hanya sebatas kemampuanya. Semua sesuai dengan kualitas iman di hati. Allah tidak akan membebani manusia biasa dengan ujian seberat yang diterima para nabi. Bersabarlah atas segala ujian yang menimpa dan jadikanlah ia jalan agar tetap bergantung pada Sang Maha sebab selalu ada himah di balik semuanya.
Menjelang pukul sebelas malam akhirnya kantuk mulai mendera. Lampu kamar sudah dipadamkan. Enre tidur di bed atas dan aku di bawah sama seperti tujuh tahun lalu saat aku sering menginap di rumahnya. Aku menatap langit-langit kamar yang masih terlihat karena nyala lampu tidur di atas meja belajar. Tiba-tiba Enre memanggil namaku dan aku hanya meresponnya dengan deheman: hmmm. Lalu Enre melanjutkan ucapannya yang membuatku terkejut dan membuat tidur malamku tak nyenyak. Gelisah.
“Besok pagi kau kuantar pulang, ya?”
***


 hadismevlana
hadismevlana