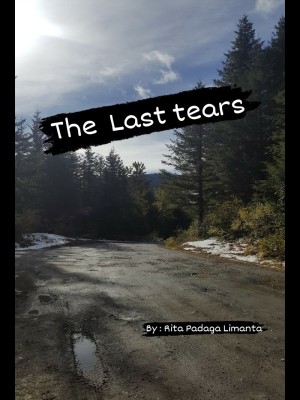Tak pernah sekali pun terucap dari lisanku untuk kecelakaan dan kemalangannya. Bertahun-tahun aku berdoa meminta seorang bapak yang baik hatinya. Namun, Allah seperti tak mendengarnya. Allah seperti tak memperkenankan permintaanku yang menurutku begitu sederhana.
Hingga akhirnya aku lelah meminta. Aku marah dan mengubah permintaanku dan berharap agar Dia mengabulkannya. Aku meminta kepada Allah untuk mengganti bapakku dengan bapak lainnya.
“Ya Allah, wellau ri idi puang tapaselleingka ambokku pappadae ambona silaungku. Ambo makessinge ampe sibawa mappojie ri anakna.[1]”
Tentang permintaanku untuk mengganti bapak itu, aku jadi teringat dengan sosok Puang Kasii Palalo[2]. Beliau adalah tetanggaku di Sengkang. Masih memiliki hubungan kekerabatan dengan Enre dari jalur ayahnya. Umurnya berbeda sekitar tujuh belas tahun dariku. Dia adalah sosok pecinta anak-anak. Selain menjadi pakkaja di Danau Tempe, hidupnya diabdikan untuk mengajarkan anak-anak mengaji selepas magrib di rumah panggung miliknya.
Puang Kasii seolah menjadi sosok yang selama ini kuharapkan. Sosok teladan yang tak pernah kudapatkan dari bapak. Dia selalu menghiburku dengan tingkah-tingkah lucunya. Puang Kasii paling jago membuat lelucon yang membuatku tertawa. Dia bisa membuatku tenang dan nyaman saat aku mendapat perlakuan buruk dari bapak. Bagiku Puang Kasii bukan hanya sekadar seorang guru ngaji dan sahabat tapi aku juga sudah menganggapnya selayaknya orang tua bagiku.
Ada sebuah peristiwa yang membuatku sangat berkesan bersama Puang Kasii. Usiaku saat itu delapan tahun. Aku masih duduk di bangku sekolah dasar kelas tiga dan pagi itu aku bolos sekolah. Sesaat sebelum aku melangkah menuju sekolah, bapak memberikan bogem mentahnya. Seperti biasa, semua dia lakukan dengan alasan yang menurutku mengada-ada. Hanya karena aku tak segera datang saat dia memanggilnya.
Pagi itu, bapak berteriak memanggilku seperti biasanya. Dia memintaku untuk mengambilkan jala. Aku sudah membawakan jala itu untuknya. Hanya saja, aku baru membawakan jala itu pada teriakan bapak yang ketiga. Bukan tanpa sebab aku tak segera memenuhi panggilannya. Saat itu aku sedang membantu ibu mencuci piring di dapur. Bapak kesal dan memukulku habis-habisan dengan sebelumnya menghujaniku dengan sumpah serapah yang menyakitkan.
Aku lari ke rumah Puang Kasii sambil menangis menahan sakit. Puang Kasii langsung panik saat melihat wajahku lebam membiru dan langsung membawaku ke dalam rumahnya. Aku duduk di ruang tamunya yang sederhana. Rumah panggung dengan lantai yang terbuat dari kayu itu hanya beralaskan tikar lusuh. Tanpa kursi dan hanya ada meja tua yang biasa Puang Kasii pakai untuk menaruh makanan di atasnya.
Puang Kasii segera mengompres lebam di wajah serta di beberapa bagian tubuhku. Aku dibiarkannya beristirahat di ruang tamu ditemani dengan segelas air putih hangat. Aku meminumnya untuk menenangkan perasaanku. Tak berapa lama kulihat Puang Kasii menggelar sajadah biru tuanya di sebelahku. Puang Kasii mengajakku salat dhuha.
Sebelumnya sudah sering kali Puang Kasii mengajakku. Namun aku selalu menolaknya. Puang Kasii selalu mengingatkanku agar jangan pernah meninggalkan salat. Sebuah nasihat yang belum pernah kudengar sekali pun dari mulut bapak. Bahkan Puang Kasii yang mengajariku tentang bagaimana cara salat yang seharusnya itu sudah menjadi tugas seorang bapak kepada anaknya. Bapakku sibuk dengan bekerja dan uangnya habis untuk berfoya-foya.
Tepat pukul sembilan pagi, aku melaksanakan salat dhuha untuk kali pertama. Entah mengapa aku merasakan pagi itu terasa sangat berbeda. Rasanya seperti ada sesuatu yang membuatku semangat untuk melaksanakanya. Salat dhuha yang begitu syahdu. Sejak takbir hingga salam kulakukan penuh khusyu. Isak dan linangan air mata banjir di pipiku.
Usai dua rakaat salat dhuha, aku bingung bagaimana caranya berdoa. Tak jauh di sebelahku kulihat Puang Kasii khusyu melirihkan doa sambil mengangkat kedua tangannya. Samar, kudengar Puang Kasii melafazkan doa-doa dalam bahasa Arab yang tak kupaham maksudnya. Tak berapa lama Puang Kasii pun menyudahi doanya. Dia heran melihatku yang hanya celingak-celinguk kebingungan. Aku bingung harus berdoa apa.
“Magai Wellang?[3]”
“Meloka mellau doang, tapi de'uwissengi parellau doang aga.[4]”
“Ellau doang bawanno nasibawai bahasamu, naissessa puang Allah Taala. Ellau bawanni aga rilalenna atimmu.[5]”
Aku mengangguk. Kuangkat tangan setinggi dada. Kupejamkan mata. Lalu, berdoa dengan khusyu. Agak lama, baru kusudahi doaku dengan mengusap wajah dan mataku yang basah. Aku lipat sajadah dan kutaruh di tempat semula.
***
Aku beranjak mendekati Puang Kasii yang sedang membetulkan jalanya. Kali ini aku ikut membantunya memasang simpul-simpul jala yang koyak menggantinya dengan benang yang baru. Aku sering membantu menyiapkan peralatan untuk digunakan Puang Kasii untuk menangkap ikan.
Aku senang membantu Puang Kasii menangkap ikan. Biasanya tagkapan Puang Kasii berupa ikan Nila, Emas atau kerapu, Gabus, Mujair sebagian besar dijual lagi ke pasar. Sementara sebagian lagi untuk diolah menjadi lauk sendiri. Kadang aku juga membantunya memanen udang di Danau Tempe. Selepas membantu memanen udang biasanya Puang Kasii memberikan sebagian hasil panennya padaku sebagai imbalannya.
Aku memang lebih sering membantu Puang Kasii menangkap ikan dibanding membantu bapak. Bukan aku tak ingin membantu, tapi setiap yang kulakukan selalu salah di matanya. Pernah satu hari aku membantunya menangkap ikan. Saat itu bapak begitu kesal, sebab tangkapan ikannya sedikit dari biasanya.
Saat bapak marah, tak segan-segan dia melontarkan kata-katanya yang kasar. Meski sudah sering sekali aku mendengarnya melontarkan kata-kata yang senada dengan itu, tapi masih saja terasa begitu sakit di hatiku.
“Cissaiii ... anak sojo ....”[6]
Bapak menumpahkan amarahnya tak cukup dengan kata-kata. Tiba-tiba mendorong tubuhku hingga jatuh ke danau. Aku berteriak meminta tolong kepadanya. Namun, dia tak menggubrisnya.
“Ambo ... kesi tulungaaa ….”[7]
Aku berusaha berenang sekuat tenaga sementara bapak meninggalkanku begitu saja. Aku berusaha berenang menuju salah satu rumah apung, tapi kehabisan tenaga. Beruntung ada perahu nelayan lain yang menolong. Jika tidak, mungkin aku sudah meregang nyawa.
***
“Wellang, tadi berdoa apa sih?” tanya Puang Kasii pelan, “khusyu banget, sampe menangis gitu.”
Aku tersenyum malu-malu. Ternyata diam-diam Puang Kasii tadi memperhatikanku.
“Rahasia dooong,” jawabku membuat Puang Kasii penasaran.
“O rahasia ya?” tanyanya, aku mengangguk sambil terus membantu membetulkan jala, “kita kan teman. Kalau teman itu apa saja boleh saling terbuka loh.”
Mendadak aku terdiam. Aku menghentikan aktifitasku lalu menunduk dalam.
“Tadi Wellang berdoa pada Allah ...,” ucapku gugup lalu memberanikan diri mengangkat wajahku lalu menatap wajahnya.
“Tapi, Paman jangan marah ya?”
Puang Kasii pun mengangguk
“Wellang minta sama Allah, kalau Wellang boleh ganti ayah, Wellang mau Paman yang jadi ayah Wellang. Boleh kan Paman?”
Puang Kasii tak menjawab. Kulihat matanya berkaca-kaca lalu memelukku erat-erat. Aku dapat merasakan dahiku basah dihujani tetes air matanya. Aku juga dapat merasakan ada gemuruh di dadanya. Dia orang yang sangat perhatian layaknya seorang ayah kepada anaknya.
Puang Kasii sangat paham dengan perasaanku. Puang Kasii sangat hafal bagaimana bapak memperlakukanku. Beberapa kali dia membela dan melindungiku dari kezaliman bapak. Bahkan Puang Kasii sempat hampir berkelahi dengan bapak saat dia mengetahui aku kena sabetan ikat pinggang, sapu lidi, penggaris dan barang lain yang biasa dijadikan sebagai bahan untuk memukulku saat bapak menumpahkan amarahnya.
***
[1] Ya Allah, aku minta agar Engkau ganti bapakku seperti bapaknya teman-temanku. Seorang bapak yang penyayang dan juga baik hatinya.
[2] Puang : sapaan untuk orang yang lebih tua dalam bahasa Bugis
[3] Kenapa Wellang?
[4] Mau berdoa, tapi bingung mau doa apa.
[5] Berdoa saja dengan bahasamu, Allah mengerti kok. Minta saja pada Allah apa yang ada di hatimu.
[6] Dasar … anak pembawa sial ….
[7] Pak … tolooong ….


 hadismevlana
hadismevlana