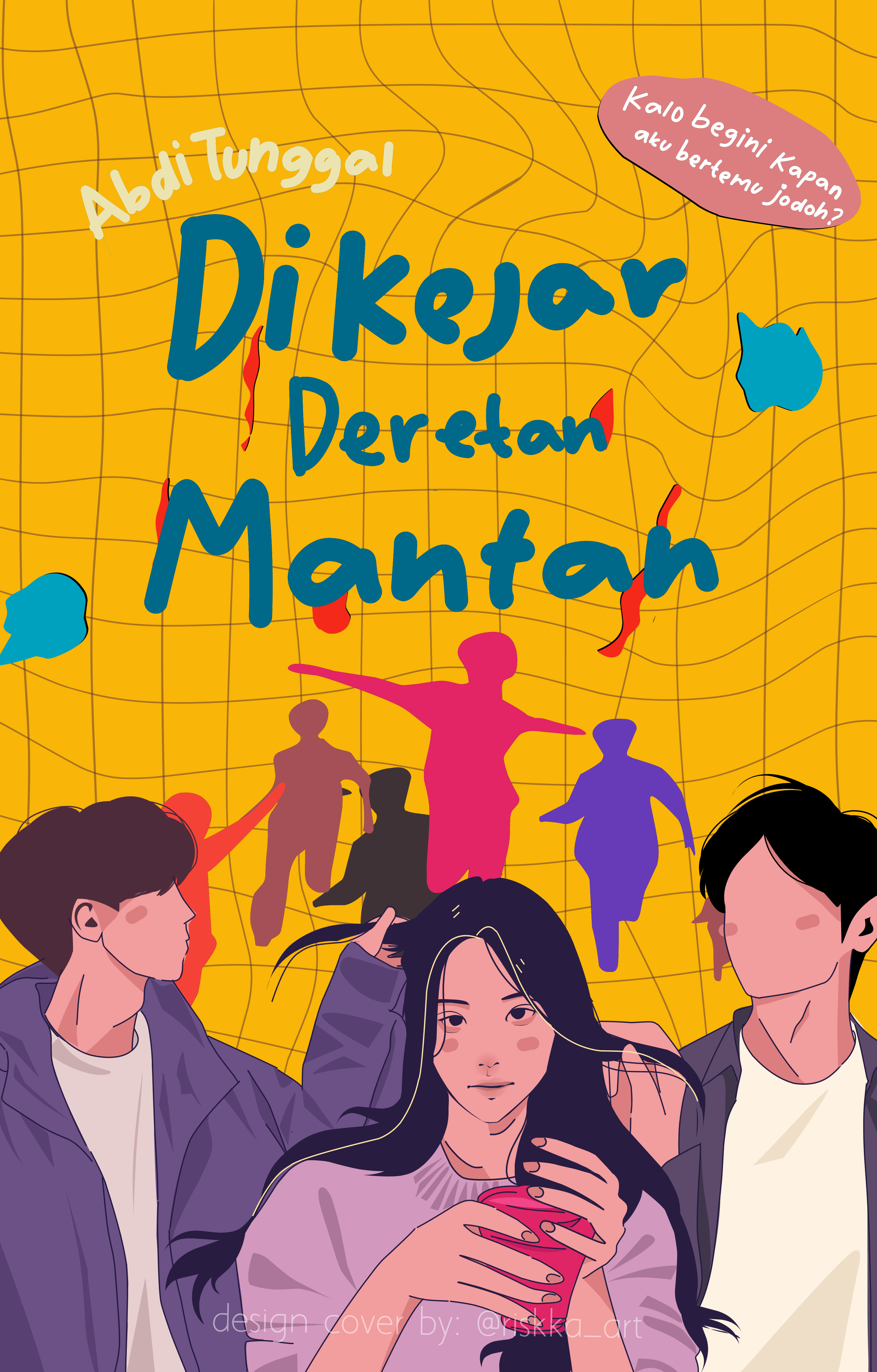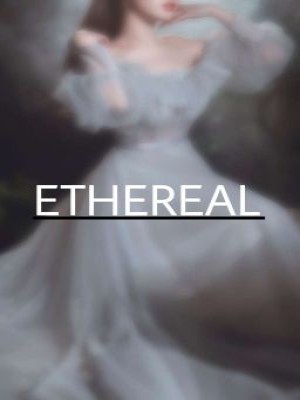“Ibuuu … Uleeeeng …,” teriaku melihat dua perempuan kesayanganku menjerit kesakitan
Ternyata ibu dan adikku berusaha melindungiku dengan badan mereka agar aku tak terkena tamparan bapak untuk yang ke sekian kalinya. Aku langsung panik dan memeluk mereka dengan erat.
“Kalian mau menjadi pahlawan untuknya?”
“Sudah, Pak! Pukul saja aku. Jangan sakiti adik dan ibuku. Ayo!” aku setengah menantang bapak.
Mata bapak makin merah. Tulang rahangnya menonjol memperlihatkan amarah. Namun, aku sudah terlanjur sakit. Aku balas menatapnya. “Jika aku harus mati di tangan bapak, maka matilah,” pikirku.
Akan tetapi, bapak akhirnya menghindar. Dia pergi keluar dengan membanting pintu keras-keras hingga kaca jendela pun bergetar. Sejenak kami aman dari amuknya. Kami saling menenangkan diri dari semua yang baru saja kami lewati.
Lagi, hari ini mesti kulingkari tanggal di kalender itu dengan spidol warna merah. Entah, kapan akan berakhirnya. Sepertinya, aku masih punya banyak kesempatan untuk melingkari kalender hingga seratus delapan puluh hari ke depan. Atau bahkan lebih hinga tahun berikutnya sampai bapak puas. Sampai aku mati.
***
Mengapa Tuhan memilihku untuk menjalani hidup seperih ini?
Mengapa Dia memilihkan langit gelap untuk memayungi hidupku tanpa henti.
Mendung dan hujan badai seperti tak berkesudahan.
Petirnya menyambar sampai ke hati membuat tubuh gemetar.
Kadang aku berpikir mengapa Tuhan begitu jahat sekali?
Mengapa Dia membuat hatiku remuk hingga tak bisa terangkai lagi.
Darahku tak panas lagi.
Napasku tak lega lagi.
Aku seperti disiksa perlahan untuk menuju kematian.
Jika hidup ibarat merajut jubah yang elok, mengapa begitu sulit untukku merajutnya? Terlalu banyak benang kusut yang mesti kuurai. Bukan enggan berikhtiar. Aku lelah. Sebab setiap langkahnya ranjau. Setiap sandarannya adalah pohon berduri.
Berkali-kali perasaan dan pikiran jahat itu datang. Berkali-kali pula Raya berusaha meluruskannya. Tak jarang dia menjadi malaikat yang hadir untuk menenangkan. Dia menjadi pendengar yang baik di setiap kali keluh kesah kuungkapkan. Sering kali, dia menasihatiku hingga terngiang-ngiang di ruang kalbu.
Aku masih mengingat betul kata-kata Raya waktu itu, “Manusia dan masalah itu ibarat api dengan panasnya. Tidak pernah bisa dipisahkan. Akan selalu ada seperti hujan di musim kemarau. Namun, Allah juga tidak akan memberikan masalah yang kita tidak bisa menghadapinya. Setiap masalah pasti ada jalan keluarnya.”
Aku percaya itu. Kata-kata indah yang membuat semangatku bangkit lagi usai terpuruk dalam sebuah masalah. Ibuku juga sering berkata seperti itu, tapi sampai kapan? Apakah sampai aku mati?
***
Pesawat transit di Changi Airport Singapore. Kami bermalam di ruang tunggu bandara di Terminal 2. Esok, baru kami akan melanjutkan perjalanan untuk kembali pulang ke Indonesia. Seandainya saja pemerintah membuka jalur penerbangan langsung dari Indonesia ke New Zealand, tentu kami tak perlu susah-susah harus transit di negeri orang. Meski sebenarnya kami bisa pulang melalui jalur lain, melalui Australia.
Namun, dengan berbagai pertimbangan, akhirnya transit di Singapura menjadi pilihan kami karena terasa lebih aman dan nyaman. Sebab, jika memilih jalur melalui Australia, kami khawatir akan ada delay pesawat. Itu artinya kami harus tinggal beberapa waktu lamanya di sana. Bukan perkara hanya sekadar lelah menunggu masa delay-nya. Itu mungkin tak jadi masalah. Sudah biasa terjadi dalam dunia penerbangan. Kekhawatiran kami lebih dari itu. Sebab, jika lebih dari delapan jam, kami memerlukan visa transit dan itu akan jauh lebih merepotkan.
Jam di dinding ruang tunggu menunjukkan tiga puluh menit berlalu dari pukul delapan malam waktu setempat. Rona terlihat begitu kelelahan. Dia duduk di sofa empuk ruang tunggu dengan kaki yang diselonjorkan. Seperti biasa, Rona menyandarkan kepalanya di pundak Raya yang duduk di sebelahnya. Kali ini Raya tak membelai kepala Rona. Mata mereka terpejam. Punggung raya bersandar di sofa dengan wajah menghadap ke langit-langit.
Sementara aku beranjak ke salah satu sudut ruang tunggu. Area seluas dua kali dua meter itu dijadikan sebagai pojok baca. Buku, majalah, koran tersusun rapi di atas rak kayu berwarna coklat tua. Aku mengambil salah satu buku bacaan dan majalah yang tersusun rapi di sana. Lalu, memilih duduk di kursi yang berada tepat di sebelahnya.
Masih ada waktu beberapa jam untuk kami beristirahat sebelum akhirnya melanjutkan perjalanan berikutnya. Masih ada waktu untukku berpikir secara jernih untuk memutuskan rencana berikutnya.
Ah Raya ... caramu kali ini membuatku seperti memakan buah simalakama.
***


 hadismevlana
hadismevlana