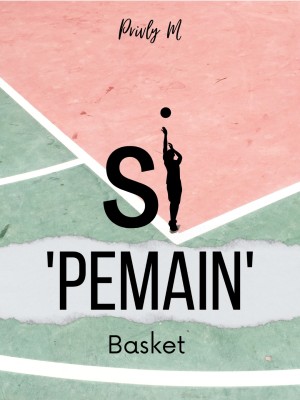“Kenapa Bapak tak bertanya terlebih dulu padaku?”
Plak!! Aku terhuyung. Hampir saja jatuh. Mataku berkunang-kunang. Tamparan bapak yang tiba-tiba membuat tubuhku kaget. Pipiku terasa panas.
“Diam! Dasar anak sialan! Ngapaian kau coret-coret kalender!” Bapak membentakku.
Aku menunduk. Tak mau menatap wajahnya yang seperti raksasa kalau sedang marah.
“Aku hanya ingin mengenang hari-hari bersejarah dalam hidupku,” ucapku sambil menahan tangis.
“Bersejarah? Jika tiap hari bersejarah tak perlu kau tandai di sini,” ucap bapak sambil menunjuk ke kalender di atas meja, “cukup kau tandai di pikiranmu saja.”
“Aku sudah mengingatnya juga bahkan sampai meresap ke hati.”
“Eeee ... kurang ajar, malah menjawab ... dasar anak durhaka ....”
“Pak ...” ucapku memberanikan diri sambil menatap mata bapak, meski sesungguhnya aku ketakutan. Jantungku mau copot sebab berdetak tak keruan, “Sebelum menyebut aku anak durhaka, apa bapak sadar kalau sebenarnya bapak telah menjadi bapak durhaka untukku?”
Sudah sering kali aku mendapat julukan anak durhaka dari bapak. Entah, karena hal apa sehingga dia dengan begitu tega menyematkanku dengan julukan itu. Padahal, aku tak pernah membantahnya. Aku selalu mendatangi setiap panggilannya. Aku berkata sopan dan tak berani melawan. Namun, kerap kali perlakuan bapak kepadaku malah sebaliknya.
Aku bingung. Perlakuan atau kata-kata yang sudah kuucapkan kepada bapak sehingga dia mengatakan aku sebagai anak durhaka? Jujur aku penasaran, apakah hanya ada istilah anak durhaka saja di dunia? Apakah tidak ada bapak yang durhaka kepada anaknya?
“Aga muaseng? Anana' sojoo![1]”
“Benar kan?" ucapku dengan bibir bergetar ketakutan, “Bapak sudah durhaka terlebih dahulu padaku.”
“Praaakkk ....”
Kembali sebuah tamparan menghantam wajahku. Panas dan sakit sekali.
“Cukup ... cukup ....” Ibu berlari sambil berurai air mata dari kamar dan langsung memelukku.
“Jangan kau siksa anakku lagi.” Air mata ibu makin deras. Pelukannya semakin erat. Ada kehangatan mengalir dari tubuh ibu ke tubuhku.
“Kamu yang sabar ya, Nak,” ucap Ibu terbata-bata di tengah isaknya.
Aku hanya mengangguk. Air mataku berlinang. Dadaku menahan sesak. Gerahamku kugigit kuat-kuat. Andai aku sudah besar pasti bapak akan aku lawan.
“I-ini pakai kalender punyaku saja, Pak,” adikku memberikan sebuah kalender meja dengan tangan gemetar lalu bersembunyi di balik punggung ibu.
Bapak menatap ganas ke adikku. Persis seperti yang bapak lakukan padaku. Tangannya gemetar sambil membenamkan wajahnya di punggung ibu. Aku menatap kalender di atas meja. Setiap kali bapak bertindak kasar padaku maka setiap kali itu pula kulingkari tanggalnya. Sudah berapa banyak yang kulingkari? Sama jawabannya dengan sudah berapa kali bapak memukulku, menamparku, berkata kasar padaku dan tindakan-tindakan lain yang tidak seharusnya dilakukan seorang bapak kepada anaknya.
Dalam kesakitan ini aku berusaha kuat. Aku memberanikan diri mengatakan kebenaran, bahwa apa yang dilakukan bapak selama ini padaku, pada kami sekeluarga adalah suatu kesalahan. Bapak makin geram mendengar penjelasanku. Bapak terlihat tak terima dengan ucapan-ucapanku untuknya. Namun, aku tetap mengungkapkan semua isi hati yang selama ini kupendam sendiri. Sementara aku melihat ibu menangis sedih dan tetap membelaiku dengan tangannya yang begitu hangat. Sehangat cinta dan kasih sayang yang selalu dia berikan untukku dan adikku.
“Aku sering melintasi pasar ketika pulang sekolah. Bapak tahu siapa saja yang kutemukan di sana selain para pedagang-pedagang, tukang ojek dan tukang parkir?”
Bapak tak mengiraukan ucapanku. Dia duduk di kursi ruang tamu dengan mata memandang langit-langit sambil menggenggam tangannya seperti siap untuk meninju. Aku tak peduli. Aku terus mengatakan semuanya meski aku tahu bapak tidak terima. Aku tahu bapak akan marah besar. Apalagi dia menganggapku bukan siapa-siapa. Mungkin bapak merasa harga dirinya akan jatuh jika mendapat nasihat dari anaknya.
“Aku bertemu dengan para preman pasar. Setiap aku melintas di sana tak sekalipun mereka berlaku kasar seperti yang Bapak lakukan selama ini padaku. Mereka kadang bisa lebih sopan dan punya hati yang sangat manusiawi.”
“Kau menyamakan Bapak dengan preman pasar?”
Jujur, aku heran mengapa bapak bisa melakukan hal-hal yang seorang preman pun tak pernah melakukan itu padaku.
“Bapak bisa menilainya sendiri ....”
Bapak makin geram. Dia bangkit dari duduknya. Tangannya mulai bersiap mengayun ke arahku. Aku memejamkan mata. Hanya bisa pasrah atas kejadian yang akan menimpaku selanjutnya.
“Kurang ajar ....”
“Praakkk ....” Kali ini bunyinya makin keras.
Namun, aku terkejut saat mendengar suara ibu dan adikku melengking kesakitan.
***
[1] Apa kau bilang? Anak tak tahu diri!


 hadismevlana
hadismevlana