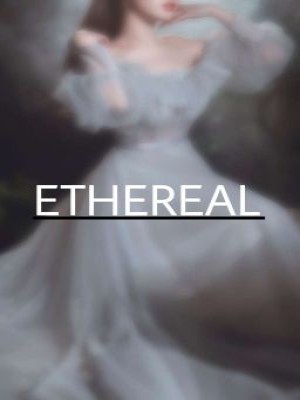Tergesa-gesa aku keluar kamar. Dan saat pintu dibuka, bau roti panggang langsung menyerang rongga hidungku. Padahal, biasanya bau roti panggang Bunda akan menyeruak ke sela-sela pintu dan otomatis membawaku melayang ke dapur. Aku akan duduk manis di meja dapur dan menunggu roti-roti itu matang untuk menyobeknya selagi masih mengepul. Ditemani segelas susu hangat pasti akan membuat sisa malamku menyenangkan. Tapi kali ini tidak. Aku lebih butuh jawaban Bunda dari pada kenikmatan hakiki itu.
“Pasti kamu keluar gara-gara nyium wangi rotinya, kan?” sapa Bunda riang ketika melihatku.
Maaf Bunda, aku memang menyukai roti manis Bunda. Tapi ada yang lebih penting dari roti-roti itu.
“Nda, Nana nemu foto ini,” kataku to the point.
Foto Tian dan Mbak Nana membuat mata Bunda terbelalak sekian detik dan berubah sendu di detik berikutnya.
“Kamu sudah menemukannya?” Sudah menemukannya?
“Iya. Di kolong tempat tidur Nana. Memangnya, Nana seharusnya sudah menemukannya sejak lama?” tuntutku.
Bunda melipat bibirnya, tanda bahwa dia sedang berpikir. Kebiasaan Bunda ketika kesulitan mengungkapkan jalan pikirnya. Dan benar, jawaban Bunda tak kunjung aku dapatkan setelah semenit penuh.
Ting!
Bunyinya berasal dari timer oven yang kemudian menginterupsi waktu tungguku.
Aku sabar menanti ketika Bunda mesti mengeluarkan roti-roti yang berwarna golden brown itu dari oven dan meletakkannya ke cooling rack. Kemudian, Bunda mengeluarkan tangannya dari sarung tangan anti panas dan dengan cekatan memoles permukaan si roti dengan butter.
Aku tahu roti itu memanggil-manggilku untuk segera mencicipi mereka. Tapi perkara kotak sepatu lebih penting.
Bunda akhirnya duduk di sebelahku. Sungguh lima menit yang panjang!
“Yang ini isi selai bluberi, coklat, keju.” Bunda menunjuk roti sobek bertabur biji wijen isi enam belas buah dalam satu loyang. “Yang satu lagi roti manis tanpa isi. Nana mau yang mana?”
“Ndaaaa,” rengekku tak sabar. “Apa seharusnya Nana membuka kotak sepatu itu sejak lama? Tapi kan, isi kotak itu bukan punya Nana. Punya Mbak Nana.”
“Mbak Nana,” ulang Bunda. Bunda tersenyum jenaka, matanya menerawang namun terkesan playful di saat yang sama. Apa ada yang terlewat olehku? Mbak Nana kan kakak sepupuku. Aku pikir tidak ada yang aneh dengan kalimatku tadi.
“Kotak sepatu itu memang kepunyaan Nana. Tapi, Bunda pikir kotak itu sudah waktunya menampakkan dirinya ke kamu, Nak. Takdirnya yang di Atas.” Telunjuk Bunda mengarah ke langit-langit rumah.
Apa lagi ini? Bunda bikin aku over thinking. Tapi over thinking untuk apa?
Bunda menurunkan kaca mata baca yang tersangkut di rambutnya yang sudah memutih.
“Nana,” ucap Bunda lembut ketika menatap foto Mbak Nana beberapa detik dengan wajah... sendu atau rindu? Entahlah. Aku juga enggak tahu. “Ini foto dia waktu kelas dua SMA. Tahun 99 atau 2000, ya?”
“Tahun 2000,” jawabku.
“Dan ini... Tian.” Tiba-tiba suara Bunda seperti menggeram rendah, layaknya sedang marah. Tapi kalau pun Bunda marah, aku bisa mengerti alasannya. Jika aku di posisi Bunda, aku juga pasti bakal marah sama si Tian. Ehm, mungkin untuk ke depannya, kamu bisa menyebutnya dengan Om Tian, Alina.
“Bunda tahu apa yang terjadi pada Mbak Nana dan Tian?”
“Ya.”
“Nana juga baru tahu kalau Bunda dulunya... pernah kena... endometriosis,” kataku terbata-bata. Aku perhatikan Bunda kaget. “Aku tahu dari buku diary Mbak Nana,” kataku buru-buru.
Kepalanya masih mendunduk, tapi matanya mengintip dari balik kaca mata plus berbingkai hitam tebal itu untuk melihatku. Bunda malah tersenyum.
“Alhamdulillah. Bunda sudah dinyatakan sembuh oleh dokter. Tapi ya, konsekuensinya rahim Bunda di angkat.”
Aku terkesiap. Spontan aku remas lembut tangannya. Bunda tersenyum tegar.
“Kapan kejadiannya, Nda?”
“Tahun 2001, saat Aruna masih di sini.”
“Di sini?!” ulangku.
Bunda mengangguk. “Nana pernah tinggal di rumah ini beberapa bulan.”
Sesuai dengan isi buku diari Mbak Nana.
Helaan nafas Bunda membuatku memperhatikan Bunda lebih saksama. Bunda menanggalkan kaca mata plus-nya dan beliau memijit pangkal hidungnya.
“Anak yang malang,” ucap Bunda bak berbela sungkawa.
“Siapa, Nda?”
“Nana.”
“Aku? Kenapa aku anak yang malang?”
Bunda terkekeh. “Maksud Bunda, Aruna. Nasib anak itu malang sekali.”
“Ooh.” Aku jadi bingung sendiri dengan dua Nana ini.
“Berarti Nana... maksudku aku belum ada waktu Mbak Nana tinggal di rumah ini. Benar, kan?” tanyaku tak yakin. Karena aku tidak pernah bertemu dengan Mbak Nana seumur hidup.
“Tentu saja belum.” Bunda lagi-lagi terkekeh. “Kamu masih... bagaimana ya Bunda menjelaskannya? Kamu masih berenang di dalam perut ibumu. Di tengah kesulitannya hamil, Nana selalu menemani Bunda bolak-balik ke rumah sakit. Dia juga yang menunggui Bunda saat Bunda operasi hingga masa pemulihan.”
Sebentar, sebentar. Perut ibuku? Perut siapa? Ibumu ya, Bundaku, kan? Bunda bikin aku bingung aja! Penjelasan Bunda terlalu berbelit-belit. Tapi karena belum ketemu ujung cerita ini, maka aku diam saja.
“Sekarang Bunda sudah segar bugar.” Bunda mengusap area perutnya. “Yaaa, kadang masih ada nyeri yang bikin nggak nyaman.”
“Kenapa Bunda enggak pernah cerita ke Nana?”
“Hmm, belum waktunya. Eh tapi, mungkin hari ini sudah waktunya ya.” Bunda kembali tertawa kecil. Tapi aku tidak melihat ada yang lucu di sini.
“Lain kali, kalau ada hal besar seperti itu, Bunda harus beri tahu Nana. Oke?”
“Oke, anak Bunda.” Tiba-tiba Bunda membelai pipiku dan wajahnya terlihat sendu.
Aku menunjuk foto Mbak Nana dan Tian. “Bunda jadi aneh setelah foto ini Nana lihatin ke Bunda.”
“Karena berkat Nana yang ini...” Bunda mengangkat foto Mbak Nana. “...Bunda akhirnya bisa merasakan bagaimana rasanya menjadi seorang Ibu setelah rahim Bunda diangkat. Setelah penantian puluhan tahun, Nak. Apa lagi Mas Raharjo sudah mendahului kita.”
Ayahku, Bapak Raharjo Budiman telah mendahului kami ketika aku masih di dalam kandungan—begitu cerita Bunda dulu. Aku tidak mempunyai kenangan apa pun bersama Ayah. Semoga Ayah tenang di alam sana. Tapi, kata-kata Bunda semakin aneh di kupingku.
“Nda, dari tadi omongan Bunda tuh bikin Nana pusing.” Itu memang benar. Aku makin pusing dengan teka-teki kata-kata Bunda.
Bunda gantian meremas tanganku kini. Mata Bunda mulai berkaca-kaca, dan akhirnya luruh juga satu tetes, tapi aku tidak bisa membaca ekspresi Bunda. Apakah itu air mata bahagia atau duka lara?
“Kamu hadir ke dunia lewat rahim Aruna Cempaka, Nak.”
“A-apa, Bun?”
Apa aku salah dengar? Mana mungkin aku lahir dari rahim Mbak Nana? Tapi selang beberapa detik, suaraku tak juga keluar karena aku sedang sibuk mengulangi kalimat, aku lahir dari rahim Mbak Nana di kepalaku.
“Bunda mengatakan yang sebenarnya.” Sialnya, tidak sedikit Bunda terlihat bercanda. Bunda.Sangat.Serius.
“Bunda jangan bercanda,” kataku dengan diiringi tawa kecil. Aku berharap aku memang salah dengar dan Bunda sedang mengerjaiku.
“Tuhan tidak pernah bercanda, Nak.” Dadaku seketika berdebar aneh. Dentamannya begitu kuat hingga membuatku tak nyaman.
Mimpi apa aku semalam? Tolong siapa pun, hantam kepala ini dengan godam dan buat pernyataan Bunda itu salah. Ini, ini pasti prank Bunda, tapi kenapa terasa begitu nyata? Tanganku yang Bunda remas aku tarik perlahan, membuat seulas luka terpancar dari wajahnya. Maafin Nana, Nda.
Ujung jariku mendingin, dadaku bergemuruh hebat. Ingin rasanya membuat Bunda tertawa, menghilangkan gurat kesedihan dan keseriusan di wajah beliau. Aku enggak suka melihatnya.
“Bunda. Bunda ngomong apa, sih? Mana mungkin Mbak Nana...” Oh Tuhan, lidahku bahkan tak sanggup mengucapkannya.
Lalu potongan demi potongan tulisan Mbak Nana menari-nari di kepalaku, seakan mencemooh, mencebik pikiranku sendiri karena menertawakan kebodohan dan kelemotan otakku dalam menyambung semua benang merah.
“Satu hal yang mesti kamu ubah. Jangan panggil dia Mbak Nana. Panggil dia Mama.”
***
Adegan aku memohon-mohon pada Bunda agar mengatakan semua yang aku dengar hanya bercandaan Bunda masih terekam dalam memoriku. Di balik selimut, aku melindungi tubuhku dari serangan kenyataan bahwa aku bukan anak Bunda. Mengingatnya membuat aku meraung sekali lagi di dalam bantal.
Oh Tuhan. Drama apa ini? Aku bukan anak Bunda melainkan anak sepupuku. Bukan, bukan. Mbak Nana bukan sepupuku. Dia ibuku! Aku kembali terisak parah. Demi Tuhan. Aruna Cempaka adalah ibu kandungku!
Betapa hebatnya takdir bermain-main denganku. Sungguh luar biasa rencana Tuhan menggiring para aktor dan aktris memperagakan peran mereka masing-masing sesuai skenario Maha Sempurna sehingga membuat orang lain terkecoh untuk ikut tertawa, menangis, dan merana. Dan aku telah terkecoh dengan sosok yang aku anggap ibu kandung ternyata adik dari papa Mbak Nana sendiri. Namun, justru kasih sayang Bunda yang sangat luar biasa membuatku percaya bahwa beliau adalah ibu kandungku.
Aku sayang bunda. Sangat. Namun, mengapa harus menunggu 21 tahun kemudian baru kebenaran diungkapkan? Mengapa harus menunggu aku kejatuhan anting?
Apa aku baru saja terkesan menyalahkan Tuhan? Oh Tuhan Yang Maha Pegampun, ampuni kelancangan hamba. Ini semua, terlalu tiba-tiba.
Dan Mbak Aruna... Dia meninggalkanku tanpa merasa bersalah dengan beralasan tak bisa menghirup oksigen yang sama denganku. Dia juga tak bisa hidup satu atap denganku. BULLSH*T. Itu pasti akal-akalannya saja karena tidak mau memelihara darah daging sendiri, kan? Mungkin kekerasan hati dan kekerasan kepala Om Widhi dan Tante Mayang sudah mengakar dalam gen Mbak Aruna.
“Aaaaargh!!!” Semoga bantal malang ini bisa meredam teriakan putus asaku.
***
Bangun pagi, mataku super bengkak dan kepalaku tak mau diajak berkompromi. Beneran sakit. Obat sakit kepala jadi solusi sebelum salat Subuh.
Setelah selesai mengadu pada Tuhan, entah mendapat wangsit dari mana aku berjalan menuju lemari pakaian dan mengeluarkan beberapa pasang baju dan celana, kemudian memasukkannya ke dalam tas ransel.
Aku robek sembarang kertas dan mulai menulis di sana.
Bunda, Nana butuh ruang dan waktu untuk menjernihkan pikiran. Nana akan pulang bila hati Nana kembali lapang.
Love, Alina Camellia, anak Bunda sampai kapan pun.
PS: Nana selalu sayang Bunda.
Semoga Bunda menemukan kertas tadi di pintu kulkas.[]
Bersambung


 kepodangkuning
kepodangkuning