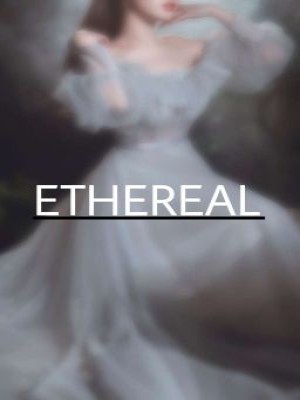Gini amat hidupku!
Apa yang sudah aku perbuat di kehidupan sebelumnya? Apa aku dulunya manusia yang merugikan negara? Membuat warga sekampung lenyap? Atau, dulu aku anak geng motor yang meresahkan masyarakat sehingga diriku yang sekarang dikutuk Tuhan?
Tapi, kata dikutuk Tuhan sepertinya berlebihan, deh. Soalnya, hidupku bersama Bunda selama mencecah di bumi begitu damai, tentram, dan menyenangkan selama dua puluh satu tahun ini. Dan ketentraman itu dihempaskan dalam sehari setelah kotak pandora itu aku buka.
Iya, kotak pandora dengan segala kejutan di dalamnya. Dan kotak pandora yang aku maksud literally sebuah kotak sepatu berdebu yang tak sengaja aku temukan di bawah dipan kasurku! Ini adalah kotak yang membelokkan hidupku yang tenang menjadi sebuah wahana halilintar. Kotak ini juga yang memberiku tahu aku bahwa selama ini aku bukanlah diriku yang sebenarnya.
Aku siapa? Aku di mana?
Ya Tuhan. Sinetron banget hidupku. Sungguh, kotak yang berhasil menciptakan plot twist yang membagongkan, menyakitkan hati, dan menyebalkan!
Mari kita mundur seminggu sebelumnya, sebelum aku dan Bunda saling meluruhkan air mata, sebelum aku nangis kejer di kamar penginapan seharian, sebelum aku sempat menjadi anak manis pemberontak di usiaku yang menginjak tahun ke dua puluh satu dan membuatku lari dari rumah, dan sebelum aku memutuskan untuk mengubah tujuan hidupku gara-gara kotak sialan ini. Aah, andai rasa penasaran itu tidak pernah ada.
Benar kata pepatah, curiosity killed the cat. Aku kucingnya. Aku!
Haaaah. Baiklah.
Di malam yang panas—suhu Jakarta sedang panas-panasnya, aku menyeret kotak itu dari kolong tempat tidur gara-gara mencari antingku yang, mungkin sudah takdirnya melompat sesuka hatinya dan berakhir di kolong tempat tidur. Dengan rasa ke-KEPO-an yang amat tinggi aku buka kotak misterius itu. Ceritanya kan, aku penasaran.
Awalnya aku enggak ngerti sama sekali dengan isinya. Hanya ada dua lembar foto, kalung emas putih beserta bandulnya yang bermata merah marun, dan sebuah buku tua bersampul kulit yang sudah retak dimakan usia.
Aku mulai teliti satu persatu. Hal pertama yang aku ambil adalah foto. Aku mengenali foto perempuan muda berseragam putih abu-abu sebagai keponakan Bunda. Dia adalah anak dari kakak laki-laki Bunda.
Lho, berarti kotak ini punya Mbak Aruna, kan? Kenapa bisa nyasar ke kamarku? Rumah kami jaraknya sejauh Jakara Timur dan Jakarta Selatan. Aku di Cililitan, Om Widhi di Setiabudi.
Nama anak Om Widhi adalah Aruna Cempaka. Kata Bunda, Mbak Aruna udah lama pergi dari rumah sejak aku lahir dan enggak tahu rimbanya di mana. Makanya kami enggak pernah ketemu. Tahu wajahnya hanya dari album foto. Bunda sepertinya enggan menceritakan lebih jauh mengenai Mbak Aruna. Orang tua Mbak Aruna juga enggak pernah mengungkit-ungkit anaknya.
Pssst, just so you know aja ya, Om dan Tanteku sendiri kayaknya enggak suka aku, deh. Setiap Bunda ajak aku ke rumah mereka, aku tuh kayak enggak dianggap. Ada tapi tiada. Mereka kayaknya enggak pernah ikhlas menerima aku sebagai anggota keluarga mereka. Padahal kan, aku keponakan mereka sendiri. Aku saudara sepupu Mbak Aruna. Aah, sudah lah. Cukup tentang mereka. Toh, mereka bukan orang tuaku. Mereka enggak punya andil untuk membesarkan aku. Jadi...masa bodo!
Kembali ke foto tadi. Selain foto Mbak Aruna, ada foto seorang pria muda. Kayaknya tuaan dia beberapa tahun dari Mbak Aruna. Tapi, untuk ukuran cowok era 2000-an—Januari 2000, begitu keterangan waktu yang ditulis di belakang foto, ganteng juga sih, mirip Nicholas Saputra. Kebayang kan, seberapa gantengnya cowok ini di masanya?
Lalu mataku beralih ke buku bersampul kulit yang permukaan kulitnya sudah retak dimakan waktu. Karena penasaran, buku itu aku buka. Sampul kulit tadi sampai berderik karena bahannya sudah kaku. Maka dari itu aku buka dengan hati-hati. Mbak Aruna, izin baca, ya.
Waah, ternyata buku diary! Kertasnya sudah berbintik kuning tanda berjamur. Di halaman pertama, ada tulisan Segala Tentang Tian dengan satu simbol hati digambar di akhir kalimat. Ini pasti pacar Mbak Aruna. Cieee, cinta monyet ini pasti.
Lembar pertama, Januari 2000.
Mbak Aruna pertama kali bertemu Tian di depan toko Bunda—Wilma Bakery. Bundaku punya toko kue yang sudah berdiri 25 tahun. Tidak ada yang tidak mengenal toko Bundaku. Waah, jadi toko kue Bunda jadi tempat bersejarahnya mereka ya. Baru aja baca, cerita Mbak Aruna bikin aku senyum-senyum sendiri.
Lembar demi lembar terus aku buka dan aku libas tulisan Mbak Aruna dengan senang hati. Bagaikan membaca sebuah novel roman picisan ala anak SMA. Aku seakan di bawa ke dalam kisah Dilan dan Milea yang bikin baper, atau larut dalam menonton kisah Galih dan Ratna yang bikin senyum-senyum sendiri. Betapa kisah cinta monyet Mbak Aruna dan Tian begitu menyenangkan dan penuh bunga bermekaran di setiap kalimat yang di tulis olehnya. Dari cara sepupuku menggambarkan visual Sebastian Wirjawan—si Tian yang di foto, aku bisa menyimpulkan bahwa sifat pria itu gentle, cerdas, dan kata-katanya manis dan romantis. Tentu saja Mbak Aruna kelepek-kelepek dibuatnya.
Aku sampai merebahkan tubuh di kasur demi menyamankan diri membaca kisah cinta anak SMA dengan seorang anak kuliahan di zamannya. Janjian di bioskop, Tian yang menjemput Mbak sepupuku di depan sekolah, keliling Jakarta dengan mobilnya Tian, makan bakso, sampai Tian yang beberapa kali main ke rumah Mbak Aruna dan sebaliknya. Wow. Bahkan zamannya Mbak Aruna, cewek main ke rumah cowok sudah biasa, ya?
Tak sadar, ternyata aku sudah sampai ke lembar-lembar terakhir. Aku mulai menemukan kejanggalan cerita, seperti tidak ada lagi kalimat berbunga-bunga. Aku tidak menemukan Tian yang menjemput Mbak Aruna. Aku juga tidak menemukan kalimat mereka yang bertemu di luar untuk sekedar kencan manis. Dadaku ikut-ikutan pedih entah untuk alasan apa. Apakah kisah ini akan berakhir patah hati? Aku makin penasaran.
Lalu sampai ke halaman berikutnya, Desember 2000. Hanya dua kata dan membuat dadaku serasa di remas. Tian pergi, sudah cukup menggambarkan semua situasi. Mbak Aruna pasti patah hati. Ditambah, di halaman yang sama ada dua titik noda bekas air yang telah mengering. Apa mungkin air mata Mbak Aruna?
Halaman berikutnya, meloncat ke lima bulan kemudian. Tulisan Mbak Aruna semakin tidak jelas. Butuh sedikit usaha untuk membacanya, soalnya tulisannya mulai seperti cakar ayam. Seperti terburu-buru atau, tangannya gemetar saat menulis, aku enggak bisa memastikannya.
Aku benci hidupku.
Aku malu.
Ma, tolong Nana. Pa, kasihani Nana. Nama panggilan Mbak Aruna ternyata sama denganku, Nana. Tapi, kenapa aku menangkap Mbak Nana frustasi?
Perutku semakin besar. Bagaimana cara mengeluarkan dia dari tubuhku?
Aku benci diriku.
Aku benci anak ini.
Kenapa kamu pergi?
Dia ada gara-gara kamu!
Aku benci kamu, Tian.
Aku ingin mati.
Mbak Nana... hamil?
Tak sadar air mataku menetes entah untuk apa dan aku terisak sendiri. Seakan akulah Nana yang hidup di tahun 2001 ini. Seakan, akulah yang ditinggal Tian dan merasakan betapa tertekannya Mbak Nana sampai ingin mati. Apa aku terlalu larut menyesapi lara yang ditorehkan Mbak Nana di buku diary-nya?
Masih terisak, aku terus membalik halaman berikutnya sambil berharap masih ada tulisan yang menandakan dia masih... hidup.
Agustus 2001.
Hanya Tante Wilma yang peduli padaku. Hanya beliau yang mau menampung anak buangan seperti aku.
Kenapa yang sedarah justru... membuangku?
Aaah, syukurlah. Mbak Arun masih menulis. Bundaku disebut-sebut oleh Mbak Nana. Tapi, membuang? Perasaanku tidak nyaman. Seketika aku teringat sikap dingin Om Widi dan istrinya padaku. Apa mereka memang sekeras itu dari dulu? Bahkan kepada darah daging mereka sendiri?
Oktober 2001.
Tante Wilma, maafin Nana. Nana... Nana enggak bisa jadi ibu. Nana enggak bisa merawat bayi itu. Nana...enggak siap. Soalnya, Nana... benci dia. Nana benci bayi itu. Nana enggak mau lihat bayi itu...
Mbak, apa yang terjadi sama kamu, Mbak? Apa yang terjadi dengan anak itu? Oh Tuhan. Ada apa sih, ini? Aku ikut geregetan.
November, 2001.
Terima kasih untuk semua ilmu baking Tante yang amat berharga. Nana yakin Nana akan bertahan dengan semua ilmu yang Tante berikan dengan cuma-cuma.
Desember, 2001.
Tante, makasih udah jaga bayi itu demi Nana. Tapi... Nana enggak bisa kalau berada satu atap dengannya. Nana enggak bisa menghirup oksigen yang sama dengan bayi itu. Nana benci makhluk kecil itu. Bersama dengan bayi itu hanya akan membuat Nana makin membenci diri Nana sendiri dan membenci dia yang meninggalkan Nana berjuang dengan bayi ini sendirian.
Tante begitu bahagia menggendong bayi itu. Mata Tante begitu berbinar ketika bercanda dengannya. Tante seperti diberi hadiah paling indah dari Tuhan, sebagai pengganti doa-doa Tante selama ini setelah endometriosis menyerang rahim Tante dan Tante divonis dokter tidak bisa lagi memiliki anak. Apa mungkin ini hikmahnya, bahwa bayi itu sekarang mempunyai ibu baru? Hahaha, betapa Tuhan Maha Baik pada umatnya. Padaku? Entahlah.
Tapi yang jelas, terima kasih Tante mau merawat bayi itu dan menganggap dia sebagai anak Tante sendiri.
Izinkan Nana pergi. Lagi pula, Nana enggak punya tempat di Jakarta. Nana akan rutin mengabari Tante agar Tante enggak khawatir sama Nana. Senang rasanya masih ada orang yang mengkhawatirkan Nana layaknya keluarga sendiri. Nana... akan berusaha menjadi manusia lebih baik lagi di belahan bumi lain. Nana enggak akan melupakan jasa Tante sama Nana.
Selamat tinggal Tante....
Aku sampai dua kali membaca halaman terakhir itu untuk memastikan sesuatu. Bukannya bahagia karena sepertinya Mbak Nana dan bayinya baik-baik saja, tapi sesak di dada yang aku dapatkan. Begitu banyak pertanyaan yang berseliweran dalam kepalaku.
Hal pertama yang aku cari adalah apa itu endometriosis di internet. Hasil pencarian membuat dadaku serasa dihimpit batu besar. Intinya, ada jaringan dari lapisan dalam rahim Bunda tumbuh di luar rongga rahimnya dan menyebabkan gangguan pada kesuburan hingga kanker ovarium. Seberapa parah endometriosis di rahim Bunda?
Apakah aku lahir dari sebuah keajaiban dari rahim Bunda yang bermasalah?
Tapi, kata Mbak Nana Bunda divonis tidak bisa memiliki anak. Mungkin aku lahir sebelum vonis itu dijatuhkan.
Di mana anak Mbak Nana yang sudah sudah Bunda anggap anak sendiri?
Kenapa Bunda tidak pernah membicarakan perihal anak itu sama sekali padaku?
Pertanyaan-pertanyaan itu memenuhi kepalaku seperti nyamuk lapar yang mengitari telinga manusia. Terlalu berisik sehingga aku harus mendapat jawaban secepatnya supaya hatiku tenang. Aku perlu Bunda saat ini juga.[]
Bersambung


 kepodangkuning
kepodangkuning