Aku dan sekitar dua puluh mahasiswa lain berada di kantor polisi. Di antaranya ada tiga mahasiswi yang ditangkap termasuk aku. Kami menjalani segala macam tes, termasuk tes urine dan tes darah. Mungkin, untuk memastikan bahwa kami bukan pengguna narkoba. Orang tua kami ditelepon dan diminta hadir di kantor polres. Pikiranku sudah melayang ke mana-mana, berharap Papa dan Mama sedang tidak di rumah. Semoga mereka tiba-tiba melakukan perjalanan ke luar negeri seminggu ini.
Kami bergantian masuk ke ruang interogas untuk diwawancarai dan semua berlangsung hingga malam, bahkan beberapa kali kami disuruh menggunakan alat pendeteksi kebohongan. Perwakilan birokrasi kampusku sudah hadir di kantor polisi, yang berasal dari Universitas S dikumpulkan, berkali-kali diberi nasihat supaya tidak sampai terperosok dalam organisasi yang merugikan diri sendiri.
“Ini bakal ditulis di SKCK kita, enggak, sih?” bisikku pada Ogi ketika kami menunggu dijemput orang tua masing-masing.
“Kata Pak Yandi enggak. Toh, kita sudah ditanya dan dipastikan identitasnya berkali-kali. Lo juga enggak ganti-ganti pernyataan, kan, tadi?” Ogi yang wajahnya masih kotor dan lusuh memandangku. Rambutnya makin terlihat kusut dan mengembang.
Kami berdua belum makan sejak pagi, sekadar merapikan rambut juga tidak sempat. Semoga saja tidak disuruh menginap di kantor polisi, kalau iya, kami akan makin mirip gelandangan besok pagi.
“Jav, rahang lo kayaknya robek, deh.” Ogi mengulurkan saputangan yang diambilnya dari dalam saku sambil menunjuk rahangku yang masih terasa perih.
Aku menatap saputangannya ragu. “Lo gimana?” Pertanyaan itu meluncur karena melihat wajah Ogi yang jauh lebih parah dibanding wajahku sekarang. Sepertinya, dia yang lebih membutuhkan saputangan itu untuk membersihkan wajahnya. Kami masih berada di ruangan tertutup dan belum boleh ke kamar mandi tanpa didampingi petugas, sudah seperti tawanan. “Muka lo lebih banyak bekas darah, Gi.” Telunjukku mengarah ke beberapa luka.
“Nih, ambil dulu,” suruh Ogi sedikit memaksa. Kemudian melepas jas almamater dan kemeja merah bata yang digunakannya. Kini yang tersisa hanya kaos hitam melekat di tubuhnya. “Gue bisa pakai ini,” ucapnya diikuti tawa pelan sambil mengusap wajahnya dengan kemeja.
Kulakukan hal yang sama, kuusap wajah dengan saputangan Ogi, dalam sekejap kainnya sudah berubah warna, kotor sekali. Aku melepas gelang rajut hitam yang sudah kupakai sejak lama. “Pakai ini, Gi, buat kuncir rambut lo. Biar enggak kayak reog, tuh.”
“Thank you.”
“Besok balikin, soalnya itu dari Kakak gue.”
“Sip. Paling enggak, gue enggak terlalu mengkhawatirkan di depan ortu gue nanti,” ucap Ogi sembari terkekeh.
Jika hari ini tidak ada Ogi, aku bisa panik setengah mati karena melaluinya sendirian. Ogi terus berada di sampingku sejak ditangkap tadi siang. Aku dicurigai provokator, tapi beruntung itu tidak terbukti, sedangkan Ogi ditangkap karena melakukan kekerasan terhadap aparat.
“Javitri Inneke, orang tua kamu di depan,” panggil salah seorang polisi bertubuh tambun.
“I-iya, Pak.” Aku beranjak dari bangku. “Gi, gue duluan, ya.”
Ogi tersenyum sambil menepuk lenganku pelan. “Everything will be okay, Jav. Kalau lo butuh bikin alasan ke bokap sama nyokap lo, gue bisa bantu.”
Aku mengangguk. “Thanks.” Detak jantungku berdetak cepat, kali ini lebih membuatku gugup dibanding saat berdiri di podium tadi. Sebenarnya aku takut dengan apa yang terjadi nanti setelah aku bertemu orang tuaku.
Apakah aku akan diusir dan namaku dicoret dari Kartu Keluarga? Lalu bagaimana dengan kuliahku selanjutnya? Apa aku tetap akan melanjutkan kuliah, atau justru berhenti karena tidak lagi dibiayai seperti yang terjadi pada Mas Januar? Apa mungkin Papa akan memukulku, atau bahkan membunuhku?
Pertanyaan itu terus berputar di pikiranku ketika tengah berjalan menuju lobi depan yang sudah terdengar ramai oleh hiruk pikuk orang tua yang menjemput anaknya.
“Javitri!” teriak Mama begitu melihatku keluar dari lorong. Dia buru-buru menghampiriku.
Aku menggigit bibir, bukan menahan tangis, tapi ini sungguh memalukan bagiku.
“Kamu enggak apa-apa, Jav? Ya ampun, itu rahangmu robek sedikit, setelah ini kita ke rumah sakit. Ada lagi yang luka?” berondong Mama penuh kecemasan.
Papa berjalan lebih santai di belakang Mama sambil menatapku tajam. “Ini yang kamu bilang hidup mandiri saat kuliah?” sindir Papa. “Kalau ini sampai masuk di riwayat kriminal, kamu enggak akan bisa kerja di mana pun! Berpikir sebelum bertindak, bukan sebaliknya!”
“Sudah. Sudah, Pa. Yang penting Javitri enggak apa-apa.” Mama mengusap bahu Papa untuk menenangkan.
Sejak tadi aku memilih diam. Aku tidak pernah membantah ucapan Papa kecuali saat ingin tinggal di indekos ketika menginjak semester dua dengan alasan lebih dekat kampus dan lebih banyak kesempatan menghabiskan waktu dengan teman-teman untuk belajar bersama. Padahal alasan sebenarnya, aku ingin menghindari orang tuaku.
“Kamu itu mahasiswa! Harusnya bersikap juga seperti layaknya mahasiswa, orang yang berpendidikan!” Papa masih mengomel walau kami sudah keluar dari kantor polisi, sedangkan Mama terus menggandeng tanganku sambil mengusap rambut dan wajahku beberapa kali.
“Mau saja dibodohi senior! Buat apa kamu ikut kegiatan seperti itu, tugasmu itu cuma belajar! Jangan ikut-ikutan bodoh seperti kakakmu!”
“Papa, setop!” teriak Mama keras. Hingga beberapa orang di sekitar kami menoleh. “Apa masih perlu mengungkit soal Januar?”
“Biar anak perempuanmu ini juga enggak seperti kakaknya! Atau perlu aku enggak biayai kuliahnya lagi biar anakmu ini sadar?” Telunjuk Papa mengarah padaku,tepat di pertengahan kedua mataku. Aku bisa melihat ujung jarinya.
“Anakmu? Januar dan Javitri anak Papa juga! Kalau Papa sudah enggak mau biayai kuliah Javitri, Mama bisa kok!” sahut Mama sambil menarik tanganku agar berjalan lebih cepat untuk sampai ke mobil.
Papa masih berdiri di belakang kami. “Sombong sekali! Kamu itu istriku! Harusnya patuh sama aku, bukannya membantah dengan suara keras! Wanita macam apa kamu itu!”
Lagi-lagi aku cuma bisa menggigit bibir tanpa bicara. Iya, di keluarga ini yang berhak bicara hanya laki-laki. Hanya Papa, karena ini keluarga patriarki. Ucapanku cuma akan membuat situasi makin rumit dan memisahkan kami dengan jarak.
Mama sendiri sudah terlalu sabar untuk Papa yang tidak mampu mengendalikan emosinya. Baru kali ini, aku melihatnya berteriak membalas ucapan Papa. Mungkin karena Mama tidak tahan lagi mendengar Papa memaki Mas Januar. Aku sendiri juga tidak tahan, tapi sayangnya yang kubisa hanya membisu dan mendengarkan semuanya.
Aku dipaksa pulang ke rumah setelah dari rumah sakit dan mendapat dua jahitan di rahang. Tidur adalah satu-satunya yang kupikirkan hingga mengalahkan rasa lapar.
“Mulai sekarang pulang ke rumah! Berangkat dan pulang kuliah, Papa yang antar dan jemput!”
“Papa! Biar Javitri makan dulu. Cukup teriak-teriaknya, ini sudah larut malam.”
“Aku tidur aja, Ma.” Perutku sudah kenyang karena mendengarkan Papa sejak tadi.
“Enggak makan dulu? Makan, ya.” Mama masih membujukku.
Alih-alih menjawab, aku hanya menggeleng.
“Biarkan saja kalau enggak makan, dia sudah dewasa untuk memikirkan urusan perutnya sendiri. Sudah bisa ikut demo, kok! Kita enggak perlu kasih maka ke dia lagi, buat apa!”
Mama mengembuskan napas panjang.
“Oh, ya! Barang-barang di kosmu cepat dikemas, keluar dari kos minggu ini juga. Jarak rumah ke kampus cuma sepuluh kilometer. Enggak perlu kos, buang-buang uang saja!” Kemudian Papa meninggalkan ruang tamu dan menuju kamar diikuti suara pintu yang ditutup dengan kasar hingga menimbulkan bunyi keras.
Aku juga masuk ke kamarku sendiri, membenamkan diri di dalam selimut. Aku membenci suasana rumah ini. Sejak tidak ada Mas Januar, semuanya berbeda. Aku tidak lagi menjadi anak bungsu yang dimanja Papa. Mama juga sama, lebih banyak menghabiskan waktu dengan melamun di rumah. Papa makin sering marah dan mengeluarkan kata makian, termasuk ketika aku menolak untuk kuliah di jurusan teknik elektro. Kesempatan untuk memutuskan masa depanku sendiri, tidak ada. Aku merasa Papa hanya melampiaskan keinginannya yang tidak berhasil dicapai Mas Januar padaku.
Esoknya, Ogi terus menelepon, tapi sengaja tidak kujawab. Aku masih mengurung diri di kamar yang kukunci sejak semalam. Mama terus mengetuk pintu dan hanya kujawab dengan singkat karena Mama akan terus menerus memanggil jika tidak ada jawaban. Mungkin khawatir jika tiba-tiba aku melarikan diri.
“Jav, ada temanmu di depan, Aya sama Ogi. Keluar, ya,” ucap Mama ketika jam menunjukkan pukul sebelas siang.
Aya memang pernah kuajak sekali ke rumah saat semester satu karena ada perlengkapan ospek yang ketinggalan. Aku tidak menyangka jika dia masih ingat. Namun, aku masih malas bertemu siapa-siapa sekarang. Aku butuh waktu untuk memikirkan apa yang akan kulakukan selanjutnya. Tidak mungkin menuruti kemauan Papa semalam. Pulang ke rumah dan diantar-jemput hanya akan membuatku terpenjara seumur hidup.
Aya dan Ogi hanya mampu menunggu tiga puluh menit tanpa kutemui. Kudengar Mama menemani mereka mengobrol dan kemudian pamit.
“Javitri, jangan begini terus, dong. Kamu enggak makan dari kemarin, sekarang pintu dikunci. Ngomong sama Mama, kamu perlu bantuan apa?”
Mama sudah cukup kesulitan menghadapi Papa yang temperamen, aku tidak mau membebani pikirannya lebih banyak lagi. Karena itu, aku tidak pernah menceritakan apapun ke Mama termasuk yang kurasakan dan kupikirkan. Sejak dulu, aku dan Mama seolah memiliki jarak yang seharusnya tidak tercipta di antara ibu dan anak. Mama lebih dekat dengan Mas Januar, sedangkan aku justru dekat dengan Papa. Namun, itu dulu.
“Jav, ini ada titipan dari Ogi. Buka pintunya,” ucap Mama tidak menyerah.
Aku turun dari tempat tidur dan membuka sedikit pintu. Mama menyerahkan sekantong kresek dari celah.
“Makan, ya?” tawar Mama ke sekian kali.
Aku menggelengkan kepala. “Nanti aja aku ambil sendiri.”
“Kamu pengin makan apa? Biar Mama masakin.”
Aku tidak menjawab, hanya menatap wajah Mama yang menyiratkan kelelahan.
“Mau pepes ikan pedas?”
“Terserah Mama aja, kalau enggak repot.”
“Enggak, lah. Kamu belum makan dari kemarin, padahal harus minum obat,” kata Mama cemas.
Aku sampai lupa kalau punya luka di rahang dan jahitan yang masih basah tertutup kasa. Karena terlalu banyak yang mengganggu pikiranku akibat rencana yang tidak berjalan semestinya. Mama sudah sibuk di depan kulkas mencari bahan memasak. Aku masuk lagi ke kamar dan membuka kantong yang terasa berat.
Dua kebab berukuran jumbo, satu cup kopi dingin, dan dua magnum classic. Aku terkekeh melihat isinya. Kubuka magnum yang hampir mencair, bisa-bisanya mereka membawa es krim saat menjenguk orang sakit. Ada plastik bening berisi gelang rajut hitam yang kupinjamkan ke Ogi kemarin malam.
Kuangkat plastik itu tinggi-tinggi, kuperhatikan simpul rajutan yang masih bagus. Sebenarnya, gelang ini milik Mas Januar, dia memakainya setiap hari sejak dia kuliah. Aku yang memintanya paksa karena itu bagus. “Mas, gue harus ngapain sekarang?” gumamku, sambil mendongak, menatap gelang hitam itu.
Tiba-tiba tebersit untuk keluar dari rumah sekarang juga. Papa sedang kerja, mungkin ini kesempatanku. Aku meraih ransel dan kumasukkan kantong kresek yang masih berisi makanan dan minuman tadi. Membuka pintu sambil mengendap-endap dan tanpa berpamitan. Kemudian berjalan menjauh dari rumah sebelum memesan ojek online. Pertama, aku harus mengambil motor di indekos dulu. Kalau aku sembunyi di indekos, tentu saja Papa dan Mama akan sangat mudah menemukanku.
“Javitri! Tadi gue ke rumah lo, terus sekarang tiba-tiba nongol di sini aja!” pekik Aya yang melihatku membuka pintu kamar untuk mengambil kunci motor.
“Gue mau ambil motor, Ya. Lo tahu enggak, Ogi di mana?” Ponselku sengaja kumatikan setelah memesan ojek online tadi.
“Kayaknya ke kampus, sih. Soalnya gue sama dia pisah di gerbang kampus tadi,” jawab Aya. Aku kira dia pulang, ternyata tidak. Katanya di grup whatsapp penghuni indekos, kegiatan UKM membuatnya harus ke kampus selama beberapa hari.
“Ya, kalau ada Mama atau Papa gue, bilang aja lo enggak tahu dan enggak ketemu gue hari ini.”
“Heh? Lo kabur dari rumah?”
“Terpaksa.”
“Terus lo mau ke mana sekarang?”
Aku bergeming, bukan tidak mau menjawab, karena aku sendiri tidak ada jawaban. “Gampang, deh. Nanti gue pikirin di jalan.” Aku sudah mendapat kunci motorku dan buru-buru turun.
Aya mencengkeram pergelangan tanganku untuk menahan. “Jav, itu luka lo enggak apa-apa?” tanyanya.
Aku meringis. “Enggak apa-apa, cuma dua jahitan. Tangan sama kaki gue masih bisa gerak ini.” Aku menepis tangan Aya, takut jika Mama menyusulku pulang. “Gue cabut dulu.”
Kedua, aku akan ke sekretariat BEM mencari Ogi dan Bang Dito. Setelah kupikirkan, aku bukan malas bertemu siapa-siapa, tapi aku cuma ingin menghindari orang tuaku dan kemarahan Papa. Makin sering aku mendengar Papa mengomel, makin penat isi kepalaku.
“Javitri?” panggil Ogi setengah tidak percaya karena aku tiba-tiba muncul dari pintu sekretariat. Ternyata sekretariat BEM sedang banyak orang. Setelah kuperhatikan, mereka adalah peserta aksi masa kemarin yang tergabung dalam BEM SI. Mereka semua memandangku, begitu juga dangan Bang Dito dan Mas Pandu yang kemarin menghilang dan menjadi tidak kasat mata ketika terjadi bentrokan.
Aku ragu untuk masuk, kakiku masih mengajak berdiri di ambang pintu. Aku bingung menerjemahkan tatapan mereka. Kasihan, menyalahkan atas kejadian kemarin, atau berharap aku tidak ada di sini?
“Masuk, Jav.” Ogi berdiri dan mendekatiku.
“Jav, gimana kondisi lo? Itu, lukanya enggak apa-apa?” timpal Bang Dito yang juga beranjak dan berjalan ke arahku.
“Eh?” Hanya itu yang keluar dari mulutku.
“Masuk,” suruh Ogi lagi.
“Hah?” Aku menggaruk rambut. Mengapa mereka semua tiba-tiba diam dan rasanya jadi canggung? Apa mereka sedang membicarakanku?
“Lo enggak mendingan istirahat aja dulu?” ucap Bang Dito yang seharusnya menunjukkan khawatir, tapi justru terdengar mengusir.
“Dia mau masuk, Bang.”
“Maksud gue, dia enggak perlu maksa kalau masih sakit, Gi. Mending istirahat total, dia masih shock sama kejadian kemarin.”
“Oke, kayaknya gue istirahat aja, Bang. Hm, gue cabut dulu, Gi,” pamitku kikuk, lalu menjauh dari pintu dan berbalik arah. Sebenarnya salahku apa? batinku berkecamuk. Ketiga, yang harus aku lakukan hari ini adalah aku perlu berendam air es untuk mendinginkan kepala!
[]


 vinni_dianita
vinni_dianita





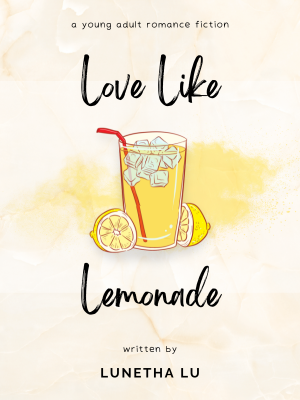




kaya gue yg nunggu ngisi air sambil main game WKWKWK
Comment on chapter Chapter 1 - Aku Javitri