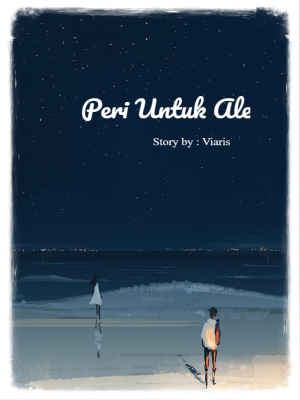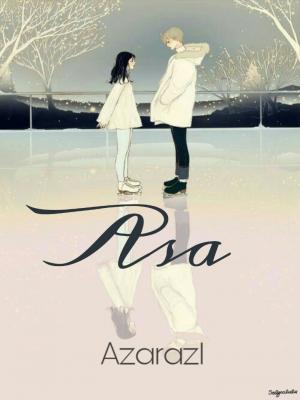Pagi ini, Shafwan dipanggil kepala sekolah SD Teladan Mulia, Ibu Lestari Andriani. Shafwan ditegur karena kedekatannya yang tidak biasa dengan keluarga Farel. Bu Lestari berpesan supaya Shafwan tetap menjaga integritasnya sebagai guru dengan tetap menjaga jarak dengan keluarga siswa. Tidak baik jika harus bepergian dan bertamasya dengan keluarga siswa.
“Jangan sampai timbul keberpihakan kepada siswa tertentu karena Ustaz Shafwan dekat dengan salah satu keluarga siswa.” Begitu kesimpulan yang disampaikan Bu Lestari kepada Shafwan.
Dalam hati, Shafwan tidak sepakat dan ingin membela diri. Shafwan merasa ia dekat dengan banyak keluarga siswanya. Beberapa kali ia mengagendakan home visit dan ngobrol via telepon dengan orang tua siswa. Adapun agenda bermain di Transmart itu juga tidak sepenuhnya dibiayai oleh keluarga Farel. Shafwan mengeluarkan uang cukup banyak untuk makan dan tentu saja perawatan kesehatan Farel di rumah sakit. Namun Shafwan menahan diri. Ia memilih mendengarkan dengan seksama dan menjadikan teguran ini sebagai evaluasi dirinya.
Belum hilang galau di hati Shafwan, ia harus menerima perubahan sikap Humaira. Shafwan merasa Humaira, rekan sesama guru, bersikap ketus hari ini. Tidak seperti biasanya, Humaira yang ramah. Bahkan ketika Shafwan meminta bantuan Humaira untuk konseling Farel di kelasnya.
“Saya hari ini masih harus konseling di kelas lain,” ujar Humaira sambil mengetikkan kata demi kata di layar komputernya.
“Kalau besok?” tanya Shafwan. Ia masih duduk di depan meja Humaira.
“Besok saya full observasi di kelas 4.”
“Kapan Ustazah ada waktu luang?” Shafwan masih saja bertanya. Matanya sibuk mencermati jurnal observasi kelas yang ada di tangannya.
“Entahlah. Saya juga masih harus membuat laporan konseling sepuluh siswa. Dan harus disampaikan ke Psikolog sekolah tiga hari lagi.” Mata Humaira masih saja fokus di depan layar. Sesekali ia melirik pria di depannya.
Shafwan menarik nafas panjang.
“Baik. Saya butuh masukan saja terkait teknis konseling terutama ke Farel. Hari ini, dia murung dan cenderung emosional lagi. Hampir saja ia memukul Faiq tadi.”
Humaira menghentikan ketikannya lalu menatap ke arah Shafwan.
“Bukankah Ustaz Shafwan sudah sangat dekat dengan Farel? Seharusnya tidak sulit untuk Ustaz konseling dengan Farel.”
“Iya. Anda benar. Tapi, tadi Farel dia tidak banyak bicara dengan saya. Tidak banyak terbuka. Barangkali dengan Ustazah Humaira, Farel mau bercerita.”
“Maaf saya belum bisa.” Ia melanjutkan aktivitas mengetiknya. Humaira masih kesal dengan Shafwan yang tetiba membatalkan janji mengajar di TPA demi jalan-jalan dengan Farel dan tantenya dua hari kemarin.
“Baiklah. Tidak biasanya Ustazah Humaira sibuk sampai menolak konseling.”
Humaira berhenti mengetik. Lalu dia menekan tombol Ctrl-S di keyboard komputer dan meng-klik tanda X di pojok kanan atas.
“Ustaz Shafwan Pramudya yang terhormat. Saya mohon maaf jika tidak bisa membantu. Load pekerjaan saya cukup banyak. Jika Ustaz tidak bisa membuat Farel bercerita, Ustaz bisa minta bantuan orang lain yang lebih dekat dengan Farel.”
“Siapa?”
“Tante-nya Farel lah. Azkadina. Ustaz juga dekat dengan tante Azkadina bukan? Langsung saja minta tolong ke beliau, selaku wali murid sementara dari Farel.”
“Oh,” gumam Shafwan,”Sebentar, kok tiba-tiba menyebut nama tantenya Farel?”
Humaira tidak menjawab. Kepalanya serasa mau meledak. Sebelum meledak beneran, ia memilih segera berdiri dan berlalu dari hadapan Shafwan yang kebingungan. Shafwan mendekati rekan sesama guru di ruang guru itu. Huda namanya. Ia guru kelas 3 dan menjadi sahabat baik Shafwan sejak awal mengajar.
“Hud, kenapa ya Ustazah Humaira begitu? Apa ada masalah keluarga?”
“Kamu tuh yang bermasalah, Bro.”
“Aku? Bermasalah gimana?”
“Lah gak nyadar arek iki. Foto ente dengan tantenya Farel bertebaran di dunia maya itu yang membuat Ustzah Humaira senewen.”
“Kenapa senewen?“ Mata sedang Shafwan membulat. Ia menutup jurnal observasinya.
“Duh, Rek! Please deh Shafwan. Humaira cemburu tauk… ente deket sama tantenya Farel yang cantik itu.”
“Oalah. Aku lho gak ada hubungan istimewa dengan tantenya Farel. Juga dengan Ustazah Humaira. Kenapa harus cemburu..”
“Arek iki jian tenan… Mikir sing dowo toh Shafwan. Humaira itu sudah lama suka sama kamu. Keliatan dari gelagatnya. Masa’ ente gak nyadar?”
“Nggak ah. Be-aja aku.”
“Duh Gusti! Wes mbuh karepmu, Shafwan.” Huda menepuk jidat, melihat kepolosan dan kenaifan Shafwan yang menggemaskan. Laki-laki yang sudah beristri itu menenggak air putih di botol minumnya.
Shafwan tertawa melihat ekspresi sahabatnya. Dalam hati, ia bingung. Apa yang harus dilakukannya. Humaira dan Azkadina, adalah perempuan yang sama-sama baik dan unik. Keduanya adalah teman Shafwan. Mengapa harus ada cemburu-cemburu?
Seolah mengerti isi hatinya, Huda berujar, “Wes ndang rabi, Wan. Biar gak ada yang cemburu-cemburu gak jelas.”
Mendengar kata rabi yang berarti menikah, hati Shafwan menciut. Ia teringat, bahkan belum bisa melupakan peristiwa empat tahun lalu. Peristiwa yang membuatnya enggan menjalin hubungan serius.
****
Sore itu, suasana masjid Ar Rahmah tak banyak pengunjung. Semilir angin berhembus lembut menyapa setiap pengunjung masjid. Masjid yang terletak di tengah danau itu memang istimewa. Banyak pepohonan dengan beragam tanaman perdu berbunga berderet di sepanjang pagar pembatas masjid dan danau. Pemandangan yang asri dengan danau buatan amat memanjakan mata yang tengah lelah didera kesibukan kota.
Selain digunakan untuk salat berjamaah, masjid ini juga kerap menjadi tempat kajian. Tampak di dalam masjid, beberapa muslimah duduk melingkar. Di tangan mereka ada buku catatan, alat tulis dan tentu saja kitab Al Quran. Mereka duduk bersila. Sesekali mereka menyimak materi dari senior mereka, lalu berdiskusi kemudian mencatat. Tak jarang pula mereka melempar candaan.
“Baik, kesimpulan dari pertemuan kali ini adalah, bagaimana kita mengelola mahabbah atau rasa cinta yang bersemayam di hati supaya tidak melebihi kadarnya. Tidak melebihi tingkatannya. Cinta terhadap apapun atau siapapun, hendaknya tidak melebihi rasa cinta kepada Allah dan RasulNya.” Perempuan berkerudung coklat itu menyampaikan konklusi.
“Ada pertanyaan?” lanjutnya.
“Mbak Hilwa, saya mau tanya. Bagaimana cara supaya kita tidak salah menempatkan cinta yang sudah terlanjur ada?” Perempuan muda berkerudung pashmina hijau itu bertanya.
“Pertama kita meluruskan niat. Agar cinta yang kita rasakan berbuah ibadah. Kembalikan cinta itu kepada pemiliknya. Kedua mencintai secara proporsional. Nah ini yang sulit. Kadangkala kalau sudah jatuh cinta itu, logika jadi tumpul. Cinta kepada barang-barang bagus membuat orang rela menghabiskan ratusan juta hanya untuk sebuah tas branded. Cinta kepada lawan jenis, membuat manusia rela menyerahkan harga dirinya, bahkan kehormatannya.”
Perempuan berkerudung coklat itu terdiam sejenak. Ia mengambil botol minum dan menenggak isinya. Lalu melanjutkan kembali penjelasannya.
“Masih ingat bukan Surat Al Baqoroh ayat 216 yang artinya boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu; Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui.”
Tangan perempuan ber-pashmina hijau itu sibuk menuliskan catatan di bukunya. Pikirannya kacau. Ia mematung, memikirkan seseorang yang sudah lama mengisi mimpi-mimpi indahnya.
“Nabi Muhammad juga pernah berpesan, “Cintailah kekasihmu sekadarnya saja, karena boleh jadi suatu hari nanti dia akan menjadi sesuatu yang engkau benci; dan bencilah sesuatu yang tidak engkau sukai sekadarnya saja, karena boleh jadi suatu hari nanti dia akan menjadi sesuatu yang engkau cintai.”
“Sepertinya, ukhty Humaira sedang memikirkan sesuatu atau seseorang nih.” Goda perempuan berhijab kuning dan berkacamata kepada Humaira.
Humaira hanya tersenyum menunduk. Ia tak berani berkomentar. Perasaannya sedang berkecamuk. Ia tak nyaman dan ingin segera mengakhirinya. Namun, majelis ilmu belum selesai. Majelis ilmu terus menggulirkan diskusi dengan tema tingkatan cinta. Sampai akhirnya, tepat pukul setengah lima sore, majelis diakhiri.
“Ukhti Humaira. Kita bisa bicara sebentar ya setelah ini.” Ujar perempuan yang dipanggil Mbak Hilwa. Humaira mengangguk.
Setelah semua muslimah itu pulang, Mbak Hilwa memulai pembicaraan.
“Ukhti. Saya melihat anti murung sepanjang materi. Apa anti sakit?”
“Ndak Mbak. Saya sehat.”
“Tidak biasanya anti seperti itu. Apa ada materi dari saya yang kurang pas?”
Humaira menggeleng. Humaira tak sanggup menceritakan keresahan hatinya.
“Apa anti ingin bercerita?”
Humaira menggeleng lagi.
“Baik. Saya mau menyampaikan maksud dan tujuan memanggil anti.” Mbak Hilwa mengeluarkan map besar berwarna coklat dari dalam ransel. Ia menunjukkan map itu kepada Humaira.
“Ukhti. Ini adalah biodata seorang laki-laki salih. Dia sudah melihat biodata dan foto anti. Sekarang giliran anti mengenal pria itu dari data dan foto di amplop ini.”
Humaira terkejut. Ia tak kuasa memegang amplop coklat itu dari tangan Mbak Hilwa.
“Ini adalah proposal nikah ketiga yang saya berikan. Proposal pertama anti tolak mentah-mentah tanpa melihat isinya. Proposal kedua juga hampir sama. Anti menolak karena dia berasal dari suku Sunda. Padahal sebelumnya, anti menyampaikan bahwa mau menikah dari suku manapun, asal orang Indonesia. Lalu tiba-tiba berubah. Saya kan jadi malu.”
Humaira menunduk seraya berkata lirih, “Maaf.”
“Saya harap, proposal ketiga ini minimal bisa anti pertimbangkan dengan baik. Setidaknya berikan alasan yang rasional bila anti menolaknya.”
Perkataan Mbak Hilwa menusuk hati Humaira. Seketika ia menangis tersedu-sedu. Mbak Hilwa menjadi serba salah. Ia mengelus punggung Humaira, menenangkannya.
“Mbak…aku mau tanya. Boleh?”
“Tentu saja.”
“Bolehkah kita berharap mendapatkan pinangan dari laki-laki tertentu?”
“Laki-laki yang definitif orangnya, begitu?”
Humaira mengangguk.
“Tentu saja boleh. Tapi bagaimana caranya?”
“Saya tidak tahu.”
“Anti ingin saya menghubungi murabbi laki-laki definitif tersebut untuk meminta biodata miliknya? Lalu saya memberikan kepada anti? Begitu?”
Humaira mengangguk.
“Lalu bagaimana jika ia menolaknya? Bukankah itu berarti ia menolak anti? Bukankah itu malah menyakiti anti?”
Humaira semakin tidak tenang. Pertanyaan balik dari Mbak Hilwa membuatnya lemas. Ia teringat Azkadina, perempuan cantik yang sekarang dekat dengan Shafwan.
Bagaimana bila Shafwan lebih suka Azkadina?
“Ukhti, metode taaruf seperti ini, sebenarnya lebih menguntungkan perempuan. Mengapa? Karena perempuan tidak menghadapi penolakan secara langsung. Dengan adanya biodata yang masuk ke pihak perempuan, tandanya, si pria setuju untuk taaruf dengan si perempuan. Kalaupun ada pria yang menolak biodata si perempuan, maka perempun itu tidak akan tahu siapa laki-laki salih yang menolaknya. Jadi aman secara hati. Begitu kan ya?”
Humaira masih terdiam. Ia mengangguk pelan. Suasana hening sejenak.
“Ukhti, sepertinya anti sedang suka dengan seseorang. Benar?”
Humaira mengangguk. Matanya masih lirih mengeluarkan air mata.
“Baiklah. Begini saja. Jika anti ingin mengupayakan berjodoh dengan laki-laki itu, silakan. Asal caranya yang baik. Jangan sampai terjadi zina, bahkan mendekati zina alias pacaran saja tidak boleh. Selesaikan urusan anti dengan laki-laki itu. Saya bantu mengawal proses anti selanjutnya dengan dia.”
Humaira mengangguk.
“Saya beri waktu dua pekan untuk istikharah dan ikhtiar. Jika ternyata kalian belum berjodoh, maka anti bisa legowo melanjutkan taaruf dengan pria lain.”
Humaira menunduk dalam diamnya. Ia terus beristighfar. Benarkah apa yang ia rasakan sekarang?
“Saya tangguhkan dulu proposal ini. Semoga takdir terbaik untukmu ya Humaira.”


 neea_sweet
neea_sweet