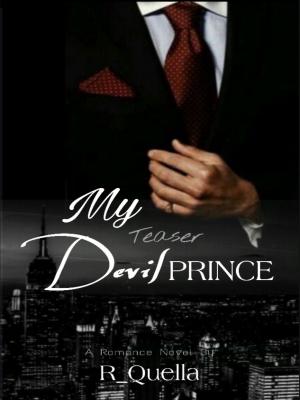Blok 5-Benita
Semesta Benita
Sakit. Sepotong tangan besi bagai menghantam perutku. Membuatku terbangun kaget di kamar hotel pagi itu. Dengan tangan gemetar, kuraba nakas hendak mencari ponsel. Dimana benda keperakan itu? Ah, ketemu. Mataku makin menyipit membaca tanggal hari ini. Jelas sekali bukan waktu menstruasi. Kenapa perutku sesakit ini?
Kuletakkan kembali gawai berlogo apel tergigit itu. Sekuat tenaga aku bangkit sambil menahan sakit. Kuseret langkah menuju kamar mandi. Cara jalanku benar-benar berbeda dari biasanya. Benita yang terbiasa melenggak-lenggok di catwalk kini terseret-seret ke ruang basah di toilet kamar.
Kunyalakan shower. Air hangat menyembur deras. Kuhempaskan tubuh di lantai sambil memeluk lutut. Ngilu, tolong pergilah. Doaku tak terkabul. Nyeri ini justru makin menjadi. Aku merintih kesakitan. Percuma saja, takkan ada yang mendengar. Aku sendirian, sempurna sendirian. Salahku juga membarikade diri di hotel bintang lima ini setelah melihat kemesraan Zakaria dan istrinya dengan mata kepalaku sendiri.
Tangan besi di dalam perutku memukul-mukul dengan kerasnya. Erangan lolos dari bibir mungilku. Aku menundukkan kepala, terperangah melihat cairan merah mengalir di sela kedua kakiku.
Likuid merah apa itu? Apakah dinding rahimku mengalami peluruhan sebelum waktunya? Haidku masih dua minggu lagi. Dan hari pertama tak pernah sebanyak ini.
Dinding bercat krem itu kucengkeram erat sebagai pegangan. Aku berdiri goyah dengan kedua kakiku. Noda darah mengambang di lantai bagai bunga-bunga merah. Tangan pucatku berusaha menyiram bersih genangan darah, membiarkannya mengalir bersama kucuran air bening ke saluran pembuangan. Samar ingatanku berputar. Rasa sakit di perutku, darah yang berceceran dari organ kewanitaan, menyeretku pada cerita sepupuku. Mutiara, sepupuku itu, pernah dua kali melahirkan. Sensasinya mirip dengan apa yang kurasakan.
Aku menggeleng kuat. Tidak, tidak mungkin. Kupastikan belum ada pria mana pun yang mengoyak selaput daraku. Tak ada yang menanamkan benihnya di rahimku. Dan aku pun belum mengizinkan hal itu. Aku berjalan terhuyung meninggalkan kamar mandiku.
Si apel memekik berulang kali. Jemariku meraih benda pipih itu. Sebuah pesan baru saja masuk ke aplikasi percakapan. Mataku melebar membacanya.
From: Mr. Right
Benita, anakku sudah lahir. Dia cantik sekali. Namanya Gemma Anindya Zakaria. Aku memanggilnya Gemmanda.
Tanganku tergantung lemas di udara persis robot kehabisan baterai. Aneh sekali. Gemmanda lahir dari rahim perempuan lain, tapi akulah yang merasakan sakit. Oh iya aku lupa mengganti nama kontak Zakaria. Dia tak pantas lagi kusebut Mr. Right. Zakaria adalah Mr. Right untuk Sabila, bukan untukku. Kuketikkan balasan dengan hati terempas taifun.
To: Mr. Right
Syukur Alhamdulillah. Aku ikut senang mendengarnya. Boleh aku liat fotonya, Kak?
Semenit berselang, Zakaria mengirimkan foto bayi berwajah manis. Bayi itu berwajah tirus dengan hidung tinggi dan mata besar. Ia berkulit gelap dan wajahnya manis sekali. Kutangkap pendar kemiripan dengan ibunya.
To: Mr Right
Wah, cantiknya Gemmanda. Gimana keadaan Sabila?
Aku terlatih menyembunyikan perasaanku sendiri. Bisa saja aku tersenyum ceria di depan orang dan berlapang dada atas kenyataan pahit ini. Namun, jauh di dalam, sesuatu runtuh perlahan. Ada robekan besar di batinku.
Cukup lama tak ada balasan. Aku berganti pakaian sambil menunggu. Secepat datangnya, kesakitan di perutku lenyap tak bersisa. Balasan Zakaria membuatku tertegun.
From: Mr. Right
Not too good, Benita. Sabila nggak mau sentuh bayinya. Dia juga menolak makan dan ketemu keluarganya.
Astaga, separah itukah kondisi Sabila? Aku curiga dia mengalami depresi postpartum atau depresi pascapersalinan. Setelah menimbang-nimbang sejenak, kuputuskan meluncur ke rumah sakit. Aku datang ke sana demi Zakaria. Dia pasti membutuhkan dukungan.
Butuh proses panjang sebelum petugas kesehatan di rumah sakit yakin kalau aku tidak membawa virus. Aku pun dibolehkan masuk dengan pengawasan ketat. Kuayun langkah secepat kilat menuju unit persalinan. Di ujung koridor, aku melihatnya. Pria yang sangat kucintai. Raut wajahnya menyimpan kesedihan mendalam. Aku berlari mendatanginya.
“Kakak ....” panggilku sambil terengah.
Kini kami berdiri berhadapan. Tuhan, sungguh kumerindukannya. Telah lama tak kulihat tubuh tinggi proporsional itu, wajah tampan itu, senyum maut itu. Tiap kali melihat tatapan terluka itu, aku ingin memeluknya.
“Be strong, Kak. Kakak nggak sendirian. Ap-apa yang bisa kulakukan?” Aku melontar tanya dengan suara bergetar.
Zakaria membisu. Kutahu jika kesedihan ini melampaui segala kata yang dapat melukiskannya. Mestinya ini menjadi hari bahagia untuk pria yang terpaut sepuluh tahun dariku. Perilaku istrinyalah yang merusak istana bahagia.
Di luar prediksi, Zakaria meraih tanganku. Lembut menuntunku ke ruangan bayi. Seorang perawat yang bertugas di dalam tersenyum pada kami.
“Mau nengok bayi ya, Pak? Wah, istrinya cantik, ya.”
Aku merona hebat mendengarnya. Apakah aku dan Zakaria terlihat seperti pasangan suami-istri? Di luar sana, banyak yang mengira kami kakak dan adik. Zakaria tak menggubris celetukan suster itu.
Kami mendekat ke sebuah ranjang mungil. Sebuah kartu kecil bertuliskan Gemma Anindya Zakaria tertempel di sisi tempat tidur. Rongga dadaku dirayapi getaran hebat melihatnya. Ada kesan yang berbeda saat bertatapan langsung dengan Gemmanda.
Tes.
Entah dari mana datangnya air mata ini. Aku terharu, terharu melihatnya. Aku sendiri bingung dengan perasaanku. Dia tidak keluar dari rahimku. Kendati begitu, aku merasakan batinku terikat dengannya.
“Boleh aku gendong Gemmanda?” pintaku parau.
Zakaria tersenyum sumringah. Sekejap saja Gemmanda telah berpindah ke dalam rengkuhanku. Dan ... saat itulah aku melihat senyumnya. Gemmanda tersenyum padaku.
Air mataku membanjir. Betapa melankolisnya perasaanku. Pantas saja kalau aku dijuluki member Magenta yang paling halus dan lembut. Bahkan Aini pernah menyebutku ibu peri di Magenta.
Kuciumi wajah Gemmanda. Tanganku mengusap hangat puncak kepalanya. Detik itu juga kurasakan gelombang kenyamanan luar biasa. Gemmanda memang tidak lahir dari rahimku, tetapi ia lahir dari hatiku.
“Ibunya bahkan tidak memberi pelukan seerat itu.” Zakaria berbisik di telingaku. Tubuhku menggelinjang. Sadar dia begitu dekat denganku. Dapat kuhirup wangi Christian Dior Eau Sauvage, parfum favoritnya.
Sisi lain hatiku berteriak tak rela. Mengapa Sabila menyia-nyiakan anugerah sebesar ini? Suami tampan dan baik hati. Bayi yang sehat dan menggemaskan. Dengarlah bayi dalam gendonganku menangis. Sepertinya dia kelaparan. Ah, andai saja aku bisa menyusuinya. Sayang sekali aku bukan ibu biologisnya.
Raungan Gemmanda beradu dengan bunyi nyaring si apel tergigit di tasku. Duet yang memekakan dan membuat bayi-bayi lainnya ikut menangis. Seorang perawat tergopoh mengambil alih. Kutinggalkan ruangan bayi bersama Zakaria dengan hati tak keruan.
Ternyata Aini menghubungiku. Aku diomelinya habis-habisan karena terlambat dua jam. Kabar kelahiran Gemmanda membuatku lupa kalau hari ini aku janjian dengan anak Magenta. Rencananya kami mau party di salah satu cabang Istana Villa.
“Ditungguin anak Magenta, ya?” terka Zakaria melihat perubahan air mukaku. Seperti biasa dia seakan mampu membaca pikiranku.
Aku mengangguk lemah. Hatiku berdilema. Magenta dan Zakaria sama pentingnya. Akan tetapi, Zakaria mendesakku untuk pergi. Dia bahkan menawarkan diri untuk mengantarku.
**
Magenta mendarat di Bandara Sam Ratulangi pukul sebelas siang. Dari bandara, kami meluncur ke Pelabuhan Bitung. Pelabuhan Bitung adalah pelabuhan terbesar di Sulawesi Utara, tempat persinggahan kapal-kapal besar dari berbagai penjuru Indonesia.
Sampai di sana kami melakukan check in. Ini bukan pelayaran biasa karena kapal yang akan kami naiki adalah cruise atau kapal pesiar. Royal Cruise berdiri gagah, tubuh perkasanya seperti siap memeluk kami. Saking besarnya badan kapal, kami tak mampu memotretnya secara keseluruhan dari satu angle.
Naik kapal pesiar hampir sama seperti naik pesawat. Kami check in lalu diberi boarding pass dan luggage tag oleh petugas. Luggage tag itu tercantum nomor kamar (stateroom) yang akan kami tempati di Royal Cruise. Setelah check in, kami menjalani pemeriksaan X-Ray. Petugas kapal memastikan kami tak membawa barang yang dilarang. Barang yang dilarang itu antara lain setrika dan colokan listrik. Larangan ini menuai keheranan Aini. Anak itu seumur-umur belum pernah berpesiar.
Selesai sudah pemeriksaan X-Ray. Koper kami diletakkan ke bag drop. Pegawai kapal yang akan membawakannya ke kamar kami. Kami berlima mendapat sea pass card. Kartu sakti itu berguna untuk kunci kamar, akses keluar-masuk kapal, dan alat bayar untuk fasilitas di kapal. Sebenarnya untuk fungsi yang terakhir tak perlu sebab kami naik kapal pesiar ini gratis.
Luas sekali kapal ini. Royal Cruise berlantai delapan dan berkapasitas tiga ribu penumpang. Fasilitasnya lengkap mulai dari spa, salon, arcade, cafe 24 jam, beberapa restoran mewah, lift, dan kamar tidur dengan tiga tipe kemewahan. Kamar tidur termurah bertipe interior dengan single bed. Tipe kedua adalah Ocean View yang memiliki jendela yang menghadap ke birunya lautan. Dan tipe termewah, yang ditempati Magenta, adalah Suite Room yang dilengkapi balkon pribadi dan bathtub di dalam kamar mandinya.
Tiba di kamar, kami lega karena koper kami telah dibawa ke sana. Sejenak kami melepas lelah. Namun tak bisa terlalu lama karena kami harus bersiap. Bersamaan dengan terangkatnya sauh, perhelatan sakral akan berlangsung: resepsi pernikahan Zakaria Pangemanan dan Sabila Anggadewi.
“Ben, lo di kamar aja kalo nggak kuat. Biar kami aja yang ikut pesta,” kata Marina berbaik hati.
Aku menepis halus usulannya. Sesakit apa pun hatiku, aku akan tetap hadir di pernikahan ini. Gabriella menepuk-nepuk pundakku.
“Ya udah. Lo yang kuat, ya. Nikmatin aja pestanya ... nggak usah fokus sama pengantinnya kalo lo nggak sanggup.”
“Iya, Gabriella. Aku tahu apa yang harus kulakukan.”
Kubuka koperku. Aku tarik gaun panjang abu-abu keperakan. Gaun itu berpotongan mewah dan terbuat dari sutra halus. Aini melirik sekilas gaun itu.
“Ben, gimana kalo lo pakai gaun putih aja? Biar si Sabila itu ada saingan,” cetusnya dengan seringai jail.
Langsung saja Aini kena timpukan gratis dari Gabriella. “Sembarangan lo! Ntar yang ada si antagonis itu ngamuk ke Benita! Gimana kalo ibu peri kita kenapa-napa?”
Sabila adalah antagonis bagi Magenta. Dia menciptakan hubungan cinta yang toksik dengan Zakaria. Pria yang kucintai adalah protagonisnya, dan Sabila adalah racun sekaligus antagonisnya. Perempuan itu pula yang menjauhkan Zakaria dariku, Yuke, dan teman-temannya. Entah sudah berapa kali Sabila merongrong orang-orang yang dekat dengan Zakaria. Aku pernah disiram kopi olehnya saat ia memergoki kami tengah berduaan di cafe. Padahal saat itu Zakaria hanya bermaksud menenangkanku yang sedang sedih setelah meninggalnya Papu (sebutan untuk nenek) dari pihak Mama.
“Gue nggak pernah lupa, ya, dia pernah marah-marah di dm hanya karena gue lagi diajarin Kak Zakaria buat persiapan UN,” geram Aini seraya menarik keluar dress Dolce and Gabbana dari dalam kopernya.
Bisa kulihat Marina, Gabriella, dan Erika tersenyum simpul memperhatikan Aini. Gadis tomboy itu terlihat tak nyaman saat mengenakan gaunnya.
“Kenapa senyum-senyum? Udah, cepetan ganti baju!” seru Aini tak sabar. Nada bicaranya persis Aldebaran Alfahri dalam serial Ikatan Cinta.
“Iya, iya. Lo cantik pakai gaun, Aini.” Erika memuji setulus hati.
Aini cemberut. Ketukan di pintu kamar menghentikan obrolan kami. Gabriella bergerak gesit membukakan pintu. Tangan kanan keluarga Pangemanan menjemput kami. Ternyata Magenta masuk list tamu yang dirias oleh perias kepercayaan keluarga.
Kami turun ke lantai tiga menggunakan elevator. Orang kepercayaan itu membawa kami ke sebuah ruangan besar penuh berisi cermin, kursi, dan alat make up. Tak tanggung-tanggung, yang akan mempercantik penampilan kami adalah tim make up artist. Aku kenal mereka karena sering bertemu dalam acara peragaan busana.
“Oh, Nona Benita. Ternyata kamu ada di sini juga. Cantiknyaaa ... coba aja mata Tuan Muda Zakaria kebuka dikit. Dia bakal milih kamu ketimbang is ... aduuuh!” celoteh salah seorang perias. Ia berhenti mengoceh karena rekannya menginjak kakinya.
Aku hanya tersenyum tipis. Mana mungkin Zakaria memilihku? Pastilah aku hanya anak kecil di matanya. Pastilah aku dianggap adik. Mana pernah, sih, seorang kakak menikahi adiknya? Kandidat magister dan CEO seperti dia mana mau menjalin kasih dengan anak SMA yang masih merintis karier sebagai model dan pianis sepertiku? Aku hanyalah butiran debu dibandingkan Sabila yang cerdas itu.
Tap tap tap
Sepasang kaki terbungkus sepatu berhak tinggi berderap memasuki ruangan. Kian lama, bunyi langkah kaki itu kian dekat. Kurasakan sepasang tangan mulus merengkuh bahuku. Aku menoleh dan terenyak mendapati Tante Yvonne berdiri di sisiku. Tante Yvonne tampak memesona dalam balutan gaun berpotongan sabrina berwarna emas. Wajah teduh menyenangkan dan tutur kata lembutnya sungguh mengingatkan pada anak tunggalnya.
“Cintaku, Zakaria ingin kamu main piano di pernikahannya. Itu pun ... kalau kamu mau.” Tante Yvonne berucap.
Kontan empat anak Magenta di sekelilingku mengeraskan tatapan. Mereka tak ingin aku terluka lebih dalam. Sepersekian menit aku terdiam.
“Tante tahu ini tak mudah. Benar, kamu tidak sendirian. Tante juga berat dengan pernikahan ini. Tapi ... semua sudah terjadi.”
Hatiku mencelos. Kupandang lekat wanita setengah baya yang kuidamkan jadi mertuaku. Sorot ketidakrelaan memancar dari sana. Mantan presiden Rotary Club di kota kami itu menyimpan kegetiran akan menantunya. Sabila, Sabila yang sering menyakiti Zakaria.
“Tuh, ‘kan, bener? Mertuanya aja nggak suka sama dia.” Gabriella tak dapat menahan komentar julidnya selesai berdandan.
Aini mencibir. “Iyalah. Cuma anak pegawai biasa kok. Dia bahkan nggak punya nama belakang. Dia bukan Rorimpandey, Wan, Prabawa, Wiguna, atau Trunajaya.”
Bukan itu yang kutangkap dari sorot mata ibu kandung Zakaria. Kurasa Tante Yvonne tidak mempermasalahkan kalau Sabila hanyalah anak PNS biasa. Ia sedih lantaran Sabila telah banyak melukai putra satu-satunya.
Pesta pernikahan dimulai. Kulihat Sabila berjalan anggun di karpet merah dengan taburan bunga putih. Tubuh sintalnya terbalut gaun pengantin mewah berwarna putih dan berhias berlian. Ekor gaun itu melambai seiring langkah. Sebentuk cincin bertatahkan berlian dua belas karat terpasang di jari manis Sabila. Pasti gaun itu cukup berat. Zakaria menjemputnya di tengah-tengah, tampak amat rupawan dengan tuxedo off white. Sah saja Zakaria menjemput istrinya di tengah alih-alih menunggu di ujung dekat pelaminan. Ini bukanlah pemberkatan.
“Masih kuat?”
Bisikan halus Marina menyapu pendengaranku. Kurasakan sahabat bermata biruku itu memberi pelukan terhangat. Ia sangat pengertian. Hatiku berdenyut. Namun, aku telah memutuskan.
“Marina, aku akan main piano untuk mereka.”
Sepasang mata biru Marina membola. Dicengkeramnya kedua bahuku erat.
“Are you sure?” tanyanya tak yakin.
Aku mengangguk mantap. Cengkeraman Marina terlepas. Ia menarik napas berat.
Satu per satu tamu undangan memberi selamat. Aku berdiri canggung saat tiba giliranku. Kusalami mereka berdua.
“Semoga berbahagia,” lirihku.
Zakaria menatapku dalam. Tatapan yang terlalu dalam untuk seorang kakak. Yuke, yang berdiri di belakangnya sebagai best man, melempar pandang menyelidik.
“Boleh peluk?”
Siapa yang telah menyita bibirku? Tidak, aku tak bermaksud bilang begitu. Namun alat bicaraku berkhianat. Sabila membeliak seolah aku adalah zombie yang bersiap menggigit. Tanpa bicara, Zakaria dan Sabila bergantian mendekapku. Kupejamkan mata saat berada dalam rengkuhan pangeranku. Ini adalah pelukan terakhir.
Aku pun melangkah turun dari pelaminan. Tetiba Sabila ikut turun menjajariku. Kami berdiri bersisian. Kulihat seringai kemenangan di wajah culasnya.
“Kenapa, anak kecil? Merasa kalah?” sindirnya.
Takkan kuperlihatkan kelemahanku di depan wanita picik ini. Aku balas seringainya dengan senyuman termanis.
“Kekalahan justru hadir saat kita tak bisa merelakan. Kamu lihat,aku bisa ‘kan?” balasku lembut.
Tangan Sabila terlipat di depan dada. “Katanya kamu mau main piano, ya? Aku dengarkan ... musik instrumental dari pianis yang patah hati.”
Aku mengangguk sopan. Akan kutunjukkan kalau aku menghadapi patah hati dengan elegan.
Tiba giliranku untuk bermain piano. Kubawakan lagu Seribu Kali Cinta dari Christie secara instrumental. Performaku mengundang tepukan kagum dari lima ratus tamu undangan. Selama bermain piano, tatapanku tak lepas dari siluet sepasang pengantin di atas pelaminan mewah.
Musim silih berganti
Banyak yang kita lalui
Saling bantu berdiri
Saat disakiti
Kita saling berjanji
Tuk saling melengkapi
Walau badai datang mengganggu
Cinta tak akan beralih
Jangan pernah bosan
Kan kukatakan cinta
Seribu kali sehari
Bukan hal mudah
Sejauh melangkah
Tenang, sayangku ada untukmu
Takkan berubah
Walaupun menua
Tenang, sayang setia hingga lanjut usia (Christie-Seribu Kali Cinta).
**
Rentetan kejadian itu telah lama berlalu. Zakaria menikahi Sabila saat aku kelas 2 SMA. Dua tahun setelah mereka menikah, lahirlah Gemmanda. Anak malang itu hadir saat dunia diguncang pandemi. Ibunya mengalami depresi postpartum dan enggan mengurusnya. Aku sendiri sangat ingin membersamainya setiap waktu. Kesibukan tugas kuliah dan kegiatan nonakademislah yang menghalangi.
Kabar buruk menimpa keluarga Pangemanan. Gemmanda tak berumur panjang. Ia harus kembali ke surga di umur enam bulan. Alih—alih Sabila, justru akulah yang berurai air mata. Aku sendiri yang turun tangan memandikan jenazahnya bersama Zakaria. Itulah pertemuan terakhirku dengan Mr. Protagonis. Beberapa hari setelah meninggalnya Gemmanda, cinta pertamaku itu terinfeksi virus yang saat ini tengah menjadi pandemik global. Virus itu memburuk dengan cepat, merusak paru-parunya, dan membuatnya terbaring koma. Duka bertubi-tubi untuk keluarga pemilik jaringan restoran dan perusahaan telekomunikasi itu.
Betapa besar rinduku untuk Zakaria. Setiap hari aku datang ke rumah sakit untuk menjenguknya. Meski aku harus bergulat dengan tantangan untuk mencapai ruang VIP tempat ia dirawat. Tantangan itu tak lain skrining dari petugas kesehatan dan makhluk halus penunggu rumah sakit.
Sejak dulu, aku memang dianugerahi mata batin yang tajam. Pengalaman merasakan sakit seperti orang melahirkan di hari kelahiran Gemmanda bukan hal pertama bagiku. Aku pernah merasakan kontak batin yang kuat dengan objek-objek tertentu sebelum itu. Salah satu kemampuanku yang unik adalah melihat hadirnya makhluk penghuni dimensi lain. Kujumpai mereka dimana-mana: di mall, rumah sakit, kendaraan umum, jalan raya, bahkan di rumahku sendiri. Suka tidak suka, kita memang hidup berdampingan dengan mereka. Kehadiran mereka adalah salah satu pertanda kekuasaan Tuhan yang Maha Agung.
Malam ini, seperti biasa aku menjenguk Zakaria. Hanya setengah jam aku di sana. Kurasakan kejanggalan sepulang dari rumah sakit. Seperti ada bayangan putih yang mengikutiku. Saat menoleh ke belakang, aku tak melihat apa-apa. Namun perasaan seperti dikuntit seseorang terus menerjang pikiranku. Aku yakin feeling-ku tak keliru.
Langkahku surut. Kini aku telah tiba kembali di kamarku. Kegiatan rutinku sepulang dari rumah sakit adalah mandi. Aku tak mau menularkan virus ke seisi rumah. Saat kubuka lemari yang menghadap cermin, aku menjerit kaget. Sosok tinggi, berwajah pucat, dan berpakaian putih terpantul dari cermin. Posisinya persis di sampingku. Aku sangat mengenalinya.
“Kak ...!”


 maurinta
maurinta