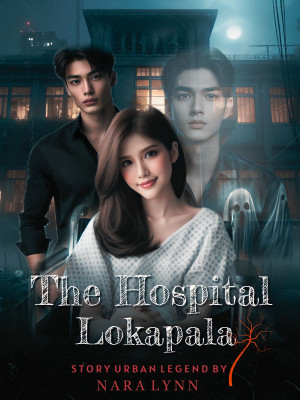Mendung tebal menyelimuti langit malam. Tiada sebentuk bintang pun yang berani menampakkan diri. Bahkan mengintip bumi pun, tidak. Semua bersembunyi di balik hamparan awan hitam yang sengaja digelar oleh penguasa kegelapan. Sesekali seberkas cahaya terang membelak langit. Lantas kepergiannya disusul oleh guntur yang berteriak menggelegar penuh kesombongan.
Bumi menggigil dalam kebisuan. Binatang malam yang biasanya bernyanyi riang, malam ini semuanya bungkam. Mereka pada bersembunyi di tempat yang paling aman. Seolah tak ada satu pun yang mau menyambut datangnya hujan. Hanya pasukan kodok yang kelihatannya masih berani berharap di balik suasana yang gelap.
Di ujung sebuah gang dari suatu perumahan elit yang ada di kota Surabaya, seorang lelaki muda bertubuh kekar sedang berjalan sempoyongan menyusuri jalan selebar tiga meter itu. Tanpa memperdulikan celana bluejins dan jaket hitam yang dikenakannya nampak mulai basah, lelaki itu terus melangkah menembus rinai hujan yang semakin deras semenjak ia memasuki mulut gang tadi. Air yang menggenangi jalan setinggi mata kaki tetap dilaluinya tanpa mencopot sepatu yang dikenakannya.
Sesekali lelaki sempoyongan itu nampak berhenti melangkah dan terbatuk-batuk di tengah jalan. Di sela batuknya ia masih sempat pula mengutuk cuaca yang tidak bersahabat itu dengan sumpah serapah yang tak begitu jelas terdengar karena suaranya berbaur dengan suara rintik hujan. Dan langkahnya yang sempoyongan menciptakan suara gemericik dari tiap muncratan air yang tersibak oleh ayunan kakinya.
Tiba di sebuah rumah mewah nomor 24, lelaki sempoyongan itu langsung membuka pintu pagar besi yang bercat hitam. Dengan langkah sempoyongan yang makin tak terkendalikan, lelaki itu mulai menggedor-gedor pintu rumah itu.
Tok! Tok! Tok! Tok tok tok!
“Mama, buka pintunya, Maa! Mama, buka pintunya! Mama!” teriaknya dengan suara berat sambil tetap menggedor-gedor pintu itu.
Sepi. Tak terdengar jawaban. Lelaki sempoyongan yang masih dalam penguasaan alkohol dari minuman keras yang tadi ditenggak bersama teman-temannya di sebuah tempat hiburan, mendengus kesal. Kembali digedornya daun pintu itu dengan lebih keras lagi.
Tok tok tok! Tok tok tok! Tok tok tok!
“Mama! Buka pintunya, Maa! Bukaaa!” teriaknya dengan lebih keras lagi.
Akh! Seorang perempuan muda yang sedari tadi duduk di sofa ruang tengah, bangkit sembari mendesah kesal. Sejenak ia melirik jam dinding berukuran besar yang menggantung di tembok sisi kanan. Jarum jamnya sudah tepat menunjukkan pukul 11 malam. Heh! Wanita itu kembali mendesah sambil melemparkan majalah fashion yang tadi dibacanya. Meski tak urung ia beranjak juga ke ruang tamu guna membukakan pintu.
Tak berlebihan kiranya jika Pratiwi begitu malas melangkah ke arah pintu. Sebab semenjak menikah dengan Gunarto, ia justru merasa bagaikan artis beken saja. Kesehariannya hanya dandan, shopping, dan menebar gossip dengan teman-teman sosialitanya. Hampir setiap hari suaminya itu keluyuran malam dan selalu pulang dalam keadaan mabuk. Seolah Gunarto sedikitpun tak mau memberi perhatian untuk keluarganya. Kebiasaannya cuma ke kantor, rapat bisnis, dan foya-foya.
Yah, terkadang Pratiwi juga menyesali pernikahannya itu. Andai saja ia tidak hamil duluan sebelum menikah, mungkin saat ini ia masih bisa menikmati saat-saat indah di bangku kuliah. Tapi mau bagaimana lagi, nasi sudah menjadi bubur. Mustahil ia bisa memutar waktu agar kembali ke masa silam.
“Maa! Buka pintunya, Maa! Cepat, buka! Cepaaat!” teriakan suaminya terdengar lagi. Bahkan kali ini dengan suara semakin keras.
“Iya, iya, ini juga masih jalan,” sahut Pratiwi sedikit mempercepat langkah.
“Cepat sedikit kenapa, sih!” damprat suaminya disertai amarah.
Pratiwi tak menyahut lagi. Meski dengan perasaan dongkol yang memenuhi rongga dadanya, begitu tuba di hadapan pintu berornamen ukiran khas daerah Yogyakarta, ia langsung memutar anak kunci yang masih menancap di lubangnya.
Klik! Perlahan ia putar handle pintu berbahan stenles mengkilat itu dan kemudian ditariknya dengan perlahan. Dan begitu daun pintu terkuak setengahnya, bau alkohol yang menyengat langsung menusuk hidungnya. Buru-buru ia menutup lubang hidungnya dengan telapak tangan.
“Tinggal buka pintu aja kok lama sekali!” damprat Gunarto lengkap dengan tudingan mengarah ke muka Pratiwi.
Masih dengan langkah sempoyongan, lelaki itu menerobos masuk dengan kasar. Bahkan tak peduli ketika tubuhnya yang limbung menyenggol pantat sang istri hingga membuat Pratiwi terhuyung beberapa langkah sambil meringis.
Brugk! Dengan kasar pula Gunarto melemparkan jaket yang baru dilepasnya ke atas sofa yang tadi diduduki istrinya. Dengan kondisi tubuh setengah basah, lelaki itu menghempaskan pantat di sofa panjang. Masih dalam pengaruh minuman keras, lelaki itu berusaha melepas sepatu dan kaos kaki yang masih melekat di kakinya dengan gerakan yang selalu salah.
Kesempatan itu digunakan oleh Pratiwi untuk menumpahkan kekesalan hatinya yang selama ia pendam hingga bertumpuk-tumpuk memnuhi rongga dadanya. Dada yang kerap merasa sesak lantaran sikap Gunarto yang tak pernah berubah sebagai bapak dari seorang gadis yang sudah kelas 2 SMA.
“Paa, kapan sih kau mau berhenti dari kebiasaan burukmu ini, heh! Kau lihat Revita yang sekarang sudah beranjak dewasa itu! Sebentar lagi kau sudah mau jadi seorang kakek. Apa jadinya kalau setiap malam kau tetap mabok seperti ini?”
Braagk! Serta merta Gunarto membanting sepatu yang baru berhasil di lepaskannya. Dengan tatapan nanar dan posisi duduk yang sedikit oleng, lelaki itu membantah.
“Diam, wanita cerewet! Suami pulang, kehujanan, capek, bukannya bikinkan kopi atau apa kek, kok malah ceramah! Dasar!”
“Aku hanya ingin membuatmu sadar, Paa!” bantah Pratiwi tak mau kalah.
“Apa? Sadar? Ha ha ha ha ha! Sadar dari apa, hah?”
“Ya sadar dari tanggung jawabmulah. Anak kita sudah besar. Kebutuhan kita pasti akan meningkat terus. Itu koleksi tas, sepatu, dan perhiasanku juga mulai kalah sama ibu-ibu komplek lainnya. Malu kan, Pa! Masa istrinya direktur cuma begini-begini aja penampilannya. Tentu tidak mungkin kalau kita terus bergantung pada satu bidang usaha aja kan?”
Braakk! Kali ini Gunarto menggebrak meja. Tatap matanya begitu penuh dengan rona kebencian yang mendalam.
“Hay, Ma! Orang tua kita kan kaya raya. Kekayaan mereka tidak akan habis dimakan tujuh turunan. Jadi buat apa aku harus capek-capek cari bisnis baru lagi, hah? Hidup ini jangan dibuat susah. Nikmati aja,” sahut Gunarto dengan senyum sinisnya.
“Pa, seberapa pun besarnya kekayaan, kalau terus menerus dipergunakan tentu ada masanya untuk habis. Sebab besar pasak daripada tiang maka lambat laun pasti akan mengalami kebangkrutan.” Kilah Pratiwi masih coba menyadarkan.
Tapi dasar sifat Gunarto yang memang pemalas dan terbiasa hidup berfoya-foya, ia tak mau mendengar alasan apapun bila sudah menyangkut tentang bekerja. Ia seolah alergi dengan kata yang satu ini. Ibarat seorang pangeran dalam kehidupan Gunarto apa yang ia mau selalu harus ada, tanpa harus keluar keringat ataupun tenaga.
“Justru itu, sebelum orang tua kita bangkrut gak ada salahnya kan kalau sekarang kita puas-puaskan menikmati kekayaan mereka. Toh mereka mengumpulkan semua kekayaan itu memang untuk dinikmati anak-anaknya termasuk kita.”
“Tapi Pa, kita itu ....”
Belum sempat Pratiwi melankutkan kalimatnya, Gunarto dengan sigap meraih tangan istrinya dan lalu dicengkeramnya erat-erat. Pratiwi sampai meringis kesakitan jadinya.
“Sudahlah, jangan banyak bacot! Aku capek! Aku mau tidur!” umpat Gunarto sambil mendorong tubuh istrinya hingga kepala belakang Pratiwi membentur sandaran sofa.
Pratiwi meringis kesakitan. Ia menggigit bibir sambil berusaha menahan air mata yang hendak tumpah. Hatinya merasa begitu nelangsa atas sikap suaminya yang tak pernah berubah tapi, Gubarto tak hirau lagi. Ia melangkah pergi ke kamar sambil bersungut-sungut dan lantas menutup pintu kamar itu dengan bantingan keras.
Brraaakk!
Tanggul di pelupuk mata Pratiwi jebollah sudah. Genangan air yang tadi coba ditahannya kini meluncur deras membasahi pipinya. Gundah hatinya tak terkira. Kepedihan yang menusuk hatinya melangutkan jiwa. Perasaannya yang membuncah mengantarnya terbang kembali kemasa silam. Masa di mana ia telah salah menentukan satu titik terpenting bagi masa depannya. Karena salah pergaulan, masa muda yang seharusnya ia pakai untuk menuntut ilmu dan mengejar cita-cita, justru ia pergunakan untuk berfoya-foya. Akibatnya, ia salah pergaulan dan terjerumus pada kehidupan sek bebas. Kehidupan bebas yang menggiringnya masuk ke dalam incidental moment lantaran ia harus menikah muda karena sudah hamil di luar nikah.
Akh! Pratiwi mendesah berat. Tantangan kehidupan yang kini dihadapinya adalah sebuah jalan panjang yang terjal dan berliku. Di situ kerikil-kerikil tajam siap menggores tapak kakinya di setiap langkah. Sedangkan ia rasanya tak sanggup bila harus luka dan berdarah. Tabiat suaminya yang kini kerap melarikan setiap persoalan ke dalam pelukan sebotol Vodka, membuat Pratiwi semakin tersiksa. Padahal ia tahu benar, sebotol Vodka hanyalah mampu memberikan surga sesaat. Solusi yang dihasilkan hanyalag semu, sebab pada hakekatnya miras hanyalah sebatas pelarian yang justru menambah runyam keadaan.
Tak kuasa menahan kepedihan hatinya yang semakin membuncah, Pratiwi membiarkan tubuhnya terkulai di sofa itu hingga matanya terpejam karena serangan rasa lelah yang menguasainya.
****
Waktu terus berlalu dengan begitu cepatnya tanpa menghiraukan orang-orang yang jungkir balik tergilas oleh kondisi perekonomian yang tak bersahabat. Kesalahan langkah Pratiwi dalam membina bahtera rumah tangga menjadi titik kulminasi bagi terciptanya rumah tangga tanpa jeda yang mau tak mau harus ia lewati. Memang dari segi materi rumah tangganya cukup melimpah namun kadang ia dan Revita putrinya membutuhkan perhatian yang lebih dari seorang suami, nyatanya harus ia lewati dengan makan hati. Sebab Gunarto lebih banyak menghabiskan waktunya untuk mencumbui botol-botol minuman keras.
Meski kehidupannya memang bergelimang harta, di mana orang tuanya sangat berkecukupan. Mereka memiliki dua rumah mewah yang didesain mirip dengan segala ornamen keraton Yogyakarta. Tiga buah mobil juga selalu siap mengantar mereka kemana saja. Betapa tidak! Selain sebagai juragan angkot dan makelar tanah yang cukup sukses, orang tua Pratiwi juga memiliki beberapa usaha di bidang retail. Tapi semua itu tak membuat bebas tertawa menikmati kehidupannya.
Akh!
Pratiwi mendesah. Hari ini dirasakannya masih sama dengan hari-hari melelahkan yang telah ia jalani sebelumnya. Sebagai seorang wanita kadang ia merindukan kehidupan yang normal seperti layaknya seorang istri pada umumnya. Di mana setiap pagi punya rutinitas untuk mempersiapkan baju kerja dan sarapan bagi suaminya. Dan jika sore menyambut kedatangan suami pulang kerja dengan scangkir teh hangat yang akan segera dibalas oleh suami dengan sebuah ciuman lembut tanda cinta.
Tapi semua itu hanya mimpi di siang hari bagi Pratiwi. Hari-hari yang dimilikinya hanyalah seperti seorang satpam yang harus bersedia membukakan pintu kapan pun Gunarto datang dengan aroma minuman keras yang memuakkan. Untunglah ia punya teman-teman sosialita yang nggak ada matinya. Sehingga ia bias merasa terhibur dengan berbagai kegiatan shopping di mall-mall ternama.
“Nyonya Tiwi, handpone Nyonya berdering tampaknya ada telepon itu,” kata Mbok Darmi, wanita setengah baya yang sudah 5 tahun lebih mengabdi sebagai pembantu rumah tangga di keluarga Pratiwi, dari dalam dapur tempatnya memasak.
“Iya Mbok, bawa ke sini,” sahut Pratiwi tanpa beranjak dari sofa ruang tengah. Ia hanya mengecilkan volume televisi yang sedang menyiarkan gosip-gosip artis ternama yang menjadi tontonan wajib baginya setiap pagi.
Mbok Darmi tergopoh-gopoh mengulurkan handpone itu pada majikan mudanya.
“Terima kasih, Mbok.”
Mbok Darmi hanya mengangguk dan tersenyum lantas kembali ke dapur guna meneruskan pekerjaannya.
“Hallo, assalammualaikum,” sapa Pratiwi seraya mendekatkan handpone itu ke telinganya.
“Wa’alaikumsalam Tiwi, ini aku Yuniar,” sahut sang teman dari seberang sana.
“Iya Yun, ada apa?”
“Tiwi, sekarang juga kamu ke sini, Tiwi. Cepat ke sini, Tiwi ... itu Antony ...” suara sang teman terdengar amat cemas.
“Ada apa dengan Antony, Yun?”
“Hari ini dia akan datang menawarkan kalung berlian model terkini. Makanya cepatlah kau ke sini, Tiwi! Ini teman yang lain juga sudah pada menghubungi!”
“Baik Yun, aku berangkat sekarang juga,”
“Iya Tiwi, cepatlah.”
Klik!
Pratiwi mematikan sambungan teleponnya. Tanpa mematikan televisi yang masih menyala ia bergegas ke rumah mamanya diantar sopir keluarga yang selalu siap sedia. Sepanjang perjalanan Pratiwi menyandarkan kepalanya yang terasa berat sambil membayangkan kalung berlian model terbaru yang akan segera menghiasi lehernya yang jenjang. Pratiwi sampai melayang memikirkannya.


 heru_patria
heru_patria