Keesokan harinya Alen memutuskan untuk naik bus. Lagi.
Ya, ya. Alen sebelumnya benci pergi ke sekolah dengan bus. Tapi itu bukan tanpa alasan. Alen benci naik bus karena naik bus sama artinya dengan mengizinkan Renata mengorbankan Alen untuk kepentingan Alice. Hal itu sudah terjadi selama beberapa tahun terakhir. Jika Alice harus pergi ke suatu tempat di saat yang bersamaan dengan waktu berangkat sekolah, maka Renata akan memilih untuk mengantarkan Alice secara ekslusif dan meminta Alen mengalah dengan naik bus sendirian ke sekolah. Mungkin karena Renata lebih menyayangi Alice?
Ya. Untuk sementara ini, jawabannya karena Renata lebih menyayangi Alice ketimbang Alen.
Namun untuk kasus naik bus hari ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan Renata atau Alice. Ini murni keputusan Alen sendiri. Ia sudah memutuskan untuk naik bus setiap hari. Dengan keputusan ini Renata bisa kapan saja mengantar Alice ke manapun. Pun, Alen bisa dengan tenang pergi ke sekolah tanpa harus merasa kalau ia baru saja tersisihkan dari hubungan kekeluargaan di rumahnya sendiri. Win win solution.
Alen memeluk cross bag-nya, menatap ke jendela selama perjalanan menuju sekolah. Setelah melaju cukup jauh, bus berhenti di perhentian pertama selama beberapa saat. Alen memalingkan wajahnya dari jendela bus. Ia menatap lurus ke depan, melihat beberapa orang masuk ke dalam bus. Secara refleks, Alen melepas pelukannya pada cross bag, lalu meletakan cross bag itu di kursi di sampingnya.
Orang-orang yang baru saja masuk sudah duduk di tempatnya masing-masing. Seperti yang Alen inginkan, tidak ada satupun yang duduk di sampingnya karena cross bag yang Alen simpan di kursi sebelah menandakan bahwa kursi itu sudah ia tandai untuk seseorang. Tapi mana orang yang Alen tunggu?
Alen memanjangkan lehernya, berusaha melihat lebih jelas ke depan. Pintu bus sudah tertutup. Bus melaju lagi. Alen mengerjap. Sekoyong-koyong ia bertanya dalam hati, ‘Mana Galen? Apa hari ini nggak masuk sekolah?’
Alen mengerjap lagi.
Tunggu, tunggu dulu. Alen tidak naik bus untuk bertemu Galen, jadi kenapa ia harus terus memanjangkan leher dan memastikan bahwa pemuda itu akan muncul dari balik pintu bus? Sambil memeluk lagi cross bag-nya, Alen menepuk wajah.
Apaan sih. Gumamnya dalam hati.
#
Seminggu berlalu. Sama sekali tidak ada perubahan. Alen bertanya-tanya apa yang ia lakukan benar? Apa keputusannya naik bus ke sekolah benar-benar karena ia tidak mau di antar Renata. Alen ragu, karena setiap kali naik bus, dengan sangat sadar, Alen sengaja meletakan cross bag-nya di kursi sebelah supaya orang lain tidak menempatinya, lalu ketika bus berhenti di perhentian pertama, Alen akan memanjangkan leher dan harap-harap cemas untuk kedatangan Galen. Tapi Galen tidak pernah datang.
Hari ini pun begitu. Alen duduk dengan wajah muram. Ia mengerling cross bag yang selama ini menemaninya di dalam bus. Beberapa kali Alen bertanya pada dirinya sendiri, ke mana Galen? Tapi tentu saja ia tidak tahu jawabannya. Mengenal pemuda itu saja Alen masih remang-remang, mustahil ia tahu ke mana Galen atau kenapa pemuda itu tidak muncul selama seminggu terakhir.
Bus melaju dengan kecepatan yang memuakan. Alen memandang ke sana kemari, berusaha mencerahkan otaknya dengan pemandangan di luar, tapi nihil. Pada akhirnya Alen tetap memikirkan perkara menghilangnya Galen secara tiba-tiba.
“Ke mana, ya?” Alen bergumam pahit. Gadis itu merogoh saku jaketnya, mengeluarkan ponsel, kemudian mengecek log panggilan dan pesan masuk. Kosong. Tidak ada panggilan atau pesan baru.
Bukannya waktu itu Galen bilang ia akan mengirim pesan lagi kapan-kapan? Alen mengembuskan napas. Jarinya yang mungil mengetuk layar ponsel dengan frekuensi gelisah.
Kapan-kapan itu kapan?
Hebat. Ketika Alen berkomitmen mengenyahkan pikiran buruknya tentang Galen dan menerimanya sebagai teman, Galen malah menghilang tanpa kabar. Tanpa jejak. Kalau tahu akhirnya akan begini, Alen tidak akan berbaik hati pada Galen, apalagi sampai meminta maaf karena waktu itu melarikan diri dari UKS sekolah. Kalau tahu akan begini, Alen pasti memutuskan untuk benar-benar tidak terlibat dengan Galen sejak awal. Ia tidak akan mengiyakan ajakan bolos Galen. Juga tidak akan naik bus sendirian dan menunggu kedatangannya yang sia-sia setiap hari.
Setelah perjalanan menuju sekolah yang jauh lebih membosankan dari pada biasanya, bus berhenti. Alen menggusur langkahnya yang gontai menuruni bus. Begitu bus pergi meninggalkan perhentian, yang pertama kali Alen lihat bukanlah gerbang sekolahnya yang sudah penuh dengan rombongan siswa, melainkan gerbang sekolah Galen. Alen mengira-ngira, apa mungkin Galen ada di antara gerombolan siswa di sana? Kalau ada, Alen pasti akan langsung menghampiri pemuda itu dan menanyakan kenapa ia tidak pernah muncul lagi secara tiba-tiba.
Mungkin hari ini ia tidak masuk sekolah, pikir Alen.
Alen berhenti memandangi gerbang sekolah di sebrang. Gadis itu mengembuskan napas sebelum berbalik dan memasuki gerbang sekolahnya dengan tubuh yang seolah-olah melayang karena hampa. Sebenarnya apa sih yang Alen harapkan dari kemunculan Galen? Toh, pemuda itu tidak melakukan hal yang istimewa. Hanya beberapa kali mengobrol random dengan Alen.
Langkah Alen lurus melewati selasar sekolah yang riuh. Alen tidak mau repot-repot melirik ke sana kemari seperti yang dilakukan teman-temannya saat berjalan ke kelas. Mereka biasanya mengedarkan pandangan ke seluruh penjuru selasar hanya untuk melambaikan tangan kalau-kalau mereka bertemu dengan orang yang disuka atau bertemu teman dari kelas lain. Alen tidak punya orang yang ia sukai, juga tidak punya teman baik dari kelasnya maupun dari kelas lain, jadi berjalan menunduk adalah pilihan yang tepat kalau Alen tidak ingin melihat teman-temannya melayangkan tatapan iba padanya.
Sembari terus menapaki selasar menuju kelas, Alen mulai memproduksi kisah menarik di benaknya. Gadis itu tersenyum tanpa sadar saat bayangan wajahnya yang elok melintas di prefontal. Alen, dengan anggun mengangkat rok hitam yang menjutai menyapu karpet merah di bawah kakinya. Sorotan lampu dari kamera berkedip-kedip ganas selagi gadis itu tersenyum di tengah-tengah karpet merah yang memanjang indah. Beberapa meter di depan, Alen bisa melihat sebuah photo booth tempat para seniornya melambaikan tangan pada ratusan wartawan dan fotografer. Sebentar lagi giliran Alen. Gadis itu tinggal melangkah beberapa kali untuk sampai di booth dan mulai melambaikan tangan untuk menyapa wartawan dengan senyum termanisnya.
Alen mungkin akan ditanyai beberapa hal soal peran barunya dalam film besar yang akan segara tayang bulan depan, tapi tak masalah, Alen sudah diberitahu harus menjawab apa saja oleh managernya. Alen tinggal bersikap anggun dan mengatakan beberapa hal dengan cara menawan supaya media bisa menulis berita baik tentang dirinya. Sayang sekali sepertinya saat ini keberuntungan sedang tidak berpihak pada Alen. sepatunya tak sengaja menginjak rok hitam yang ia kenakan. Akibatnya, langkahnya timpang. Alen ambruk ke depan, menabrak seseorang yang seketika langsung mengaduh.
“Lo kalo jalan pake mata dong!”
Alen mengerjap. Ia mengangkat kepalanya, mendapati beberapa orang sedang menontonnya. Alen sendiri tersungkur di lantai selasar bersama seorang gadis yang sama sekali tidak ia kenal. Sambil berusaha berdiri, Alen mengumpat, teringat bahwa dengan tololnya ia baru saja membayangkan sedang berjalan di acara red carpet sebagai aktor terkenal.
Beberapa hari terakhir Alen tidak tenggelam dengan imajinasinya. Baru hari ini ia tenggelam lagi, membuat masalah pula.
“Maaf.” Alen mengulurkan tangannya, menawarkan bantuan pada gadis yang sepertinya tak sengaja Alen tabrak karena terlalu hanyut dengan bayangan di benaknya.
Gadis itu membersihkan roknya, lalu bersungut-sungut berdiri tanpa menerima uluran tangan Alen.
“Gue gak butuh bantuan dari cewek gila.” Gadis itu mendelik menakutkan. Bibirnya yang dipoles pewarna merah terangkat kesamping sebelum berlalu meninggalkan atmosfer yang tak nyaman.
Alen berkedip beberapa kali. Ia tidak salah dengar, kan? Gadis itu baru saja mengatai Alen ‘cewek gila’ di depan beberapa siswa lain yang juga sedang melintas di selasar.
Alen tidak gila. Alen benar-benar tidak gila. Ia hanya sedang menikmati kreativitas yang muncul di otaknya. Kenapa orang-orang selalu berpikir Alen gila sementara Alen sangat sadar dengan dirinya sendiri?
“Itu Alen, kan? Kenapa lagi dia?”
Alen menoleh mendengar suara yang samar-samar menyebut namanya.
“Udahlah. Gak penting banget ngurusin dia.”
“Bisa ketularan gila, ya?”
Alen mengerjap. Percakapan itu seolah dibisikan ditelinganya ketika dua gadis—teman sekelas Alen melintasi Alen menuju kelas. Dua gadis itu cekikikan, lalu masuk ke kelas dan meledakkan tawa yang terdengar jelas sampai ke tempat Alen berdiri.
Sesuatu yang menyesakkan muncul dan menabrak dada Alen dari dalam. Gadis itu berdiri di selasar, sama sekali tak bisa mengubah posisinya meski ingin. Alen membayangkan dirinya berlari ke kelas, duduk di bangku, dan segera menelungkupkan wajah di antara tangan-tangannya.
Sepertinya bukan hanya di bayangan saja, perihal keberuntungan yang sedang tidak berpihak padanya juga berlaku di dunia nyata. Imajinasi Alen tidak berjalan saat Alen merasa tergucang. Gadis itu mencoba menyusun cerita lain yang menyenangkan, namun jelas-jelas ia masih tetap berdiri di tengah selasar, nampak menyedihkan dengan mata kosong menatap ubin putih yang sempat dilapisi karpet merah beberapa detik lalu.
Alen menggigit bibirnya, mulai diserang oleh perasaan-perasaan yang jahat dan menyakitkan. Gadis itu merasa kosong dan pahit dalam waktu bersamaan. Di saat Alen butuh kehebatan imajinasi untuk menghiburnya, imajinasi sialan itu tidak bekerja. Tapi disaat Alen sedang ingin terlihat normal dan waras, imajinasi itu malah mengambil alih kesadarannya dan membuatnya dicap gila dua kali dalam waktu yang sama.
Apa mungkin Alen memang benar-benar gila?


 Uswatunn
Uswatunn


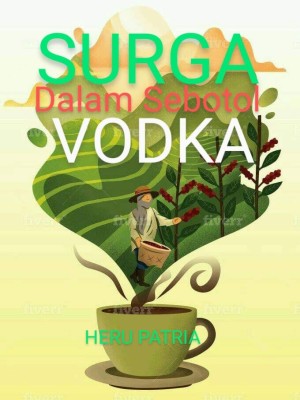







bagus
Comment on chapter Yang tidak diketahui